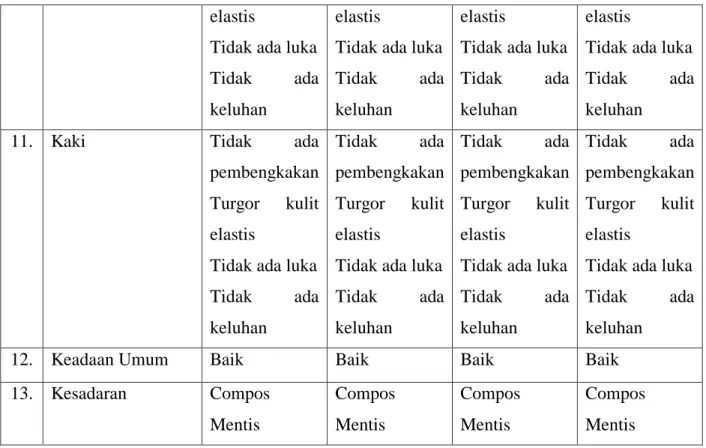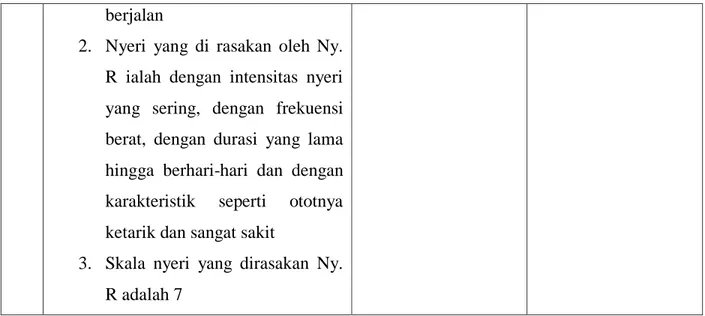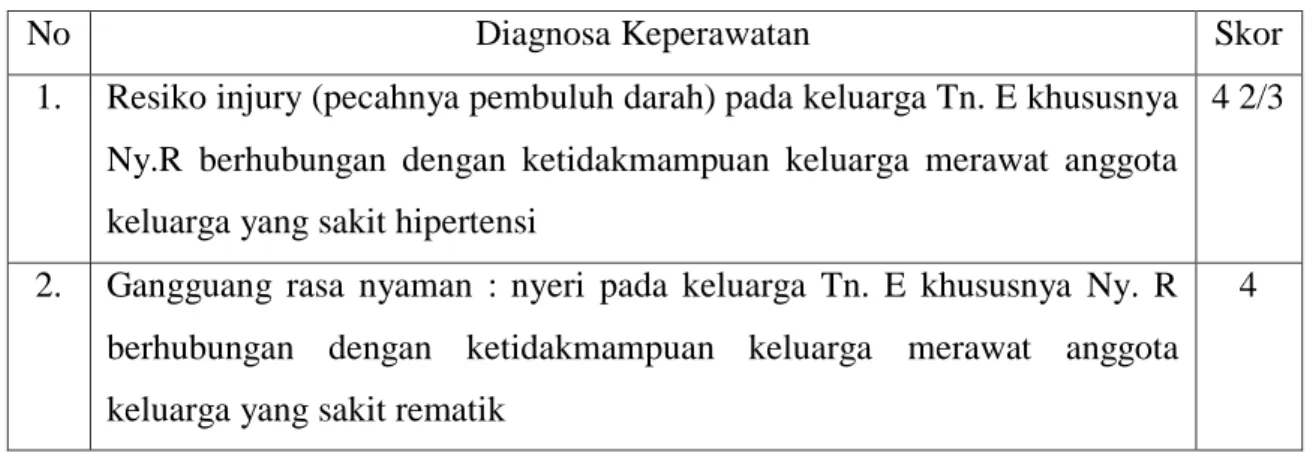57
PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR KELUARGA TN. E KHUSUSNYA
NY. R DENGAN GANGGUAN SISTEM KARDIOVASKULER :
HIPERTENSI DI RT 07 RW 07 KELURAHAN SUMUR BATU
KECAMATAN KEMAYORAN JAKARTA PUSAT
TANGGAL 18 MEI – 30 MEI 2016
Disusun Oleh :
REIZA MARDHATILA
2013750037
PROGRAM D III KEPERAWATAN FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
KATA PENGATAR
Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatu,.
Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat ALLAH SWT atas rahmat dan hidayahnya saya dapat menyusun dan menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini dengan judul “ Asuhan
Keperawatan Pada Keluarga Tn. E khususnya Ny. R dengan masalah sistem
kardiovaskuler : Hipertensi khususnya di Wilayah RT 07 RW 07 Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat pada tanggal 18 – 30 Mei 2016 “.
Tujuan penulis dalam karya tulis ilmiah ini adalah untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menempuh tugas akhir pada program D-III Keperawatan FIK Universitas Muhammadiyah Jakarta. Walaupun karya tulis ilmiah ini telah penulis selesaikan dengan tepat waktunya, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :
1. Ibu Ns. Idriani, M. Kep., Sp. Mat selaku Ka Prodi D-III Keperawatan FIK UMJ 2. Ibu Ns. Nurhayati, M. Kep., Sp.Kom selaku wali tingkat serta dosen pembimbing
Karya Tulis Ilmiah 3. Dosen penguji
4. Seluruh staf pengajar Program D-III Keperawatan FIK UMJ
5. Bapak/Ibu kepala Puskesmas serta Kakak-kakak Kelurahan Sumur Batu dan staf-staf yang telah memberikan doa-doa untuk menunjang karya tulis ilmiah ini.
6. Keluarga Tn. E yang banyak membatu untuk terwujudnya karya tulis ilmiah ini. 7. Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai, kasihi, dan sayangi yang telah
memberikan banyak semangat, dukungan moril dan materil dan doa-doa yang tak pernah putus untuk kemudahan, kelancaran serta kesuksesan untuk saya dengan penuh keikhlasan dan ketulusan beserta kasih sayangnya.
8. Untuk kakak kandung saya Aries Febrianto yang ikut memberi semangat untuk mengerjakan karya tulis ilmiah ini
9. Seluruh keluarga besar saya yang selalu mendoakan saya sehingga saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dengan lancar dan baik.
10. Teman-teman saya Niswah Afifah Istiqomah, Ella Herviani, Ardini Fauziyah, Susi Oktaviyani, Dwi Nuraini, Dwi Putri Aryaningsih, Dina Rosdiana,dan Lala Larasati
yang telah memberi semangat sangat besar, membantu serta selalu menghibur disaat kegudah gulana, lelah, dan malas.
11. Teman teman seperjuangan keluarga samawa anak bimbingan bu nung yaitu Steffi Purnama Sari, Rahmawati, Fudoelah, Nerissa Herviany dan maemuna yang sangat-sangat dalam hal apapun
12. Teman-teman seperjuangan angkatan XXXI yang segala sumber dari sumber apapun. Kebahagian, kebetean, kekesalan, pertengkaran apapun selalu sama kalian. Walau seperti itu tetep salut dengan energi positif dan semangat yang luar biasa untuk kita semua
13. Untuk Ridwan Hidayat yang selalu menjadi moodboster untuk saya. semangat serta doanya lah yang menjadikan saya lebih kuat untuk melalui semua ini.
14. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun karya tulis ilmiah ini yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Semoga bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan dari ALLAH SWT. Amiiiiinn... Akhir kata penulis menyadari karya tulis ilmiah ini banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya masukan baik itu berupa saran maupun kritik yang membangun dari semua pihak dan semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama kesehatan.
Jakarta, Mei 2016
DAFTAR ISI LEMBAR PERSETUJUAN LEMBAR PENGESAHAN KATA PENGANTAR ... i DAFTAR ISI ... ... ii BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ... 1 B. Tujuan Penulis ... 4 1. Tujuan Umum ... 4 2. Tujuan Khusus... 5 C. Ruang Lingkup ... 5 D. Metode Penulisan ... 5 E. Sistematika Penulisan ... 6
BAB II TINJAUAN TEORITIS A. Konsep Dasar Masalah Kesehatan ... 7
1. Pengertian ... 7
2. Patofisiologis (etiologi, proses, manifestasi klinik, dan komplikasi) .... 8
3. Penatalaksanaan ... 12
B. Pemenuhan Kebutuhan ... 19
C. Asuhan Keperawatan Keluarga ... 29
1. Konsep Keluarga ... 29 a. Pengertian ... 29 b. Jenis/Tipe Keluarga ... 30 c. Struktur Keluarga ... 31 d. Peran Keluarga ... 31 e. Fungsi Keluarga ... 33
f. Tahapan Perkembangan Tugas Perkembangan Keluarga ... 39
2. Konsep Proses Keperawatan Keluarga ... 39
b. Diagnosa Keperawatan ... 47
c. Perencanaan Keperawatan ... 53
d. Pelaksanaan Keperawatan ... 54
e. Evaluasi Keperawatan ... 54
BAB III TINJAUAN TEORITIS A. Pengkajian Keperawatan ... 57 B. Diagnosa Keperawatan ... 72 C. Perencanaan Keperawatan ... 75 D. Pelaksanaan Keperawatan ... 92 E. Evaluasi Keperawatan ... 96 BAB IV PEMBAHASAN A. Pengkajian Keperawatan ... 105 B. Diagnosa Keperawatan ... 107 C. Perencanaan Keperawatan ... 108 D. Pelaksanaan Keperawatan ... 109 E. Evaluasi Keperawatan ... 109 BAB V PENUTUP A. Kesimpulan ... 110 B. Saran ... 111 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH
Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Keluarga sebagai sistem sosial di dalamnya berlangsung interaksi secara terus menerus antara anggota keluarga dan lingkungan. Sebagai dampak perubahan yang terjadi pada lingkungan internal dan eksternal, maka dengan sendirinya keluarga akan melakukan kompensasi sebagai upaya untuk menyesuaikan dengan perubahan tersebut sehingga fungsi kesehatannya dapat terjaga. Kesehatan keluarga dipengaruhi oleh anggota keluarga dalam menjalankan fungsinya dengan baik (Sulistyo Andarmoyo 2012).
Berbagai masalah kesehatan yang muncul dikeluarga dan masyarakat karena dampak dari pola perilaku hidup yang tidak sehat. Salah satu penyakit yang diakibatkan dari perilaku hidup yang tidak sehat yaitu hipertensi atau yang lebih dikenal masyarakat dengan darah tinggi. Hipertensi merupakan peningkatan tekanan sistolik lebih besar atau sama dengan 140mmHg dan atau tekanan diastolik sama atau lebih besar 90mmHg. Klien didiagnosis dengan Hiperetensi Sistolik Terisolasi apabila terkena hipertensi refraktori dengan elevasi sistolik atau diastolik terus menerus dan/atau jika tekanan darah diastolik terus diatas 110 sampai 120mmHg didiagnosis dengan hipertensi resistan. Jika penyakit hipertensi tidak ditagani dan dilakukan pengontrolan kesehatan secara teratur akan menimbulkan komplikasi seiring dengan peningkatan kasus hipertensi dan komplikasi yang dapat terjadi jika hipertensi tidak ditangani dengan tepat, maka penggunaan obat yang rasional pada pasien hipertesi merupakan salah satu elemen penting dalam tercapainya kualitas kesehatan serta perawatan medis bagi pasien sesuai standar yang diharapkan maka dilakukan penelitian untuk melakukan penelitian terhadap rasionalitas penggunaan obat antihipertensi pada pasien hipertensi pengguna obat secara tidak rasional dapat menyebabkan timbulnya reaksi obat yang tidak diinginkan, memperparah penyakit, hingga kematian, selain itu biaya yang dikeluarkan menjadi sangat tinggi. Komplikasi
dari hipertensi yaitu penyakit stroke, jantung koroner, infark jantung, gagal ginjal (Black Joyce M. dan Jane Hokanson Hawks, 2014).
Profil data kesehatan Indonesia tahun 2011 menyebutkan bahwa hipertensi merupakan salah satu dari 10 penyakit dengan kasus rawat inap terbanyak di rumah sakit pada tahun 2010, dengan proporsi kasus 42,38% pria dan 57,62% wanita serta 4,8% pasien meninggal dunia (Kemenkes RI, 2012).
Penyakit hipertensi dapat mengakibatkan infark miokard, stroke, gagal ginjal, dan kematian jika tidak dideteksi secara dini dan ditangani dengan tepat (James.dkk,2014). Sekitar 69% pasien dengan jantung, 77% pasien dengan stroke, dan 74% pasien dengan
congestive heart failure (CHF) menderita hipertensi dengan tekanan darah >140/90
mmHg (Go.dkk,2014). Hipertensi dapat mengakibatkan kematian pada 45% penderita penyakit jantung dan 51% kematian pada penderita stroke pada tahun 2008 (WHO, 2013).
Berdasarkan Data Statistik Kesehatan Dunia WHO tahun 2012, hipertensi menyumbang 51% kematian akibat stroke dan 45% kematian akibat jantung koroner. Hipertensi yang tidak diobati dapat menyebabkan kebutaan, irama jantung tidak beraturan, dan gagal jantung (SuaraKarya 2004).
Berdasarkan data Riskesdas 2010 salah satu penyebab kematian pada kasus kardiovaskuler adalah hipertensi dan angka kejadian 2.385 jiwa dari seluruh penyakit kardiovaskuler. Hipertensi menempati urutan kedua dari sepertiga penyebab kematian (Riskesdas 2010)
Prevelensi di Indonesia sebesar 28,5% pada tahun 2013, tetapi yang terdiagnosis oleh tenaga kesehatan dan/atau riwayat minum obat hanya sebesar 9,5%. Hal itu menandakann bahwa sebagaian besar kasus hipertensi di masyarakat belum terdiagnosis dan terjangkau pelayanan kesehatan (Kemenkes RI, 2013).
Prevalensi hipertensi berdasarkan pengukuran tekanan darah menunjukkan penurunan dari 31,7 persen tahun 2007 menjadi 25,8 persen tahun 2013. Asumsi terjadi penurunan bisa bermacam-macam mulai dari alat pengukur tensi yang berbeda sampai pada kemungkinan masyarakat sudah mulai datang berobat ke fasilitas kesehatan. Namun prevalensi hipertensi berdasarkan wawancara (apakah pernah didiagnosis nakes dan minum obat hipertensi) terjadi peningkatan dari 7,6 persen tahun 2007 menjadi 9,5 persen tahun 2013.(Riskesdas, 20013)
Data Statistik dari puskesmas kelurahan sumur batu jumlah penderita hipertensi yang berkunjung ke puskesmas kelurahan sumur batu pada tahun 2012 sebesar 4.174 jiwa (12,26%), golongan usia 45-54 tahun adalah 850 jiwa, sedangkan pada tahun 2014 diperoleh gambar jumlah penderita hipertensi yang berkunjung ke puskesmas sumur batu pada bulan januari sampai april 2014 sebanyak 2.340 jiwa (30,2%) dan pada tahun 2015 diperoleh data dari puskesmas sumur batu sebanyak 3.177 jiwa, golongan pada lansia sebanyak 2.545. mengalami peningkatan yang cukup besar (Puskesmas Kelurahan Sumur Batu)
Berdasarkan data diatas terdapat hasil bahwa adanya peningkatan pada penderita hipertensi. Oleh karena itu untuk mencegah akibat dari penyakit hipertensi, maka keluarga mempunyai peran besar untuk mencegah akibat tersebut. Menurut Fridmen keluarga berperan dalam memelihara kesehatan keluarga. Tugas keluarga dalam kesehatan yaitu mengenal masalah penyakit menderita Hipertensi, keluarga mampu mengambil keputusan bagian anggota keluarga yang menderita Hipertensi, keluarga mampu merawat anggota keluarga yang menderita Hipertensi, keluarga mampu memodifikasi lingkungan keluarga yang menderita Hipertensi dan keluarga mampu memanfaatkan fasilitas kesehatan bagi penderita Hipertensi (Leatham Aurbey, 2005)
Pemenuhan dasar yang terganggu adalah rasa nyaman : nyeri dikarenakan adanya peningkatan darah yang tinggi yang menimbulkan rasa nyeri pada leher bagian belakang dan nyeri pada kepala. Nyeri adalah persaan yang tidak nyaman yang sangat subjektif dan
hanya orang yang mengalaminya yang dapat menjelaskan dan mengevaluasi perasaan tersebut (Iqbal & Chayati, 2007)
Selain peran keluarga perawat mempunyai tanggung jawab untuk menekan masalah hipertensi, peran perawat pun penting untuk mengatasi masalah khususnya pada penyakit hipertensi. Peran perawat melalui upaya promotif (promosi, preventif (pencegahan), kuratif (pengobatan), dan rehabilitas (setelah pengobatan). (Setiadi, 2008)
Aplikasi yang di lakukan perawat dalam upaya promotif adalah melakukan penyuluhan tentang penyakit Hipertensi, upaya preventif (pencegahan) adalah menganjurkan keluarga apabila pusing,lemas dan nyeri pada leher bagian belakang segera istirahat, upaya kuratif (pengobatan) adalah menganjurkan keluarga untuk berobat ke puskesmas dan minum obat antihipertensi (penurun darah tinggi) secara teratur, upaya rehabilitatif adalah menganjurkan keluarga apabila sudah mendapatkan obat penurun darah tinggi maka ingatkan klien untuk periksakan kembali ke puskesmas.
B. TUJUAN PENULISAN 1. Tujuan Umum
Memperoleh pengalaman secara nyata dalam pemenuhan kebutuhan dasar pada keluarga dengan masalah kesehatan gangguan sistem kardiovaskuler khususnya hipertensi.
2. Tujuan Khusus
a. Mampu melakukan pengkajian pada klien dengan masalah kardiovaskuler : hipertensi
b. Mampu menentukan masalah dan merumuskan diagnosa
c. Mampu merencanakan tindakan keperawatan pada klien dengan masala kardiovaskuler : hipertensi
d. Mampu melaksanakan tindakan keperawatan pada klien dengan masalah kerdiovaskuler : hipertensi
e. Mampu melakukan evaluasi keperawatan pada klien dengan masalah kardiovaskuler : hipertensi
g. Mampu mengidentifikasi faktor-faktor pendukung, penghambat, serta dapat mencari solusi
h. Mampu mendokumentasikan semua kegiatan keperawatan dalam bentuk narasi
C. METODE PENULISAN
Metode yang digunakan adalah metode deskriptif adalah proses pengkajian, rumusan diagnosa, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
D. RUANG LINGKUP
Dalam penyusunan makalah ini, penulis membatasi hanya pada pembahasan tentang pemberian asuhan keperawatan keluarga Tn. E khususnya Ny. R dengan gangguan sistem kardiovaskuler : Hipertensi di RT 07 RW 07 Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan 30 Mei 2016.
E. SISTEMATIKA PENULISAN
Penulisa karya tulis ilmiah ini disusun secara sistematis yang terdiri dari : BAB I : PENDAHULUAN
Meliputi latar belakang masalah, tujuan penulis, ruang lingkup, metode penulisan dan sistematika penulisan
BAB II : LANDASAN TEORI
Yang membahas tentang konsep dasar masalah kesehatan yang terdiri dari pengertian, patofisiologi, dan penatalsanaan. Pemenuhan kebutuhan dasar pada keluarga Tn. E khususnya Ny. R dengan gangguan sistem kardiovaskuler : hipertensi. Dan konsep asuhan keperawatan keluarga secara teori, yang meliputi : pengkajian, diagnosa, perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi.
BAB III : TINJAUAN KASUS
Yang merupakan laporan dari hasil langsung tentang asuhan keperawatan keluarga meliputi : pengkajian, diagnosa, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
BAB IV : PEMBAHASAN
Yang membahas kesenjangan antara teori dan kasus, analisa dari faktor-faktor pendukung dan penghambat serta alternatif pemecahan masalah dalam memberikan asuhan keperawatan ditiap-tiap tahapanyang meliputi : pengkajian, diagnosa, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
BAB V : KESIMPILAN DAN SARAN
Dalam bab ini meliputi kesimpilan dari asuhan keperawatan degan masalah kardiovaskuler : hipertensi, dan saran yang ditujukan kepada keluarga dan petugas kesehatan serta kader kesehatan.
DAFTAR PUSTAKA
BAB II
TINJAUAN TEORITIS
A. Konsep Dasar Masalah Kesehatan 1. Pengertian
Hipertensi merupakan salah satu penyakit mematikan di dunia. Namun, hipertensi tidak dapat dapat secara langsung membunuh penderitanya, melaikan dapat memicu terjadinya penyakit lain yang tergolong kelas berat alias mematikan. (Leatham Aurbey, 2005)
Hipertensi adalah peingkatan abnormal pada tekanan sistolik 140mmHg atau lebih dan tekanan diastolik 120mmHg. Hipertensi sebagai suatu peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90mmHg. Hipertensi sebagai suatu keadaan saat terjadi peingkatan tekanan darah sistolik 140mmHg atau lebih, dan tekanan darah diastolik 90mmHg atau lebih.( Setiati Siti, 2015)
Berdasarkan dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa hiperetensi merupakan salah satu penyakit mematikan di dunia. Hipertensi adalah peningkatan abnormal pada tekanan sistolik 140mmHg dan tekanan diastolik 120mmHg. Hipertensi sebagai suatu peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90mmHg.(Setiati Siti, 2015).
2. Klasifikasi
Hipertensi merupakan kelainan yang sulit diketahui oleh tubuh kita. Satu-satunya cara untuk mengetahui hipertensi adalah dengan mengukur tekanan darah secara teratur. Para ahli memberikan klasifikasi tekanan darah yang yang berbeda-beda, namun pada dasarnya, seseorang dikatakan menderita tekanan darah tiggi jika tesinya di atas 140/90 mmHg. Menurut WHO, tekanan darah dianggap normal bila kurang dari
135/85 mmHg, dikatakan hipertensi bila lebih dari 140/90 mmHg, dan di antara nilai tersebut digolongkan normal tinggi.
seventh Report of the Joint National Committee VII (JNC VII) on Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure memberikan klasifikasi
tekanan darah bagi dewasa usia 18 tahun ke atas yang tidak sedang dalam pengobatan tekanan darh tinggi dan tidak menderita penyakit serius dalam jangka waktu tertentu.
Klasifikasi Tekanan darah Menurut JNC VII
Katagori Sistolik Diastolik
Normal <120 <80
Prahipertensi 120-139 80-89
Hipertensi =140 =90
Stadium 1 140-159 90-99
Stadium 2 160=180 100=110
Merujuk dari data pusat kesehatan jantung, paru-paru, darah di Amerika Serikat (NHLBI), tekanan darah 140/90 mmHg dan 139/89 mmHg dikatakan prahipertensi. National Institute of Health, lembaga kesehatan nasional di Amerika megklasifikasikan sebagai berikut.
Kategori Sistolik Diastolik
Normal =119 <79
Prahipertensi 120-139 80-89
Hipertensi derajat 1 140-159 90-99 Hipertensi derajat 2 =160 =100
NM Kaplan (Bapak Ilmu Penyakit Dalam) memberikan batasan dengan memebedakan usia dan jenis kelamin sebagai berikut :
1. Pria, usia <45 tahun, dikatakan hipertensi bila tekanan darah pada waktu berbaring >=130/90mmHg
2. Pria,usia >45 tahun, dikatakan hipertensi jika tekanan darahnya >145/95mmHg
3. Wanita dikatakan hipertensi jika mempunyai tekanan darah 160/95mmHg
Ahli penyakit dalam lain,Gordon H. Williams, mengklasifikasikan hipertensi sebagai berikut. Tensi sistolik : 1. <140 : Normal 2. 140-159 : Normal Tinggi 3. >159 : Hipertensi Tensi diastolik : 1. <85 : Normal 2. 85-89 : Normal Tinggi 3. 90-104 : Hipertensi rigan 4. 105-114 : Hipertensi sedang 5. >115 : Hipertensi berat 3. Etiologi
Berdasarka penyebabnya hipertensi dibagi menjadi 2 golongan: a. Hipertensi Primer (esensial)
Disebut juga hipertensi idiopatik karena tidak diketahui penyebabnya. Faktor yang mempengaruhinya yaitu: genetik, lingkungan, hiperaktifitas saraf simpatis sistem renin. Angiotensin dan peningkatan Na + Ca intraseluler. Faktor yang meningkat resiko:makanan yang asin, obesitas, merokok, alkohol dan polisitemia. b. Hipertensi Sekunder
Penyebabnya yaitu: penggunaan estrogen, penyakit ginjal, sindrom cushing dan hipertensi yang berhubungan dengan kehamilan.
(Aplikasi Asuhan Keperawatan Berdasarkan Diadnosa medis dan Nanda Nic-Noc, 2015)
Jantung memompa lebih kuat sehingga mengalirkan lebih banyak darah pada setiap detiknya, arteri besar kehilangan kelenturannya dan menjadi kaku,sehingga tidak dapat mengembang pada saat jatung memompa darah melalui arteri tersebut, karenanya darah pada setiap denyut jantung di paksa untuk melalui pembuluh darah yang sempit daripada biasanya dan menyebabkan naiknya tekanan darah.
5. Tanda dan Gejala
Tanda dan gejala pada hipertensi dibedakan menjadi: a. Tidak ada gejala
Hal ini berarti hipertensi arterial tidak akan pernah terdiagnosa jika tekanan arteri tidak terukur
b. Gejala yang lazim
Dalam kenyataannya ini merupakan gejala terlazim yang mengenai kebanyakan pasien yang mencari pertolongan medis.
Beberapa pasien yang menderita hipertensi yaitu: a. Mengeluhkan sakit kepala, pusing
b. Lemas,kelelahan c. Sesak nafas d. Gelisah e. Mual f. Muntah g. Epistaksis h. Kesadaran menurun
(Aplikasi Asuhan Keperawatan Berdasarkan Diadnosa medis dan Nanda Nic-Noc, 2015)
5. Komplikasi
menurut Priscilla Lemone 2015 1) Gagal Jantung
Hipertensi menetap mempengaruhi system kardiovaskuler,saraf, dan ginjal. Laju aterosklerosis meningkat, meningkatkan resiko penyakit jantung coroner dan stroke. Beban kerja ventrikel kiri meningkat, menyebabkan hipertropi ventrikel, yang kemudian meningkatkan resiko penyakit jantung coroner, disritmia, dan
gagal jantung. Tekanan darah sistolik adalah faktor resiko kardiovaskular signifikan sampai usia 50 tahun, tekanan sistolik kemudian menjadi faktor yang penting yang menyebabkan resiko kardiovaskuler. (NHBL,2004). Sebagian besar kematian akibat hiertensi disebabkan oleh penyakit jantung coroner dan infark miokardium akut atau gagal jantung.
2) Stroke
Percepatan aterosklerosis yang terkait dengan hipertensi meningkatkan resiko infark cerebral (stroke). Peningkatan tekananan pada pembuluh serebral dapat menyebabkan perkembangan mikroneurisme dan peningkatan resiko hemoragi cerebral.
3) Nefrosklerosis dan insufisiensi ginjal
Proteinuria dan hematuria mikroskopik berkembang, serta gagal ginjal kronik. 7. Penatalaksanaan
Tujuan pengobatan penderita hipertensi adalah menurunkan morbiditas dan mortalitas penyakit cardiovascular dan ginjal. Beberapa percobaan klinis menunjukan penurunan insiden payah jantung kongestif, infark miokard dan stroke sebesar > 50% 20% dan 35%, dengan control tekanan darah yang adekuat. karenanya JNC7, dan guidelines yang lain merekomendasikan untuk seluruh penderita hipertensi diharuskan tekanan darah sistolik< 140 mmHg, dan diastolic <90 mmHg.
(Chandra Irwanadi Mohani, 2015) a. Terapi
Menururt Pricilla Lemone 2015 Modifikasi Gaya hidup
1) Pertahankan berat badan normal 2) Lakukan modifikasi diet :
a) Makan diet kaya buah, sayuran, dan produk susu rendah lemak b) Mengurangi asupan natrium
3) Batasi asupan alcohol tidak lebih dari 1 ons etanol ( ½ ons untuk wanita dan orang berbobot lebih ringan) per hari
4) Ikuti senam aerobic selam 30menit setiap hari 5) Berhenti merokok
6) Gunakan teknik pengelolaan stress seperti terapi relaksasi. Terapi Relaksasi Otot Progresif
Menurut Herodes, Terapi Relaksasi Otot Progresif adalah Teknik relaksasi otot yang tidak menggunakan imajinasi, ketekunan atau sugesti.Berdasarkan keyakinan bahwa tubuh manusia berespon pada kecemasan dan kejadian yang merangsang pikiran dengan ketegangan otot.
Teknik Relaksasi Otot Progresif memusatkan perhatian pada suatu aktivitas otot dengan mengidentifikasi otot yang tegang kemudian menururnkan ketegangan dengan melakukan teknik relaksasi untuk mendapatkan perasaan relaks
Teknik relaksasi otot progresif merupakan suatu terapi relaksasi yang diberikan kepada klien dengan menegangkan otot otot tertentu dan kemudian relaksasi. ( Setyoadi,2011)
1) Tujuan Terapi Relaksasi tot Progresif (herodes,2010 )
a) Menurunkan Ketegangan Otot,Kecemasan, Nyeri Leher dan Punggung, Tekanan Darah Tinggi, Frekuensi Jantung, dan Laju Metabolik.
b) Mengurangi Disritmia Jantung, Kebutuhan Oksigenasi
c) Meningkatkan gelombang alfa otak yang terjadi ketika klien sadar dan tidak memfokuskan perhatian serta relaks
d) Meningkatkan rasa kebugaran, Konsentrasi e) Memperbaiki kemampuan untuk mengatasi stress
f) Mengatasi insomnia, depresi kelelahan,,iritabilitas, spasme otot, fobia ringan,gagap ringan,
g) Membangun emosi positif dari emosi negative. 2) Indikasi Terapi Relaksasi Otot Progresif
b) Untuk yang sering mengalami stress c) Untuk yang mengalami kecemasan d) Untuk yang mengalami depresi
3) Kontraindikasi Terapi Relaksasi Otot Progresif
a) Untuk yang memiliki ketebatasan gerak , Misalnya tidak bisa menggerakan badan
b) Untuk yang menjalani perawatan tirah baring, ( bedrest) 4) Hal hal yang Perlu di Perhatikan
a) Jangan terlau menegangkan otot berlebihan karena dapat melukai diri sendiri
b) Dibutuhkan waktu sekitar 20-50 detik untuk membuat otot otot relaks.
c) Perhatikan posisi tubuh, Lebih nyaman dengan posisi mata tertutup, hindari posisi berdiri
d) Menegangkan kelompok otot 2 kali tegangan
e) Melakukan pada bagian kanan tubuh dua kali, kemudian bagian kiri dua kali.
f) Memeriksa apakah klien benar benar relaks. g) Terus menerus memberikan intruksi
h) Memberika intruksi tidak trlalu cepat dan tidak terlalu lambat. 5) Teknik Terapi Relaksasi Otot Progresif
a) Persiapan
Persiapan alat dan lingkungan kursi, bantal, serta lingkungan yang tenang, dan sunyi.
b) Persiapan klien :
i). Jelaskan tujuan, manfaat, prosedur, dan pengisian lembar persetujuan terapi kepada klien.
ii). Posisikan tubuh klien secara nyaman yaitu berbaring dengan mata tertutup dengan menggunakan banatal dibawah kepala dn
lutut, atau duduk di kursi dengan kepala di topang, hindari posisi berdiri.
iii). Lepaskan asesoris yang digunaksn seperti kacamata, jam, dan sepatu.
iv). Longgarkan ikatan dasi, ikat pinggang atau hal lain yang sifatnya mengikat ketat.
c) Prosedur
Gerakan 1 : Gerakan pertama ditujukan untuk melatih otot tangan i) Genggam tangan kiri sambil membuat satu kepalan
ii) Buat kepalan semakin kuat sambil merasakan sensasi ketegangan yang terjadi
iii) Pada saat kepalan dilepaskan, Klien dipandu untuk merasakan relaks se;ama 10 detik.
iv) Gerakan pada tnagan kiri ini dilakukan dua kali sehingga klien dapat membedakan perbedaan antara ketegangan otot dan keadaan relaks yang dialami
v) Prosedur serupa juga dilatihkan pada tangan kanan
Gerakan 2 : Ditujukan untuk melatih otot tangan bagian belakang Gerakan ini dilakukan dengan cara menekuk kedua lengan ke belakang pada pergelangan tangan sehingga otot-otot di tangan bagian belakang dan lengan bawah menegang, jari-jari menghadap ke langit-langit.
Gerakan 3 : Ditujukan untuk melatih otot biseps ( Otot besar pada bagian atas lengan )
i) Genggam kedua tangan sehingga membuat kepalan
ii) Kemudian membawa kedua kepalan ke pundak sehinnga otot biseps akan menjadi tegang
i). Angkat kedua bahu setinggi tingginya seakan akan menyentuh kedua telinga
ii). Fokuskan perhatian gerakan pada kontras ketegangan yang terjadi dibahu, punggung atas,dan leher.
Gerakan 5 dan 6 : Ditujukan untuk melemaskan otot otot wajah ( seperti otot dahi, mata, rahang ,dan mulut )
i). Gerakan otot dahi dengan cara mengerutkan dahi dan alis sampai otot terasa dan kulitnya keriput.
ii). Tutup keras keras mata sehingga dapat dirasakan ketegangan di sekitar mata dan otot otot yang mengendalikan gerakan mata.Gerakan 7
Gerakan 7 : Ditujukan untuk memgendurkan ketegangan yang dialami oleh otot rahang, katupan rahang, diikuti dengan mengigit gigi sehingga terjadi ketegangan di sekitar otot rahang.
Gerakan 8 : Ditujukan untuk mengendurkan otot otot sekitar mulut, bibir di moncongkan sekuat kuatnya sehingga akan di rasakan ketegangan disekitar mulut.
Gerakan 9 : Ditujukan untuk merelakskan otot leher bagian depan maupun belakang.
i). Gerakan diawali dengan otot leher bagian belakang baru kemudian otot leher bagian depan.
ii). Letakkan kepala sehingga dapat beristirahat.
iii). Letakan kepala pada permukaan bantalan kursi sedemikian rupa sehingga dapat merasakan ketegangan di bagian belakang leher dan punggung atas.
Gerakan 10 : Ditujukan untuk melatih otot leher bagian depan i) Gerakan membawa kepala ke muka
ii) Benamkan dagu ke dada, sehingga dapat merasakan ketegangan di daerah leher bagian muka
Gerakan 11 : Ditujukan untuk melatih otot punggung i) Ankgat tubuh dari sandaran kursi
ii) Punggung di lengkungkan
iii) Busungkan dada, tahan kondisi tegang selama 10 detik, kemudian relaks
iv) Saat relaks, letakan tubuh kembali ke kursi sambil membiarkan otot menjadi lemas.
Gerakan 12 : Ditujukan untuk melemaskan otot dada
i) Tari nafas panjang untuk mengisi paru paru dengan udara sebanyak banyak nya.
ii) Ditahan selama beberapa saat, sambil merasakan ketegangan di bagian dada sampai turun ke perut , kemudian di lepas.
iii) Saat ketegangan di lepas, akukan nafas normal dengan lega. iv) Ulangi sekali lagi sehingga dapat di rasakan perbedaan antara
kondisi tegang dan relaks
Gerakan 13 : Ditujukan untuk melatih otot perut i) Tari dengan kuat perut ke dalam
ii) tahan sampai menjadi kencang dank eras selam 10 detik, lalu dilepaskan bebas
iii) Ulangi kembali seperti gerakan awal untuk perut ini.
Gerakan 14-15 : Ditujukan untuk melatih otot otot kaki (seperti paha dan betis )
i) Luruskan kedua telapak kaki sehingga otot paha terasa tegang. ii) Lanjutkan dengan mengunci lutut sedemikian rupa sehingga
ketegangan pindah ke otot betis. iii) Tahan posisi tegang selaa 10 detik.
iv) Ulangi setiap gerakan masing masing 2 kali. 6) Kriteria Evaluasi
a) Klien tidak mengalami gangguan tidur ( insomnia ) dan tidak stress. b) Kebutuhan dasar klien terpenuhi.
c) Tanda tanda vital dalam batas normal.
menurut Priscila Lemone,2015 1) Diuretik
Terapi pilihan untuk hipertensi pada lansia. Hidroklorotiazid adalah diuretic yang paling di seringdi resepkan untuk mengobati hipertensi ringan.
2) Penyekat alfa- adrenergic
Agen penyekat alfa adrenergic menghambat reseptor alfa pada otot polos vascular,menurunkan tegangan vasomotor dan vasokontriksi. Obat yang digunakan yaitu;
3) Inhibitor angiotensis- Converting Enzym
Menurunkan tekanan darah dengan mencegah angiotensin 1 menjadi angiotensin 11. obat obatan yang di gunakan yaitu; Kaptopril, Enalapril, Fasinopril, dll.
4) Agen penyekat beta adregenerik
Di gunakan untuk mengontrol hipertensi. penyekat beta untuk menurunkan tekanan darah dengan mencegah stimullasi reseptor beta di jantung, sehingga menurunkan frekuensi jantung dan curah jantung. obat obatan yang digunakan yaitu; asebutolol, atenolol, betaxolol, dll.
5) Penyekat saluran kalsium
Untuk menghambat aliran ion kalsium yang melintasi membrane sel jaringan vaskulerdan sel jantung. obat obatan yang digunakan yairu; Amlodipin, Klevidipin, Diltiazem, Felodipin, Isradipin, Nikardipin dll. 6) Simpatolitik kerja sentral
Untuk menekan aliran keluar simpatis ke jantung dan pembuluh darah. Penurunan curah jantung dan vasodilatasi terjadi, menurunkan tekanan darah. obat yang digunakan yaitu Klonidin, Guanfaksin, Metildopa, Reserpin.
7) Vasodilator
Menurunkan tekanan darah dengan mengendurkan otot polos vascular, khususnya arteri dan menurunkan resistensi vaskuler perifer. obat yang sering digunakan Hidralazin,minoksidil.
B. Pemenuhan Kebutuahan dasar
Pemenuhan kebutuhan dasar yang terkait dengan hipertensi adalah : 1. Kebutuhan Keamanan
a. Definisi Keamanan
Keamanan seringkali didefinisikan sebagai keadaan bebas dari cedera fisik dan psikologis adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Lingkungan pelayanan kesehatan dan komunitas yang aman merupakan hal yang penting untuk kelangsungan hidup klien. Perawat harus mengkaji bahaya yang mengancam keamanan klien dan lingkungan, dan selanjutnya melakukan intervensi yang diperlukan. Dengan melakukan hal ini, maka perawat adalah orang yang berperan aktif dalam usaha pencegahan penyakit, pemeliharaan kesehatan, dan peningkatan kesehatan.
b. Klasifikasi Kebutuhan Keamanan 1). Keselamatan Fisik
Keselamatan fisik tergantung dari keamanan Lingkungan. Lingkungan klien mencangkup semua faktor fisik dan psikologis yang mempengaruhi atau berakibat terhadap kehidupan dan kelangsungan hidup klien. Definisi yang luas tentang lingkungan ini menggabungkan seluruh tempat terjadinya interaksi antara perawat dan klien. Keamanan yang ada didalam lingkungan ini akan mengurangi insiden terjadinya penyakit dan cedera, memperpendek lama tindakan dan/atau hospitalisasi, meningkatkan kesejahteraan klien. Lingkungan yang aman juga akan memberikan perlindunngan kepada stafnya, dan memungkinkan mereka untuk berfungsi pada tingkat yang optimal.
Lingkungan yang aman adalah salah satu kebutuhan dasar yang terpenuhi, bahaya fisik akan berkurang, bahaya fisik yang ada didalam komunitas dan tempat pelayanan kesehatan menyebabkan klien beresiko mengalami cedera. Dari keseluruhan kematian yang disebabkan oleh kecelakaan akibat jatuh, keracunan, tenggelam, kebakaran dan luka bakar. Jatuh merupakan penyebab utama kematian akibat kecelakaan pada klien berusia 75 tahun atau lebih (Accident Facts,1993) lebih dari 40% orang berusia 65 tahun mengalami jatuh sedikitnya 1 kali dalam setahun, dengan 1% hingga 6% diantaranya menyebabkan cedera serius (Loew,1993). Banyak bahaya fisik, khususnya yang mengakibatkan jatuh, dapat diminimalkan melalui pencahayaan yang adekuat, pengurangan penghalang fisik. Pengontrolan bahaya yang mungkin ada dikamar mandi, dan tindakan pengamanan.
2). Keselamatan Psikologis
Untuk selamat dan aman secara psikologi, seorang manusia harus memahami apa yang diharapkan dari orang lain, termasuk anggota keluarga dan profesionl pemberi perawatan kesehatan. Seseorang harus mengethuai apa yang diharapkan dari prosedur, pengalaman yang baru, dan hal-hal yang dijumpai dalam lingkungan. Setiap orang merasakan beberapa ancaman keselamatan psikologis pada pengalaman yang baru dan yang tidak dikenal. (Potter&Perry,2005).
Orang dewasa yang sehat secara umum mampu memenuhi kebutuhan keselamatan fisik dan psikologis merekat tanpa bantuan dari profsional pemberi perawatan kesehatan.Bagaimanapun,orang yang sakit atau acat lebih
renta untukterncam kesejahteraan fisik dan emosinya,sehingga intervensi yang dilakukan perawat adalah untuk membantu melindungi mereka dari bahaya. (Potter&Perry, 2005).
c. Lingkup Kebutuhan Keamanan
Lingkungan Klien mencakup semua faktor fisik dan psikososial yang mempengaruhi atau berakibat terhadap kehidupan dan kelangsungan hidup klien. 1). Kebutuhan Fisiologis
Kebutuhan fisiologis yang terdiri dari kebutuhan terhadap oksigen, kelembaban yang optimum, nutrisi, dan suhu yang optimum akan mempengauhi kemampuan seseorang.
2). Oksigen
Bahaya umum yang ditemukan dirumah adalah sistem pemanasan yang tidak berfungsi dengan baik dan pembakaran yang tidak mempunyai sistem pembuangan akan menyebabkan penumpukan karbondioksida.
3). Kelembaban
Kelembaban akan mempengaruhi kesehatan dan keamanan klien, jika kelembaban relatifnya tinggi maka kelembaban kulit akan terevaporasi dengan lambat
4). Nutrisi
Makanan yang tidak disimpan atau disiapkan dengan tepat atau benda yang dapat menyebabkan kondisi kondisi yang tidak bersih akan meningkatkan resiko infeksi dan keracunan makanan.
d. Cara Meningkatkan Keamanan
1). Menjamin pencahayaan yang adekuat
Pencahayaan yang adekuat akan mengurangi bahaya fisik dengan cara menerangi tempat klien bergerak dan bekerja. Karena dapat membantu aktivitas klien terutama pada lansia akan membantu memelihara keamanan mereka dengan cara mengurangi resiko jatuh.
2). Mengurangi Penghalang Fisik
Cedera yang terjadi dirumah seringkali disebabkan oleh berbagai benda, termasuk keset dan lantai. Noda basah dilantai yang menyebabkan lantai licin. Dan barang barang rumah tangga yang tidak ada pada tempatnya. Resiko terbesar dialami oleh lansia. Untuk mengurangi resiko cidera, seluruh penghalang fisik harus dipindahkan. Dan benda-benda yang dibutuhkan klien ditempatkan dekat dengan klien. Perawatan juga harus dilakukan untuk memastikan ujung meja telah aman dan meja mempunyai kaki meja yang stabil dan lurus. Jika menggunakan keset, maka keset harus dilindungi dengan alas yang tidak licin atau bahan perekat yang tahan licin.
3). Mengontrol bahaya yang ada di kamar mandi
Kecelakaan sering terjadi dikamar mandi. Pegangan yang mudah terlihat dan aman dan tidak licin yang ada didasar bak mandi berguna untuk mengurangi resiko jatuh dalam bak mandi. Tempat duduk toilet yang ditinggikan dengan pegangan tangan dan alas yang tidak licin pada lantai depan toilet juga sangat
berguna untuk mengurangi bahaya yang ada dikamar mandi (Tideiksaar,1989).
2. Kebutuhan aman dan nyaman : Nyeri
Nyeri adalah persaan yang tidak nyaman yang sangat subjektif dan hanya orang yang mengalaminya yang dapat menjelaskan dan mengevaluasi perasaan tersebu (Long, 1996). Secara umum , nyeri dapat di definisikan sebagai persaan tidak nyaman, baik ringan maupun berat (Priharjo, 1992).
a. Fisiologi nyeri 1) Nosisepsi
Sistem saraf perifer terdiri atas saraf sensorik primer yang khusus bertugas mendeteksi kerusakan jaringan dan membangkitkan sensasi sentuhan, panas, dingin, nyeri, dan tekanan . Reseptor yang bertugas merambatkan sensasi nyeri disebut nosiseptor. Proses tersebut terdiri atas empat fase, yakni:
2) Transduksi. Pada fase transduksi, stimulus atau rangsangan yang membahayakan (mis., bahan kimia, suhu, listrik atau mekanis) memicu pelepasan mediator biokimia (mis., prostaglandin, bradikinin, histamin, substansi P) yang mensensitisasi nosiseptor.
3) Transmisi. Fase transmisi nyeri terdiri atas tiga bagian. Pada bagian pertama, nyeri merambat dari serabut saraf prifer ke medulla spinalis. 4) Persepsi. Pada fase ini, inidividu mulai menyadari adanya nyeri.
Tampaknya persepsi nyeri tersebu terjadi di struktur korteks sehingga memungkinkan munculnya berbagai setrategi perilaku-kognitif untuk mengurangi komponen sensorik dan afektif nyeri (McCaffery & Pasero, 1999).
5) Modulasi. Fase ini disebut juga “sistem desenden.” Pada fase ini, neuron di batang otak mengirimkan sinyal-sinyal kembali ke medula spinalis. Serabut desenden tersebut melepaskan substansi seperi opioid, serotonin, dan
norepinefrin yang akan menghambat impuls asenden yang membahayakan di bagian dorsal medula spinalis.
6) Teori Gate Control. Banyak teori yang menjelaskan fisiologi nyeri, namun yang paling sederhana adalah teori Gate Control yang dikemukakan oleh Melzack dan Well (1965). Dalam teorinya, kedua orang ahli ini menjelaskan bahwa substansi gelatinosa (SG) pada medula spinalis bekerja layaknya pintu gerbang yang memungkinkan atau menghalangi masuknya impuls nyeri menuju otak.
7) Pengalaman nyeri. Jenis dan bentuk nyeri 8) Jenis nyeri
Ada tiga klasifikasi nyeri:
a) Nyeri perifer. Nyeri ini ada tiga macam: (1) nyeri superfisial, yakni rasa nyeri muncul akibat rangsangan pada kulit dan mukosa; (2) nyeri viseral, yakni rasa nyeri yang muncul akibat stimulasi pada reseptor nyeri di rongga abdomen, kranium, dan toraks; (3) nyeri ahli, yakni nyeri yang dirasakan pada daerah lain yang jauh dari jaringan penyebab nyeri.
b) Nyeri sentral. Nyeri yang muncul akibat stimulasi pada medula spinalis, batang otak, dan talamus.
c) Nyeri psikogenik. Nyeri yang tidak diketahui penyebab fisiknya. Dengan kata lain, nyeri ini timbul akibat pikiran si penderita sendiri. Seringkali, nyeri ini muncul karena faktor psikologis, bukan fisiologis.
9) Bentuk nyeri
Secara umum, bentuk nyeri terbagi atas nyeri akut dan nyeri kronis.
a) Nyeri akut. Nyeri ini biasanya berlangsung tidak lebih dari enam bulan. Awitan gejalanya mendadak, dan biasanya penyebab serta lokasi nyeri sudah diketahui. Nyeri akut ditandai dengan peningkatan tegangan otot dan kecemasan yang keduanya meningkatkan persepsi nyeri.
b) Nyeri kronis. Nyeri ini berlangsung lebih dari enam bulan. Sumber nyeribisa diketahui atau tidak. Nyeri cenderung hilang timbul dan biasanya tidak dapat disembuhkan. Selain itu, penginderaan nyeri menjadi lebih dalam sehingga penderita sukar untuk menunjukan lokasinya. Dampak dari nyeri ini antara lain penderita menjadi mudah tersinggung dan sering mengalami insomnia. Akibatnya, mereka menjadi kurang perhatian, sering merasa putus asa, dan terisolir dari kerabat dan keluarga. Nyeri kronis biasanya hilang timbul dalam periode waktu tertentu. Ada kalanya penderita terbebas dari rasa nyeri (mis., sakit kepala migran).
10) Faktor yang Mempengaruhi Nyeri a) Etnik dan nilai budaya
Latar belakang etnik dan budaya merupakan faktor yang memengaruhi reaksi terhadap nyeri dan ekspresi nyeri. Sebagai contoh, individu dari budaya tertentu cenderung ekspresif dalam mengungkapkan nyeri, sedangkan individu dari budaya lain justru lebih memilih menahan perasaan mereka dan tidak ingin merepotkan orang lain.
b) Tahap perkembangan
Usia dan tahap perkembangan seseorang merupakan variable penting yang akan memengaruhi reaksi dan ekspresi terhadap nyeri. Dalam hal ini, anak-anak cenderung kurang mampu mengungkapkan nyeri yang mereka rasakan dibandingkan orang dewasa, dan kondisi ini dapat menghambat penanganan nyeri untuk mereka. Di sisi lain, prevalensi nyeri pada individu lansia lebih tinggi karena penyakit akut atau kronis yang mereka derita. Walaupun ambang batas nyeri tidak berubah karena penuaan, tetapi efek analgesik yang diberikan menurun karena perubahan fisiologis yang terjadi.
c) Lingkungan dan Individu pendukung
Lingkungan yang asing, tingkat kebisingan yang tinggi, pencahayaan, dan aktivitas yang tinggi di lingkungan tersebut dapat memperberatkan nyeri. Selain itu, dukungan dari keluarga dan orang terdekat menjadi
salah satu faktor penting yang memengaruhi persepsi nyeri individu. Sebagai contoh, individu yang sendirian, tanpa keluarga atau teman-teman yang mendukungnya, cenderung merasakan nyeri yang lebih berat dibandingkan mereka yang mendapat dukungan dari keluarga dan orang-orang terdekat.
d) Pengalaman nyeri sebelumnya
Pengalaman masa lalu juga berpengaruh terhadap persepsi nyeri individu dan kepekaannya terhadap nyeri. Individu yang pernah mengalami nyeri atau menyaksikan penderitaan orang terdekatnya saat mengalami nyeri cenderung merasa terancam dengan peristiwa nyeri yang akan terjadi dibandingkan individu lain yang belum pernah mengalaminya. Selain itu, keberhasilan atau kegagalan metode penanganan nyeri sebelumnya juga berpengaruh terhadap harapan individu terhadap penanganan nyeri saat ini.
e) Ansietas dan setres
Ansietas sering kali menyertai peristiwa nyeri yang terjadi. Ancaman yang tidak jelas asalnya dan tidak ketidakmampuan mengontrol nyeri atau peristiwa di sekelilingnya dapat memperberat persepsi nyeri. Sebaliknya, individu yang percaya bahwa meraka mampu mengontrol nyeri yang meraka rasakan akan mengalami penurunan rasa takut dan kecemasan yang akan menurunkan persepsi nyeri mereka.
Cara mengukur intensitas nyeri
Hayward (1975) mengembangkan sebuah alat ukur nyeri (painomenter ) dengan skala longitudinal yang pada salah satu ujungnya tercantum nilai 0 (untuk keadaan tanpa nyeri) dan ujung lainnya naialai 10 (untuk kondisi nyeri paling hebat). Untuk mengukurnya, penderita memilih salah satu bilangan yang menurutnya paling menggambarkan pengalaman nyeri yang terakhir kali ia rasakan, dan nilai ini dapat dicatat pada sebuah sebuah grafik yang dibuat menurut waktu. intensitas nyeri ini sifatnya subjektif dan dipengaruhi oleh banyak hal,
seperti tingkat kesadaran, konsentrasi, jumlah distraksi, tingkat aktivitas, dan harapan keluarga. Insensitas nyeri dapat dijabarkan dalam sebuah skala nyeri dengan beberapa kategori.
Skala Nyeri Menurut Hayward
Skala Keterangan 0 1-3 4-6 7-9 10 Tidak Nyeri Nyeri Ringan Nyeri Sedang
Sangat Nyeri, tetapi masih bisa di control dengan aktivitas yang biasa di lakukan
Sangat Nyeri dan tidak bisa di kontrol
C. Asuhan Keperawatan Keluarga 1. Konsep Keluarga
a. Pengertian Keluarga
1) Keluarga adalah kumpulan dua atau lebih individu yang saling tergantung satu sama lainnya untuk emosi, fisik dan dukungan ekonomi (Hanson, 1996) 2) Keluarga adalah suatu sistem sosial yang berisi dua atau lebih orang yang
hidup bersama yang mempunyai hubungan darah, perkawinan atau adopsi, atau tiggal bersama dan saling menguntungkan, mempunyai tujuan bersama, mempunyai generasi penerus, saling pengertian dan saling menyayangi (Murray & Zentner, 1997)
Berdasarkan dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa keluarga adalah kumpulan dua atau lebih individu yag saling tergantung satu sama lainyang memiliki hubugan darah, perkawinan atau adopsi, atau tinggal bersama dan saling mengutungkan yang bertujuan menciptakan dan mempertahankan budaya yang umum, meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional dan sosial dari individu-individu yang ada di dalamya.
b. Tipe Keluarga
1) Keluarga Tradisional
a) Tradisional Nuclear/ keluarga inti
Merupakan satu bentuk keluarga tradisional yang diaggap paling ideal. Keluarga inti adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak, tinggal dalam satu rumah, di mana ayah adalah pencari nafkah dan ibu sebagai ibu rumah tangga.
2) Keluarga Nontradisional
Bentuk-bentuk varian keluarga ontradisional meliputi bentuk-bentuk keluarga yang sangat berbeda satu sama lain, baik dalam struktur maupun diamikanya, meskipun lebih memiliki persamaan satu sama lain dalam hal tujuan dan nilai daripada keluarga inti tradisional. Orang-orang dalam pengaturan keluarga nontradisional sering mebekankan nilai aktualisasi diri, kemandirian, persamaan jenis kelamin, keintiman dalam berbagai hubungan interpersonal. Bentuk-bentuk keluarga ini meliputi :
a) Communal/Commune Family
Keluarga dimana dalam satu rumah terdiri dari dua atau lebih pasangan yag monogami tanpa pertalian keluarga dengan anak-anaknya dan bersama-sama, dalam penyediaan fasilitas. Tipe keluarga ini biasanya terjadi pada daerah perkotaan dimana penduduknya padat.
b) Unmaried Parent and Child
Keluarga yang terdiri dari ibu-anak, tidak ada perkawian dan anaknya dari hasil adopsi
c) Cohibing Couple
Merupaka keluarga yang terdiri dari dua orang atau satu pasangan yang tinggal bersama tanpa kawin
d) Institusional
Keluarga yang terdiri dari anak-anak atau orag-orang dewasa yang tinggal bersama-sama dalam panti. Sebenarnya keluarga ini tidak cocok untuk
disebut keluarga, tetapi mereka sering mempunyai sanak saudara yang mereka anggap sebagai keluarga sehigga sebenarnya terjadi jaringan yang berupa kerabat.
c. Struktur Keluarga
Keluarga adalah suatu sistem terbuka yang terdiri dari beberapa komponen/subsistem yang selalu berinteraksi degan lingkungan eksternal maupun internal. Struktur keluarga adalah pengetahuan tentang cara keluarga mengorganisasikan subsistem yang ada pada keluarga serta bagaimana komponen-komponen keluarga tersebut berhubungan. Dimensi dasar struktur keluarga terdiri dari; pola dan proses komunikasi, struktur kekuatan/kekuasaan, struktur peran, serta struktur nilai keluarga. Keempat elemen ini memiliki interrelast dan saling bergantung satu sama lain. Struktur ini akan dievaluasi untuk mengetahui bagaimana keluarga mampu melaksanakan fungsinya.
d. Peran Keluarga
Peran meujuk kepada beberapa set perilaku yang kurag lebih bersifat homogen, yang didefinisikan dan diharapkan secara normatif dari seorang okupan dalam situasi sosial tertentu. Peran didasarkan pada preskripsi dan harapan pera yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut (Nye, 1976)
Menurut Andreson Carter, ciri-ciri peran adalah: 1). Terorganisasi, yaitu adanya interaksi dan interdenden, 2). Terdapat keterbatasan dalam menjalankan tugas dan fungsi, 3). Terdapat perbedaan dan kekhususan.
1) Peran-peran Formal Keluarga
Peran formal bersifat eksplisit. Peran formal keluarga adalah : 2) Peran Parenatal dan Perkawinan
Nye dan Gecas (1976), telah mengidentifikasi enam peran dasar yang membentuk posisi sosial sebagai suami-ayah dan istri-ibu. Peran tersebut adalah; 1). Peran provider/penyediaan, 2). Peran pengatur rumah tangga, 3). Peran perawat anak, 4). Peran sosialisasi anak, 5). Peran rekresai, 6). Peran
persaudaraan/kindship/pemeliharaan hubungan keluarga paternal dan maternal, 7). Peran teraupetik/memnuhi kebutuhan afektif dari pasangan, 8). Peran seksual.
3) Peran Anak
Peran anak adalah melaksanakan tugas perkembangan dan pertumbuhan fisik, psikis, sosial.
4) Peran Kakek/Nenek
Menurut Bengston (1985), peran kakek/nenek dalam keluarga adalah: 1). Semata-mata hadir dalam keluarga, 2). Pengawal (menjaga dan melindungi bila diperlukan, 3). Menjadi hakim (arbritrator), negosiasi antara anak dan orang tua, 4). Menjadi partisipan aktif, meciptakan keterkaitan antara, masa lalu dengan sekarang serta masa yang akan datang.
5) Peran Informal Keluarga
Peran informal bersifat implisit biasanya tidak tampak ke permukaan dan dimaikan hanya untuk memnuhi kebutuhan-kebutuhan emosional individu (satir, 1967) dan/atau untuk menjaga keseimbangan dalam keluarga. Keberadaan peran informal penting bagi tuntutan-tuntutan integratif dan adaptif kelompok keluarga.
e. Fungsi Keluarga
Fungsi keluarga merupakan hasil atau konsekuensi dari struktur keluarga atau sesuatu tentang apa yang dilakukan oleh keluarhga. Terdapat bebrapa fungsi keluarga menurut Friedman (1998); Setiawan & Dermawan (2005) yaitu:
1) Fungsi afektif
Fungsi afektif merupakan fungsi keluarga dalam memenuhi kebutuhan pemeliharaan kepribadian dari anggota keluarga. Merupakan respon dari keluarga terhadap kondisi dan situasi yang dialami tiap anggota keluarga baik senang maupun sedih, dengan melihat bagaimana cara keluarga mengeksperikan kasih sayang.
2) Fungsi sosialisasi
Fungsi sosialisasi tercermin dalam melakukan pembinaan sosialisasi pada anak, membentuk nilai dan orma yang diyakini anak, memberikan batasan perilaku
yang boleh dan tidak boleh pada anak, meneruskan nilai-nilai budaya keluarga. Bagaimana keluarga produktif terhadap sosial dan bagaimanakeluarga memperkenalkan anak dengan dunia luar dengan belajar disipli, mengenal budaya dan norma melalui hubugan interaksi dalam keluarga sehingga mampu berperan dalam masyarakat.
3) Fungsi perawatan kesehatan
Fungsi perawatan kesehatan keluarga merupakan fungsi keluaraga dalam melindungi keamanan dan kesehatan seluruh anggota keluarga seta menjami pemenuhan kebutuhan perkembangan fisik, mental dan spiritual, dengan cara memelihara dan merawat anggota keluarga serta mengenali kondisi sakit tiap anggota keluarga.
4) Fungsi ekonomi
Fungsi ekonomi, untuk memenuhi kebutuhan keluarga seperti sandang, pangan dan kebutuhan lainnya melalui keefektifan sumber dana keluarga. Mencari sumber penghasilan guna memenuhi kebutuhan keluarga, pengaturan penghasilan keluarga, meabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
5) Fungsi biologis
Fungsi biologis, bukan hanya ditunjukan untuk meneruskan keturunan tetapi untu memlihara dan membesarkan anak untuk kelanjutan generasi selanjutnya. 6) Fungsi psikologis
a. Fungsi psikologis, terlihat bagaimana keluarga memberikan kasih sayang dan rasa aman, memberikan perhatian diatara anggota keluarga, membina pendewasaan kepribadian anggota keluarga dan memberikan identitas keluarga. 7) Fungsi pendidikan
a. Fungsi pendidikan diberikan keluarga dalam rangka memberikan pengetahuan, keterampilan, membentuk perilaku anak, mempersiapkan anak untuk kehidupan dewasa, medidik anak sesuai dengan tingkatan perkembangannya.
Fungsi keluarga (PP No. 21 Th. 1994 dan UU No. 10 Tahun 1992) : 1) Fungsi Keagamaan
Keluarga adalah wahana utama dan pertama menciptakan seluruh anggota keluarga menjadi insan yang taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tugas dari fungsi keagamaan adalah:
a) Membina norma/ajaran agama sebagai dasar dan tujuan hidup seluruh anggota keluarga
b) Menerjemahkan ajaran/norma agama ke dalam tingkah laku hidup sehari-hari seluruh anggota keluarga
c) Memberikan contoh konkrit pengalaman ajaran agama dalam hidup sehari-hari
d) Melengkapi dan menambah proses kegiatan balajar anak tentang keagamaan yang tidak atau kurang diperolehnya di sekolah atau masyarakat
e) Membina rasa, sikap dan praktik kehidupan keluarga beragama sebagai fondasi menuju keluarga kecil bahagia
2) Fungsi Sosial Budaya
Keluarga berfungsi untuk menggali,mengembangkan dan melestarikan sosial budaya indonesia, dengan cara:
a) Membina tugas-tugas keluarga sebagai lembaga untuk meneruskan norma dan budaya masyarakat dan bangsa yang ingin dipertahankan
b) Membina tugas-tugas keluarga sebagai lembaga untuk menyaring norma budaya asing yang tidak sesuai
c) Membina tugas-tugas keluarga sebagai lembaga di mana anggotanya mengadakan kompromi/adaptasi dari praktik globalisasi dunia
d) Membina budaya keluarga yang sesuai, selaras dan seimbang dengan budaya masyarakat/bangsa untuk terwujudnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera.
3) Fungsi Kasih Sayang
Keluarga berfungsi mengembangkan rasa cinta dan kasih sayang setiap anggota keluarga, antarkerabat, antar generasi. Termasuk dalam fungsi ini adalah: a) Menumbuh kembangkan potensi kasih sayag yang telah ada di antara
anggota keluarga ke dalam simbol-simbol nyata/ucapan dan perilaku secara optimal dan terus menerus
b) Membina tingkah laku saling menyayangi baik antarkeluarga yang satu dengan yang lainnya secara kuantitatif dan kualitatif.
c) Membina praktik kecintaan terhadap kehidupan duniawi dan ikhrowi dalam keluarga secara serasi, selaras dan seimbang
d) Membina rasa, sikap dan praktik hidup keluarga dan mampu memberikan dan menerima kasih sayang sebagai pola hidup ideal menuju KKBS.
4) Fungsi perlindungan
Fungsi untuk memberikan rasa aman secara lahir dan batin kepada setiap anggota keluarga. Fungsi ini menyangkut:
a) Memenuhi kebutuhan rasa aman anggota keluarga baik dari rasa tidak aman yang timbul dari dalam maupun dari luar keluarga
b) Membina keamanan keluarga baik fisik, psikis, maupun dari berbagai bentuk ancaman dan tantagan yang datang dari luar
c) Membina dan menjadikan stabilitas dan keamanan keluarga sebagai keluarga sebagai modal menuju KKBS
5) Fungsi Reproduksi
Memberikan keturunan yang berkualitas melalui: pengaturan dan perencanaan yang sehat dan menjadi insan pembangunan yang handal, dengan cara:
a) Membina kehidupan keluarga sebagai wahana pendidikan reproduksi sehat bagi anggota keluarga maupun bagi keluarga sekitarnya
b) Memberikan contoh pengalaman kaidah-kaidah pembentukan keluarga dalam hal usia, pendewasaan fisik maupun mental
c) Mengamalkan kaidah reproduksi sehat, baik yang berkaitan dengan waktu melahirkan, jarak dan jumlah ideal anak yang diinginkan dalam keluarga d) Mengembangkan kehidupan repsroduksi sehat sebagai modal yang kondusif
menuju KKBS
6) Fungsi Pendidikan dan Sosialisasi
Keluarga merupakan tempat pendidikan utama dan pertama dari anggota keluarga yang berfungsi untuk meningkatkan fisik, mental, sosial dan spiritual secara serasi selaras dan seimbang. Fungsi ini adalah:
a) Menyadari, merencanakan dan menciptakan lingkungan keluarga sebagai wahana pendidikan dan sosialisasi anak yang pertama dan utama
b) Menyadari, merencanakan dan menciptakan kehidupan keluarga sebagai pusat di mana anak dapat mencari pemecahan masalah dari konflik yang dijumpainya, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat
c) Membina proses pendidikan dan sosialisasi anak tentang hal-hal yang diperlukannya untuk meningkatkan kematangan dan kedewasaan fisik dan mental, yang tidak/kurang diberikan oleh lingkungan sekolah maupu masyarakat
d) Membina proses pendidikan dan sosialisasi yang terjadi dalam keluarga sehingga tidak saja dapat bermanfaat positif bagi anak, tetapi juga bagi orang tua dalam rangka perkembangan dan kematangan hidup bersama menuiju KKBS
7) Fungsi Ekonomi
Keluarga meningkatkan keterampilan dalam usaha ekonomis produktif agar mendapatkan keluarga meningkat dan tercapai kesejahtaraan.
a) Melakukan kegiatan ekonomi baik diluar maupun di dalam lingkungan keluarga dalam rangka menopang kelangsungan dan perkembangan kehidupan keluarga
b) Mengelola ekonomi keluarga sehingga terjadi keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran keluarga
c) Mengatur waktu sehingga kegiatan orang tua di luar rumah dan perhatiannya terhadap anggota keluarga berjalan serasi, selaras dan seimbang
d) Membina kegiata dan hasil ekonomi keluarga sebagai modal mewujudkan KKBS
8) Fungsi Pembinaan Lingkungan
Meningkatkan diri dalam ligkungan sosial budaya dan lingkungan alam sehingga tercipta lingkungan yang serasi, selaras, dan seimbang.
a) Membina kesadaran, sikap dan praktik pelestarian lingkungan hidup interen keluarga
b) Membina kesadara, sikap dan praktik pelestarian lingkungan hidup ekstern keluarga
c) Membina kesadaran, sikap dan praktik pelestarian lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang antara lingkugan keluarga dengan lingkungan hidup masyarakat sekitarnya
d) Membina kesadaran, sikap dan praktik pelestarian lingkungan hidup sebagai pola hidup keluarga menuju KKBS
Meskipun banyak fungsi-fungsi keluarga seperti disebutkan di atas, pelaksanaan fungsi keluarga di indonesia secara singkat dapat disebutkan sebagai berikut:
ASIH : Memberi kasih sayang, perhatian, rasa aman, hangat kepada seluruh anggota keluarga sehingga dapat berkembang sesuai usia dan kebutuhan ASAH : Memenuhi pendidikan anak sehingga siap menjadi manusia dewasa, mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan masa depan
ASUH : Memelihara dan merawat anggota keluarga agar tercapai kondisi yang sehat fisik, mental, sosial dan spiritual.
f. Tahapan Perkembangan Keluarga dan Tugas Perkembangan Keluarga Perawat keluarga perlu mengetahui tentang tahapan dan tugas perkembangan keluarga, untuk memberikan pedoman dalam menganalisis pertubuhan dan kebutuhan promosi kesehatan keluarga serta untuk memberikan dukungan pada keluarga untuk kemajuan dari satu tahap ke tahap berikutnya. Tahap perkembangan keluarga menurut Duvall & Miller (1985) ; Carter & Mc Goldrick (1988), mempunyai tugas perkembangan yang berbeda seperti:
1) Keluarga dengan anak remaja (anak tertua berumur 13-20 tahun)
Tugas perkembangan keluarga pada tahap V yaitu menyeimbangkan kebebasan dan tanggung jawab ketika remaja menjadi dewasa dan mandiri, memfokuskan kembali hubungan perkawinan, berkomunikasi secara terbuka antara orang tua dan anak-anak, memberikan perhatian, memberikan kebebasan dalam batasan tanggung jawab, mempertahankan komunikasi terbuka dua arah.
2. Kosep Proses Keperawatan Keluarga a. Pengkajian Keperawatan
1) Pengkajian Keluarga
Pengkajian adalah suatu tahapan di mana seorang perawat mengambil informasi secara terus menerus terhadap anggota keluarga yang dibinanya. Agar di peroleh data pengkajian yang akurat dan sesuaidengan keadaan keluarga, perawat diharapkan menggunakan bahasa yang mudah dimegerti yaitu bahasa yang digunakan dalam aktivitas keluarga sehari-hari.
2) Proses Pengkajian
Proses pengkajian dimulai dengan mengumpulkan informasi secara terus-menerus, dalam hal ini data dikumpulkan secara sistematis (dengan menggunakan alat pengkajian keluarga), kemudian diklasifikasikan dan dianalisis. Jika dalam pengkajian, perawat menemukan datayang bermakna atau berpotensi masalah maka digali lebih mendalam. Pengumpulan data merupakan syarat utama untuk pengidentifikasi masalah. Dalam pelaksanaannya proses pengkajian keperawatan bersifat dinamis, interaktif dan fleksibel.
3) Sumber-sumber Pengkajian Data
Pengumpulan data tentang keluarga didapatkan dari berbagai sumber di antaranya adalah: 1). Wawancara dengan klien dalam hubungannya dengan kejadian pada waktu lalu dan sekarang. 2). Temuan-temuan yang objektif (misal, observasi terhadap rumah dan fasilitas-fasilitas yang ada didalamnya). 3). Informasi-informasi tertulis atau lisan dan rujukan, berbagai lembaga yang menangani keluarga dan anggota tim kesahatan lainnya.
Salah satu peran penting dalam perawat kesehata keluarga adalah menjadi partisipasi pengawal dalam keluarga, sementara perawat bekerja secara aktif dalam keluarga. Ia juga harus memiliki kemampuan “melangkah mundur” dan secara objektif mengobservasi kodisi dan situasi di rumah.
Selai denga wawancara, dalam proses pengumpulan data dapat digunakan pula daftar cek, intervensi, kuesioner (Holman, 1983)
4) Membangun Hubungan Saling Percaya
Salah satu fungsi perawat keluarga adalah menciptakan hubugan salig percaya. Menciptakan hubungan saling percaya adalah dimana adalanya saling terbuka, saling menghormati dan momunnikasi berjalan dengan efektif. Hubungan saling percaya dapat di kembangkan dengan menyampaikan tujuan kunjungan, menerima dan megakui hak-hak keluarga pada perasaan dan keyakinan mereka sendiri tanpa keluar dari tujuan, nilai-nilai dan harapan perawat. Diawali dengan memberi kesempatan keluarga mengungkapkan persoalan dan masalahnya sendiri kemudian perawat memahami persoalan berdasarkan pengalamannya, pada akhirnya bersama-sama keluarga mendalami persoalan dan dilanjutkan dengan pemecahan persoalan secara bersama-sama.
5) Persiapan Untuk Kunjungan Keluarga
Cara yag efektif dalam persiapan kunjungan adalah: 1). Membaca catatan (medical record) dari keluarga yang akan di kujungi; 2). Mendiskusikan dengan tim keperawatan yang mengenal keluarga yang di maksud; 3). Mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan yang mungkin muncul pada keluarga; 4). Buat kontrak perjajian dengan keluarga yang akan di kunjungi (melalui telepon, lisan atau surat) dan perkenalkan diri terlebih dahulu, utarakan maksud dan tujuan kunjungan anda, dan buatlah persiapan (Leahay et. Al. 1977).
Setelah selesai mengumpulkan data, langkah berikutnya adalah analisa data. Data perlu diringkas dan disusun kemudian dikelompokkan. Kemudian kelompokkan data-data yang sama dan susun dalam bentuk yang teratur sehingga dapat dibuat kesimpulan yang akurat dan masalah-masalah dapat diidentifikasi.
6) Kekuatan-kekuatan Keluarga
Dalam menganalisa data, kekuatan-kekuatan keluarga sangat perlu diidentifikasi. Kekuatan-kekuatan tersebut dapat digunkan sebagai sumber ketika dilakukan perencanaan intervensi. Powerdan Dell Orto (1988)
Pengkajian asuhan keperawatan keluarga menurut teori/model Family Centre
Nursing Fridman, meliputi 7 kompone pengkajian yaitu:
a. Identitas kepala keluarga 1) Nama kepala keluarga (KK) 2) Umur (KK)
3) Pekerjaan Kepala Keluarga (KK) 4) Pendidikan Kepala Keluarga (KK) 5) Alamat dan Nomor Telepon
b. Komposisi anggota keluarga nama umur sex Hub
dgn kel
pendidikan pekerjaan ket
c. Genogram :
Genogram harus menyangkut minimal 3 geerasi, harus tertera nama, umur, kondisi kesehatan tiap keterangan gambar. Terdapat keterangan gambar dengan simbol berbeda (Fridman,1988) sepert :
Laki-laki : Perempua :
Meninggal Dunia :
Tinggal Serumah : --- Pasien yang Diidentifikasi :
Kawin :
Cerai :
Aborsi/ Keguguran :
Anak Kembar :
d. Tipe keluarga e. Suku bangsa :
1) Asal Suku Bangsa Keluarga 2) Bahasa yang Dipakai Keluarga
3) Kebiasaan Keluarga yang dipengaruhi suku yang dapat mempengaruhi kesehatan
f. Agama :
1) Agama yang dianut keluarga
2) Kepercayaan yang mempengaruhi kesehatan g. Status Sosial Ekonomi Keluarga :
1) Rata-rata penghasilan seluruh anggota keluarga 2) Jenis pengeluaran keluarga tiap bulan
3) Tabungan khusus kesehatan
4) Barang (harta benda) yang dimiliki keluarga (perabotan, transportasi) h. Aktifitas rekreasi keluarga
II. Riwayat dan Tahap Perkembangan Keluarga
a. Tahap perkembangan keluarga saat ini (ditentukan dengan anak tertua) b. Tahap perkembangan keluarga yang belum terpenuhi
c. Riwayat keluarga inti :
1) Riwayat terbentunya keluarga inti
2) Penyakit yang diderita keluarga orag tua (adanya penyakit menular atau penyakit menular di keluarga)
d. Riwayat keluarga sebelumnya (suami istri) :
1) Riwayat penyakit keturunan dan penyakit menular di keluarga 2) Riwayat kebiasaan/ gaya hidup yang mempengaruhi kesehatan III. Lingkungan
a. Karakteristik rumah :
1) Ukuran rumah (luas rumah) 2) Kondisi dalam dan luar rumah 3) Kebersihan rumah
4) Ventilasi rumah
5) Saluran pembuangan air limbah (SPAL) 6) Air bersih
7) Pengelolaan sampah 8) Kepemilikan rumah 9) Kamar mandi/wc 10) Denah rumah
b. Karakteristik tetangga dan komunitas tempat tinggal : 1) Apakah ingin tinggal dengan satu suku saja 2) Aturan dan kesepakatan penduduk setempat 3) Budaya setempat yang mempengaruhi kesehatan c. Mobilitas geografis keluarga :
1) Apakah keluarga sering pindah rumah
2) Dampak pidah rumah terhadap kondisi keluarga (apakah menyebabkan stres)
d. Perkumpulan keluarga dan interaksi dengan masyarakat
1) Perkumpulan/organisasi sosial yang diikuti oleh anggota keluarga 2) Digambarkan dalam ecomap
Termasuk siapa saja yang terlibat bila keluarga mengalami masalah IV. Struktur keluarga
a. Pola komunikasi keluarga :
1) Cara dan jenis komunikasi yang dilakuka keluarga 2) Cara keluarga memcahkan masalah
b. Struktur kekuatan keluarga
1) Respon keluarga bila ada anggota keluarga yang mengalami masalah 2) Power yang digunakan keluarga
c. Struktur peran (formal fan informal) : 1) Peran seluruh anggota keluarga d. Nilai dan norma agama
V. Fungsi keluarga a. Fungsi afektif :
1) Bagaimana cara keluarga mengekspresikan perasaan kasih sayang 2) Perasaan saling memiliki
3) Dukungan terhadap anggota keluarga 4) Saling menghargai, kehangatan b. Fungsi sosialisasi :
1) Bagaimana memperkenalkan anggota keluarga dengan dunia luar 2) Interaksi dan hubungan dalam keluarga
c. Fungsi perawatan kesehatan :
1) Kondisi perawatan kesehatan seluruh anggota keluarga (bukan hanya kalau sakit diapakan tetapi bagaimana prevensi/promosi)
2) Bila ditemui data maladaptif, langsung lakukan penjajagan tahap II (berdasarkan 5 tugas keluarga seperti bagaimana keluarga mengenal masalah, mengambil keputusan, merawat anggota keluarga, memodifikasi lingkugan dan memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan)
VI. Stress dan koping keluarga