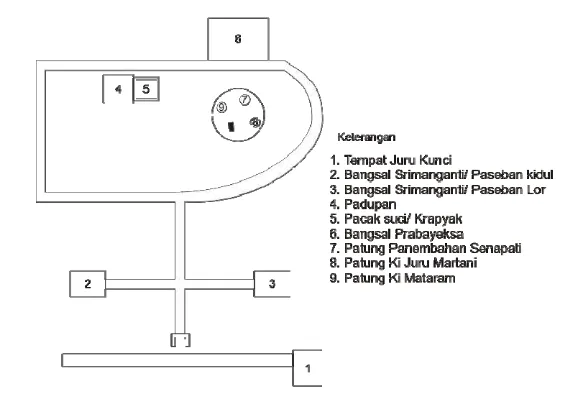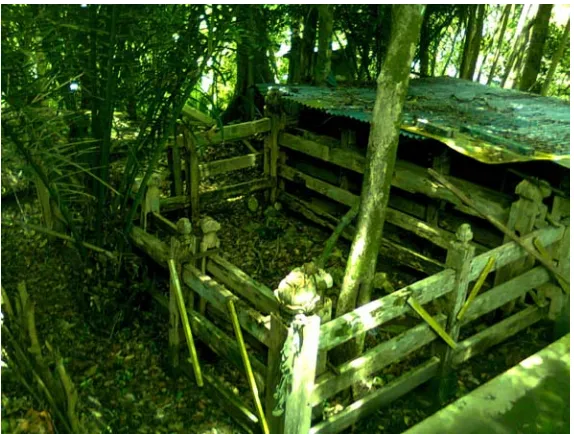Tugas Akhir
Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Program Studi Sastra Indonesia
Oleh
MATHEUS NASTITI NURCAHYO WIJAYA
NIM : 044114006
PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA
JURUSAN SASTRA INDONESIA FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
DI PERTAPAAN BANG LANPIR : KAJIAN FOLKLOR
Tugas Akhir
Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Program Studi Sastra Indonesia
Oleh
MATHEUS NASTITI NURCAHYO WIJAYA
NIM : 044114006
PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA
JURUSAN SASTRA INDONESIA FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA
i
MOTTO
Hidup akan lebih bahagia kalau kita dapat menikmati apa yang kita miliki. Karena itu bersyukur merupakan kualitas hati yang tertinggi.
Bersyukurlah !
Bersyukurlah bahwa kamu belum siap memiliki segala sesuatu yang kamu inginkan . Seandainya sudah, apalagi yang harus diinginkan?
Bersyukurlah !
Bersyukurlah apabila kamu tidak tahu sesuatu . Karena itu memberimu kesempatan untuk belajar .
Bersyukurlah !
Bersyukurlah untuk masa-masa sulit . Karena Di masa itulah kamu tumbuh …
Bersyukurlah !
Bersyukurlah untuk keterbatasanmu .
Karena itu memberimu kesempatan untuk berkembang .
Bersyukurlah untuk setiap tantangan baru . Karena itu akan membangun kekuatan dan karaktermu .
Bersyukurlah untuk kesalahan yang kamu buat . Itu akan mengajarkan pelajaran yang berharga .
Bersyukurlah bila kamu lelah dan letih . Karena itu kamu telah membuat suatu perbedaan .
Mungkin mudah untuk kita bersyukur akan hal-hal baik…
Hidup yang berkelimpahan datang pada mereka yang juga bersyukur akan masa surut… Rasa syukur dapat mengubah hal yang negatif menjadi positif …
Temukan cara bersyukur akan masalah-masalahmu dan semua itu akan menjadi berkah bagimu …
Jika kita melayani, maka hidup akan lebih berarti
HALAMAN PERSEMBAHAN
Skripsi ini aku persembahkan kepada:
kedua orangtuaku
Bapak L. Danis Subroto dan A. Titi Savitri,
Kakak dan adikku
R.B.N Diyan Wijanarko (Chataq) dan N. Eksi Prana Wijayanti (Eksi),
dan untuk kekasihku
Sinarku (Odilia Kunthi Wulandari)
Aku sangat mencintai kalian semua
ABSTRAK
Wijaya, Matheus Nastiti Nurcahyo. 2011. Ritual Nggayuh Wahyu di Pertapaan Bang Lanpir: Kajian Folklor. Skripsi Strata 1 (S-1). Program Studi Sastra Indonesia, Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma.
Skripsi ini membahas tentang mistik kejawen ritual nggayuh wahyu di Pertapaan Bang Lanpir: kajian folklor. Studi ini mempunyai tiga tujuan yaitu (1) Mendeskripsikan sejarah ditemukannya Pertapaan Bang Lanpir sebagai tempat diterimanya wahyu, (2) Mendeskripsikan bagaimana ritual di Pertapaan Bang Lanpir, (3) Menjelaskan nilai budaya di Pertapaan Bang Lanpir.
Judul ini dipilih karena studi mengenai ritual nggayuh wahyu di Pertapaan Bang Lanpir sepanjang pengetahuan penulis belum pernah dilakukan. Ritual
nggayuh wahyu memiliki nilai budaya yang sangat penting yaitu mengajarkan keselarasan hidup dan hubungan yang harmonis antara diri sendiri, lingkungan sekitar dan dengan Sang Pencipta.
Pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan Folklor. Penelitian ini menggunakan empat teknik pengumpulan data yaitu teknik wawancara,observasi, kepustakaan, dan dokumentasi.
Hasil penelitian mengenai ritual nggayuh wahyu yang dilaksanakan di Bang Lanpir adalah sebagai berikut : (1) Sejarah Pertapaan Bang Lanpir yang terdiri dari sejarah Dinasti Mataram Islam, sejarah Bumi Mentaok, sejarah Bang Lanpir sebagai tempat diterimanya wahyu kelapa, sejarah bangunan
Bang Lanpir, sejarah nama bang Lanpir. (2) Ritual nggayuh wahyu di
pertapaan Bang Lanpir. Penulis memberikan dahulu penjelasan tentang komponen ritualnya yaitu juru kunci, ritualis, sesaji dan maknanya, waktu dan tempat ritual dan tata cara ritual. Selain itu, hal yang dipandang cukup penting adalah tentang larangan yang terdapat di Bang Lanpir. Dari semua hal itu terselip nilai-nilai budaya. Nilai budaya yang terkandung dalam Pertapaan Bang Lanpir dan ritualnya adalah nilai ekonomi, nilai sosial, nilai estetika dan nilai agama. Semua nilai yang terkandung, merupakan sarana untuk menerapkan pendidikan kepada masyarakat.
ABSTRACT
Wijaya, Matheus Nastiti Nurcahyo. 2011. Ritual Nggayuh Wahyu di Pertapaan Bang Lanpir: Kajian Folklor. Skripsi Strata 1 (S-1). Program Studi Sastra Indonesia, Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma.
This thesis is about the mystical Javanese ritual Discussing nggayuh wahyu in the Hermitage Bang Lanpir: study of folklore. This study has three objectives: (1) Describe the history of the discovery of Bang Lanpir Hermitage as a place of receipt of wahyu, (2) Describe how the ritual in the Hermitage Bang Lanpir. (3) Explain the value of culture in the Hermitage Bang Lanpir.
The title was chosen because the study of ritual nggayuh wahyu along the Hermitage Bang Lanpir authors knowledge has not been done. Ritual nggayuh wahyu has a very important cultural value that is taught harmony of life and a harmonious relationship between ourselves, the environment and with the God.
The approach used in this study is the approach of Folklore. This study used four data collection techniques of interviewing techniques, observation, literature, and documentation.
Results of research on rituals nggayuh wahyu which was held in Bang Lanpir are as follows: (1) History of the Hermitage Bang Lanpir which consists of the history of Islamic Mataram dynasty, Mentaok Earth's history, history as the place of receipt Bang Lanpir coconut wahyu, historical buildings Lanpir Bang, the history of the name Lanpir bang. (2) Ritual nggayuh wahyu in the hermitage Bang Lanpir. The author gives first an explanation of the ritual component of caretaker, ritualist, offerings and its meaning, time and place of rituals and procedures of other ritual.hal deemed important enough is about the prohibition contained in Bang Lanpir. Of all the things that stuck cultural values. Cultural values contained in the Hermitage Bang Lanpir and rituals are of economic value, social value, aesthetic value and religious value. Of all the values contained, all is as a means to apply the education to the public.
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Bapa di Surga karena berkat
karuniaNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Ritual
Nggayuh Wahyu di Pertapaan Bang Lanpir: Kajian Folklor” yang disusun
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Program Studi
Sastra Indonesia, Jurusan Sastra Indonesia Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta.
Penulis menyadari bahwa studi ini tidak akan mungkin terselesaikan
tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah diberikan dengan segala
ketulusan dan keiklasan. Dengan segala kerendahan hati penulis
menyampaikan ucapan syukur dan semoga bantuan dan perhatian yang telah
diberikan oleh berbagai pihak kepada penulis akan selalu diberkati oleh Tuhan
yang selalu memberikan cinta kasihNya kepada semua umatNya. Dalam
kesempatan ini pula dari hati yang paling dalam penulis menyampaikan
terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :
Ibu S. E. Peni Adji, S.S, M. Hum selaku pembimbig I, dengan segala
perhatian dan kebijakan serta kebaikannya yang begitu tulus. Beliau
memberikan arahan dan masukan yang sangat berharga dan berarti bagi
penulis dan koreksi untuk perbaikan-perbaikan skripsi ditengah waktu yang
sangat berharga dan kesibukan tugas beliau sehari-hari. Dengan segala ucapan
dan nasehat beliau sangat menyejukkan hati dan menentramkan di saat penulis
menghadapi masa akhir studi dengan sesuatu yang mencemaskan, sehingga
membuat penulis lebih percaya diri. Pengalaman berbincang-bincang dengan
beliau sangat bermanfaat bagi penulis.
Ibu Dra. Fr. Tjandrasih Adji, M. Hum, Pembimbing II. Beliau dengan
penuh kearifan telah memberikan masukan dan arahan yang sangat berharga.
Dengan kesibukan masih meluangkan waktu untuk penulis di saat waktu yang
terbatas beliau telah memberikan motivasi agar cepat menyelesaikan penulisan
ini. Segala bimbingan dan nasehat beliau sangat bermanfaat untuk penulis
demi kemajuan studi.
Bapak Drs. Hery Antono, M. Hum Kaprodi Sastra Indonesia USD,
dengan segala kesibukan telah meluangkan waktu untuk membimbing saya
dengan masukan yang sangat bermanfaat untuk kemajuan penulis selanjutnya.
Beliau dengan telaten ngelingke penulis dan ngoyak-oyak supaya penulis bisa cepat menyelesaikan studi. Dengan ketulusan hati telah memberikan dorongan
moril kepada penulis untuk selalu sabar dalam penulisan Skripsi ini. Dengan
senyum dan keramahannya beliau semangat pada penulis. Untuk itu semua
penulis menghaturkan terima kasih dan semoga penulis dapat belajar dari
keramahan dan ketulusan beliau selama ini.
Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Drs. Yapi Taum, M.
Hum, Bapak Dr. I. Praptomo Baryadi, M.Hum, Bapak Drs. P.Ari Subagyo,
M.Hum, Drs. B. Rahmanto, M. Hum, Pak Santosa. Juga kepada Pak Arwan
(alm), terima kasih atas masukan mengenai topik penelitianku ini. Tak lupa
staf sekretariat Mbak Ros dan Mas Tri.
Kepada narasumber, Pak Sarjono, Pak Kadi, Pak Tris dan GBPH
Joyokusumo. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk berbagi cerita
mengenai filsafat Jawa. Semua yang telah kalian ceritakan adalah harta yang
tak ternilai bagiku.
Selanjutnya secara khusus terima kasih dan bakti serta harapan
disampaikan penulis untuk :
Bapak R.L Danis Subroto dan Ibu Anastasia Titi Savitri yang telah
memberikan segala hal baik buruk dan segala hal mengenai ajaran cinta kasih.
Penulis mengucapkan terima kasih atas segala pengorbanan untuk mengasuh,
mendidik dan memberikan teladan untuk hidup secara sederhana dan takut dan
taat kepada firman Tuhan, untuk itu semua penulis mengucapkan terima kasih.
Penulis berdoa bapak dan ibu akan selalu ada dalam lindungan kasih Kristus.
Bulik-bulik, Bu Nani dan Bu yanti yang sudah seperti orang tua angkat
penulis, beliau telah mendidik dan mengasuh semasa kecil hingga besar, juga
membantu kehidupan ekonomi keluargaku. Untuk itu penulis ucapkan terima
kasih dan doa semoga mendapatkan limpahan kasih Kristus.
Kepada kakak yang tercinta mas Diyan dan adikku yang kucintai yang
selalu mendukung selama penulis studi selama ini dengan selalu bertanya,
kapan rampunge?, kapan luluse?, meh ujian kapan?
Seseorang kekasih yang bernama Odilia Kunthi Wulandari yang telah
menjadi teman dan sahabat di saat duka dan suka, yang selalu mendukung
dengan penuh kasih, setia menunggu ketika diriku kehilangan arah dan yang
mengisi hari-hari dengan penuh warna…(”Makasih udah mengajarkan untuk
bersabar…mengajarkan pengampunan, kesetiaan dan kenyataan bahwa semua akan bisa takluk hanya karena kasih”)
Ucapan terima kasihku juga kuucapkan kepada kawan-kawan Siesen
Insadha, mudika St. Anna, Daemon Aerish, Duff dan Mellow. Kalian adalah
pengisi jiwaku yang sepi. Tanpa kalian aku adalah sepi.
Spesial dan takkan lupa terima kasih untuk teman-teman Sastra
Indonesia angkatan 2004. ”Kawan-kawan, ternyata aku tak bisa lulus tepat
waktu”.
Yogyakarta, 15 Juni 2011
Penulis
Matheus Nastiti Nurcayho W
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ... i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ... ii
HALAMAN PENGESAHAN ... iii
BAB II SEJARAH PERTAPAAN BANG LANPIR ... 21
2.1 Pengantar ... 21
2. 2 Sejarah Dinasti Mataram Islam ... 21
2.3 Sejarah Bimi Mentaok ... 27
2.4 Sejarah Bang Lanpir versi Juru Kunci ... 31
2.5 Sejarah Bangunan Bang Lanpir ... 35
xiv
2.6 Sejarah Nama Bang Lanpir ... 43
BAB III KOMPONEN DAN TATA CARA RITUAL NGGAYUH WAHYU DI PERTAPAAN BANG LANPIR ... 47
3.1 Pengantar ... 47 WAHYU DI PERTAPAAN BANG LANPIR ... 65
BAB I
PENDAHULUAN
I. 1 Latar Belakang Masalah
Mistik kejawen adalah suatu upaya (laku) spiritual ke arah pendekatan diri terhadap Tuhan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Jawa. Upaya
tersebut bisa digolongkan dalam kelompok yang disebut ”mistisme” yang
berusaha untuk mempersatukan jiwa manusia dengan Tuhan. Golongan ini
sejalan dengan teori kebatinan yang dikemukakan Mulder yang bertitik tolak
dari pandangan umum, bahwa segala sesuatu yang hidup itu satu atau tunggal.
Manusia dipandang sebagai percikan dari Zat Hidup yang meliputi segala
sesuatu, manusia mempunyai dua segi, lahir dan batin. Melalui segi batin
manusia dapat mencapai persatuan dengan Zat Hidup (Imam, 2005: 88).
Secara khusus tempat yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah
petilasan Ki Ageng Pemanahan dan Panembahan Senapati, Pertapaan Bang
Lanpir di Desa Girisekar, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul.
Tempat ini merupakan pertapaan Ki Ageng Pemanahan ketika mencari wahyu
keraton Mataram. Banyak alasan mengapa tempat ini banyak dikunjungi, salah
satunya adalah karena tempat ini dipercaya sebagai cikal bakal dinasti
Mataram Islam, yaitu tempat munculnya Wahyu Mataram pertama kali.
Wahyu sebelum Ki Ageng Pemanahan berkuasa dan mendirikan kerajaan
yang dikenal dengan Mataram Islam.
Dalam keyakinan orang Jawa dikatakan bahwa raja sebagai kinarya
wakiling Hyang Agung (wakil dari Tuhan di dunia). Raja bertugas memelihara hukum dan keadilan. Untuk itu setiap rakyat harus taat kepada raja, barang
Hyang Agung (menentang kehendak Tuhan yang maha besar), maka siapa pun yang mengabdi harus taat kepadanya tanpa syarat atau lebih dikenal dengan
ngawula Gusti dalam masa sekarang ini kita kenal orang-orang yang
mengabdi ini desebut dengan abdi dalem. Sebuah kerajaan yang diyakini
orang Jawa adalah dinasti Mataram. Sampai saat ini masih terdapat sisa
kekuasaan Mataram yang terbesar yaitu Kraton Kasunanan Surakarta, Kraton
Kasultanan Yogyakarta, Kraton Pura Mangkunegaran Surakarta, dan Kraton
Pura Pakualaman Yogyakarta (Purwadi, 2007: 156).
Untuk mencapai sebuah kekuasaan dan menjadi seorang raja yang
dianggap sebagai kinarya wakiling Hyang Agung (wakil dari Tuhan di dunia)
maka, sesorang harus mendapatkan pulung, wahyu dan ndaru yang harus
dicapai melalui laku spiritual (Purwadi, 2007: 158).
Kekuasaan dalam budaya Jawa diperoleh melalui proses turunnya
pulung, wahyu, dan ndaru. Ketika seseorang mampu mencapai tingkatan
tertentu, dirinya akan mudah menerima apa saja dari Tuhan. Termasuk di
dalamnya, adalah pulung, wahyu, dan ndaru (Purwadi, 2007: 158).
Endraswara dalam bukunya Mistik Kejawen ( 2003: 215) menjelaskan
bahwa Pulung adalah cahaya berwarna biru cerah dan hijau terang, yang
merupakan perpaduan cahaya emas, permata, dan timah. Orang yang
menerima pulung, biasanya akan mendapatkan kabegjan (keberuntungan)
yang telah seukur dengan dirinya. Tanda-tanda orang akan mendapatkan
pulung berupa wahyu, yaitu cahaya berwarna putih dan kuning cerah,
perpaduan dari cahaya permata, perak, dan timah. Wahyu tersebut akan
berbingar-bingar dan lebih berwibawa dalam hidupnya. Dia akan menerima
ndaru pada malam hari, biasanya di waktu dua pertiga malam.
Sewaktu terjadi pemilihan kepala desa (pilkades), para calon kades itu
biasanya saling berebut pulung. Mereka datang ke dukun-dukun, orang tua, atau tempat keramat atau kuburan leluhur hanya demi keinginannya untuk
mendapatkan pulung kekuasaan tersebut (Purwadi, 2007: 61).
Penulis menyimpulkan bahwa dalam konsep kepercayaan orang Jawa,
untuk menjadi seorang raja atau penguasa, wahyu adalah hal yang paling
pokok. Tanpa wahyu, sang raja maupun sang penguasa tak diakui
keberadaannya oleh rakyat dan tak akan menjadi kuat.
Bermacam-macam definisi dari wahyu. Ada yang menyebut bahwa
wahyu adalah karunia Tuhan. Wahyu dari Tuhan dipercaya tak akan turun ke lebih dari satu orang, maka banyak orang yang saling berebut wahyu untuk
mendapatkan kekuasaan atau dalam bahasa Jawa sering disebut sebagai jimat, kemat, pangkat. Jimat biasa kita sebut sebagai sesuatu hal yang kita bawa
dan dipercaya membawa sebuah kekuatan bagi yang memegang. Kemat,
maksudnya adalah kehormatan atau wibawa, dan pangkat adalah sebuah
jabatan tertentu (Subroto, wawancara pribadi, 20 Oktober 2008)
Proses turunnya wahyu, pulung atau ndaru biasanya diperoleh melalui jalan atau laku mistik, salah satu cara yakni dengan bertapa. Endraswara ( 2003: 215) menjelaskan bahwa jika pelaku mistik melakukan semedi atau
bertapa akan merasa heneng, hening,eling, lalu sampai tingkatan mayangkara
(untuk pria) dan mayang sakara (untuk wanita). Keduanya sering disebut
mayang gaseta. Mayang artinya cinta suci dan gaseta berarti Gusti. Mayang
tingkatan itu, dirinya akan mudah menerima apa saja dari Tuhan. Termasuk di
dalamnya adalah pulung, wahyu, dan ndaru.
Proses semedi atau bertapa hingga mencapai heneng, hening,eling itu sering disebut orang Jawa sebagai klenik. Menurut pendapat Probosutedjo via Artha (2007: 15), klenik itu disampaikan dengan cara berbisik-bisik atau
glenikan. Oleh sebab itu, disebut ilmu klenik atau ilmu kebatinan.
Probosutedjo menggambarkan ilmu klenik seperti saat kita membaca buku di
tempat ramai, atau di dalam kereta atau di atas bus, tidak diucapkan melainkan
hanya dengan batin.
Penjelasan mengenai mistik kejawen demi mendapatkan wahyu yang
dilakukan para penganut kejawen jelas memiliki tujuan yang mulia. Tujuan
utamanya adalah memperoleh ngelmu sejati yang akan menjadi bekal
manunggaling kawula Gusti, mereka mampu berkonsentrasi membentuk
benteng diri untuk menghadang angkara murka pribadi dan selalu berserah diri
kepada Tuhan. Dengan bekal itu manusia akan dapat menjalankan kewajiban
hidup luhur dengan rasa tenang (Endraswara, wawancara pribadi, 19
September 2008)
Pertapaan Bang Lanpir merupakan tempat yang dianggap keramat dan
para pelakunya pun melakukan laku mistik Kejawen untuk nggayuh wahyu.
Hal yang menarik adalah, bagaimana asal mula Pertapaan Bang Lanpir dan
praktik mistik kejawen nggayuh wahyu itu terjadi. Hal-hal tersebutlah yang memotivasi penulis untuk melakukan studi lapangan untuk memaparkan dan
mengungkapnya secara tuntas.
Ada beberapa alasan penulis memilih topik ‘Wahyu di Pertapaan Bang
Istimewa Yogyakarta sebuah kajian folklor’. Pertama, berkaitan dengan
tempat objek penelitian, yaitu Pertapaan Bang Lanpir yang dipercaya sebagai
awal dan saksi sejarah terbentuknya kerajaan Mataram Islam, sepengetahuan
penulis belum pernah ada penelitian yang mengaji mengenai hal ini.
Alasan ke dua, banyak yang datang untuk nggayuhwahyu di pertapaan Bang Lanpir dengan harapan mendapatkan jimat, kemat, dan pangkat. Peneliti ingin mengungkap proses terjadinya wahyu dan laku spiritualnya.
Alasan ketiga, banyak orang yang memaknai istilah mistik Kejawen
sebagai sesuatu yang negatif dan bersifat irasional. Pemikiran negatif ini
melekat karena mistik Kejawen selalu melekat dengan kata ”klenik”. Mistik kejawen selalu identik dengan sesaji untuk roh halus, padahal laku mistik
Kejawen bukanlah hal yang negatif. Peneliti ingin membantu masyarakat
meluruskan pandangan laku mistik Kejawen yang sering dianggap negatif.
Mistik Kejawen adalah cara berdoa orang Jawa yang diungkapkan dengan
simbol sesaji kepada Tuhan dan laku spiritual dengan cara semedi.
I. 2 Rumusan masalah
Berdasarkan uraian di atas, masalah-masalah yang dibahas dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut.
I.2.1 Bagaimana sejarah Pertapaan Bang Lanpir sebagai tempat nggayuh
wahyu?
I.2.2 Bagaimana komponen dan tata cara ritual nggayuh wahyu di Pertapaan Bang Lanpir?
I. 3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas,
penelitian ni bertujuan untuk :
I.3.1 Melacak dan mendeskripsikan sejarah ditemukannya Pertapaan Bang
Lanpir sebagai tempat diterimanya wahyu keprabon.
I.3. 2 Mendeskripsikan bagaimana komponen dan ritual nggayuh wahyu di
Pertapaan Bang Lanpir.
I.3. 3 Mendeskripsikan nilai budaya di Pertapaan Bang Lanpir.
I. 4 Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini berupa deskripsi tentang Sejarah Pertapaan Bang
Lanpir dan komponen ritual yang digunakan di pertapaan itu. Dalam bidang
sastra lisan atau folklore, Penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai
tradisi lisan yang ada di sekitar kita. Dalam bidang sejarah, penelitian ini dapat
menambah wawasan mengenai cerita asal usul wahyu yang didapatkan para
pemimpin sebelum mereka bertahta. Hasil penelitian ini juga menambah
referensi baru tentang situs religi dan budaya di Indonesia.
I. 5 Tinjauan Pustaka
Penelitian yang berkaitan dengan mistik kejawen memang bukan hal
baru dalam ilmu budaya. Hadiwidjono (1984) dalam bukunya Kebatinan Jawa
dalam Abad Sembilan Belas lebih terfokus pada deskripsi kehidupan aliran
kebatinan saja.
penelitian ini hanya terfokus pada pembahasan terhadap karya-karya R. Ng
Ranggawarsita.
Fokus penelitian yang telah dilakukan di atas jelas berbeda dengan
penelitian ini yang lebih difokuskan pada laku mistik kejawen demi
mendapatkan wahyu. Hal yang berbeda di Pertapaan Bang Lanpir ini adalah
orang-orang biasanya mencari restu untuk kenaikan pangkat ataupun jabatan.
Belum ada penelitian mengenai Pertapaan Bang Lanpir dari perspektif
mana pun. Hanya saja dalam situs resmi Rumah Budaya Tembi dituliskan
Bang Lanpir merupakan petilasan Ki Ageng Pemanahan yang terletak di Desa
Girisekar, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul. Tempat ini
merupakan pertapaan Ki Ageng Pemanahan ketika mencari wahyu kraton
Mataram (http://www.tembi.org/mataram/mataram02.htm)
I. 6 Landasan Teori
I. 6. 1 Folklore
Teori ini akan dipakai untuk menjelaskan laku mistik nggayuh wahyu di Pertapaan Bang Lanpir. Banyak hal yang akan dijelaskan adalah berkaitan
dengan sejarah, bagaimana laku mistik pengunjung, dan motif para pelaku datang ke Pertapaan Bang Lanpir seperti apa yang dibicarakan di masyarakat
selama ini.
Folklor berasal dari kata folklore (bahasa Inggris). Jika dieja menjadi folk artinya ‘rakyat’ dan lore artinya ‘tradisi’. Folk adalah kelompok atau kolektif yang memiliki ciri-ciri pengenal kebudayaan yang membedakan
dengan kelompok lain. Lore merupakan wujud tradisi dari lore. Tradisi
tradisi rakyat yang sebagian disampaikan secara lisan, yaitu kelisanan menjadi
pijakan folklor (Endraswara, 2005: 11).
Folklor adalah kebudayaan kolektif yang tersebar dan diawariskan
turun-temurun secara tradisional dalam versi yang berbeda baik dalam bentuk
lisan maupun tulisan (Danandjaja, 1984: 2). Folklor Indonesia yang berjenis
lisan ada dua jenis, yaitu kepercayaan rakyat dan permainan rakyat
(Danandjaja, 1984: 153).
Folklor berasal dari dua kata dasar folk dan lore. Folk artinya “sekelompok orang yang memiliki ciri pengenal fisik, sosial, dan kebudayaan
sehingga dapat dibedakan dari kelompok lainnya. Sedangkan lore adalah
‘tradisi folk’ yaitu sebagian dari kebudayaan yang diwariskan turun temurun secara lisan atau melalui contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat
pembantu pengingat. Jadi, folklor adalah sebagian kebudayaan yang kolektif dan diwariskan secara turun temurun secara lisan, baik yang disertai dengan
gerak isyarat atau alat pembantu pengingat” (Danandjaja, 2002 : 1-2).
Menurut Brunvand via Danandjaja (2002 : 21-22) folklor dapat
digolongkan ke dalam tiga kelompok besar berdasarkan tipenya: (1) folklor
lisan (verbal fololore), (2) folklor sebagian lisan (partly verbal folklore), (3) folkor bukan lisan (non verbal folklore). Folklor lisan adalah folklore yang bentuknya memang murni lisan. Bentuk-bentuk (genre) folklor yang termasuk ke dalam kelompok besar ini antara lain (a) bahasa rakyat (folk speech) seperti logat, julukan, pangkat tradisional, dan titel kebangsawanan; (b) ungkapan
tradisonal, seperti peribahasa, pepatah, dan pemeo; (c) pertanyaan tradisonal,
seperti tekateki; (d) puisi rakyat, seperti pantun, gurindam dan syair; (e) cerita
lisan juga mempunyai fungsi sebagai penghibur atau senagai penyalur
perasaan yang terpendam
Folklor bukan lisan adalah folklor yang bentuknya bukan lisan,
walaupun cara pembuatannya diajarkan secara lisan. Kelompok besar ini dapat
dibagi menjadi dua subkelompok, yakni yang material dan yang bukan
material. Yang tergolong material antara lain: arsitektur rakyat (bentuk asli
rumah daerah, bentuk lumbung padi, dan sebagainya), kerajinan tangan rakyat;
pakaian dan perhiasan tubuh adat, makanan dan minuman rakyat, dan
obat-obatan tradisional. Sedangkan yang termasukyang bukan material antara lain:
gerak isyarat tradisional (gesture), bunyi isyarat untuk komunikasi rakyat (kentongan), dan musik rakyat.
Menurut Budiaman (1979: 14-15) betapa pentingnya kita mempelajari
folklor dalam rangka mengenal kebudayaan masyarakat tertentu karena fungsi
yang terkandung di dalamnya, yaitu sebagai sistem proyeksi yang dapat
mencerminkan angan-angan kelompok, sebagai alat pengesahan
pranata-pranata dan lembaga kebudayaan, sebagai alat pendidikan anak, dan sebagai
alat pemaksa dan pengawas agar norma-norma masyarakat dipatuhi.
Dari yang saya uraikan di atas, folklore merupakan salah satu sarana
yang berperan penting dalam masyarakat tradisional dalam menjaga
kelestarian adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Skripsi ini membahas
tentang ritual nggayuh wahyu di Pertapaan Bang Lanpir. Ritual nggayuh
wahyu di Pertapaan Bang Lanpir masuk ke dalam kelompok folklor lisan,
sebagian lisan dan bukan lisan. Sampai sekarang ritual nggayuh wahyu di
Pertapaan Bang Lanpir masih dilaksanakan baik dari pihak Kraton Yogyakarta
ritual nggayuh wahyu di Pertapaan Bang Lanpir sampai saat ini masih beredar turun temurun dan masih mempertahankan identitas Jawa.
I. 6. 2 Mistik Kejawen
Hadiwidjono via Endraswara (2006: 228) menjelaskan bahwa istilah
mistik kejawen pada dasarnya merujuk pada wacana budaya spiritual yanag
dianut oleh sebagian besar masyarakat Jawa. Budaya spiritual yang dimaksud
sebenarnya merupakan sinkriteisme antara agama Siwa, Budha, Hindu, dan
Islam yang diramu menjadi bentuk kebatinan Jawa. Dalam hal ini
Koentjaraningrat (1984: 312) juga menyatakan bahwa sinkreteisme telah
diolah dan disesuaikan dengan adat istiadat Jawa, lalu dinamakan agama Jawa atau Kejawen dan selanjutnya menjadi tradisi rakyat.
Penulis akan menggunakan teori menurut Prawirohardjono via
Endraswara (2006: 229) untuk menjelaskan proses laku mistik kejawen yang dilakukan oleh para pengunjung Pertapaan Bang Lanpir. Dimulai dari awal
laku hingga hasil dari ritual dan semua komponen yang terlibat. Tata cara yang dilakukan oleh pelaku mistik untuk melakukan ritual mistik menurut
Prawirohardjono adalah sebagai berikut :
(1) sebelum melakukan penghayatan ritual: sesuci, dengan
mencuci muka, tangan, kaki dan sebagainya, dan jika memungkinkan lebih utama mandi terlebih dahulu, (2) pakaian ritual: asal bersih, rapi dan sopan, bisa menggunakan warna putih berjubah, (3) tempat ritual: sembarang, di mana saja, (4) perlengkapan ritual: alas, lilin, (5) sikap: duduk saja terus-terusan, sambil memejamkan mata, tangan bebas dan serasi, sikap kepala/ muka menunduk, dapat berdiri, di kursi, (6) arah
penghayatan: bebas dan serasi, (7) upacara doa dan ritual:
Dari uraian tersebut dapat dinyatakan bahwa tata cara mistik kejawen
nomer (1) sampai (6), baru menunjukkan syarat terkait dengan sikap perilaku
seseorang melakukan meditasi. Nomor (7) telah menggambarkan bagaimana
proses seseorang melakukan mistik kejawen.
I. 6. 3 Wahyu
Menurut Pigeaud via Hadisiswaya (2009: 18) wahyu diartikan sebagai ruh atau kekuatan ilahi berupa petunjuk dari Tuhan. Bagi masyarakat Jawa,
wahyu atau pulung dianggap sebagai rahmat atau karunia untuk suatu
kedudukan tertentu. Selanjutnya, wahyu ini dibedakan dengan pulung yang berarti bintang kebahagiaan sebagai dasar kekuasaan. Wahyu ini diharapkan hadir bagi priyayi-gung, yaitu bangsawan tingkat tinggi dan diberlakukan pula bagi masyarakat luas sebagai manusia terpilih dalam suatu lingkungan tertentu
pula. Pulung cenderung berlaku umum untuk semua golongan masyarakat
sejak tingkat bawah hingga tingkat tinggi, sehingga tidak memiliki batas atas
kuasa Ilahi, Tuhan. Biasanya wahyu atau pulung ini berkaitan secara langsung dengan bidang kerohanian dan keagamaan, sehingga keduanya tidak dapat
dipaksakan ataupun dipindahkan dari manusia satu kepada manusia lainnya,
karena bersifat pribadi atau ruh. Untuk itu, keduanya tidak hanya diisyaratkan
untuk satu agama dan kepercayaan tertentu, atau hanya etnis tertentu, kaya
atau miskin, tua atau muda, dan seterusnya. Wahyu yang telah lama dikenal
masyarakat Jawa ketika diperintah oleh raja-raja tidak dapat terpisahkan oleh
petunjuk-petunjuk Sang pencipta jagad, Tuhan yang Maha Esa.
Dijelaskan pula mengenai wahyu oleh Endraswara dalam bukunya
kehidupan manusia dibagi menjadi tiga, yaitu (1) alam gaib, (2) alam rame atau alam mudita, dan (3) alam sunya ruri. Alam gaib, adalah alam ketika manusia Jawa belum ada. Manusia masih berada dalam alam yang sulit
dijangkau oleh panca indera. Yakni alam ketika manusia belum ada secara
wadhag (ujud). Alam rame atau alam mudita, adalah alam makhluk
perempuan dan laki-laki. Keduanya adalah pengisi dunia. Kedua makhluk ini
adalah penghias dunia. Sedangkan alam sunya ruri, berasal dari kata sunya (sepi) atau kosong dan ruri adalah suasana gelap gulita. Keadaan saat manusia mencapai tingkat kesunyian.
Dalam menjalankan semedi, pelaku mistik ingin mencapai Alam sunya
ruri , yakni alam yang suwung, tanpa batas, yang ada tetapi tak ada. Alam sunya ruri sebagai witing rame saka sepi, witing gumelar seka sonya, artinya alam ramai yang berasal dari sepi dan mulainya ada berasal dari sepi. Orang
yang berhasil mencapai alam sepi itu akan sampai kasunyatan. Alam
kasunyatan, ibarat dambaan orang Jawa ketika semedi (nutupi babahan hawa sanga) seperti sedang mencari tapake kontul nglayang, nggoleki galiheing
kangkung. Logikanya, tapak kaki kuntul atau bangau yang sedang terbang
tentu tidak ada. Begitu pula kalau manusia mencari galih batang kangkung
yang tengahnya berlubang, tentu ada tetapi tak ada (Endraswara, 2003: 215).
Pada waktu orang semedi akan merasa heneng, hening, eling, lalu
sampai tingkatan mayangkara (untuk pria) dan mayang sarkara (untuk
menerima apa saja dari Tuhan. Termasuk di dalamnya, adalah pulung, wahyu, dan ndaru (Endraswara, 2003: 215).
Pulung adalah cahaya berwarna biru cerah dan hijau terang, yang
merupakan perpaduan cahaya emas, permata, dan timah. Orang yang
menerima pulung, biasanya akan mendapatkan kabegjan (keberuntungan)
yang telah seukur dengan dirinya. Tanda-tanda orang yang akan mendapatkan
pulung berupa wahyu, yaitu cahaya berwarna putih dan kuning cerah,
perpaduan dari cahaya permata, perak, dan timah. Wahyu tersebut akan
diterimakan melalui laku (nenepi). Orang yang menerima wahyu, akan
berbingar-bingar dan lebih berwibawa dalam hidupnya. Dia akan menerima
ndaru pada malam hari, biasanya di waktu dua pertiga malam (Endraswara,
2003: 216).
Wahyu ada tiga wujud, yaitu: (a) wahyu nurbuwah, yaitu wahyu
keraton. Wahyu ini akan menandakan siapa yang kuat menjadi raja. Ia akan
menjadi raja utama, berwibawa, dan terhormat. Namun, hal ini juga bisa
dikiaskan bagi segala bentuk kekuasaan. Jadi, siapa saja yang mendapatkan
wahyu jenis ini akan mendapatkan kedudukan tertentu. Orang tersebut akan
bertambah wibawa dan sangat dihormati; (b) wahyu kukumah, yaitu berupa
cahaya berwarna kuning keemasan. Ini sebagai wahyu seseorang yang akan
menjadi raja adil paramarta dan (c) wahyu wilayah, yaitu wahyu yang diterima oleh seorang wali. Jika menerima wahyu ini, dia berhak menyebarkan wahyu
Tuhan (Endraswara, 2003: 216).
Sebagai tanda kalau seseorang telah mendapatkan wahyu, akan
pulung, wahyu, maupun ndaru akan nampak melalui tanda-tanda misalkan saja berupa teja (cahaya). Teja tersebut nampak adakalanya di tempat yang puncak dan sepi. Hal ini hanya dapat dimengerti oleh orang yang telah
memiliki daya linuwih sehingga pandai menggunakan ngelmu titen
(Endraswara, wawancara pribadi, 18 September 2008)
Dalam wawancara pribadi (25 Desember 2010) Joyokusumo
menjelaskan jika orang telah merasa khidmat dalam menjalani proses
liyep-layap ing ngaluyup dalam semedi, pulung, wahyu, dan ndaru akan mudah
diraih. Bahkan, pelaku akan memahami tiga hal, yaitu: (a) pangrasa, yaitu alat
untuk menghayati baik dan buruk, (b) pranawa, yaitu sarana batin untuk
menghayati kesenangan, dan (c) prawasa, batin untuk memahami rasa susah. Perpaduan tiga hal tersebut, pelaku mistik akan sadar kosmis, sehingga tahu
asal mula kejadiannya.
Dalam tradisi filsafat Islam, wahyu bahkan bertindak sebagai sumber
pengetahuan (Bakar via Boy Perdana 1997). Pengetahuan manusia yang
diperoleh melalui wahyu memiliki status yang spesifik, karena seorang
penerima pengetahuan melalui wahyu adalah orang yang memiliki otoritas
keagamaan tinggi yang sering diistilahkan dengan Nabi. Sementara manusia
biasa menerima keberadaan wahyu sebagai rukun iman yang harus dipercayai
secara taken for granted atau apa adanya. Para filosof berusaha untuk
mendudukkan wahyu sebagai realitas keilmuan yang bisa dikaji secara
I. 6. 4 Nilai Budaya
Allport, vernom dan Lindzey via Suriasumantri (1995: 263)
mengidentifikasikan enam nilai dasar dalam kebudayaan yakni nilai teori,
ekonomi, estetika, sosial, politik dan agama. Nilai teori adalah hakikat
penemuan kebenaran lewat berbagai metode seperti rasionalisme, empirisme
dan metode ilmiah. Nilai ekonomi mencakup kegunaan dari berbagai benda
dalam memenuhi kebutuhan manusia. Nilai estetika berhubungan dengan
keindahan dan segi-segi artistik yang menyangkut antara lain bentuk, harmoni
dan wujud kesenian lainnya yang memberikan kenikmatan manusia. Nilai
sosial berorientasi kepada hubungan antarmanusia dan penekanan segi
kemanusiaan yang luhur. Nilai politik berpusat kepada kekuasaan dan
pengaruh baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dunia politik.
Sedangkan nilai agama atau religi merengkuh penghayatan yang bersifat
mistik dan transcendental dalam usaha manusia untuk mengerti dan memberi
arti bagi kehadirannya di muka bumi karena anugrah Tuhan yang harus
disyukuri.
I.7 Metode Penelitian
Metode merupakan cara dan prosedur yang akan ditempuh oleh
peneliti dalam rangka mencari pemecahan masalah (Santosa, 2004: 8). Tulisan
ini disajikan menggunakan metode deskriptif analisis. Metode ini dilakukan
dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan
analisis. Dalam hal ini analisis tidak semata-mata menguraikan, melainkan
Penelitian ini menggunakan tiga jenis teknik pengumpulan data yaitu
teknik analisis data, dan teknik penyajian data. Penulis melakukan
pengumpulan data dengan teknik observasi, teknik wawancara mendalam,
teknik dokumentasi, penelusuran data online dan studi pustaka. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis.
I.7.1 Metode Pengumpulan Data
I.7.1. 1 Observasi
Sutrisno Hadi via Sugiyono (1999 :139) mengemukakan bahwa
observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun
dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting
adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik Pengumpulan data
dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku
manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati
tidak terlalu besar.
Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat
dibedakan menjadi (1) participant observation (observasi berperan serta) yaitu peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau
yang digunakan sebagai sumber data penelitian, (2) non participant
observation (observasi nonpartisipan) yaitu peneliti tidak terlibat dan ha nya sebagai pengamat independent (Sugiyono, 1999 :139).
Dari segi instrumentasi yang digunakan, maka observasi dapat
dibedakan menjadi (1) observasi terstruktur yaitu observasi yang telah
dirancang secara sistematis, tentang apa yang akan diamati, di mana
dengan pasti tentang variabel yang akan diamati, (2) observasi tidak
terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang
apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahu secara
pasti tentang apa yang akan diamati (Sugiyono, 1999: 140).
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi terstruktur,
observasi yang telah dirancang secara sistematis, karena penulis sudah
mengetahui tentang apa yang akan diamati dan di mana tempatnya yaitu
mengamati proses ritual, pandangan masyarakat tentang ritual nggayuh wahyu di Pertapaan Bang Lanpir serta makna, nilai budaya ritual nggayuh wahyu di Pertapaan Bang Lanpir.
I.7.1. 2 Wawancara
Wawancara sebagai suatu proses tanya jawab lisan, yaitu dua orang
atau lebih berhadap-hadapan secara fisik, yaitu satu dapat melihat muka yang
lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri (Hadi, 1979: 192). Metode
wawancara ini dilakukan dengan mewawancarai narasumber yang dianggap
mampu memberikan penjelasan tentang segala sesuatu mengenai Pertapaan
Bang Lanpir. Dalam hal ini, suatu percakapan meminta keterangan yang tidak
untuk tujuan suatu tugas, tetapi yang hanya untuk tujuan beramah-tamah,
untuk tahu saja, atau untuk ngobrol saja, tidak disebut wawancara. Seorang
anak bertanya-tanya kepada orang tuanya mengenai aneka warna hal, biasanya
I.7.1. 2.1 Wawancara Mendalam
Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh
keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap
muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai,
dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, di mana
pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.
Dengan demikian, kekhasan wawancara mendalam adalah keterlibatannya
dalam kehidupan informan (Bungin, 2008:108).
Dalam mengkaji tentang pertapaan Bang Lanpir ini penulis juga
menggunakan sumber data hasil wawancara dengan narasumber yaitu a) Juru
kunci pertapaan Bang Lanpir Bapak Sarjono dan Bapak Triono, b) Mantan
kepala Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Sukadi, c) Bapak
Danis Subroto yaitu salah satu pelaku di pertapaan dan pihak yang ikut
membangun pertapaan Bang Lanpir, d) GBPH Joyokusumo dari pihak Kraton
Yogyakarta, serta masih banyak lagi pihak yang perlu dimintai keterangan.
I.7.1. 3 Kepustakaan
Metode kepustakaan adalah mencari data mengenai hal-hal atau
variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, rapat, dan
sebagainya (Arikunto, 1993:234). Teknik kepustakaan digunakan untuk
mendapatkan data yang konkret. Pelaksanaan teknik ini yaitu menelaah
pustaka yang ada kaitannya dengan objek penelitian yaitu wahyu pertapaan
Bang Lanpir. Penulis mencari dan mengumpulkan data dari perpustakaan dan
I.7.1. 4 Teknik Dokumentasi
Teknik yang keempat adalah teknik dokumentasi. Teknik ini berupa
informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi
maupun perorangan, baik berupa tulisan maupun lisan. Teknik dokumentasi
dilakukan dengan wawancara mendalam, menggali informasi atau data
sebanyak-banyaknya dari responden atau informan agar informasi yang detail
diperoleh peneliti (Hamidi, 2004: 72-78). Melalui teknik dokumentasi, peneliti
menggunakan alat perekam untuk mendapatkan informasi dalam bentuk lisan.
Selain itu, teknik pencatatan juga digunakan untuk melengkapi data yang
sudah ada.
I.7.2. Metode Analisis Data
Skripsi ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif
merupakan penelitian tentang data-data yang lengkap secara tipikal dengan objek
penelitian berupa makna dibalik tindakan yang mendorong timbulnya gejala
sosial. Data dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan kaidah.
Kata-kata disusun menjadi kalimat, misalnya kalimat hasil wawancara antara
peneliti dengan informan. Karakter penelitian kualitatif, yaitu berusaha
mendapatkan informasi yang selengkap mungkin mengenai suatu hal
(http://www.damandiri.or.id/file/mariasugiharyaiunmuhsolobab3.pdf., download,
Desember 2009). Menurut Maryaeni (2005: 60), data-data penelitian kualiatif
berupa tulisan, rekaman dari ujaran lisan, gambar, angka, pertunjukan kesenian,
relief, beberapa bentuk data lain yang dapat ditransposisikan menjadi teks. Data
bersumber dari hasil survei, observasi, wawancara, dokumen, rekaman, hasil
evaluasi, dan lain-lain. Penelitian dilakukan melalui tiga tahap, yaitu
I.8 Sistematika penyajian
Penelitian ini terdiri dari beberapa bab. Bab I berisi pendahuluan.
Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, metode penelitian dan
sistematika penyajian.
Bab II berisi tentang sejarah ditemukannya pertapaan Bang Lanpir
sebagai tempat diterimanya wahyu. Sejarah yang ditampilkan meliputi sejarah
singkat kerajaan Mataram Islam, sejarah Bang Lanpir sebagai tempat
diterimanya wahyu menurut juru kunci, sejarah bangunan Bang Lanpir dan
sejarah nama Bang Lanpir.
Bab III berisi tentang komponen ritual di pertapaan Bang Lanpir,
termasuk tata cara ritualnya. Komponen ritualnya yaitu juru kunci, ritualis,
sesaji dan maknanya, waktu dan tempat ritual, tata cara ritual, larangan dan
nilai-nilai budaya yang terkandung.
Bab IV berisi tentang nilai budaya yang terkandung dalam ritual
nggayuh wahyu di Pertapaan Bang Lanpir. Nilai budaya akan diuraikan adalah nilai teori, nilai ekonomi, nilai sosial, dan nilai agama.
Bab V adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.
Kesimpulan yang dimaksud adalah kesimpulan tentang asal-usul Bang Lanpir
sebagai tempat diterimanya wahyu hingga populer di mayarakat dan tentang
tentang komponen ritual di pertapaan Bang Lanpir, termasuk tata cara
BAB II
SEJARAH PERTAPAAN BANG LANPIR
2.1 Pengantar
Pertapaan Bang Lanpir sangat erat hubungannya dengan kerajaan
Mataram. Tokoh yang menjadi intisari dan titik awal pertapaan Bang Lanpir
adalah pendiri Kerajaan Mataram Islam. Untuk lebih memperdalam asal-usul
pertapaan Bang Lanpir, maka akan diuraikan secara singkat sejarah dinasti
Mataram Islam, sejarah Bumi Mentaok, cerita perjalanan Ki Ageng
Pemanahan Menuju Wahyuning Kraton atau Wahyuning Ratu yang didapat
dari Wahyu Kelapadan sejarah nama Bang Lanpir.
2. 2 Sejarah Singkat Dinasti Mataram Islam
Bukti keberadaan Keraton Mataram itu masih dapat disaksikan
peninggalannya hingga saat ini. Bahkan keberadaan makam dari Panembahan
Senapati beserta keluarganya di Makam Raja-raja di Kota Gede. Dahulu
makam ini dikenal dengan “Makam 81 Tokoh Penting Mataram”. Pada
kelompok makam itu, antara lain dapat dijumpai makam Sultan
Hadiwijaya-Pajang dan Kyai Ageng Pemanahan. Makam lainya adalah penerus
Panembahan Senapati, seperti prabu Hanyakrawati dan keluarganya. Selain
itu, juga makam keluarga Paku Alam-Yogyakarta pada periode awal yang
bersumber atas leluhurnya melalui P. Natakusuma dan P. Adipati Pringgalaya
Mataram. Perlu pula dicatat, bahwa Kyai Ageng Sela (ayah Kyai Ageng
Pemanahan) tidak dimakamkan di kelompok makam Kota Gede. Karena telah
dimakamkan sebelumya di daerah Sesela, Grobogan, Jawa Tengah.
Berbeda dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya di Indonesia yang
bersifat maritim, kerajaan Mataram bersifat agraris. Kerajaan yang beribu kota
di pedalaman Jawa ini banyak mendapat pengaruh kebudayaan Jawa Hindu
baik pada lingkungan keluarga raja maupun pada golongan rakyat jelata.
Pemerintahan kerajaan ini ditandai dengan perebutan tahta dan perselisihan
antaranggota keluarga karena gangguan campur tangan Belanda.
Kebijaksanaan politik pendahulunya sering tidak diteruskan oleh
pengganti-penggantinya. Walaupun demikian, kerajaan Mataram merupakan
pengembang kebudayaan Jawa yang berpusat di lingkungan keraton Mataram.
Kebudayaan tersebut merupakan perpaduan antara kebudayaan Indonesia
lama, Hindu-Budha, dan Islam (Sjafii, 1978: 9).
Banyak versi mengenai masa awal berdirinya kerajaan Mataram
berdasarkan mitos dan legenda. Pada umumnya versi-versi tersebut
mengaitkannya dengan kerajaan-kerajaan terdahulu, seperti Demak dan
Pajang. Menurut salah satu versi, setelah Demak mengalami kemunduran,
ibukotanya dipindahkan ke Pajang dan mulailah pemerintahan Pajang sebagai
kerajaan. Kerajaan ini terus mengadakan ekspansi ke Jawa Timur dan juga
terlibat konflik keluarga dengan Arya Penangsang dari Kadipaten Jipang
Panolan. Setelah berhasil menaklukkan Aryo Penangsang, Sultan Hadiwijaya
(1550-1582), raja Pajang memberikan hadiah kepada 2 orang yang dianggap
berjasa dalam penaklukan itu, yaitu Ki Ageng Pemanahan dan Ki Penjawi. Ki
Ageng Pemanahan memperoleh tanah di Hutan Mentaok dan Ki Penjawi
memperoleh tanah di Pati (Sjafii, 1978: 11).
Pemanahan berhasil membangun hutan Mentaok itu menjadi desa yang
dengan Pajang sebagai atasannya. Setelah Pemanahan meninggal pada tahun
1575 ia digantikan putranya, Danang Sutawijaya, yang juga sering disebut
Pangeran Ngabehi Loring Pasar (Sjafii, 1978: 12 ). Sutawijaya kemudian
berhasil memberontak pada Pajang. Setelah Sultan Hadiwijaya wafat (1582)
Sutawijaya mengangkat diri sebagai raja Mataram dengan gelar Panembahan
Senapati. Pajang kemudian dijadikan salah satu wilayah bagian daari Mataram
yang beribukota di Kotagede. Senapati bertahta sampai wafatnya pada tahun
1601 (Tuti, 2009: 53).
Selama pemerintahannya saya menyimpulkan terjadi terus-menerus
perang menundukkan bupati-bupati daerah. Kasultanan Demak menyerah,
Panaraga, Pasuruan, Kediri, Surabaya, berturut-turut direbut. Cirebon pun
berada di bawah pengaruhnya. Panembahan Senapati dalam babad dipuji
sebagai pembangun Mataram.
Senapati digantikan oleh putranya, Mas Jolang, yang bertahta tahun
1601 1613. Mas Jolang lebih dikenal dengan sebutan Panembahan Seda
Krapyak. Pada masa pemerintahannya, dibangun taman Danalaya di sebelah
barat kraton. Panembahan Seda Krapyak hanya memerintah selama 12 tahun
Ia meninggal ketika sedang berburu di Hutan Krapyak (Moedjanto, 1994: 11).
Kemudian bertahtalah Mas Rangsang, yang bergelar Sultan Agung
Hanyakrakusuma, putra dari Panembahan seda Krapyak. Di bawah
pemerintahannya (tahun 1613-1645) Mataram mengalami masa kejayaan.
Ibukota kerajaan Kotagede dipindahkan ke Kraton Plered. Sultan Agung
merupakan raja yang menyadari pentingnya kesatuan di seluruh tanah Jawa.
Daerah pesisir seperti Surabaya dan Madura ditaklukkan supaya kelak tidak
pertama yang secara besar-besaran dan teratur mengadakan peperangan
dengan Belanda yang hadir lewat kongsi dagang VOC (Vereenigde Oost
Indische Compagnie). Kekuasaan Mataram pada waktu itu meliputi hampir
seluruh Jawa, dari Pasuruan sampai Cirebon. Sementara itu VOC telah
menguasai beberapa wilayah seperti di Batavia dan di Indonesia Bagian Timur
(Sudarjanto, 2003: 2).
Pada tahun 1645 Sultan Agung meninggal dengan meninggalkan
Mataram dalam keadaan yang kokoh, aman, dan makmur. Ia diganti oleh
putranya yang bergelar Amangkurat I. Amangkurat I tidak mewarisi sifat-sifat
ayahnya. Pemerintahannya yang berlangsung tahun 1645-1676 diwarnai
dengan banyak pembunuhan/kekejaman. Pada masa pemerintahannya ibukota
kerajaan Mataram dipindahkan ke Kerta yaitu sebuah kota di daerah Bantul
yang sekarang disebut Pleret (Sudarjanto, 2003: 2).
. Pada tahun 1674 pecahlah Perang Trunajaya yang didukung para
ulama dan bangsawan, bahkan termasuk putra mahkota sendiri juga
memberontak melawan Amangkurat I. Ibukota Kerta jatuh dan Amangkurat I
melarikan diri untuk mencari bantuan VOC. sesampainya di Tegalarum,
sebuah kota di dekat Tegal, Jawa Tengah Amangkurat I jatuh sakit dan
akhirnya wafat. Suksesi di kerajaan pun terjadi dan bertahtalah putra mahkota
yang mendukung kebijakan Amangkurat I dan bergelar Amangkurat II atau
dikenal juga dengan sebutan Sunan Amral. Sunan Amangkurat II bertahta
pada tahun 1677-1703. Ia sangat tunduk kepada VOC demi mempertahankan
tahtanya. Pada akhirnya Trunajaya berhasil dibunuh oleh Amangkurat II
perjanjian yang berisi Mataram harus menggadaikan pelabuhan Semarang dan
Mataram harus mengganti kerugian akibat perang (Sudarjanto, 2003: 3).
Hubungan Amangkurat II dengan VOC menjadi tegang dan semakin
memuncak setelah Amangkurat II mangkat (1703) dan digantikan oleh
putranya, Sunan Mas dan bergelar Amangkurat III yang juga menentang VOC.
Pihak VOC mengetahui rasa permusuhan yang ditunjukkan raja baru tersebut,
maka VOC tidak setuju dengan penobatannya. Pihak VOC lantas mengakui
Pangeran Puger sebagai raja Mataram dengan gelar Paku Buwana I. Hal ini
menyebabkan terjadinya perang saudara atau dikenal dengan sebutan Perang
Perebutan Mahkota I (1704-1708). Akhirnya Amangkurat III menyerah dan ia
dibuang oleh VOC. Namun Paku Buwana I harus membayar ongkos perang
dengan menyerahkan Priangan, Cirebon, dan Madura bagian timur kepada
VOC (Sudarjanto, 2003: 4).
Paku Buwana I meninggal tahun 1719 dan digantikan oleh
Amangkurat IV (1719-1727) atau dikenal dengan sebutan Sunan Prabu. ,
dalam pemerintahannya dipenuhi dengan pemberontakan para bangsawan
yang menentangnya, dan seperti bisaa VOC turut andil pada konflik ini,
sehinggga konflik membesar dan terjadilah Perang Perebutan Mahkota II
(1719-1723). VOC berpihak pada Sunan Prabu sehingga para pemberontak
berhasil ditaklukkan dan dibuang VOC ke Sri Langka dan Afrika Selatan.
Sunan Prabu meninggal tahun 1727 dan diganti oleh Paku Buwana II
(1727-1749). Pada masa pemerintahannya terjadi pemberontakan China terhadap
VOC (Santosa: 1970: 246)
Hubungan manis Paku Buwana II dengan VOC menyebabkan rasa
pemberontakan terhadap raja. Paku Buwana II menugaskan adiknya, Pangeran
Mangkubumi, untuk membasmi kaum pemberontak dengan janji akan
memberikan hadiah tanah di Sukowati (Sragen sekarang). Usaha Mangkubumi
berhasil. Tetapi Paku Buwana II mengingkari janjinya, sehingga Mangkubumi
berdamai dengan Raden Mas Said dan melakukan pemberontakan
bersama-sama. Mulailah terjadi Perang Perebutan Mahkota III (Santosa: 1970: 245)
Paku Buwana II dan VOC tak mampu menghadapi Pangeran
Mangkubumi dan Mas Said. Karena tekanan yang cukup kuat akhirnya Paku
Buwana II jatuh sakit dan wafat pada tahun1749. Menurut pengakuan VOC
Semarang, saat sakratul maut Paku Buwana II menyerahkan tahtanya kepada
VOC. Sejak saat itulah VOC merasa berdaulat atas Mataram. Atas inisiatif
VOC, putra mahkota dinobatkan menjadi Paku Buwana III (1749).
Pengangkatan Paku Buwana III tidak menyurutkan pemberontakan, bahkan
wilayah yang dikuasai Mangkubumi telah mencapai Yogya, Bagelen, dan
Pekalongan. Namun justru saat itu terjadi perpecahan anatara Mangkubumi
dan Raden Mas Said. Hal ini menyebabkan VOC berada di atas angin. VOC
lalu mengutus seorang Arab dari Batavia bernama Sayid dengan penyamaran
lengkap menggunakan sorban untuk mengajak Mangkubumi berdamai
(Nitinegoro: 1983: 51)
Pangeran Mangkubumi menerima tawaran yang disampaikan oleh
Sayid dengan beberapa syarat yaitu pertama, Mangkubumi harus menjadi raja
yang diangkat oleh rakyatnya dan bukan diangkat oleh VOC, yang kedua
adalah meminta agar Sunan Paku buwana III tetap menjadi raja di Surakarta,
yang ketiga Mangkubumi meminta agar pusaka peninggalan nenek moyang
terakhir adalah menuntut Gubernur Jendral di Belanda harus diganti karena
terlalu bersikap egois dan tidak berpihak kepada rakyatnya. Setelah semua
dipenuhi, terjadilah apa yang sering disebut sebagai Palihan Nagari atau Perjanjian Giyanti (1755). Inti dari perjanjian tersebut adalah bahwa Mataram
dibagi menjadi dua. Bagian barat dibagikan kepada Pangeran Mangkubumi
yang bergelar Sri Sultan Hamengku Buwana, Senapati Ing Ngalaga, Ngabul
Rahman Sayidin Kalipatolah Ingkang Jumeneng Kaping I dan mendirikan
kraton di Yogyakarta. Sedangkan bagian timur diberikan kepada Paku Buwana
III. Mulai saat itulah Mataram dibagi dua, yaitu Kasultanan Yogyakarta
dengan raja Sri Sultan Hamengku Buwana I dan Kasunanan Surakarta dengan
raja Sri Susuhunan Paku Buwana III (Nitinegoro: 1983: 63)
2. 3 Sejarah Bumi Mentaok
Sejarah yang akan terpapar di bawah ini adalah penuturan dari juru
kunci Pertapaan Bang Lanpir. Pada tanggal 11 Maret 2009 penulis berhasil
melakukan wawancara kepada juru kunci kepala Pertapaan Bang Lanpir yaitu
bapak Sarjono. Pada saat itu pak Sarjono menceritakan tentang asal usul Bumi
Mentaok dan bagaimana Bumi Mentaok bisa menjadi tanah yang dipakai Ki
Ageng Pemanahan dan Panembahan Senapati untuk wilayah Mataram Islam
yang Pertama kali.
Bumi mentaok berasal dari kata talok. Kata talok diambil pada saat
Sultan Hadiwijoyo (Sultan Pajang) melakukan tapa Brata di tanah Banyu
Sumurup. Sultan Hadiwijoyo tiba-tiba membuka matanya di saat ia melakukan tapa brata. Di depan matanya berdiri pohon talok. Sultan Hadiwijoyo merasa bahwa pohon itu harus ditebang. Rasa itu muncul semata-mata hanya ia ingin
dan ternyata talok itu tak juga patah ataupun tumbang. Sultan Hadiwijoyo heran akan hal itu. Pada saat itu juga emosinya sudah lepas. Sultan merasa
bahwa ia telah diberi tanda hasil dari pertapaannya. Tanda itu ialah bahwa ia
dan miliknya harus kuat seperti pohon talok itu. Meskipun terlihat kecil, tetapi pohon itu ternyata kokoh maka tanah tempat ia bertapa itu dinamai Bumi
Mentaok dengan harapan agar tempat itu menjadi kuat.
Bumi Mentaok bisa menjadi tanah yang digunakan Ki ageng
Pemanahan dan Panembahan Senapati sebagai wilayah kerajaan Mataram
Islam awal mulanya adalah dari kerajaan Pajang membuka sayembara, siapa
yg bisa mengalahkan Arya Penangsang akan diberikan hadiah berupa Bumi
mentaok yaitu daerah dari gunung kidul hingga Kotagedhe. Kemudian
diadakan perundingan besar untuk merencanakan bagaimana mengalahkan
arya penangsang. Mereka lalu mencari orang yang bisa diandalkan untuk
melawan Arya Penangsang. Ditunjuklah Danang Sutawijaya (nama
Panembahan Senapati). Danang Sutawijaya ditunjuk menjadi utusan karena
dialah anak tertua dari Panembahan Senapati yang bernama R. Bagus Srubut
atau R. Sutawijaya atau disebut R. Ngabehi Loring Pasar. Disebut demikian,
karena berdasarkan atas tempat tinggal yang terletak di utara Pasar Gede (Kota
Gede, sekarang).
Dari saat itu Danang Sutawijaya digembleng oleh Ki Juru Martani untuk
mengolah keberanian. Sutawijaya yang sudah beranjak dewasa itu mengabdi
sebagai Prajurit Tamtama kepada Sultan Hadiwijaya-Pajang hingga
dikukuhkan menjadi Raja, bahkan kemudian menjadi menantu dari Sultan
Panembahan Senapati, sekaligus menjadi penerus Sultan Hadiwijaya-Pajang
sebagai Raja Jawa.
Ki Juru Martani telah mengetahui kelemahan dari Arya Penangsang.
Setelah Danang Sutawijaya menyanggupi dan yakin untuk maju melawan
Arya Penangsang, maka dia dibekali pusaka berupa tombak Kyai Pleret. Ki
Juru Martani kemudian mengatur siasat dan persiapan menyerang. Suatu hari
siasat sudah dilaksanakan dengan tertib. Perjalanan mereka tidak diceritakan,
dengan cepat mereka tiba di tepi sebelah barat Bengawan Sore atau
Bengawan Lanang. Mereka berhenti untuk sekedar melepas lelah dan berbuat
seperti seolah bukan tentara yang hendak berperang. Segala senjata dan
perlengkapan perang disembunyikan dengan sebaik-baiknya. Tempat mereka
berhenti itu sudah dekat sekali dengan perkampungan Arya Penangsang,
hanya terpisah oleh sungai itu. Ki Juru Martani telah membuat surat tantangan
yang isinya sangat menghina Arya Penangsang. Bersama Ki Warantaka dan
Waraseca, Ki Juru Martani mencari tukang rumput (gamel) Arya Penangsang.
Gamel itu lalu dipotong telinganya dan disuruh kembali kepada Arya
Penangsang dan membawa surat tantangan.
Pada saat Patih Jipang yang bernama Mentaun sedang hendak
menghadap Arya Penangsang, ternyata sang Pangeran sedang makan,
sehingga terpaksa menunggu di depan pendapa. Tiba-tiba datanglah si
perumput dengan berlumuran darah. Ditahanlah dia oleh Mentaun. Mentaun
menenangkan perumput itu dan menyuruh menunggu di luar. Patih masuk ke
dalam dan bertemu dengan Arya Penangsang yang sedang makan. Setelah
Mentaun melapor, sang gamel pun meronta kesakitan dan memaksa ikut
marah terlebih saat sang gamel menunjukkan surat tantangan dari Ki Juru Martani. Menurut kepercayaan orang Jawa, pada saat makan tidak boleh
marah. Arya Penangsang sudah kehilangan akal dan hanya emosi lalu
mempersiapkan kuda jantannyanya bernama Gagak Rimang. Dengan
bersenjatakan tombak ia melonpat ke atas kudanya yang lari bagaikan terbang
ke arah Bengawan Sore.
Sementara itu ki Juru telah mempersiapkan sambutan yang hangat bagi
Arya Penangsang. Ketika Arya Penangsang telah terlihat, bende becak pusaka
dari sela dipukul dan berbunyi nyaring, tanda akan mendapat kemenangan.
Ketika Arya penangsang telah tiba di tepi sungai sebelah timur, Danang
Sutawijaya memperlihatkan diri dan mulai menantangnya. Arya Penangsang
menjadi gelap mata dan hanya ada emosi tanpa perhitungan dan
mengesampingkan kelemahannya bahwa Arya Penangsang tidak boleh
menyeberang sungai Bengawan Sore. Arya Penangsang melewati sungai itu
dalam hujan panah dan senjata lain yang dilontarkan oleh para prajurit.
Sesampainya di seberang, Arya Penangsang segera mengamuk. Melihat
pasukannya bubar, Danang Sutawijaya menyerang dengan bersenjatakan
tombak Kyai Plered, waktu itu kebetulan ia naik kuda betina. Gagak Rimang menjadi gembira melihat kuda betina dan ia lari tak terkendalikan. Danang
Sutawijaya cepat-cepat turun dari kudanya dan Arya Jipang sibuk
mengendalikan si Gagak Rimang lalu Danang Sutawijaya menusuknya dengan
tombak. Arya Penangsang Jatuh dan masih ingin membalas tetapi karena
sudah lemas, Danang Sutawijaya melingkarkan usus Arya Penangsang yang
penangsang menghunus kerisnya dan tanpa sengaja memotong ususnya sendiri
dan akhirnya dia tewas.
Kembali pada perjanjian awal dari kraton Pajang. Siapa yang bisa
membunuh Arya Penangsang, akan dianugrahi Bumi Mentaok yaitu tanah dari
Kota Gedhe hingga Gunung Kidul. Ki Penjawi dan Pemanahan dipanggil
Sultan Hadiwijaya untuk menerima ucapan terima kasih dan hadiah berupa
Bumi Mentaok.
2. 4 Bang Lanpir sebagai Tempat Diterimanya Wahyu Kelapa versi
JuruKunci
Juru kunci menceritakan bagaimana Bang Lanpir bisa menjadi tempat
diterimanya Wahyu Kelapa atau wahyu degan oleh Ki Ageng Pemanahan.
Cerita dari juru kunci ini didapat dari wawancara pribadi penulis dan bapak
Suraksa Cempakasari pada tanggal 7 Maret 2011. Cerita wahyu kelapa yang
dituturkan oleh juru kunci hanyalah sepenggal kisah ringkas seperti berikut.
Pencarian wahyu Keraton Mataram itu konon merupakan petunjuk
Sunan Kalijaga kepada Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng
Giring disuruh menanam sepet (sabut kelapa kering), yang kemudian tumbuh
menjadi pohon kelapa yang menghasilkan degan (buah kelapa muda).
Sedangkan Ki Ageng Pemanahan melakukan tirakat di Kembang Semampir
(Bang Lanpir), Panggang, Gunung Kidul.
Menurut wisik 'bisikan gaib' yang didapat, air degan milik Ki Ageng
Giring itu harus diminum saendhegan (sekaligus habis) agar kelak dapat
menurunkan raja. Ki Ageng Giring berjalan-jalan ke ladang terlebih dulu agar
dengan sekali minum. Namun sayang, ketika Ki Ageng Giring sedang di
ladang, Ki Ageng Pemanahan yang baru pulang dari bertapa di Bang Lanpir
singgah di rumahnya, dalam keadaan haus ia meminum air kelapa muda itu
sampai habis dengan sekali minum.
Betapa kecewa perasaan Ki Ageng Giring melihat kenyataan itu
sehingga dia hanya bisa pasrah, namun ia menyampaikan maksud kepada Ki
Ageng Pemanahan agar salah seorang anak keturunannya kelak bisa turut
menjadi raja di Mataram. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa kesempatan
menjadi raja Mataram pupus sudah, tinggal harapan panjang yang barangkali
bisa dinikmati pada generasi ke tujuh.
Rupanya Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pemanahan terlibat dalam
pembicaraan penting mengenai Wahyu. Mereka mencari Petunjuk dengan
melakukan tirakat, berpuasa dan berdoa memohonkan petunjuk serta arahan
dari Sang Pencipta Jagad. . Ki Ageng Giring tirakat untuk memperoleh Wahyu
Mataram di Kali Gowang. Istilah gowang konon berasal dari suasana batin
yang kecewa (gowang) karena gagal meminum air degan oleh karena telah
didahului oleh Ki Ageng Pemanahan. Sedangkan Ki ageng Pemanahan
melakukan tirakat di luar rumah Ki ageng Giring. Cukup menyita banyak
waktu hingga menjelang malam hari itu keduanya berkesepakat menyebut
nama wahyu yang diperoleh mereka dengan “Wahyu Kelapa”.
Mereka melanjutkan pembicaraan mengenai berbagai kisah,
cerita-cerita masa lalu, cariyos-cariyos, dan pengetahuan tentang Wahyu dari
kerajaan-kerajaan sebelumnya juga menjadi topik pembicaraan. Berlanjut
agama Islam dan seterusnya hingga zaman Kerajaan Pajang saat itu yang silih
berganti serta turun-temurun.
Dalam diskusi mengenai Wahyu tersebut kemudian diakhiri oleh
permintaan dari Ki Ageng Giring agar diberikan jatah, kewenangan untuk
saling mengisi harapan kemuliaan di masa mendatang tentang Tumuruning
Wahyu kepada keturunan dari Kyai Ageng Giring. Diusulkan agar Ki Ageng
Pemanahan akan memberikan kemuliaan secara bergantian kepada Ki Ageng
Giring. Rupanya Ki Ageng Pemanahan tidak menyetujuinya. Beberapa kali Ki
Ageng Giring meyakinkan tindakan untuk membagi kemuliaan bersama
Pemanahan dalam hitungan kedua, yaitu akan jatuh bergantian setelah
berselang hingga generasi kedua. Akan tetapi, Pemanahan masih tetap
berpendirian sama. Demikian seterunya desakan Ki Ageng Giring memohon
kembali agar untuk generasi keenam dan generasi ketujuh dalam pergantian
kemuliaan itu cukup memberikan alasan atas semua peristiwa.
Untuk permohonan terakhir itu, Ki Ageng Pemanahan dapat
memahami perjuangan Ki Ageng Giring. Penghargaan itu kemudian menjadi
kesepakatan dari mereka bahwa salah satu ketentuan bahwa setelah enam
generasi pemangku keraton dipegang oleh keturunan dari Ki Ageng
Pemanahan, barulah diberikan kepada pemangku keraton yang masih
keturunan langsung dari Ki Ageng Giring. Demikian seterusnya, hingga
akhirnya selalu terjadi pengulangan kembali Pemangku Adat Jawa, yang
bersumber atas keturunan kedua Ki Ageng tersebut.
Pembagian kekuasaan antara keturunan Ki Ageng Pemanahan dan Ki
Ageng Giring bisa dilihat dari urutan penguasa Mataram. Dapat dilihat bahwa
1. Panembahan Senapati, putra Ki Ageng Pemanahan atau Kyai Ageng
Mataram,
2. Digantikan oleh Susuhunan Adi-Prabu Hanyakrawati, putra
Panembahan Senapati,
3. Digantikan oleh Sultan Agung Hanyakrakusuma, putra Adi-Prabu
Hanyakrakusuma,
4. Dilanjutkan oleh Hamangkurat Agung (Tegal-Arum), putra Sultan
Agung Hanyakrakusuma,
5. Dikukuhkannya Hamangkurat Amral, putra Hamangkurat
Agung/Tegal-Arum,
6. Pangeran Puger bergelar Paku Buwana I (adik Hamangkurat Amral),
putra Hamangkurat Agung/Tegal-Arum.
Nama urutan yang disebut terakhir merupakan nama istilah baru bagi
penerus Mataram yang tidak lagi mengikuti pola “ayah-anak” secara langsung.
Jika diteliti lebih lanjut, ternyata Paku Buwana I tersebut juga masih keturunan
dari Kyai Ageng Giring yang diambil menurut garis ibu (Jawa: pancer puteri). Silsilah dan asal-usul dari Pangeran Puger itu baru diketahui setelah beliau
bertahta sebagai Paku Buwana I-Mataram. Tinjauan silsilah Raja-raja
Mataram sejak pembentukannya, ternyata menjadi catatan yang tidak
terlupakan, sekaligus menjadi cerita dari sekalian krandhah (kerabat, saudara,
dan keturunan/trah) Mataram agar selalu mengenang adanya Wahyu Kelapa
2. 5 Sejarah Bangunan Bang Lanpir
Pertapaan Bang Lanpir dahulunya sempat tidak diketahui di mana
letaknya. Pihak Kraton hanya mengetahui letak desanya saja tanpa
mengetahui letak pertapaan secara pasti. Melalui laku mistik dan memohon petunjuk kepada Tuhan, Sri Sultan HB IX memerintahkan penasihat
spiritualnya yaitu Ki Mataram dan murid-muridnya untuk membantu
pencarian jejak pertapaan. Pertapaan Bang Lanpir dibangun kembali pada
tahun 1975. Pembangunan kembali Pertapaan Bang Lanpir diprakarsai karena
perintah Sri Sultan Hamengkubuono IX dengan maksud untuk
memonumenkan tempat yang dianggap sangat bersejarah untuk Kraton
Yogyakarta. Orang-orang yang membangun adalah Bapak Sukadi yang
menjabat kepala PU saat itu, Bapak Darmakum yang saat itu menjabat sebagai
Bupati Gunung Kidul, Bapak Sintarjo dan Bapak Prodjo Saputro yang pada
saat itu menjabat sebagai anggota DPR Kabupaten Gunung Kidul. Semua
orang yang ikut membangun adalah murid dari Ki Metaram. Ki Metaram
adalah Penasehat spiritual Sri Sultan HB IX. (Sukadi, wawancara pribadi, 18
Februari 2011)
Pembangunan kembali Pertapaan Bang Lanpir bertujuan untuk
mengonservasi tempat bersemedi Ki Ageng Pemanahan dan Panembahan
Senapati. Dibuatlah patung tiga tokoh yang berperan besar dalam Bang Lanpir
dan Mataram Islam untuk mengenang mereka. Tokoh yang dibuatkan patung
adalah Ki Ageng Pemanahan, Ki Juru Martani, dan Panembahan Senapati
(Sukadi, wawancara pribadi, 18 Februari 2011)
Untuk dapat sampai ke tempat pertapaan ini pengunjung harus