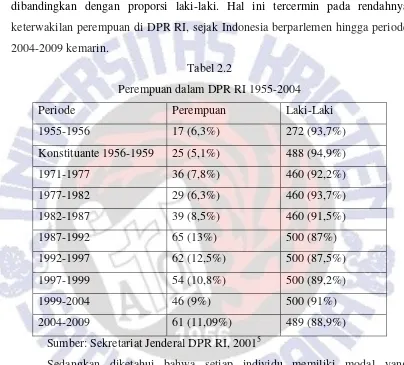BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Bukan Demokrasi, Melainkan Dominasi
Sistem politik demokrasi di Indonesia sebenarnya masih memikirkan
toleransi dan intoleransi. Intoleransi sendiri adalah politik arogansi. Ketika
intoleransi mendapat legitimasi ranah politik, filosof Levinas mengingatkan,
politik demi dirinya sendiri memiliki kodrat tranik, ibu segala kekerasan.
Demikianlah kita menyaksikan dari waktu ke waktu politik intoleransi Indonesia
terhadap warga minoritas (Riyanto, 2011).Kenyataanya sampai saat ini,
perempuan masih merupakan kelompok marjinal yang secara historis selalu
disisihkan dalam dunia politik dan pada proses-proses pengambilan keputusan
publik1. Bahwa perempuan di anggap sebagai kaum marjinal tersebut, perempuan
secara tidak langsung juga merupakan warga minoritas yang akhirnya
berkesempatan untuk didengar suaranya.
Pada dasarnya negara yang menggunakan sistem politik demokrasi
seharusnya lebih mementingkan toleransi antar sesama. Baik itu toleransi antar
etnis, suku, budaya, ras, maupun agama. Dari asal katanya (Latin) tolerare, toleransi berarti menanggung, memanggul, memikul bersama (beban). Dalam
ranah politik toleransi memaksudkan pemakluman perbedaan (Riyanto, 2011).
Masalah mengukur gejala ada atau tidaknya demokrasi bukanlah hal mudah.
Misalnya, banyak orang di Barat yang mengukur adaa atau tidaknya demokrasi
dengan ada aatau tidaknya pemilihan umum. Pemilihan umum memang
merupakan satu manifestasi adanya demokrasi, tapi belum tentu dengan adanya
pemilihan umum, demokrasi pasti ada. Ini menunjukkan bahwa mencari indikator
dari gejala demokrasi tidak begitu mudah.
Namun, apa pun bentuk sebuah demokrasi, di Barat maupun di Timur, ada
ciri utama yang tidak dapat ditawar, yakni dalam demokrasi dimungkinkan
adanya partisipasia dari semua golongan masyarakat. Manifestasi dari partisipasi
1
Ratu Dian Hatifah, Sekjen KPPI.
ini dapat berupa pemilihan umum, demokrasi dalam masyarakat tersebut selalu
dapat dikatakan ada.
Sedangkan pendekatan sistem politik sendiri diharapkan dapat digunakan
untuk menjelaskan yang bersifat ilmiah terhadap fenomena politik, atau
kehidupan politik dan dapat diterapkan secara universal. Pendekatan sistem politik
dimaksudkan juga untuk menggantikan pendekatan klasik ilmu politik yang hanya
mengandalkan analisis pada negara dan kekuasaan.
Apabila masyarakat menerima pengertian demokrasi sebagai partisipasi
dari anggota atau golongan yang ada dalama masyarakat, apa pun bentuk
partisipasinya, maka pada dasarnya masyarakat menerima pendirian yang
menyatakan bahwa demokrasi hanya mungkin bila golongan masyarakat yang ada
mempunyai kekuatan politik yang relatif seimbang. Bila satu golongan
masyarakat menjadi terlalu kuat, maka kehidupan demokrasi di masyarakat itu
jadi terancam, atau paling sedikit, demokrasi jadi tergantung pada kemauan, baik
dari orang atau aagolongan yang berkuasa.
Kemudian fakta yang ada yaitu warga Salatiga sendiri khususnya yang
tinggal di daerah Sarirejo, tidak memahami sistem politik yang ada di Indonesia
lebih tepatnya pendidikan politik masih cukup kurang2. Tidak hanya warga
Sembir kota Salatiga saja, tapi sebagian besar orang Salatiga tidak memahami
tentang politik.
Demokrasi sendiri dapat dikatakan sistem yang liberal, justru lebih
mementingkan kebebasan individu untuk berkreasi. Akan tetapi masih dalam
norma atau aturan yang berlaku pada wilayah tertentu. Namun, perempuan sendiri
masih tergolong pada kaum marjinal. Bahwa, kuota calon wakil rakyat saat ini
hanya 30% perempuan. Dengan fakta tersebut, bisa dikatakan bahwa dominasi
laki-laki yang merupakan budaya patriarki sangat berkuasa di dunia
politik.Budaya patriarki yang tertanam dalam struktur dan budaya dalam suatu
2
Hasil Wawancara dengan pembicara dari Panwaslu Kota Salatiga.
masyarakat mampu mengakibatkan ketimpangan gender di dalam masyarakat
tersebut (Mac Donald, 1999)3.
2.2 Perempuan Sebagai Kaum Marginal dalam Politik
Saat ini opini publik menganggap bahwa perempuan sebagai makhluk
yang lemah, dan tidak akan mampu menjadi seorang pemimpin. Opini tersebut
sudah ada sejak jaman nenek moyang. Opini publik sendiri merupakan suatu
akumulasi citra yang tercipta atau diciptakan oleh proses komunikasi. Citra
tentang sesuatu itu, entah dalam tataran yang abstrak ataupun kongkret selalu
menjadi bermuka banyak atau berdimensi jamak karena perbedaan penafsiran
(persepsi) yang terjadi di antara peserta komunikasi. Itulah sebabnya, dalam opini
publik terjadi pergeseran-pergeseran citra (Panuju, 2002).
Menurut Mino Vianello dalam penelitiannya, ia menemukan bahwa
kesenjangan dan ketimpangan tersebut dibentuk oleh berbagai hal, di antaranya
adalah pemahaman perbedaan sex dan nilai-nilai dalam masyarakat.Sebenarnya
yang harus diperhatikan adalah gender inequalities (ketidakadilan gender) merupakan sistem dan struktur dimana kaum laki-laki dan perempuan menjadi
korban dari sistem tersebut. Dengan demikian agar dapat memahami perbedaan
gender yang menyebabkan ketidakadilan maka dapat dilihat dari berbagai
manifestasinya, yaitu salah satunya adalah marginalisasi. Marginalisasi
merupakan timbulnya kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat dan negara
merupakan sebagai akibat dari proses marginalisasi yang menimpa kaum laki-laki
dan perempuan yang disebabkan oleh berbagai kejadian, antara lain penggusuran,
bencana alam, proses eksploitasi atau korban politik praktis.
Ketimpangan gender masih dapat ditemukan dalam berbagai lingkup
kehidupan, baik sosial maupun politik. Salah satu bentuk dari ketimpangan gender
tersebut terjadi di dalam struktur lembaga perwakilan kita. Berdasarkaan catatan
dari BPS pada tahun 2000, dari jumlah penduduk Indonesia sebesar 209.000.000
3
Mac Donald, Mandy., Sprenger, Ellen dan Dubel. Gender dan Perubahan Organisasi. Yogyakarta: ISIST dan REMDEC, 1999. Hal.1.
orang, jumlah wanita lebih besar yakni 105 juta dibandingkan dengan populasi
laki-laki yang berjumlah 104 juta4. Namun lebih besarnya populasi perempuan
tersebut, tidak menunjukan hal yang serupa dalam representasinya sebagai wakil
rakyat. Sebaliknya perempuan memiliki proporsi yang jauh lebih sedikit
dibandingkan dengan proporsi laki-laki. Hal ini tercermin pada rendahnya
keterwakilan perempuan di DPR RI, sejak Indonesia berparlemen hingga periode
2004-2009 kemarin.
Tabel 2.2
Perempuan dalam DPR RI 1955-2004
Periode Perempuan Laki-Laki
1955-1956 17 (6,3%) 272 (93,7%)
Konstituante 1956-1959 25 (5,1%) 488 (94,9%)
1971-1977 36 (7,8%) 460 (92,2%)
1977-1982 29 (6,3%) 460 (93,7%)
1982-1987 39 (8,5%) 460 (91,5%)
1987-1992 65 (13%) 500 (87%)
1992-1997 62 (12,5%) 500 (87,5%)
1997-1999 54 (10,8%) 500 (89,2%)
1999-2004 46 (9%) 500 (91%)
2004-2009 61 (11,09%) 489 (88,9%)
Sumber: Sekretariat Jenderal DPR RI, 20015
Sedangkan diketahui bahwa setiap individu memiliki modal yang
bermacam-macam, mulai dari modal pendidikan, ekonomi, sosial, bahkan budaya.
Perempuan yang tergolong dalam individu itu sendiri juga memiliki modal. Akan
tetapi, karena konstruksi sosial bahwa perempuan tidak mempunyai modal itu
dibangun sudah cukup lama, maka perempuan terlihat susah untuk bersaing
dengan laki-laki khususnya di bidang politik. Kemudian dari konstruksi tersebut
terbentuk kelas-kelas yang membuat perempuan susah untuk bergerak.Dalam
4
www.bps.go.id. Diakses pada tanggal 26 November 2005 pada pukul 10.45 WIB. 5
Ani Widyani Soetjipto, “Politik Perempuan Bukan Gerhana” (Jakarta:Kompas, 2005), hal. 239.
wawancara singkat dengan seorang pemandu karaoke di Sarirejo kota Salatiga
menyebutkan bahwa:
“Gak ik mbak. Ada sih komunitas paguyuban karaoke, tapi saya gak ikut.
Lagian yang ikut itu paguyuban itu kebanyakan pemilik karaoke. Jadi kita
anak buah paling dapat kabar dari pemilik karaoke aja. Walah, boro-boro
dikasih tau mbak. Bahas soal pemilu aja gak. Kemarin itu malah bahas
soal kita yang harus libur pas pemilu, jadi kita rugi. Karena gak dapat
penghasilan sehari. Ya paling saya tau kabar soal pemilu itu dari TV atau
baca di internet mbak.”
Wawancara tersebut jelas dikatakan bahwa perlakuan berbeda di dapatkan
oleh individu yang kelasnya berbeda antara pemandu karaoke dengan pemilik
karaoke. Hasil wawancara tersebut juga berarti bahwa meskipun PK tidak
mendapatkan fasilitas pendidikan politik secara langsung, namun mereka juga
bisa mengaksesnya melalui media sosial yang lainnya. Sehingga mereka bisa
mengambil tindakan atau keputusan yang sesuai dengan keadaan mereka.
Sedangkan orientasi subjektivitas terhadap kelas sendiri menurut Bourdieu
dalam salah satu wawancara:
Memahami kelas sebagai sebuah konstruksi sosial dapat menuntun pada
sebuah penyimpangan subjektivitas...akhir bagian pertama dari Le Sens Pratique berada pada batas ujung penyimpangan subjektivistik (tapi)....ada dasar-dasar objektif bagi semua keputusan ini... terdapat perjuangan yang
real atas kelas-kelas, sebuah perjuangan simbolik dan perorangan, atau
sebuah perjuangan kolektif.
Seseorang dapat memutuskan tindakan dan sikap diatur oleh kebiasaan
atau nilai-nilai yang sudah ada pada individu dalam jangka waktu yang lama.
Sehingga kebiasaan tersebut yang disebut habitus. Tindakan seorang PK dalam
masalah politik juga dapat terbentuk melalui kehidupan sehari-hari. Melaui proses
lobi dalam mendapatkan pelanggan, waktu bekerja dan beristirahat, serta kegiatan
yang lainnya. Menurut (Mahar, 2009) Habitus mengacu pada sekumpulan
disposisi yang tercipta dan terformulasi melalui kombinasi struktur objektif dan
sejarah personal. Disposisi diperoleh dalam berbagai posisi sosial yang berada di
dalam suatu ranah, dan mengimplikasikan suatu penyesuaian subjektif terhadap
posisi itu. Umpamanya, dalam tingkah laku seseorang, ‘penyesuaian diri’
semacam ini seringkali terimplikasikan melalui sense6 seseorang pada keberjarakan sosial, atau bahkan terimplikasikan dalam sikap-sikap tubuh mereka.
Oleh sebab itu, tempat dan habitus seseorang membentuk basis persahabatan,
cinta, dan hubungan pribadi lainnya, dan juga mengubah kelas-kelas teoretis
kelompok-kelompok real.
2.3 Pendidikan Politik bagi Kaum Marginal
Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan sistem politik
demokrasi. Salah satu bentuk sistem demokrasi ditandai dengan adanya pesta
demokrasi yang diadakan setiap lima tahun sekali, yaitu saat pemilihan wakil
rakyat (Legislatif dan Presiden). Akan tetapi, banyak warga Indonesia yang masih
belum mendapatkan pendidikan politik yang benar, khususnya bagi perempuan
yang masuk dalam kategori kaum marginal. Bahkan kewajiban LSM (maksudnya
masyarakat sipil) untuk mempersiapkan perempuan berkualitas bagi partai.
Betapa naifnya, karena UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang
merupakan penyempurnaan dari UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik,
disana secara tegas dikatakan bahwa partai politik melakukan pendidikan politik
bagi anggotanya dan masyarakat7.
Sebenarnya salah satu sebab perempuan digolongkan dalam kaum
marginal adalah ketika perempuan belum mampu mengimbangi peran laki-laki di
dunia politik praktis maupun dalam dunia kerja. Kemudian hambatan perempuan
berpolitik lainnya yakni karena pada dasarnya perempuan telah memiliki beban
berlapis, dimana perempuan memiliki tanggung jawab di ruang privat (sebagai
6
Dalam Bahasa Indonesia yaitu pengetahuan 7
Kelompok-Kerja-Keterwakilan-Perempuan.
isteri dan ibu di rumah), ruang publik dan juga komunitas. Beban berlapis ini
tentunya menjadi hambatan perempuan mengikuti kegiatan politik, terutama
proses kampanye dan Pemilu yang menguras banyak waktu, uang dan tenaga bagi
para pemain di dalamnya. Namun demikian, dari hasil penelitian Women
Research Institute (WRI), beban berlapis yang dimiliki oleh perempuan ternyata
mampu memberikan dampak positif bagi perempuan untuk meraih suara dalam
Pemilu.
Selain itu, perempuan juga memiliki modal yang cukup banyak untuk
mampu bersaing dengan laki-laki. Akan tetapi, karena sudah terbentuknya
kelas-kelas antara perempuan dan laki-laki bahkan tiap individu, maka dengan
menggunakan tiga kategori kualitatif besar (rasa keberbedaan untuk kelas atas,
kehendak baik budaya untuk kelas menengah, pilihan kebutuhan untuk kelas
pekerja), Bourdieu sanggup membuat keterkaitan antara kelas dan disposisi
menjadi jelas dan tidak ambigu. Jadi:
Kelas dominan merupakan sebuah ruang yang relatif otonom, yang
strukturnya didefinisikan oleh distribusi modal ekonomi dan budaya di
antara anggotanya. Masing-masing fraksi kelas dicirikan oleh konfigurasi
distribusi tertentu ini yang berkorespondensi dengan sebuah gaya hidup
tertentu, lewat perantara habitus (Bourdieu, 1984: 260).
Sedangkan modal yang sudah dipunyai setiap perempuan sendiri dirasa
sudah cukup dan mereka juga berhak mendapatkan hak yang sama dengan
laki-laki, maka fakta yang ada di Sarirejo berkata lain, bahwa pemandu karaoke atau
perempuan marginal (PK) mayoritas bukan orang asli Salatiga, banyak yang tidak
mempunyai fasilitas untuk mereka bersuara dan mendapatkan pendidikan politik
secara langsung selama proses pemilu dilaksanakan. Sehingga bulan April 2014,
saat semua warga Indonesia merayakan pesta demokrasi, mereka tidak dapat ikut
serta dalam pesta tersebut. Itu semua dikarenakan mereka tidak mengerti
bagaimana cara memberikan suara saat pemilu berlangsung. Berikut hasil
wawancara dengan pemandu karaoke di Sarirejo:
“Tidak nyoblos mbak aku. Lah ribet ngurusnya mbak. Harus pakai kartu
apa itu namanya. Belum lagi saya malas. Mending saya dirumah aja
nemenin anak”.
Sebenarnya jika perempuan juga mendapatkan pendidikan politik sejak
dini, maka perempuan akan jauh lebih hebat dari pada laki-laki untuk menjadi
seorang pemimpin. Karena perempuan sudah memiliki modal awal berupa
komunitas di lingkungan tempat mereka tinggal (arisan, PKK, Dasawisma, dll).
Negara sendiri yang berperan sebagai administrasi publik, yang mengacu kepada
tiga lembaga politik yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif sampai saat ini masih
sangat kecil peluang perempuan masuk kedalam tiga lembaga politik tersebut.
Sehingga suara-suara perempuan yang lain juga masih belum didengar dan
ditindak lanjuti dengan program-program tepat sasaran bagi salah satu kaum
marginal ini.
Sehingga konsep gender dan administrasi publik sendiri memaksa setiap
orang berpikir bahwa perempuan hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, yang
bergantung kepada suami untuk penghidupan mereka, terlepas apakah mereka
secara de factoibu rumah tangga atau bukan. Definisi sosial wanita sebagai ibu rumah tangga adalah pasangan definisi sosial laki-laki sebagai pencari nafkah,
terlepas dari kontribusi nyata yang mereka berikan kepada rumah tangga dan
keluarga. Konstruksi tersebut sebenarnya dibentuk melalui kebijakan-kebijakan
publik dan implementasi-implementasi kebijakan tersebut. Karena yang membuat
kebijakan-kebijakan tersebut bukan dari kaum hawa akan tetapi mayoritas kaum
adam. Meskipun yang membuat kebijakan terdapat beberapa kader perempuan,
namun suara perempuan ini masih sangat kecil dan belum di dengar, kebanyakan
kader perempuan pun juga belum mendapatkan pendidikan politik yang cukup
kuat untuk menyampaikan kebutuhan perempuan yang lain sebenarnya itu seperti
apa.
Konsep diatas diinspirasi oleh pemikiran Michael Foucault dalam History of Sexuality (1980) yang mengatakan bahwa seks tidak hanya dilihat sebagai
sekedar sarana reproduksi atau sebagai sumber kesenangan, tapi juga telah
menjadi pusat keberadaan diri kita berada8. Artinya, makna akan kebenaran
diletakkan diatas basis perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Di sini wacana
gender bertemu dengan kebijakan publik, atau dalam konteks yang lebih luas
wacana gender bertemu dengan administrasi publik sebagai lembaga pembuat dan
pelaksana kebijakan publik9.
8
Dikutip Suryakusumah, 1991a, hlm. 7-8. 9
Dr. Riant Nugroho et,al, 2008, Gender dan Administrasi Publik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
2.4 Kerangka Pikir Penelitian
Peneliti menggambarkan kerangka pikir penelitian dibawah ini, dengan
maksud agar individu yang membaca menjadi mudah untuk memahami konsep
teori maupun praktik yang dimaksudkan oleh si peneliti. Sehingga dalam
penelitian ini terdapat sebuah kerangka berpikir seperti berikut:
Fakta Pemilu
Caleg
Capres
Modal
Sosial
Ekonomi
Pendidikan
Budaya Modal
Sosial
Ekonomi
Pendidikan
Budaya Pemandu Karaoke
(Perempuan)
CALEG (Perempuan)
Arena
Tindakan
Kesadaran - Habitus Kesadaran
-Habitus