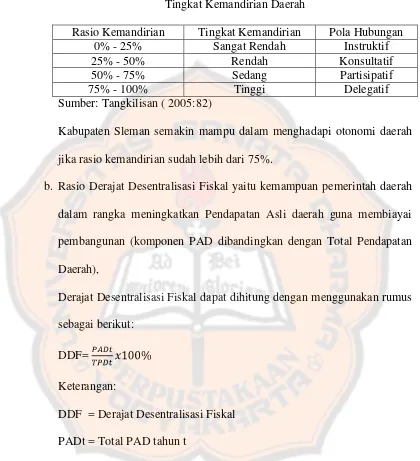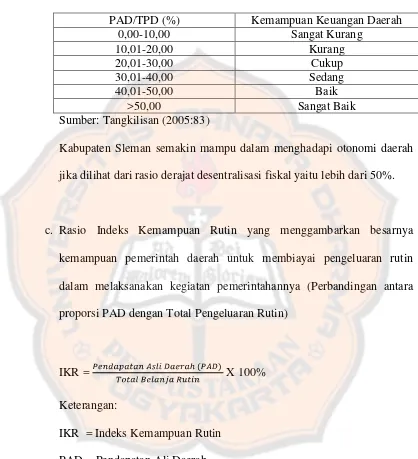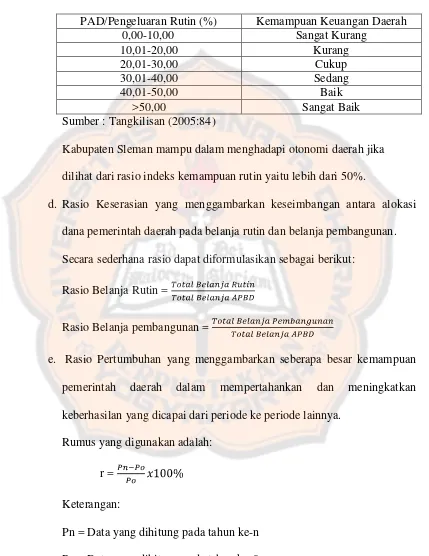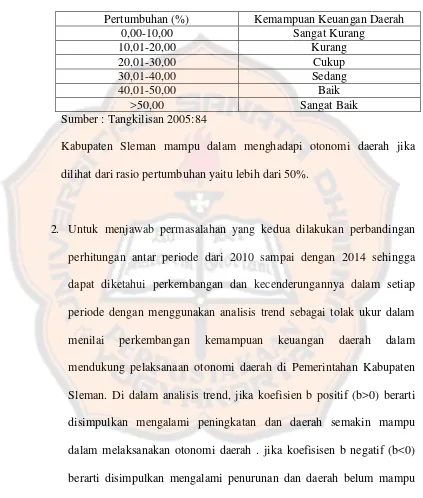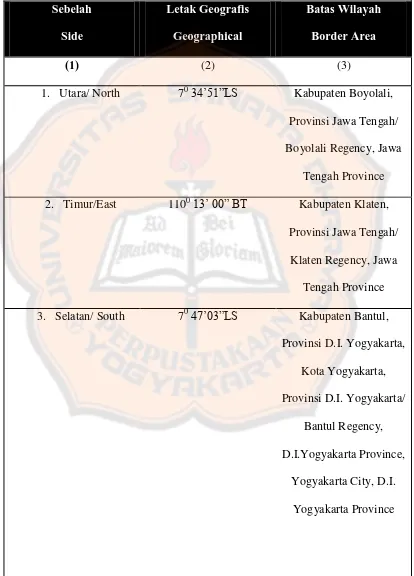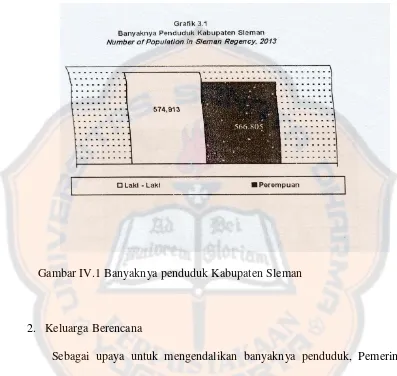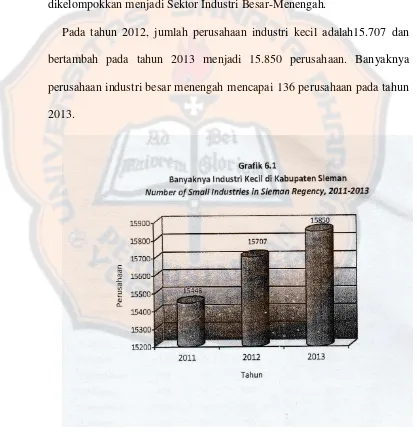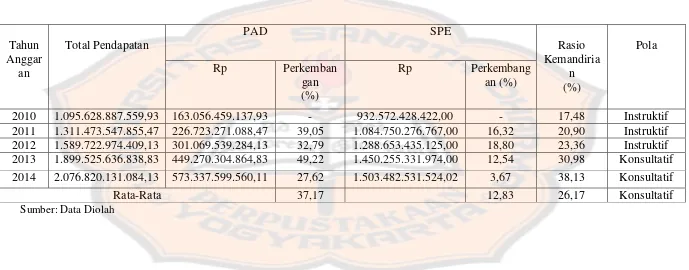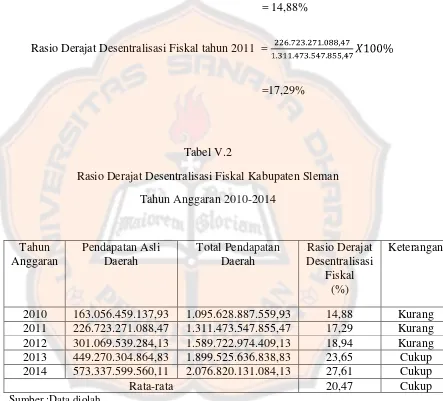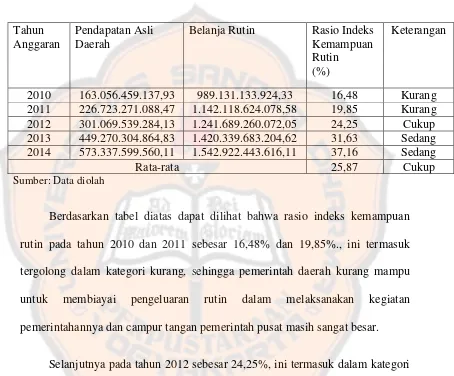xiv
ABSTRAK
ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Sleman
Maria Margareta Cahyaningrat Warih Kusuma Puspita Handayani
NIM:112114068
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2015
Tujuan penelitian ini : 1) untuk mengetahui pendapatan Kabupaten Sleman dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah dari tahun anggaran 2010-2014 dengan dilihat dari rasio kemampuan keuangan daerah, rasio derajat desentralisai fiskal, rasio indeks kemampuan rutin, rasio keserasian, rasio pertumbuhan. 2) Untuk mengetahui Kabupaten Sleman semakin mampu dalam melaksanakan otonomi daerah dengan menggunakan analisis trend. Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan beberapa rasio keuangan.
Jenis penelitian ini adalah studi kasus pada pemerintah Kabupaten Sleman. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan adalah deskriptif dengan angka indeks kemampuan keuangan sebagai alat ukur dalam menilai kemampuan keuangan dari satu periode ke periode yang lainnya.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Sleman belum mampu mendukung pelaksanaan otonomi daerah dilihat dari analisis rasio dan analisis trend.
xv
ABSTRACT
AN ANALYSIS OF REGIONAL FINANCIAL CAPABILITY IN SUPPORTING THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL AUTONOMY
Case Study on the Sleman District Government
Maria Margareta Cahyaningrat Warih Kusuma Puspita Handayani
NIM:112114068
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2015
The purpose of this research were: 1) to determine whether incomes of Sleman District has supported the implementation of regional autonomy of fiscal year 2010-2014 as seen from the ratio of the regional of financial independence, the degree of fiscal decentralization ratio, the ratio of routine capability index, the ratio of the harmony, and the growth ratio. 2) To investigate whether Sleman District is more able to carry out regional autonomy by using analysis of trend. Types of this research uses quantitative with the use of several financial ratios.
Types of this research is a case study to the Sleman Regency government. The data was obtained by interview and documentation. The data technical analysis used is descriptive with the index of financial capabilities as measurement tools in assessing financial capabilities from one period to another.
ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Sleman
S K R I P S I
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi
Oleh:
Maria Margareta Cahyaningrat Warih Kusuma Puspita Handayani
NIM: 112114068
PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
i
ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Sleman
S K R I P S I
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi
Oleh:
Maria Margareta Cahyaningrat Warih Kusuma Puspita Handayani
NIM: 112114068
PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
iv
Halaman Persembahan
Apapun yang kita mohon dari Tuhan biarlah kita juga berusaha
untuk mencapainya. ( 2Petrus 1.4)
Three grand essentials to happiness in this life are something to do,
something to love, and something to hope for. Tiga hal penting untuk
kebahagiaan dalam hidup ini adalah sesuatu untuk dikerjakan; sesuatu
untuk dicintai, dan sesuatu untuk diharapkan. (Joseph Addison-Penulis
dan penyair Inggris)
Skripsi Ini Kupersembahkan untuk :
v
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI-PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:
ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Sleman
dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 26 Agustus 2015 adalah hasil karya saya.
Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.
Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.
Yogyakarta, 31 agustus 2015
Yang membuat pernyataan,
vi
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:
Nama : Maria Margareta Cahyaningrat Warih Kusuma Puspita Handayani
Nim : 112114068
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul:
ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Sleman
Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencamtumkan nama saya sebagai penulis.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.
Yogyakarta, 31 Agustus 2015
vii
KATA PENGANTAR
Puji syukur dan terima kasih kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah
melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan
skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma.
Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat bantuan, bimbingan dan
araham dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih
yang tak terhingga kepada :
1. Drs. Johanes Eka Priyatma, M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Sanata
Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan
mengembangkan kepribadian kepada penulis
2. Dr.Fr. Reni Retno Anggraini, M.Si., Akt.,C.A. selaku Dosen Pembimbing
yang telah membantu serta membimbing penulis dalam menyelesaikan
skripsi ini.
3. A.Diksa Kuntara,S.E., MFA.,QIA. dan Josephine Wuri, S.E.,M.Si. selaku
dosen penguji skripsi saya.
4. Seluruh Dosen Program Studi Akuntansi Universitas Sanata Dharma.
5. Drs. Ardani selaku Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Sleman.
6. Erny Maryatun, S.IP, MT selaku Kepala bidang Statistik, Penelitian, dan
Perencanaan yang mengatasnamakan Kepala Badan Perencanaan
viii
7. Dra. Rini Murti Lestari, Akt, MM selaku Kepala Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman .
8. Drs. Harjana selaku Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman.
9. Orangtua penulis dan kakak penulis yang telah memberikan kasih sayang,
dukungan, doa, dan semangat sehingga terselesaikannya skripsi ini.
10. Teman-teman mahasiswa akuntansi angkatan 2011 atas dukungan dan
kebersamaannya selama ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, oleh karena
itu penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat
bermanfaat bagi pembaca.
Yogyakarta, 31 Agustus 2015
ix
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ... i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ... ii
HALAMAN PENGESAHAN ...iii
HALAMAN PERSEMBAHAN ... iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ... v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ... vi
HALAMAN KATA PENGANTAR ... vii
HALAMAN DAFTAR ISI ... ix
HALAMAN DAFTAR TABEL ... xi
HALAMAN DAFTAR GAMBAR ... xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN ...xiii
ABSTRAK ... xiv
ABSTRACT ... xv
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ... 1
B. Rumusan Masalah ... 4
C. Tujuan Penelitian ... 5
D. Manfaat Penelitian ... 6
E. Sistematika Penulisan ... 7
BAB II LANDASAN TEORI A. Akuntansi Pemerintahan... 8
B. Otonomi Daerah ... 14
C. Keuangan Daerah ... 18
D. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ... 31
E. Kerangka Pemikiran ... 40
BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis dan Sumber Data ... 42
B. Waktu dan Tempat Penelitian ... 42
C. Teknik Pengumpulan Data ... 43
x
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
A. Letak Geografis ... 50
B. Pemerintahan ... 53
C. Penduduk, Tenaga Kerja, Keluarga Berencana, dan Transmigrasi ... 53
D. Sosial ... 55
E. Pertanian ... 57
F. Industri ... 59
G. Pertambangan dan Penggalian ... 60
H. Perdagangan ... 60
I. Hotel ... 60
J. Pariwisata ... 61
K. Transportasi ... 61
L. Keuangan dan Perbankan ... 61
M. Produk Domestik Regional Bruto ... 62
BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN A. Analisis Data dan Pembahasan ... 63
BAB VI PENUTUP A. Kesimpulan ... 92
B. Keterbatasan Penelitian ... 94
C. Penutup ... 94
DAFTAR PUSTAKA ... 96
xi
DAFTAR TABEL
III.1 Tingkat Kemandirian Daerah ... 45
III.2 Tingkat Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah ... 46
III.3 Tingkat Kemampuan Rutin Daerah ... 47
III.4 Tingkat Pertumbuhan Daerah ... 48
IV.1 Letak Geografis dan Batas Wilayah ... 51
V.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ... 65
V.2 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal ... 67
V.3 Rasio Indeks Kemampuan Rutin ... 69
V.4 Rasio Keserasian ... 72
V.5 Rasio Pertumbuhan ... 75
V.6 Analisis Trend Rasio Kemandirian Daerah ... 77
V.7 Analisis Trend Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal ... 79
V.8 Analisis Trend Rasio Indeks Kemampuan Rutin ... 80
V.9 Analisis Trend Rasio Keserasian (Belanja Operasi) ... 82
V.10 Analisis Trend Rasio Keserasian (Belanja Modal) ... 83
V.11 Analisis Trend Rasio Pertumbuhan (PAD) ... 85
V.12 Analisis Trend Rasio Pertumbuhan (TPD) ... 86
V.13 Analisis Trend Rasio Pertumbuhan (Belanja Operasi) ... 88
xii
DAFTAR GAMBAR
IV.1 Banyaknya Penduduk Kabupaten Sleman ... 54
IV.2 Banyaknya Industri Kecil di Kabupaten Sleman ... 59
V.1 Grafik Tend Rasio Kemandirian Daerah ... 78
V.2 Grafik Trend Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal ... 80
V.3 Grafik Trend Rasio Indeks Kemampuan Rutin ... 81
V.4 Grafik Trend Rasio Keserasian (Belanja Operasi) ... 83
V.5 Grafik Trend Rasio Keserasian (Belanja Modal ... 84
V.6. Grafik Trend Rasio Pertumbuhan (PAD) ... 86
V.7 Grafik Trend Rasio Pertumbuhan (TPD) ... 87
V.8 Grafik Trend Rasio Pertumbuhan (Belanja Operasi) ... 89
V.9 Grafik Trend Rasio Pertumbuhan(Belanja Modal) ... 90
xiii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Surat Izin Tentang Penelitian ... 99
Lampiran 2 Surat Izin Tentang Penelitian ... 100
Lampiran 3 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2010 ... 101
Lampiran 4 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2011 ... 103
Lampiran 5 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2012 ... 105
Lampiran 6 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2013 ... 107
Lampiran 7 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2014 ... 109
Lampiran 8 Output Spss Rasio Kemandirian ... 111
Lampiran 9 Output Spss Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal ... 112
Lampiran 10 Output Spss Rasio Indeks Kemampuan Rutin ... 113
Lampiran 11 Output Spss Rasio Keserasian (Belanja Operasi) ... 114
Lampiran 12 Output Spss Rasio Keserasian (Belanja Modal) ... 115
Lampiran 13 Output Spss Rasio Pertumbuhan (PAD) ... 116
Lampiran 14 Output Spss Rasio Pertumbuhan (TPD) ... 117
Lampiran 15 Output Spss Rasio Pertumbuhan (Belanja Operasi) ... 118
xiv
ABSTRAK
ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Sleman
Maria Margareta Cahyaningrat Warih Kusuma Puspita Handayani
NIM:112114068
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2015
Tujuan penelitian ini : 1) untuk mengetahui pendapatan Kabupaten Sleman dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah dari tahun anggaran 2010-2014 dengan dilihat dari rasio kemampuan keuangan daerah, rasio derajat desentralisai fiskal, rasio indeks kemampuan rutin, rasio keserasian, rasio pertumbuhan. 2) Untuk mengetahui Kabupaten Sleman semakin mampu dalam melaksanakan otonomi daerah dengan menggunakan analisis trend. Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan beberapa rasio keuangan.
Jenis penelitian ini adalah studi kasus pada pemerintah Kabupaten Sleman. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan adalah deskriptif dengan angka indeks kemampuan keuangan sebagai alat ukur dalam menilai kemampuan keuangan dari satu periode ke periode yang lainnya.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Sleman belum mampu mendukung pelaksanaan otonomi daerah dilihat dari analisis rasio dan analisis trend.
xv
ABSTRACT
AN ANALYSIS OF REGIONAL FINANCIAL CAPABILITY IN SUPPORTING THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL AUTONOMY
Case Study on the Sleman District Government
Maria Margareta Cahyaningrat Warih Kusuma Puspita Handayani
NIM:112114068
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2015
The purpose of this research were: 1) to determine whether incomes of Sleman District has supported the implementation of regional autonomy of fiscal year 2010-2014 as seen from the ratio of the regional of financial independence, the degree of fiscal decentralization ratio, the ratio of routine capability index, the ratio of the harmony, and the growth ratio. 2) To investigate whether Sleman District is more able to carry out regional autonomy by using analysis of trend. Types of this research uses quantitative with the use of several financial ratios.
Types of this research is a case study to the Sleman Regency government. The data was obtained by interview and documentation. The data technical analysis used is descriptive with the index of financial capabilities as measurement tools in assessing financial capabilities from one period to another.
1
BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Di dalam sebuah organisasi tentu memerlukan manajemen yang baik.
Organisasi merupakan sekumpulan orang yang bersama-sama mencapai tujuan
yang telah ditetapkan. Berdasarkan tujuan, organisasi dikelompokkan menjadi tiga
menurut Jones dan Pendlebury dalam Sholihin(2015:1), yaitu profit-oriented
merupakan organisasi yang mempunyai tujuan utama memaksimumkan laba,
seperti perusahaan yang melakukan bisnis untuk tujuan utama memperoleh laba,
type A non-profit merupakan organisasi non laba yang seluruh atau hampir seluruh sumber daya finansialnya diperoleh dari pendapatan penjualan barang dan jasa,
seperti rumah sakit pemerintah yang pendapatannya diperoleh dari jasa pelayanan
kesehatan dan tidak tergantung pendapatannya dari anggaran pemerintah, type B
non-profit merupakan organisasi non laba yang memperoleh sumber daya finansial dalam jumlah yang signikan dari sumber selain penjualan barang dan
jasa, seperti pemerintah pusat dan daerah.
Pemerintah merupakan sebuah organisasi. Pemerintah ke dalam konteks
negara pastilah bertujuan nirlaba. Tujuan pemerintah tentu melaksanakan tujuan
negara. Oleh sebab itu, dapat dipahami tujuan pemerintah merupakan tujuan
negara. Pemerintah mempunyai tujuan yaitu untuk memajukan kesejahteraan
Di dalam pemerintahan daerah terdapat undang-undang yang mengatur
tentang otonomi daerah yang terdapat pada undang-undang nomor 23 tahun 2014.
Otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Perubahan sistem politik, sosial, dan kemasyarakatan serta ekonomi yang
dibawa oleh arus reformasi telah menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap
pengelolaan pemerintah yang baik . PP nomor 58 tahun 2005 diganti menjadi PP
nomor 39 tahun 2007 mensyaratkan perlu dilakukannya pertanggungjawaban
dalam bentuk laporan keuangan (neraca, laporan arus kas, laporan realisasi
anggaran dan catatan atas laporan keuangan) oleh kepala daerah.
Kemampuan keuangan daerah pada dasarnya adalah kemampuan dari
pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya sendiri.
Menurut Munir dkk (2004:105), ciri utama yang menunjukkan suatu daerah
mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah, artinya daerah
otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali
sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang
Kinerja keuangan merupakan tingkat pencapaian suatu target kegiatan
keuangan pemerintah daerah yang diukur melalui indikator-indikator keuangan
yang dapat dinilai dari hasil pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tolak ukur yang dapat dipakai
untuk meningkatkan adanya pembangunan suatu daerah dari berbagai macam
sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan
ekonomi. Menurut Arsyad (1992), suatu perekonomian bisa dikatakan mengalami
pertumbuhan jika tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai lebih tinggi dari waktu
sebelumnya. Dengan kata lain, perkembangannya baru terjadi jika jumlah barang
dan jasa secara fisik yang dihasilkan perekonomian tersebut bertambah besar pada
tahun-tahun berikutnya.
Tujuan pelaporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah untuk
menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk
menunjukkan akuntabilitas (pertanggungjawaban) pemerintah daerah atas sumber
yang dipercayakan. Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas untuk
menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib
menyampaikan laporan pertanggungiawaban keuangan daerahnya untuk dinilai
apakah ia berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat
untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan
daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang
Hasil analisis rasio keuangan digunakan sebagai alat ukur dalam menilai
kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi
daerah, mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan
daerah, mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan
pendapatan daerahnya, mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan
dalam pembentukan pendapatan daerah, melihat pertumbuhan dan perkembangan
perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu
tertentu.
Peranan Pendapatan Asli Daerah dalam keuangan daerah menjadi salah
satu tolak ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, dalam arti semakin
besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun PAD maka akan semakin besar
pula tersedianya jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan Otonomi Daerah.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan
masalah dalam penelitian ini, adalah:
1. Apakah pendapatan Kabupaten Sleman mampu mendukung pelaksanaan
otonomi daerah dilihat dari rasio kemampuan keuangan daerah, rasio derajat
desentralisai fiskal, rasio indeks kemampuan rutin, rasio keserasian, rasio
2. Apakah Kabupaten Sleman semakin mampu melaksanakan otonomi daerah
dengan menggunakan analisis trend sebagai alat ukur dalam menilai
perkembangan kemampuan keuangan daerah?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan penelitian ini, antara
lain:
1) Untuk mengetahui pendapatan Kabupaten Sleman mampu mendukung
pelaksanaan otonomi daerah dilihat dari rasio kemampuan keuangan
daerah, rasio derajat desentralisai fiskal, rasio indeks kemampuan rutin,
rasio keserasian, rasio pertumbuhan.
2) Untuk mengetahui Kabupaten Sleman semakin mampu melaksanakan
otonomi daerah dengan menggunakan analisis trend sebagai alat ukur
dalam menilai perkembangan kemampuan keuangan daerah.
D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:
1.Bagi Instansi pemerintahan
Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi,
perbandingan, dan bahan acuan bagi instansi pemerintahan dalam rangka
pengelolaan keuangan daerah demi tercapainya keberhasilan pelaksanaan
otonomi daerah.
2. Bagi Peneliti
Diharapkan melalui penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan
wawasan tentang kinerja keuangan daerah
3. Bagi Pembaca
Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran
tentang sejauh mana perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah,
dan dapat digunakan sebagai bahan pengembangan bagi penelitian
selanjutnya.
E. Sistematika Penulisan
Bab I Pendahuluan
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan
sistematika penulisan.
Bab II Landasan Teori
Bab ini menjelaskan tentang pengertian akuntansi
pemerintahan, tujuan akuntansi pemerintahan, karakteristik
akuntansi pemerintahan, syarat akuntansi pemerintahan,
teknik pencatatan dalam akuntansi sektor publik, pengertian
otonomi daerah, beberapa komponen yang membentuk
otonomi daerah, kemampuan keuangan daerah, peningkatan
pendapatan daerah, pengelolaan pengeluaran daerah,
penyebab ketergantungan fiskal, anggaran pendapatan dan
belanja daerah, analisis rasio anggaran pendapatan dan
belanja daerah.
Bab III Metode Penelitian
Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian dan sumber data,
waktu dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data,
teknik analisis data
Bab IV Gambaran Umum Kabupaten Sleman
Bab ini menjelaskan tentang keadaan geografis,
pemerintahan, keadaan penduduk, sosial, pertanian, industri,
pertambangan dan penggalian, perdagangan, hotel,
pariwisata, transportasi, keuangan dan perbankan, produk
domestik regional bruto.
Bab V Analisis Data dan Pembahasan
Bab ini berisi tentang analisis data dan hasil penelitian serta
pembahasannya.
Bab VI Penutup
Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, saran.
8
proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan & pelaporan transaksi
keuangan dari suatu organisasi publik yang menyediakan informasi
keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk
pengambilan keputusan.
Menurut Halim, dkk (2012) Akuntansi sektor publik adalah suatu
proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi
ekonomi dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM,
dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil
keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.
2. Tujuan Akuntansi Pemerintahan
Menurut Nordiawan, dkk (2007:7), akuntansi pemerintahan mempunyai tiga
tujuan pokok, yaitu :
1) Pertanggungjawaban
Tujuan dari akuntansi pemerintahan adalah memberikan informasi
keuangan yang lengkap, cermat, dan dalam bentuk dan waktu yang
tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggungjawab, terkait
mengandung implikasi bahwa akuntansi pemerintahan seharusnya
menyediakan informasi tentang berbagai tindakan pemerintah selama
periode bersangkutan. Jadi, dapat dikatakan bahwa fungsi
pertanggungjawaban mengandung arti yang lebih luas dari sekadar
ketaatan kepada peraturan.
2) Manajerial
Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi keuangan
yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan,
pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah. Tujuan
manajerial ini perlu dikembangkan agar organisasi pemerintahan
tingkat atas dan menengah dapat mengandalkan informasi keuangan
atas pelaksanaan sebelumnya untuk membuat keputusan atau
menyusun perencanaan masa yang akan datang.
3) Pengawasan
Akuntansi pemerintah juga harus memungkinkan terselenggaranya
pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan
3. Karakteristik Akuntansi Pemerintahan
Akuntansi Pemerintahan memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan
dengan akuntansi bisnis. Menurut Nordiawan,dkk (2007:7), akuntansi
pemerintahan mempunyai ciri-ciri khas sebagai berikut:
1) Investasi pada aset yang tidak menghasilkan pendapatan
Pada umumnya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat memerlukan investasi yang besar pada aset yang tidak
menghasilkan pendapatan, seperti jalan, jembatan, dan bangunan publik
lainnya.
2) Tidak ada pengungkapan laba
Tujuan pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat,
bukan pencapaian laba. Dalam sektor pemerintahan, tidak terdapat
hubungan langsung antara pembayaran pajak oleh masyarakat dengan jasa
yang diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, tidak akan terdapat
laporan laba rugi yang mengungkapkan pencapaian sebuah laba.
3) Tidak ada pengungkapan kepemilikan
Pemerintah tidak mempunyai kekayaan sendiri sebagaimana perusahaan
dan pemerintah tidak dimiliki oleh individu atau golongan. Dengan
demikian, tidak akan terdapat pernyataan atau pengungkapan yang
menunjukkan kepemilikan suatu pihak seperti halnya ditunjukkan oleh
4) Penggunaan akuntansi dana
Dengan segala karakteristik yang melekat pada organisasinya, akuntansi
lebih memandang pemerintah sebagai kesatuan dana dengan tujuan dan misi
tertentu, tidak sebagai sebuah entitas organisasi yang mempunyai
kepemilikan.
4. Syarat Akuntansi Pemerintahan
Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah sesuai dengan karakteristik
dan bertujuan untuk memenuhi akuntabilitas keuangan negara yang memadai.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan suatu pedoman untuk akuntansi
pemerintahan A Manual Governmental Accounting yang diringkas dalam Bachtiar Arif (2002: 9) yaitu :
1) Dapat memenuhi persyaratan UUD, UU, dan Peraturan lain.
Akuntansi pemerintahan dirancang untuk persyaratan-persyaratan yang
ditentukan oleh UUD, UU, dan Peraturan lain. Apabila terdapat dua pilihan
yaitu untuk kepentingan efisiensi dan ekonomis di satu sisi, sedangkan disisi
lain hal tersebut bertentangan dengan UUD, UU atau Peraturan lainnya, maka
akuntansi tersebut harus disesuaikan dengan UUD, UU dan Peraturan lainnya.
2) Dikaitkan dengan klasifikasi anggaran
Sistem akuntansi pemerintah harus dikembangkan sesuai dengan klasifikasi
anggaran dan akuntansi harus saling melengkapi di dalam pengelolaan
keuangan negara serta harus diintegrasikan.
3) Perkiraan-perkiraan yang harus diselenggarakan
Sistem akuntansi pemerintah harus mengembangkan perkiraan perkiraan untuk
mencatat transaksi uang terjadi. Perkiraan-perkiraan yang dibuat harus dapat
menunjukkan akuntabilitas keuangan negara yang andal dari sisi obyek dan
tujuan penggunaan dana serta pejabat atau organisasi yang mengelolanya.
4) Memudahkan pemeriksaan oleh aparatur negara
Sistem akuntansi pemerintah yang dikembangkan harus memungkinkan aparat
pemeriksaan untuk melakukan tugasnya.
5) Sistem akuntansi harus terus dikembangkan
Dengan adanya perubahan lingkungan dan sifat transaksi, sistem akuntansi
pemerintahan harus terus disesuaikan dan dikembangkan sehingga tercapai
efisiensi, efektivitas dan relevansi.
6) Perkiraan-perkiraan yang harus dikembangkan secara efektif
Sistem akuntansi pemerintahan harus mengembangkan perkiraan perkiraan
secara efektif sehubungan dengan sifat dan perubahan lingkungan sehingga
dapat mengungkapkan hasil ekonomi dan keuangan dari pelaksanaan suatu
7) Sistem harus dapat melayani kebutuhan dasar informasi keuangan guna
pengembangan rencana dan program.
Sistem akuntansi pemerintahan harus dikembangkan untuk para pengguna
informasi keuangan, yaitu pemerintah, rakyat (lembaga legislatif), lembaga
donor, Bank Dunia, dan lain sebagainya.
8) Pengadaan suatu perkiraan
Perkiraan-perkiraan yang dibuat harus memungkinkan analisis ekonomi atas
data keuangan dan mereklasifikasi transaksi-transaksi pemerintah baik pusat
maupun daerah dalam rangka pengembangan perkiraan-perkiraan nasional.
5. Teknik pencatatan dalam akutansi sektor publik
Sesuai dengan amanat UU no.17 tahun 2003 dan PP No.71 tahun 2010
maka pemerintah daerah wajib menggunakan basis akrual. Basis akrual adalah
basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada
saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau
setara kas diterima atau dibayar.
Menurut Sholihin(2015:10), basis akuntansi yang digunakan dalam
laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan
dalam Laporan Operasional, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Basis akrual
untuk pendapatan Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada
saat hak untuk memperoleh pendapatan diakui pada saat hak untuk
memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di
saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah
terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah
atau entitas pelaporan.
Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas
diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau
kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Secara ringkas,
basis akrual adalah basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa
akuntansi dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya
transakasi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan.
B. Otonomi Daerah
1. Pengertian Otonomi Daerah
Dalam Undang-Undang No.23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6, pengertian
otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menurut Mardiasmo (2002: 25) otonomi daerah adalah kewenangan daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
2. Beberapa komponen yang membentuk otonomi daerah yaitu:
1) Kewenangan Otonomi Luas
Yang dimaksud dengan kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan
daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup semua
bidang pemerintahan kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan
keamanan, peradilan, moneter, fiskal, dan agama serta kewenangan dibidang
lainnya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Disamping itu
keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam
penyelenggaraan mulai dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,
pengendalian dan evaluasi.
2) Otonomi Nyata
Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan
kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan
diperlukan serta tumbuh hidup dan berkembang di daerah.
3) Otonomi Yang Bertanggung Jawab
Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan
pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan
kepada daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi berupa
peningkatan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik,
pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta
pemeliharaan hubungan yang sehat antara pusat dan daerah serta antar daerah
Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 8,9,10,11 tentang
Pemerintah Daerah, ada 4 dasar sistem hubungan antara pusat dan daerah
yaitu :
a) Desentralisasi yaitu penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah
Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
b) Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau
kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan
pemerintahan umum.
c) Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga
pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang
tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam
rangka Dekonsentrasi.
d) Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah
otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi
kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan
3. Prinsip otonomi Daerah
Kuncoro(2014:6), perkembangan prinsip dan tingkatan otonomi
pemerintah daerah di Indonesia pada dasarnya dibedakan menjadi: 1)
rumah tangga secara materiil, di mana terdapat pembagian kewenangan
secara terperinci antara tugas pemerintah pusat dan daerah; 2) rumah
tangga secara riil, suatu sistem rumah tangga yang didasarkan pada
keadaan, faktor, tindakan dan kebijakan yang nyata, sehingga terdapat
harmoni antara tugas, kemampuan dan kekuatan baik dalam daerah itu
sendiri maupun dengan pemerintah pusat; 3) rumah tangga secara formal,
dimana tidak terdapat perbedaan dari sisi sifat dan urusan yang
diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan daerah, sehingga perbedaan
tugas yang dilaksanakan dengan kesanggupan daerah yang bersangkutan.
4. Tujuan kebijakan Otonomi Daerah
Kuncoro (2014:30), Salah satu tujuan kebijakan desentralisasi dan otonomi
daerah adalah untuk menjadikan pemerintah lebih dekat dengan rakyatnya,
sehingga pelayanan pemerintah dapat dilakukan dengan lebih efisien,
cepat, dan efektif. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa pemerintah
kabupaten dan kota memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai
C. Keuangan Daerah
1. Kemampuan Keuangan Daerah
Kriteria penting yang lain untuk mengetahui secara nyata kemampuan
daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan
daerah dalam bidang keuangan. Dengan perkataan lain, faktor keuangan
merupakan faktor yang penting dalam mengatur tingkat kemampuan daerah
dalam melaksanakan otonomi daerah. Dalam Peraturan Pemerintah No. 39
tahun 2007, menyebutkan bahwa Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan
dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan
yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan tersebut, APBD sebagai
salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur
dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan dikeluarkannya
undang-undang tentang Otonomi Daerah, membawa konsekuensi bagi daerah yang
akan menimbulkan perbedaan antar daerah yang satu dengan yang lainnya,
terutama dalam hal kemampuan keuangan daerah, antara lain (Nataluddin,
2001: 167):
1) Daerah yang mampu melaksanakan otonomi daerah.
2) Daerah yang mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah.
3) Daerah yang sedikit mampu melaksanakan otonomi daerah
Selain itu ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu
melaksanakan otonomi daerah adalah sebagai berikut (Nataluddin, 2001:167):
1) Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan
dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan
menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahannya.
2) Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin agar
Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan
terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan
daerah, sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.
Berkaitan dengan hakekat otonomi daerah yaitu berkaitan dengan pelimpahan
wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan
pengaturan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan
masyarakat, maka peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk
mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja
yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara
efektif dan efisien. Data keuangan daerah yang memberikan gambaran statistik
perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran dan
analisa terhadapnya merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat
kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah untuk melihat kemampuan /
Pola hubungan daerah menurut Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam
Halim (2002:169) mengemukakan pola hubungan antara pemerintah pusat dan
daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.
1) Pola Hubungan Instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan dari
pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan
otonomi daerah).
2) Pola Hubungan Konsultatif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai
berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi.
3) Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang,
mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu
melaksanakan urusan otonomi.
4) Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada
karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan
otonomi daerah. Bertolak dari teori tersebut, karena adanya potensi sumber daya
alam dan sumber daya manusia yang berbeda, akan terjadi pula perbedaan pola
hubungan dan tingkat kemandirian antar daerah.
Menurut Kuncoro (2014:8), berpijak pada tiga asas desentralisasi
(dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas perbantuan), pengaturan hubungan
keuangan pusat daerah didasarkan atas 4 prinsip yaitu urusan yang merupakan
tugas pemerintah pusat di daerah dalam rangka dekonsentrasi dibiayai dari dan
atas beban APBN, urusan yang merupakan tugas pemerintah sendiri dalam rangka
pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya yang dilaksanakan dalam
rangka tugas perbantuan dibiayai oleh pemerintah pusat atas beban APBN atau
oleh pemerintah daerah tingkat atasnya atas beban APBD sebagai pihak yang
menugaskan, sepanjang potensi sumber-sumber keuangan daerah belum
mencukupi pemerintah pusat memberikan sejumlah sumbangan.
2. Peningkatan Pendapatan Daerah
Langkah-langkah yang dapat dilaksanakan agar pendapatan daerah dapat
ditingkatkan antara lain sebagai berikut (Nirzawan, 2001: 75):
1) Intensifikasi, dilaksanakan antara lain dengan cara sebagai berikut :
a) Melaksanakan tertib penetapan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak,
tertib dalam pemungutan kepada wajib pajak, tertib dalam administrasi
serta tertib dalam penyetoran.
b) Melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah
sesuai dengan potensi yang obyektif berdasarkan peraturan yang berlaku.
c) Melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan
berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam
pelaksanaan pemungutan di lapangan oleh petugas.
d) Membentuk tim satuan tugas (satgas) pada dinas terkait yang bertugas
mengawasi pemungutan di lapangan oleh petugas.
e) Memberikan insentif secara khusus kepada aparat pengelola PAD yang
f) Mengadakan pendekatan persuasif kepada wajib pajak agar memenuhi
kewajibannya melalui kegiatan penyuluhan.
g) Melakukan langkah-langkah pengendalian lain guna menghindari
timbulnya penyimpangan terhadap pelaksanaan peraturan daerah
mengenai pengelolaan maupun penetapan pajak dan retribusi daerah.
2)Ekstensifikasi, dilaksanakan dengan cara antara lain sebagai berikut:
a) Menyusun program kebijakan dan strategi pengembangan dan menggali
obyek pungutan baru yang potensial dengan lebih memprioritaskan
kepada retribusi daerah untuk ditetapkan dan dijabarkan dalam peraturan
daerah.
b) Meninjau kembali ketentuan tarif dan pengembangan sasaran sesuai
dengan peraturan daerah yang ada dan mengkaji ulang peraturan daerah
untuk diajukan perubahan.
c) Mengadakan studi banding ke daerah lain guna mendapat informasi
terhadap jenis-jenis penerimaan pajak dan retribusi lain yang
memungkinkan untuk dikembangkan.
3 Pengelolaan Pengeluaran Daerah
Dalam Peraturan pemerintah No. 39 tahun 2007, menyebutkan bahwa
Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah periode tahun
anggaran yang bersangkutan. Menurut Sholihin (2015:31) berdasarkan
karakteristiknya, belanja dikelompokkan menjadi belanja rutin (belanja
1) Belanja Operasi
Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari
pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja
operasi terdiri dari:
a. Belanja Pegawai
Merupakan belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun
barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang diberikan kepada pejabat daerah, Pegawai Negeri Sipil (PNS),
dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemda yang belum berstatus
PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali
pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
b. Belanja Barang
Merupakan pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan
jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang
dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang
dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan
belanja perjalanan. Belanja barang dapat dibedakan menjadi belanja
barang dan jasa, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan dinas.
1. Belanja Barang dan Jasa
Merupakan pengeluaran yang antara lain dilakukan untuk
membiayai keperluan kantor sehari-hari, pengadaan/
penggantian inventaris kantor, langganan daya dan jasa,
nonfisik dan secara langsung menunjang tugas pokok dan
fungsi SKPD, pengadaan inventaris kantor yang nilainya
tidak memenuhi syarat nilai kapitalisasi minimum yang
diatur oleh pemda dan pengeluaran jasa nonfisik seperti
pengeluaran untuk biaya pelatihan dan penelitian.
2. Belanja Pemeliharaan
Merupakan pengeluaran yang dimaksudkan untuk
mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada
ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar
kecilnya jumlah belanja. Belanja pemeliharaan meliputi
antara lain pemeliharaan tanah, pemeliharaan gedung dan
bangunan kantor, rumah dinas, kendaraan bermotor dinas,
perbaikan peralatan dan sarana gedung, jalan, jaringan
irigasi, peralatan mesin, dan lain-lain sarana yang
berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
3. Belanja Perjalanan Dinas
Merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai
perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan
jabatan.
c. Belanja Bunga
Belanja bunga adalah pengeluaran pemda untuk pembayaran
outstanding) yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panajang
d. Belanja Subsidi
Belanja Subsidi yaitu alokasi anggaran yang diberikan kepada
perusahaan/ lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau
mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang
banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau
masyarakat.
e. Hibah
Hibah adalah pengeluaran pemda dalam bentuk uang/barang atau
jasa kepada pemda lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan
organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan
peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak
secara terus menerus.
f. Bantuan Sosial
Bantuan sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan
kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya
risiko sosial.
2) Belanja Modal
Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap
dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode
pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset
lainnya yang dengan demikian menambah aset pemda, pengeluaran tersebut
melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah
ditetapkan oleh pemda, perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk
dijual.
Belanja modal terdiri meliputi antara lain: belanja modal untuk
perolehan tanah, gedung, dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi
dan jaringan, dan aset tetap lainnya
3) Belanja tidak terduga
Menurut pasal 48 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Belanja Tak Terduga
adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan
berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak
diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan
daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.
Pengeluaran daerah tersebut harus dikelola dengan memperhatikan beberapa
prinsip yang harus dipertimbangkan antara lain (Nirzawan,2001: 77):
1) Akuntabilitas
Akuntabilitas pengeluaran daerah adalah kewajiban pemerintah daerah untuk
memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan melaporkan segala aktivitas
dan kegiatan yang terkait dengan penggunaan uang publik kepada pihak yang
(DPRD dan masyarakat luas). Aspek penting yang harus dipertimbangkan oleh
para manajer daerah adalah :
a) Aspek legalitas pengeluaran daerah yaitu setiap transaksi pengeluaran yang
dilakukan harus dapat dilacak otoritas legalnya.
b) Pengelolaan (stewardship) atas pengeluaran daerah yang baik, perlindungan aset fisik dan finansial, mencegah terjadinya pemborosan dan salah urus.
Prinsip-prinsip akuntabilitas pengeluaran daerah :
a) Adanya sistem akuntansi dan sistem anggaran yang dapat menjamin bahwa
pengeluaran daerah dilakukan secara konsistensi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
b) Pengeluaran daerah yang dilakukan dapat menunjukkan tingkat pencapaian
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
c) Pengeluaran daerah yang dilakukan dapat berorientasi pada pencapaian visi,
misi, hasil dan manfaat yang akan diperoleh.
2) Value of Money
Pengeluaran daerah harus mendasarkan konsep value of money,yaitu:
a) Ekonomi, adalah hubungan antara pasar (nilai uang) dan masukan (input).
Ekonomi adalah pembelian barang dan jasa pada kualitas yang diinginkan
dan pada harga terbaik yang memungkinkan. Pengertian ekonomi sebaiknya
mencakup juga pengeluaran daerah yang berhati-hati atau cermat dan
Suatu kegiatan operasional dikatakan ekonomis apabila dapat menghilangkan
atau mengurangi biaya yang dianggap tidak perlu. Dengan demikian pada
hakekatnya ada pengertian yang serupa antara efisiensi dan ekonomi, karena
kedua-keduanya menghendaki penghapusan dan penurunan biaya.
b) Efisiensi, berhubungan erat dengan konsep efektivitas, yaitu rasio yang
membandingkan antara output yang dihasilkan terhadap input yang
digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dilakukan secara efisiensi
apabila suatu target kinerja tertentu dapat dicapai dengan menggunakan
sumber daya dan biaya yang serendah-rendahnya.
c) Efektivitas, merupakan kaitan atau hubungan antara keluaran suatu pusat
pertanggung jawaban dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapainya.
Efektivitas dalam Pemerintah Daerah dapat diartikan penyelesaian kegiatan
tepat pada waktunya dan didalam batas anggaran yang tersedia, dapat berarti
pula mencapai tujuan dan sasaran seperti apa yang telah direncanakan.
Namun demikian, walaupun ada yang dilaksanakan menyimpang dari rencana
semula, tetapi mempunyai dampak yang menguntungkan pada kelompok
penerima sasaran manfaat, maka dapat dikatakan efektif. Semakin besar
kontribusi pengeluaran yang dilakukan terhadap nilai pencapaian tujuan atau
sasaran yang ditentukan dapat dikatakan efektif proses kerja dari unit kerja
4. Penyebab Ketergantungan Fiskal
Menurut Kuncoro (2014:13), Penyebab utama rendahnya Pendapatan Asli
Daerah yang menyebankan tingginya ketergantungan terhadap subsidi dari
pusat adalah Pertama, kurang berperannya perusahaan daerah sebagai
sumber pendapatan daerah, seperti Daerah Tingkat 1 bagian laba BUMD
selama tahun 1988-1993 meningkat pesat (tahun 1988 berjumlah Rp16,7
milyar meningkat menjadi Rp 40,2 milyar pada tahun 1993), namun
sumbangannya terhadap pendapatan daerah relatif masih kecil.
Kedua, tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan. Semua
pajak utama yang paling produktif baik pajak langsung dan tak langsung
ditarik oleh pusat. Pajak penghasilan badan maupun perorangan, Pajak
Pertambahan Nilai, bea cukai, PBB, royalti/IHH/IHPH (atas minyak,
pertambangan, kehutanan) semua diadministrasi dan ditentukan tarifnya oleh
pusat.
Ketiga, kendati pajak daerah cukup beragam, ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan. Pajak daerah yang ada saat ini
berjumlah 50 jenis pajak, tetapi yang bersifat ekonomis bisa dilakukan
pemungutannya hanya terdiri dari 12 jenis pajak. Sekitar 90% pendapatan
Daerah Tingkat I hanya berasal dari dua sumber: Pajak Kendaraan Bermotor
dan Balik Nama. Di Daerah Tingkat II, sekitar 85% pendapatan daerah hanya
berasal dari enam sumber: pajak hotel dan restauran, penerangan jalan,
pertunjukan, reklame, pendaftaran usaha, ijin penjualan/ pembikinan petasan
dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Balik Nama. Pajak-pajak daerah lainnya
sulit sekali untuk diharapkan karena untuk mengubah kebijakan pajak daerah
memerlukan persetujuan dari Departemen Dalam Negeri dan Menteri
Keuangan.
Keempat, ada yang khawatir apabila daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi akan mendorong terjadinya disintegrasi dan
separatisme. Yugoslavia dan Uni Soviet sering ditunjuk sebagai contoh
negara yang cerai berai karena dorongan dari daerah yang merasa cukup kuat
dalam sumber keuangan untuk berdiri sendiri sebagai sebuah negara.
Kelima, kelemahan dalam pemberian subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Selama ini pemerintah memberikan subsidi dalam
bentuk blok dan spesifik. Subsidi yang bersifat blok terdiri dari Inpres Dati I,
Inpres Dati II dan Inpres desa. Subsidi yang bersifat spesifik meliputi Inpres
pengembangan wilayah, Sekolah Dasar, kesehatan, penghijauan dan
reboisasi, jalan serta jembatan. Perbedaan utama antara subsidi blok dengan
subsidi spesifik adalah daerah memiliki keleluasaan dalam penggunaan
subsidi blok, sedangkan penggunaan dana subsidi spesifik sudah ditentukan
oleh pemerintah pusat dan daerah tidak mempunyai keleluasaan dalam
D. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Menurut Sholihin (2010:3) anggaran pemerintah merupakan dokumen
formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang
ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang
diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang
diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus.
Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat yang
memegang peranan penting dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan
kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas,
nyata, dan bertanggung jawab. Dengan demikian maka APBD harus
benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan
potensi dan keanekaragaman daerah.
Atas dasar tersebut, penyusunan APBD hendaknya mengacu pada
norma-norma dan prinsip anggaran sebagai berikut (Nirzawan, 2001: 79) :
a. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran
Transparansi tentang anggaran daerah merupakan salah satu persyaratan
untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab.
Mengingat anggaran daerah merupakan salah satu sarana evaluasi
pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah menyejahterakan
masyarakat, maka APBD harus dapat memberikan informasi yang jelas
suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Selain itu setiap dana yang
diperoleh, penggunaannya harus dapat dipertanggung jawabkan.
b. Disiplin Anggaran
Anggaran yang disusun harus dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat
guna, tepat waktu dan dapat dipertanggung jawabkan. Pemilihan antara
belanja yang bersifat rutin dengan belanja yang bersifat pembangunan /
modal harus diklasifikasikan secara jelas agar tidak terjadi
pencampuradukan kedua sifat anggaran yang dapat menimbulkan
pemborosan dan kebocoran dana. Pendapatan yang direncanakan merupakan
perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap
sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap pos /
pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
c. Keadilan Anggaran
Pembiayaan pemerintah dapat dilakukan melalui mekanisme pajak dan
retribusi yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat, untuk itu
pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunannya secara adil agar
dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi
dalam pemberian pelayanan.
d. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat
menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal
tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan perlu
ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang akan
diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang diprogramkan.
e. Format Anggaran
Pada dasarnya APBD disusun berdasarkan format anggaran defisit (defisit
budget format). Selisih antara pendapatan dan belanja mengakibatkan
terjadinya surplus atau defisit anggaran. Apabila terjadi surplus, daerah
dapat membentuk dana cadangan, sedangkan bila terjadi defisit, dapat
ditutupi melalui sumber pembiayaan pinjaman dan penerbitan obligasi
daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) disusun dengan
pendekatan kinerja dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 1 (satu)
bulan setelah APBN ditetapkan, demikian juga halnya dengan perubahan APBD
ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum
berakhirnya tahun anggaran. Sedangkan perhitungan APBD ditetapkan paling
lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.
Sholihin (2010:3), fungsi anggaran di lingkungan pemerintah mempunyai
pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan antara lain karena
anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik, anggaran merupakan target
fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan
pembiayaan yang diinginkan, anggaran menjadi landasan pengendalian yang
pemerintah, hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan
pemerintah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik.
2. Analisis Rasio Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis,
efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan
walaupun perakuntasian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang
dimiliki perusahaan swasta. Analisis rasio pada APBD dilakukan dengan
membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan
periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang
terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio
keuangan yang dimiliki suatu pemerintah tertentu dengan rasio keuangan daerah
lain yang terdekat maupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat
bagaimana posisi rasio keuangan Pemerintah Daerah tersebut terhadap Pemerintah
Daerah lainnya. Adapun pihak-pihaknya yang berkepentingan dengan rasio
keuangan pada APBD ini adalah:
1. DPRD sebagai wakil dari pemilik daerah (masyarakat).
2. Pemerintah eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya.
3. Pemerintah pusat / provinsi sebagai bahan masukan dalam pembinaan
pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
4. Masyarakat dan kreditur, sebagai pihak yang akan turut memiliki saham
Beberapa rasio yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan data keuangan
yang bersumber dari APBD diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
a) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu
daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan
pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai
sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian ditunjukkan
oleh besarnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah
yang berasal dari sumber lain (pihak ekstern) antara lain : Bagi hasil pajak,
Bagi hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana
Alokasi Khusus, Dana Darurat dan Dana Pinjaman, (Halim, 2012:L-5).
Rumus yang digunakan adalah:
Rasio Kemandirian =
Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber
dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa
tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin
rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan
tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi
rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar
pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli
daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan
Semakin tinggi rasio Kemandirian, maka semakin tinggi pula kemampuan
keuangan daerah dalam mendukung otonomi daerah.
b) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal
Derajat Desentralisasi Fiskal adalah kemampuan pemerintah daerah dalam
rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan.
Derajat Desentralisasi Fiskal, khususnya komponen PAD dibandingkan dengan
Total Pendapatan Daerah.
Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dihitung dengan menggunakan rumus
sebagai berikut :
DDF =
Keterangan :
DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal
PADt =Total PAD tahun t
TPDt = Total Penerimaan Daerah Tahun t
Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal menggambarkan besarnya campur tangan
pemerintah pusat dalam pembangunan daerah yang menunjukkan tingkat
kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Semakin
tinggi rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, maka semakin tinggi pula
c) Rasio Indeks Kemampuan Rutin
Indeks Kemampuan Rutin yaitu : Proporsi antara PAD dengan pengeluaran
rutin . Sedangkan dalam menilai Indeks Kemampuan Rutin daerah (IKR)
dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
Rumus :
IKR =
Keterangan :
IKR = Indeks Kemampuan Rutin
PAD = Pendapatan Asli Daerah
Rasio Indeks Kemampuan Rutin menggambarkan besarnya kemampuan
pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran rutin dalam melaksanakan
kegiatan pemerintahanya. Semakin tinggi rasio Indeks Kemampuan Rutin,
maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan daerah dalam mendukung
otonomi daerah.
d) Rasio Keserasian
Keserasian ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan
alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal.
Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti
presentase belanja pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana
Secara sederhana rasio keserasian ini dapat diformulasikan sebagai berikut:
Rasio Belanja Rutin =
Rasio Belanja Pembangunan =
Rasio Keserasian menggambarkan keseimbangan antara alokasi dana
pemerintah daerah pada belanja rutin dan belanja pembangunan. Semakin
tinggi rasio Keserasian, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan
daerah dalam mendukung otonomi daerah.
e) Rasio Pertumbuhan
Rasio pertumbuhan menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah
daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai
dari periode ke periode lainnya. Pertumbuhan APBD dilihat dari berbagai
komponen penyusun APBD yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Total
Pendapatan, Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan, (Halim, 2012: L-9).
Rumus yang digunakan adalah :
r =
Keterangan :
Pn = Data yang dihitung pada tahun ke-n
Po = Data yang dihitung pada tahun ke-0
Data yang dihitung adalah PAD, TPD, Belanja Rutin, Belanja
Pembangunan. Apabila semakin tinggi nilai PAD, TPD dan Belanja
Pembangunan yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Rutin, maka
pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah
mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode satu
ke periode yang berikutnya.
Selanjutnya jika semakin tinggi nilai PAD, TPD, dan Belanja Rutin yang
diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Pembangunan, maka pertumbuhannya
adalah negatif, artinya bahwa daerah yang bersangkutan belum mampu
mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode yang satu ke
periode yang berikutnya. Semakin tinggi rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli
Daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan daerah dalam
mendukung otonomi daerah.
f) Trend
Purwanto (2007:176), Trend adalah suatu gerakan kecenderungan naik atau
turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu
ke waktu dan nilainya cukup rata. Trend data berkala bisa berbentuk trend yang
meningkat dan menurun. Trend yang meningkat disebut trend positif dan trend
yang menurun disebut trend yang negatif. Trend menunjukkan perubahan
waktu yang relatif panjang dan stabil. Trend positif dan negatif :
a. Trend Positif
Trend positif mempunyai kecenderungan nilai ramalan (Y’) meningkat