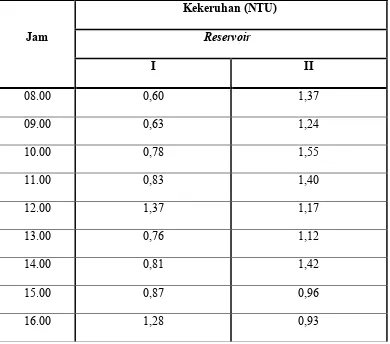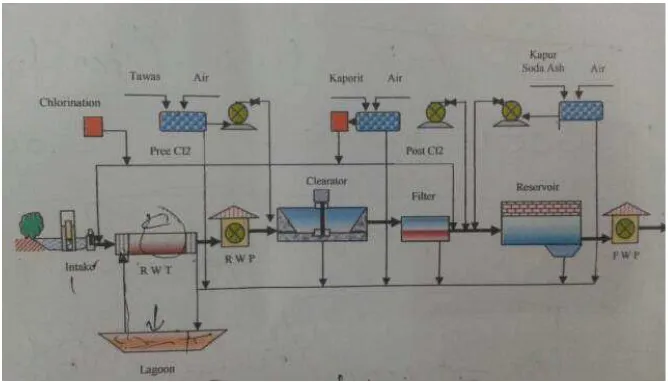PEMERIKSAAN KEKERUHAN DARI AIR RESERVOIR
PADA PDAM TIRTANADI INSTALASI SUNGGAL MEDAN
TUGAS AKHIR
OLEH:
PUJI NURANI
NIM 102410072
PROGRAM STUDI DIPLOMA III
ANALIS FARMASI DAN MAKANAN
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberi
limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas
akhir ini sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian Program Studi Diploma III
Analis Farmasi pada Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara.
Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang
tak terhingga kepada orang tua penulis yang telah memberikan dukungan moril
maupun materil dalam penyelesaian tugas akhir ini. Terima kasih pula untuk kasih
sayang, semangat, dan doa yang selalu menyertai setiap langkah penulis.
Dalam penyelesaian tugas akhir ini, penulis melibatkan banyak pihak yang
telah membantu sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu
sudah sepatutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada:
1. Bapak Prof. Dr. Sumadio Hadisahputra, Apt., selaku Dekan Fakultas
Farmasi
2. Bapak Prof. Dr. Matheus Timbul Simanjuntak, M.Sc., Apt., selaku Dosen
Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk
membimbing dan mengarahkan penyelesaian tugas akhir ini
3. Bapak Prof. Dr. Jansen Silalahi, M.App.Sc., Apt., selaku Koordinator
Program Studi Diploma III Analis Farmasi
4. Bapak Ir. Mawardi, selaku Kepala Instalansi Pengolahan Air PDAM
5. Bapak Iwan Setiawan, selaku Kepala Bagian Laboratorium Pengendalian
Mutu di PDAM Tirtanadi Sunggal yang telah bersedia meluangkan
waktunya untuk memberikan ilmunya selama menjalani Praktek Kerja
Lapangan di Instalansi Pegolahan Air Sunggal
6. Bapak Adi dan Ibu Cempaka, selaku asisten Laboratorium Pengendalian
Mutu PDAM Tirtanadi Sunggal yang telah banyak memberikan masukan
dan motivasi
7. Para karyawan dan seluruh staf di Instalansi Pengolahan Air Sunggal
8. Seluruh staf pengajar dan pegawai di Fakultas Farmasi
9. Dian dan Clara yang merupakan rekan seperjuangan selama menjalani
PKL
10. Seluruh rekan mahasiswa/i Analis Farmasi angkatan 2010
Dalam menyelesaikan tugas akhir ini penulis telah berusaha semaksimal
mungkin. Namun penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih banyak terdapat
kekurangan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan
kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk menyempurnakan tugas
akhir ini.
Semoga tugas akhir yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi
seluruh pembacanya. Untuk mengakhiri kata pengantar ini penulis mengucapkan
terima kasih.
Medan, Juni 2013
EXAMINATION TURBIDITY OF THE WATER RESERVOIR IN PDAM TIRTANADI INSTALASI SUNGGAL MEDAN
ABSTRACT
Reservoir water is raw water that has undergone processing at the water treatment plant and ready to be distributed to the community. Turbidity is one of the physical parameters of the water reservoir, because turbid water will reduce the aesthetic value of the water. In PDAM Tirtanadi IPA Sunggal, examination of turbidity with turbidimetri method. Principle of this method measure the interference light path through a water sample. The water will be include in the cuvette, after that measured with a turbidimeter and will be shown the value of turbidity. Measurement results show the turbidity value of reservoir water no more than 2 NTU. According by Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 492/MENKES/PER/2010 maximum turbidity of the water is 5 NTU.
PEMERIKSAAN KEKERUHAN DARI AIR RESERVOIR
PADA PDAM TIRTANADI INSTALASI SUNGGAL MEDAN
ABSTRAK
Air reservoir adalah air baku yang telah mengalami proses pengolahan pada instalasi pengolahan air dan siap untuk didistribusikan pada masyarakat. Kekeruhan menjadi salah satu parameter fisik dari air reservoir, karena air yang keruh akan mengurangi nilai estetika dari air tersebut. Pada PDAM Tirtanadi IPA Sunggal pemeriksaan kekeruhan dilakukan dengan menggunakan metode turbidimetri. Prinsip metode ini mengukur gangguan lintasan cahaya melalui suatu contoh air. Air akan dimasukkan pada kuvet yang selanjutnya akan diukur dengan alat turbidimeter dan akan tertera nilai kekeruhannya. Hasil pengukuran menunjukkan nilai kekeruhan air reservoir PDAM Tirtanadi memenuhi persyaratan yaitu tidak lebih dari 2 NTU. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 492/MENKES/PER/IV/2010 batas maksimum kekeruhan air adalah 5 NTU.
DAFTAR ISI
2.3.4 Parameter Radioaktivitas ... 6
2.4Kategori Air Minum ... 7
2.5Unit-Unit Pengolahan Air Minum ... 7
2.6Proses Pengolahan Air Minum ... 11
2.6.1 Metode-Metode Pengolahan Fisik ... 11
2.7Kekeruhan pada Air ... 18
2.7.1 Penyebab Kekeruhan ... 19
2.7.2 Deteksi Kekeruhan ... 21
BAB III METODE PENGUJIAN ... 23
3.1Alat dan Bahan ... 23
3.1.1 Alat ... 23
3.1.2 Bahan ... 23
3.2Prosedur Pengujian ... 23
BAB IV HASIL DAN PENGAMATAN ... 24
4.1Hasil ... 24
4.2Pembahasan ... 25
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ... 26
5.1Kesimpulan ... 26
5.2Saran ... 26
DAFTAR PUSTAKA ... 27
DAFTAR TABEL
DAFTAR LAMPIRAN
Halaman Lampiran 1. Alat yang Digunakan pada Pemeriksaan Kekeruhan ... 28 Lampiran 2. Proses Pengolahan Air pada IPA Sunggal ... 29 Lampiran 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
EXAMINATION TURBIDITY OF THE WATER RESERVOIR IN PDAM TIRTANADI INSTALASI SUNGGAL MEDAN
ABSTRACT
Reservoir water is raw water that has undergone processing at the water treatment plant and ready to be distributed to the community. Turbidity is one of the physical parameters of the water reservoir, because turbid water will reduce the aesthetic value of the water. In PDAM Tirtanadi IPA Sunggal, examination of turbidity with turbidimetri method. Principle of this method measure the interference light path through a water sample. The water will be include in the cuvette, after that measured with a turbidimeter and will be shown the value of turbidity. Measurement results show the turbidity value of reservoir water no more than 2 NTU. According by Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 492/MENKES/PER/2010 maximum turbidity of the water is 5 NTU.
PEMERIKSAAN KEKERUHAN DARI AIR RESERVOIR
PADA PDAM TIRTANADI INSTALASI SUNGGAL MEDAN
ABSTRAK
Air reservoir adalah air baku yang telah mengalami proses pengolahan pada instalasi pengolahan air dan siap untuk didistribusikan pada masyarakat. Kekeruhan menjadi salah satu parameter fisik dari air reservoir, karena air yang keruh akan mengurangi nilai estetika dari air tersebut. Pada PDAM Tirtanadi IPA Sunggal pemeriksaan kekeruhan dilakukan dengan menggunakan metode turbidimetri. Prinsip metode ini mengukur gangguan lintasan cahaya melalui suatu contoh air. Air akan dimasukkan pada kuvet yang selanjutnya akan diukur dengan alat turbidimeter dan akan tertera nilai kekeruhannya. Hasil pengukuran menunjukkan nilai kekeruhan air reservoir PDAM Tirtanadi memenuhi persyaratan yaitu tidak lebih dari 2 NTU. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 492/MENKES/PER/IV/2010 batas maksimum kekeruhan air adalah 5 NTU.
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Air merupakan kebutuhan utama bagi proses kehidupan di bumi. Air yang
bersih sangat diperlukan untuk keperluan sehari-hari, industri, kebersihan sanitasi
kota, maupun untuk keperluan pertanian dan lain sebagainya. Namun
kenyataannya pada saat ini untuk mendapatkan air yang bersih sesuai dengan
standart tertentu sangatlah sulit. Hal ini dikarenakan air sudah banyak tercemar
oleh bermacam-macam limbah dari hasil kegiatan manusia, baik limbah rumah
tangga maupun limbah dari kegiatan industri (Wardhana, 2001).
Peningkatan kualitas air minum dengan jalan mengadakan pengelolaan
terhadap air yang akan diperlukan sebagai air minum dengan mutlak diperlukan
terutama apabila air tersebut berasal dari permukaan. Pengelolaan yang dimaksud
bisa dimulai dari yang sangat sederhana sampai pengolahan yang lengkap, sesuai
dengan tingkat kekotoran dari sumber asal air tersebut. Semakin kotor semakin
berat pengolahan yang dibutuhkan, dan semakin banyak ragam zat pencemar akan
semakin banyak pula teknik-teknik yang diperlukan untuk mengolah air tersebut,
agar bisa dimanfaatkan sebagai air minum (Sutrisno, 2010).
Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No.492/MENKES/ PER/IV/2010,
persyaratan air minum dapat ditinjau dari parameter fisika, parameter kimia,
parameter mikrobiologi, dan parameter radioaktivitas yang terdapat di dalam air
Kekeruhan merupakan salah satu bagian dari parameter fisika yang sangat
perlu diperhatikan dalam penyediaan air minum. Air yang baik idealnya tidak
berbau dan harus jernih. Air yang keruh mengandung partikel padat tersuspensi
yang dapat berupa zat berbahaya bagi kesehatan manusia. Disamping itu air yang
keruh sulit didesinfeksi. Tingkat kekeruhan ini dapat ditentukan dengan metode
turbidimetri. Dengan mengukur tingkat kekeruhan pada air, kita akan mengetahui
kualitas air (Mulia, 2005).
1.2 Tujuan dan Manfaat 1.2.1 Tujuan
- Untuk menentukan nilai kekeruhan (turbiditas) air reservoir setelah
mengalami proses pengolahan
- Untuk mengetahui apakah tingkat kekeruhan air reservoir memenuhi
persyaratan Peraturan Menteri Kesehatan RI No.
492/MENKES/PER/IV/2010 dan layak untuk didistribusikan atau tidak
1.2.2 Manfaat
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Air
Air merupakan zat yang paling penting dalam kehidupan setelah udara.
Sekitar tiga perempat bagian dari tubuh kita terdiri dari air dan tidak seorang pun
dapat bertahan hidup lebih dari 4-5 hari tanpa minum air. Selain itu, air juga
dipergunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan membersihkan kotoran yang
ada di sekitar rumah. Air juga digunakan untuk keperluan industri, pertanian,
pemadam kebakaran, tempat rekreasi, transportasi, dan lain-lain (Chandra, 2006).
Ditinjau dari sudut ilmu kesehatan masyarakat, penyediaan air bersih harus
dapat memenuhi kebutuhan masyarakat karena persediaan air bersih yang terbatas
memudahkan timbulnya penyakit di masyarakat. Volume rata-rata kebutuhan air
setiap individu per hari berkisar antara 150-200 liter atau 35-40 galon (Chandra,
2006).
2.2 Sumber-Sumber Air Baku 2.2.1 Air Angkasa
Air hujan jumlahnya sangat terbatas, dipengaruhi antara lain oleh musim,
jumlah, intensitas, dan distribusi hujan. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh letak
geografis suatu daerah dan lain-lain. Kualitas air hujan sangat dipengaruhi oleh
baik, namun kurang mengandung mineral dan sifatnya mirip air suling (Chandra,
2006).
2.2.2 Air Permukaan
Kondisi air permukaan sangat beragam karena banyak dipengaruhi oleh
banyak hal yang berupa elemen metereologi dan elemen daerah pengairan.
Kualitas air permukaan tersebut, tergantung dari daerah yang dilewati oleh air.
Pada umumnya kekeruhan air permukaan cukup tinggi karena banyak
mengandung lempung dan substansi organik. Sehingga ciri air permukaan yaitu
memiliki padatan terendap (dissolved solid) rendah dan bahan tersuspensi
(suspended solids) tinggi. Atas dasar kandungan bahan terendap dan bahan
tersuspensi tersebut maka kualitas air sungai relatif lebih rendah daripada kualitas
air danau, pond, rawa, dan reservoar. Air permukaan dapat dimanfaatkan oleh
masyarakat setelah melalui proses tertentu (Chandra, 2006).
2.2.3 Air tanah
Air tanah adalah air yang bergerak di dalam tanah, terdapat di antara
butir-butir tanah atau dalam retakan bebatuan. Ciri-ciri air tanah yaitu memiliki
suspended solid rendah dan dissolved solid tinggi. Permasalah yang timbul pada
air tanah adalah tingginya angka kandungan total dissolved solid (TDS), besi,
mangan, dan kesadahan. Air tanah dapat berasal dari mata air kaki gunung, atau di
sepanjang aliran air sungai atau berasal dari air tanah dangkal dengan kedalaman
15-30 m yaitu air sumur gali, sumur pantek, sumur bor tangan, serta yang berasal
dari tanah dalam yaitu air sumur bor yang dalamnya lebih dari 30 meter atau
2.3 Persyaratan Air Minum
Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No.492/MENKES/PER/IX/2010,
persyaratan air minum dapat ditinjau dari parameter fisika, parameter kimia,
parameter mikrobiologi, dan parameter radioaktivitas yang terdapat di dalam air
minum tersebut.
2.3.1 Parameter Fisika
Parameter fisika umumnya dapat diidentifikasi dari kondisi fisik air
tersebut. Parameter fisika meliputi bau, kekeruhan, rasa, suhu, warna, dan jumlah
zat yang terlarut (TDS) (Chandra, 2006).
Air yang baik idealnya tidak berbau dan harus jernih. Air yang keruh
mengandung partikel padat tersuspensi yang dapat berupa zat berbahaya bagi
kesehatan manusia. Disamping itu air yang keruh sulit didesinfeksi (Chandra,
2006).
Air yang baik idealnya tidak memiliki rasa/tawar. Selain itu juga air yang
baik tidak boleh memiliki perbedaan suhu yang mencolok dengan udara sekitar
(udara ambien). Di indonesia, suhu air minum idealnya ±30C dari suhu udara. Air
yang secara mencolok mempunyai suhu diatas atau dibawah suhu udara berarti
mengandung zat-zat tertentu atau sedang terjadi proses biokimia yang
mengeluarkan atau menyerap energi dalam air (Chandra, 2006).
Padatan terlarut total (Total Dissolved Solid-TDS) adalah bahan terlarut dan
koloid berupa senyawa kimia. Bila TDS bertambah, kesadahan akan naik dan
2.3.2 Parameter Kimia
Parameter kimia dikelompokkan menjadi kimia anorganik dan kimia
organik. Dalam standar air minum Indonesia zat kimia anorganik dapat berupa
logam, zat reaktif, zat-zat berbahaya dan beracun serta derajat keasaman (pH).
Sedangkan zat kimia organik dapat berupa insektisida dan herbisida, zat kimia
mudah menguap, zat-zat berbahaya dan beracun maupun zat pengikat oksigen
(Chandra, 2006).
2.3.3 Parameter Mikrobiologi
Parameter mikrobiologi menggunakan bakteri coliform sebagai organisme
petunjuk (indicator organisme). Dalam laboratorium, istilah total coliform
menunjukkan bakteri coliform dari tinja, tanah atau sumber alamiah lainnya.
Penentuan parameter mikrobiologi dimaksudkan untuk mencegah adanya mikroba
patogen di dalam air minum (Chandra, 2006).
2.3.4 Parameter Radioaktivitas
Apapun bentuk radioaktivitas efeknya adalah sama yakni menimbulkan
kerusakan pada sel yang terpapar. Kerusakan dapat berupa kematian dan
perubahan komposisi genetik. Kematian sel dapat diganti kembali apabila sel
dapat beregenerasi dan apabila tidak seluruh sel mati. Perubahan genetis dapat
2.4 Kategori Air Minum
Menurut Pitojo, 2002, air minum menurut kandungan kolitinja yaitu sejenis
bakteri patogen yang berkembang biak, serta koliform yaitu bakteri sebagai
indikator kualitas kesehatan (saniter), dibedakan dalam 5 kategori:
1. Air minum kelas A kategori baik adalah tidak mengandung bakteri koli atau
koliform.
2. Air minum kelas B kategori kurang baik mengandung kolitinja 1-10/1-50
koliform.
3. Air minum kelas C kategori jelek mengandung kolitinja 10-50/51-100
koliform.
4. Air minum kelas D kategori amat jelek mengandung kolitinja
51-100/101-1000 koliform.
5. Air minum kelas E kategori sangat jelek mengandung kolitinja >100/>1000
koliform
Air minum kategori kelas A adalah yang langsung dapat diminum dan air
murni kategori B, C, D serta E, harus diperlakukan agar tidak mengandung
kolitinja dan koliform, dan sebelum diminum harus dimasak hingga mendidih
(Pitojo, 2002).
2.5 Unit-Unit Pengolahan Air Minum a. Bangunan Penangkap air
Menurut Sutrisno, 2010, bangunan penangkap air ini merupakan bangunan
dimanfaatkan. Fungsi dari bangunan penangkap ini sangat penting artinya untuk
menjaga kontinuitas pengaliran. Penanganan bangunan penangkap air ini
ditujukan terhadap:
Kuantitas:
- Pencatatan tingkah laku keadaan dari sumber asal air
- Pencatatan debit air pada setiap saat
- Mengontrol/memeriksa peralatan pencatatan debit serta peralatan lainnya
(misalnya: pompa, saringan, pintu air) untuk menjaga kontinuitas debit
pengaliran
Kualitas
- Hal ini penting terutama terhadap kemungkinan pencemaran sumber air
- Pemeriksaan kualitas air pada sumber air secara periodik
b. Bangunan Pengendap Pertama
Bangunan pengendap pertama dalam pengolahan ini berfungsi untuk
mengendapkan partikel-partikel padat dari air sungai dengan cara gravitasi. Pada
proses ini tidak ada penambahan zat/bahan kimia. Untuk instalasi penjernihan air
minum, yang air bakunya cukup jernih, bak pengendap pertama tidak dibutuhkan
(Sutrisno, 2010).
c. Pembubuhan Koagulan
Koagulan adalah bahan kimia yang dibutuhkan pada air untuk membantu
proses pengendapan partikel-partikel kecil yang tak dapat mengendapkan dengan
sendirinya. Unit ini berfungsi untuk membubuhkan koagulan secara teratur sesuai
Menurut Sutrisno, 2010, alat pembubuh koagulan yang banyak dikenal
sekarang ini dapat dibedakan dari cara pembubuhannya:
- Secara gravitasi, dimana bahan/zat kimia mengalir dengan sendirinya
karena gravitasi
- Memakai pompa: pembubuhan zat kimia dengan bantuan pemompaan
Bahan/zat kimia yang dipergunakan sebagai koagulant yaitu: Aluminium
Sulfat, biasa disebut dengan tawas. Bahan ini digunakan untuk mengurangi kadar
karbonate. Bahan ini paling murah dan mudah didapat pada pasaran serta mudah
disimpan. Bentuk: serbuk, kristal, koral (Sutrisno, 2010).
d. Bangunan Pengaduk Cepat
Menurut Sutrisno, 2010, unit ini untuk meratakan bahan/zat kimia yang
ditambahkan agar dapat bercampur dengan air secara baik, sempurna dan cepat.
Cara pengadukan dengan:
- Alat mekanis: motor dengaan alat pengaduknya
- Penerjun air: dengan bantuan udara bertekanan
Yang perlu diperhatikan dalam pengadukan cepat adalah alat/cara
pengadukannya, supaya mendapat pengadukan yang sempurna dan sesuai
(Sutrisno, 2010).
e. Bangunan Pembentuk Floc
Unit ini berfungsi untuk membentuk partikel padat yang lebih besar supaya
dapat diendapkan dari hasil reaksi partikel kecil (koloidal) dengan bahan/zat
Faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk floc-floc (partikel yang lebih
besar dan bisa mengendap dengan gravitasi) adalah kekeruhan pada baku air, tipe
dari suspended solid, pH, alkalinity, bahan koagulan yang dipakai, dan lamanya
pengadukan. Pada unit ini kita usahakan supaya tak terbentuk endapan floc
(Sutrisno, 2010).
f. Bangunan Pengendapan Kedua
Menurut Sutrisno, 2010, unit ini berfungsi untuk mengendapkan floc yang
terbentuk pada unit bak pembentuk floc. Pengendapan disini dengan gaya berat
floc sendiri (gravitasi). Penanganan unit bak pengendap kedua sama dengan pada
unit bak pengendap pertama. Dengan teknologi modern terbagi menjadi:
1. Unit pengadukan cepat
2. Unit pengadukan lambat
3. Unit pengendap kedua
Unit tersebut digabungkan menjadi satu unit tersendiri yang kompak. Kita
kenal dengan sebutan Accelator Clarifier atau Pulsator Clarifier (Sutrisno, 2010).
g. Filter (Saringan)
Menurut Sutrisno, 2010, dalam proses penjernihan air minum dikenal 2
macam filter yaitu:
• Saringan pasir lambat (slow sand filter)
• Saringan pasir cepat (rapid sand filter)
Dalam bentuk bangunan saringan, dikenal dua macam yaitu: • Saringan yang bangunannya terbuka (gravity filter)
Effeuent dari bak pengendap (sedimentation basin) mengalir ke filter,
gumpalan-gumpalan dan lumpur (floc) tertahan pada lapisan atas filter. Pada saat
tertentu dimana hilangnya tekanan dari air di atas saringan terlalu tinggi, yaitu
karena adanya lapisan lumpur pada bagian atas bagian dari saringan, maka
saringan akan dicuci kembali (back wash) dengan air bertekanan dari bawah
(Sutrisno, 2010).
h. Reservoir
Air yang telah melalui filter sudah dapat dipakai untuk air minum. Air
tersebut telah bersih dan bebas dari bakteriologis dan ditampung pada bak
reservoir (tandon) untuk diteruskan pada konsumen (Sutrisno, 2010).
2.6 Proses Pengolahan Air Minum
Metode yang dipergunakan untuk pengolahan air berkaitan dengan
pencemar-pencemar yang ada dalam persediaan air tertentu. Metode yang
digunakan dapat digolongkan menurut sifat fenomena yang menghasilkan
perubahan yang diamati.
2.6.1 Metode-Metode Pengolahan Fisik a. Penyaringan
Untuk memastikan bahwa satuan-satuan utama dalam suatu instalansi
pengolahan bekerja dengan efisien, maka yang perlu dilakukan pembuangan
sampah-sampah besar yang mengambang dan terapung. Saringan kasar dari
batang-batang yang berjarak kira-kira 0,75 hingga 2 inci (20 hingga 50 mm)
b. Aerasi
Menurut Sutrisno, 2010, Aerasi adalah suatu bentuk perpindahan gas dan
dipergunakan dalam berbagai variasi operasi meliputi sebagai berikut:
- Tambahan oksigen untuk mengoksidasi besi dan mangan terlarut
- Pembuangan karbondioksida
- Pembuangan hidrogen sulfida untuk menghapuskan bau dan rasa
- Pembuangan minyak yang mudah menguap dan bahan-bahan penyebab bau
dan rasa serupa yang dikeluarkan oleh ganggang serta mikroorganisme
yang serupa
Menurut Sutrisno, 2010, Aerasi dilaksanakan dengan cara membuat air
terbuka bagi udara atau dengan memasukkan udara kedalam air. Jenis-jenis utama
alat aerasi adalah
- Aerator gaya berat misalnya kaskade air terjun atau bidang-bidang miring
- Aerator semprotan atau air mancur, di mana air disiramkan ke udara
- Penyebar suntikan, dimana udara dalam bentuk gelembung-gelembung
kecil disuntikkan kedalam zat cair
- Aerator mekanis yang meningkatkan pencampuran zat cair dan membuat
air terbuka ke atmosfer dalam bentuk butir-butir tetesan (Sutrisno, 2010).
c. Pencampuran
Bahan-bahan kimia yang dipergunakan untuk pengolahan air dapat
dimasukkan dengan mesin pemasukan larutan atau mesin pemasukan kering.
Untuk dapat menjadi efektif, bahan-bahan kimia ini haruslah tersebar dengan baik
d. Flokulasi
Bila bahan-bahan pengental kimia ditambahkan ke air yang mengandung
kekeruhan, akan terbentuk kumpulan partikel yang turun mengendap (koagulasi).
Untuk melakukan pembuangan kumpulan partikel yang pada awalnya sangat kecil
ini, pengadukan cepat harus diikuti dengan suatu jangka waktu pengadukan halus
(flokulasi) selama 20 menit hingga 30 menit. Hal ini akan menyebabkan
bertumbukannya kumpulan-kumpulan partikel kecil yang akan membentuk
partikel-partikel yang lebih besar dan jumlahnya lebih sedikit. Berhubung dengan
ukuran dan kerapatannya, partikel-partikel besar ini dapat dibuang dengan
pengendapan gaya berat (Sutrisno, 2010).
Flokulasi dapat dilaksanakan dengan mempergunakan berbagai cara,
termasuk pemutaran dayung-dayung dengan lambat, pengaliran melalui, di atas
dan di bawah kolam-kolam pengaduk dan dengan penambahan suatu gas,
biasanya udara. Input tenaga yang dibutuhkan untuk mencapai flokulasi
berbeda-beda dari kira-kira 1 hingga 2 hp per juta gallon (0,2 hingga 0,4 kw/103 m3)
kapasitas tangki flokulator (Sutrisno, 2010).
e. Pengendapan
Laju pengendapan suatu partikel didalam air tergantung pada kekentalan
dan kerapatan air maupun ukuran, bentuk dan berat jenis partikel yang
bersangkutan. Air hangat kurang rapat, sehingga partikel akan mengendap lebih
cepat dari pada di dalam air yang dingin. Partikel-partikel anorganik terapung
yang terdapat di dalam air mempunyai berat jenis yang berkisar dari 2,65 untuk
lumpur yang terkumpul. Kumpulan-kumpulan kimiawi mempunyai kisaran berat
jenis yang serupa, tergantung pada jumlah kandungan air dalam kumpulan itu
(Sutrisno, 2010).
Kecepatan mengendap partikel-partikel bulat yang terlepas di air tenang
pada suhu 68˚F (20˚C). Kecepatan mengendap di dalam suatu kolam pengendapan
akan jauh lebih kecil, karena partikel-partikelnya tidak bulat, adanya perpindahan
zat cair ke atas akibat pengendapan partikel-partikel lain serta adanya arus
konveksi. Pemurnian air dengan cara pengendapan dimaksudkan untuk
menciptakan suatu kondisi sedemikian rupa, sehingga bahan-bahan terapung di
dalam air dapat diendapkan ke luar. Kolam pengendapan yang direncanakan
dengan baik akan menghilangkan 50 hingga 80 persen bahan padat terapung yang
ada di dalam air (Sutrisno, 2010).
f. Flokulasi dan pengendapan digabungkan
Bila mutu air tidak bervariasi besar dan laju aliran cukup seragam, maka
tangki gabungan untuk flokulasi dan pengendapan telah dipergunakan dengan
berhasil. Flokulasi dan pengendapan dilaksanakan dalam suatu tangki tunggal
yang bersekat pembagi (Sutrisno, 2010).
g. Filtrasi
Filter yang biasa terdiri dari selapis pasir atau pasir dan tumbukan batu bara
yang ditunjang di atas suatu tumpukan kerikil. Suatu lapisan pasir setebal 24
hingga 30 inci (60 hingga 75 cm) dengan ukuran butir yang seragam (bergaris
tengah 0,35 hingga 0,4 5 mm) memberikan hasil yang baik. Pasir itu biasanya
cm) yang butir-butirnya tersusun menurut besarnya. Suatu lapisan batubara
antrasit (batu bara yang keras dan mengkilat) kadang-kadang dipergunakan di
dalam filter (Sutrisno, 2010).
2.6.2 Metode-Metode Pengolahan Kimiawi
Koagulasi dan disinfeksi adalah merupakan proses yang paling umum
dipergunakan dalam pengolahan air. Pelembutan presipitasi, pertukaran ion,
adsorpsi dan oksidasi kimiawi dipergunakan bila kondisi setempat menuntut
demikian (Sutrisno, 2010).
a. Koagulasi
Bila bahan-bahan padat terapung di dalam air ukurannya halus atau
koloidal, sering dipergunakan bahan-bahan kimia untuk menghilangkan
benda-benda terapung dengan lebih sempurna. Koagulan bereaksi dengan air dan
partikel-partikel yang membuat keruh untuk membuat endapan flokulan. Selama
flokulasi masing-masing partikel kumpulan diubah menjadi partikel-partikel yang
lebih besar pada waktu bertumbukan satu sama lain. Partikel-partikel yang lebih
besar mempunyai kerapatan yang cukup untuk memungkinkan pembuangannya
dengan cara pengendapan gravitasi. Koagulan yang paling dikenal adalah alum
Al2(SO4)3.18H2O yang bereaksi dengan alkalinitas di dalam air untuk membentuk
kumpulan alumunium hidroksida, sesuai dengan persamaan sebagai berikut:
Al2(SO4)3. 18H20 + 3Ca(HCO3)2 → 3CaSO4 + 2Al(OH)3 + 6CO2 +18H2O
Bila air tidak mengandung alkalinitas yang diperlukan, maka mungkin perlu
ditambahkan kapur (CaO) atau abu soda (Na2CO3) disamping alum untuk
ditambahkan ke air untuk menjadi inti bagi pembentukan kumpulan. Dosis alum
yang biasa adalah 10 hingga 40 mg/l (kira-kira 75 hingga 300 lb per juta gallon).
Jumlah bahan kimia pelengkap yang digunakan tergantung pada sifat air. Ferrous
sulfat (FeSO4) dan ferric klorida (FeCl3) juga dipergunakan sebagai koagulan.
Bahan ini membentuk endapan hidroksida besi. Garam ferrous membutuhkan
kapur sebagai bahan kimia pelengkap, kalau tidak garam ferrous harus diubah ke
dalam bentuk ferric dengan menambahkan klorin (Sutrisno, 2010).
b. Disinfeksi
Lebih dari 50 persen patogen di dalam air akan mati dalam waktu 2 hari dan
90 persen akan mati pada akhir 1 minggu. Klorin telah terbukti merupakan
disinfeksi yang ideal. Bila dimasukkan ke dalam air akan mempunyai pengaruh
yang segera dan membinasakan kebanyakan makhluk mikroskopis (Sutrisno,
2010).
Dua jenis reaksi akan terjadi bila klorin dimasukkan ke dalam air, yaitu
hidrolisis dan ionisasi. Reaksi hidrolisis adalah
Cl2 + H2O → HOCl + Cl- + H+
Gas klorin asam hipoklorit
Reaksi ionisasi adalah
HOCl → OCl- + H+
Asam hipoklorit ion hipoklorit
Karena klorin dalam bentuk asam hipoklorus 40 hingga 80 kali lebih efektif
daripada ion hipoklorit, maka disinfeksi dengan klorin akan paling efektif pada
dimasukkan kedalam air melalui suatu klorinator. Klorinator kecil memasukkan
gas tersebut secara langsung ke dalam air, sedangkan klorinator besar biasanya
melarutkan gas di dalam air, kemudian mengisi larutan itu. Klorinator harus dijaga
pada suhu 70˚F (21˚C) untuk mencegah ko ndensasi gas klorin di pipa-pipa
pengisian (Sutrisno, 2010).
Secara umum, kebanyakan air akan mengalami desinfeksi cukup baik bila
residu klorin bebas sebanyak kira-kira 0,2 mg/l diperoleh setelah klorinasi selama
10 menit. Residu klorin yang lebih besar dapat menimbulkan bau yang tak enak,
sedangkan yang lebih kecil tidak dapat diandalkan. Klorin akan sangat efektif bila
pH air rendah. Bila persediaan air mengandung fenol, penambahan klorin ke air
akan mengakibatkan rasa yang kurang enak akibat pembentukan senyawa
klorofenol. Rasa ini dapat dihilangkan dengan menambahkan amoniak ke air
sebelum klorinasi. Campuran klorin dan amoniak membentuk kloramin, yang
merupakan disinfektan yang relatif mantap, walaupun tidak sefektif hipoklorit.
Kloramin tidak bereaksi dengan cepat, tetapi bekerja terus untuk waktu yang
lama. Karena itu, mutu disinfeksinya dapat berlanjut jauh ke dalam jaringan
distribusi (Sutrisno, 2010).
Klorinasi-akhir, yaitu pemakaian klorin setelah pengolahan, merupakan
metode yang umum. Klorinasi-awal, yaitu pemakaian klorin sebelum pengolahan,
akan menyempurnakan koagulasi, mengurangi beban filter dan mencegah
tumbuhnya ganggang. Klorinasi awal dan akhir sering dipergunakan
bersama-sama sehingga meninggalkan residu besar yang berlebihan (superklorinasi) sering
diikuti dengan deklorinasi yang biasanya berupa pengolahan dengan sulfur
dioksida atau dengan melewatkan air yang bersangkutan melalui suatu filter
butiran karbon yang diaktifkan (Sutrisno, 2010).
2.7 Kekeruhan pada Air
Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 492/MENKES/PER/IV/2010,
parameter fisika umumnya dapat diidentifikasi dari kondisi fisik air. Salah satu
parameter fisika adalah kekeruhan.
Air dikatakan keruh, apabila air tersebut mengandung banyak partikel bahan
yang tersuspensi sehingga memberikan warna/rupa yang berlumpur dan kotor.
Bahan-bahan yang menyebabkan kekeruhan ini meliputi: tanah liat, lumpur,
bahan-bahan organik yang tersebar secara baik dan partikel-partikel kecil yang
tersuspensi lainnya (Sutrisno, 2010).
Kekeruhan adalah efek optik yang terjadi jika sinar membentuk material
tersuspensi di dalam air. Kekeruhan air terjadi karena adanya partikel hidup atau
mati, berukuran besar atau pun berukuran kecil yang berada di dalam air,
misalnya ganggang pada air waduk, atau lumpur yang terbawa pada air tanah saat
turun hujan. Kekeruhan walaupun hanya sedikit dapat menyebabkan warna yang
lebih tua dari warna sesungguhnya. Tingkat kekeruhan dipengaruhi oleh pH air.
(Pitojo, 2002).
Nilai numerik yang menunjukkan kekeruhan didasarkan pada turut
campurnya bahan-bahan tersuspensi pada jalannya sinar melalui sampel.
tidak disenangi karena rupanya. Menurut Clair N Sawyer, dkk., kekeruhan dapat
mengurangi segi esthetika, menyulitkan dalam usaha penyaringan, dan akan
mengurangi efektivitas usaha desinfeksi (Sutrisno, 2010).
Tingkat kekeruhan bergantung pada kehalusan partikel-partikel dan
konsentrasinya. Air permukaan yang mengalami kenaikan tingkat kekeruhan
setelah terjadi hujan akan lebih sulit diolah daripada air dengan tingkat kekeruhan
yang tetap (Linsley, 1991).
2.7.1 Penyebab Kekeruhan
a. Adanya Endapan, Koloid, dan Bahan Terlarut
Endapan dan koloidal serta bahan terlarut berasal dari adanya bahan
buangan industri yang berbentuk padat. Bahan buangan industri yang berbentuk
padat kalau tidak dapat larut sempurna akan mengendap di dasar sungai dan yang
dapat larut sebagian akan menjadi koloidal. Endapan sebelum sampai di dasar
sungai akan melayang di dalam air bersama-sama dengan koloidal. Endapan dan
koloidal yang melayang di dalam air akan menghalangi masuknya sinar matahari
ke dalam lapisan air. Padahal sinar matahari sangat diperlukan oleh
mikroorganisme untuk melakukan proses fotosintesis. Karena tidak ada sinar
matahari maka proses fotosintesis tidak dapat berlangsung. Akibatnya, kehidupan
mikroorganisme menjadi terganggu (Wardhana, 2001).
Keberadaan endapan dan koloid dari limbah organik, maka mikroorganisme
dengan bantuan oksigen yang terlarut di dalam air akan melakukan degradasi
bahan organik tersebut sehingga menjadi bahan yang lebih sederhana. Banyaknya
Oxygen Demand (BOD). Adanya koloid, bahan pencemar, plankton serta
beberapa jenis mineral akan menyebabkan kekeruhan pada air. Kekeruhan air
dapat dipisahkan agar lebih jernih seperti dengan proses filtrasi (Sunu, 2001).
b. Padatan Tersuspensi Total (TSS)
Padatan tersuspensi adalah padatan yang menyebabkan kekeruhan air, tidak
terlarut, dan tidak dapat mengendap langsung. Padatan tersuspensi terdiri dari
partikel-partikel yang ukuran maupun beratnya lebih kecil dari pada sedimen,
seperti bahan-bahan organik tertentu, tanah liat, dan lain-lain. Misalnya air
permukaan mengandung tanah liat dalam bentuk suspensi (Sunu, 2001).
Pengukuran langsung padatan tersuspensi total (TSS) sering membutuhkan
waktu cukup lama. TSS ialah jumlah bobot bahan yang tersuspensi dalam suatu
volume air tertentu, yang biasanya diberikan dalam miligram per liter atau ppm.
Mengukur kekeruhan/ turbiditas air dilakukan untuk dapat memperkirakan TSS
dalam suatu contoh air. Turbiditas diukur dengan turbidiuster yang mengukur
kemampuan cahaya untuk melewati suatu contoh air (Sunu, 2001).
Partikel yang tersuspensi tersebut akan menyebar cahaya yang datang,
sehingga menurunkan intensitas cahaya yang disebarkan. Padatan yang
tersuspensi dalam air umumnya terdiri dari fitoplankton, zooplankton, kotoran
hewan, sisa tanaman dan hewan, kotoran manusia, dan limbah industri (Sunu,
2001).
Kejernihan dan warna air akan dipengaruhi oleh padatan terlarut dan
tersuspensi. Kejernihan air yang rendah menunjukkan produktivitas tinggi, karena
tersuspensi tinggi, maka sinar matahari tidak dapat menembus ke dalam air
dengan sempurna (Sunu, 2001).
2.7.2 Deteksi Kekeruhan
Tujuan deteksi kekeruhan adalah untuk mengetahui macam partikel
penyebab pencemar air yang dideteksi. Deteksi kekeruhan (turbidity) pada air
minum dapat dilakukan dengan alat turbidimeter dan dinyatakan dengan satuan
NTU (Nephelometric Turbidity Unit). Untuk melihat macam zat yang terlarut
penyebab kekeruhan tersebut digunakan alat elektrolyzer (Pitojo, 2002).
Kekeruhan dinyatakan dalam satuan unit turbiditas, yang setara dengan 1
mg/liter SiO2. Peralatan yang pertama kali digunakan untuk mengukur turbiditas
adalah Jackson Candler Turbidimeter, yang dikalibrasi dengan menggunakan
silika. Kemudian Jackson Candler Turbidimeter dijadikan sebagai alat baku atau
standar bagi pengukuran kekeruhan. Satu unit Jackson Candler Turbidimeter
dinyatakan dalam satuan 1 JTU. Pengukuran kekeruhan dengan menggunakan
Jackson Candler Turbidimeter bersifat visual, yaitu membandingkan air sampel
dengan air standar (Effendi, 2003).
Selain diukur dengan menggunakan Jackson Candler Turbidimeter,
kekeruhan sering diukur dengan metode Nephelometric. Pada metode ini, sumber
cahaya dilewatkan pada sampel dan intensitas cahaya yang dipantulkan oleh
bahan-bahan penyebab kekeruhan diukur dengan menggunakan suspensi polimer
formazin sebagai larutan standar. Satuan kekeruhan yang diukur dengan metode
sebenarnya tidak dapat saling mengonversi, akan tetapi Sawyer dan McCarty
(1978)mengemukakan bahwa 40 NTU setara dengan 40 JTU (Effendi, 2003).
Kekeruhan dalam air minum/air bersih tidak boleh lebih dari 5 NTU.
Penurunan kekeruhan ini sangat diperlukan karena selain ditinjau dari segi
estetika yang kurang baik juga proses desinfeksi untuk air keruh sangat sukar, hal
ini disebabkan karena penyerapan beberapa koloid dapat melindungi organisme
BAB III
METODE PENGUJIAN
3.1 Alat dan Bahan 3.1.1 Alat
- Turbidimeter
- Kuvet
3.1.2 Bahan
- Sampel air
3.2 Prosedur
- Dihidupkan Turbidimeter dengan menekan switch dibelakang alat, layar
akan menunjukkan 2100, kemudian angka 0,0045
- Diisi kuvet dengan sampel air sampai tanda batas
- Dibersihkan kuvet sampel dengan tissue sampai kering
- Diletakkan kuvet sampel ke dalam tempat sampel sel, tutup penutupnya
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil
Pemeriksaan kekeruhan merupakan parameter fisik dari air. Pemeriksaan ini
dilakukan setiap jamnya, dengan memasukkan sampel air pada kuvet kemudian
diletakkan pada dudukan kuvet dari alat turbidimeter. Data pemeriksaan
kekeruhan pada tanggal 25 februari 2013 dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Hasil Pemeriksaan Kekeruhan Air Reservoir
4.2 Pembahasan
Air reservoir merupakan air baku yang telah mengalami serangkaian proses
pengolahan. Pada PDAM Tirtanadi IPA Sunggal terdapat 2 buah bak
penampungan air reservoir yaitu reservoir 1 dan reservoir 2. Meskipun air
reservoir tersebut terbagi dalam dua bak penampungan namun kualitasnya
tetaplah sama. Berdasarkan pemeriksaan nilai kekeruhan pada tanggal 25 Februari
2013 pukul 08.00-16.00 WIB terlihat perbedaan yang signifikan antara reservoir 1
dan reservoir 2. Akan tetapi hal tersebut bukan disebabkan oleh adanya perbedaan
proses pengolahannya melainkan mungkin disebabkan oleh kondisi bak
penampungan maupun pipa penyalurannya. Perbedaan nilai kekeruhan pada kedua
air reservoir masih dapat ditoleransi karena nilainya masih berada dibawah 2
NTU. Nilai kekeruhan dari kedua air reservoir telah memenuhi persyaratan
internal yang diterapkan pada Instalansi Pengolahan Air Sunggal.
Semakin rendah nilai kekeruhan menandakan bahwa kualitas air semakin
baik. Hal tersebut menandakan bahwa air bersih yang telah diperoleh dari
Instalansi Pengolahan Air Sunggal layak untuk didistribusikan kepada masyarakat
guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Kekeruhan dalam air minum tidak boleh lebih dari 5 NTU. Penurunan
kekeruhan ini sangat diperlukan karena selain ditinjau dari segi estetika yang
kurang baik juga proses desinfeksi untuk air keruh sangat sukar, hal ini
disebabkan karena penyerapan beberapa koloid dapat melindungi organisme dari
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
- Nilai kekeruhan air reservoir (reservoir 1 dan reservoir 2) setelah
mengalami proses pengolahan adalah lebih kecil dari 2 NTU.
- Kekeruhan pada air reservoir (reservoir 1 dan reservoir 2) telah memenuhi
persyaratan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan RI No.
492/MENKES/PER/IV/2010 dan layak untuk didistribusikan pada
masyarakat.
5.2 Saran
Apabila pada saat melakukan pengukuran kekeruhan nilainya terlalu tinggi,
sebaiknya dilakukan pengukuran ulang 15 menit kemudian, karena bisa saja ada
DAFTAR PUSTAKA
Chandra, B. (2006). Pengantar Kesehatan Lingkungan. Jakarta: EGC. Halaman 39.
Effendi, H. (2003). Telaah Kualitas Air. Yogyakarta: Kanisius. Halaman 59-61.
Joko, T. (2010). Unit Produksi dalam Sistem Penyediaan Air Minum. Yogyakarta: Graha Ilmu. Halaman 4-22.
Linsley, R.K. (1991). Teknik Sumber Daya Air. Jakarta: Erlangga. Halaman 117-134.
Mulia, R. (2005). Kesehatan Lingkungan. Yogyakarta: Graha Ilmu. Halaman 59-63.
Pitojo, S., dan Eling, P. (2002). Deteksi Pencemar Air Minum. Semarang: Aneka Ilmu. Halaman 37-65.
Sunu, P. (2001). Melindungi Lingkungan Dengan Menerapkam ISO 14001.
Jakarta: PT. Grasindo. Halaman 107-142.
Sutrisno, T. (2010). Teknologi Penyediaan Air Bersih. Jakarta: Rineka Cipta. Halaman 52-60.
Lampiran 1. Alat yang Digunakan pada Pemeriksaan Kekeruhan
Gambar 1. Alat Turbidimeter
Lampiran 2. Proses Pengolahan Air pada IPA Sunggal
Lampiran 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 492/MEN KES/PER/IV/2010