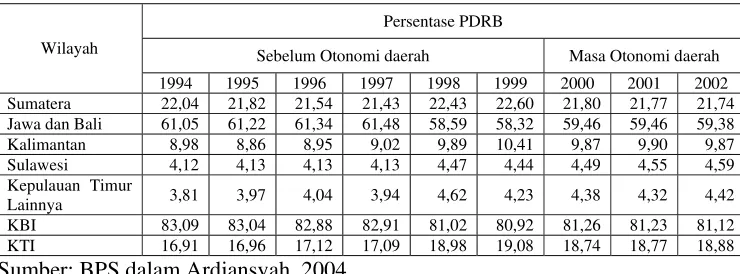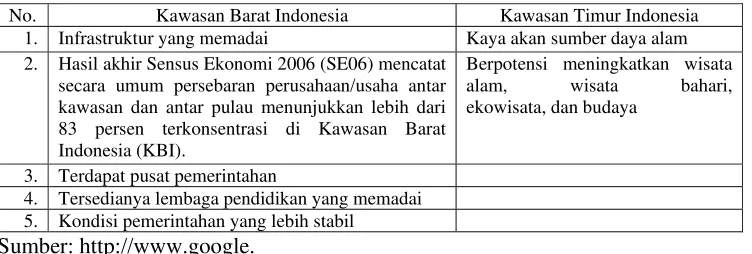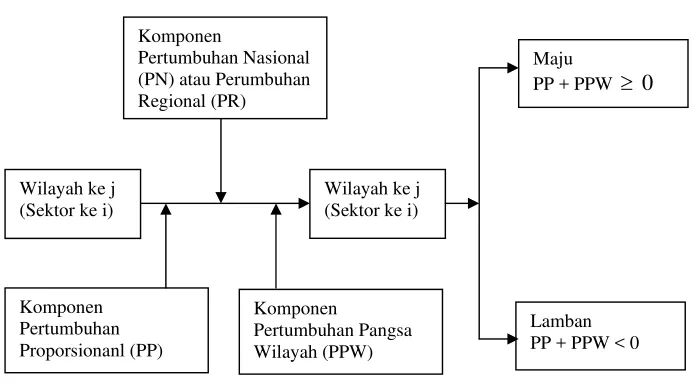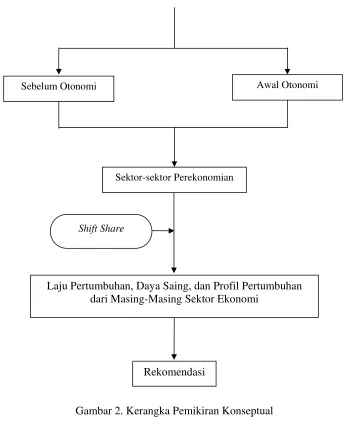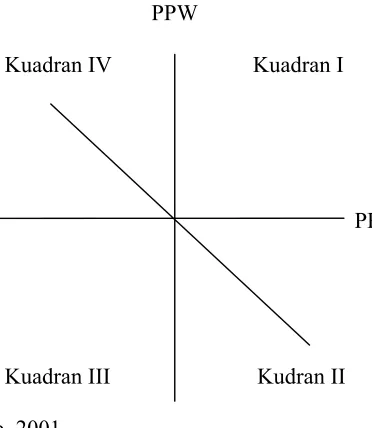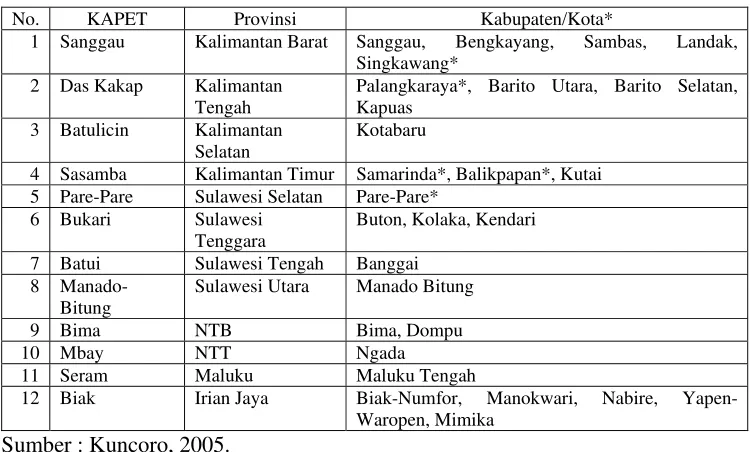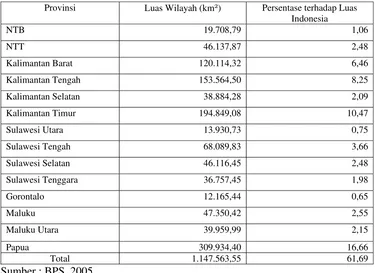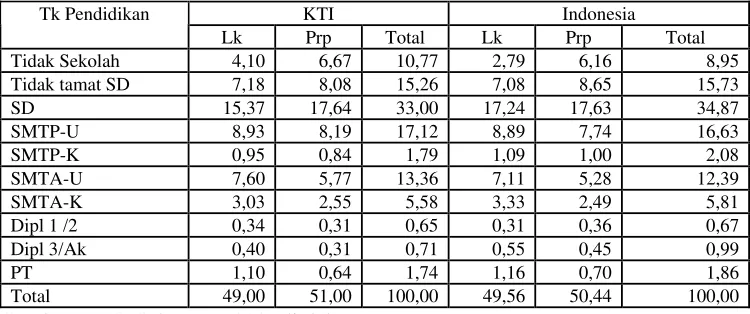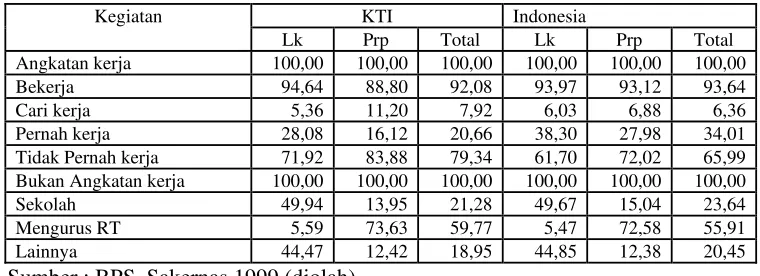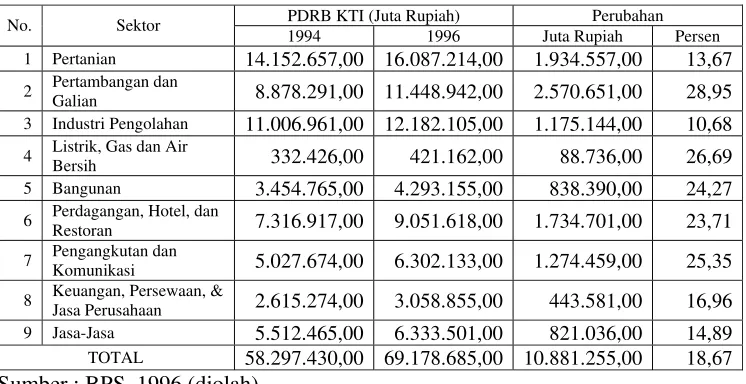Oleh
TIRANI SAKUNTALA DEVI H14103030
DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
RINGKASAN
TIRANI SAKUNTALA DEVI. Analisis Pertumbuhan Sektor-Sektor Perekonomian Kawasan Timur Indonesia Sebelum dan Pada Awal Otonomi Daerah (dibimbing oleh Fifi Diana Thamrin).
Pembangunan yang tidak seimbang antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) mengakibatkan ketimpangan. Ketimpangan antara KBI dan KTI dapat dilihat dari besarnya investasi di kedua kawasan tersebut. Ketimpangan juga bisa dilihat dari tingkat kemiskinan. Dari tahun 1999-2003 angka kemiskinan yang tertinggi ada di KTI. Selain itu hampir di semua daerah di KTI dapat dikatakan tidak memiliki infrastruktur yang memadai, sehingga menyebabkan pembangunan KTI sangat tertinggal. Padahal, untuk dapat menghasilkan produktivitas modal yang optimal kebutuhan akan infrastruktur, seperti jalan raya, pelabuhan laut dan udara, sarana telekomunikasi dan lain-lain, merupakan kebutuhan yang mutlak. Kondisi tersebut masih diperparah lagi dengan ”masalah sosial dan keamanan” yang selalu dipertanyakan oleh setiap investor yang akan menanamkan modalnya ke KTI. Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) seluruh Propinsi di KTI lebih rendah jika dibandingkan PDRB seluruh Propinsi di KBI.
Kebijakan otonomi daerah yang ditetapkan pada tahun 1999 menimbulkan dampak yang menguntungkan bagi daerah yang mampu melaksanakannya. Sejalan itu, KTI ikut serta mengimplikasikan kebijakan otonomi daerah tersebut, sehingga provinsi-provinsi di KTI memiliki wewenang pemerintahan dan menentukan sendiri kemajuan pembangunan. Kebijakan otonomi daerah yang dikeluarkan pada tahun 1999 mulai dilaksanakan di KTI pada tahun 2000 dan hal ini berpengaruh terhadap pemerintahan dibeberapa provinsi di KTI.
Permasalahan yang menjadi fokus penelitian adalah adanya perubahan atau selisih PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing sektor perekonomian di KTI dan perubahan PDB nasional dalam kurun waktu 9 tahun terutama sejak diberlakukannya undang-undang otonomi daerah di KTI pada tahun 2000. pada kurun waktu 9 tahun tersebut PDRB KTI meningkat dan yang menjadi pertanyaan adalah apakah peningkatan tersebut termasuk dalam pertumbuhan progresif
(maju) atau tergolong dalam pertumbuhan yang lambat.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pertumbuhan sektor-sektor ekonomi di KTI sebelum dan pada awal otonomi daerah. Hal yang akan dilihat adalah laju pertumbuhan, daya saing, profil pertumbuhan dan pergeseran bersih dari masing-masing sektor perekonomian di KTI.
otonomi daerah yang menggambarkan kondisi ekonomi pada saat krisis, dan tahun 2000-2002 periode awal otonomi daerah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kurun waktu 1994-1996 sektor listrik, gas dan air bersih merupakan sektor yang memiliki laju pertumbuhan paling cepat dan sektor yang mempunyai laju pertumbuhan paling lambat adalah sektor jasa-jasa. Sektor perekonomian yang mempunyai daya saing paling tinggi pada kurun waktu 1994-1996 adalah sektor pertambangan dan galian dan sektor yang sangat tidak bisa bersaing adalah sektor industri pengolahan. Pada tahun 1997-1999 sektor listrik, gas dan air bersih tetap mempunyai laju pertumbuhan yang tertinggi dan sektor bangunan merupakan sektor dengan laju pertumbuhan paling lambat. Sektor pertambangan dan galian tetap menempati posisi pertama sektor yang berdaya saing dan terdapat sektor pertanian yang tidak mempunyai daya saing dengan wilayah lain pada kurun waktu 1997-1999.
Sektor pengangkutan dan komunikasi mempunyai laju pertumbuhan yang tercepat pada kurun waktu 2000-2002 dan sektor pertambangan dan galian merupakan sektor dengan laju pertumbuhan lambat. Pada tahun 2000-2002 sektor pertambangan dan galian tetap menjadi sektor dengan daya saing tertinggi, sedangkan sektor yang keuangan, persewaan dan jasa perusahaan merupakan sektor yang sangat tidak bisa bersaing dengan sektor wilayah lain.
Berdasarkan hasil penelitian, secara keseluruhan pada masa sebelum dan awal otonomi daerah pertumbuhan ekonomi KTI termasuk dalam pertumbuhan yang progresif (maju) namun apabila dilihat dari masing-masing sektor masih terdapat sektor yang mempunyai pertumbuhan lambat. Pada tahun 1994-1996 sektor yang tergolong dalam pertumbuhan yang lambat antara lain sektor pertanian, sektor industri pengolahan, dan sektor jasa-jasa. Pada tahun 1997-1999 sektor yang tergolong dalam sektor dengan pertumbuhan lambat yaitu sektor bangunan dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Pada tahun 2000-2002 sektor yang tergolong dalam sektor dengan pertumbuhan lambat yaitu sektor industri pengolahan dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.
ANALISIS PERTUMBUHAN SEKTOR-SEKTOR
PEREKONOMIAN KAWASAN TIMUR INDONESIA SEBELUM
DAN PADA AWAL OTONOMI DAERAH
Oleh
TIRANI SAKUNTALA DEVI H14103030
Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi
DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang disusun oleh,
Nama : Tirani Sakuntala Devi
Nomor Registrasi Pokok : H14103030
Program Studi : Ilmu Ekonomi
Judul Skripsi : Analisis Pertumbuhan Sektor-Sektor
Perekonomian Kawasan Timur Indonesia Sebelum
dan Pada Awal Otonomi Daerah
dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada
Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian
Bogor.
Menyetujui, Dosen Pembimbing
Fifi Diana Thamrin, M. Si. NIP 132 321 453
Mengetahui,
Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Dr. Ir. Rina Oktaviani, M. S. NIP 131 846 872
PERNYATAAN
DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI ADALAH
BENAR-BENAR HASIL KARYA SAYA SENDIRI YANG BELUM PERNAH
DIGUNAKAN SEBAGAI SKRIPSI ATAU KARYA ILMIAH PADA
PERGURUAN TINGGI ATAU LEMBAGA MANAPUN.
Bogor, Mei 2007
Mukti Rahardjo dan Sri Murtini. Penulis menamatkan pendidikan dasar di SDN
KAYEN 5 kemudian melanjutkan ke SLTP Negeri 3 Pati pada tahun 1997 dan
lulus SLTP pada tahun 2000. Setelah lulus dari SLTP penulis melanjutkan
pendidikan di SLTA Negeri 1 Pati.
Pada tahun 2003 penulis diterima menjadi mahasiswa Institut Pertanian
Bogor melalui jalur USMI (Undangan Seleksi Masuk IPB) dan diterima sebagai
mahasiswa Program Studi Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan
karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan
judul ”Analisis Pertumbuhan Sektor-Sektor Perekonomian Kawasan Timur Indonesia Sebelum dan Pada Awal Otonomi Daerah ”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen
Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.
Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Fifi
Diana Thamrin yang telah memberikan bimbingan baik secara teknis maupun
teoritis dalam proses pembuatan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis
tujukan kepada Ibu Wiwiek Rindayati yang telah menguji hasil karya ini. Semua
saran dan kritikan beliau merupakan hal yang sangat berharga dalam
penyempurnaan skripsi ini. Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih
kepada Ibu Widyastutik terutama atas perbaikan tata cara penulisan skripsi ini.
Penulis juga sangat terbantu oleh kritik dan saran dari para peserta seminar
hasil penelitian skripsi ini. Penulis juga berterima kasih kepada pihak-pihak yang
telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan
satu-persatu.
Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada orang tua penulis, Bapak Mukti Rahardjo dan Ibu Sri Murtini, keluarga di
Cibinong, teman kost bawah, teman KKP, dan teman satu pembimbing skripsi.
Terima kasih atas doa, dukungan dan nasehat yang telah diberikan.
Bogor, Mei 2007
Tirani Sakuntala Devi
DAFTAR GAMBAR ... xiii
DAFTAR LAMPIRAN...xiv
I. PENDAHULUAN ...1
1.1. Latar Belakang ...1
1.2. Perumusan Masalah ...7
1.3. Tujuan ...9
1.4. Kegunaan Penelitian...10
II. TINJAUAN PUSTAKa ...11
2.1. Konsep Otonomi Daerah...11
2.2. Teori Pertumbuhan Rostow ...16
2.3. Konsep Wilayah ...17
2.4. Kerangka Teoritis...20
2.4.1. Analisis Shift Share...20
2.4.2. Keterbatasan-Keterbatasan Analisis Shift Share...23
2.5. Kerangka Pemikiran Konseptual...24
III. METODE PENELITIAN...27
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian ...27
3.2. Jenis dan Sumber Data ...27
3.3. Metode Analisis Shift Share...27
3.3.1. Analisis PDRB KTI dan PDB Indonesia ...28
3.3.2. Rasio PDRB KTI dan PDB Indonesia (Nilai Ra, Ri, dan ri) ...30
3.3.3. Analisis Komponen Pertumbuhan Wilayah ...32
3.3.4. Analisis Profil Pertumbuhan PDRB dan Pergeseran Bersih ...34
3.4. Definisi Operasional...38
3.4.1. Produk Domestik Regional Bruto ...38
3.4.2. Tahun Dasar Analisis dan Tahun Akhir Analisis...39
IV. GAMBARAN UMUM ...41
4.1. Pembangunan Kawasan Timur Indonesia...41
4.2. Ketertinggalan Kawasan Timur Indonesia...44
4.3. Kualitas Sumber Daya Manusia...46
4.3.1. Tingkat Pendidikan ...46
4.3.2. Tingkat Kesehatan...48
4.3.3. Ketenagakerjaan...50
4.4. Perkembangan PDRB di Kawasan Timur Indonesia ...53
V. HASIL DAN PEMBAHASAN...56
5.1. Sektor-Sektor Perekonomian di Kawasan Timur Indonesia Sebelum Otonomi Daerah Tahun 1994-1996 ...56
5.1.1. Analisis PDRB Kawasan Timur Indonesia Tahun 1994-1996 ...56
5.1.2. Rasio PDRB Kawasan Timur Indonesia dan PDB Indonesia (Ra, Ri, dan ri) Tahun 1994-1996...57
5.1.3. Analisis Komponen PertumbuhanWilayah Tahun 1994-1996 ...59
5.1.4. Analisis Profil Pertumbuhan PDRB Kawasan Timur Indonesia dan Pergeseran Bersih Tahun 1994-1996 ...64
5.2. Sektor-Sektor Perekonomian di Kawasan Timur Indonesia Sebelum Otonomi Daerah Tahun 1997-1999 ...68
5.2.1. Analisis PDRB Kawasan Timur Indonesia Tahun 1997-1999 ...68
5.2.2. Rasio PDRB Kawasan Timur Indonesia dan PDB Indonesia (Ra, Ri, dan ri) Tahun 1997-1999...69
5.2.3. Analisis Komponen PertumbuhanWilayah Tahun 1994-1996 ...70
5.2.4. Analisis Profil Pertumbuhan PDRB Kawasan Timur Indonesia dan Pergeseran Bersih Tahun 1997-1999 ...75
5.3. Sektor-Sektor Perekonomian di Kawasan Timur Indonesia Sebelum Otonomi Daerah Tahun 2000-2002 ...78
5.3.1. Analisis PDRB Kawasan Timur Indonesia Tahun 2000-2002 ...78
5.3.2. Rasio PDRB Kawasan Timur Indonesia dan PDB Indonesia (Ra, Ri, dan ri) Tahun 2000-2002...79
5.3.3. Analisis Komponen PertumbuhanWilayah Tahun 2000-2002 ...80
5.3.4. Analisis Profil Pertumbuhan PDRB Kawasan Timur Indonesia dan Pergeseran Bersih Tahun 2000-2002 ...84
Oleh
TIRANI SAKUNTALA DEVI H14103030
DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
RINGKASAN
TIRANI SAKUNTALA DEVI. Analisis Pertumbuhan Sektor-Sektor Perekonomian Kawasan Timur Indonesia Sebelum dan Pada Awal Otonomi Daerah (dibimbing oleh Fifi Diana Thamrin).
Pembangunan yang tidak seimbang antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) mengakibatkan ketimpangan. Ketimpangan antara KBI dan KTI dapat dilihat dari besarnya investasi di kedua kawasan tersebut. Ketimpangan juga bisa dilihat dari tingkat kemiskinan. Dari tahun 1999-2003 angka kemiskinan yang tertinggi ada di KTI. Selain itu hampir di semua daerah di KTI dapat dikatakan tidak memiliki infrastruktur yang memadai, sehingga menyebabkan pembangunan KTI sangat tertinggal. Padahal, untuk dapat menghasilkan produktivitas modal yang optimal kebutuhan akan infrastruktur, seperti jalan raya, pelabuhan laut dan udara, sarana telekomunikasi dan lain-lain, merupakan kebutuhan yang mutlak. Kondisi tersebut masih diperparah lagi dengan ”masalah sosial dan keamanan” yang selalu dipertanyakan oleh setiap investor yang akan menanamkan modalnya ke KTI. Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) seluruh Propinsi di KTI lebih rendah jika dibandingkan PDRB seluruh Propinsi di KBI.
Kebijakan otonomi daerah yang ditetapkan pada tahun 1999 menimbulkan dampak yang menguntungkan bagi daerah yang mampu melaksanakannya. Sejalan itu, KTI ikut serta mengimplikasikan kebijakan otonomi daerah tersebut, sehingga provinsi-provinsi di KTI memiliki wewenang pemerintahan dan menentukan sendiri kemajuan pembangunan. Kebijakan otonomi daerah yang dikeluarkan pada tahun 1999 mulai dilaksanakan di KTI pada tahun 2000 dan hal ini berpengaruh terhadap pemerintahan dibeberapa provinsi di KTI.
Permasalahan yang menjadi fokus penelitian adalah adanya perubahan atau selisih PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing sektor perekonomian di KTI dan perubahan PDB nasional dalam kurun waktu 9 tahun terutama sejak diberlakukannya undang-undang otonomi daerah di KTI pada tahun 2000. pada kurun waktu 9 tahun tersebut PDRB KTI meningkat dan yang menjadi pertanyaan adalah apakah peningkatan tersebut termasuk dalam pertumbuhan progresif
(maju) atau tergolong dalam pertumbuhan yang lambat.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pertumbuhan sektor-sektor ekonomi di KTI sebelum dan pada awal otonomi daerah. Hal yang akan dilihat adalah laju pertumbuhan, daya saing, profil pertumbuhan dan pergeseran bersih dari masing-masing sektor perekonomian di KTI.
otonomi daerah yang menggambarkan kondisi ekonomi pada saat krisis, dan tahun 2000-2002 periode awal otonomi daerah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kurun waktu 1994-1996 sektor listrik, gas dan air bersih merupakan sektor yang memiliki laju pertumbuhan paling cepat dan sektor yang mempunyai laju pertumbuhan paling lambat adalah sektor jasa-jasa. Sektor perekonomian yang mempunyai daya saing paling tinggi pada kurun waktu 1994-1996 adalah sektor pertambangan dan galian dan sektor yang sangat tidak bisa bersaing adalah sektor industri pengolahan. Pada tahun 1997-1999 sektor listrik, gas dan air bersih tetap mempunyai laju pertumbuhan yang tertinggi dan sektor bangunan merupakan sektor dengan laju pertumbuhan paling lambat. Sektor pertambangan dan galian tetap menempati posisi pertama sektor yang berdaya saing dan terdapat sektor pertanian yang tidak mempunyai daya saing dengan wilayah lain pada kurun waktu 1997-1999.
Sektor pengangkutan dan komunikasi mempunyai laju pertumbuhan yang tercepat pada kurun waktu 2000-2002 dan sektor pertambangan dan galian merupakan sektor dengan laju pertumbuhan lambat. Pada tahun 2000-2002 sektor pertambangan dan galian tetap menjadi sektor dengan daya saing tertinggi, sedangkan sektor yang keuangan, persewaan dan jasa perusahaan merupakan sektor yang sangat tidak bisa bersaing dengan sektor wilayah lain.
Berdasarkan hasil penelitian, secara keseluruhan pada masa sebelum dan awal otonomi daerah pertumbuhan ekonomi KTI termasuk dalam pertumbuhan yang progresif (maju) namun apabila dilihat dari masing-masing sektor masih terdapat sektor yang mempunyai pertumbuhan lambat. Pada tahun 1994-1996 sektor yang tergolong dalam pertumbuhan yang lambat antara lain sektor pertanian, sektor industri pengolahan, dan sektor jasa-jasa. Pada tahun 1997-1999 sektor yang tergolong dalam sektor dengan pertumbuhan lambat yaitu sektor bangunan dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Pada tahun 2000-2002 sektor yang tergolong dalam sektor dengan pertumbuhan lambat yaitu sektor industri pengolahan dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.
ANALISIS PERTUMBUHAN SEKTOR-SEKTOR
PEREKONOMIAN KAWASAN TIMUR INDONESIA SEBELUM
DAN PADA AWAL OTONOMI DAERAH
Oleh
TIRANI SAKUNTALA DEVI H14103030
Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi
DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang disusun oleh,
Nama : Tirani Sakuntala Devi
Nomor Registrasi Pokok : H14103030
Program Studi : Ilmu Ekonomi
Judul Skripsi : Analisis Pertumbuhan Sektor-Sektor
Perekonomian Kawasan Timur Indonesia Sebelum
dan Pada Awal Otonomi Daerah
dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada
Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian
Bogor.
Menyetujui, Dosen Pembimbing
Fifi Diana Thamrin, M. Si. NIP 132 321 453
Mengetahui,
Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Dr. Ir. Rina Oktaviani, M. S. NIP 131 846 872
PERNYATAAN
DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI ADALAH
BENAR-BENAR HASIL KARYA SAYA SENDIRI YANG BELUM PERNAH
DIGUNAKAN SEBAGAI SKRIPSI ATAU KARYA ILMIAH PADA
PERGURUAN TINGGI ATAU LEMBAGA MANAPUN.
Bogor, Mei 2007
Mukti Rahardjo dan Sri Murtini. Penulis menamatkan pendidikan dasar di SDN
KAYEN 5 kemudian melanjutkan ke SLTP Negeri 3 Pati pada tahun 1997 dan
lulus SLTP pada tahun 2000. Setelah lulus dari SLTP penulis melanjutkan
pendidikan di SLTA Negeri 1 Pati.
Pada tahun 2003 penulis diterima menjadi mahasiswa Institut Pertanian
Bogor melalui jalur USMI (Undangan Seleksi Masuk IPB) dan diterima sebagai
mahasiswa Program Studi Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan
karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan
judul ”Analisis Pertumbuhan Sektor-Sektor Perekonomian Kawasan Timur Indonesia Sebelum dan Pada Awal Otonomi Daerah ”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen
Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.
Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Fifi
Diana Thamrin yang telah memberikan bimbingan baik secara teknis maupun
teoritis dalam proses pembuatan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis
tujukan kepada Ibu Wiwiek Rindayati yang telah menguji hasil karya ini. Semua
saran dan kritikan beliau merupakan hal yang sangat berharga dalam
penyempurnaan skripsi ini. Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih
kepada Ibu Widyastutik terutama atas perbaikan tata cara penulisan skripsi ini.
Penulis juga sangat terbantu oleh kritik dan saran dari para peserta seminar
hasil penelitian skripsi ini. Penulis juga berterima kasih kepada pihak-pihak yang
telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan
satu-persatu.
Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada orang tua penulis, Bapak Mukti Rahardjo dan Ibu Sri Murtini, keluarga di
Cibinong, teman kost bawah, teman KKP, dan teman satu pembimbing skripsi.
Terima kasih atas doa, dukungan dan nasehat yang telah diberikan.
Bogor, Mei 2007
Tirani Sakuntala Devi
DAFTAR GAMBAR ... xiii
DAFTAR LAMPIRAN...xiv
I. PENDAHULUAN ...1
1.1. Latar Belakang ...1
1.2. Perumusan Masalah ...7
1.3. Tujuan ...9
1.4. Kegunaan Penelitian...10
II. TINJAUAN PUSTAKa ...11
2.1. Konsep Otonomi Daerah...11
2.2. Teori Pertumbuhan Rostow ...16
2.3. Konsep Wilayah ...17
2.4. Kerangka Teoritis...20
2.4.1. Analisis Shift Share...20
2.4.2. Keterbatasan-Keterbatasan Analisis Shift Share...23
2.5. Kerangka Pemikiran Konseptual...24
III. METODE PENELITIAN...27
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian ...27
3.2. Jenis dan Sumber Data ...27
3.3. Metode Analisis Shift Share...27
3.3.1. Analisis PDRB KTI dan PDB Indonesia ...28
3.3.2. Rasio PDRB KTI dan PDB Indonesia (Nilai Ra, Ri, dan ri) ...30
3.3.3. Analisis Komponen Pertumbuhan Wilayah ...32
3.3.4. Analisis Profil Pertumbuhan PDRB dan Pergeseran Bersih ...34
3.4. Definisi Operasional...38
3.4.1. Produk Domestik Regional Bruto ...38
3.4.2. Tahun Dasar Analisis dan Tahun Akhir Analisis...39
IV. GAMBARAN UMUM ...41
4.1. Pembangunan Kawasan Timur Indonesia...41
4.2. Ketertinggalan Kawasan Timur Indonesia...44
4.3. Kualitas Sumber Daya Manusia...46
4.3.1. Tingkat Pendidikan ...46
4.3.2. Tingkat Kesehatan...48
4.3.3. Ketenagakerjaan...50
4.4. Perkembangan PDRB di Kawasan Timur Indonesia ...53
V. HASIL DAN PEMBAHASAN...56
5.1. Sektor-Sektor Perekonomian di Kawasan Timur Indonesia Sebelum Otonomi Daerah Tahun 1994-1996 ...56
5.1.1. Analisis PDRB Kawasan Timur Indonesia Tahun 1994-1996 ...56
5.1.2. Rasio PDRB Kawasan Timur Indonesia dan PDB Indonesia (Ra, Ri, dan ri) Tahun 1994-1996...57
5.1.3. Analisis Komponen PertumbuhanWilayah Tahun 1994-1996 ...59
5.1.4. Analisis Profil Pertumbuhan PDRB Kawasan Timur Indonesia dan Pergeseran Bersih Tahun 1994-1996 ...64
5.2. Sektor-Sektor Perekonomian di Kawasan Timur Indonesia Sebelum Otonomi Daerah Tahun 1997-1999 ...68
5.2.1. Analisis PDRB Kawasan Timur Indonesia Tahun 1997-1999 ...68
5.2.2. Rasio PDRB Kawasan Timur Indonesia dan PDB Indonesia (Ra, Ri, dan ri) Tahun 1997-1999...69
5.2.3. Analisis Komponen PertumbuhanWilayah Tahun 1994-1996 ...70
5.2.4. Analisis Profil Pertumbuhan PDRB Kawasan Timur Indonesia dan Pergeseran Bersih Tahun 1997-1999 ...75
5.3. Sektor-Sektor Perekonomian di Kawasan Timur Indonesia Sebelum Otonomi Daerah Tahun 2000-2002 ...78
5.3.1. Analisis PDRB Kawasan Timur Indonesia Tahun 2000-2002 ...78
5.3.2. Rasio PDRB Kawasan Timur Indonesia dan PDB Indonesia (Ra, Ri, dan ri) Tahun 2000-2002...79
5.3.3. Analisis Komponen PertumbuhanWilayah Tahun 2000-2002 ...80
5.3.4. Analisis Profil Pertumbuhan PDRB Kawasan Timur Indonesia dan Pergeseran Bersih Tahun 2000-2002 ...84
xi
DAFTAR TABEL
Halaman
1. Investasi di KTI dan KBI, 2005-2006... ...1
2. Persentase Penduduk Miskin Menurut Propinsi Tahun 2002, 2003
dan 2004 ...2
3. Persentase PDRB Wilayah-Wilayah Di Indonesia Atas Dasar Harga
Konstan 1993 (Persen) ...5
4. Posisi Dana Simpanan Rupiah dan Posisi Kredit Rupiah Pada Bank Umum Menurut Daerah Propinsi se-KTI Bulan Juni 2001 (Dalam
Miliar Rupiah)...5
5. Keunggulan KBI Dan KTI ...8
6. Lokasi KAPET ...42
7. Luas Daerah Provinsi-Provinsi di Kawasan Timur Indonesia, 2004 ...45
8. Kualitas Sumber Daya Manusia Menurut Pendidikan
di KTI dan Indonesia,1999...48
9. Angka Kematian Umur 0-14 Tahun Menurut Kawasan ...49
10.Kegiatan Tenaga Kerja di Pasar Kerja KTI dan Indonesia (persen) ...51
11.PDRB KTI Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Lapangan
Usaha (Tahun 1994-1996) ...56
12.Nilai Ra, Ri, dan ri Sebelum Implementasi Kebijakan
Otonomi Daerah (Tahun 1994-1996)...59
13.Komponen Pertumbuhan Nasional Sebelum Implementasi
Kebijakan Otonomi Daerah (Tahun 1994-1996) ...60
14.Komponen Pertumbuhan Proporsional KTI Sebelum
Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah (Tahun 1994-1996)...62
15.Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah KTI Sebelum
Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah (Tahun 1994-1996)...64
16.Pergeseran Bersih Sektor-Sektor Perekonomian Kawasan Timur
Indonesia Sebelum Kebijakan Otonomi Daerah (Tahun 1994-1996)...67
17.PDRB KTI Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Lapangan
Usaha (Tahun 1997-1999) ...68
18.Nilai Ra, Ri, dan ri Sebelum Implementasi Kebijakan Otonomi
19.Komponen Pertumbuhan Nasional Sebelum Implementasi
Kebijakan Otonomi Daerah (Tahun 1997-1999) ...71
20.Komponen Pertumbuhan Proporsional Sebelum
Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah (Tahun 1997-1999)...73
21.Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah Sebelum
Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah (Tahun 1997-1999)...74
22.Pergeseran Bersih Sektor-Sektor Perekonomian Kawasan Timur
Indonesia Sebelum Kebijakan Otonomi Daerah (Tahun 1997-1999)...77
23.PDRB KTI Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Lapangan
Usaha (Tahun 1994-1996) ...79
24.Nilai Ra, Ri, dan ri Awal Implementasi Kebijakan Otonomi
Daerah (Tahun 2000-2002) ...80
25.Komponen Pertumbuhan Nasional Awal Implementasi
Kebijakan Otonomi Daerah (Tahun 2000-2002) ...81
26.Komponen Pertumbuhan Proporsional Awal Implementasi
Kebijakan Otonomi Daerah (Tahun 2000-2002) ...83
27.Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah Awal Implementasi
Kebijakan Otonomi Daerah (Tahun 2000-2002) ...84
28.Pergeseran Bersih Sektor-Sektor Perekonomian Kawasan Timur Indonesia Awal Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah
(Tahun 2000-2002) ...88
29.Pergeseran Bersih Sektor-Sektor Perekonomian KTI Sebelum dan
xiii
DAFTAR GAMBAR
Halaman
1.Model Analisis Shift Share...21 2. Kerangka Pemikiran Konseptual...26
3. Profil Pertumbuhan PDRB...35
4. Profil Pertumbuhan Sektor-Sektor Perekonomian Kawasan Timur
Indonesia Tahun 1994-1999 ...66
5. Profil Pertumbuhan Sektor-Sektor Perekonomian Kawasan Timur
Indonesia Tahun 1997-1999 ...76
6. Profil Pertumbuhan Sektor-Sektor Perekonomian Kawasan Timur
DAFTAR LAMPIRAN
Halaman
1. PDRB KTI Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Lapangan
Usaha (Juta Rupiah) ...97
2. PDB Indonesia Atas Dasa Harga Konstan 1993 Menurut Lapangan
Usaha (Miliar Rupiah)...98
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam rangka meningkatkan perekonomian Indonesia dan memperluas
hasil pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, rencana pengembangan wilayah
dianggap paling strategis di Indonesia. Ketimpangan antara Kawasan Barat
Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) seharusnya ditiadakan
karena akan semakin memperlebar terjadinya pertumbuhan yang tidak seimbang
antar sektor, kesenjangan ekonomi antar golongan penduduk dan kesenjangan
pembangunan antar wilayah.
Ketimpangan antara KBI dan KTI dapat dilihat dari besarnya investasi di
kedua kawasan tersebut. Proses pembangunan yang bersumber dari investasi, baik
investasi dalam negeri maupun investasi luar negeri lebih terkonsentrasi di pusat
(Pulau Jawa). Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa penanaman modal dalam negeri
dan penanaman modal asing lebih terfokus di KBI dibandingkan dengan KTI yang
ditujukkan dengan besarnya investasi di KBI yang lebih besar daripada di KTI.
Tabel 1. Investasi di KTI dan KBI, 2005-2006
PMDN (Miliar Rupiah) PMA (Juta Rupiah) Wilayah
2005 2006 (1 Jan s/d 31 Mei) 2005 2006 (1 Jan s/d 31 Mei)
Sumatera 13.234,9 5.659,3 1.355,8 725,1
Jawa dan Bali 26.332,0 9.103,3 10.837,4 2.545,6
Kalimantan 5.212,2 41.073,5 1.005,3 286,4
Sulawesi 4.034,4 963,5 310,7 52,1
Kepulauan Timur Lainnya
1.762,9 20,6 70,1 50,4
KBI 39.566,9 14.762,6 12.193,2 3.270,7
KTI 11.009,5 42.057,6 1.386,1 388,9
Ketimpangan juga bisa dilihat dari tingkat kemiskinan. Angka kemiskinan
yang tertinggi ada di KTI. Menurut Tabel 2 peringkat kemiskinan yang tertinggi
berada di Papua (41,80 persen) dan tingkat kemiskinan terendah berada di DKI
Jakarta (3,42 persen) pada tahun 2002. Pada tahun 2004 tingkat kemiskinan
tertinggi tetap berada di Papua (38,69 persen) dan tingkat kemiskinan terendah
berada di DKI Jakarta (3,18 persen).
Tabel 2. Persentase Penduduk Miskin Menurut Propinsi Tahun 2002, 2003, dan 2004
Persentase Penduduk Miskin Provinsi
2002 2003 2004 Nangroe Aceh Darussalam 29,83* 29,76 28,47 Sumatera Utara 15,84 15,89 14,93 Sumatera Barat 11,57 11,24 10,46
Riau 13,61 13,52 13,12
Jambi 13,18 12,74 12,45
Sumatera Selatan 22,32 21,54 20,92
Bengkulu 22,70 22,69 22,39
Lampung 24,05 22,63 22,22
Bangka Belitung 11,62 10,06 9,07
DKI Jakarta 3,42 3,42 3,18
Jawa Barat 13,38 12,90 12,10
Jawa Tengah 23,06 21,78 21,11
DI Yogyakarta 20,14 19,86 19,14
Jawa Timur 21,91 20,93 20,08
Banten 9,22 9,56 8,58
Bali 6,89 7,34 6,85
NTB 27,76 26,34 25,38
NTT 30,74 28,63 27,86
Kalimantan Barat 15,46 14,79 31,91 Kalimantan Tengah 11,88 11,37 10,44 Kalimantan Selatan 8,51 8,16 7,19 Kalimantan Tmur 12,20 12,15 11,57
Sulawesi Utara 11,22 9,01 8,94
Sulawesi Tengah 24,89 23,04 21,69 Sulawesi Selatan 15,88 15,85 14,90 Sulawesi Tenggara 24,22 22,84 21,90
Gorontalo 32,12 29,25 29,01
Maluku 34,78* 32,85 32,13
Maluku Utara 14,03* 13,92 12,42
Papua 41,80* 39,03 38,69
Sumber : BPS, 2004.
3
Lambatnya arus investasi di KTI menyebabkan pembangunan KTI sangat
tertinggal dibanding KBI dan hal ini dapat diindentifikasi beberapa faktor utama
penyebabnya, antara lain yaitu: (1) terbatasnya sarana dan prasarana
(infrastruktur) seperti transportasi darat, laut dan udara dan telekomunikasi, serta
tersedianya tenaga listrik yang sangat berpengaruh terhadap berbagai aspek yang
dapat mendorong pertumbuhan misalnya, mengurangi minat investor untuk
menginvestasikan modalnya di KTI, meningkatnya biaya produksi, dan
menurunkan daya saing produk yang dihasilkan oleh KTI; (2) terbatasnya sarana
pendidikan dan tenaga pendidik yang berkualitas, yang berakibat terhadap
rendahnya kualitas SDM yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan KTI;
(3) terbatasnya kewenangan pengambilan keputusan seperti di bidang perbankan,
berbagai perijinan dan lain-lain di KTI, sehingga proses pengambilan keputusan
memakan waktu lama karena harus diputuskan oleh pusat. Di samping itu, hal ini
menyebabkan tingginya biaya operasional dari para pengguna jasa tersebut; dan
(4) kondisi sosial dan keamanan di beberapa daerah yang belum kondusif, telah
menyebabkan para investor enggan untuk menanamkan modalnya di KTI. Akibat
dari semua faktor sebagai di atas, menyebabkan produktivitas KTI sangat rendah
(Setiono, 2001).
Dalam kondisi tidak ada hambatan dalam mobilitas, modal cenderung
akan mengalir ke daerah yang terbelakang kemajuan perekonomiannya. Proses ini
akan berlangsung hingga tercapai keseimbangan produktivitas modal antar daerah.
Namun demikian, di negara-negara berkembang, modal bergerak ke arah yang
yang maju. Untuk mencegah timbulnya ketidakseimbangan pembangunan yang
makin besar, diperlukan realokasi investasi (yang besar) ke daerah yang
tertinggal.
Dalam melakukan realokasi investasi, khususnya di KTI tampaknya tidak
sederhana, dan untuk itu, harus memenuhi beberapa kondisi; pertama, perlu
penyiapan kondisi daerah sasaran untuk dapat menghasilkan produktivitas modal
yang optimal, dalam arti efisien secara teknis maupun secara ekonomis. Kedua,
peningkatan produktivitas modal tersebut dapat dicapai apabila mampu
menstimulasi terjadinya aliran investasi yang berkelanjutan. Di samping itu,
beberapa faktor seperti yang telah disebutkan di atas patut pula dipertimbangkan.
Hampir di semua daerah di KTI dapat dikatakan tidak memiliki
infrastruktur yang memadai seperti KBI. Padahal, untuk dapat menghasilkan
produktivitas modal yang optimal dalam arti efisien secara teknis dan ekonomis,
kebutuhan akan infrastruktur, seperti jalan raya, pelabuhan laut dan udara, sarana
telekomunikasi dan lain-lain, merupakan kebutuhan yang mutlak. Kondisi di atas
masih ditambah lagi dengan ”masalah sosial dan keamanan” yang selalu
dipertanyakan oleh setiap investor yang akan menanamkan modalnya ke KTI.
Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila total Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) seluruh Propinsi di KTI pada tahun 1998 tercatat hanya sebesar
18,98 persen dari PDRB seluruh Propinsi Indonesia. PDRB yang rendah di atas,
merupakan pencerminan akan rendahnya tingkat investasi di KTI baik melalui
5
Tabel 3. Persentase PDRB Wilayah-Wilayah Di Indonesia Atas Dasar Harga Konstan 1993 (Persen)
Persentase PDRB
Sebelum Otonomi daerah Masa Otonomi daerah Wilayah
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Sumatera 22,04 21,82 21,54 21,43 22,43 22,60 21,80 21,77 21,74 Jawa dan Bali 61,05 61,22 61,34 61,48 58,59 58,32 59,46 59,46 59,38 Kalimantan 8,98 8,86 8,95 9,02 9,89 10,41 9,87 9,90 9,87 Sulawesi 4,12 4,13 4,13 4,13 4,47 4,44 4,49 4,55 4,59 Kepulauan Timur
Lainnya 3,81 3,97 4,04 3,94 4,62 4,23 4,38 4,32 4,42 KBI 83,09 83,04 82,88 82,91 81,02 80,92 81,26 81,23 81,12 KTI 16,91 16,96 17,12 17,09 18,98 19,08 18,74 18,77 18,88 Sumber: BPS dalam Ardiansyah, 2004.
Rendahnya produksi dan kebutuhan investasi diperburuk dengan
rendahnya penyaluran kredit perbankan di KTI. Akses sumber dana melalui
Perbankan dan Lembaga-lembaga Keuangan di KTI sangat terbatas dan dengan
persyaratan-persyaratan yang berat. Selisih dana simpanan rupiah dibandingkan
dengan posisi kredit pada Bank Pemerintah, Bank Swasta maupun Bank
Perkreditan Rakyat di KTI cukup signifikan seperti dapat dilihat dalam Tabel 4.
Tabel 4. Posisi Dana Simpanan Rupiah dan Posisi Kredit Rupiah Pada Bank Umum Menurut Daerah Propinsi se-KTI, Bulan Juni 2001 (dalam Miliar Rupiah)
Propinsi Posisi Dana Simpanan Posisi Kredit Selisih
Berdasarkan Tabel 4 kondisi simpanan yang jauh lebih besar daripada
jumlah dana yang disalurkan (kredit), jelas tidak dapat dipertahankan dan
dibiarkan berlangsung terus, karena selain akan memperlebar tingkat kesenjangan,
juga dapat menyebabkan ketidakpuasan masyarakat di wilayah KTI, yang pada
gilirannya dapat menekan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Dana yang ada
harus disalurkan kepada masyarakat daerah agar mereka menjadi lebih produktif.
Di samping itu, daerah miskin dan terbelakang akan mengalami (1) banyak
kesulitan dalam membangun sektor industrinya dan memperluas kesempatan
kerja. Akibatnya, pendapatan daerah dan pendapatan perkapita penduduknya
berjalan sangat lambat serta masalah pengangguran menjadi bertambah serius;
(2) perubahan struktur ekonomi (tradisional) yang lambat di daerah tersebut;
(3) kesulitan di dalam mencari pekerjaan di daerahnya, sehingga menyebabkan
mengalirnya tenaga kerja (terutama tenaga kerja yang produktif, dinamis dan
berpendidikan) ke daerah yang lebih maju perekonomiannya. Karenanya,
diperlukan langkah-langkah untuk mempercepat pembangunan KTI dengan
mengoptimalkan aktivitas ekonominya sehingga selain mampu berdaya saing,
diharapkan pula akan mampu mengejar ketertinggalan pembangunan dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah
dinyatakan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan
7
yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah
otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, KTI ikut serta
mengimplikasikan kebijakan otonomi daerah tersebut, sehingga provinsi-provinsi
di KTI memiliki wewenang pemerintahan dan menentukan sendiri kemajuan
pembangunan. Undang-undang otonomi daerah yang dikeluarkan pada tahun
1999, yaitu UU No.22 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25 tentang
Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan
kerangka bagi agenda reformasi pemerintahan di Indonesia. Undang-undang ini
menjadi sangat penting bagi KTI yang sedang berusaha mencoba untuk
memperbaiki ketidakseimbangan kekuasaan antara pusat dan daerah, eksploitasi
sumber daya dengan keuntungan yang tidak seimbang dalam hal peningkatan
prasarana dan pelayanan masyarakat, serta marginalisasi masyarakat lokal dalam
program-program pembangunan.
Proses desentralisasi bisa berjalan baik apabila didukung dengan keadaan
yang kondusif yang tercermin dari sarana dan prasarana yang mendukung
pelaksanaan pemerintahan. Setiap kawasan, baik KBI maupun KBI pasti
mempunyai keunggulan tersendiri yang dapat menunjang pembangunan daerah.
Tabel 5. Keunggulan KBI dan KTI
No. Kawasan Barat Indonesia Kawasan Timur Indonesia 1. Infrastruktur yang memadai Kaya akan sumber daya alam 2. Hasil akhir Sensus Ekonomi 2006 (SE06) mencatat
secara umum persebaran perusahaan/usaha antar kawasan dan antar pulau menunjukkan lebih dari 83 persen terkonsentrasi di Kawasan Barat Indonesia (KBI).
Berpotensi meningkatkan wisata alam, wisata bahari, ekowisata, dan budaya
3. Terdapat pusat pemerintahan
4. Tersedianya lembaga pendidikan yang memadai 5. Kondisi pemerintahan yang lebih stabil
Sumber: http://www.google.
1.2. Perumusan Masalah
Undang-undang otonomi daerah telah dijalankan dan berbagai dampak
ditimbulkan dari pelaksanaan implementasi undang-undang tersebut, baik berupa
pemekaran wilayah maupun peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Daerah-daerah yang mampu melaksnakan otonomi sudah tidak tergantung lagi pada dana
anggaran dari Pemerintah. Daerah-daerah otonom dituntut mampu
mengoptimalkan peran sektor-sektor perekonomian lokalnya untuk meningkatkan
PAD. Setiap daerah memiliki kebijakan masing-masing dalam melaksanakan
pembangunan sesuai dengan potensi sumber dayanya.
Perkembangan suatu wilayah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonominya.
Salah satu indikator perkembangan atau pertumbuhan suatu wilayah adalah
PDRB. Sejak diimplementasikan kebijakan otonomi daerah PDRB KTI
mengalami peningkatan (Lampiran 1). Dalam kurun waktu 2000-2002 PDRB KTI
meningkat sebesar 8,71 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi
perekonomian KTI mengalami pertumbuhan yang positif sejak diberlakukan
9
Pada kurun waktu 9 tahun yaitu tahun 1994-2002 dapat dilihat kondisi
perekonomian yang berbeda-beda. Periode 1994-1996 perekonomian dalam
keadaan yang stabil. Pada periode 1997-1999 perekonomian berada dalam
keadaan krisis yang parah. Selanjutnya untuk periode 2000-2002 perekonomian
mulai menampakkan pertumbuhan kembali dan di berbagai daerah mulai
diimplementasikan otonomi daerah.
Permasalahan yang menjadi fokus penelitian adalah adanya perubahan
atau selisih PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing sektor perekonomian di
KTI dan perubahan PDB nasional dalam kurun waktu 9 tahun terutama sejak
diberlakukannya undang-undang otonomi daerah pada tahun 2000. Telah
diketahui pada uraian sebelumnya nilai PDRB KTI meningkat (Lampiran 1), yang
menjadi pertanyaan adalah apakah peningkatan tersebut termasuk dalam
pertumbuhan progresif (maju) atau tergolong dalam pertumbuhan yang lambat. Dari uraian di atas maka dapat ditentukan perumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana laju pertumbuhan sektor-sektor perekonomian di KTI sebelum dan
pada awal otonomi?
2. Bagaimana daya saing sektor-sektor ekonomi di KTI sebelum dan pada awal
otonomi daerah?
3. Bagaimana profil pertumbuhan PDRB dan pergeseran bersih sektor-sektor
1.3. Tujuan
Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:
1. Menganalisis laju pertumbuhan sektor-sektor perekonomian KTI sebelum dan
pada awal otonomi daerah.
2. Menganalisis daya saing sektor-sektor ekonomi KTI sebelum dan pada awal
otonomi daerah.
3. Mengidentifikasi profil pertumbuhan PDRB dan pergeseran bersih
sektor-sektor ekonomi KTI.
1.4. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah
dalam (1) memberikan prioritas pada sektor-sektor perekonomian yang bisa
memajukan perekonomian di KTI dan menjaga kelestariannya; (2)
mengembangkan sektor-sektor perekonomian yang yang mempunyai laju
pertumbuhan lambat dan tidak berdaya saing agar dapat turut meningkatkan
perekonomian KTI. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memperdalam
ilmu dalam bidang perekonomian dan perencanaan. Bagi pembaca, penelitian ini
II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Konsep Otonomi Daerah
Semenjak berakhirnya pemerintahan Orde Baru muncul harapan untuk
melakukan perbaikan dan perubahan, tidak terkecuali semangat reformasi
dibidang birokrasi pemerintah. Kondisi dan semangat reformasi seharusnya bisa
melahirkan tiga hal penting sebagai harapan yang diwujudkan dalam
pemerintahan. Pertama, diwujudkan harapan agar demokrasi bisa dijalankan
dalam birokrasi pemerintahan, sehingga bisa mengganti birokrasi otoriter yang
sentralistik. Kedua, birokrasi pemerintahan yang mengakomodasikan perubahan
sistem politik dari mono loyalitas dan single majority pada satu partai yang berkuasa kepada multi partai hasil bentukan rakyat yang memungkinkan tidak
adanya mono loyalitas lagi. Ketiga, pelaksanaan otonomi daerah yang
memungkinkan bagi kemajuan daerahnya masing-masing.
Menurut Sidik dalam Pattimura (2003) hakekat otonomi daerah adalah
untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bersama bagi seluruh rakyat
Indonesia melalui pelaksanaan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung
jawab dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Otonomi
daerah hendaknya dijadikan alat untuk meningkatkan kualitas kehidupan
masyarakat sesuai dengan prakarsa masing-masing daerah sehingga daerah bisa
memenuhi kebutuhan yang paling mereka butuhkan.
Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk
pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan
keamana, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya
yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (Bratakusumah dan Solihin,
2003).
Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut UU No.22/1999
tentang Pemerintahan Daerah adalah :
1. Asas Dekonsentrasi, artinya pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada
Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah.
2. Asas Desentralisasi, artinya penyerahan wewenang pemerintahan oleh
Pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
3. Asas Tugas Pembantuan, artinya penugasan dari Pemerintah kepada daerah
dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang
disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan
kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya
kepada yang menugaskan.
Dengan adanya UU No.22/1999 dan UU No.25/1999 sebagai dasar
kekuatan otonomi kewenangan pemerintahan dan otonomi keuangan maka daerah
berkeinginan ada kepastian keleluasaan untuk membangun kesejahteraan dan
kemakmuran melalui hidup mandiri. UU No.22/1999 tentang Pemeritahan Daerah
dan UU No.25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah, antara lain juga mengatur bagaimana pemerintah daerah membiayai
13
daerah, yaitu diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD).
Sumber pendapatan daerah terdiri dari:
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi:
a) Hasil pajak daerah
b) Hasil retribusi daerah
c) Hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan
d) Lain-lain pendapatan asli daerah
2. Dana perimbangan yaitu bagian daerah dari Penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),
Penerimaan dari Sumber Daya alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi
Khusus.
3. Pinjaman daerah
Disamping itu dalam hal-hal tertentu yaitu untuk keperluan mendesak,
kepada daerah tertentu juga diberikan dana darurat yang berasal dari APBN.
PAD salah satunya berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah diatur
dalam UU No.18/1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah kemudian
direvisi dengan UU No.34/2000, merupakan reformasi di bidang perpajakan dan
retribusi daerah. Dengan UU No.34/2000, daerah dibebaskan untuk menciptakan
pajak daerah dan retribusi daerah asal memenuhi kriteria pajak daerah dan kriteria
retribusi yang telah di atur dalam undang-undang tersebut. Pengawasan terhadap
preventif (terlebih dahulu mendapat persetujuan pemerintah pusat) tetapi lebih
bersifat refresif. Artinya persetujuan pemerintah pusat sebelum Perda berlaku
sudah tidak diperlakukan lagi akan tetapi Perda tersebut dapat dicabut oleh
pemerintah pusat jika bertentangan dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.
Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah adalah suatu sistem
pembiayaan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta
pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan
dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, sejalan dengan
kewajiban pengelolaan dan pengawasan keuangannya. Perimbangan keuangan
antara pusat dan daerah ini merupakan alat utama dalam pelaksanaan
desentralisasi fiskal, sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah.
Ketentuan-ketentuan tentang Dana Perimbangan diatur dalam PP No.104/2000
sebagai derivatif dari UU No.25/1999.
DAU sebagai komponen dari dana perimbangan dimaksudkan sebagai alat
pemerintah untuk melaksanakan pemerataan kemampuan daerah untuk membiayai
pelayanan masyarakat. Oleh karena itu rumusan DAU didasarkan atas potensi dan
kebutuhan daerah. Secara teoritis DAU dimaksudkan untuk menutupi fiscal gap
yaitu selisih antara kebutuhan pembiayaan (fiscal need) dengan kemampuan keuangan daerah (fiscal capacity). Perhitungan distribusi alokasi DAU telah ditetapkan dalam Kepres No.181/2000 sedangkan untuk penyaluran DAU
15
DAK merupakan komponen dari Dana Perimbangan yang diberikan
kepada daerah. DAK digunakan untuk pembiayaan prasarana yang bersifat
strategis dan daerah kurang mampu untuk membiayai sendiri. Ketentuan
penyaluran DAK ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan No.555/KMK-03/2000
Agar keuangan pemerintah daerah yang sumbernya berasal dari banyak
variasi tersebut berjalan efektif dan efisien, diperlukan pengendalian pengawasan
dan pemeriksaan yang seharusnya diatur secara jelas tentang mekanisme
pelaksanaan, ruang lingkup dan waktunya. Dengan kata lain diperlukan suatu
manajemen keuangan daerah yang tepat. Manajemen keuangan daerah
dimaksudkan pada pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara tertib, taat
pada peraturan perundangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan serta kepatuhan
sebagaimana diatur dalam PP No.105/2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungan Jawab Keuangan Daerah.
Otonomi daerah yang efektif senantiasa memerlukan dukungan pemerintah
pusat walaupun kadang-kadang terdapat perbedaan pendapat dan kepentingan satu
sama lain. Pemerintah pusat senantiasa berupaya menjamin adanya kesamaan
perlakuan bagi setiap warga negara, sedangkan pemerintah daerah bertanggung
jawab mengatasi kebutuhan-kebutuhan spesifik dari masyarakatnya (Sarundajang,
2.2. Teori Pertumbuhan Rostow
Menurut Rostow dalam Irawan dan Suparmoko (1999) proses
pembangunan ekonomi dapat dibedakan dalam lima tahap dan setiap negara di
dunia dapat digolongkan ke dalam salah satu dari kelima tahap pertumbuhan
ekonomi. Kelima tahap pertumbuhan itu adalah (1) tahap masyarakat tradisional;
(2) tahap prasyarat untuk lepas landas; (3) tahap lepas landas; (4) tahap ke arah
kedewasaan; dan (5) tahap konsumsi tinggi. Teori Rostow mengenai tahap-tahap
pertumbuhan ekonomi mempunyai ruang lingkup yang luas dan teorinya tidak
secara terperinci menganalisa corak perubahan yang terjadi pada suatu sektor
dalam proses pembangunan. Analisanya lebih dititikberatkan pada peranan
beberapa faktor tertentu dalam menimbulkan pertumbuhan ekonomi dan
menganalisa ciri-ciri perubahan yang tercipta dalam tiap-tiap tahap pembangunan
suatu masyarakat.
Rostow mengartikan masyarakat tradisional sebagai suatu masyarakat
yang strukturnya berkembang dalam fungsi produksi yang terbatas, cara-cara
memproduksi yang relatif primitif, produktivitas per pekerja masih sangat terbatas
dan cara hidup masyarakat hidup yang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai yang
dicetuskan cara pemikiran yang tidak rasional atau didasarkan pada kebiasaan
yang berlangsung secara turun temurun. Ciri-ciri tahap prasyarat lepas landas
dibedakan menjadi dua yaitu tahap prasyarat lepas landas yang dicapai dengan
merombak sistem masyarakat tradisional yang sudah lama ada dan tahap untuk
mencapai tahap lepas landas tanpa harus merombak sistem masyarakat tradisional.
17
dalam masyarakat, seperti revolusi politik, terciptanya kemajuan yang pesat dalam
inovasi atau terbukanya pasar-pasar baru. Faktor penyebab dimulainya masa lepas
landas berbeda-beda yang terpenting dari perubahan-perubahan tersebut akan
mengakibatkan pembaharuan-pembaharuan dan peningkatan penanaman modal.
Rostow menekankan berlakunya proses kenaikan penanaman modal sebagai
prasyarat untuk mencapai lepas landas karena hanya dengan terciptanya keadaan
tersebut perekonomian dapat berkembang lebih cepat daripada tingkat
pertumbuhan penduduk.
Tahap gerakan ke arah kedewasaan diartikan sebagai masa di mana
masyarakat sudah secara efektif menggunakan teknologi modern pada sebagian
besar faktor-faktor produksi dan kekayaan alamnya. Ciri-ciri lain dari tahap
gerakan ke arah kedewasaan yang bukan bersifat ekonomi antara lain (1) struktur
dan keahlian tenaga kerja mengalami perubahan. Sektor industri bertambah
penting peranannya, sedangkan sektor pertanian menurun peranannya terhadap
perekonomian. Tahap terakhir dari teori pertumbuhan Rostow adalah tahap
konsumsi tinggi yang dicirikan dengan masa dimana perhatian masyarakat lebih
ditekankan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan konsumsi dan
kesejahteraan masyarakat dan bukan lagi kepada masalah produksi.
2.3. Konsep Wilayah
Wilayah diartikan sebagai suatu unit geografi yang dibatasi oleh kriteria
tertentu yang bagian-bagiannya tergantung secara internal. Batas-batas wilayah
1. Konsep Homogenitas. Menurut konsep homogenitas wilayah dipandang dari
satu aspek/kriteria yang memiliki sifat-sifat atau ciri-ciri yang relatif sama.
Misalnya daerah dengan struktur produksi dan konsumsi yang homogen,
daerah dengan pendapatan yang rendah (keadaan perekonomian sama),
persamaan keadaan topografi, persamaan agama, suku, dan lain sebagainya.
Dasar untuk wilayah homogen adalah suatu output yang dapat diekspor
bersama, dimana seluruh wilayah merupakan suatu daerah surplus untuk suatu
output tertentu, sehingga berbagai tempat di wilayah tersebut kecil
kemungkinannya untuk perdagangan secara luas diantara satu sama lainnya.
2. Konsep Nodalitas. Menurut konsep nodalitas wilayah secara fungsional
mempunyai ketergantungan antara pusat (inti) dan daerah belakangnya
(hinterland). Konsep ini menekankan pada perbedaan struktur tata ruang di dalam wilayah, dimana terdapat hubungan saling ketergantungan yang bersifat
fungsional. Batas wilayah nodal ditentukan oleh sejauh mana pengaruh dari
suatu pusat kegiatan ekonomi jika diganti oleh pengaruh dari pusat ekonomi
lainnya.
3. Konsep Administratif. Menurut konsep administratif batas-batas suatu wilayah
ditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan/politik seperti
provinsi dan kabupaten/kota. Penentuan batas wilayah berdasarkan kriteria
konsep administratif paling banyak digunakan karena (1) di dalam
melaksanakan kebijaksanaan dan rencana pembangunan wilayah diperlukan
tindakan-tindakan dari berbagai badan pemerintah agar lebih praktis jika
19
ada; (2) wilayah yang batasnya ditentukan berdasarkan atas satuan
administrasi pemerintahan lebih mudah dianalisis karena sejak lama
pengumpulan data di berbagai wilayah berdasarkan satuan wilayah
administrasi tersebut.
Selain penggunaan batasan berdasarkan konsep homogenitas, konsep
nodalitas, dan konsep administratif, klasifikasi wilayah dapat pula dibedakan
menjadi wilayah formal, wilayah fungsional, dan wilayah perencanaan. Wilayah
formal adalah wilayah yang mempunyai beberapa persamaan dalam kriteria
tertentu. Wilayah fungsional ialah wilayah yang memperlihatkan adanya suatu
hubungan fungsional yang saling tergantung dalam kriteria tertentu atau wilayah
fungsional ialah wilayah nodal yang saling tergantung satu sama lain. Wilayah
perencanaan adalah wilayah yang memperlihatkan koherensi/kesatuan
keputusan-keputusan ekonomi.
Ketimpangan seperti yang terjadi pada KTI dan KBI disebabkan oleh
beberapa faktor antara lain: perbedaan karakteristik potensi SDM, demografi
kemampuan SDM, potensi lokal dan lain sebagainya. Berdasarkan
perbedaan-perbedaan tersebut klasifikasi wilayah dapat dibedakan sebagai berikut :
1. Wilayah Maju. Wilayah maju merupakan wilayah yang telah berkembang dan
diidentifikasikan sebagai wilayah pusat pertumbuhan, pemusatan penduduk,
industri, pemerintahan, pasar potensial, dan tingkat pendapatan serta kualitas
sumber daya manusia yang tinggi. Perkembangan wilayah pada wilayah yang
hinterland, potensi lokasi strategis, sarana pendidikan yang memadai, serta adanya kelengkapan infrastruktur.
2. Wilayah Sedang Berkembang. Wilayah sedang berkembang ditandai dengan
adanya pertumbuhan penduduk yang cepat sebagai implikasi dari peranannya
sebagai penyangga wilayah maju.
3. Wilayah Belum Berkembang. Potensi sumber daya alam yang terdapat pada
wilayah ini belum dikelola dengan baik. Karakteristik dari wilayah yang
belum berkembang antara lain tingkat aksesibilitas yang masih rendah
terhadap wilayah lain, struktur ekonomi yang masih didominasi oleh sektor
primer.
4. Wilayah Tidak Berkembang. Wilayah ini ditandai dengan tidak adanya
sumber daya alam, sehingga secara alamiah tidak dapat berkembang. Tingkat
kepadatan penduduk, kualitas sumber daya manusia, dan tingkat pendapatan
masih rendah, terjadinya regional linkages, infrastruktur yang tidak lengkap serta aksesibilitas yang masih rendah terhadap daerah lain.
2.4. Kerangka Teoritis 2.4.1. Analisis Shift Share
Analisis shift share memperlihatkan hubungan antara struktur
perekonomian dengan pertumbuhan ekonomi wilayah. Analisis shift share
merupakan metode untuk melihat aktifitas ekonomi di suatu wilayah dengan
21
menganalisis pertumbuhan sektor-sektor selain dapat digunakan untuk menduga
dampak kebijakan wilayah ketenagakerjaan.
Analisis shift share menganalisis berbagai perubahan indikator kegiatan ekonomi, seperti produksi dan kesempatan kerja pada dua titik waktu di suatu
wilayah. Hasil analisis dapat menunjukkan perkembangan suatu sektor di suatu
wilayah jika dibandingkan secara relatif dengan sektor-sektor lainnya. Hasil
analisis shift share dapat mengidentifikasi suatu perkembangan yang cepat atau lambat. Hasil analisis ini juga dapat menunjukkan bagaimana perkembangan suatu
wilayah bila dibandingkan dengan wilayah lainnya. Tujuan analisis shift share
juga dapat menentukan produktivitas kerja perekonomian daerah dan
membandingkannya dengan daerah yang lebih besar (regional atau nasional).
Secara skematik model analisis shift share dapat dilihat dalam Gambar 1 sebagai berikut :
Sumber : Budiharsono, 2001.
Gambar 1. Model Analisis Shift Share
Berdasarkan Gambar 1 dapat dipahami bahwa pertumbuhan sektor
perekonomian pada suatu wilayah dipengaruhi oleh beberapa komponen, yaitu
(1) komponen pertumbuhan nasional (national growth component) disingkat PN atau komponen pertumbuhan regional (regional growth component) disingkat PR; (2) komponen pertumbuhan proporsional (proportional or industrial mix growth component) disingkat PP; (3) komponen pertumbuhan pangsa wilayah (regional share growth component) disingkat PPW. Dari tiga komponen tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi cepat atau lambat pertumbuhan suatu sektor
perekonomian. Apabila PP + PPW ≥ 0, maka pertumbuhan sektor perekonomian
termasuk ke dalam kelompok progresif (maju), tetapi apabila PP + PPW ≤ 0 berarti sektor perekonomian tersebut memiliki pertumbuhan yang lambat.
Penjelasan dari tiga komponen yang mempengaruhi pertumbuhan sektor suatu
wilayah adalah sebagai berikut :
1. Komponen Pertumbuhan Nasional/Pertumbuhan Regional
Komponen pertumbuhan nasional/pertumbuhan regional adalah perubahan
produksi suatu wilayah yang disebabkan oleh perubahan produksi nasional
secara umum, perubahan kebijakan ekonomi nasional atau perubahan dalam
hal-hal yang mempengaruhi perekonomian suatu sektor dan wilayah. Bila
diasumsikan bahwa tidak ada perbedaan karakteristik ekonomi antar sektor
dan antar wilayah, maka adanya perubahan akan membawa dampak yang
sama pada semua sektor dan wilayah. Akan tetapi pada kenyataannya
beberapa sektor dan wilayah tumbuh lebih cepat daripada sektor dan wilayah
23
2. Komponen Pertumbuhan Proporsional
Komponen pertumbuhan proporsional tumbuh karena perbedaan sektor dalam
permintaan produk akhir, perbedaan dalam ketersediaan bahan mentah,
perbedaan dalam kebijakan industri dan perbedaan dalam struktur, dan
keragaman pasar.
3. Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah
Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah timbul karena peningkatan atau
penurunan PDRB atau kesempatan kerja dalam suatu wilayah dibandingkan
dengan wilayah lainnya. Cepat atau lambatnya pertumbuhan ditentukan oleh
keunggulan komparatif, akses pasar, dukungan kelembagaan, prasarana sosial
dan ekonomi serta kebijakan ekonomi regional pada wilayah tersebut.
2.4.2. Keterbatasan-Keterbatasan Analisis Shift Share
Analisis shift share dapat menganalisis pertumbuhan sektor-sektor perekonomian suatu wilayah, baik itu laju pertumbuhan maupun daya saing sektor
tersebut, akan tetapi analisis shift share juga memiliki beberapa keterbatasan. Keterbatasan-keterbatasan analisis shift share dijelaskan sebagai berikut (Soepono dalam Ardiansyah, 2004):
1. Analisis shift share merupakan suatu teknik pengukuran yang mencerminkan suatu sistem akunting dan tidak analitik oleh karena itu analisis tidak untuk
menjelaskan mengapa suatu wilayah memiliki daya saing yang positif di satu
2. Komponen pertumbuhan nasional secara implisit mengemukakan bahwa laju
pertumbuhan suatu wilayah hendaknya tumbuh pada laju nasional tanpa
memperhatikan sebab-sebab laju pertumbuhan wilayah.
3. Arti ekonomi dari kedua komponen pertumbuhan wilayah (PP dan PPW) tidak
dikembangkan dengan baik. Keduanya berkaitan dengan prinsip-prinsip
ekonomi yang sama, seperti perubahan penawaran dan permintaan, perubahan
teknologi dan perubahan lokasi.
4. Teknik analisis shift share secara implisit mengambil asumsi bahwa semua barang dijual secara nasional padahal tidak semua demikian. Bila pasar suatu
wilayah bersifat lokal maka barang itu tidak dapat bersaing dengan
wilayah-wilayah lain yang menghasilkan barang yang sama sehingga tidak
mempengaruhi permintaan agregat.
2.5. Kerangka Pemikiran Konseptual
Kondisi perekonomian suatu wilayah dipengaruhi oleh kondisi demografi,
potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, aksesibilitas, dan
kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Salah satu kebijakan-kebijakan
pemerintah yang berpengaruh terhadap kondisi perekonomian daerah adalah
kebijakan otonomi daerah. Pada masa sebelum otonomi, kewenangan pemerintah
pusat sangat dominan dalam menentukan arah pembangunan suatu daerah,
sehingga daerah mampu tidak bisa menentukan arah dan sasaran pemerintahan
daerahnya. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah menuntut daerah-daerah
25
Potensi sektor-sektor perekonomian berpengaruh terhadap perkembangan
suatu wilayah. Apabila sektor-sektor ekonomi memiliki pertumbuhan yang cepat,
maka suatu wilayah berkembang dengan cepat pula, begitu pula sebaliknya. Laju
pertumbuhan sektor-sektor perekonomian dapat dianalisis dengan menggunakan
analisis shift share. Pada penelitian ini analisis shift share digunakan untuk menganalisis perekonomian KTI sebelum dan pada awal otonomi daerah,
sehingga dapat diketahui sektor-sektor yang memiliki pertumbuhan cepat dan
sektor-sektor yang mempunyai pertumbuhan lambat. Dengan menggunakan
analisis shift share dapat juga digunakan untuk menganalisis daya saing sektor-sektor ekonomi yaitu sektor-sektor mana yang mampu bersaing dan sektor-sektor mana yang
tidak mempunyai daya saing. Informasi mengenai pertumbuhan sektor-sektor
perekonomian dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk
menentukan kebijakan pembangunan dan perencanaan pembangunan. Bagi para
investor untuk menanamkan modalnya pada sektor-sektor yang menguntungkan.
Secara sistematis kerangka pemikiran konseptual dapat dijelaskan dengan
Gambar 2.
Gambar 2. Kerangka Pemikiran Konseptual
Ket :
Hal yang dianalisis :
Alat analisis :
Sebelum Otonomi Awal Otonomi
Sektor-sektor Perekonomian
Shift Share
Laju Pertumbuhan, Daya Saing, dan Profil Pertumbuhan dari Masing-Masing Sektor Ekonomi
III. METODE PENELITIAN
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari sampai April 2007. KTI dipilih
menjadi lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa : (1) KTI mengalami
pemekaran setelah diberlakukannya kebijakan otonomi daerah; (2) KTI memiliki
sumber daya alam yang sangat potensial untuk dikembangkan seperti yang
terdapat di Papua ataupun Kalimantan Timur namun potensi tersebut belum dapat
memajukan kehidupan masyarakat di sekitarnya; dan (3) Belum ada penelitian
tentang analisis pertumbuhan sektor-sektor perekonomian di KTI sebelum dan
pada awal masa otonomi daerah.
3.2. Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang
diperoleh dari BPS Pusat, Lembaga Sumberdaya Informasi (LSI) IPB,
Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM), dan dari media informasi
lain. Data yang dibutuhkan yaitu data PDRB Provinsi-provinsi di KTI dan PDB
Indonesia dari tahun 1994 sampai 2002 atas dasar harga konstan 1993 menurut
lapangan usaha.
3.3. Metode Analisis Shift Share
Analisis shift share menganalisis berbagai perubahan indikator kegiatan
wilayah. Hasil analisis dapat menunjukkan perkembangan suatu sektor di suatu
wilayah jika dibandingkan secara relatif dengan sektor-sektor lainnya. Hasil
analisis shift share dapat mengidentifikasi suatu perkembangan yang cepat atau
lambat. Hasil analisis shift share juga dapat menunjukkan bagaimana
perkembangan suatu wilayah bila dibandingkan dengan wilayah lainnya.
Perubahan indikator kegiatan ekonomi dilihat dari dua titik waktu yaitu tahun
akhir analisis dan tahun dasar analisis. Analisis shift share menggunakan data
PDRB KTI yang terjadi pada dua titik waktu yaitu tahun akhir analisis dan tahun
dasar analisis. Ada tiga komponen pertumbuhan yang terdapat dalam analisis shift
share, yaitu komponen pertumbuhan nasional, komponen pertumbuhan proporsional dan komponen pertumbuhan pangsa wilayah. Penjumlahan dari
ketiga komponen tersebut dapat mengetahui perubahan PDRB KTI pada suatu
wilayah.
3.3.1. Analisis PDRB KTI dan PDB Indonesia
Andaikan dalam suatu wilayah terdapat m provinsi (j = 1, 2, 3, 4,..., m)
dan n merupakan sektor ekonomi (i = 1, 2, 3, 4,..., n) maka perubahan dalam
PDRB KTI dapat dinyatakan sebagai berikut :
ij ij
ij+PP +PPW
PN =
ΔYij ...(1)
dimana :
ij
Y
Δ = perubahan dalam PDRB KTI sektor i.
ij
PN = persentase perubahan PDRB KTI yang disebabkan komponen
29
ij
PP = persentase perubahan PDRB KTI yang disebabkan komponen
pertumbuhan proporsional.
ij
PPW = persentase perubahan PDRB KTI yang disebabkan komponen
pertumbuhan pangsa wilayah.
Untuk memperoleh nilai PN, PP, dan PPW ada beberapa rumusan yang harus
dipenuhi dan dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. PDB dari sektor i pada tahun dasar analisis :
‡”
2. PDB dari sektor i pada tahun akhir analisis :
‡”
Sedangkan total PDB pada tahun dasar analisis dan tahun akhir analisis,
dirumuskan sebagai berikut :
3. Total PDB pada tahun dasar analisis :
dimana :
Y.. = total PDB dari sektor i pada tahun dasar analisis.
ij
Y = PDRB KTI sektor i pada tahun dasar analisis.
4. Total PDB pada tahun akhir analisis :
‡”‡”
nNilai Ra, Ri, dan ri digunakan untuk mengidentifikasi perubahan PDRB KTI
dari sektor i pada tahun dasar analisis maupun tahun akhir analisis. Menghitung
nilai Ra, Ri, dan ri menggunakan nilai PDRB KTI yang terjadi pada dua titik
waktu yaitu tahun dasar analisis dan tahun akhir analisis.
1. Nilai Ra
Nilai Ra merupakan selisih antara total PDB pada tahun akhir analisis dengan total
PDB pada tahun dasar analisis dibagi total PDB pada tahun dasar analisis.
Dirumuskan sebagai berikut :
31
..
Y = total PDB pada tahun dasar analisis.
2. Nilai Ri
Ri merupakan selisih antara PDB dari sektor i pada tahun akhir analisis
dengan PDB sektor i pada tahun dasar analisis dibagi PDB sektor i pada tahun
dasar analisis. Dirumuskan sebagai berikut :
Ri =
= PDB dari sektor i pada tahun akhir analisis.
.
Yi = PDB dari sektor i pada tahun dasar analisis.
3. Nilai ri
ri merupakan selisih antara PDRB KTI dari sektor i pada tahun akhir
analisis dengan PDRB KTI dari sektor i pada tahun dasar analisis dibagi PDRB
KTI dari sektor i pada tahun dasar analisis.
Dirumuskan sebagai berikut :
ri =
Y = PDRB KTI sektor i pada tahun akhir analisis.
ij
3.3.3. Analisis Komponen Pertumbuhan Wilayah
Nilai komponen Pertumbuhan Nasional atau Pertumbuhan Regional,
Pertumbuhan Proporsional, dan Pertumbuhan Pangsa Wilayah didapat dari
perhitungan nilai Ra, Ri, dan ri. Dari ketiga komponen tersebut apabila
dijumlahkan akan didapat nilai perubahan PDRB.
1. Komponen Pertumbuhan Nasional (PN)
Komponen PN adalah perubahan produksi suatu wilayah yang disebabkan
oleh perubahan produksi regional secara umum, perubahan kebijakan ekonomi
regional, atau perubahan dalam hal-hal yang mempengaruhi perekonomian suatu
sektor dan wilayah. Bila tidak ada perbedaan karakteristik ekonomi antar sektor
dan wilayah maka adanya perubahan akan membawa dampak yang sama pada
semua sektor dan wilayah. Akan tetapi pada kenyataannya beberapa sektor dan
wilayah tumbuh lebih cepat daripada sektor dan wilayah lainnya. Komponen
pertumbuhan nasional dapat dirumuskan sebagai berikut :
ij
Apabila persentase total perubahan PDRB suatu wilayah lebih besar
daripada persentase komponen pertumbuhan nasional maka pertumbuhan