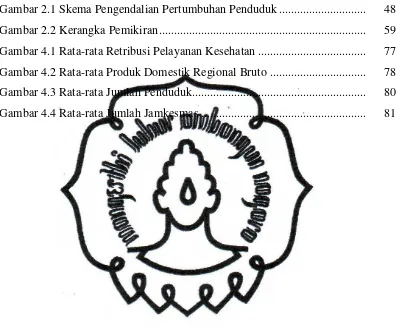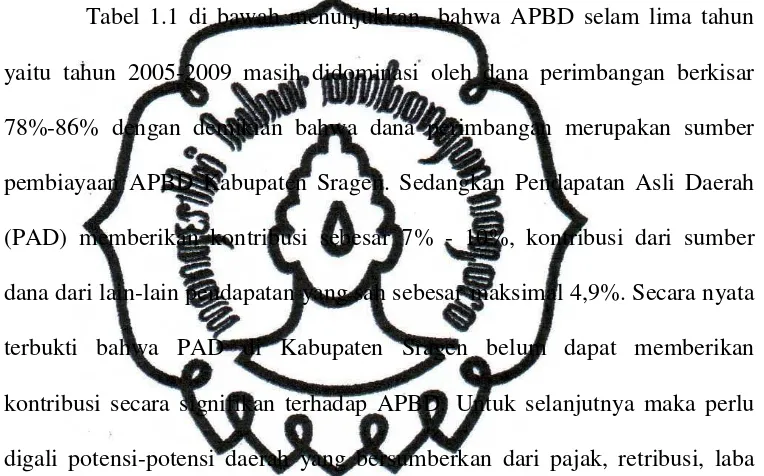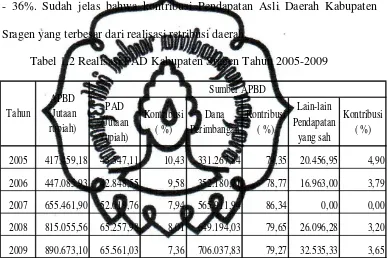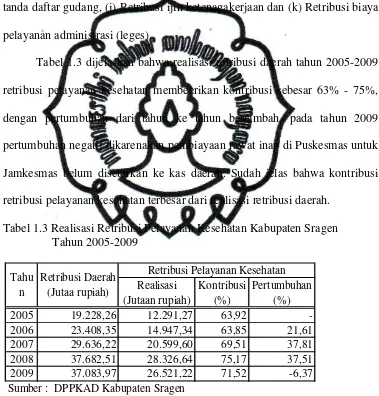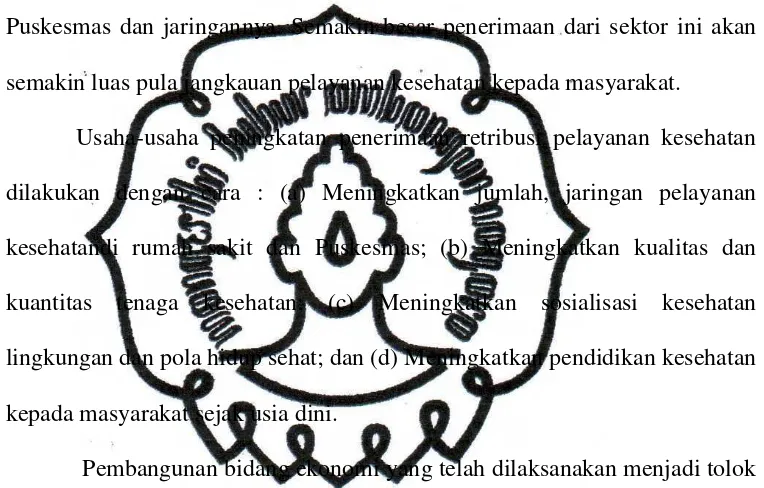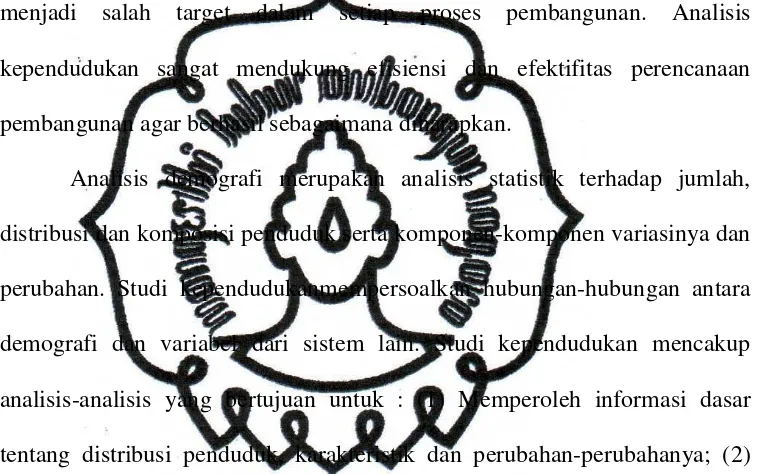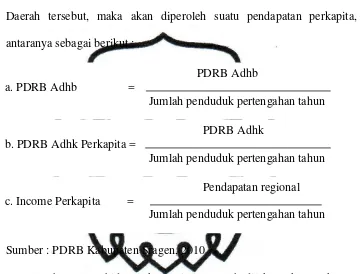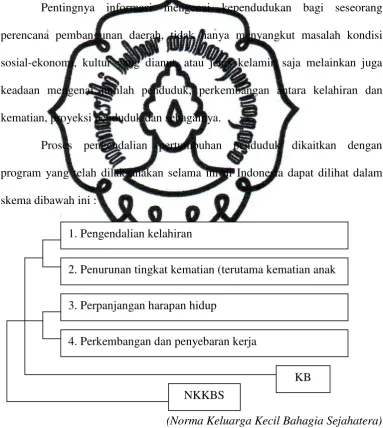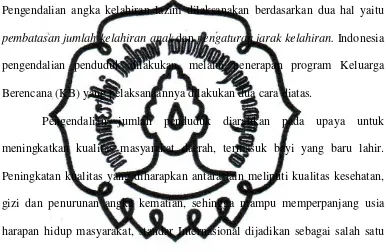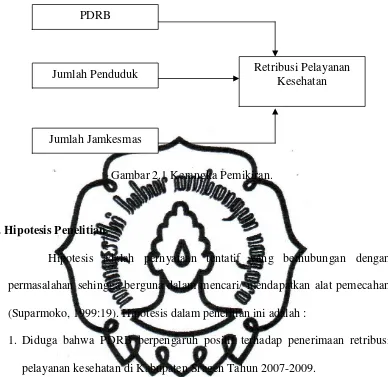commit to user
i
PENGARUH PDRB, JUMLAH PENDUDUK DAN JUMLAH
JAMKESMAS TERHADAP RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN DI KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2007-2009
TESIS
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister
Program Studi MESP
Konsentrasi : Keuangan dan Perencanaan Wilayah
Oleh :
SUYATMO
S 4209144
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
commit to user
commit to user
commit to user
commit to user
commit to user
vi
MOTTO
1. Demi masa, Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal sholeh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran. (QS. Al’Ashr:1-3)
2. Pengetahuan itu milik orang mukmin yang hilang, dimana saja ia menemukannya, ia lebih berhak atasnya. (HR. Turmudzy)
commit to user
vii
PERSEMBAHAN
Karya ini kupersembahkan kepada :
v Anakku tersayang yang telah memberikan semangat.
v Istriku yang telah memberikan dorongan dan kasih sayangnya.
commit to user
viii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian tesis dengan judul: ” PENGARUH PDRB, JUMLAH PENDUDUK, JUMLAH JAMKESMAS TERHADAP RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2007-2009” , dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan penyelesaian derajat sarjana S-2 Program Studi Magister Ekonomi Dan Studi Pembangunan Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2011.
Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :
1. Dr. JJ. Sarungu, MS selaku Ketua Program Studi Magister Ekonomi Dan Studi Pembangunan Universitas Sebelas Maret.
2. Dr. Agustinus Suryantoro, MS selaku pembimbing pertama dalam penyusunan tesis yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, arahan, dorongan dan berbagai ide selama penulisan penelitian ini.
3. Drs. Supriyono, MSi selaku pembimbing kedua penulis dalam penyusunan tesis yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, arahan, dorongan dan berbagai ide selama penelitian ini.
4. Segenap Staf UNS.
5. Seluruh rekan–rekan mahasiswa program Studi Magister Ekonomi Dan Studi Pembangunan Universitas Sebelas Maret di Surakarta dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah memberikan dukungan dan masukan kepada penulis selama menyelesaikan usaha penelitian ini.
Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu sumbang dan saran sangat penulis harapkan demi penyempurnaan penelitian ini.
commit to user
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS ... iv
MOTTO ... v
F. Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin ... 49
G. Peneliti Terdahulu ... 55
H. Kerangka Pemikiran ... 58
commit to user
1. Regresi Linier Berganda... 66
2. Uji Statistik ... 66
a. Uji Ketepatan Parameter Penduga (Uji t) ... 66
b. Uji Ketepatan Model (Uji F) ... 68
3. Koefisien Determinasi Ganda ... 69
4. Uji Asumsi Klasik ... 69
D. Interpretasi Hasil Penelitian ... 90
BAB V PENUTUP... 97
A. Kesimpulan ... 97
B. Saran... 98 DAFTAR PUSTAKA
commit to user
xi
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Sumber APBD Kabupaten Sragen ... 7
Tabel 1.2 Sumber Penerimaan APBD Kabupaten Sragen ... 9
Tabel 1.3 Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan ... 12
Tabel 4.1 Kontribusi RPK ... 76
Tabel 4.2 Kontribusi PDRB ... 78
Tabel 4.3 Pertumbuhan Jumlah Penduduk ... 79
Tabel 4.4 Pertumbuhan Jumlah Jamkesmas ... 81
Tabel 4.5 Hasil Regresi Linier Berganda ... 82
Tabel 4.6 Anova ... 85
Tabel 4.7 Koefisien Determinasi ... 86
Tabel 4.8 Uji Normalitas ... 87
Tabel 4.9 Uji Multikolinearitas ... 88
commit to user
xii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Skema Pengendalian Pertumbuhan Penduduk ... 48
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran ... 59
Gambar 4.1 Rata-rata Retribusi Pelayanan Kesehatan ... 77
Gambar 4.2 Rata-rata Produk Domestik Regional Bruto ... 78
Gambar 4.3 Rata-rata Jumlah Penduduk ... 80
commit to user
xiii
ABTRAKSI
PENGARUH PDRB, JUMLAH PENDUDUK, JUMLAH JAMKESMAS TERHADAP RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DI KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2007-2009
SUYATMO
Retribusi daerah mampu memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu retribusi daerah harus dipungut dan dikelola secara lebih profesional dan diharapkan dapat menunjang usaha peningkatan perekonomian, menjadi sumber pembiayaan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, jumlah penduduk dan jaminan kesehatan masyarakat miskin terhadap penerimaan retribusi pelayanan kesehatan di Kabupaten Sragen tahun 2007-2009.
Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda doubel logaritma natural dengan tingkat kemaknaan 5% untuk setiap uji statistik. Untuk mendapatkan hasil model penaksiran yang terbaik, parameter yang sebenarnya, linier maka uji asumsi klasik semua terpenuhi. Penelitian ini telah menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama dan parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan retribusi pelayanan kesehatan.
Koefisien determinasi ganda diperoleh sebesar sebesar 0,563, menunjukkan bahwa variabel independen hanya mampu menjelaskan vareasi variabel dependen sebesar 56,3%, sedangkan sisanya 43,7% dijelaskan oleh vareasi variabel lain diluar model penelitian ini.
Saran-saran yang diajukan karena dengan penyediaan barang publik yang wajib oleh pemerintah maka penerimaan pendapatan asli daerah akan meningkat.
Meningkatkan produk domestik, mengatur pertumbuhan penduduk agar tidak terjadi peledakan kelahiran bayi. Mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Mengalokasikan dana untuk sarana dan prasarana
pelayanan kesehatan di Rumah sakit, Puskesmas dan memudahkan pemberian ijin mendirikan sarana kesehatan swasta.
commit to user
xiv ABSTRACT
THE EFFECT OF GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCT, POPULATION AND HEALTH SECURITY OF THE POOR TO HEALTH SERVICES LEVY REVENUE IN SRAGEN REGENCY YEAR 2007-2009
SUYATMO
Retribution can provide a significant contribution to the region income. Therefore, levies should be collected and managed in a more professional and is expected to support efforts to improve the economy, a source of financing for the governance and development. The purpose of this study was to determine the effect of Gross Regional Domestic Product, population and health security of the poor to health services levy revenue in Sragen regency year 2007-2009.
The analytical tool used is multiple linear regression with natural logarithm doubel 5% significance level for each statistical test. To get the best results of the assessment model, the actual parameters, linear then the classical assumption of all are met. This study has shown that the independent variables together and partially have a significant impact on the health service fee revenue.
Multiple determination coefficient of 0.563 obtained equal, indicating that the independent variables can only explain the dependent variable vareasi of 56.3%, while the remaining 43.7% is explained by other variables outside the model vareasi this research.
The suggestions put forward for the provision of public goods required by the government of the revenue receipts will increase. Increasing domestic product, set the population growth in order to avoid blasting the birth of a baby. Alleviate poverty and improve people's welfare. Allocating funds for facilities and infrastructure of health services in hospitals, health centers and facilitate the granting permission to establish private health facilities.
commit to user
PENGARUH PDRB, JUMLAH PENDUDUK, JUMLAH JAMKESMAS TERHADAP RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN terhadap Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu retribusi daerah harus dipungut dan dikelola secara lebih profesional dan diharapkan dapat menunjang usaha peningkatan perekonomian, menjadi sumber pembiayaan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, jumlah penduduk dan jaminan kesehatan masyarakat miskin terhadap penerimaan retribusi pelayanan kesehatan di Kabupaten Sragen tahun 2007-2009.
Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda doubel logaritma natural dengan tingkat kemaknaan 5% untuk setiap uji statistik. Untuk mendapatkan hasil model penaksiran yang terbaik, parameter yang sebenarnya, linier maka uji asumsi klasik semua terpenuhi. Penelitian ini telah menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama dan parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan retribusi pelayanan kesehatan.
Koefisien determinasi ganda diperoleh sebesar sebesar 0,563, menunjukkan bahwa variabel independen hanya mampu menjelaskan vareasi variabel dependen sebesar 56,3%, sedangkan sisanya 43,7% dijelaskan oleh vareasi variabel lain diluar model penelitian ini.
Saran-saran yang diajukan karena dengan penyediaan barang publik yang wajib oleh pemerintah maka penerimaan pendapatan asli daerah akan meningkat.
Meningkatkan produk domestik, mengatur pertumbuhan penduduk agar tidak terjadi peledakan kelahiran bayi. Mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Mengalokasikan dana untuk sarana dan prasarana
pelayanan kesehatan di Rumah sakit, Puskesmas dan memudahkan pemberian ijin mendirikan sarana kesehatan swasta.
commit to user
EFFECT OF GDP, TOTAL POPULATION, THE NUMBER OF HEALTH INSURANCE LEVY ON COMMUNITY HEALTH SERVICES
IN THE DISTRICT SRAGEN YEAR 2007-2009 Suyatmo
MIM. S4208144 Abstraction
Retribution can provide a significant contribution to the region income. Therefore, levies should be collected and managed in a more professional and is expected to support efforts to improve the economy, a source of financing for the governance and development. The purpose of this study was to determine the effect of Gross
Regional Domestic Product, population and health security of the poor to health services levy receipts in Sragen the year 2007-2009.
The analytical tool used is multiple linear regression with natural logarithm doubel 5% significance level for each statistical test. To get the best results of the
assessment model, the actual parameters, linear then the classical assumption of all are met. This study has shown that the independent variables together and
partially have a significant impact on the health service fee revenue. Multiple determination coefficient of 0.563 obtained equal, indicating that the independent variables can only explain the dependent variable vareasi of 56.3%,
while the remaining 43.7% is explained by other variables outside the model vareasi this research.
The suggestions put forward for the provision of public goods required by the government of the revenue receipts will increase. Increasing domestic product, set
the population growth in order to avoid blasting the birth of a baby. Alleviate poverty and improve people's welfare. Allocating funds for facilities and infrastructure of health services in hospitals, health centers and facilitate the
granting permission to establish private health facilities.
commit to user BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang
Sejarah perekonomian mencatat desentralisasi telah muncul kepermukaan sebagai paradigma baru dalam kebijakan dan administrasi pembangunan sejak dasawarsa 1970-an. Tumbuhnya perhatian terhadap desentralisasi tidak hanya dikaitkan dengan gagalnya perencanaan terpusat dan populernya strategi pertumbuhan dengan pemerataan (growth with
equity), tetapi juga adanya kesadaran bahwa pembangunan adalah suatu
proses yang komplek dan penuh ketidakpastian yang tidak mudah dikendalikan dan direncanakan dari pusat. Dengan penuh keyakinan para pelopor desentralisasi mengajukan sederet panjang alasan dan argumen tentang pentingnya desentralisasi dalam perencanaan dan administrasi di negara dunia ketiga (Allen, 1990). Berbagai pengertian desentralisasi. Leemans, misalnya membedakan dua macam desentralisasi : representative
local government dan field administration (Leemans, 1970). Maddick
mendefinisikan desentralisasi sebagai proses dekonsentrasi dan devolusi (Maddick, 1983). Devolusi adalah penyerahan kekuaaan untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu kepada pemerintah daerah; sedang dekonsentrasi merupakan pendelegasian wewenang atas fungsi-fungsi tertentu kepada staf pemerintah pusat yang tinggal diluar kantor pusat.
Sentralisasi ataupun desentralisasi sebagai suatu sistem administrasi pemerintahan, dalam banyak hal, tidak dapat dilepaskan dari proses
commit to user
pertumbuhan suatu negara. Sejarah mencatat desentralisasi di Indonesia mengalami pasang surut seiring dengan perubahan konstelasi politik yang melekat dan terjadi pada perjalanan kehidupan bangsa. Pada prakemerdekaan, Indonesia dijajah Belanda dan Jepang. Penjajah telah menerapkan desentralisasi yang bersifat sentralistis, birokratis dan feodalistis untuk kepentingan mereka. Penjajah Belanda menyususn suatu hierarki Pangreh Praja Bumiputra dan Pangreh Praja Eropa yang harus tunduk kepada Gubernur Jendral. Dikeluarkannya Decentralisatie Wet pada tahun 1903 yang ditindaklanjuti dengan Bestuurshervorming Wet pada tahun 1922, menetapkan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri sekaligus membagi daerah-daerah otonom yang dikuasai Belanda menjadi gewes
(identik dengan provinsi), regentschap (Kabupaten), dan Staatsgemeente
(Kotamadya). Pemerintah pendudukan Jepang pada dasarnya melanjutkan sistem pemerintahan daerah seperti zaman Belanda, dengan perubahan ke dalam bahasa Jepang (Kuncoro, 2006:3-5).
commit to user
sudah terlanjur biasa menunggu “petunjuk” dari pusat dan tuntunan dari atas. Setralisasi birokrasi maupun konsentrasi geografis aktifitas bisnis kearah pusat kekuasaan dan modal menjadi keniscayaan. Tak pelak, pembangunan pun bias kekawasan barat Indonesia, khususnya Jawa dan daerah Metropolitan (Kuncoro,2002).
Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang telah dilaksanakan sejak tahun 2001 adalah dalam rangka mendukung pencapaian
tujuan pembangunan nasional. Seiring dengan perubahan dinamika sosial
politik, Pemerintah telah melakukan revisi beberapa materi dalam
undang-undang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dengan ditetapkannya
Undang- Undang (UU) Nomor 12 tahun 2008 perubahan UU nomor 32 tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Substansi perubahan kedua undang-undang tersebut adalah semakin besarnya
kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahan dan keuangan
daerah. Diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan
aspirasi, kebutuhan, dan prioritas daerah, sehingga dapat memberikan dampak
positif bagi perkembangan ekonomi regional, yang pada gilirannya akan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desentralisasi fiskal sebagai salah
satu instrumen kebijakan Pemerintah mempunyai prinsip dan tujuan, antara
lain, untuk (1) mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan
pemerintah daerah (vertical fiscal imbalance) dan antardaerah (horizontal
commit to user
mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah; (3) meningkatkan
efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional; (4) tata kelola, transparan, dan
akuntabel dalam pelaksanaan kegiatan pengalokasian transfer ke daerah yang
tepat sasaran, tepat waktu, efisien, dan adil; dan (5) mendukung
kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro.
Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah agar meningkat, kepada
daerah diberikan kewenangan memungut pajak (taxing power). Instrumen
utama kebijakan desentralisasi fiskal adalah melalui kebijakan transfer ke
daerah, yang terdiri atas dana perimbangan dan dana otonomi khusus. Dana
perimbangan tersebut terdiri atas dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum
(DAU), dan dana alokasi khusus (DAK), yang merupakan komponen terbesar
dari dana transfer ke daerah. Selain dana desentralisasi tersebut, Pemerintah
juga mengalokasikan dana untuk membiayai program dan kegiatan yang
menjadi kewenangan Pemerintah di daerah, yaitu dana dekonsentrasi, dana
tugas pembantuan, dan dana untuk melaksanakan program dan kegiatan
instansi vertikal di daerah. Walaupun dana-dana tersebut tidak masuk dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), secara nyata dana
tersebut dibelanjakan di daerah, baik dalam bentuk belanja fisik maupun
nonfisik. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, kebijakan desentralisasi fiskal ke
depan perlu diarahkan pada upaya untuk melakukan reformulasi kebijakan
transfer dana desentralisasi, penguatan taxing power daerah, dan sinkronisasi
antara dana desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Upaya
commit to user
percepatan penetapan APBD, penerapan APBD yang berbasis kinerja, dan
penerapan penganggaran jangka menengah. Untuk mengejar pembangunan di
beberapa daerah yang masih tertinggal dibutuhkan dana yang cukup besar,
terutama untuk investasi awal di bidang infrastruktur. Efektivitas percepatan
pembangunan di beberapa daerah tersebut, kebijakan belanja daerah harus
lebih diarahkan kepada program-program riil yang langsung menyentuh
kehidupan masyarakat. Keberhasilan desentralisasi fiskal dalam mendorong
pembangunan daerah harus didukung pula oleh peran sektor swasta dan
penciptaan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi daerah, di
samping adanya pengaruh dari dinamika perkembangan ekonomi
global.(APBN 2009, Bab V-1).
Sejarah sistem hubungan keuangan pusat daerah diawali dari
Undang-undang (UU) pertama yang mengatur hubungan fiskal (keuangan)
pusat-daerah adalah UU No. 32 tahun 1956. UU ini menetapkan sumber-sumber
keuangan daerah sebagai berikut (Kristiadi,1991) : (1) Pendapatan Asli
Daerah (PAD) : Sumber PAD terdiri dari Pajak daerah, retribusi daerah dan
hasil perusahaan daerah. Adapun pajak pusat yang diserahkan kepada daerah
meliputi pajak verponding, pajak verponding Indonesia, pajak rumah tangga,
pajak kendaraan bermotor, pajak jalan, pajak potong hewan, pajak kopra dan
pajak pembangunan 1; (2) Sebagian dari hasil pemungutan pajak negara
tertentu, bea masuk, bea keluar dan cukai diserahkan kepada daerah. Pajak
commit to user
kekayaan dan pajak perseroan; (3) Ganjaran, subsidi dan bantuan diberikan
kepada daerah dalam hal-hal tertentu.
Pajak serta ganjaran dan bantuan yang tidak dapat dilaksanakan
berdasarkan UU No.32 tahun 1956 (Kristiadi, 1991) : (1) Penyerahan
tambahan tiga pajak negara kepada daerah yaitu bea balik nama kendaraan
bermotor, pajak radio dan pajak bangsa asing. Dengan demikian daerah
memungut 11 macam pajak; (2) Subsidi Daerah Otonom (SDO) diberikan
sebagai ganti dari hasil pajak diatas. Pembagian SDO didasarkan pda
perimbangan jumlah pegawai daerah otonom, dengan alasan penggunaan
SDO diarahkan kepada gaji pegawai daerah otonom ditambah across untuk
belanja non pegawai, yang kemudian digunakan untuk subsidi biaya
operasional serta ganjaran untuk Dati I, Dati II dan Kecamatan; (3) Sebagai
ganti ganjaran, subsidi dan bantuan diperkenalkan program bantuan Inpres
sejak tahun 1969; (4) Pinjaman kepada daerah dimulai dengan bantuan uang
IPEDA (tahun 1969), bantuan Inpres Pasar (tahun 1976) dan pinjaman lain
(tahun 1978).
Berpijak pada tiga asas desentralisasi (dekonsentrasi, desentralisasi
dan tugas pembantuan), pengaturan hubungan keuangan pusat-daerah
didasarkan atas 4 prinsip (lihat gambar 1) : (1) Urusan yang merupakan tugas
pemerintah pusat di daerah dalam rangka dekonsentrasi dibiayai dari dan atas
beban APBN; (2) Urusan yang merupakan tugas pemerintah daerah sendiri
dalam rangka desentralisasi dibiayai dari dan atas beban APBN; (3) Urusan
commit to user
2005 43.547,11 6.957,12 15,98 19.228,26 44,16 1.382,93 3,18 15.978,79 36,69
2006 42.848,55 8.072,13 18,84 23.408,35 54,63 4.102,72 9,57 7.265,35 16,96
2007 52.019,76 8.859,37 17,03 29.636,22 56,97 2.755,40 5,30 10.768,76 20,70
2008 65.257,98 10.454,24 16,02 37.682,51 57,74 3.678,29 5,64 13.442,94 20,60
2009 65.561,03 11.958,35 18,24 37.083,97 56,56 4.504,71 6,87 12.014,00 18,32
Laba
Sumber : DPPKAD Kabupaten Sragen, 2009
atasnya, yang melaksanakan dalam rangka tugas pembantuan, dibiayai oleh
pemerintah pusat atas beban APBN atau oleh pemerintah daerah tingkat
atasnya atas beban APBD sebagai pihak yang menugaskan; (4) Sepanjang
potensi sumber-sumber keuangan daerah belum mencukupi, pemerintah pusat
memberikan sejumlah sumbangan.
Tabel 1.1 di bawah menunjukkan bahwa APBD selam lima tahun yaitu tahun 2005-2009 masih didominasi oleh dana perimbangan berkisar 78%-86% dengan demikian bahwa dana perimbangan merupakan sumber pembiayaan APBD Kabupaten Sragen. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kontribusi sebesar 7% - 10%, kontribusi dari sumber dana dari lain-lain pendapatan yang sah sebesar maksimal 4,9%. Secara nyata terbukti bahwa PAD di Kabupaten Sragen belum dapat memberikan kontribusi secara signifikan terhadap APBD. Untuk selanjutnya maka perlu digali potensi-potensi daerah yang bersumberkan dari pajak, retribusi, laba BUMD & Asset daerah maupun dari Lain-lain PAD yang sah.
commit to user
Sumber APBD Kabupaten Sragen masih tergantung pada pemerintah pusat dibandingkan dengan pendapatan asli daerah. Dengan demikian di Kabupaten Sragen masih diperlukan upaya-upaya untuk digali potensi-potensi yang ada agar meningkatkan pendapatan pendapatan asli daerah sehingga pembangunan dapat merata dan dapat dinikmati oleh masyarakat. Sumber pendapatan asli daerah meliputi : (i) Hasil pajak daerah, (ii) Hasil Retribusi daerah, (iii) Hasil perusahaan milik daerah, (iv) Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sumber pendapatan tersebut diharapkan menjadi sumber-sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan rakyat. Sektor pajak dan reitribusi daerah merupakan sektor pendapatan asli daerah yang diterima secara rutin. Penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah untuk tiap-tiap daerah berbeda-beda, tergantung pada pengelolaan yang dilakukan oleh dinas pendapatan daerah yang bersangkutan.
Pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah atas penyediaan jasa, pemerintah daerah telah menyederhanakan berbagai jenis retribusi berdasarkan penggolongan jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah. Menurut UU No. 28 tahun 2009 perubahan atas UU No. 34 tahun 2000 dan
diatur dalam PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah terdiri dari : (i)
commit to user
2005 417.459,18 43.547,11 10,43 331.267,84 79,35 20.456,95 4,90
2006 447.085,93 42.848,55 9,58 352.180,71 78,77 16.963,00 3,79 2007 655.461,90 52.019,76 7,94 565.911,94 86,34 0,00 0,00
2008 815.055,56 65.257,98 8,01 649.194,03 79,65 26.096,28 3,20
2009 890.673,10 65.561,03 7,36 706.037,83 79,27 32.535,33 3,65 Sumber : DPPKAD Kabupaten Sragen, 2009
Sumber APBD
Tahun
APBD (Jutaan rupiah)
pajak daerah perlu ditingkatkan sehingga Pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.
Tabel 1.2 dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah tahun 2005-2009 dari pajak daerah sebesar 6% - 11%, retribusi daerah sebesar 44% - 57%, laba BUMD & aset daerah sebesar 3% - 9%, lain-lain PAD yang sah sebesar 16% - 36%. Sudah jelas bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sragen yang terbesar dari realisasi retribusi daerah.
Tabel 1.2 Realisasi PAD Kabupaten Sragen Tahun 2005-2009
Melaksanakan ketentuan pasal 18 ayat (3), pasal 22 dan pasal 33 Undang-undang nomor 28 tahun 2009 perubahan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah dengan jelas diterangkan berbagai retribusi.
Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2001 dijelaskan :
commit to user
tertentu. Pasal 2 ayat (2) Jenis-jenis jasa umum adalah : (a) Retribusi Pelayanan Kesehatan; (b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; (c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil; (d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; (e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; (f) Retribusi Pelayanan Pasar; (g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; (h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; (i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; (j) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan. Pasal 2 ayat(2) Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah (a) Retribusi Pelayanan
Kesehatan; (b) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan; (c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil; (d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; (e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; (f) Retribusi Pelayanan Pasar; (g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; (h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; (i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; (j) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan. Pasal 3 ayat (2) Jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah : (a) Retribusi
commit to user
di Atas Air; (l) Retribusi Pengolahan Limbah Cair; (m) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
Pasal 4 ayat (2) Jenis-jenis perizinan tertentu adalah (a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; (b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; (c) Retribusi Izin Gangguan; (d) Retribusi Izin Trayek. Pasal 5 ayat (3) Rincian dari masing-masing jenis retribusi diatur dalam
Peraturan Daerah masing-masing.
Pasal 6 Selain jenis retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini, dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis retribusi lainnya sesuai kriteria yang ditetapkan dalam Undang-undang.
commit to user mendirikan bangunan, (b) Retribusi ijin gangguan/ keramaian, (c) Retribusi ijin trayek, (d) Retribusi ijin gangguan/ HO, (e) Retribusi ijin peruntukan penggunaan tanah, (f) Retribusi tanda daftar dan ijin industri, (g) Retribusi tanda daftar perusahaan, (h) Retribusi ijin usaha perdagangan, (i) Retribusi tanda daftar gudang, (j) Retribusi ijin ketenagakerjaan dan (k) Retribusi biaya pelayanan administrasi (leges).
Tabel 1.3 dijelaskan bahwa realisasi retribusi daerah tahun 2005-2009 retribusi pelayanan kesehatan membeerikan kontribusi sebesar 63% - 75%, dengan pertumbuhan dari tahun ke tahun bertambah, pada tahun 2009 pertumbuhan negatif dikarenakan pembiayaan rawat inap di Puskesmas untuk Jamkesmas belum disetorkan ke kas daerah. Sudah jelas bahwa kontribusi retribusi pelayanan kesehatan terbesar dari realisasi retribusi daerah.
Tabel 1.3 Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan Kabupaten Sragen Tahun 2005-2009
commit to user
Penerimaan dari pemberian izin mendirikan rumah sakit swasta; (iii) penerimaan dari jasa pendidikan tenaga kesehatan; (iv) penerimaan dari jasa pemeriksaan laboratorium; (v) penerimaan dari jasa pemeriksaan air secara kimia lengkap; (vi) penerimaan dari jasa balai pengobatan penyakit paru-paru (BP4); (vii) penerimaan dari jasa balai kesehatanmata masyarakat (BKMM); (viii) penerimaandari uji pemeriksaan spesimen; dan (ix) penerimaan dari jasa pelayanan rumah sakit.
commit to user
sendiri kabupaten/ kota perlu terus meningkatkan kemampuannya dalam pengelolaan keuangan daerah.
Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan murni daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli yang sah. Pendapatan daerah mempunyai peranan penting dalam keuangan daerah yang merupakan salah satu tolok ukur di dalam pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab secara proporsional. Retribusi daerah lebih beraneka ragam dan bervariasi antara daerah yang satu dengan yang lain. Semakin maju suatu daerah akan semakin banyak fasilitas atau jasa yang perlu disediakan untuk pemenuhan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat sehingga semakin banyak pula jasa-jasa retribusi yang dapat dipungut oleh daerah.
commit to user
terhadap variabel-variabel yang mempengaruhinya, misalnya pertumbuhan penduduk dan pendapatan.
Retribusi pelayanan kesehatan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan jaringannya. Semakin besar penerimaan dari sektor ini akan semakin luas pula jangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Usaha-usaha peningkatan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan dilakukan dengan cara : (a) Meningkatkan jumlah, jaringan pelayanan kesehatandi rumah sakit dan Puskesmas; (b) Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan; (c) Meningkatkan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat; dan (d) Meningkatkan pendidikan kesehatan kepada masyarakat sejak usia dini.
commit to user
Produk domestik adalah seluruh produk barang dan jasa serta hasil kegiatan ekonomi yang diproduksi diwilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk region tersebut. Wilayah domestik suatu region adalah meliputi wilayah yang berada di dalam batas geografis region tersebut seperti propinsi, kabupaten/ kota, kecamatan, atau desa. Produk regional adalah merupakan produk yang ditimbulkan oleh faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk suatu region (PDRB Kabupaten Sragen, 2010:11)
commit to user
Penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam perencanaan pembangunan daerah karena penduduk merupakan sumber daya manusia yang partisipasinya sangat diperlukan agar pelaksanaan hasil-hasil perencanaan dapat berjalan dengan baik. Penduduk juga merupakan motor penggerak pembangunan, juga dapat bertindak sebagai obyek, dimana ia akan menjadi salah target dalam setiap proses pembangunan. Analisis kependudukan sangat mendukung efisiensi dan efektifitas perencanaan pembangunan agar berhasil sebagaimana diharapkan.
Analisis demografi merupakan analisis statistik terhadap jumlah, distribusi dan komposisi penduduk serta komponen-komponen variasinya dan perubahan. Studi kependudukanmempersoalkan hubungan-hubungan antara demografi dan variabel dari sistem lain. Studi kependudukan mencakup analisis-analisis yang bertujuan untuk : (1) Memperoleh informasi dasar tentang distribusi penduduk, karakteristik dan perubahan-perubahanya; (2) Menerangkan sebab-sebab perubahan dari faktor dasar tersebut; (3) Menganalisis segala konsekwensi yang mungkin sekali terjadi di masa depan sebagai hasil perubahan-perubahan itu.
sumber-commit to user
sumber alam dan tenaga manusia; (6) Kesatuan dan perstuan bangsa; (7) Memperluas pertahanan dan keamanan nasional.
Pentingnya informasi mengenai kependudukan bagi seseorang perencana pembangunan daerah, tidak hanya menyangkut masalah kondisi sosial-ekonomi, kultur yang dianut, atau jenis kelamin saja melainkan juga keadaan mengenai jumlah penduduk, perkembangan antara kelahiran dan kematian, proyeksi penduduk dan sebagainya.
Aktivitas sehari-hari di suatu wilayah mempunyai kontribusi terhadap perekonomian yang ditempati dan menimbulkan berbagai konsekuensi yang berkaitan dengan hak maupun kewajiban. Pertambahan penduduk bermakna sebagai jumlah penduduk yang lebih banyak sehingga membutuhkan pelayanan kesehatan. Semakin banyak jumlah penduduk diharapkan semakin tinggi pula jumlah kunjungan pada setiap pelayanan kesehatan.
commit to user
yayasan yang masih mampu membayar/ klaim beban pembiayaan pelayanan kesehatan.
Berdasarkan uraian tersebut mendorong untuk meneliti dan lebih mencermati tentang penelitian dengan judul ” Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk, Jumlah Jamkesmas Terhadap Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Sragen Tahun 2007-2009”.
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut, bahwa seberapa besar pengaruh PDRB, jumlah penduduk, jumlah Jamkesmas, terhadap pendapatan retribusi pelayanan kesehatan, jika mempunyai pengaruh yang signifikan maka Puskesmas di Kabupaten Sragen akan diperluas jaringannya. Untuk itu pertanyaan peneliti yang diajukan adalah :
1. Apakah ada pengaruh PDRB, jumlah penduduk, jumlah Jamkesmas terhadap retribusi pelayanan kesehatan di Kabupaten Sragen Tahun 2007-2009 ?
commit to user C. Tujuan Penelitian
1. Tujuan umum
Mengetahui penerimaan retribusi pelayanan kesehatan di Kabupaten Sragen.
2. Tujuan khusus
a. Mengetahui pengaruh jumlah PDRB, jumlah penduduk, jumlah Jamkesmas terhadap penerimaan retribusi pelayanan kesehatan di Kabupaten Sragen Tahun 2007-2009.
b. Mengetahui faktor dominan antara PDRB, jumlah penduduk, jumlah Jamkesmas terhadap retribusi pelayanan kesehatan.
D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan dapat bermanfaat sebagai berikut : 1. Untuk memberikan kontribusi akademis yaitu untuk pengembangan ilmu
pengetahuan khususnya mengenai retribusi pelayanan kesehatan.
commit to user BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Otonomi Daerah
Otonomi daerah (otda) dicanangkan oleh pemerintah pusat tanggal 1 Januari 2001, banyak yang mempertanyakan apakah otomatis akan terjadi perubahan paradigma yang mendasar dan bersifat struktural. Pasalnya “lagu” yang berkumandang di seluruh provinsi, Kabupaten dan kota di Indonesia adalah sentralisasi (baca : kontrol dari pusat) yang dominan dalam perencanaan maupun implementasi pembangunan Indonesia (Kuncoro, 1995). Satu nusa, satu bangsa diterjemahkan dalam satu perencanaan dan satu komando pembangunan, keseragaman. Akibatnya para birokrat di daerah sudah terlanjur biasa menunggu “petunjuk” dari pusat dan tuntunan dari atas. Setralisasi birokrasi maupun konsentrasi geografis aktifitas bisnis kearah pusat kekuasaan dan modal menjadi keniscayaan. Tak pelak, pembangunan pun bias kekawasan barat Indonesia, khususnya Jawa dan daerah Metropolitan (Kuncoro,2002).
Salah satu fenomena paling mencolok dari hubungan antara sistem pemerintah daerah (Pemda) dengan pembangunan adalah ketergantungan Pemda yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Ketergantungann ini terlihat jelas dari aspek keuangan : Pemda kehilangan keleluasaan bertindak (Local
discretion) untuk mengambil keputusan-keputusan penting dan adanya campur
tangan pemerintah pusat yang tinggi terhadap Pemda. Pembangunan di daerah terutama fisik memang cukup pesat, tetapi tingkat ketergantungan fiskal antara
commit to user
daerah dengan pusat sebagai dari akibat pembangunan juga semakin besar. Ketergantungan fiskal terlihat dari relatif rendahnya pendapatan asli daerah (PAD) dan dominannya transfer dari pusat. Adalah ironis, kendati UU telah menggarisbawahi titik berat otonomi pada Kabupaten/kota, namun justru Kabupaten/kota-lah yang mengalami tingkat ketergantungan yang lebih tinggi dibanding provinsi (Kuncoro, 2004).
B. Penyediaan Barang Publik
Salah satu kewajiban pemerintah adalah menyediakan barang dan jasa
yang tidak dapat dihasilkan oleh fihak swasta. Masalah selanjutnya adalah,
seberapa besar pemerintah harus menyediakan barang publik,karena
keterbatasan kemampuan anggaran pemerintah. Penyediaan barang publik
dalam jumlah yang terlalu besar akan menyebabakan terjadinya pemborosan
sumber-sumber ekonomi, sebaliknya penyediaan barang dan jasa publik yang
terlalu sedikit akan menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Beberapa teori
telah dikemukakan oleh para ahli ekonomi, seperti Pigou, Bowen, Lindahl,
Samuelson dan teori anggaran.
A.C. Pigou berpendapat, bahwa penyediaan barang publik akan
memberi manfaat (utility) bagi masyarakat; sebaliknya pajak yang dikenakan
akan menimbulkan ketidakpuasan masyarakat (disutility). Semakin banyak
barang dan jasa publik disediakan pemerintah, maka tambahan manfaat yang
dirasakan oleh masyarakat akan semakin menurun. Hal ini analog dengan
commit to user
segelas air yang diberikan terus menerus kepada seseorang. Gelas pertama
akan memberikan kepuasan yang sangat besar. Gelas ketiga akan memberikan
kepuasan lebih kecil dan akhirnya gelas keenam, ketujuh, kedelapan dan
seterusnya mungkin tidak memberi kepuasan sama sekali.
Sebaliknya, semakin banyak barang dan jasa publik, semakin besar
biaya yang dibutuhkan dan konsekwensinya semakin besar pula pajak yang
dipungut dari masyarakat. Keadaan ini menyebabkan meningkatnya
ketidakpuasan masyarakat. Secara teoristis, penyediaan barang dan jasa publik
akan optimal, apabila kepuasan masyarakat yang diperoleh sama dengan
ketidakpuasan masyarakat dari pemungutan pajak. Kesulitan dari analisis ini
adalah, kepuasan dan ketidakkpuasan adalah merupakan suatu yang tidak dapat
diukur secara kuantitatif, karena analisisnya didasarkan pada rasa
ketidakpuasan marginal masyarakat dalam membayar pajak dan rasa kepuasan
marginal terhadap barang publik.
Teori yang dikemukakan oleh Bowen, Lindahl, Samuelson dan teori
anggaran, berusaha memberi jawaban mengenai berapa jumlah barang publik
yang harus disediakan pemerintah, sehingga kepuasan masyarakat terhadap
alokasi sumber ekonomi antara barang publik dan barang swasta tercapai
tingkat optimal. Teori yang dikemukakan Bowen mengenai penyediaan barang
publik, didasarkan pada teori harga seperti dalam penentuan harga pada barang
swasta.
Lindahl mengemukakan analisisnya yang mirip dengan Bowen,
commit to user
menggunakan harga absolut, sementara Lindahl menggunakan harga relatif,
yaitu presentasi dari pembiayaan pemerintah total.
Samuelson juga mengemukakan teorinya dengan menggunakan
pendekatan biaya keseimbangan umum (general equilibrium). Ia
menyimpulkan bahwa adanya barang publik tidak menghambat masyarakat
untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang optimal (Pareto optimality).
Teori Samuelson mengenai pengeluaran pemerintah merupakan teori paling
baik, karena sederhana, jelas, dan komfrehensif. Namun inipun juga
mengandung beberapa kelemahan, misalnya pada anggapan bahwa konsumen
dapat mengemukakan kesukaan mereka terhadap barang publik. Hal ini
merupakan kelemahan hal yang mendasar dari analisis pengeluaran
pemerintah, karena masalah utamanya adalah bagaimana pemerintah
memungut pembayaran dari konsumen barang publik. Tidak seorangpun mau
dengan sukarela mengemukakan kesukaanya akan barang sosial karena
kesukaan ini akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam mengenakan tarif.
Selain itu apabila barang publik sudah tersedia, mereka tidak dapat
dikecualikan dari penggunaan barang tersebut. Kelemahan berikutnya adalah
barang publik yang dibahas mempunyai sifat kebersamaan yang dapat
digunakan konsumen dalam jumlah yang sama. Barang-barang publik yang
memiliki sifat tersebut praktis sangat terbatas, misalnya pertahanan,
kehakiman. Sementara itu sebagian besar dari barang publik tidak mengandung
commit to user
Teori lain yang menerangkan tentang penyediaan barang-barang
publik adalah teori alokasi barang sosial melalui anggaran. Teori ini didasarkan
suatu analisis bahwa setiap orang harus membayar pengunaan barang publik
dalam jumlah yang sama sesuai dengan sistem harga untuk barang swasta.
Semua teori ekonomi mengenai penyediaan barang publik diatas,
secara konseptual sangat baik. Sayangnya semua itu kurang bermanfaat untuk
diterapkan dalam praktek. Oleh karena itu untuk mendapatkan cara mengenai
penentuan jumlah barang publik perlu ”meminjam” teori yang dikembangkan
dalam ilmu politik yaitu pemungutan suara ”voting”. Pemungutan suara dapat
dilakukan dalam berbagai cara tetapi cara yang terbaik adalah dengan
aklamasi, dimana suatu program pemerintah akan dilaksanakan apabila semua
orang menyatakan setuju. Hasil yang diperoleh dengan cara aklamasi akan
sama dengan mekanisme pasar sehingga dapat dicapai hasil yang terbaik.
Namun demikian cara aklamasi inipun dalam praktek juga sering sulit
direalisasikan sehingga muncul alternatif lain mengenai jumlah suara minimal
yang diperlukan dalam suatu pemungutan suara. Pada awalnya teori ini
dikemukakan oleh Knut Wicksell. Ia berpendapat bahwa sistem yang baik
adalah apabila 2/3 suara menyatakan persetujuannya. Buchanan-Tullock
kemudian mencoba memberikan jawaban bahwa pemungutan suara harus
dilakukan dengan cara meminimalkan biaya pemungutan suara.
Sistem pemungutan suara dengan sistem mayoritas sederhana (simple
majority), dalam memilih dua atau lebih program pemerintah, dapat terjadi
commit to user
Untuk menghindarinya maka dapat ditempuh beberapa cara altrnatif, seperti,
plural voting, point voting dan sebagainya. Pemungutan suara dengan cara
pemilihan langsung sulit dilakukan dinegara-negara yang berpenduduk sangat
banyak karena faktor pembiayaan. Pemungutan suara untuk memilih program
pemerintah dilakukan secara demokratis melalui perwakilan rakyat. Tetapi
masalahnya adalah apakah dengan cara ini dapat dijamin bahwa suara wakil
rakyat selaras dengan kehendak rakyat yang diwakilinya. Schumpeter dan A.
Down menunjukkan bahwa karena dengan adanya motivasi dan rasa
individualistik dari rakyat dan wakil rakyat maka akan ada jaminan keserasian
antara pilihan wakil rakyat dan kehendak rakyat (A.Tony Prasentiantono,
1994:16-20).
C. Kebijakan Desentralisasi
Sejalan dengan tuntutan demokratisasi dalam bernegara,
penyelenggaraan pemerintahan juga mengalami perubahan. Sistem
pemerintahan yang semula lebih condong pada sentralisasi menjadi
desentralisasi. Selaras dengan perubahan sistem tersebut, maka tata aturan juga
mengalami perubahan yang lebih mengarah kepada penyempurnaan
pelaksanaan otonomi daerah, melalui pemberian kewenangan yang
seluas-luasnya dengan tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI). Berbagai penyempurnaan dilakukan seperti yang tertuang dalam UU
Nomor 33 Tahun 2004, yang merupakan penyempurnaan dari UU Nomor 25
sumber-commit to user
sumber pendanaan untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah
berdasarkan kewenangan Pemerintah, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas
pembantuan, perlu diatur melalui perimbangan keuangan antara Pemerintah
dan pemerintahan daerah, yang berupa sistem keuangan yang diatur
berdasarkan kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antarsusunan
pemerintahan.
Hakikat penyempurnaan utamanya menjaga prinsip money follows
function, artinya pendanaan mengikuti fungsi-fungsi pemerintahan sehingga
kebijakan perimbangan keuangan mengacu kepada 3 prinsip yakni (1)
perimbangan keuangan antara Pemerintah dengan pemerintahan daerah
merupakan subsistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas
antara Pemerintah dan pemerintah daerah; (2) pemberian sumber keuangan
negara kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada pemerintah daerah
dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal; dan (3)
perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah merupakan
suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas
desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Mempertegas
perimbangan keuangan sebagai unsur utama dalam kebijakan desentralisasi
fiskal, maka pelaksanaan tiga paket undang-undang di bidang keuangan
negara, yakni UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15
commit to user
Negara merupakan acuan dasar pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2004,
khususnya pengaturan komponen dana perimbangan yang terdiri atas DBH,
DAU, dan DAK.
Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 1999, maka penyempurnaan yang
dimuat dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 antara lain (1) DBH Pajak, yang
meliputi DBH PBB dan DBH BPHTB, ditambah dengan DBH PPh wajib pajak
orang pribadi dalam negeri (WPOPDN); (2) DBH SDA kehutanan, dengan
mengakomodir dana reboisasi, yang semula merupakan DAK-DR; dan (3)
DBH SDA, yang meliputi SDA minyak bumi, gas alam, pertambangan umum,
kehutanan dan perikanan, ditambahkan dengan DBH Panas Bumi. Pelaksanaan
kebijakan perimbangan keuangan dalam tatanan keuangan negara yang semula
termasuk dalam kategori belanja ke daerah juga disempurnakan secara
bertahap. Penyempurnaan tersebut meliputi pola pembagian DBH yang lebih
transparan dan akuntabel, penyempurnaan formulasi DAU yang dilakukan
secara konsisten dan mengarah kepada fungsi pemerataan kemampuan
keuangan daerah, serta penyempurnaan terhadap penerapan kriteria penentuan
DAK.
Penyempurnaan juga dilakukan untuk memenuhi ketentuan
perbendaharaan negara, sehingga sejak tahun 2008 sebagai pelaksanaan
pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum
daerah, belanja ke daerah dikategorikan sebagai transfer ke daerah. Diharapkan
arah kebijakan desentralisasi fiskal dalam pelaksanaannya menjadi lebih
commit to user
Pemerintah juga memberikan perhatian yang besar terhadap sumber PAD. Hal
ini dimaksudkan agar daerah dapat memungut sumber-sumber pendapatannya
secara optimal sesuai dengan potensi tiap-tiap daerah. Pelaksanaan
pemungutannya tidak boleh menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan tetap
menciptakan iklim yang kondusif bagi para investor.
Pemerintah dan DPR saat ini telah melakukan perubahan UU Nomor
34 Tahun 2000 menjadi UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah untuk memperkuat taxing power daerah dan meningkatkan
kepastian hukum di bidang perpajakan daerah. Sumber-sumber PAD yang
sebagian besar terdiri atas pajak daerah dan retribusi daerah diatur oleh
undang-undang tersendiri, yang memberikan kewenangan kepada daerah
provinsi dan Kabupaten/kota untuk memungut pajak dan retribusi.
Undang-undang tersebut juga diatur jenis-jenis pajak dan retribusi yang dipungut
provinsi dan Kabupaten/kota, sehingga dapat dihindari adanya tumpang tindih
pemungutan pajak atau satu objek pajak dikenai dua atau lebih pungutan pajak.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat pendanaan daerah dalam
menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan masyarakat. APBD
mengalami defisit, pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman. Pelaksanaan
pinjaman daerah harus mengikuti kriteria dan persyaratan yang ditetapkan oleh
Pemerintah, seperti pemerintah daerah tidak dapat melakukan pinjaman
langsung ke luar negeri, jumlah pinjaman tidak boleh lebih dari 75 persen
commit to user
persen. ( APBN 2009, Bab V Kebijakan Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan
Keuangan Daerah)
Pengelolaan keuangan, daerah diberikan keleluasaan, sehingga dapat
mengalokasikan dananya sesuai dengan kebutuhan daerah dengan tetap
mengacu pada peraturan perundangan. Alokasi dana transfer Pemerintah yang
sebagian besar telah diberikan diskresi sepenuhnya kepada pemerintah daerah.
Pengelolaan keuangannya, daerah harus melakukan secara tertib, efisien,
ekonomis, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para
pemangku kepentingan. Seluruh penerimaan dan pengeluaran daerah yang
menjadi hak dan kewajiban harus diadministrasikan dalam APBD. Pengelolaan
keuangan daerah selain dilakukan secara efektif dan efisien diharapkan dapat
mendukung terwujudnya tata kelola pemerintah daerah yang baik bersandarkan
pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Pengelolaan keuangan daerah,
telah dilakukan juga perubahan yang cukup mendasar antara lain mengenai
bentuk dan struktur APBD, anggaran berbasis kinerja, klasifikasi anggaran, dan
prinsip- prinsip akuntansi.
1. Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan kegiatan
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan
keuangan daerah secara umum mengacu pada paket reformasi keuangan
negara, yang dituangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan,
commit to user
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,
UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Subsistem dari pengelolaan keuangan negara dan merupakan
kewenangan pemerintah daerah, pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah
diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur secara komprehensif dan
terpadu (omnibus regulation) ketentuan-ketentuan dalam bidang
pengelolaan keuangan daerah, dengan mengakomodasi berbagai substansi
yang terdapat dalam berbagai undang-undang di atas. Peraturan
perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah, diharapkan dapat
mengharmoniskan pengelolaan keuangan daerah, baik antara Pemerintah
dan pemerintah daerah, serta antara pemerintah daerah dan DPRD, ataupun
antara pemerintahan daerah dan masyarakat. Daerah dapat mewujudkan
pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien, serta dapat mewujudkan
tata kelola pemerintahan yang baik, berdasarkan tiga pilar utama, yaitu
transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 memuat berbagai kebijakan terkait dengan perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses
commit to user
pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala
prioritas dan penetapan alokasi, serta distribusi sumber daya dengan
melibatkan partisipasi masyarakat. Proses dan mekanisme penyusunan
APBD dapat memperjelas jenjang tanggung jawab, baik antara pemerintah
daerah dan DPRD, maupun di lingkungan internal pemerintah daerah.
Pengelolaan keuangan daerah juga menerapkan prinsip anggaran berbasis
kinerja.
Dokumen penyusunan anggaran yang disampaikan oleh tiap-tiap
satuan kerja perangkat daerah (SKPD) disusun dalam format rencana kerja
dan anggaran (RKA) SKPD dan harus betul-betul dapat menyajikan
informasi yang jelas, tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran
anggaran (beban kerja dan harga satuan), dengan manfaat dan hasil yang
ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang
dianggarkan. Penerapan anggaran berbasis kinerja mengandung makna
bahwa setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk bertanggung jawab
atas hasil proses dan penggunaan sumber dayanya. Keterkaitan antara
kebijakan perencanaan dengan penganggaran oleh pemerintah daerah
sedemikian rupa, sehingga sinkron dengan berbagai kebijakan Pemerintah.
Sisi pelaksanaan APBD telah diatur mengenai pemberian peran dan
tanggung jawab pengelola keuangan, sistem pengawasan pengeluaran dan
sistem pembayaran, manajemen kas dan perencanaan keuangan,
pengelolaan piutang dan utang, pengelolaan investasi, pengelolaan barang
commit to user
yang dikuasai negara/daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban
APBD, serta akuntansi dan pelaporan. Pengaturan bidang akuntansi dan
pelaporan dilakukan dalam rangka menguatkan pilar akuntabilitas dan
transparansi.
Pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan,
pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa (1)
laporan realisasi anggaran; (2) neraca; (3) laporan arus kas; dan (4) catatan
atas laporan keuangan. Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 24
Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan PP Nomor 8 Tahun
2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Menilai
ketaatan dan kewajaran sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui
DPRD, laporan keuangan perlu diperiksa terlebih dahulu oleh Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai UU Nomor 15 Tahun 2004.
Implementasinya penerapan pengelolaan keuangan daerah telah
ditindaklanjuti dengan berbagai peraturan teknis sebagai acuan pelaksanaan
bagi setiap pemerintah daerah, antara lain dituangkan dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Aspek tata urutan dan
kelengkapan peraturan perundang-undangan, masih banyak daerah yang
belum memiliki peraturan daerah dan peraturan kepala daerah terkait
commit to user
Tahun 2005. Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah ini sangat
penting sebagai acuan bersama baik bagi eksekutif, legislatif, pemeriksa,
dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Dasar hukum keuangan daerah : (i) Undang- Undang Nomor 12 tahun
2008 perubahan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah
daerah; (ii) Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara;
(iii) Undnag-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan
antara pemerintah pusat dan pemerintah derah; (iv) Peraturan
perundang-undangan sebagai pedoman dan pengaturan operasional lain dalam
pengelolaan keuangan daerah :
a. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara.
Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan
dan tanggungjawab keuangan negara.
b. Peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2005 tentang pinjaman daerah.
c. Peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan.
d. Peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2005 tentang sistem informasi
keuangan daerah.
e. Peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2005 tentang hibah kepada daerah.
f. Peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan
derah.
g. Peraturan Menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman
commit to user
2. Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal
Perkembangan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal,
nomenklatur pendanaan desentralisasi dalam APBN juga mengalami
perubahan. Sejak tahun 2001-2007, dalam postur APBN nomenklatur untuk
pendanaan desentralisasi telah mengalami penyesuaian beberapa kali.
Anggaran yang didaerahkan disesuaikan menjadi belanja daerah, dan
terakhir sampai dengan tahun 2007 disesuaikan menjadi belanja ke daerah.
Mulai tahun 2008 nomenklatur tersebut berubah menjadi transfer ke daerah
yang selanjutnya ditetapkan pengaturannya dalam Bagan Akun Standar.
Pada tahun 2001, alokasi transfer ke daerah baru mencakup dana
perimbangan. Sejak tahun 2002, alokasi transfer ke daerah juga mencakup
dana otonomi khusus untuk Provinsi Papua sebagai pelaksanaan UU Nomor
21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, dan Dana
Penyeimbang (Dana Penyesuaian), yang dialokasikan kepada daerah-daerah
yang menerima DAU lebih kecil dari tahun sebelumnya. Mulai tahun 2008,
sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,
Pemerintah juga mengalokasikan dana otonomi khusus untuk Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), dengan nilai setara 2 persen dari pagu
DAU nasional selama 15 tahun, mulai tahun 16 sampai dengan tahun
ke-20 setara 1 persen dari pagu DAU nasional. Dilaksanakannya kebijakan
desentralisasi fiskal, perkembangan alokasi transfer ke daerah dari tahun
2001-2008 secara nominal terus meningkat, dari Rp81,1 triliun (4,8 persen
commit to user
terhadap PDB) pada tahun 2007, dan diperkirakan menjadi Rp293,6 triliun
(6,3 persen terhadap PDB) pada tahun 2008, atau rata-rata tumbuh 20,2
persen per tahun. Alokasi transfer ke daerah dapat dilihat pada Dalam kurun
waktu 2001-2008, dana perimbangan, yang merupakan komponen terbesar
dari transfer ke daerah, yang terdiri atas dana bagi hasil (DBH), dana alokasi
umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK), menunjukkan peningkatan
yang cukup signifikan, dari Rp81,1 triliun (4,8 persen terhadap PDB) pada
tahun 2001 menjadi Rp244,0 triliun (6,2 persen terhadap PDB) pada tahun
2007, dan diperkirakan mencapai Rp279,6 triliun (6,0 persen terhadap PDB)
pada tahun 2008, atau ratarata tumbuh 19,3 persen per tahun. Perkembangan
alokasi dana perimbangan dari tahun 2001—2008. (APBN 2009, Bab V
Kebijakan Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah)
3. Efektivitas Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah
Pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, provinsi
dan Kabupaten/kota juga diberikan kewenangan untuk memungut pajak dan
retribusi sebagaimana diatur dalam UU No. 28 tahun 2009 perubahan atas
UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
Berdasarkan undang-undang tersebut, terdapat 11 jenis pajak daerah, yaitu 4
jenis pajak provinsi dan 7 jenis pajak Kabupaten/kota. Jenis pajak provinsi
ditetapkan secara limitatif, sedangkan pajak Kabupaten/ kota selain yang
ditetapkan dalam undang-undang dapat ditambah oleh daerah sesuai dengan
commit to user
dalam undang-undang. Penetapan tarif definitif untuk pajak provinsi
ditetapkan dengan peraturan pemerintah, sedangkan tarif definitif untuk
pajak Kabupaten/kota diserahkan sepenuhnya kepada tiap-tiap daerah,
dengan mengacu kepada tarif tertinggi untuk masingmasing jenis pajak,
sebagaimana diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009. Pajak daerah diatur
dalam PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Retribusi daerah
dikelompokkan menjadi tiga golongan sesuai dengan jenis pelayanan dan
perizinan yang diberikan, yaitu sebagai berikut: (1) retribusi jasa umum, (2)
retribusi jasa usaha, dan (3) retribusi perizinan tertentu. Yang termasuk
golongan jasa umum adalah pelayanan yang wajib disediakan oleh
pemerintah daerah.
Pemungutan jenis retribusi yang termasuk dalam golongan Jasa
Usaha dilakukan sesuai dengan pelayanan yang diberikan oleh daerah. Jenis
retribusi daerah juga diberikan kewenangan untuk memungut jenis retribusi
baru sesuai dengan kriteria retribusi yang ditetapkan dalam undang-undang.
Jenis retribusi selengkapnya sebagai berikut :
a) Golongan Retribusi Jasa Umum
1) Retribusi pelayanan kesehatan;
2) Retribusi pelayanan persampahan / kebersihan;
3) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte;
4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
5) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ;
commit to user
7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
9) Retribusi penggantian cetak peta;
10) Retribusi pengujian kapal perikanan;
b) Golongan retribusi Jasa Usaha
1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
2) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
3) Retribusi tempat pelelangan;
4) Retribusi terminal;
5) Retribusi tempat khusus parkir;
6) Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
7) Retribusi penyedotan kakus;
8) Retribusi rumah potong hewan;
9) Retribusi pelayanan pelabuhan kapal;
10) Retribusi tempat rekreasi dan olah raga;
11) Retribusi penyeberangan diatas air;
12) Retribusi pengelolaan limbah cair;
13) Retribusi penjualan produk usaha daerah;
c) Golongan Retribusi Perijinan Tertentu
1) Retribusi izin mendirikan bangunan;
2) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
3) Retribusi izin gangguan;
commit to user
Peningkatkan PAD pemerintah daerah cenderung untuk memungut
berbagai jenis pajak dan retribusi selain yang telah ditetapkan dalam
undang-undang dan peraturan pemerintah, meskipun hasilnya kurang signifikan.
Setiap daerah mengenakan lebih dari 10 jenis retribusi baru dengan hasil yang
sangat kecil. Penerimaan retribusi yang memberikan hasil yang relatif besar
adalah retribusi yang berkaitan dengan pemanfaatan hasil hutan dan
pertambangan, yang sebenarnya telah dikenakan pungutan sejenis oleh
Pemerintah. Sebagian besar pungutan tersebut, baik pajak maupun retribusi
mempunyai kaitan dengan lalu-lintas barang, misalnya pengenaan
pajak/retribusi atas pengeluaran dan pemasukan barang, hasil-hasil bumi,
hewan dan ternak, serta retribusi atas penggunaan jalan umum. Sebagian
lainnya adalah retribusi yang berkaitan dengan pelayanan administrasi
pemerintahan, seperti penerbitan izin usaha, rekomendasi, legalisasi surat,
dan administrasi lainnya, yang seharusnya dapat dibiayai dari penerimaan
umum daerah.
Pengenaan pajak dan retribusi baru tersebut cenderung mendorong
terjadinya ekonomi biaya tinggi dan tidak kondusif bagi iklim investasi,
karena investor dihadapkan dengan berbagai macam pemungutan sehingga
dapat meningkatkan biaya pemenuhan penerimaan pajak dan retribusi
(compliance cost). Pajak dan retribusi baru yang bermasalah telah dibatalkan
oleh Pemerintah. Pembatalan tersebut dilakukan juga karena tidak memenuhi
kriteria sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Retribusi
commit to user
bersifat pajak belum dibatalkan. Pemberikan ruang bagi daerah dalam
meningkatkan penerimaan dan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi.
Kecenderungan daerah untuk menciptakan jenis pajak dan retribusi baru
disebabkan karena UU No.28 Tahun 2009 telah memberikan ruang bagi
daerah untuk menciptakan berbagai jenis retribusi dan pajak baru untuk
Kabupaten/kota. Akan tetapi, ruang ini dimanfaatkan hampir semua daerah
tanpa memperhatikan kriteria sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang.
4. Retribusi Pelayanan Kesehatan
Pelaksanaan Undang-undang No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dan peraturan pelaksanaannya serta untuk mewujudkan otonomi daerah di Kabupaten Sragen maka perlu diupayakan intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan sebagai peningkatan pendapatan asli daerah. Peningkatan kesehatan masyarakat serta meningkatan pendapatan daerah maka perlu dengan adanya pengaturan pemungutan retribusi di Puskesmas. Pemungutan retribusi bisa dilaksanakan dengan tertib maka perlu diatur pelayanan kesehatan pada rumah sakit dan Puskesmas dengan peraturan daerah.
commit to user
orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan. Bukan termasuk askes wajib (PNS/TNI/POLRI/Veteran), askes sosial ( Jamkesmas / JPS), surat keterangan tidak mampu yang disahkan oleh pejabat yang berwewenang dan gratis; (Pasal 7) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah pelayanan, jenis pelayanan, pemakaian alat pelayanan kesehatan dan kelas serta waktu pelayanan yang diterima oleh wajib retribusi di Puskesmas atau Puskesmas perawatan; (Pasal 8) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya administrasi rawat jalan, rawat inap, kunjungan rumah, tindakan medis dan pemeriksaan penunjang diagnostik kepada pribadi dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
D. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB Adhb) adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah (region). Nilai tambah yaitu merupakan nilai yang ditambahkan kepada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input antara. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa atas ikut sertanya faktor produksi dalam proses produksi.
NTB = Nilai produksi (output) – biaya antara