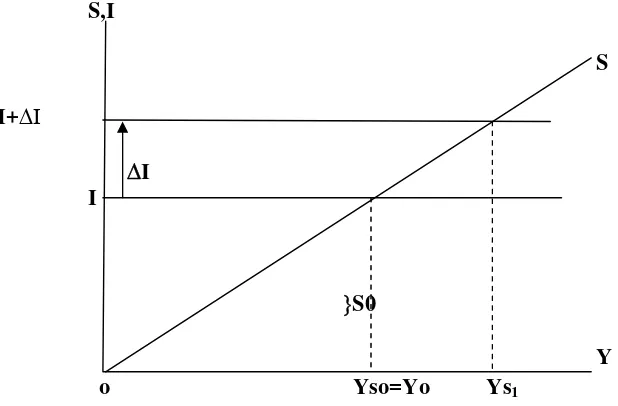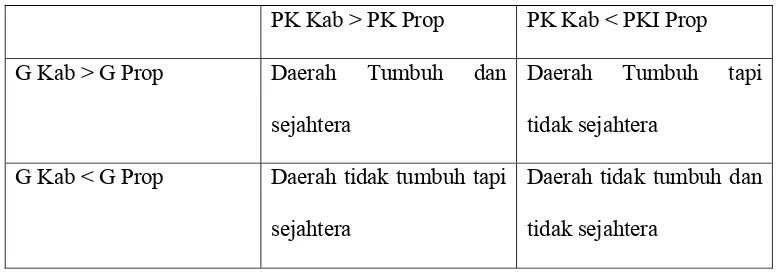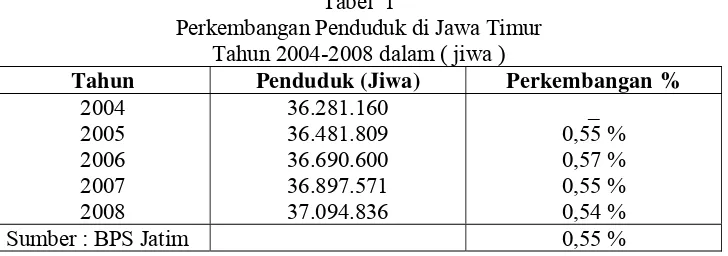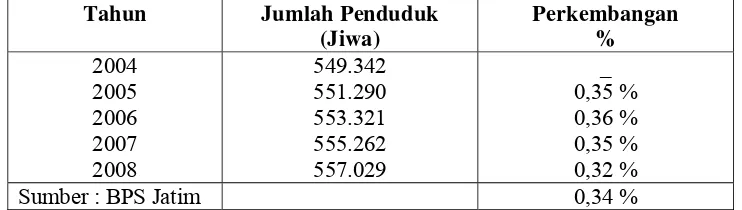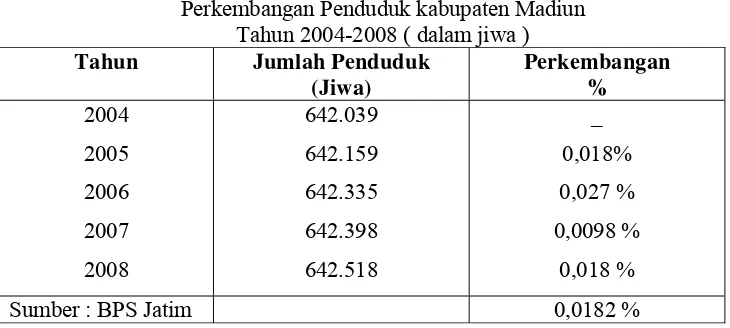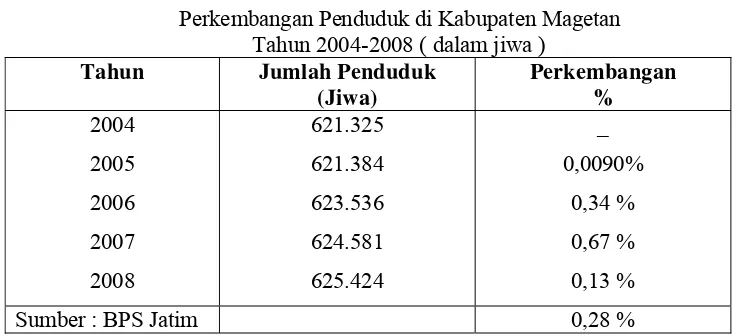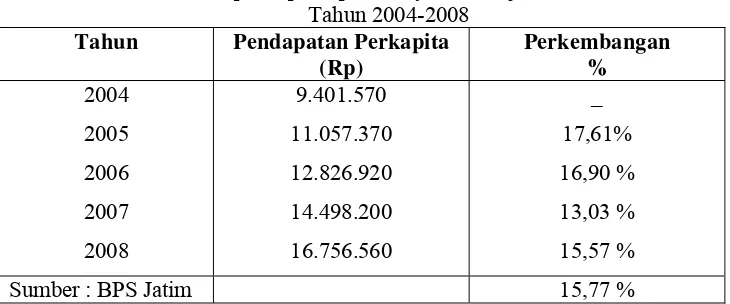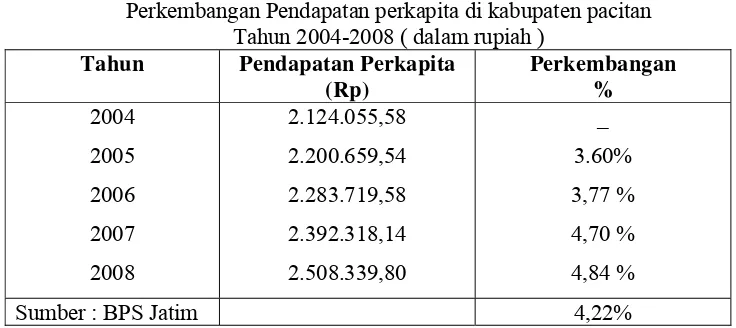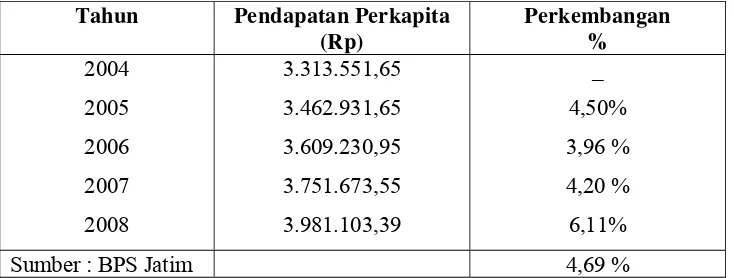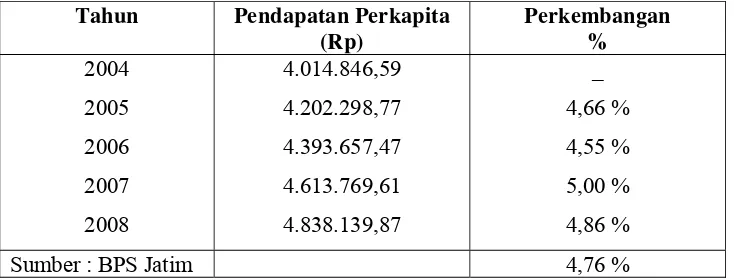SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Ekonomi Pembangunan
Yang Diajukan: RETNO ASIH JUWITASARI
0511010176 / EP
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
JAWA TIMUR
i Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah
memberikan segala rahmat, karunia dan pertolongan-Nya, sehingga skripsi yang
berjudul ANALISIS KESENJANGAN PEMBAGIAN PENDAPATAN
PERKAPITA DAN TIPOLOGI DAERAH DI KABUPATEN PACITAN, MAGETAN, MADIUN dapat terselesaikan dengan lancar dan tepat waktu.
Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh
mahasiswa jenjang pendidikan Strata-1 (Sarjana) Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas
Ekonomi, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur guna
memperoleh gelar kesarjanaan.
Dalam penyusunan skripsi ini, dengan segala kerendahan hati, penulis
ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
Bapak Drs. Ec. Wiwin Priana,MT, selaku Dosen Pembimbing yang telah
meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, saran dan motivasi selama
proses penyelesaian penyusunan skripsi ini.
Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima
kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pikiran, waktu dan
tenaga serta bantuan moril dan materiil khususnya kepada:
1. Bapak Prof. Dr. Ir. Teguh Soedarto, MP, selaku Rektor Universitas
ii
3. Bapak Drs. Ec. Marseto DS, MSi, selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Studi
Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional
“VETERAN” Jawa Timur.
4. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan
Nasional “Veteran” Jawa Timur, yang telah membekali kami dengan
pengetahuan-pengetahuan yang sangat berguna dan berharga.
5. Pimpinan dan Staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan
Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Papa Ir. H. Mudjianto, Sp dan Mama Hj. Evy Rosiana, adikku Rohman
Prayogi, dan buah hatiku Rengganis Putri Arasy, beserta semua anggota
keluargaku yang telah memberikan dukungan, doa, semangat dan dorongan
moral serta spiritualnya yang tulus kepada penulis, sehingga penulis dapat
menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
7. Seluruh Teman-temanku dan seseorang yang berarti bagi penulis yang telah
membantu memberikan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat
terselesaikan.
Semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, baik
sebagai bahan kajian maupun sebagai salah satu sumber informasi.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Surabaya, 22 Oktober 2010
iii
KATA PENGANTAR ... i
DAFTAR ISI ... iii
DAFTAR GAMBAR ... viii
DAFTAR TABEL ... ix
DAFTAR LAMPIRAN ... xi
ABSTRAKSI ... x
BAB I PENDAHULUAN ... 1
1.1 Latar belakang ... 1
1.2 Rumusan masalah ... 4
1.3 Tujuan Penelitian ... 4
1.4 Manfaat Penelitian ... 5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 6
2.1 Penelitian Sebelumnya ... 6
2.2 Landasan Teori ... 10
2.2.1 Konsep Tentang Daerah ... 10
2.2.1.1 Perencanaan Pembangunan ... 12
2.2.1.2 Konsep Pembangunan Regional ... 13
2.2.1.3 Uraian Sektoral ... 17
2.2.2 Pertumbuhan Ekonomi ... 18
iv
2.2.3.2 Pendekatan Perhitungan Produk Domestik
Regional Bruto... 23
2.2.4 Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita... 25
2.2.4.1Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan ... 26
2.2.4.2Teori pertumbuhan Harrod-domar... 28
2.2.5 Pengertian Sektor-Sektor Ekonomi ... 32
2.2.5.1 Sektor Pertanian ... 32
2.2.5.2 Sektor Pertambangan dan Penggalian... 33
2.2.5.3 Sektor Industri Pengolahan ... 33
2.2.5.4 Klasifikasi Industri ... 34
2.2.5.5 Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih... 35
2.2.5.6 Sektor Bangunan ... 36
2.2.5.7 Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran... 36
2.2.5.8 Sektor Angkutan dan Komunikasi ... 37
2.2.5.9 Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan... 38
2.2.5.10 Sektor Jasa... 38
2.2.6 Analisis Tipologi Daerah... 39
2.3 Kerangka Pikir ... 40
v
3.2. Jenis dan Sumber Data ... 44
3.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data ... 44
3.4. Teknis Analisis ... 45
BAB IV HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN ... 47
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian... 47
4.1.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian ... 47
4.1.1.1Kondisi Umum Kabupaten Pacitan ... 47
4.1.1.1.1 Letek Geografis... 47
4.1.1.1.2 Struktur Pemerintah ... 48
4.1.1.1.3 Penduduk... 48
4.1.1.2Kondisi Umum Kabupaten Madiun... 49
4.1.1.3Kondisi Umum Kabupaten Magetan ... 49
4.2 Deskripsi hasil Penelitian ... 50
4.2.1 Penduduk ... 50
4.2.2 Penduduk Jawa Timur ... 50
4.2.3 Perkembangan Penduduk Kabupaten Pacitan ... 51
4.2.4 Perkembangan Penduduk Kabupaten Madiun ... 52
4.2.5 Perkembangan Penduduk di Kabupaten Magetan... 52
4.3 Perkembangan Pendapatan Perkapita ... 53
vi
4.3.3 Perkembangan pendapatan Perkapita Kabupaten
Madiun ... 55
4.3.4 Perkembangan Pendapatan Perkapita di Kabupaten Magetan ... 56
4.3.5 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Jawa Timur ... 57
4.3.6 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pacitan... 58
4.3.7 Pertumbuhan ekonomi kabupaten Madiun... 49
4.3.8 Pertumbuhan ekonomi kabupaten Magetan ... 60
4.4 Analisa dan Pengujian Hipotesa... 61
4.4.1 Uji Indeks Williamson ... 61
4.4.1.1Uji Indeks Williamson antara Pendapatan Perkapita dengan Penduduk Kabupaten Pacitan ... 62
4.4.1.2Uji Indeks Williamson antara Pendapatan Perkapita dengan penduduk kabupaten Madiun... 63
vii
4.4.2.1Indeks Williamson kabupaten Pacitan antara
Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk.. 65
4.4.2.2Indeks Williamson kabupaten Madiun antara pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk .. 66
4.4.2.3Indeks Williamson kabupaten Magetan antara pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk .. 67
4.4.3 Uji Tipologi Daerah ... 68
4.4.3.1Analisa Tipe Daerah Kabupaten Pacitan ... 68
4.4.3.2Analisa Type Daerah Kabupaten Madiun ... 69
4.4.3.3Analisa Daerah di Kabupaten Magetan ... 69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ... 71
5.1 Kesimpulan ... 71
5.2 Saran... 71
DAFTAR PUSTAKA
viii
ix
TABEL 1 : Perkembangan Penduduk di Jawa Timur tahun 2004-2008 ... 50
TABEL 2 : Jumlah Perkembangan Penduduk Pacitan tahun 2004-2008 ... 51
TABEL 3 : Jumlah Perkembangan Penduduk Madiun tahun 2004-2008 ... 52
TABEL 4 : Jumlah Perkembangan Penduduk Magetan tahun 2004-2008 ... 53
TABEL 5 : Pendapatan perkapita masyarakat di Jawa Timur Tahun 2004-2008 ... 54
TABEL 6 : Perkembangan Pendapatan perkapita Perkapita di Kabupaten Pacitan tahun 2004-2008 ... 55
TABEL 7 : Perkembangan Pendapatan perkapita Perkapita di Kabupaten Madiun tahun 2004-2008... 56
TABEL 8 : Perkembangan Pendapatan perkapita Perkapita di Kabupaten Magetan tahun 2004-2008 ... 57
TABEL 9 : Pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur tahun 2004-2008... 58
TABEL 10: Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pacitan tahun 2004-2008.... 59
TABEL 11 : Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Madiun tahun 2004-2008 ... 60
TABEL 12 : Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magetan Tahun 2004-2008 ... 61
TABEL 13 : Perhitungan Indeks Williamson di Kabupaten Pacitan Tahun 2004-2008 ... 62
x
TABEL 16 : Perhitungan Indeks Williamson di Kabupaten Pacitan antara
Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk tahun 2004-2008.. 65
TABEL 17 : Perhitungan Indeks Williamson di Kabupaten Madiun antara
Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk tahun 2004-2008.. 66
TABEL 18 : Perhitungan Indeks Williamson di Kabupaten Magetan antara
Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk tahun 2004-2008.. 67
xi
Lampiran 1 : Hasil Uji Indeks Williamson dengan menggunakan variabel
pendapatan perkapita dan Jumlah Penduduk di Kabupaten
Pacitan,Madiun dan Magetan
Lampiran 2 : Hasil Uji Indeks Williamson dengan mengganakan variabel
pertumbuhan ekonomi dan jumlah Penduduk di Kabupaten
xii Oleh:
Retno Asih Juwitasari
ABSTRAKSI
Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang lebih luas dari yang hanya memfokuskan pada perumbuhan ekonomi.peningkatan pembangunan ekonomi merupakan peningkatan jumlah produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu Negara atau daerah dalam kurun waktu tertentu yang lebih tinggi dari pada kenaikan jumlah penduduk sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah nyata termasuk di peningkatan pendapatan perkapita disertai perubahan struktur ekonomi suatu Negara tersebut dan terjadi dalam waktu jangka panjang.
Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Puat Statistik (BPS) Jawa Timur selama lima tahun yaitu dari tahun 2004-2008. Data yang dianalisis menggunakan Indeks Williamson yaitu suatu analisis untuk mengetahui daerah kabupaten Pacitan,Magetan Dan Madiun mana yang mempunyai korelasi atau kontribusi yang bagus terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi Jawa Timur.
Berdasarkan hasil analisis dan pengujian Indeks Williamsson semua daerah di Kabupaten Pacitan,Magetan dan Madiun mengalami kesenjangan dan hipotesa tidak terbukti. Akan tetapi semua daerah di Kabupaten Pacitan,Magetan,Madiun mempunyai Tipe daerah yang tumbuh tapi tidak sejahtera.
1 1.1 Latar belakang
Beberapa ciri dari pembangunan ekonomi sebagai adanya peningkatan
pendapatan nasional yang nyata. Peningkatan tersebut berarti Gross Domestic Product (jumlah produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu Negara dalam kurun waktu tertentu) atau GDP-nya lebih tinggi daripada kenaikan jumlah penduduk sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah nyata termasuk
peningkatan pendapatan perkapita disertai perubahan struktur ekonomi suatu
negara tersebut dan terjadi dalam jangka waktu yang panjang, (Jhingan, 2000 : 5)
Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang lebih luas dari hanya
memfokuskan pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini disadari oleh banyak Negara
khususnya Negara Indonesia. Perkembangan nasional tertuang dalam misi untuk
mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan
UUD 45. Dengan pemahaman bahwa pembangunan ekonomi identik dengan
pertumbuhan, pada awalnya akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang
tinggi, tetapi akan dibarengi dengan masalah-masalah, pengangguran, kemiskinan
di pedesaan, ketimpangan distribusi pendapatan dan ketidakseimbangan
struktural. Pertumbuhan ekonomi harus dapat diarahkan untuk meningkatkan
pendapatan masyarakat serta mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan
Penelitian tentang distribusi pendapatan biasanya dikaitkan dengan
pertumbuhan ekonomi (peningkatan pendapatan) dimana terdapat hubungan
negatif diantara keduanya. Artinya semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi
maka, akan semakin timpang distribusi pendapatannya (Yuwono, 1997 : 17)
Dan pertumbuhan ini dapat digunakan sebagai alat untuk mengurangi
ketimpangan pendapatan regional yaitu melalui efek sabar dari pertumbuhan
ekonomi suatu daerah yang akan berpengaruh ke daerah lainnya (Booth dalam
Utomo, 2004 : 56)
Pembangunan dalam lingkup Negara secara spesial selalu merata.
Kesenjangan antar daerah seringkali menjadi permasalahan serius beberapa
daerah mencapai pertumbuhan cepat sedangkan daerah lain pertumbuhannya
lambat. Perbedaan pertumbuhan ekonomi antar daerah akan berdampak pada
tingkat kesejahteraan antar daerah yang pada akhirnya menyebabkan ketimpangan
regional antar daerah yang pada akhirnya menyebabkan ketimpangan regional
antar daerah semakin besar. Ketimpangan tersebut meliputi, ketimpangan antar
propinsi, kabupaten / kota, ketimpangan sektoral dan ketimpangan pendapatan
antar penduduk (pendapatan perkapita).
Ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi telah dicapai oleh propinsi
Jawa Timur salah satunya dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang
dicerminkan dalam perkembangan PDRB. Pertumbuhan ekonoi , pendapatan per
kapita tersebut merupakan indicator makro ekonomi yang dibentuk dari berbagai
macam sektor ekonomi, potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, yang
terjadi bagi daerah. Indikator ini penting untuk mengetahui keberhasilan
pembangunan yang telah dicapai, dan berguna untuk menentukan arah
pembangunan di masa yang akan datang.
Pertumbuhan ekonomi diperlukan guna menggerakkan dan memacu
pembangunan diberbagai bidang sekaligus pemerataan pembangunan dan
hasil-hasilnya. Ada sembilan sektor ekonomi atau kelompok lapangan usaha yang
umumnya dapat dihitung dalam PDB atau PDRB jika dalam lingkup regional /
daerah. Adapun kesembilan sektor tersebut yaitu (Anonim, 2004 : 12) :
1. Sektor pertanian
2. Sektor pertambangan dan penggalian
3. Sektor industri pengolahan
4. Sektor listrik, gas dan air bersih
5. Sektor bangunan
6. Sektor perdagangan, hotel dan restoran
7. Sektor pengangkutan dan komunikasi
8. Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan
9. Sektor jasa-jasa
Dari perhitungan sektor-sektor ekonomi tersebut, kondisi struktur ekonomi dari
suatu daerah Negara dapat ditentukan. Suatu daerah dikatakan agraris bila peran
sektor pertanian sangat dominant dalam PDRB-
nya, demikian pula sebaliknya dikatakan sebagai daerah industri apabila yang
Dari sembilan sektor ekonomi diatas dapat dikelompokkan menjadi
kelompok sektor primer (pertanian dan pertambangan), kelompok sektor sekunder
(industri, Listrik gas air bersih, dan kontruksi), kelompok sektor tersier
(perdagangan, pengangkutan, keuangan, dan jasa-jasa lainnya).
Dalam penelitian ini akan diteliti tentang tingkat kesejahteraan yaitu
dengan melihat pendapatan perkapita suatu daerah yaitu kota Surabaya dan diteliti
pula. Tentang pertumbuhan ekonomi, untuk melihat pendapatan perkapita atau
senjang atau tidak maka digunakan suatu indek yang dinamakan Analisis William
Son.
Adapun kabupaten yang akan diteliti adalah 3 kabupaten yaitu kabupaten
Pacitan, Magetan dan Madiun ,. Maka dengan penelitian ini dapat diketahui
wilayah mana yang mengalami kesenjangan dan Tipe daerah apa di tiga daerah
tersebut dimana daerah tersebut yang berbatasan dengan propinsi jawa Tengahan
.
1.2 Rumusan masalah
Adapun perumusan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut :
1. Wilayah mana yang mempunyai ketimpangan pendapatan
2. Wilayah mana yang mempunyai ketimpangan pertumbuhan ekonomi
3. Tipe daerah apa di masing-masing kabupaten tersebut.
1.3 Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui ketimpangan perwilayah di kabupaten Pacitan
Magetan dan Madiun
2. Untuk mengetahui Tipe daerah apa di kabupaten Pacitan, Magetan dan
Madiun.
1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah :
1. Manfaat ilmiah diharapkan dapat dijadikan bahan referensi bagi
penelitian lebih lanjut.
2. Manfaat praktis diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi
pihak yang berkepentingan.
3. Diharapkan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan atau masukkan
dalam menentukan kebijakan-kebijakan pembangunan-pembangunan di
6 2.1 Penelitian Sebelumnya
Pada penelitian sebelumnya akan dikemukakan mengenai penelitian yang
telah dilakukan oleh :
a. Wibowo (2003) dengan judul penelitian“ Analisis Pertumbuhan Ekonomi
Antar Wilayah Kabupaten / Kotamadya di Jawa Timur” periode tahun 1987
sampai 2001. Penelitian tersebut menggunakan variabel Pertumbuhan
Ekonomi Jawa Timur sebagai variabel terikat (Y), sedangkan variabel
bebasnya antara lain, Pertumbuhan PDRB = X1' PDRB per kapita = X2'
Investasi = X2' . Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
location Quotient. Hasil penelitiannya mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi antar wilayah di Jawa Timur di pengaruhi juga oleh investasi swasta
yang tidak merata.
b. Wedhahuditama (2003), dalam penelitiannya membahas tentang Identifikasi
Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan PDRB Jawa Timur
1980-1986 dan implikasinya terhadap pembangunan potensi daerah di Jawa Timur.
Variabel yang digunakan adalah variabel yang terdapat pada alat analisis
Tipologi klassen yaitu PDRB perkapita daerah dan pertumbuhan perekonomian daerah. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah
masing-masing wilayah merupakan penyumbang / memberikan kontribusi paling
besar terhadap PDRB masing-masing daerah.
c. Kuncoro dan Aswadi (220) Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol. 17,
No. 1, dengan judul :”Evaluasi Penetapan Kawasan Andalan : Studi Empiris
di Kalimantan Selatan tahun 1993-1999” dalam penelitian ini variabel yang
digunakan adalah Dummy Variabel, dimana 1 = Kawasan andalan; 0 =
Kawasan bukan andalan sebagai variabel terikat (Y), sedangkan variabel
bebasnya antara lain X1 = Spesialisasi daerah, alat analisis yang digunakan
dalam penelitian ini adalah sebagai variabel terikat (Y) sedangkan variabel
bebasnya antara lain X1 = Pertumbuhan PDRB, X2 = PDRB perkapita, X3 =
Spesialisasi daerah, alat analisis Tipologi Klassen,Location Quotient, Indeks Spesialisasi Regional, Model Logit (Binary Logistic Regression), dan Multinomial Logistic Regression. Dan hasil dari penelitian ini adalah pertimbangan penetapan kawasan andalan di Kalimantan Selatan hanya
mengacu pada pendapatan perkapita dan subsektor unggulan, yang
ditunjukkan oleh hasil analisis location Quotient dan model logit. Pertumbuhan PDRB dan spesialisasi daerah ternyata tidak menjadi bahan
pertimbangan dalam penetapan kawasan andalan di Kalimantan Selatan.
Analisis Tipologi Klasen menunjukkan, dari tiga daerah di kawasan andalan hanya Kabupaten Kotabaru yang berada pada daerah cepat-tumbuh dengan
tingkat pertumbuhan dan pendapatan perkapita tinggi. Kota Banjarmasin
merupakan daerah maju tapi tekanan dengan tingkat pertumbuhan rendah,
klasifikasi relatif tertinggal dengan tingkat pertumbuhan dan pendapatan per
kapita rendah. Hasil analisis spesialisasi regional menunjukkan bahwa
kemampuan kawasan andalan sebagai daerah yang memiliki keterkaitan
perekonomian (sektoral) dengan daerah lainnya masih lemah. Hal tersebut
ditunjukkan dengan semakin terdiversifikasinya subsektor usaha
daerah-daerah di kawasan andalan bahkan terjadi penurunan tingkat spesialisasi antar
daerah kawasan andalan selama tahun 1993-1999. implikasi dari seluruh
persyaratan yang harus dipenuhi adalah kebijakan penetapan kawasan
andalan di Propinsi Kalimantan Selatan tidak tepat, terutama penetapan Kota
Banjarmasin dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hasil analisis
pengklasifikasian menunjukkan bahwa pengklasifikasian daerah di Provinsi
Kalimantan Selatan lebih baik dengan menggunakan empat klasifikasi
menurut Tipologi Klassen daripada hanya berdasarkan klasifikasi kawasan
andalan dan kawasan bukan andalan. Empat klasifikasi daerah tersebut yaitu
daerah cepat-maju dan cepat-tumbuh, daerah maju tapi tertekan, daerah
berkembang cepat, dan daerah relatif tertinggal.
d. Pusat Studi Asia Pasifik UGM dan PT. Toyota Astra Motor (2006), dalam
penelitiannya “Analisis Tipologi Klassen untuk melihat posisi sembilan sektor PDRB Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) selama periode
2001-2004. Laju pertumbuhan PDRB masing-masing sektor dan pangsa
masing-masing sektor terhadap PDRB Provinsi NAD menurut lapangan
usaha tahun 2001-2004 dihitung kemudian dicari rata-ratanya. Setelah itu laju
PDRB Provinsi NAD dibandingkan dengan rata-rata laju pertumbuhan
masing-masing sektor PDRB dan rata-rata pangsa masing-masing sektor
PDRB menurut lapangan usaha tahun 2001-2004 secara nasional. Sektor yang
memiliki kontribusi terhadap PDRB NAD paling besar dimiliki oleh Sektor
Keuangan, Asuransi, Sewa Rumah dan Jasa Perusahaan. Sementara itu sektor
yang memiliki pertumbuhan paling kecil bahkan negatif adalah Sektor
Bangunan. Hasil analisis, sektor yang dapat dikategorikan sebagai sektor
maju dan tumbuh pesat adalah Sektor Pertambangan dan Penggalian. Sektor inilah yang sebaiknya mendapat perhatian yang lebih dari Pemerintah
Daerah untuk dikembangkan. Lebih lanjut, dengan didukung oleh data yang
memadai, Pemerintah Daerah sebaiknya menganalisis hingga ke tingkat
komoditi. Apabila pada tingkat komoditi sudah ditemukan komoditi yang
maju dan tumbuh pesat, maka sebaiknya anggaran pengeluaran diprioritaskan
pada komoditi tersebut. Sektor Pertanian termasuk ke dalam sektor maju tapi
tertekan. Sektor-sektor yang masuk ke dalam sektor potensial untuk
berkembang adalah Sektor Listrik, Gas dan Air Minum, Sektor Keuangan,
Asuransi dan Sewa Rumah, dan Sektor Pemerintahan dan Jasa. Sayang sekali
menurut hasil analisis ternyata banyak sektor-sektor di Provinsi NAD yang
termasuk ke dalam sektor relatif tertinggal. Sektor-sektor tersebut adalah
Sektor Industri Pengolahan, Sektor pengolahan, Sektor Perdagangan, Hotel
2.2 Landasan Teori
Berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan, maka perangkat
analisis yang digunakan untuk menjelaskan fenomena tersebut didasarkan pada
teori ekonomi.
Beberapa teori dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut :
2.2.1. Konsep Tentang Daerah
Suatu daerah dapat diklasifikasikan berdasarkan dasar-dasar / tujuan
pembentukan daerah itu sendiri. Adapun konsep daerah dibedakan menjadi 3
pengertian sebagai berikut (Tarigan, 2002)
Pertama adalah daerah dianggap sebagai suatu space atau ruang dimana
kegiatan ekonomi berlaku dan diberbagai pelosok ruang tersebut sifatnya adalah
sama. Jadi batas-batas diantara satu daerah dan daerah-daerah lainnya ditentukan
oleh titik-titik dimana kesamaan sifat-sifat tersebut sudah mengalami perubahan.
Persamaan sifat-sifat tersebut dapat ditinjau dari segi pendapatan perkapita
penduduknya, agama atau suku bangsa ataupun struktur ekonominya. Daerah
dengan pengertian tersebut dinamakan daerah homogen atau daerah formal.
Konsep daerah menurut homogenitas tersebut berguna bagi perencanaan sektoral.
Dalam hal ini daerah-daerah yang memiliki kesamaan dalam sektor yang dibahas
dapat dijadikan suatu wilayah daerah. Dengan demikian dapat dibuat satu pusat
pelayanan yang menangani masalah yang sama dengan program penanganan yang
Kedua, daerah sebagai suatu ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau
beberapa pusat kegiatan ekonomi, daerah dengan pengertian ini disebut daerah
nodal. Dalam hal ini keseluruhan dari daerah ini ditetapkan beberapa pusat
pertumbuhan yang biasanya adalah kota-kota terbesar didalam suatu unit wilayah
dan ditetapkan batas pengaruh dari masing-masing pusat pertumbuhan tersebut.
Daerah pengaruh pusat pertumbuhan (hinterland) dalam memenuhi kebutuhannya tergantung pada daerah yang menjadi pusat pertumbuhan (kota). Konsep daerah
seperti ini tidak berdasarkan pada sektor-sektor yang ada pada daerah itu.
Sektor-sektor yang ada pada daerah tersebut memiliki ketergantungan antara pusat
pertumbuhan akan mempengaruhi pusat pertumbuhannya. Konsep daerah
berdasarkan ruang lingkup pengaruhnya. Perubahan pada pusat pertumbuhan akan
mempengaruhi hinterlandnya, begitu sebaliknya perubahan pada daerah pengaruh
akan mempengaruhi pusat pertumbuhannya. Konsep daerah berdasarkan ruang
lingkup pengaruh ekonomi tersebut lebih tepat untuk perencanaan daerah, karena
menyangkut keseluruhan aspek pengembangan wilayah dan aspek keterkaitan.
Ketiga, daerah adalah suatu ekonomi ruang yang berbeda dibawah suatu
administrasi tertentu seperti satu propinsi, kabupaten, desa dan sebagainya.
Daerah menurut pengertian ini disebut daerah administrasi atau daerah
perencanaan. Konsep daerah berdasarkan administrasi pemerintah biasanya terikat
pada sejarah yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang, sehingga tidak
mudah dirubah. Berdasarkan sejarah pembentukannya tersebut, maka daerah
administrative di Indonesia terbagi atas daerah propinsi, kabupaten / kota,
ditetapkan batas-batas daerah secara jelas, batas ini seringkali menggunakan
kondisi di lapangan yang memiliki ciri-ciri yang jelas, seperti sungai, laut,
gunung, jurang, jalan, batas hutan, dan lain-lain.
Jika membahas perencanaan pembangunan ekonomi daerah, maka
pengertian daerah sebagai daerah perencanaan / administrasi yang lebih banyak
digunakan karena pelaksanaan kebijaksanaan dan rencana pembangunan daerah
diperlukan tindakan dari berbagai lembaga pemerintah sehingga lebih praktis dan
mudah bila suatu Negara dipecah menjadi beberapa daerah ekonomi berdasarkan
satuan administrative. Daerah yang batasnya ditentukan secara administratif lebih
mudah dianalisis, karena biasanya pengumpulan data diberbagai daerah dalam
suatu negara pembagiannya didasarkan pada satuan administratif (Sukirno, 995)
2.2.1.1. Perencanaan Pembangunan
Perencanaan pembangunan mempunyai peranan penting didalam
mewujudkan tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu Negara.
“Perencanaan adalah suatu persiapan langkah dan kegiatan yang disusun atas
pemikiran yang logis untuk mencapai tujuan yang ditentukan” (Sitanggang, 1999)
Perencanaan pada dasarnya berkisar pada dua hal yaitu, Pertama adalah
penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan kongkrit yang hendak dicapai
dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai yang dimiliki masyarakat yang
bersangkutan. Kedua adalah pilihan-pilihan diantara cara-cara alternatif yang
efisien secara rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut (Nitisastro dalam
nasional yang diatur, yang direncanakan tujuannya dan jalannya (Hatta dalam
Arsyard, 1999).
“Perencanaan pembangunan merupakan suatu usaha pemerintahan
mengkoordinasi semua keputusan ekonomi dalam jangka panjang guna
mempengaruhi secara langsung serta mengendalikan variabel-variabel ekonomi
yang penting (penghasilan, konsumsi, lapangan kerja, investasi, dan sebagainya)
suatu negara dalam rangka mencapai tujuan pembangunan”.
2.2.1.2. Konsep Pembangunan Regional
Apabila kita, menganalisa tentang masalah perekonomian daerah
merupakan pekerjaan yang sulit bila dibandingkan dengan menganalisis terdapat
dua teori mengenai konsep pembangunan yaitu, pertama, berasal dari tentang
perekonomian nasional. Keadaan yang demikian dapat timbul karena :
1. Pertama, karena data mengenai daerah masih sangat terbatas, apalagi
apabila daerah tersebut dibedakan berdasarkan pengertian daerah nodal,
dimana daerah diartikan sebagai suatu ekonomi ruang yang dikuasai oleh
satu atau beberapa pusat kegiatan ekonom, dimana pengaruh yang timbul
dari satu beberapa pusat kegiatan ekonomi, dimana pengaruh yang timbul
dari satu atau beberapa pusat-pusat kegiatan ekonomi digantikan dengan
pengaruh dari pusat lainnya.
2. Kedua, data yang ada mengenai perekonomian daerah sangat sukar
perekonomian nasional. Sehingga mengakibatkan aliran-aliran yang masuk
maupun keluar dari suatu daerah sangat sukar diperoleh.
Pembangunan daerah dapat diartikan sebagai semua kegiatan
pembangunan yang ada atau dilakukan di daerah yang unsurnya terdiri dari,
pertama kegiatan dan proyek pembangunan daerah itu sendiri diluar yang telah
direncanakan oleh pemerintah pusat.
Sasaran pembangunan daerah yang diingankan adalah berkembangnya
otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dititikberatkan
pada daerah Kabupaten / Kota, meningkatnya kemandirian dan kemampuan
daerah dalam merencanakan dan mengelola pembangunan di daerah dan makin
terkoordinasinya pembangunan antar sektor dan antar daerah serta antar
pembangunan sektoral dengan pembangunan daerah.
Masalah pokok pembangunan daerah terletak pada penekanan-penekanan
kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang
bersangkutan (endegeoneous development) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal (daerah).
Orientasi ini mengarahkan pada pengambilan inisiatif yang berasal dari daerah
dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja dan merangsang
peningkatan kegiatan ekonomi.
Terdapat dua teori mengenai konsep pembangunan yaitu :
1. Konsep pembangunan dari atas (top-down planning)
Teori ini mengatakan bahwa timbulnya pembangunan itu karena adanya
kelompok sektoral yang dinamis atau kelompok geografis, pembangunan
diharapkan dapat merembes ke daerah-daerah sekitarnya, baik merata
spontan maupun secara diarahkan” (Syamsi, 1986 : 41). Dengan konsep
ini, memungkinkan terjadinya pembangunan proyek-proyek besar dan
padat modal (capital intensive system). Konsep pembangunan dari atas memerlukan pengaruh dari pemerintah pusat, dan perencanaannya
dilakukan dari atas ke bawah.
2. Konsep pembangunan dari bawah (bottom-up planning)
Konsep ini didasarkan pada mobilitas maksimal sumber-sumber daya
alam, sumber daya manusia, kelembagaan yang tujuan utamanya adalah
pemenuhan kebutuhan pokok bagi masyarakat daerah itu. Adapun wujud
pembangunannya adalah proyek-proyek kecil dengan sistem padat karya
(labor intensive system), menggunakan teknologi tepat guna dan potensi-potensi daerah itu sendiri, perencanaan pembangunannya dilakukan dari
bawah. (Syamsi, 1986 : 40).
Salah satu aspek pembangunan regional adalah pembangunan ekonomi
yang bertujuan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan perubahan
struktur ekonomi. Menurut Hoover dan Fisher (dalam Hadi Prayitno,
1996 : 225), pembangunan ekonomi regional dapat melalui beberapa
1. Subsistensi ekonomi
Dalam tahap ini masyarakat hanya dapat memenuhi kebutuhannya
sendiri pada tingkat cukup untuk hidup sehari-hari. Kehidupan
penduduk sebagian besar masih tergantung pada sektor pertanian
dan mengumpulkan hasil alam hasilnya.
2. Pengembangan transportasi dan spesialisasi lokal.
Pada tahap ini telah terdapat peningkatan baik dalam prasarana
maupun sarana transportasi yang berakibat pada terjadinya
spesialisasi pada lokasi-lokasi tertentu. Dikalangan masyarakat
petani timbul spesialisasi baru diluar pertanian, dimana hasil
produksi, bahan dasar, dan pemasarannya masih terbatas dan
tergantung pada daerah pertanian yang bersangkutan.
3. Perdagangan antar daerah.
Pada tahap ini telah terjadi perkembangan perdagangan antar
daerah. Hal ini mungkin saja terjadi karena telah terjadi perbaikan
di bidang transportasi dan perubahan di sektor kegiatan dari arah
peningkatan produksi jenis ekstenfikasi menjadi pertanian yang
lebih dititik beratkan pada intensifikasi.
4. Industrialisasi.
Dengan makin bertambahnya penduduk dan menurunnya potensi
produksi pertanian serta kegiatan ekstratif lainnya, daerah dipaksa
untuk mengembangkan sumber pendapatan dan lapangan kerja,
kegiatan-kegiatan yang menyangkut industri manufaktur serta
pertambangan dan galian.
5. Spesialisasi daerah.
Pada tahap ini daerah telah sampai pada tingkat spesialisasi
kegiatan, baik barang dan jasa untuk keperluan penjualan ke
daerah lain termasuk tenaga ahli dan jasa-jasa khusus.
6. Aliran faktor produksi antar daerah.
Peningkatan infrastruktur dan arus informasi pada akhirnya
menaikkan tingkat mobilisasi faktor produksi antar daerah
2.2.1.3. Uraian Sektoral
1. Sektor listrik, gas, dan air bersih meliputi subsektor listrik ;
subsektor gas kota ; dan air bersih.
2. Sektor pembangunan / kontruksi meliputi semua kegiatan
pembangunan fisik konstruksi, baik berupa gedung, jalan,
jembatan, pelabuhan, terminal, dam, irigasi, eksplorasi minyak
bumi maupun jaringan listrik, gas, air minum, telepon dan
sebagainya.
3. Sektor perdagangan dan komunikasi meliputi subsektor
perdagangan besar dan eceran, subsektor hotel, dan subsektor
restoran.
4. Sektor pengangkutan dan komunikasi meliputi subsektor angkutan
subsektor angkutan penyeberangan, sektor angkutan udara,
subsektor jasa penunjang angkutan, subsektor pos dan
telekomunikasi, subs ektor jasa penunjang telekomunikasi.
5. Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan meliputi
subsektor lembaga keuangan bukan bank, subsektor penunjang
keuangan, subsektor sewa bangunan, dan subsektor jasa
perusahaan.
6. Sektor-sektor jasa meliputi subsektor pemerintahan umum ;
subsektor sosial kemasyarakatan, subsektor jasa hiburan dan
kebudayaan, subsektor jasa perorangan dan RT.
2.2.2. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan dalam Gross Domestic Product (GDP), tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil daripada tingkat pertambahan penduduk, atau apakah perubahan dalam
struktur ekonomi berlaku atau tidak. Sedangkan pembangunan ekonomi diartikan
sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu
masyarakat dalam jangka panjang yang melebihi dari tingkat pertambahan
penduduk. (Sukirno, 1980 : 14), tetapi pada umumnya, para ahli ekonomi
memberikan pengertian yang sama dengan pembangunan ekonomi yaitu sebagai
kenaikan dalam Gross Domestic Product. Dalam penggunaan yang lebih umum
istilah, istilah pertumbuhan ekonomi biasanya digunakan untuk menyatakan
digunakan untuk menyatakan perkembangan ekonomi di Negara berkembang.
Suatu perekonomian dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila pendapatan
perkapita menunjukkan kecenderungan / mengalami suatu kenaikan dalam jangka
panjang dan kegiatan ekonomi secara rata-rata meningkat dari tahun ke tahun.
Pertumbuhan ekonomi daerah-daerah SWP I Jawa Timur yang paling
besar pada tahun 2001 adalah kabupaten Mojokerto yaitu 5,65% disusul oleh Kota
Surabaya dengan pertumbuhan sebesar 4,65%, Sedangkan pertumbuhan dengan
persentase paling kecil adalah Kabupaten Gresik 1,14 % disusul Kabupaten
Lamongan dengan persentase sebesar 3,08%. Pada tahun 2006 pertumbuhan
paling besar ditunjukkan oleh Kabupaten Gresik yang pada tahun 2001
merupakan daerah yang paling sedikit pertumbuhan ekonominya menjadi daerah
dengan pertumbuhan ekonomi terbesar kedua setelah Kabupaten Mojokerto
dengan persentase sebesar 6,88 % dan Kabupaten Mojokerto sendiri mengalami
pertumbuhan sebesar 7,30 %. Sedangkan daerah paling kecil pertumbuhan
ekonominya adalah Kota Mojokerto dengan persentase 3,81 %.
(Anonim, 2006 : 137).
“Pola pertumbuhan ekonomi regional tidaklah sama dengan apa yang
lazim ditemukan pada pertumbuhan nasional”, hal ini disebabkan pada analisa
pertumbuhan ekonomi regional lebih ditekankan pada pengaruh perbedaan
karakteristik space terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam teori pertumbuhan
ekonomi regional faktor-faktor yang mendapat perhatian utama adalah
Secara umum, pendapat-pendapat dalam bidang teori pertumbuhan regional dapat
dibagi dalam empat kelompok besar yaitu :
Export Base –Models, Noe-Classic, jalur pemikiran ala Keynes, dan model Core Periphery (Sjafrizal, 1985 : 331)
Export Base –Models pandangannya berdasarkan pada sudut teori lokasi, yaitu bahwa pertumbuhan ekonomi suatu region akan lebih banyak ditentukan
oleh jenis keuntungan lokasi yang selanjutnya dapat digunakan oleh area tersebut
sebagai kekuatan ekspor. Keuntungan lokasi tersebut tergantung pada kondisi
geografis daerah setempat, ini berarti bahwa strategis pembangunan suatu daerah
untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya harus disesuaikan dengan
keuntungan lokasi yang dimilikinya dan tidak harus sama dengan strategi
pembangunan pada tingkat nasional (Sjafrizal, 1985 : 332).
Model Neo-Classic berdasarkan pada peralatan fungsi produksi, yaitu bahwa unsur-unsur yang menentukan pertumbuhan ekonomi regional adalah
Modal, Tenaga kerja dan Kemajuan Teknologi. Dalam model ini terdapat
hubungan antara tingkat pertumbuhan suatu Negara dengan perbedaan
kemakmuran suatu daerah (disparitas regional) pada Negara yang bersangkutan.
Dikatakan bahwa pada saat pembangunan baru dimulai (di Negara sedang
berkembang), tingkat perbedaan antar wilayah cenderung menjadi tinggi,
sedangkan bila proses pembangunan telah berjalan dalam waktu lama, maka
perbedaan tingkat kemakmuran antar wilayah cenderung menurun. Hal ini
masih kuatnya tradisi yang mengalami mobilitas penduduk dan modal antar
daerah (Sjafrial. 1985 : 333).
Jalur pemikiran ala Keynes menamakan pendapatannya sebagai model
Cumulative Causation, penganut pemikiran ini berpendapat bahwa peningkatan pemerataan pembangunan antar daerah tidak dapat hanya diserahkan pada
kekuatan pasar sebagaimana yang dikemukakan oleh kaum Neo-klasik, tetapi hal ini baru akan dapat dilakukan melalui campur tangan aktif pemerintah dalam
bentuk program-program pembangunan wilayah, terutama untuk daerah-daerah
yang masih terbelakang. (Sjafrizal, 1985 : 334).
Model Core Periphery menekankan analisanya pada hubungan yang erat dan saling mempengaruhi antara pembangunan kota (core) dan desa (periphery). Menurut teori ini, gerak langkah pembangunan daerah perkotaan akan lebih
banyak ditentukan oleh keadaan desa-desa sekitarnya. Sebaliknya corak
pembangunan daerah pedesaan tersebut juga dapat ditentukan oleh arah
pembangunan daerah perkotaan. Dengan demikian aspek interaksi antar daerah
sangat ditonjolkan (Sjafrizal, 1985 : 334).
Adapun teori pusat pertumbuhan (growth pole theory) memandang lokasi industri sebagai fungsi dari cabang penting industri tersebut. Wilayah semacam
inilah yang akan mampu mengembangkan wilayah-wilayah di sekitarnya. Tidak
mengherankan bahwa konsep yang dikemukakan adalah pengembangan industri
di wilayah tertinggal. Intervensi diarahkan kepada lokasi industri. Tujuan
intervensi ialah menciptakan hubungan antar wilayah yang memiliki perbedaan
industri, serta penyediaan akses modal kerja langsung dari pemerintah. (Sjafrizal,
1985 : 335).
2.2.3. Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB )
2.2.3.1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB )
Pengertian Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ),menurut beberapa ahli
ekonomi adalah sebagai berikut:
1. Produk Domestik Regional Bruto, didefinisikan sebagai jumlah nilai
tambah bruto dari semua sektor dan diperoleh dari sebagian selisih antara
nilai bruto yang dinilai atas dasar harga konstan yang diterima oleh
produsen dikurangi pemakaian bahan baku dan penolong yang dinilai atas
dasr pembelian. ( Sukirno,1991 : 165 ).
2. Produk Domestik Regional Bruto adalah nilai barang jadi yang diproduksi
dalam negeri ( Doernbusch dan fisher, 1992 :30 )
3. Menurut ( Rosyidi,1997 : 342 ), salah satu pengukuran produk domestik
regional bruto,dengan menghitung seluruh pengeluaran untuk penelitian
barang dan jasa yang dihasilkan oleh negara atau daerah yang
bersangkutan,yaitu:
a. Konsumsi Rumah Tangga.
b. Konsumsi Pemerintah.
c. Investasi Pemerintah dan Swasta.
e. Impor barang dan jasa.
4. Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah barang dan jasa akhir kali
harga sebagai alat produksi barang-barang dan jasa-jasa suatu daerah
ditambah dengan hasil produksi barang dan jasa orang-orang dan
perusahaan-perusahaan asing. (Partadireja,1982 : 50 )
5. Produk Domestik Regional Bruto adalah total nilai produksi barang dan
jasa yang diproduksi di wilayah regional tertentu dalam waktu tertentu
atau biasanya 1 (satu ) tahun. ( Anonim,1995 : 01 ).
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa produk Domestik Regional
Bruto adalah jumlah nilai produksi barang dan jasa pada suatu wilayah tertentu
dihitung dengan harga pasar dalam waktu tertentu biasanya dalam 1 ( satu ) tahun
2.2.3.2. Pendekatan Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto
Cara perhitungan Produk Domestik Regional Bruto dapat diperoleh
melalui 3 ( tiga ) pendekatan, yaitu :
1. Menurut Pendekatan Produksi
Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai barng dan jasa akhir
yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka
waktu tertentu atau 1 ( satu ) tahun. Unit- unit produksi tersebut didalam
penyajiannya dikelompokkan menjadi sembilan ( 9 ) sektor lapangan
usaha, yaitu :
a. Pertanian
c. Industri Pengolahan
d. Listrik, Gas, dan Air Bersih
e. Konstruksi
f. Perdagangan, Hotel, dan Restoran
g. Pengangkutan dan Komunikasi
h. Jasa Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan
i. Jasa – jasa
2. Menurut Pendekatan Pengeluaran
Produk Domestik Regional Bruto adalah penjumlahan semua komponen
permintaan akhir,
yaitu:
a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang
tidak mencari untung
b. Konsumsi Pemerintah
c. Pembentukan modal tetap domestik bruto
d. Perubahan stok
e. Ekspor netto dalam jangka waktu tertentu atau biasanya satu
(1) tahun.
3. Menurut Pendekatan Pendapatan
Produk Domestik Regional Bruto Merupakan jumlah balas jasa yang
suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu ( biasanya satu tahun ). Balas
jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji , sewa tanah,
bunga modal dan keuntungan. Semus hitungan tersebut sebelum dipotong
pajak langsung lainnya. Dalam pengertian Produk Domestik Regional
Bruto, kecuali faktor pendapatan, termasuk semua komponen penyusutan
dan pajak tak langsung netto. Jumlah semua komponen pendapatan ini
menurut sektor disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. Produk
Domestik Regional Bruto merupakan jumlah dari nilai tambah bruto
seluruh sektor atau lapangan kerja.
Dari tiga ( 3 ) perhitungan pendekatan tersebut , secara konsep
seyogyanya jumlah pengeluaran tadi harus sama dengan jumlah barang
dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah
pendapatan untuk faktor- faktor produksinya. Selanjutnya Produk
Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar, karena mencakup
komponen pajak tidak langsung.
( Anonim,1995 : 03 )
2.2.4. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita
Bila Produk Domestik Regional Bruto dibagi dengan jumlah penduduk
pertengahan tahun yang tinggal di wilayah ini, maka akan diperoleh suatu Produk
2.2.4.1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Angka pendapatan Regional atas dasar harga konstan 1993 sangat penting
untuk melihat perkembangan riil bagi setiap agregat ekonomi yang diamati.
Agregat yang dimaksud tersebut dapat merupakan Produk Domestik Regional
Bruto secara keseluruhan , nilai tambah sektoral. Pada dasarnya dikenal empat( 4 )
cara untuk memperoleh nilai tambah sektoral atas dasar harga konstan, yaitu :
1. Revaluasi
Cara ini dilakukan dengan menilai produksi dan biaya antara
maasing-masing tahun dengan harga pada tahun dasar 1993. Selanjutnya nilai
tambah bruto atas dasar harga konstan diperoleh dari selisih antara niali
output dan biaya antara atas dasar harga konstan 1993. Dalam praktek
sangat sulit melakukan revaluasi terhadap biaya antara yang digunakan,
karena mencakup komponen input yang sangat beragam, disamping data
harga yang tak tersediatidak dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut.
Oleh karena itu biaya antara atas dasar harga konstan biasanya diperoleh
dari perkalian antara output atas dasar harga konstan masing-masing tahun
dengan rasio ( tetap ) biaya antara terhadap output pada tahun dasar atau
dengan rasio biaya antara terhadap output pada tahun berjalan.
2. Ekstrapolasi
Nilai tambah masing-masing tahun atas dasar harga konstan 1993
diperoleh dengan cara mengalikan nilai tambah pada tahun dasar 1993
dengan indeks kuantum produksi. Indeks ini bertindak sebagai
produksi yang dihasilkan ataupun indeks dari berbagai indikator kuantum
produksi lainnya seperti tenega kerja, jumlah perusahaaan yang dianggap
cocok dengan jenis kegiatan yang sedang dihitung. Ekstrapolator dapat
juga dilakukan terhadap output atas dasar harga konstan, kemudian dengan
menggunakan rasio nilai tambah terhadap output akan diperoleh perkiraan
nilai tambah atas harga konstan.
3. Deflasi
Nilai tambah atas dasar harga konstan 1993 dapat diperoleh dengan cara
membagi nilai tambah atas dasar harga berlaku pada masing-masing tahun
dengan indeks harganya. Indeks harga yang digunakan sebagai deflator
biasanya merupakan indeks harga konsumen, indeks harga perdagangan
besar dan sebagainya, tergantung indeks mana yang dianggap lebih cocok.
Indeks harga tersebut dapat pula dipakai sebagai inflator, yang berarti nilai
tambah atas dasar harga yang berlaku diperoleh dengan mengalikan nilai
tambah atas dasar harga konstan dengan indeks tersebut.
4. Dalam deflasi berganda ini, yang deflasikan adalah output dan biaya
antara. Sedangkan nilai tambah diperoleh dari selisih antara output dan
biaya antara hasil pendeflasian tersebut. Indeks harga yang digunakan
sebagai deflator biasanya merupakan indeks hargaprodusen atau indeks
harga perdagangan besarsesuai dengan cakupan komoditinya, sedangkan
indeks harga untuk biaya antara adalah indeks harga dari komponen input
besar. Dalam kenyantaanya, sangat sulit melakukan deflasiterhadap biaya
indeks haraga yang cukup mewakili sebagai deflator. Oleh karena itu
didalam perhitungan nilai tambah atas dasar harga konstan, deflasi
berganda ini belum banyak dipakai, termasuk dalam publikasi ini.
Perhitungan komponen penggunaan Produk Domestik Regional Bruto
atas dasar harga konstan dengan menggunakan cara-cara diatas, tetapi
mengingat terbatasnya data yang tersedia maka cara deflasi dan ekstrapolasi
lebih banyak di pakai.
2.2.4.2. Teori pertumbuhan Harrod-domar
Teori pertumbuhan ekonomi Harrod- Domar tetap mempertahankan pendapat dari ahli-ahli ekonomi yang terdahulu, menekankan peranan dalam
pembentukan modal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan
berbeda dengan pendapat kaum klasik dan keynes, yang memberikan pada
satu aspek saja dari pembentukan modal, teori Harrod- Domar menekankan
dua aspek dari pembentukan modal. Menurut pendapat dari kaum klasik,
pembentukan modal merupakan satu pengeluaran yang akan menambah
kesanggupan suatu masyarakat untuk menambah produksi.
Bagi kaum klasik pembentukan modal adalah pengeluaran yang akan
mempertinggi jumlah alat-alat masyarakat. Apabila hal tersebut bertambah,
maka dengan sendirinya produksi dan pendapatan nasional akan bertambah
tinggi dan pembangunan ekonomi akan tercipta. Kaum klasik berpendapat
sendirinya menciptakan pertambahan produksi nasional dan pembangunan
ekonomi.
Dengan adanya keyakinan seperti itu kaum klasik tidak memberi
perhatian kepada fungsi kedua dari pembentukan modal dalam perekonomian
yaitu untuk mempertinggi tingkat pengeluaran masyarakat. Keadaan
sebaliknya ada dalam analisis Keynes, yaitu mengabaikan sama sekali peranan
pembentukan modal sebagai pengeluaran yang akan mempertinggi
kesanggupan sektor produksi untuk menghasilkan barang yang diperlukan
masyarakat. Dalam analisa Keynes perhatian lebih ditekankan pada masalah
kekurangan pengeluaran masyarakat, karena Keynes menanggap kegiatan
ekonomi ditentukan untuk tingkat pengeluaran masyarakat dan bukan pada
kesanggupan alat-alat modal untuk memproduksi barang-barang. Oleh sebab
itu dalam menganalisa mengenai penanaman modal, kegiatan tersebut
terutama dipandang sebagai tindakan untuk memperbesar pengeluaran
masyarakat.
Teori Harrod- Domar memperhatikan kedua fungsi dari
pembentukan modal tersebut dalam kegiatan ekonomi. Dalam teori Harrod-
Domar pembentukan modal dipandang sebagai pengeluaran yang akan
menambah efektif permintaan seluruh masyarakat. Teori tersebut
menunjukkan suatu kenyataan yang diabaikan dalam analisa Keynes, yaitu
apabila dalam suatu masa tertentu dilakukan pembentukan modal, maka pada
masa berikutnya perekonomian tersebut memiliki kesanggupan yang lebih
Disamping itu, sesuai dengan pendapat Keynes, teori Harrod- Domar
pertambahan dalam kesanggupan memproduksi ini tidak dengan sendirinya
akan menciptakan pertambahan produksi dan kenaikan pendapatan nasional.
Teori Harrod- Domar sependapat dengan teori keynes, bahwa
pertambahan produksi dan dan kenaikan pendapatan nasional bukan
ditentukan oleh pertambahan dalam kapasitas produksi masyarakat, tetapi
akan kenaikan pengeluaran masyarakat. Dengan demikian, walaupun
memproduksi bertambah, pendapatan nasional baru bertambah, dan
pertumbuhan ekonomi tercipta apabila pengeluaran masyarakat mengalami
kenaikan dengan masa sebelumnya. Bertitik tolak dari pandangan ini, analisa
Harrod Domar bertujuan untuk menunjukan syarat yang diperlukan supaya
dalam jangka panjang kemampuan memproduksi yang bertambah dari masa
ke masa ( yang diakibatkan oleh pembentukan modal pada masa sebelumnya )
akan selalu sepenuhnya digunakan. Maka dapat disimpulkan bahwa agar
perekonomiam selalu tercapai tingkat kapasitas penuh dalam pengunaan
alat-alat modal yang tersedia haruslah pertambahan dalam tingkat penanaman
Gambar 2.1 : Teori pertumbuhan Harrod-Domar
S,I
S I+I I
I
S0
Y o Yso=Yo Ys1
Sumber : Sukirno, Sudono, 1985, Ekonomi Pembangunan Proses dan Dasar
Kebijaksanaan, Penerbit Bina Grafika, Jakarta, halaman 291.
Syarat untuk menciptakan pertumbuhan teguh yang dikemukakan oleh
Harrod-Domar (Sukirno, 1994 : 433) ada dua hal yang perlu diketahui :
1. Pertambahan kapasitas barang modal tergantung dua faktor yaitu ( i ) Rasio modal produksi ( misalkan bernilai COR ), ( ii ) Investasi yang dilakukan ( misalkan bernilai I ). Pertambahan kapasitas barang modal (c
) dinyatakan dalam persamaan berikut:
2. Pertambahan pendapatan nasional (y ) yang sama dengan kapasitas
pertambahan barang modal (c ). Teori Harrod-Domar adalah perluasan
dari analisis Keynes. Dengan demikian teori itu berpendapat bahwa
kapasitas penuh pada tahun berikut akan tercapai apabila pengeluaran
agregat bertambah dengan cukup besar sehingga tercapai keadaan.
c = y……….(Sukirno, 1994 : 434).
Teori keynes telah menerangkan, apabila ada pertambahan
pengeluaran agregat ( misalnya I ) maka pendapatan nasional akan bertambah. Besarnya pertambahan pendapatan nasional tergantung kepada
besarnya multiplier, dan pertambahan pendapatan tersebut dapat dihitung
menggunakan persamaan berikut :
Y = ___I___ . I MPS
Dengan demikian : ___I___ = ___I___ . I COR MPS
Atau: __I__ = MPS …………..( Sukirno, 1994 : 443 ). I
Persamaan diatas bearti tingkat kenaikan investasi (I / I ) adalah sama dengan MPS / COR.
2.2.5. Pengertian Sektor-Sektor Ekonomi 2.2.5.1. Sektor Pertanian
Pertanian merupakan basis perekonomian indonesia. Walaupun
berdasarkan proporsi nilai tambahnya dalam mementuk Produk Domestic
Regional Bruto atau pendapatan nasional tahun demi tahun kian mengecil, hal
itu bukanlah berarti nilai dan peranannya semakin tidak bermakna. Nilai
tambah sektor pertanian dari waktu ke waktu tetap selalu meningkat. Kecuali
itu peranan sektor ini dalam menyerap tenaga kerja tetap terpenting. Mayoritas
penduduk indonesia, yang sebagian besar tinggal didaerah pedesaan, hingga
saat ini masih menyandarkan mata pencahariannya pada sektor pertanian.
(Dumairy, 1997: 207).
2.2.5.2. Sektor Pertambangan dan Penggalian
Komoditi yang dicakup meliputi minyak mentah dan gas bumi,
yodium, biji mangan, beserta semua jenis hasil penggalian seperti pasir dan
tanah liat. Kegiatan sektor ini hanya terbatas pada penggalian dan bata dimana
data produksi dan lainnya diperoleh dari survey khusus.
2.2.5.3. Sektor Industri Pengolahan
Disamping sektor pertanian, sektor industri juga mengandung
pengertian yaitu pertama, industri dapat berarti himpunan
perusahaan-perusahaan sejenis. Dalam konteks ini sebutan industri kosmetika, misalnya
berarti himpunan perusahaan penghasil produk-produk kosmetik.
Kedua, Industri dapat pula menunjuk ke suatu sektor ekonomi yang
didalamnya terdapat kegiatan produktif yang mengolah bahan menjadi barang
marjinal, elektrikal atau bahkan manual. Sektor industri manufaktur adalah
sebagai salah satu sektor produksi atau lapangan usaha dalam perhitungan
pendapatan nasional menurut pendekatan produksi. ( Dumairy, 1997 : 227 ).
2.2.5.4. Klasifikasi Industri
Industri dapat digolong-golongkan berdasarkan beberapa sudut
tinjauan atau pendekatan, yaitu :
1. Kelompok komoditas berdasarkan International standart of
industrial classification, ISIC antara lain :
a. Industri makanan, minuman dan tembakau.
b. Industri tekstil, pakaian jadi dan kulit.
c. Idustri kayu dan barang-barang dari kayu termasuk perabot
rumah tangga.
d. Industri kertas, dan barang-barang dari kertas, percetakan
dan penerbitan.
e. Industri kimia dan bahan kimia.
f. Industri barang galian bukan logam, kecuali minyak bumi
dan batu bara.
g. Industri logam dasar.
h. Industri barang dari logam, mesin dan pengecatannya.
i. Industri pengolahan.
2. Industri berdasarkan skala usaha yaitu :
b. Sub sektor pengilangan minyak bumi.
c. Sub sektor pengolahan gas lam cair.
3. Industri berdasarkan arus produknya, yaitu :
a. Industri hulu, terdiri dari industri kimia dasar dan industri
mesin, logam dasar dan elektronika.
b. Industri hilir, terdiri dari aneka industri dan industri kecil.
4. Industri berdasarkan pendekatan besar kecilnya tenaga kerja
pengunit usaha, yaitu :
a. Industri besar, berpekerja 100 orang atau lebih.
b. Industri sedang, berpekerja antara 20 sampai 99 orang.
c. Industri kecil, berpekerja antara 5 sampai 19 orang.
d. Industri atau kerajinan rumah tangga, berpekerja kurang dari 5 orang. (Dumairy, 1997 : 231 ).
2.2.5.5. Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih
Cakupan sub-sub sektor ini meliputi listrik dan seluruh kegiatan
kelistrikan, baik yang diusahakan oleh Perusahaan Listrik Negara (
PLN ) maupun non Perusahaan Listrik Negara ( PLN ). Data
produksi diperoleh dari kantor Perusahaan Listrik Negara ( PLN ). Gas
meliputi usaha pembuatan dan penyaluran gas kota, dan air bersih
adalah usaha pengolahan, penjernihan dan pendistribusian air bersih
yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM ).
2.2.5.6. Sektor Bangunan
Cakupan sektor ini adalah semua pengembangan fisik seperti
gedung, jembatan, jalan, terminal, bendungan, saluran irigasi, jaringan
listrik, air, telepon, gas, dan sebagainya. Nilai tambah bruto atas dasar
harga berlaku dihitung dengan cara deflasi, dimana sebagai deflatornya
adalah indeks Harga perdagangan Besar ( HPB ) bahan bangunan dan
konstruksi. (Anonim, 2003 : 27 ).
2.2.5.7. Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran
Pengertian perdagangan adalah segala transaksi yang dilakukan
oleh suatu negara dalam hubungan ekonominya dengan negara lain
baik berupa barang, jasa, maupun dana. ( Dumairy,1997 : 90 ).
Perdagangan Luar Negeri merupkan salah satu aspek penting
dalam perekonomian setiap Negara. Perdagangan Luar Negeri menjadi
semakin penting, bukan saja dalam kaitan dengan haluan
pembangunan yang berorientasi ke luar, yakni membidik masyarakat
di negara-negara lain sebagai pasar hasil-hasil produksi dalam negeri,
tetapi juga berkaitan dengan pengadaan barang-barang modal untuk
memacu industri dalam negeri. Mengenai kecenderungan serta kinerja
ekspor dan impor bukan saja berguna untuk mencermati
perkembangan neraca perdagangan suatu Negara, akan tetapi
bermanfaat pula untuk menyingkap pola dan karakteristik perdagangan
diketahui keunggulan dan kelemahan ekspor Negara yang
bersangkutan, perilaku konsumsi masyarakatnya, serta kerentanan
sektor industri Negara tersebut.
( Anonim, 2003 : 27 ).
2.2.5.8. Sektor Angkutan dan Komunikasi
Sektor angkutan dan komunikasi mencakup sub-sub sektor sebagai
berikut ini :
1. Angkutan rel, cakupan sub sektor ini meliputi kegiatan angkutan
barang dan penumpang yang dilakukan oleh perusahaan angkutan
rel ( kereta api).
2. Angkutan jalan raya, cakupan sub sektor ini meliputi kegiatan
angkutan barang dan penumpang yang dilakukan oleh
perusahaan/usaha angkutan umum, baik bermotor, seperti bus,
truk, angkutan desa/kota, taksi, ojek, dokar, becak, dan lain-lain.
3. Angkutan udara, cakupan sub sektor ini meliputi kegiatan angkutan
barang dan penumpang termasuk kegiatan lainnya berkaita dengan
penerbangan yang dilakukan oleh perusahaan penerbangan
nasional, Dalam Negeri maupun Luar Negeri .
4. Pos dan Telekomunikasi, cakupan sub sektor ini meliputi kegiatan
pemberian jasa pos dan giro seperti pengiriman surat, wesel, paket,
5. Telekomunikasi, cakupan sub sektor ini meliputi semua kegiatan
pemberian jasa dalam pemakaian sambungan telepon, teleks, dan
telegram. ( Anonim,2003 : 29 ).
2.2.5.9. Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan
Cakupan sektor ini meliputi cakupan sub sektor baik diperoleh
dari data Bank Indonesia tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia (
SBI ) dan pinjaman luar negeri, karena hal ini merupakan
kebijaksanaan moneter yang bukan merupakan kegiatan komersial
bank. Cakupan sub sektor lembaga bukan bank meliputi kegiatan
asuransi, koperasi, yayasan dana pensiun dan pegadaian. Jasa
penunjang keuangan meliputi, kegiatan ekonomi antara lain bursa efek,
perdagangan valuta asing, perusahaan anjak piutang, modal ventura,
dan sewa bangunan meliputi semua kegiatan atas penggunaan
bangunan rumah sebagai tempat tinggal dan bukan tempat tinggal,
tanpa memperhatikan apakah rumah itu milik sendiri atau rumah yang
disewa.
( Anonim, 2003 : 33 ).
2.2.5.10. Sektor Jasa
Cakupan sektor ini meliputi jasa pemerintahan yaitu, meliputi seluruh
kegiatan pemerintah yang bersifat memberikan jasa kekayaan umum kepada
melaksanakan kegiatan ekonomi umum, memberikan jaminan keamanan dan
hukum dan menjadikan sarana dan prasarana. ( Anonim, 2003 : 35 ).
2.2.6. Analisis Tipologi Daerah
Analisis Tipologi Daerah merupakan alat analisis yang dapat digunakan
untuk mengidentifikasi sektor, subsektor, usaha, atau komoditi prioritas atau
unggulan suatu daerah. Dalam hal ini Analisis Tipologi Daerah dilakukan dengan
membandingkan pertumbuhan ekonomi daerah yang menjadi acuan atau nasional
dan membandingkan pangsa sektor, subsektor, usaha atau komoditi suatu derah
dengan nilai rata-ratanya ditingkat yang lebih tinggi atau secara nasional. Hasil
analisis Tipologi Daerah akan menunjukkan posisi pertumbuhan dan pangsa
sektor, subsektor, usaha, atau komoditi pembentuk variabel regional suatu daerah.
Tipologi Daerah juga merupakan suatu alat analisis ekonomi regional,yaitu alat
analisis yang digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur
pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pada pengertian ini, Tipologi Daerah
dilakukan dengan membandingkan pertumbuhan ekonomi daerah dan
pertumbuhan ekonomi daerah yang menjadi acuan atau nasional dan
membandingkan pertumbuhan PDRB per kapita daerah dengan PDRB per kapita
daerah yang menjadi acuan atau PDB per kapita ( secara nasional ). Teknik yang
digunakan untuk mengetahui gambaran pola dan struktur pertumbuhan ekonomi
daerah. Sjafrizal ( 1997 : 68 ) menjelaskan bahwa dengan menggunakan alat
Kuadran I, Daerah cepat tumbuh dan cepat sejahtera. Apabila
pertumbuhan ekonomi daerah tersebut lebih besar daripada rata-rata
pertumbuhan ekonomi daerah dan PDRB per kapitanya lebih besar dari
dari rata-rata PDRB.
Kuadran II, daerah tidak tumbuh tapi sejahtera. Apabila PDRB per
kapitanya lebih besar dari rata-rata PDRB sedangkan pertumbuhan
ekonomi daerah tersebut lebih kecil dari rata-rata pertumbuhan
ekonomi daerah.
Kuadran III, keadaan dimana PDRB perkapita daerah ( I ) acuan lebih
besar daripada PDRB rata-rata propinsi, akan tetapi laju pertumbuhan
ekonomi daerah acuan lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan
ekonomi, atau lebih besar dari propinsi. Daerah ini bisa disebut daerah
yang tumbuh tapi tidak sejahtera.
Kuadran IV, keadaan dimana PDRB perkapita daerah ( I ) sasaran
lebih kecil daripada PDRB rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah
propinsi tetapi pertumbuhan ekonominya pun juga tidak lebih kuat
daripada rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah. Daerah ini disebut
daerah tidak tumbuh dan tidak berkembang.
2.3 Kerangka Pikir
Dalam penelitian ini indikator pertama yang digunakan adalah produk
pendapatan perkapita yang diuji dengan menggunakan Indeks Wiliamson
Dengan menggunakan Indeks Wiliamson, kita dapat diketahui daerah mana
Wiliamson dihubungkan dengan pertumbuhan ekonomi maka dapat diketahui
pengaruh kuat maupun tidak kuat setelah itu dapat di buat suatu korelasi daerah
menjadi tiga bagian.
- Daerah ekonomi tumbuh dan sejahtera
- Daerah ekonomi tapi tidak sejahtera
- Daerah ekonomi tidak tumbuh tapi sejahtera
Pendapatan Perkapita
IndeksWiliamson
senjang tidak senjang
Tipologi Daerah
2.4 Hipotesis
Berdasarkan perumusan masalah, yang dapat diajukan sebagai suatu
hipotesis adalah sebagai berikut :
a. Diduga ketimpangan pembagian pendapatan perkapita semakin
kecil di 3 kabupaten
b. Diduga pertumbuhan ekonomi dapat mempersempit ketimpangan
pembangunan di 3 kabupaten
c. Diduga bahwa 3 kabupaten tersebut mempunyai tipe daerah yang
43
3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Yang dimaksud dengan definisi operasional dan pengukuran variabel
adalah mendefinisikan konsep yang akan dioperasionalkan kedalam penelitian dan
kemudian dilakukan sebuah pengukuran berdasarkan teori-teori yang ada maupun
pengalaman-pengalaman empiris. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi salah
pengertian terhadap variabel yang dibahas serta memudahkan dalam penerapan
data yang digunakan. Penelitian ini dalam menganalisis permasalahan
menggunakan variabel-variabel dari alat analisis tipologi daerah. Variabel tersebut
terdiri atas :
1. PDRB perkapita wilayah di Kabupaten
Adalah total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi di suatu
wilayah (regional) dibagi dengan jumlah penduduk dalam waktu satu
tahun daerah yang digunakan. Dalam hal ini adalah daerah wilayah
kabupaten Pacitan, Magetan, Madiun.
2. IW menjadi acuan Indek WilliamSon per wilayah di kabupaten
Pacitan, Magetan, dan Madiun.
3. Pertumbuhan ekonomi perwilayah di Kabupaten Pacitan, Magetan,dan
Adalah kenaikan PDRB wilayah tanpa memandang apakah kenaikan
tersebut lebih besar atau lebih kecil daripada dinyatakan dalam satu
persen.
3.2. Jenis dan Sumber Data
Dalam penelitian ini data yang digunakan berasal dari sumber data
sekunder, data tersebut adalah :
1. Data PDRB Propinsi Jawa Timur menurut lapangan usaha, PDRB
perkapita Propinsi Jawa Timur mulai tahun 2004 sampai tahun 2008 atas
harga dasar konstan. Dan tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik
Propinsi Jawa Timur.
2. Data Laju pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pacitan,Magetan, Madiun
tahun 2004 sampai dengan tahun 2008. Data tersebut diperoleh dari
Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur.
3. Data Pendapatan Perkapita di kabupaten Pacitan , Magetan, dan Madiun.
Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik Produksi Jawa Timur.
4. Data pendukung lainnya seperti jumlah penduduk, luas wilayah yang
diperoleh dari berbagai literatur bacaan.
3.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data
Untuk melengkapi data guna menganalisis permasalahan, maka data
1. Metode dokumentasi
Melalui metode ini data dikumpulkan dari berbagai literatur, laporan
penelitian, jurnal dan lainnya yang mendukung penelitian ini.
2. Pengolahan data.
Data yang berhubungan dengan obyek penelitian disusun untuk
selanjutnya diolah dengan menggunakan alat analisis matematis yang
berupa Indek Williamson yang kemudian dilakukan pengamatan selama
kurun waktu tertentu.
3.4. Teknis Analisis
Analisis yang digunakan adalah
1) Indek Williamson
IW = (Y Y)2fi/n
1
Y1 = PDRB perkapita wilayah Kabupaten
Y = PDRB perkapita Jawa Timur
Y1 = jumlah penduduk di masing-masing wilayah Kabupaten
n = jumlah penduduk Jawa Timur
Keterangan : -.
Makin kecil Indeks WilliamSon makin tidak timpang dan sebaliknya.
2) Mencari Tipologi Daerah dengan membandingkan
- Pendapatan perkapita Kabupaten dengan Pendapatan perkapita
- Pertumbuhan ekonomi Kabupaten dengan Pertumbuhan ekonomi Jawa
Timur
(G Kab : G Prop)
Tabel : Tipe daerah
PK Kab > PK Prop PK Kab < PKI Prop
G Kab > G Prop Daerah Tumbuh dan
sejahtera
Daerah Tumbuh tapi
tidak sejahtera
G Kab < G Prop Daerah tidak tumbuh tapi
sejahtera
Daerah tidak tumbuh dan
tidak sejahtera
Sumber :Mudrajad 2008:334
Keterangan :
PK Kab : Pendapatan perkapita Kabupaten
PK Prop: Pendapatan perkapita Propinsi
G Kab : Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten