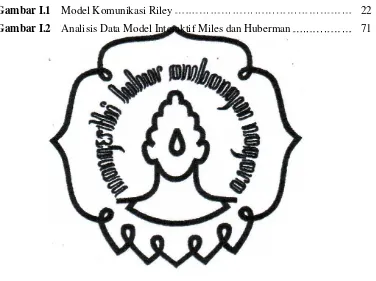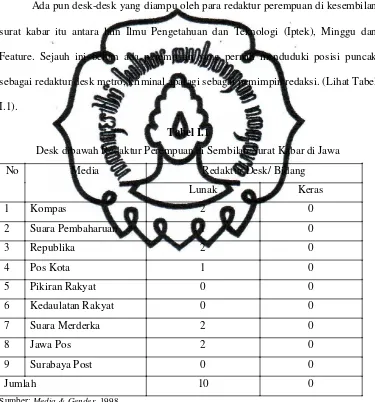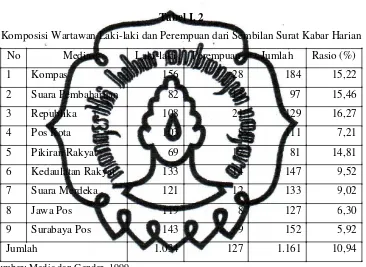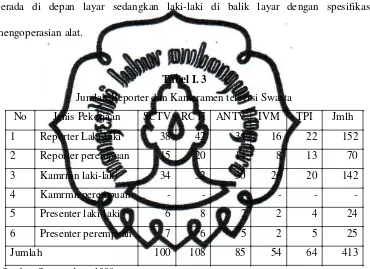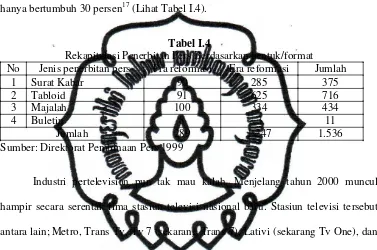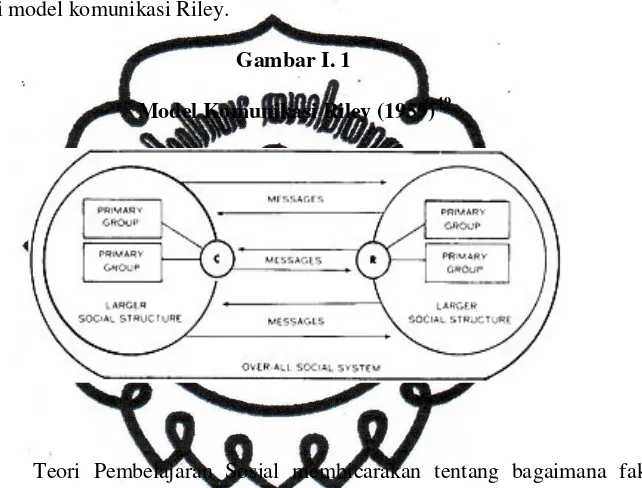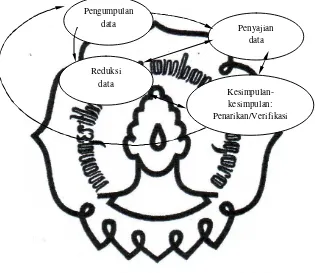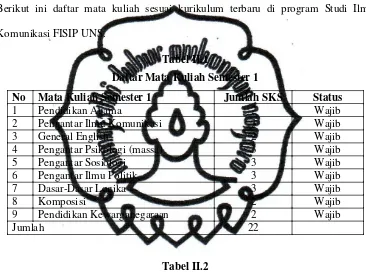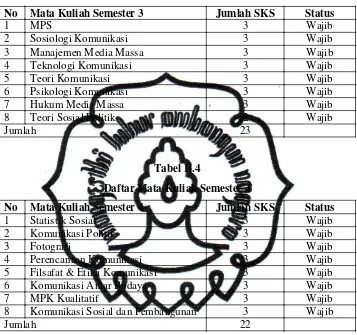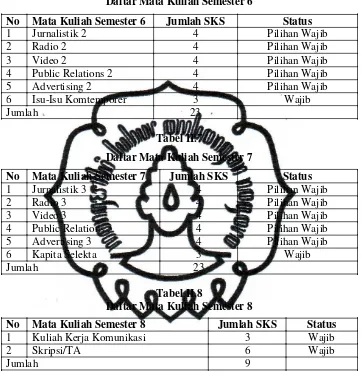PEREMPUAN DAN PROFESI JURNALIS
(
Studi Kasus Mengenai Persepsi Perempuan terhadap Profesi
Jurnalis di Kalangan Mahasiswi S-1 Program Studi Ilmu
Komunikasi FISIP UNS)
SKRIPSI
Disusun Oleh:
FRANCISKA ANISTIYATI
D0206054
Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi
pada Program Studi Ilmu Komunikasi
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
Motto:
Persembahan:
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kepada Allah Bapa Yang Maha Kasih, karena hanya dengan
kehendak-Nya, skripsi berjudul PEREMPUAN DAN PROFESI JURNALIS (Studi
Kasus mengenai Persepsi Perempuan terhadap Profesi Jurnalis di Kalangan
Mahasiswi S-1 Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UNS) telah terselesaikan
dengan baik.
Skripsi ini dilatarbelakangi oleh minat Penulis pada kajian perempuan
khususnya di bidang media. Ada pun secara khusus, buku
telah menginspirasi Penulis untuk menyusun skripsi ini. Buku tersebut
memaparkan data bahwa jumlah jurnalis perempuan di Indonesia begitu sedikit. Dari
situ Penulis menjadi tertarik untuk mengetahui mengapa hanya sedikit perempuan
yang tertarik menjadi jurnalis. Sebagai penelitian komunikasi, Penulis kemudian
membatasi permasalahan ini dalam bingkai konsep persepsi.
Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan pertolongan baik moril
maupun material dari berbagai pihak. Atas selesainya skripsi ini, Penulis ingin
mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berbaik hati memberikan
dukungan:
1. Prof. Drs. H. Pawito, Ph.D, selaku Dekan FISIP UNS sekaligus Ketua Panitia
Ujian Skripsi Penulis. Terima kasih atas koreksi dan masukan yang
2. Dra. Prahastiwi Utari, M.Si, Ph.D, selaku Ketua Program Studi Ilmu
Komunikasi FISIP UNS sekaligus pembimbing skripsi Penulis, terima kasih
untuk setiap diskusi yang mencerahkan. Terima kasih pula telah mengajari
Penulis tentang arti kesabaran dan ketekunan. Penulis yakin, kehadiran Ibu
dalam skripsi ini bukanlah sebuah kebetulan.
3. Mahfud Anshori, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Panitia Ujian Skripsi Penulis.
Terima kasih atas koreksi dan masukan yang membangun sehingga skripsi ini
menjadi lebih baik.
4. Drs. H. Dwi Tiyanto, SU selaku pembimbing Akademik Penulis. Terima
kasih untuk motivasi yang diberikan.
5. Teman-teman Informan: Annisa Fitri dkk, Dian Erika dkk dan Ema Yuliani
dkk, t berhenti
sebagai impian belaka.
6. Bapak Supriyono, Ibu MM. Suti Rahayu dan Mas Yoseph Kelik Prirahayanto,
terima kasih karena telah bersabar, terima kasih untuk doa dan semangat yang
terus mengalir. Semoga skripsi ini dapat menjadi alasan untuk tersenyum dan
menghirup nafas yang dalam
7. Cosmas Irmawan Henry Asmanto, terima kasih telah menjadi sahabat, kakak
dan partner yang setia.
8. Suki Family tercinta: Mutiara Oktaviani, Dara Narendra Dhuhita, Lopiana
Sita Hirlawati, Tri Setyo Ariyanti, Galuh Anindhita, Wahyu Aji Putranto,
Satria Yudha. Terima kasih telah menjadi teman curhat mulai dari urusan
remeh temeh hingga impian masa depan.
9. Saudara-saudariku seibu: Candra, Mas Fijar, Mbak Dhita, Era, Dewi, Mbak
Elya, Aang, Asiska, Dinda. Kebersamaan dan perjuangan bersama kalian tak
pernah terlupa teman. Sukses untuk kita semua,
10.Teman-teman Komunikasi 2006 yang baik hati: Cesil, Duo Arum, Fika,
Nunung, Lalak dan semuanya saja, sukses untuk kita semua. Yang masih
berjuang semangat ya, kebersamaan dengan kalian akan menjadi kenangan
indah di masa depan.
11.Bapak Argyo Dewantoto, terima kasih atas pinjaman buku-buku gender yang
sangat bermanfaat.
12.Mas Budi, staff pendidikan, dan pihak-pihak yang tak dapat disebut satu per
satu, terima kasih atas kebaikannya
Penulis tak menutup mata bahwa sebagai pekerjaan manusia, skripsi ini
bukanlah pekerjaan yang sempurna. Oleh sebab itu Penulis membuka diri untuk
setiap kritik dan saran yang membangun. Akhir kata, terima kasih.
ABSTRAK
FRANCISKA ANISTIYATI, D0206054, PEREMPUAN DAN PROFESI JURNALIS (Studi Kasus mengenai Persepsi Perempuan terhadap Profesi Jurnalis di Kalangan Mahasiswi S-1 Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UNS)Skripsi, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret (FISIP UNS) Surakarta, 2012.
Media massa disebut-sebut sebagai dunia maskulin. Bias gender yang cenderung merugikan perempuan masih mewarnai media di berbagai aspek mulai dari struktur organisasi, ritme kerja hingga berita yang dihasilkan. Rendahnya jumlah jurnalis perempuan dituding sebagai salah satu faktor pelestari maskulinitas media. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat pada laki-laki penganut prinsip kesetaraan gender, perjuangan keadilan bagi perempuan di media idealnya dipelopori oleh perempuan itu sendiri. Sebagaimana termaktup dalam rumusan jurnalisme sensitif gender, peningkatan jumlah jurnalis perempuan pun menjadi agenda mendesak dalam rangka menciptakan media yang lebih adil gender.
Tingginya harapan akan peningkatan partisipasi perempuan sebagai jurnalis pada perjalanannya harus terkendala oleh minat perempuan yang masih rendah. Kondisi ini patut dipertanyakan karena jurusan Ilmu Komunikasi yang merupakan pendidikan untuk mencetak praktisi media tengah dibanjiri peminat. Perlu pula untuk digarisbawahi bahwa mayoritas peminat jurusan Ilmu Komunikasi adalah perempuan. Disini Penulis melihat adanya kesenjangan antara perempuan yang berpotensi sebagai jurnalis dengan mereka yang kemudian memutuskan menjadi jurnalis.
Berdasarkan uraian di atas, masalah yang diangkat pada penelitian ini yaitu bagaimana persepsi mahasiswi terhadap profesi jurnalis serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi. Ada pun subjek penelitian ini yaitu Mahasiswi S-1 Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UNS dengan pertimbangan aksesbilitas.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan postpositivistik rasionalistik. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Untuk pengumpulan data digunakan
metode wawancara mendalam (indepth interview). Selanjutnya dengan menggunakan
teknik purpossive sampling diperoleh 18 orang informan penelitian. Untuk validitas data diuji melalui teknik triangulasi sumber (data) dan analisa data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman.
Persepsi idealistis terjadi pada mahasiswi semester awal dimana jurnalis menjadi pekerjaan ideal bagi mereka. Menurut mereka profesi ini menjanjikan berbagai kesenangan diantaranya seperti jalan-jalan dan menyalurkan hobi menulis. Namun, minat tersebut mengalami pergeseran dan munculkan persepsi realistis. Beberapa mahasiswi menjadi kurang tertarik menjadi jurnalis karena menurut mereka pekerjaan ini terlalu berat untuk perempuan, diantaranya dalam hal jam kerja yang tidak tentu, lokasi kerja di lapangan dan juga sisi keamanan. Pergeseran minat tersebut terjadi setelah mereka mengikuti mata kuliah profesi dan ada program Kuliah Kerja Komunikasi (K3).
ABSTRACT
FRANCISKA ANISTIYATI, D0206054, YOUNG WOMEN AND JOURNALIST (Case Study about Young Women Perception toward Journalist in Undergraduate Female Students on Communication Department of Social and Political Faculty Sebelas Maret University Surakarta), Paper, Communication Science Majors, Social and Political Science Faculty, Surakarta Sebelas Maret University (FISIP UNS), 2012
Mass media is regarded as masculine world. Gender bias still colors the media in many aspects such as the organization structure, work rhythm, and the presenting of sensitive gender news. The low number of female journalist is regarded as one of the supportive factor of media masculinity. Without decreasing the respect to men
must be started by women theirselves. The improvement of female journalist number is expected can give more fair perspective dealing with gender in media, such as formulated in sensitive gender journalism.
fact should face any obstacles because women have low interest to be a journalist. This condition must be asked because people who are interested in Communication Department Education increases recently and one thing that must be underlined is woman have been the majority of people who are interested in this department. The writter see that there was gap between women who are potential as journalist and women who decide to be a journalist.
Based on the statement above, the problem raised in this research is how
of this research are Undergraduate Female Students of Communication Department of Social and Political Faculty Sebelas Maret University Surakarta with the accessibility consideration.
To answer that problem, researcher uses qualitative research methodology with postpositivism-rasionalism approach. Meanwhile, the writter used case study as a method research. Meanwhile the data collection uses in depth interview. Purposive sampling technique is used to choose eighteen research informants. The validity of the data is tested through source triangulation technique (data) and the data analysis uses Miles and Huberman Interactive model.
there is a change after that. This is the rising of realistic perception. Many student became uninterested to be journalist because it feel too hard for woman such as uncertain work time, outdoor place, and the safety. This change happen after they follow profession class dan Kuliah Kerja Komunikasi (K3).
The perception of Female Students to journalist was happen through social learning process by Osgood . They try to collect information about journalist to get final evaluation that become the basic of their attitude exchange. The writer sees there is a strong negative impact from the environment and the lack of motivation of
DAFTAR ISI
F. Review Penelitian Terdahulu ... 53
3. Subjek Penelitian ... 65
A. Gambaran Umum Prodi Ilmu Komunikasi FISIP UNS ... 72
1. Sejarah Prodi Ilmu Komunikasi FISIP UNS ... 72
2. Struktur Organisasi Prodi Ilmu Komunikasi FISIP UNS... 73
3. Visi Program Studi ... 74
4. Misi Program Studi ... 74
5. Tujuan Program Studi ... 75
6. Kurikulum ... 76
7. Substansi Mata Kuliah Spesialisasi ... 80
8. Profil Dosen... 81
9. Kemahasiswaan ... 82
10. Sarana dan Prasarana Pendidikan ... 82
11. Profil Lulusan ... 84
B. Gambaran Umum Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi FISIP UNS ... 84
C. Data Subjek Penelitian ... 86
BAB III. PERSEPSI MAHASISWI S-1 PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI FISIP UNS TERHADAP PROFESI JURNALIS ... 95
A. Pemilihan Jurusan Ilmu Komunikasi ... 97
1. Faktor Personal ... 98
1.1. Pengetahuan Mengenai Jurusan Ilmu Komunikasi ... 94
1.2. Motif Kuliah di Jurusan Ilmu Komunikasi ... 112
2. Faktor Situasional ... 130
2.1. Significant Others ... 131
B. Pemilihan Pekerjaan Bidang Komunikasi ... 154
1. Ideal Type ... 155
2. Transition Type ... 173
3. Real Type ... 181
C. Persepsi Mahasiswi S-1 Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UNS terhadap Profesi Jurnalis ... 195
1. Persepsi Idealistis ... 196
2. Persepsi Realistis ... 213
3. Pengaruh Significant Others ... 228
BAB IV. PENUTUP ... 235
A.Kesimpulan ... 235
B.Saran ... 240
DAFTAR PUSTAKA ... 242
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel I.1 Desk dibawah Redaktur Perempuan di Sembilan Surat Kabar di
4
Tabel I.2 Komposisi Wartawan Laki-laki dan Perempuan dari Sembilan
6
Tabel I.3 Jumlah Reporte 7
Tabel I.4 Rekapitulasi Penerbitan Pers Berdasarkan bentuk/format 9
Tabel II.1 Daftar Mata Kuliah Semester 1 77
Tabel II.2 Daftar Mata Kuliah Semester 2 77
Tabel II.3 Daftar Mata Kuliah Semester 3 78
Tabel II.4 Daftar Mata Kuliah Semester 4 78
Tabel II.5 Daftar Mata Kuliah Semester 5 78
Tabel II.6 Daftar Mata Kuliah Semester 6 79
Tabel II.7 Daftar Mata Kuliah Semester 7 79
Tabel II.8 Daftar Mata Kuliah Semester 8 79
Tabel II.9 Daftar Mata Kuliah Pilihan 79
Tabel II.10Jumlah Mahasiswa S-1 Reguler Program Studi Ilmu Komunikasi
FISIP UNS Akademik 2010/2011 85
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar I.1 Model Komunikasi Riley 22
DAFTAR BAGAN
Halaman
Bagan I.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi menurut
Robbins dan Judge 32
Bagan I.2 Kerangka Berpikir 58
Bagan II.1 Struktur Organisasi Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UNS .... 73
Bagan III.1 Pemilihan Jurusan Ilmu Komunikasi 153
Bagan III.2 193
Bagan III.3 Pergeseran Pilihan Pekerjaan Bidang Komunikasi 193
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH
Media massa disebut-sebut sebagai dunia maskulin. Kepekaan media terhadap
persoalan-persoalan gender dianggap masih kurang dan cenderung merugikan
perempuan. Mengutip pernyataan Marwah Daud Ibrahim dalam Ibrahim dan Suranto,
sejauh ini media dianggap masih melanggengkan stereotip yang merugikan
perempuan. Perempuan disosialisasikan sebagai makhluk yang pasif, tergantung pada
pria, didominasi, menerima keputusan yang dibuat oleh pria dan terutama pasrah
melihat dirinya sebagai simbol seks1.
Bias gender di media pertama-tama dapat dilihat dari bagaimana surat kabar,
majalah, film, televisi, iklan, dan buku-buku menampilkan potret diri perempuan.
Mari kita sejenak melihat fenomena perempuan dalam berita kejahatan dan kriminal.
-2
;
3. Tanpa membaca berita lebih
lanjut, dari judul dapat ditangkap bahwa korban dari tindak pelecehan seksual adalah
1
Marwah Daud Ibrahim dalam Idi Subandy Ibrahim, dkk (ed), Wanita dan Media: Konstruksi Ideologi gender dalam Ruang Publik Orde Baru. (Bandung:Remaja Rosdakarya, 1998), hlm.107
2
eptember 2010
3
Ahmad Tarmizi,
perempuan dan laki-laki berperan sebagai pelaku. Tidak dapat disangkal bahwa kasus
pelecehan seksual selama ini begitu identik dengan keberadaan laki-laki sebagai
pelaku dan perempuan sebagai korban.
Selanjutnya, ada beberapa kata yang sering muncul dalam berita kriminal
khususnya berita perkosaan antara lain sebagai berikut:
dsb. Secara tidak langsung korban (perempuan) justru semakin dieksploitasi dengan
pilihan-pilihan kata di berita. Sebaliknya, sosok pelaku (laki-laki) yang semestinya
mereka lakukan. Dalam kasus ini lengkaplah sudah derita perempuan. Sudah jatuh
masih tertimpa tangga. Sudah menjadi korban yang menanggung beban psikologis
masih diberitakan tanpa rasa simpati yang semakin menambah luka.
Menjadikan berita kriminal sebagai bukti dari bias gender di media mungkin
terlalu ekstrim. Ada baiknya kita mencoba mengamati berita-berita regular tentang
perempuan yang dimuat dalam rubrik atau media khusus perempuan. Hasilnya,
menurut Debra H. Yatim selama ini media perempuan cenderung menyajikan berita
atau artikel yang bersifat domestik yaitu menyangkut rumah tangga, mode,
perawatan, keluarga dan anak, serta profil tokoh perempuan yang berhasil pada
bidang-bidang tersebut4. Disini dapat dirasakan bagaimana media mengkonstruksikan
peran perempuan sebagai penguasa wilayah domestik.
4
Sekadar sebagai pembelaan terhadap media, kerap dikatakan bahwa media
tidak lebih, tidak kurang adalah cermin bagi realitas yang beredar di masyarakat.
Namun, pembelaan itu ditangkis oleh Debra H. Yatim dengan mengajukan sudut
pandang lain bahwa media memiliki hubungan dua arah dengan realitas sosial. Selain
menjadi cermin dari realitas, media sebenarnya juga menciptakan realitas (realitas
media)5. Saat sebuah berita dianggap kurang sensitif gender, melalui kaca mata Debra
H Yatim penyebabnya dapat dirunut dari dua sumber: pertama, kenyataan di
masyarakat memang demikian, atau kedua, subjektivitas wartawan dan editorlah yang
bermain.
Kiranya berita bias gender dapat diminimalisir jika didasari oleh kesadaran
akan kemungkinan kedua. Nursyahbani Katjasungkana dalam sebuah artikel pernah
menuliskan harapannya untuk gerakan kesetaraan gender, yang tentunya ini relevan
juga jika dihadapkan pada bias gender yang masih mewarnai media:
eputusan, mungkin akan lebih cepat mewujudkan kesetaraan dan keadilan antara laki-laki
6
.
Pada kenyataannya, media masih sepi dari campur tangan perempuan. Jumlah
redaktur perempuan di media sejauh ini masih minim. Menurut hasil penelitian dari
Lembaga Penelitian Pendidikan Penerbitan Yogyakarta (LP3Y) dan Ford Foundation
tahun 1998, pada sembilan surat kabar di Jawa (Kompas, Republika, Suara
5
Ibid, hlm. 134 6
Pembaharuan, Pos Kota, Pikiran Rakyat, Suara Merdeka, Kedaulatan Rakyat,
Surabaya Post, Jawa Pos) maksimal baru terdapat dua jurnalis perempuan yang
menduduki jabatan sebagai redaktur desk dan bidang7.
Ada pun desk-desk yang diampu oleh para redaktur perempuan di kesembilan
surat kabar itu antara lain Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek), Minggu dan
Feature. Sejauh ini belum ada perempuan yang pernah menduduki posisi puncak
sebagai redaktur desk metro, kriminal apalagi sebagai pemimpin redaksi. (Lihat Tabel
I.1).
Tabel I.1
Desk dibawah Redaktur Perempuan di Sembilan Surat Kabar di Jawa
No Media Redaktur Desk/ Bidang
Lunak Keras
1 Kompas 2 0
2 Suara Pembaharuan 1 0
3 Republika 2 0
4 Pos Kota 1 0
5 Pikiran Rakyat 0 0
6 Kedaulatan Rakyat 0 0
7 Suara Merderka 2 0
8 Jawa Pos 2 0
9 Surabaya Post 0 0
Jumlah 10 0
Sumber: Media & Gender, 1998
7
Di lingkup yang lebih sempit, Dalam struktur kepengurusan PWI Cabang
Surakarta masa bakti 2006-2010 hasil Konferensi Cabang 2 Desember 2006 terdapat
kenderungan sama. Dari 14 pengurus, hanya dua orang perempuan yang masuk dalam
struktur organisasi PWI Cabang Surakarta. Itu pun masih menjadi orang nomer dua,
masing-masing sebagai Wakil Sekretaris II dan Wakil Ketua Seksi Seni, Budaya dan
Pariwisata8.
Melalui stuktur keorganisasian, maskulinitas media begitu terasa melalui
pembagian kerjanya yang bersifat sex-line. Laki-laki ditempatkan pada bidang kerja keras (hard) seperti bidang politik, ekonomi, hukum dan kriminal serta olahraga.
Sedangkan perempuan ditempatkan pada bidang yang lunak (soft) seperti pendidikan,
kesejahteraan masyarakat, pariwisata, budaya, dan hiburan serta ilmu pengetahuan
dan teknologi9. Terdapat sebuah kecenderungan bahwa perempuan masih dianggap
sebagai orang nomer dua di media.
Lemahnya bargaining position maupun peran strategis perempuan di media menjadi tak mengherankan karena jumlah jurnalis yang ada di industri media selama
ini ternyata didominasi oleh laki-laki. Data tahun 1998 menunjukkan masih adanya
ketimpangan yang cukup jauh antara proporsi jurnalis perempuan dan laki-laki. Data
sembilan surat kabar harian besar yang terbit di Jawa yakni; harian Kompas, Suara
Pembaharuan, Republika, Pos Kota, Pikiran Rakyat, Kedaulatan Rakyat, Suara
8
Sumber: Data PWI Cabang Surakarta 9
Merdeka, Jawa Pos dan Surabaya Pos menunjukkan bahwa rata-rata hanya terdapat
14 orang jurnalis perempuan dari total 129 orang jurnalis yang bekerja, atau sekitar
11 persen saja. (Lihat pada Tabel I. 2)10.
Tabel I. 2
Komposisi Wartawan Laki-laki dan Perempuan dari Sembilan Surat Kabar Harian
No Media Laki-laki Perempuan Jumlah Rasio (%)
1 Kompas 156 28 184 15,22
2 Suara Pembaharuan 82 15 97 15,46
3 Republika 108 21 129 16,27
4 Pos Kota 103 8 111 7,21
5 Pikiran Rakyat 69 12 81 14,81
6 Kedaulatan Rakyat 133 14 147 9,52
7 Suara Merdeka 121 12 133 9,02
8 Jawa Pos 119 8 127 6,30
9 Surabaya Pos 143 9 152 5,92
Jumlah 1.034 127 1.161 10,94
Sumber: Media dan Gender, 1999
Kondisi yang sama juga terjadi di industri televisi. Dari Lima stasiun televisi
swasta di Indonesia yaitu SCTV, RCTI, ANTV, IVM dan TPI (sekarang MNCTV),
rata-rata perbandingan reporter perempuan dan laki-laki adalah 1: 211. Perbandingan
itu akan berubah nilainya jika seluruh kameramen masuk hitungan. Angka
10
Ibid. hlm.14 11
perbandingan bisa membengkak menjadi 1: 412 karena tidak ada kameramen
perempuan (Lihat Tabel I.3). Tak berbeda dari media cetak, industri televisi pun
membagi peran perempuan dan laki-laki dalam penugasan. Kebanyakan perempuan
berada di depan layar sedangkan laki-laki di balik layar dengan spesifikasi
mengoperasian alat.
Tabel I. 3
Jumlah Reporter dan Kameramen televisi Swasta
No Jenis Pekerjaan SCTV RCTI ANTV IVM TPI Jmlh
1 Reporter Laki-laki 38 42 34 16 22 152
2 Reporter perempuan 15 20 14 8 13 70
3 Kamrmn laki-laki 34 32 30 26 20 142
4 Kamrmn perempuan - - - -
5 Presenter laki-laki 6 8 2 2 4 24
6 Presenter perempuan 7 6 5 2 5 25
Jumlah 100 108 85 54 64 413
Sumber: Soemandoyo:1998
Dalam lingkup yang lebih luas, Data PWI tahun 1998 tentang data jumlah
wartawan di Indonesia menampilkan kecenderungan yang sama. Dari 4.687 orang
wartawan di Indonesia, diperoleh data bahwa jumlah wartawan perempuan hanya 461
orang atau sekitar 10 persen13.
12
ibid
13
Nur Iman Subono, , Jurnal Perempuan, Nomor. 28,
Adanya kecenderungan berita yang merugikan perempuan, sedikitnya
redaktur perempuan hingga rendahnya jumlah jurnalis perempuan, menjadi fakta dari
bias gender di media massa yang terjadi secara sistematis. Tak berlebihan jika Debra
H. Yatim kemudian menyebut media massa selama ini digarap, disunting, dan
diedarkan oleh pria untuk pria14.
Peningkatan jumlah jurnalis perempuan kemudian mengemuka sebagai salah
satu solusi untuk memutus mata rantai bias gender di media. Hal itu didukung oleh
Ana Nadhya Abrar yang menyatakan bahwa dengan tanpa mengurangi penghargaan
pada jurnalis laki-laki yang menganut prinsip kesetaraan gender, pelopor kesetaraan
gender di media tetaplah perempuan15. Masih rendahnya jumlah jurnalis perempuan
mengkondisikan peran perempuan yang masih terbatas dan untuk memperbesar
kekuatan perempuan di media maka dibutuhkah jumlah jurnalis perempuan yang
lebih banyak.
Harapan akan adanya peningkatan jumlah jurnalis perempuan di Indonesia
cukup terpupuk oleh pesatnya pertumbuhan industri media belakangan ini. Sejak era
booming pers16, Direktorat Pembinaan Pers tahun 1999 mencatat fenomena yang
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada Volume 7 No.3, Maret 2004, hlm. 384
16
Mursito BM, Memahami Institusi Media:Sebuah Pengantar, (Surakarta:Lindu Pustaka & Spikom,2006), hlm.190
terjadi khusus pada penerbitan cetak rata-rata terjadi lonjakan hingga 3 kali lipat.
Lonjakan paling tinggi terjadi pada tabloid disusul oleh surat kabar dan majalah.
Satu-satunya media cetak yang pertumbuhannya kurang signifikan yaitu buletin. Ia
hanya bertumbuh 30 persen17 (Lihat Tabel I.4).
Tabel I.4
Rekapitulasi Penerbitan Pers Berdasarkan bentuk/format
No Jenis penerbitan pers Pra reformasi Era reformasi Jumlah
1 Surat Kabar 90 285 375
hampir secara serentak lima stasiun televisi nasional baru. Stasiun televisi tersebut
antara lain;Metro, Trans Tv, Tv 7 (sekarang Trans 7), Lativi (sekarang Tv One), dan
Global18. Pers semakin diramaikan pula oleh munculnya media-media lokal19.
Sampai dengan tahun 2005 tercatat pertumbuhan televisi lokal mencapai angka 86
stasiun, tersebar di lebih dari 50 kota besar dan di hampir semua provinsi di
Indonesia20.
politik yang dikenal dengan era reformasi. Lonjakan pendirian penerbitan pers terjadi karena pencabutan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP).
17
Ibid, hlm.192 18
www.jiastisipolcandradimuka.blogspot.com diakses pada 19 Maret 2012 pukul 10: 29 WIB 19
http://www.mercubuana.ac.id/file/modul/CIPTONOSETYOBUDI-TEKNOLOGIKOMUNIKASI diakses pada 9 Desember 2011 pukul 06.53 WIB
20
Fenomena pertumbuhan media cetak dan televisi di atas dapat menjadi pijakan
untuk membayangkan betapa industri media di Indonesia sejak reformasi 1998
mengalami pertumbuhan yang signifikan. Kondisi itu menyiratkan adanya peluang
kerja di industri media salah satunya sebagai jurnalis, baik itu untuk laki-laki maupun
perempuan.
Idealnya, booming pers dapat menjadi peluang bagi perempuan untuk tampil sebagai jurnalis. Namun pada kenyataannya profesi ini belum cukup berhasil menarik
minat perempuan. Data tahun 2006 menunjukkan kondisi yang tak jauh berbeda dari
tahun 1998. Mengacu Laporan Kementerian Komunikasi dan Informasi RI tahun itu,
jumlah jurnalis laki-laki adalah 11.603 orang sedangkan jurnalis perempuan hanya
2.031 orang atau sekitar 15 persen21.
Permasalahan mengenai rendahnya jumlah jurnalis perempuan jika digali ke
akar pada akhirnya akan sampai pada institusi pendidikan tinggi. Hafied Cangara
dalam sebuah artikel mengatakan:
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kajian komunikasi yang selama ini banyak dikaitkan dengan media, kebijakan komunikasi (communication policies), isi (content), dan juga para pekerja komunikasi itu sendiri (wartawan, presenter, public relations officer, dan juga para dosen komunikasi),22. Dengan kata lain saat kita
21
Laporan Kementrian Komunikasi dan Informasi RI 2006 22
Hafied Cangara, dalam Farid
membicarakan rendahnya jumlah jurnalis perempuan kita pun harus menelusuri
persoalan itu dari hulunya yaitu pendidikan Ilmu Komunikasi.
Di Indonesia, pendidikan Ilmu Komunikasi mengalami pertumbuhan yang
cukup bagus. Menurut catatan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, pada tahun
2011 jumlah pendidikan Ilmu Komunikasi di Indonesia telah mencapai 199
perguruan tinggi negeri maupun swasta, baik dalam bentuk fakultas,
jurusan/departemen, STIKOM, politeknik maupun dalam bentuk program studi
(prodi) yang dicangkokkan di bawah jurusan non-komunikasi. Besarnya jumlah
lembaga pendidikan komunikasi ini menempatkan ilmu komunikasi di Indonesia
pada posisi ketiga program studi yang paling banyak ditawarkan setelah program
studi Ilmu Komputer (sekitar 500-an) sebagai peringkat pertama, dan program studi
akuntansi (sekitar 300-an) sebagai peringkat kedua23.
Pertumbuhan itu tak lepas dari tingginya minat calon mahasiswa baru untuk
kuliah di jurusan Ilmu Komunikasi. Dari tahun ke tahun peminat jurusan Ilmu
Komunikasi meningkat sejalan dengan pertumbuhan media massa belakangan ini.
Katakanlah pada SNMPTN tahun 2010, Ilmu Komunikasi menempati urutan pertama
sebagai program studi dengan peminat tertinggi. Disusul kemudian prodi Pendidikan
Dokter sebagai peminat tertinggi kedua, dan prodi Manajemen dengan peminat
tertinggi ketiga24.
23
Ibid, hlm. 32 24
Tingginya minat untuk mendaftar di jurusan Ilmu Komunikasi sudah tak
terbantahkan. Lantas bagaimana dengan input mahasiswa Ilmu Komunikasi sendiri? Jika dipilah berdasarkan jenis kelaminnya, ternyata diperoleh fakta bahwa komposisi
mahasiswa di jurusan Ilmu Komunikasi di Indonesia rata-rata di dominasi oleh
perempuan. Lock dalam Utari & Nilan menyebutkan bahwa perbandingan antara
perempuan dan laki-laki yang menempuh pendidikan di jurusan Ilmu Komunikasi di
Indonesia kurang lebih 7: 325.
Kondisi yang sama berlaku pula di Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UNS.
Turun temurun jumlah mahasiswi lebih banyak dari mahasiswa. Sebagai contoh pada
tahun ajaran 2010/2011. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bagian Pendidikan
FISIP UNS tahun 2010, mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi FISIP UNS yang masih
aktif sampai saat itu sebanyak 410 orang, yang terdiri dari 260 orang mahasiswi dan
150 orang mahasiswa26.
Banyaknya perempuan yang menempuh pendidikan Ilmu Komunikasi dapat
dibaca pula sebagai peluang semakin banyaknya perempuan yang akan masuk dalam
industri komunikasi salah satunya sebagai jurnalis. Namun, input mahasiswi jurusan Ilmu Komunikasi yang cukup besar ternyata tidak menjamin terpenuhinya pekerja di
bidang komunikasi. Sebagai contoh yang terjadi pada mahasiswa Prodi Ilmu
Komunikasi FISIP UNS angkatan 2005. Berdasarkan catatan alumni angkatan
25
The Lucky Few: Female Graduates of Communication Studies in the Indonesian Media Industry
26
tersebut dari 51 alumni, 31 diantaranya adalah perempuan. Hanya ada dua alumni
perempuan yang bekerja sebagai jurnalis (1 di majalah dan datu di surat kabar lokal).
Alumni perempuan lainnya bekerja di instansi-instansi lain seperti perbankan,
pendidikan dan pemerintahan27.
Dari secuil data di atas nampak adanya keengganan alumni jurusan Ilmu
Komunikasi untuk menjadi jurnalis. Secara keilmuan tentunya mereka mampu,
namun mengapa mereka justru lebih tertarik pada bidang pekerjaan lain bahkan
sampai menyeberang ke bidang kerja disiplin lain. Kiranya keengganan ini menjadi
kondisi yang perlu digali lebih dalam, mengapa perempuan tidak ingin menjadi
jurnalis. Pengalaman subjektif perempuan menjadi kunci jawabannya.
Fenomena ini menarik untuk diteliti karena rendahnya jumlah jurnalis
perempuan akhir-akhir ini mulai diperbincangkan terkait dengan agenda jurnalisme
humanitarian khususnya jurnalisme sensitif gender. Kehadiran jurnalis perempuan
dirasa perlu untuk menciptakan iklim hubungan gender yang lebih seimbang dan adil
di media. Namun sayang sekali harapan yang digantungkan pada jurusan Ilmu
Komunikasi untuk memasok jurnalis-jurnalis perempuan yang handal tidak
membuahkan hasil yang signifikan. Penelitian ini kemudian difokuskan pada konsep
persepsi. Dalam konteks penelitian komunikasi, penelitian ini termasuk sebagai
27
audience analysis atau studi khalayak yaitu penelitian yang fokus pada unsur komunikan (perempuan)28.
Sebagai mahasiswa komunikasi, penelitian ini menarik karena dapat
mempelajari bagaimana sebuah pesan dimaknai sehingga berpengaruh terhadap
sikap/perilaku manusia. Penelitian ini melihat komunikasi sebagai sebuah proses
namun yang dilihat bukanlah keseluruhan prosesnya melainkan terfokus pada efek
yang ditimbulkan oleh pesan. Metodologi penelitian ini adalah kualitatif. Adapun
metode penelitian ini menerapkan studi kasus.
B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah di
atas, maka Penulis merumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana persepsi mahasiswi S-1 Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP
UNS terhadap profesi jurnalis?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswi S-1 Program
Studi Ilmu Komunikasi FISIP UNS terhadap profesi jurnalis?
C.TUJUAN PENELITIAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:
28
1. Persepsi mahasiswi S-1 Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UNS terhadap
profesi jurnalis
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswi S-1 Program Studi Ilmu
Komunikasi FISIP UNS terhadap profesi jurnalis
D.MANFAAT PENELITIAN
Penulis berharap, penelitian ini dapat bermanfaat bagi :
1. Perempuan yang ingin berprofesi sebagai jurnalis,
Semoga penelitian ini dapat memberi gambaran mengenai realitas profesi
sebagai jurnalis sehingga para perempuan dapat mempersiapkan diri lebih
matang baik dalam hal pengetahuan, keterampilan maupun kesiapan mental.
2. Pengajar di Jurusan Ilmu Komunikasi
Semoga penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi para pengajar di
jurusan Ilmu Komunikasi terkait salah satu tujuan akademis di jurusan Ilmu
Komunikasi yaitu mencetak praktisi di bidang media. Semoga penelitian ini
menjadi awal dari evaluasi kurikulum pendidikan di jurusan Ilmu Komunikasi
khususnya terkait dengan pendidikan jurnalistik.
3. Pemerhati media dan gender
Semoga penelitian ini dapat memberi gambaran kesadaran gender di kalangan
mahasiswi, untuk selanjutnya menyelenggarakan penelitian atau membuat
E.TELAAH PUSTAKA
1. Komunikasi
1.1. Definisi Komunikasi
Sebagai makhluk sosial, manusia akan terus berinteraksi dengan
sesamanya. Selama itu pula manusia akan berkomunikasi. Menurut Habermas
dalam Bungin, komunikasi adalah inti dari interaksi sosial29. Pemikiran itu
kemudian disempurnakan John Fiske dengan mendefinisikan komunikasi
sebagai interaksi sosial melalui pesan30. Berpijak pada definisinya, Fiske
kemudian mengelompokkan komunikasi ke dalam dua mazhab yaitu Mazhab
Proses dan Mazhab Semiotika.
Mazhab Proses melihat komunikasi sebagai transmisi pesan. Bagaimana
pengirim-penerima mengkonstruksi pesan (encode) kemudian
menerjemahkannya (decode) dan bagaimana transmiter menggunakan saluran
dan media komunikasi merupakan fokus dari mazhab ini. Mazhab ini menaruh
ketertarikan pada efisiensi dan akurasi komunikasi yaitu saat komunikasi
mampu mempengaruhi perilaku atau state of mind orang lain. Komunikasi akan
dianggap gagal, apabila efek yang terjadi berbeda dari atau lebih kecil daripada
yang diharapkan31.
29
Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi, Cet.ke-2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007)hlm.26
30
John Fiske, Cultural and Communication Studies, (Yogyakarta: Jalasutra, 2011), hlm. 8 31
Di sisi lain, Mazhab Semiotika melihat komunikasi sebagai produksi
dan pertukaran makna. Mazhab ini berkenaan dengan bagaimana pesan atau
teks berinteraksi dengan orang-orang dalam rangka menghasilkan makna. Bagi
mazhab ini, studi komunikasi adalah studi tentang teks dan kebudayaan.
Berbeda dengan Mazhab Proses, Mazhab Semiotika tidak memandang
kesalahpahaman sebagai bukti yang penting dari kegagalan komunikasi32.
Antara Mazhab Proses dan Semiotika terdapat beberapa perbedaan yang
signifikan. Pertama fokus studi: Mazhab Proses memusatkan diri pada perilaku
atau tindakan komunikasi, sedangkan Mazhab Semiotika lebih fokus pada
karya komunikasi33. Kedua pendekatan keilmuan: Mazhab Proses cenderung mempergunakan ilmu-ilmu sosial seperti psikologi dan sosiologi sedangkan
Mazhab Semiotika cenderung mempergunakan linguistik dan subjek seni34.
Dan ketiga sifat pesan: menurut Mazhab Proses pesan bersifat statis. Artinya, pesan yang disampaikan adalah sama, tidak berubah. Yang dinamis adalah cara
penyampaiannya. Sebaliknya menurut Mazhab Semiotika pesan bersifat
dinamis. Mazhab ini lebih fokus pada bagaimana pesan dimaknai berdasarkan
referensi setiap orang yang tentunya berubah-ubah sesuai dengan
perkembangan kerangka referensi.
Mengacu pada pemikiran Fiske di atas, kiranya penelitian ini termasuk
dalam kategori mazhab komunikasi yang pertama yaitu komunikasi sebagai
32
Ibid, hlm.9 33
Ibid
34
proses. Hal itu karena fokus penelitian ini adalah mengamati perilaku
komunikasi yaitu bagaimana perempuan menanggapi profesi sebagai jurnalis.
Dan karena mengamati gejala perilaku maka penelitian ini tak luput dari
pengaruh disiplin ilmu sosiologi dan psikologi.
Harold Lasswell dalam karyanya yang berjudul The Structure and
Function of Communication in Society mengutarakan bahwa cara terbaik untuk menjelaskan komunikasi sebagai proses adalah dengan menjawab pertanyaan:
Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect?35Jawaban dari pertanyaan itu tidak lain adalah komponen-komponen komunikasi yaitu:
komunikator (orang yang menyampaikan pesan), pesan (pernyataan yang
didukung oleh lambang), komunikan (orang yang menerima pesan), media
(sarana atau saluran yang mendukung pesan bila komunikan jauh tempatnya
atau banyak jumlahnya) dan efek (dampak sebagai pengaruh dari pesan). Jadi
berdasarkan Paradigma Lasswell, komunikasi adalah proses penyampaian
pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan
efek tertentu36.
Menurut Effendy, setidaknya terdapat tiga tingkatan efek yang
diharapkan dalam proses komunikasi yaitu: efek kognitif, efek afektif dan efek
behavioral. Efek kognitif yaitu saat komunikan menjadi tahu atau intelektualitasnya meningkat; efek afektif yaitu saat komunikan tergerak hatinya
35
Effendy,Op.cit. hlm.10 36
sehingga memiliki perasaan tertentu dan efek behavioral yaitu saat komunikan tergerak untuk mengubah perilaku37.
Idealnya, komunikasi disebut efektif bilamana ia menghasilkan efek
behavioral. Hal itu seperti didefinisikan oleh Hovland, Janis dan Kelly dalam Rakhmat bahwa komunikasi adalah proses dimana individu menyalurkan
rangsangan untuk mengubah perilaku orang lain (communication is the process
by which an individual transmits stimuli to modify the behavior of the other individuals)38.
Sebagai proses, kelima komponen komunikasi yang terkandung dalam
paradigma Lasswell mutlak harus ada dalam setiap fenomena komunikasi.
Namun, penelitian ini tidak berniat mempelajari proses komunikasi dari awal
dan lebih fokus pada efek yang terjadi pada komunikan (perempuan). Menurut
Lasswell, penelitian ini disebut sebagai studi khalayak (audience analysis)39. Ada pun berdasarkan jumlah dan karakter komunikannya, penelitian ini
termasuk dalam konteks komunikasi antarpribadi (interpersonal
communication). Menurut Ruesch dan Bateson dalam Littlejohn yang kemudian dikutip oleh Liliweri, komunikasi antarpribadi yaitu relasi individual dengan
orang lain dalam konteks sosialnya. Melalui proses ini individu menyesuaikan
dirinya dengan orang lain lewat peran yang disebut transmitting dan
37
Onong Uchjana Effendy, Dinamika Komunikasi, Cet. ke-6, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm.7
38
Marhaeni Fajar, Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 31 39
receiving40. Transmitting yaitu pemindahan pesan baik verbal maupun
nonverbal sebagaimana telah dipaparkan di muka, sedangkan receiving
merupakan proses penerimaan pesan-pesan41.
Messege reception merupakan proses aktif yang terdiri dari tiga elemen yaitu: seleksi, interpretasi dan memori42. Seleksi yaitu bagaimana seseorang
memilih suatu pesan di antara banyaknya pesan yang ada di sekitarnya.
Interpretasi yaitu bagaimana seseorang memaknai pesan yang ia terima dan
memori adalah bagaimana seseorang mengorganisasikan pesan dalam sistem
ingatan43.
Menurut Littlejohn, proses messege reception mengarah pada tiga
aktivitas yang saling berhubungan yaitu interpretation, organization dan
judgement. Interpretation yaitu bagaimana individu memaknai suatu pesan, mencoba mengetahui maksud dari pesan, mencari sebab akibat. Organization
yaitu internalisasi pesan dalam sistem kepercayaan dan sikap. Sedangkan
judgement adalah penilaian berdasarkan informasi44.
Penelitian ini sendiri lebih fokus pada aktivitas pertama yaitu
interpretation, sebagai dasar dari persepsi khalayak terhadap profesi sebagai
40
Alo Liliweri, Perspektif Teoritis Komunikasi Antarpribadi, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 3 41
jurnalis. Menurut Deddy Mulyana, persepsi adalah inti dari komunikasi45.
Disebut sebagai inti komunikasi karena efektivitas komunikasi sangat
tergantung pada proses persepsi. Pembahasan persepsi lebih lanjut ada pada
point 2.
1.2. Teori Pembelajaran Sosial (Sosial Learning Theory)
Penelitian ini menggunakan Teori Pembelajaran Sosial (Social Learning
Theory) yang disampaikan oleh Charles Osgood. Teori ini berpijak pada model komunikasi paling sederhana yaitu Stimulus-Respon (S-R) yang berasumsi
bahwa individu akan memberi respon terhadap rangsangan yang ada di
sekitarnya46. Model komunikasi S-R kemudian dikoreksi oleh John W. Riley
dan Mathilda W. Riley dalam tulisannya yang berjudul Mass Communication and the Social System. Menurut mereka, komunikan dalam menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator tidak langsung bereaksi begitu saja. Ada
faktor-faktor di luar dirinya yang turut mempengaruhi dan bahkan
mengendalikan aksi dan reaksinya terhadap suatu pesan yang diterimanya47.
Faktor-faktor yang dimaksud terutama berkaitan dengan pesan dan
kelompok primer (misalnya keluarga) dan kelompok lainnya yang menjadi
rujukan (referensi) dari si komunikan. Nilai-nilai yang berlaku pada kelompok
primer dan kelompok rujukan ini lah yang lazimnya mempengaruhi komunikan
45
Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi:Suatu Pengantar, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003 ), hlm. 151
46
Littlejohn, Op.Cit, hlm. 118 47
dalam menetukan sikap dan tindakan-tindakan. Hal ini terjadi karena umumnya
orang akan selalu berusaha agar sikap dan tindakannya tidak terlalu
menyimpang dari nilai-nilai kelompok lingkungannya48. Berikut adalah ilustrasi
dari model komunikasi Riley.
Gambar I. 1
Model Komunikasi Riley (1959)49
Teori Pembelajaran Sosial membicarakan tentang bagaimana faktor
lingkungan dan kognitif berinteraksi untuk mempengaruhi pemahaman dan
perilaku seseorang. Teori yang dicetuskan oleh Albert Bandura ini terfokus
pada pembelajaran dalam konteks sosial. Seseorang mempelajari suatu konsep
dari sesamanya melalui proses observasi, imitasi dan mengamati model50.
Teori ini menganggap media massa sebagai agen sosialisasi yang
pertama dalam komunikasi di samping keluarga, guru di sekolah dan sahabat
48
Ibid
49
http://extension.missouri.edu , Developing Effective Communications, diakses pada 28 april 2012 pukul 21:18
50
http://www.southalabama.edu/oll/mobile/theory_workbook/social_learning_theory.htm ,
karib51. Menurut teori ini, media massa menjadi objek imitasi dan identifikasi
bagi setiap orang. Imitasi adalah replika atau peniruan secara langsung dari
perilaku yang diamati. Sedangkan identifikasi merupakan perilaku meniru yang
bersifat khusus dimana pengamat tidak meniru secara persis sama apa yang
dilihatnya. Meskipun lebih sulit untuk dilihat dan dipelajari, identifikasi dinilai
memberikan pengaruh terhadap perilaku individu52.
Teori Pembelajaran Sosial mengukur makna dengan menggunakan
semantic differential dimana makna dapat ditunjukkan dengan kata sifat. Terdapat dua kata sifat yang saling berlawanan53. Kata sifat dipasangkan secara
berlawanan seperti baik-buruk, tinggi-rendah, lambat-cepat54.
Dalam proses belajar sosial terdapat empat tahapan yaitu perhatian
(attention process), retensi (retention process), reproduksi motor (motor reproduction motor) dan motivasional (motivational process)55.
Perhatian. Seseorang pertama-tama perlu untuk melihat model yaitu
berupa perilaku atau tindakan orang lain yang ingin ditiru
Retensi. Hasil pengamatan kemudian akan disimpan dalam ingatan untuk
digunakan di kemudian hari saat menghadapi situasi yang sama
51
Onong Uchjana Effendy, Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 282
52
Reproduksi tindakan. Pada tahap praktek, seseorang dituntut untuk bisa
mengaplikasikan pengetahuan yang didapat dalam tindakan nyata.
Motivasi. Perilaku meniru orang lain sangat ditentukan oleh faktor
motivasi yang dimiliki orang yang ingin meniru56.
Menurut teori ini, terbentuknya perilaku adalah perpaduan dari sejumlah
kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam diri khalayak yaitu faktor internal dan
faktor situasional atau faktor eksternal57.
1. Faktor Internal
Kemampuan memahami pesan sangat tergantung pada pengetahuan
atau pengalaman. Proses belajar tidak lepas dari kemampuan berpikir
(kognitif) seseorang. Berpikir berarti menganalisa, mengabstraksi dan
seterusnya atau merangkaikan tanggapan yang satu dengan tanggapan yang
lain. Hal itu disebut dengan field of experience58.
Dr. Astrid Susanto menyebut lapangan pengalaman itu sebagai
pedoman individu yang dibuat atas dasar hal yang pernah dialaminya sendiri.
Segala sesuatu yang pernah dialami menjadi pedoman. Kemudian
pengalaman-pengalaman orang lain yang tidak dialaminya, tetapi menjadi
pedoman dalam lingkungan sosialnya atau masyarakat, dan diambil juga
sebagai pedomannya disebut frame of reference atau kerangka referensi59.
Dalam kerangka referensi ini segala hal-hal baru, ide baru, gagasan
baru atau pengalaman-pengalaman baru akan diletakkan, tiap kali
pengalaman-pengalaman baru itu datang. Seseorang melakukan penyesuaian
(enactive) dengan mengkonfrontasi lapangan pengalaman dan kerangka referensi lama dengan baru. Bila sesuai, pesan itu akan diterima, dan bila
tidak, akan ditolaknya60.
Skinner menemukan bahwa komunikasi akan berlangsung selama
expectation of reward
harapan akan memperoleh keuntungan dari pelaksanaan komunikasi.
Keuntungan atau reward yang diharapkan bisa merupakan pemenuhan
kebutuhan orang dalam bentuk: personal need atau social needs61.
expectation of reward
Motif adalah suatu pengertian mengenai keadaan mobilisasi energi dengan
suatu tujuan62. Motif menerangkan mengapa tingkah laku terarah kepada
suatu tujuan tertentu. Dengan kata lain, motif merupakan dorongan dari
dalam diri yang menggerakkan seseorang untuk melakukan suatu aktivitas
guna mewujudkan tujuan tertentu.
Motif-motif yang dikemukakan para tokoh seperti: W.I Thomas dan
Znaniecki, David McCelland, Abraham Maslow dan Melvin H. Marx tidak
60
Morisan, Op.Cit, hlm. 244 61
Fajar, hlm. 173 62
menunjukkan perbedaan yang tegas. Oleh karena itu Jalaluddin Rakhmat
kemudian merangkum motif-motif tersebut dan dihasilkan enam jenis motif,
yaitu:
Motif Ingin Tahu. Kecenderungan setiap orang untuk mengerti, menata
dan menduga.
Motif Kompetensi. Keinginan membuktikan kemampuan mengatasi
persoalan hidup.
Motif Cinta. Keinginan untuk memperoleh kehangatan persahabatan,
ketulusan kasih sayang dan penerimaan dari orang lain.
Motif harga diri dan kebutuhan untuk mencari identitas. Seseorang
berharap supaya keberadaannya tidak hanya dilihat sebagai bilangan
tetapi juga diperhitungkan.
Kebutuhan akan nilai, kedambaan dan makna kehidupan. Ini erat
kaitannya dengan kebidupan spiritual dimana setiap orang
membutuhkan nilai-nilai sebagai pegangan menghadapi realitas hidup
Kebutuhan akan pemenuhan diri. Setiap orang ingin mempertahankan
dan meningkatkan kualitas kehidupan dengan memenuhi potensi-potensi
yang dimiliki63.
63
2. Faktor eksternal
Seperti telah disinggung di awal, kehadiran media massa dan
orang-orang sekitar penting dalam proses belajar sosial. Jika media berperan dalam
modeling, maka orang-orang disekitar pengaruhnya jauh lebih kuat yaitu
persuatif.
Menurut George Herbert Mead, orang-orang yang berpengaruh dalam
proses belajar sosial atau orang-orang yang sangat penting bagi setiap orang
disebut dengan Siginificant others. Dalam perkembangannya, significant others meliputi semua orang yang mempengaruhi perilaku, pikiran dan
perasaan kita64. Ada pun lebih lanjut menurut Mead, terdapat significant
others yang terhimpun dalam kelompok dan mereka disebut sebagai
kelompok rujukan (reference group)65.
Keberadaan significant others maupun reference group pada
prinsipnya menghasilkan dua efek yaitu efek larangan (inhibitory effect) dan efek suruhan (disinhibitory effect). Efek larangan terjadi ketika significant others menghalangi atau mencegah seseorang untuk melakukan sesuatu. Sedangkan efek suruhan merupakan kebalikan dari efek larangan yang justru
mendorong orang untuk melakukan suatu tindakan atau perilaku66.
64
Ibid, hlm. 103 65
Ibid, hlm. 104 66
2. Persepsi
Persepsi menurut Joseph A. Devito didefinisikan sebagai proses dimana
kita menjadi sadar terhadap sebuah objek, peristiwa, khususnya manusia
melalui indera (Perception is the process by which you became aware of objects, events, and especially people through your sense: sight, smell, taste, touch and hearing)67.
Selanjutnya menurut Berelson dan Steiner dalam Severin dan Tankard,
persepsi didefinisikan sebagai proses yang kompleks dimana orang memilih,
mengorganisasikan dan menginterpretasikan respons terhadap suatu rangsangan
ke dalam situasi masyarakat dunia yang penuh arti dan logis68.
Dalam hal ini persepsi merupakan aktivitas belajar yang aktif dan
berkesinambungan sebagaimana disampaikan oleh Bennett, Hoffman dan
Prakash dalam Severin dan Tankard bahwa persepsi adalah aktivitas aktif yang
melibatkan pembelajaran, pembaharuan cara pandang, dan pengaruh timbal
balik dalam pengamatan69. Severin & Tankard kemudian merumuskan adanya
faktor-faktor psikologis yang berpengaruh terhadap persepsi. Terdapat lima
faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu asumsi (yang didasarkan pada
67
Joseph A. DeVito, The Interpersonal Communications, 9th ed, (New York: Addison Wesley Longman, 1986), hlm. 93
68
Werner J. Severin & James W. Tankard, Jr, Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, dan Terapan di Dalam Media Massa), Alih Bahasa; Sugeng Hariyanto, Cet. ke-4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), hlm. 84
69
pengalaman-pengalaman masa lalu), harapan-harapan budaya, motivasi
(kebutuhan), suasana hati (mood), serta sikap70.
Definisi persepsi pada perjalanannya mulai menyentuh pula aspek
fungsional. Deddy Mulyana yang mendefinisikan persepsi sebagai proses
internal yang memungkinkan kita memilih, mengorganisasikan dan
menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita, dan proses tersebut
mempengaruhi perilaku kita71. Hal ini sesuai dengan pemikiran Robbins dan
Judge yang menyatakan bahwa persepsi penting untuk mempengaruhi perilaku
manusia. Perilaku manusia tergantung dari persepsinya mengenai realitas bukan
realitas itu sendiri.
based on their perception of what reality is, not on reality itself. The world as its perceived is the world that is behaviorally important)72. Pentingnya persepsi dalam pembentukan perilaku kiranya dipertegas oleh pernyataan Toeti Heraty
Noerhadi yang menyatakan bahwa persepsi adalah suatu persiapan ke perilaku
konkret73.
Disini benang merah antara persepsi dan komunikasi mulai terlihat.
Komunikasi disebut efektif jika dapat mengubah perilaku manusia. Ada pun
persepsi disebut-sebut sebagai aktivitas penting yang menentukan perilaku
70
Ibid, hlm. 85 71
Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 167
72
Stephen P Robbins & Timothy A Judge, Organizational Behavior. (New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2009), hlm. 173
73
manusia. Menurut Deddy Mulyana, persepsi adalah inti dari komunikasi,
sedangkan penafsiran (interpretasi) adalah inti dari persepsi yang identik
dengan penyandian balik (decoding) dalam proses komunikasi74.
Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Menurut Bimo
Walgito, terdapat dua faktor yang berpengaruh terhadap persepsi yaitu faktor
internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu apa yang ada dalam diri
individu. Sedangkan faktor eksterrnal terdiri dari faktor stimulus itu sendiri dan
faktor lingkungan dimana persepsi itu berlangsung75.
Ada pun menurut Jalaluddin Rakhmat, terdapat tiga faktor yang
mempengaruhi persepsi yaitu perhatian, faktor fungsional dan faktor
struktural76. Kenneth A. Andersen dalam Rakhmat menyebut perhatian sebagai
proses mental ketika stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran dan stimuli
lainnya melemah77. Menurut David Krech dan Richard S. Crutchfield dalam
Rakhmat, faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu,
pengetahuan dsb yang bersifat personal atau disebut juga sebagai kerangka rujukan (frame of reference). Selanjutnya, faktor struktural memandang persepsi semata-mata dipengaruhi oleh sifat stimuli fisik dan efek-efek saraf
yang ditimbulkannya pada sistem saraf individu78
74
Mulyana, Op.Cit, hlm. 180-181 75
Bimo Walgito, Psikologi sosial, Cetakan ke-4, (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), hlm.46 76
Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, Cetakan ke-17. (Bandung: Remaja Rosdakarya Rakhmat, 2001), hlm. 51
77
Ibid, hlm. 52 78
Selanjutnya, Robbins dan Judge memberi perspektif lain dalam
merumuskan faktor-faktor pembentuk persepsi. Terdapat tiga faktor yaitu faktor
subjek, situasi dan objek. Faktor subjek meliputi: sikap, motif, ketertarikan,
pengalaman masa lalu dan dugaan. Faktor situasi terdiri dari: waktu, latar
belakang pekerjaan dan latar belakang sosial. Sedangkan faktor objek terdiri
dari: kebaruan, gerakan, suara, ukuran, latarbelakang, kedekatan dan
kemiripan79. (Lihat bagan I.1 )
Dari definisi-definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi
merupakan proses penafsiran terhadap informasi inderawi yang bersifat
internal, aktif dan vital bagi setiap orang dalam proses komunikasi.
Terbentuknya persepsi dipengaruhi oleh banyak faktor. Kiranya faktor-faktor
yang sampaikan oleh Robbins dan Judge dapat merangkum kompleksitas
faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi yang disampaikan oleh Bimo
Walgito, Jalaluddin Rakhmat serta Severin dan Tankard.
79
Bagan I. 1
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi menurut Robbins dan Judge80
3. Jurnalis sebagai Pesan
Jurnalis merupakan kata serapan dari kata journal dalam bahasa Inggris dan kata diurnal dalam bahasa Latin yang artinya orang yang melakukan pekerjaan jurnalistik81. Jurnalistik atau jurnalisme sendiri diartikan sebagai
Dengan demikian secara sederhana jurnalis dapat diartikan sebagai seseorang
yang bertugas menghimpun berita, mencari fakta dan melaporkan peristiwa.
Ada tiga sebutan yang berbeda untuk sebuah profesi yang sama, yaitu:
jurnalis, wartawan dan reporter. Ketiga sebutan tersebut sebenarnya mempunyai
makna yang sama yaitu sebuah profesi yang tugasnya mencari, mengumpulkan,
menyeleksi dan menyebarluaskan informasi kepada khalayak melalui media
massa83. Yang membedakan adalah medianya. Di Indonesia, sebutan wartawan
identik dengan mereka yang bekerja di media massa cetak, reporter cenderung
digunakan untuk media massa televisi dan radio, sementara sebutan jurnalis
untuk wartawan asing84.
Wartawan adalah profesi. Disebut sebagai profesi karena ia memiliki
empat ciri yaitu: 1) Mempunyai kebebasan dalam melakukan pekerjaan, 2)
Didasari atas panggilan hati dan keterikatan dengan pekerjaan, 3) Dibutuhkan
keahlian dan 4) Bertanggung jawab dan terikat pada kode etik pekerjaan85. Oleh
karena itu, masyarakat memandang wartawan sebagai professional. Profesional
disini memuat tiga arti: pertama, professional adalah kebalikan dari amatir;
kedua, sifat pekerjaan wartawan menuntut pelatihan khusus; norma-norma yang
mengatur perilakunya dititik beratkan pada kepentingan khalayak pembaca86.
83
Jani Yosef, To Be A Journalist, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 43 84
Ibid, hlm. 44 85
Ibid
86
Ada pun di China ternyata tidak setiap jurnalis bisa merasakan predikat
sebagai tenaga profesional. Berdasarkan wawancara yang dilakukan Lin
oleh golongan menengah ke atas. Mereka adalah redaktur dan pemimpin
umum. Di sisi lain, jurnalis yang jabatannya di bawah mereka merasa bahwa
pekerjaan mereka tak ubahnya pekerjaan lain yang membutuhkan kerja keras
dengan tanpa jaminan kerja yang memadai.
-level managing editors or directors of a department are more likely to proudly label themselves as professionals. The -mockery for most working journalists who are at the bottom of the hierarchy in the organization, usually younger and with less working experience, who have a contract-based employment relationship with the organization. Some of the working journalists do not have medical insurance, and they can be expected to change jobs relatively more frequently. Some of them ev
journalism as a job87.
Secara umum, sebagai turunan dari kegiatan komunikasi, wartawan
adalah elemen yang berfungsi sebagai komunikator di tubuh pers. Wartawan
87
FEN J. LIN (City University of Hong Kong),
Liter International Journal of
atau reporter adalah seseorang yang bertugas mencari, mengumpulkan dan
mengolah informasi menjadi berita, untuk disiarkan melalui media massa88.
Kedudukan jurnalis sebagai komunikator professional dalam
komunikasi massa telah menjadi pesan tersendiri. Seperti disampaikan oleh
Marshal McLuhan bahwa media adalah pesan (The medium is the messege).
Bukan isi media yang mempengaruhi khalayak melainkan media itu sendiri89.
Dapat dipastikan tentunya bahwa media tak sungguh-sungguh berniat
mempengaruhi khalayak agar tertarik menjadi jurnalis tetapi diluar kontrol
media, justru jurnalis dapat menjadi pesan yang berdampak pada orang-orang
yang menerimanya.
4. Budaya Patriarki
Kata patriarki secara harafiah berarti kekuasaan bapak atau
patriarch 90. Melekat dalam sistem ini yaitu ideologi yang menyatakan bahwa laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, bahwa perempuan harus dikontrol
oleh laki-laki dan bahwa perempuan adalah milik laki-laki91. Sebagaimana
disampaikan oleh Duru bahwa hakikat patriarki terletak pada adanya dominasi
laki-laki terhadap perempuan.
subordination (Hunnicutt, 2009). In patriarchal societies, men are in charge
88
Totok Djuroto, Manajemen Penerbitan Pers,Cetakan Ketiga, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm.22
89
Rakhmat. Op.Cit, hlm. 220 90
Kamla Bhasin.Menggugat Patriarki: Pengantar tentang Persoalan Dominasi terhadap Kaum Perempuan. (Yogyakarta: Bentang, 1996), hlm. 1
91
of establishing the social order, and they are situated in dominant position of authority (Lawrence-Webb, Littlefield, & Okundaye, 2004)92.
Selama ini patriarki dianggap alamiah. Alasannya adalah bahwa
laki-laki karena kekuatan badannya yang lebih besar, menjadi pemburu dan pencari
nafkah, dan karena itu juga ksatria, sementara kaum perempuan, karena mereka
melahirkan dan mengasuh dan membesarkan anak, membutuhkan perlindungan
laki-laki. Penjelasan biologis deterministis ini, kata Lerner turun temurun terus
menerus dari zaman batu ke zaman sekarang dan diyakini bahwa kaum laki-laki
lahir superior93.
Patriarki pada prinsipnya berakar dari pemikiran bahwa manusia tercipta
dengan identitas seks yang berbeda yaitu laki-laki dan perempuan. Perbedaan
identitas seks kemudian memunculkan adanya perbedaan identitas gender.
Meskipun saling berkaitan namun pengertian antara seks dan gender
tidak bisa disamakan. Seks bersifat statis. Perempuan dianggap berbeda dari
laki-laki karena secara biologis mereka memiliki organ biologis yang tak dapat
dipertukarkan. Menjadi perempuan atau laki-laki bersifat permanen tidak
92
Annie N. Duru (Howard University, Washington DC, US) Ideological Criticism of a Nigerian Video Film, August Meeting: A Feminist Perspectiv -journalist Vol.10.no2 (2010), hlm.75
93
berubah dan merupakan ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai
ketentuan Tuhan atau kodrat94.
Hal itu berbeda dengan gender yang merupakan suatu sifat yang melekat
pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial
maupun kultural dan dapat dipertukarkan95 dimana kemudian muncul konsep
feminim (kewanitaan) dan maskulin (kelelakian). Menurut Illich, gender
mengisyaratkan polaritas sosial yang sifatnya fundamental dan tak akan serupa
di dua tempat yang berlainan96. Lebih lanjut ia menyebut gender dengan istilah
dengan gender kedaerahan (vernacular)97.
Gender differences (perbedaan gender) sebenarnya bukan suatu masalah
sepanjang tidak menimbulkan gender inequalities (ketidakadilan gender).
Namun yang menjadi masalah ternyata adalah gender differences ini telah menimbulkan berbagai ketidakadilan. Gender Inequalities merupakan sistem dan struktur dimana kaum laki-laki atau perempuan menjadi korban dari sistem
tersebut98.
94
Riant Nugroho, Gender dan Strategi Pengarus-Utamanya di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm 21
95
Ibid, hlm. 18 96
Ivan Illich, Matinya Gender, Cetakan ke-5, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 45 97
Ibid, hlm.43 98
Bayang-bayang ptriarki tak dapat lepas dari munculnya ketimpangan
gender. Hal itu seperti dipikirkan oleh Duru bahwa ideologi patriarki senantiasa
diasosiasikan dengan isu ketidakadilan gender.
inequality.99
Ada pun secara umum terdapat perdebatan mengenai asal-usul patriarki
yang berakar dari dua teori besar yaitu teori Nature dan Teori Nurture100.
Menurut Teori Nature, perbedaan psikologis antara laki-laki dan perempuan
disebabkan oleh faktor-faktor biologis kedua insan. Disini, patriarki dianggap
bersifat alami sebagai kodrat hubungan laki-laki dan perempuan. Hal ini
didukung oleh kaum tradisional101.
Si sisi lain, penganut Teori Nurture beranggapan bahwa perbedaan itu
tercipta melalui proses belajar dari lingkungan percaya patriarki adalah
bentukan manusia. Patriarki diciptakan dan bisa untuk dihapuskan102. Diluar
mana yang benar dari perdebatan itu, faktanya adalah ideologi patriarki bisa
99
Duru, Op.Cit, hlm. 77 100
Dwi Ismi Astuti Nurhaeni, Kebijakan Publik Pro Gender, (Surakarta: UNS Press, 2009), hlm.19 101
Ibid, hlm. 28 102