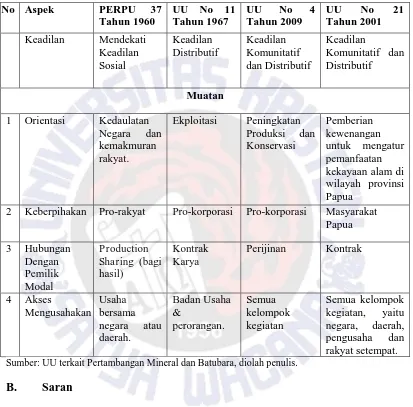167 BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Konsepsi keadilan mengenai penguasaan dan penggunaan kekayaan
alam yang terkandung dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945 adalah keadilan sosial.
Landasan konstitusional konsepsi keadilan sosial dalam
pengelolaan pertambangan adalah Pasal 33 UUD 1945. Secara
historis, pembahasan mengenai Pasal 33 UUD 1945 tidak dapat
dilepaskan dari pemikiran Mohammad Hatta. Menurut Bung Hatta
(dalam kerangka keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia)
terhadap peranan modal bahwa perekonomian Indonesia di masa
datang seharusnya diusahakan dengan jenjang prioritas berikut:
Pertama, mendayagunakan rakyat sebagai pelaku pembangunan
ekonomi dengan jalan koperasi; kedua, yaitu golongan swasta dan
modal nasional; ketiga, bila tenaga dan modal nasional tidak
mencukupi, maka kegiatan produksi dilakukan dengan meminjam
tenaga dan modal asing; keempat, bila bangsa asing tidak bersedia
168 untuk menanam modal di Indonesia dengan syarat-syarat oleh
pemerintah agar kekayaan alam Indonesia tetap terjaga.
Pada Pasal 33 UUD 1945 disebutkan bahwa cabang-cabang
produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup
orang banyak dikuasai oleh negara; bumi dan air dan kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Konsepsi ‘dikuasai negara’ merupakan kata kunci Pasal 33 UUD 1945 dalam
mengintreprestasikan akses mengusahakan pertambangan di
Indonesia. Bung Hatta menginterprestasikan mengenai penguasaan
negara dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, sebagai berikut:
Dikuasai oleh negara dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tidak berarti negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan atau ondernemer. Lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan guna melancarkan jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula “pengisapan” orang yang lemah oleh orang lain yang bermodal.
Selain itu, dalam Pasal 33 UUD 1945 konsepsi “dikuasai oleh Negara” ini, merupakan kreasi dan kecerdikan intelektual dari para
pendiri Negara kita tersebut, karena bila dirumuskan dengan kata “dikuasai oleh Pemerintah”, maka rumusan tersebut akan bermakna
dapat dikuasai baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah
Daerah. Sesuai konsep Hukum Administrasi Negara, bahwa
169 Daerah. Jadi bila dirumuskan dengan kata dikuasai oleh Pemerintah,
maka amanat untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dapat menjadi
hanya sebatas kemakmuran rakyat setempat tempat terdapatnya
bahan galian dimaksud.
Selanjutnya dalam Pasal 33 UUD 1945, dirumuskan oleh
founding father bahwa: ...”dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”. Pemanfaatan bahan galian, tujuannya hanya
satu yaitu: untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat seluruh
Indonesia. Bila yang dimaksudkan tujuannya untuk lebih
menekankan pada rakyat setempat (tempat terdapatnya bahan galian
tersebut ), maka tentunya akan dirumuskan dengan kata ‘kemakmuran masyarakat’ dan bukan ‘kemakmuran rakyat’. Dari hal
tersebut, jelas bahwa founding father Negara Indonesia menghendaki
bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; bumi dan
air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia—bukan hanya
masyarakat setempat.
2. Hanya ketentuan dalam Perpu 37 Tahun 1960 yang mendekati prinsip
keadilan sosial dalam penguasaan dan penggunaan pertambangan
170 Tahun 1967 hanya menekankan kepada keadilan distributif.
Sedangkan UU No 4 Tahun 2009 dan UU No. 21 Tahun 2001 lebih
menekankan kepada keadilan distributif dan komunitatif.
a. Pada tataran konsepsi, pengertian ”dikuasai negara” dalam UU
pertambangan ternyata telah ditafsirkan berbeda-beda dari waktu ke
waktu.
Pertama, pada masa Orde Lama, masa Perpu No. 37 Tahun
1960, pengertian ”dikuasai negara” diartikan sebagai negara memiliki
wewenang untuk menguasai dan mengusahakan langsung semua
sumber daya alam melalui perusahaan-perusahaan milik negara.
Dalam hal ini hubungan dengan pemilik modal lebih merupakan
ProductionSharing (bagi hasil).
Kedua, pada masa Orde Baru, yaitu masa UU No 11 Tahun
1967, pengertian ”dikuasai negara” telah bergeser dari ”pemilikan dan penguasaan secara langsung” menjadi ”penguasaan secara tidak
langsung”. Hal ini terjadi karena pemerintah menyadari sepenuhnya
bahwa mengelola sumber daya alam secara langsung memerlukan
sumber daya manusia yang terampil (skill), modal yang sangat besar
(high capital), teknologi tinggi (high technology), dan berisiko tinggi
(high risk). Hubungan dengan pemilik modal bersifat kontrak karya.
171 dalam sengketa dengan pihak swasta (asing) berkaitan dengan
sumberdaya alam yang dikuasainya. Hal ini tidak lain karena
Pemerintah dapat melakukan perjanjian atau kontrak dengan pihak
swasta dalam ekonomi sumberdaya alam. Keadaan ini menurunkan derajat negara sebagai representasi “Yang Publik.” Degradasi ini
terjadi secara sistematis lewat deregulasi yang dilakukan dengan
mengadopsi hubungan perjanjian atau kontrak antara Pemerintah dengan Swasta dalam “pengalihan” suatu hak atas sumberdaya alam
pertambangan. Hubungan keperdataan antara Pemerintah dengan
Investor ini dapat menggeser urusan publik ke dalam ruang bisnis dan
berorientasi pada keuntungan ekonomi. Pada hal-hal tertentu
pemerintahan yang demikian dapat dikategorikan sebagai
Corporatocracy. Corporatocracy tidak saja dimaknai bahwa
orang-orang di dalam pemerintahan didominasi oleh orang-orang berlatarbelakang
saudagar dengan motif ekonomi yang diraih dari kekuasaan politik,
tetapi juga ditelaah dari konsep hubungan hukum yang dibangun
dengan pihak investor.
Ketiga, pada masa Reformasi, yaitu masa UU No 4 Tahun
2009, pengertian ”dikuasai negara” bergeser ke arah yang lebih
praktis dan terbuka. Pemerintah memberikan peluang
172 dalam pengusahaan sumber daya alam melalui pemberian izin
langsung (license). Dalam hal ini hubungan dengan pemilik modal
bersifat perizinan. Meski dalam UU Minerba telah merubah kontrak
(pada UU UU Nomor 11 Tahun 1967) menjadi izin, tetap harus
diperhatikan bahwa penguasaan negara mempunyai relasi dengan
hak-hak individu masyarakat serta hak masyarakat adat atas
sumberdaya alam. Selama ini dalam praktiknya formalisasi hak oleh
negara malah menjauhkan masyarakat untuk memanfaatkan dan
menikmati sumberdaya alam. Bahkan mengusir masyarakat dari
wilayah yang mereka tempati karena izin sudah diberikan kepada
pihak swasta.
Jika kita cermati dalam peraturan pelaksanaan pertambangan,
yaitu UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua, akses mengusahakan adalah semua kelompok
kegiatan, yaitu negara, daerah, pengusaha dan rakyat setempat, di
mana hubungan dengan pemilik modal dalam adalah melalui
perjanjian kontrak. Wajar saja jika UU No. 21 Tahun 2001 masih
menganut sistem kontrak sama seperti di dalam UU No 11 Tahun
1967, karena UU No. 21 Tahun 2001 ini keluar di saat UU No 4
173 b. Pada tataran konsepsi, pengertian ’dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat’ dalam UU pertambangan ternyata telah
ditafsirkan berbeda-beda dari waktu ke waktu.
Pertama, pada masa Orde Lama, masa Perpu No. 37 Tahun
1960, pengertian ’dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat’ dalam konsideran Perpu No. 37 Tahun 1960 diartikan
menjadi dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik
secara gotong-royong maupun secara perseorangan. Dalam hal inilah
maka keberpihakan Perpu No. 37 Tahun 1960 lebih pro-rakyat.
Kedua, pada masa Orde Baru, yaitu masa UU No 11 Tahun
1967, pengertian ’dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat’ ternyata melenceng jauh, sejak dari konsiderans sudah terlihat
bahwa UU Nomor 11 Tahun 1967 beorientasi kepada eksploitasi.
Eksploitasi tambang yang diusung oleh UU Nomor 11 Tahun 1967
memang sejalan dengan politik pembangunan ekonomi yang
digerakkan oleh rezim yang berkuasa saat itu. Dalam hal inilah maka
keberpihakan UU Nomor 11 Tahun 1967 lebih pro-korporasi.
Ketiga, pada masa Reformasi, yaitu masa UU No 4 Tahun
2009, pengertian ’dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat’, diintreprestasikan menjadi memberikan perhatian terhadap
174 mineral dan batubara (minerba) pada lingkungannya. Dalam hal
inilah maka keberpihakan dalam UU No 4 Tahun 2009 masih sama
seperti UU Nomor 11 Tahun 1967 yaitu pro-korporasi. Namun, jika
kita cermati dalam peraturan pelaksanaan pertambangan, yaitu UU
No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua,
pengertian ’dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat’
pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi
Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri
di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kewenangan yang lebih luas tersebut berarti pula mencakup
kewenangan untuk mengatur pemanfaatan kekayaan alam di wilayah
provinsi Papua, sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua.
Jadi keberpihakan dalam UU No. 21 Tahun 2001 adalah masyarakat
setempat, dalam hal ini yaitu masyarakat Papua. Untuk lebih jelasnya
175 Tabel 2.
Pemaknaan Keadilan Dalam UU Terkait Pertambangan Mineral dan Batubara
No Aspek PERPU 37
Tahun 1960
UU No 11 Tahun 1967
UU No 4
Tahun 2009
UU No 21
Tahun 2001
Keadilan Mendekati
Keadilan Sosial Keadilan Distributif Keadilan Komunitatif dan Distributif Keadilan
Komunitatif dan Distributif
Muatan
1 Orientasi Kedaulatan
Negara dan
kemakmuran rakyat.
Ekploitasi Peningkatan
Produksi dan Konservasi
Pemberian kewenangan untuk mengatur pemanfaatan kekayaan alam di wilayah provinsi Papua
2 Keberpihakan Pro-rakyat Pro-korporasi Pro-korporasi Masyarakat
Papua
3 Hubungan
Dengan Pemilik Modal
Production Sharing (bagi hasil)
Kontrak Karya
Perijinan Kontrak
4 Akses
Mengusahakan
Usaha bersama negara atau daerah. Badan Usaha & perorangan. Semua kelompok kegiatan
Semua kelompok kegiatan, yaitu negara, daerah,
pengusaha dan
rakyat setempat. Sumber: UU terkait Pertambangan Mineral dan Batubara, diolah penulis.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis paparkan, maka penulis
menyarankan dua hal berkenaan dengan keadilan dalam pengaturan
176 1. Masalah keadilan tidak hanya kompleks dalam tatanan operasional di
masyarakat tetapi juga dalam tatanan konsep. Secara praktis
permasalahan keadilan makin kompleks karena sangat mungkin
konsep keadilan dalam tatanan nilai-nilai masyarakat menjadi
berbeda dalam penilaian tiap-tiap rezim. Pada sisi lain implementasi
konsep-konsep keadilan sering tidak didasarkan pada keadilan sosial
dalam UUD 1945 sehingga justru sering menimbulkan konflik sosial.
Untuk itu diharapkan pada masa mendatang berbagai kebijakan
didasarkan pada pengaturan pengelolaan pertambangan yang sesuai
dengan keadilan sosial dalam UUD 1945.
2. Prinsip keadilan sosial menjadi salah satu cita hukum yang dalam hal
ini secara eksplisit termuat dalam UUD 1945. Prinsip tersebut
hendaknya menjadi pedoman di dalam melakukan penafsiran dan
menjadi penguji kebenaran hukum positif serta menjadi arah hukum
untuk dikristalisasikan dalam bentuk norma yang imperatif guna
memperoleh keadilan sosial dalam pengaturan pengelolaan
pertambangan di Indonesia. Terkait dengan hal itu, maka penulis
menyarankan supaya pengaturan pengelolaan pertambangan
mengandung norma-norma sebagai berikut:
a. Bercirikan keadilan sosial
177 c. Keberpihakan: Pro rakyat.
d. Hubungan dengan pemilik modal lebih ke ProductionSharing
(bagi hasil).