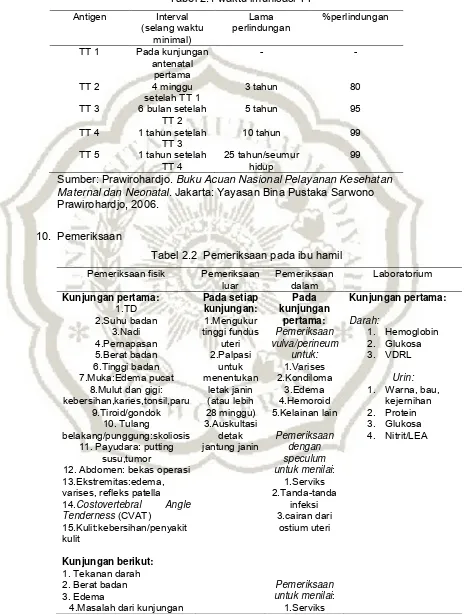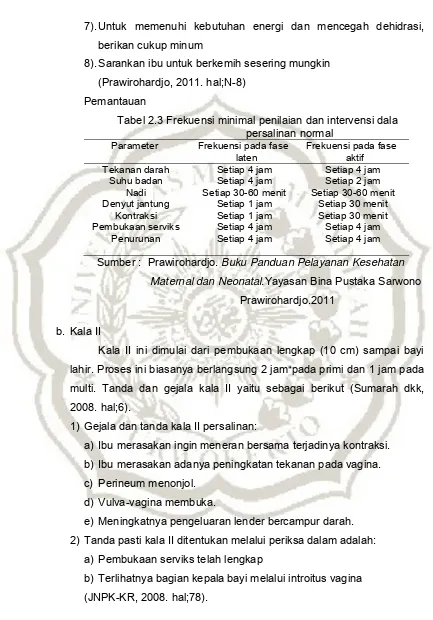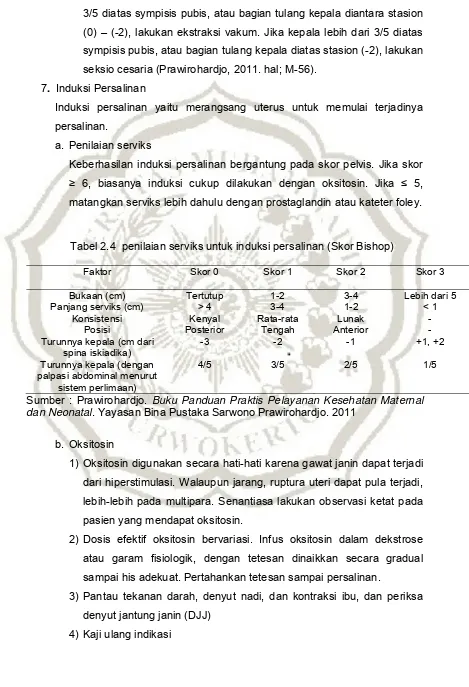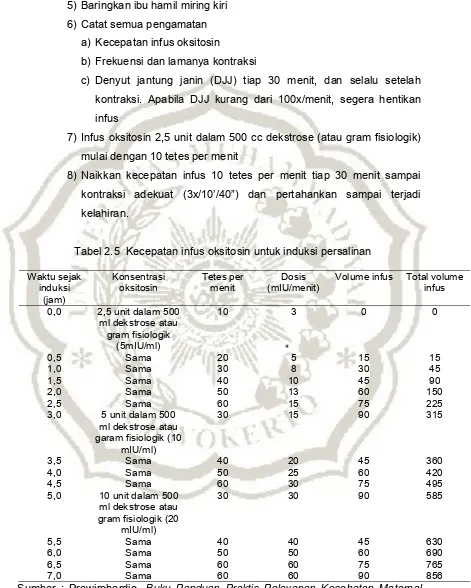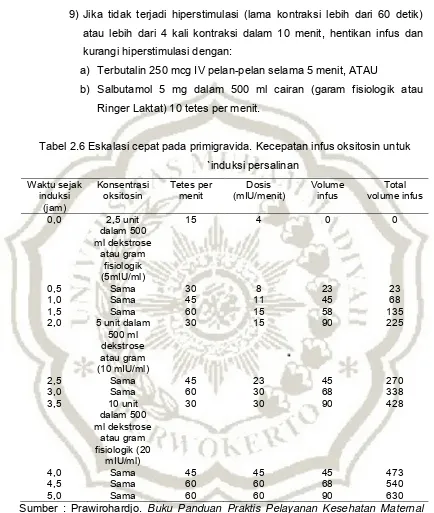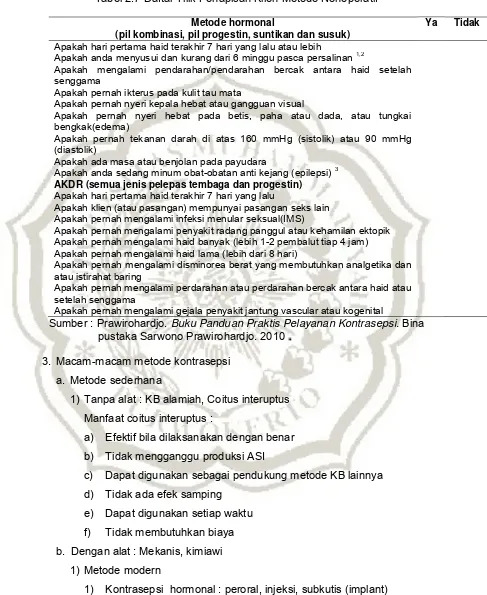BAB II TINJAUAN TEORI
A. Kehamilan 1. Pengertian
Kehamilan merupakan rangkaian bagian rantai yang saling
berhubungan dari spermatozoa, ovum, pembuahan ovum (konsepsi), dan
nidasi (implantasi) pada uterus, dan proses pembentukan struktur dan jenis
plasenta sampai masa aterm (Prawirohardjo, 2010. hal;139).
Kehamilan adalah periode yang dihitung dari hari pertama haid terakhir
(HPHT) hingga dimulainya persalinan sejati, ini yang menandai awal
periode antepartum. Peroide antepartum dibagi menjadi tiga trimester yang
masing-masing terdiri dari 13 minggu atau tiga bulan menurut hitungan
kalender. Pembagian waktu ini diambil dari ketentuan yang
mempertimbangkan bahwa lama kehamilan diperkirakan kurang lebih 280
hari, 40 minggu, 10 bulan, atau 9 bulan sejak hari pertama haid terakhir
(Varney, 2006. hal;492).
Jadi, kehamilan merupakan periode bertemunya spermatozoa, ovum,
pembuahan ovum dan nidasi di tuba falopi sampai perkiraan lahir atau
aterm.
a. Etiologi
Peristiwa kehamilan ini tidak lepas dari kejadian yang meliputi :
pembuahan gamet (sperma dan ovum), fertilisasi (pembuahan), nidasi,
dan pembentukan plasentasi.
1) Pembuahan gamet
a) Sperma
Sperma dibentuk ditubulus seminiferus dengan jumlah 100
juta/ml setiap ejakulasi. Pematangan sperma berlangsung di
epidimis bagian kepala, badan dan ekor. Sperma yang sudah
b) Ovum
Ovulasi atau pelepasan sel telur merupakan bagian dari siklus
menstruasi normal, yang terjadi sekitar 14 hari sebelum
menstruasi yang akan datang, ovum keluar dari robekan folikel de
Graaf menuju tuba.
2) Fertilisasi ( pembuahan)
Fertilisasi adalah penyatuan ovum (oosit sekunder) dan spermatozoa
yang biasanya berlangsung di ampula tuba.
3) Nidasi
Nidasi (implantasi) merupakan penanaman sel telur yang sudah
dibuahi ke dalam dinding uterus pada awal kehamilan.
4) Plasentasi
Plasentasi adalah proses pembentukan struktur dan jenis plasenta.
Setelah nidasi embrio ke dalam endometrium, plasentasi dimulai.
Pada manusia plasentasi berlangsung sampai 12-18 minggu setelah
fertilisasi (Prawirohardjo, 2009. hal;139).
b. Diagnosa kehamilan
1). Tanda tidak pasti
Tanda tidak pasti adalah perubahan-perubahan fisiologis yang dapat
dikenali dari pengakuan atau yang dirasakan oleh wanita hamil.
a). Amenorea (tidak dapat haid)
konsepsi dan nidasi menyebabkan tidak terjadi pembentukan
folikel de Graaf dan ovulasi sehingga menstruasi tidak terjadi.
Lamanya amerorea dapar dikonfirmasi dengan memastikan hari
pertama haid terakhir (HPHT), dan digunakan untuk
memperkirakan usia kehamilan dan taksiran persalinan.
b). Mual dan muntah
Pengaruh hormon estrogen dan progesteron terjadi pengeluaran
asam lambung yang berlebihan dan menimbulkan mual muntah
yang terjadi terutama pada pagi hari yang disebut morning
sickness.
c). Ngidam
Ngidam sering terjadi pada bulan-bulan pertama kehamilan dan
d). Kelelahan
Sering terjadi pada trimester pertama, akibat dari penurunan
kecepatan basal metabolisme pada masa kehamilan.
e). Payudara tegang
Hormon esterogen meningkatkan perkembangan sistem duktus
pada payudara, sedangkan hormon progesterone menstimulasi
perkembangan sistem alveolar payudara.
f). Sering kencing
Desakan rahim kedepan menyebabkan kandung kemih cepat
terasa penuh sehingga sering kencing.
g). Konstipasi atau obstipasi
Pengaruh hormon progesteron dapat menghambat peristaltik
usus sehingga kesulitan untuk BAB.
h). Pigmentasi kulit
Pigmentasi terjadi pada usia kehamilan lebih dari 12 minggu.
Terjadi akibat pengaruh hormon kortikosteroid plasenta yang
merangsang melanofor dan kulit.
i). Varices
Pengaruh hormon esterogen dan progesteron menyebabkan
pelebaran pembuluh darah terutama bagi wanita yang
mempunyai bakat.
2. Tanda-tanda kehamilan
Tanda kemungkinan merupakan:
a. Perut membesar
b. Uterus membesar
c. Tanda Hegar
d. Tanda Chadwick
e. Tanda piscaseck
f. Kontraksi-kontraksi kecil uterus bila dirangsang (Braxton hicks)
g. Teraba Ballotement
h. Reaksi kehamilan positif
Tanda pasti (tanda positif):
a. Gerakan janin yang dapat dilihat atau dirasa atau diraba, juga
b. Denyut jantung janin
1) Didengar dengan stetoskop
2) Dicatat dan didengar dengan alat Doppler
3) Dilihat pada ultrasonografi
( Hani, 2011. hal;72).
3. Tanda-tanda bahaya kehamilan
Pada setiap kunjungan antenatal bidan harus mengajarkan pada ibu
bagaimana mengenal tanda-tanda bahaya, dan menganjurkan untuk
datang ke klinik dengan segera jika ia mengalami tanda-tanda bahaya
tersebut dari beberapa pengalaman akan lebih baik memberikan
pendidikan pada ibu dan anggota keluarganya, khususnya pembuatan
keputusan utama, sehingga si ibu akan didampingi untuk mendapatkan
asuhan.
Enam tanda-tanda bahaya selama periode antenatal adalah :
a. Pendarahan Vagina
Perdarahan vagina adalah normal, pada masa awal kehamilan
mungkin ibu akan mengalami perdarahan yang sedikit disekitar waktu
pertama haidnya terlambat. Pendarahan ini adalah pendarahan
implantasi dan pendarahan normal. Pada waktu yang lain dalam
kehamilan, pendarahan kecil mungkin pertanda dari variable cerviks.
Pendarahan semacam ini mungkin normal atau mungkin pertanda
adanya suatu infeksi. Pada awal kehamilan, perdarahan yang tidak
normal adalah merah, perdarahan banyak, atau perdaraha dengan nyeri
(abortus, kehamilan ektopik, molahetidosa).
b. Sakit kepala yang hebat
Sakit kepala selama kehamilan adalah umum, dan sering kali
ketidaknyamanan yang normal dalam kehamilan. Sakit kepala yang
menunjukan suatu masalah yang serius adalah sakit kepala hebat, yang
menetap dan tidak hilang dengan beristirahat. Kadang-kadang dengan
sakit kepala yang hebat tersebut, ibu mungkin menemukan bahwa
penglihatanya menjadi kabur atau berbayang. Sakit kepala yang hebat
c. Perubahan visual secara tiba-tiba (pandangan kabur, rabun senja)
Karena pengaruh hormonal dalam kehamilan, ketajaman visual ibu
dapat berubah. Perubahan yang kecil adalah normal. Masalah visual
yang mengindikasikan keadaan yang mengancam jiwa adalah
perubahan visual mendadak, misalnya pandanagan kabur atau
berbayang.
d. Nyeri abdomen yang hebat
Nyeri abdomen yang tidak berhubungan dengan persalinan normal
adalah tidak normal. Nyeri abdomen yang mungkin menunjukan
masalah yang mengancam keselamatan jiwa adalah nyeri yang hebat,
menetap, dan tidak hilang setelah beristirahat. Hal ini bisa terjadi
appendicitis, kehamilan ektopik, aborsi, penyakit radang panggul,
persalinan preterm, gastritis, penyakit kantong empedu, abrupsi
plasenta, infeksi saluran kemih, atau infeksi lain.
e. Bengkak pada muka atau tangan
Hampir seluruh dari ibu-ibu akan mengalami bengkak yang normal
pada kaki yang biasa muncul pada sore hari dan biasanya hilang
setelah beristirahat atau meletakanya lebih tinggi. Bengkak bisa
menunjukan adanya masalah serius jika muncul pada muka dan tangan,
tidak hilang setelah beristirahat, dan diseratai dengan keluhan fisik yang
lain. Hal ini dapat merupakan pertanda, anemia, gagal jantung atau
preeklamsi.
f. Bayi kurang bergerak seperti biasa
Ibu mulai merasa gerakan bayinya pada bulan ke 5 atau ke 6,
beberapa ibu dapat merasakan bayinya lebih awal. Jika bayi tidur
gerakanya akan melemah. Bayi harus bergerak sedikitnya tiga kali
dalam periode 3 jam. Gerakan bayi akan lebih mudah terasa jika ibu
berbaring atau beristirahat dan jika makan dan minum dengan baik.
Tanda bahya masa kehamilan muda, masa kehamilan berlanjut dan
penatalaksanaanya meliputi:
1) Perdarahan pervaginam masa kehamilan muda
Perdarahan pervaginam masa kehamilan muda bisa disebabkan oleh
a) Abortus
(1) Abortus imminens
Terjadi perdarahan bercak yang menunjukkan ancaman
terhadap kelangsungan suatu kehamilan. Dalam kehamilan
seperti ini, kehamilan masih mungkin berlanjut atau
dipertahankan.
Penanganan spesifik:
Tidak diperlukan pengobatan medik yang khusus atau tirah
baring secara total. Anjurkan ibu untuk tidak melakukan
aktifitas fisik secara berlebihan atau melakukan hubungan
seksual. Bila perdarahan, berhenti lakukan asuhan antenatal
terjadual dan penilaian ulang bila terjadi perdarahan lagi, atau
terus berlangsung nilai kondisi janin (uji kehamilan/USG)
lakukan konfirmasi kemungkinan adanya penyebab lain (hamil
ektopik atau mola).
(2) Abortus insipiens
Perdarahan ringan hingga sedang pada kehamilan muda
dimana hasil konsepsi masih berada dalam kavum uteri.
Kondisi ini menunjukkan proses abortus sedang berlangsung
dan akan berlanjut menjadi abortus inkomplit atau komplit.
Penanganan spesifik:
Lakukan prosedur evakuasi hasil konsepsi, bila usia gestasi ≤
16 minggu evakuasi dilakukan dengan peralatan Aspirasi
Vakum Manual (AVM) setelah bagian-bagian janin dikeluarkan
atau bila usia gestasi ≥ 16 minggu evakuasi dilakukan dengan
prosedur Dilatasi dan Kuretase.
Bila prosedur evakuasi tidak tidak dapat segera dilaksanakan
atau usia gestasi lebih besar dari 16 minggu, lakukan tindakan
pendahuluan dengan: infus oksitosin 20 unit dalam 500 ml NS
atau RL mulai dengan 8 tpm yang dapat dinaikkan hingga 40
tpm sesuai dengan kondisi kontraksi uterus hingga terjadi
pengeluaran hingga konsepsi. Ergometrin 0,2 mg IM yang
apabila masih diperlukan, dapat diulangi dengan dosis yang
sama setelah 4 jam dari dosis awal.
Hasil konsepsi yang tersisa dalam kavum uteri dapat
dikeluarkan dengan Aspirasi Vakum Manual atau Dilatasi dan
Kuretase.
(3) Abortus inkomplit
Perdarahan pada kehamilan muda dimana sebagian dari hasil
konsepsi telah keluar dari vakum uteri melalui kanalis
servikalis.
Penanganan spesifik:
Tentukan besar uterus (taksir usia gestasi). Kenali dan atasi
setiap komplikasi (perdarahan hebat, syok, infeksi/sepsis).
Hasil konsepsi yang terperangkap pada serviks yang disertai
perdarahan hingga ukuran sedang, dapat dikeluarkan secara
digital atau cunam ovum. Setelah itu evaluasi perdarahan: Bila
perdarahan berhenti, beri ergometrin 0,2 mg IM atau
misoprostol 400 mg per oral. Atau bila perdarahan terus
berlangsung, evakuasi sisa hasil konsepsi dengan AVM atau
D&K (pilih tergantung dari usia gestasi, pembukaan serviks
dan keberadaan bagian-bagian janin).
Bila tidak ada tanda-tanda infeksi, beri antibiotika profilaksis
(ampisilin 500 mg oral atau doksisiklin 100 mg). Bila terjadi
infeksi, beri ampisilin 1 gram dan metronidazol 500 mg setiap
8 jam.
Bila terjadi perdarahan hebat dan usia gestasi dibawah 16
minggu, segera lakukan evakuasi dengan AVM. Bila pasien
tampak anemik, berikan sulvas ferosus 600 mg per hari
selama 2 minggu (anemia sedang) atau transfusi darah
(anemia berat).
(4) Abortus komplit
Perdarahan pada kehamilan muda dimana seluruh hasil
Penanganan spesifik:
Apabila kondisi pasien baik, cukup diberi tablet Ergometrin
3x1 tablet/hari untuk 3 hari.
Apabila pasien mengalami anemia sedang, berikan tablet
Sulfas Ferosus 600 mg/hari selama 2 minggu disertai dengan
anjuran mengkonsumsi makanan bergizi (susu, sayuran
segar, ikan, daging, telur), untuk anemia berat, berikan
transfusi darah.
Apabila tidak terdapat tanda-tanda infeksi tidak perlu diberi
antibiotika, atau apabila khawatir akan infeksi dapat diberi
antibiotika profilaksis.
b). Kehamilan ektopik terganggu
Kehamilan ektopik merupakan kehamilan dimana setelah
fertilisasi, implantasi terjadi diluar endometrium kavum uteri.
Kehamilan ektopik dapat mengalami abortus atau ruptura apabila
massa kehamilan berkembang melebihi kapasitas ruang
implantasi (misalnya: tuba) dan peristiwa ini disebut sebagai
kehamilan ektopik terganggu.
Penilaian Klinik:
1). Kehamilan ektopik yang belum terganggu
Pada keadaan ini, juga ditemui gejala-gejala kehamilan
muda atau abortus imminens (terlambat haid, mual dan
muntah, pembesaran payudara, hiperpigmentasi areola dan
garis tengah perut, peningkatan rasa ingin berkemih, portio
livide, pelunakan serviks, perdarahan bercak berulang).
Tanda-tanda umum dari hasil pemeriksaan bimanual
pada tahapan ini adalah: Adanya massa lunak di adneksa
(hati-hati saat melakukan pemeriksaaan karena dapat terjadi
ruptur atau salah duga dengan ovarium atau kista kecil) dan
adanya nyeri goyang portio.
2). Kehamilan ektopik yang terganggu
Pada tahapan ini, selain gejala kehamilan muda dan
abortus imminens, pada umumnya juga ditemui kondisi gawat
menurun dan lemah, syok (hipovolemik) sehingga isi dan
tekanan denyut nadi berkurang serta meningkatnya frekuensi
nadi (diatas 112x/menit), perut kembung (adanya cairan
bebas intra abdomen) dan nyeri tekan, nyeri perut bawah
yang makin hebat apabila tubuh digerakkan, dan nyeri goyang
portio.
Penanganan:
a) Setelah diagnosis ditegakkan, segera lakukan persiapan
untuk tindakan operatif gawat darurat.
b) Ketersediaan darah pengganti bukan menjadi syarat
untuk melakukan tindakan operatif karena sumber
perdarahan harus segera dihentikan.
c) Upaya stabilisasi dilakukan dengan segera mengestorasi
cairan tubuh dengan larutan kristaloid NS atau RL (500
mL dalam 15 menit pertama) atau 2 L dalam 2 jam
pertama (termasuk selama tindakan berlangsung).
d) Bila darah pengganti belum tersedia, berikan
autotransfusion berikut ini:
Pastikan darah yang dihisap dari rongga abdomen telah
melalui alat pengisap dan wadah penampung yang steril.
Saring darah yang tertampung dengan kain steril dan
masukkan kedalam kantung darah. Apabila kantung
darah tidak tersedia, masukkan dalam botol bekas cairan
infus dengan diberikan larutan sodium sitrat 10 ml untuk
setiap 90 ml darah.
Transfusikan darah melalui selang transfusi yang
mempunyai saringan pada bagian tabung tetesan.
e) Tindakan pada tuba dapat berupa:
Parsial salpingektomi yaitu melakukan eksisi bagian tuba
yang mengandung hasil konsepsi.
Salpingostomi (hanya dilakukan sebagai upaya
konservasi dimana tuba tersebut merupakan salah satu
yang masih ada) yaitu mengeluarkan hasil konsepsi pada
bagian tersebut. Risiko tindakan ini adalah kontrol
perdarahan yang kurang sempurna atau frekuensi (hamil
ektopik ulangan).
(f) Mengingat kehamilan ektopik berkaitan dengan gangguan
fungsi transportasi tuba yang disebabkan oleh proses
infeksi maka sebaiknya pasien diberi antibiotika
kombinasi atau tunggal dengan spektrum yang luas.
(g) Untuk kendali nyeri pascatindakan dapat diberikan:
Ketoprofen 100 mg supositoria, Tramadol 200 mg IV, dan
Pethidin 50 mg IV.
(h) Atasi anemia dengan tablet besi 600 mg per hari.
(i) Konseling pascatindakan:
Kelanjutan fungsi reproduksi, resiko hamil ektopik
ulangan, kontrasepsi yang sesuai, asuhan mandiri selama
dirumah, dan jadual kunjungan ulang.
c) Mola hidatidosa
Hamil mola merupakan suatu kehamilan dimana setelah
fertilisasi hasil konsepsi tidak berkembang menjadi emberio
tetapi tidak terjadi proliferasi dari vili koriales disertai dengan
degenerasi hidropik. Uterus melunak dari berkembang lebih
cepat dari usia gestasi yang normal, tidak dijumpai adanya
janin, kavum uteri hanya terisi oleh jaringan seperti rangkaian
buah anggur.
Penanganan umum:
(1) Diagnosis dini akan menguntungkan prognosis
(2) Pemeriksaan ultrasonografi sangat membantu diagnosis.
Pada fasilitas kesehatan dimana sumber daya sangat
terbatas dapat dilakukan: Evaluasi klinik dengan fokus
pada (riwayat haid terakhir dan kehamilan, perdarahan
tidak teratur atau spotting, pembesaran abnormal uterus,
pelunakan serviks dan korpus uteri), kajian uji kehamilan
dengan pengenceran urine, dan pastikan tidak ada janin
(ballotement) atau denyut jantung janin sebelum upaya
(3) Lakukan pengosongan jaringan mola dengan segera.
(4) Antisipasi komplikasi (krisis tiroid, perdarahan hebat atau
perforasi uterus).
(5) Lakukan pengamatan lanjut hingga minimal 1 tahun
pasca evakuasi
(Prawirohardjo, 2006. hal;147-171).
2) Perdarahan kehamilan lanjut
Perdarahan antepartun pada umumnya disebabkan oleh kelainan
implantasi plasenta (letak rendah dan previa), kelainan inersia tali
pusat atau pembuluh darah pada selaput amnion (vasa previa) dan
separasi plasenta sebelum bayi lahir.
a) Plasenta previa
Plasenta previa merupakan plasenta yang berimplantasi pada
segmen bawah rahim dan menutupi sebagian atau seluruh
ostium uteri internum. Gejala perdarahan awal plasenta previa,
pada umumnya hanya berupa perdarahan bercak atau ringan
(Prawirohardjo, 2006. hal;162).
Terapi spesifik:
(1) Terapi ekspektatif
(a) Tujuan terapi ekspektatif ialah supaya janin tidak terlahir
prematur, penderita dirawat tanpa melakukan
pemeriksaan dalam melalui kanalis servisis. Upaya
diagnosis dilakukan secara non-invasif. Pemantauan
klinis dilaksanakan secara ketat dan baik.
Syarat-syarat terapi ekspektatif: kehamilan preterm
dengan perdarahan sedikit yang kemudian berhenti,
belum ada tanda-tanda in partu, keadaan umum ibu
cukup baik (kadar hemoglobin dalam batas normal),
janin masih hidup.
(b) Rawat inap, tirah baring dan berikan antibiotik
profilaksis.
(c) Lakukan pemeriksaan USG untuk mengetahui
implantasi plasenta, usia kehamilan, profil biofisik, letak
(d) Berikan tokolitik bila ada kontraksi:
MgSO4 4g IV dosis awal dilanjutkan 4g setiap 6 jam,
Nifedipin 3x20 mg/hari, Betamethason 24 mg IV dosis
tunggal untuk pematangan paru janin
(e) Uji pematangan paru janin dengan Tes Kocok dari hasil
amniosentesis.
(f) Bila setelah usia kehamilan diatas 34 minggu, plasenta
masih berada disekitar ostium uteri internum, maka
dugaan plasenta previa menjadi jelas, sehingga perlu
dilakukan observasi dan konseling untuk menghadapi
kemungkinan keadaan gawat darurat.
(g) Bila perdarahan berhenti dan waktu untuk mencapai 37
minggu masih lama, pasien dapat dipulangkan untuk
rawat jalan dengan pesan untuk segera kembali
kerumah sakit apabila terjadi perdarahan ulang.
Cara persalinan dengan diagnosa plasenta previa
seperti: Seksio cesaria maupun melahirkan secara
pervaginam.
b) Solusio plasenta
Solusio plasenta merupakan terlepasnya plasenta dari tempat
implantasinya yang normal pada uterus, sebelum janin
dilahirkan. Definisi ini berlaku pada kehamilan dengan masa
gestasi diatas 22 minggu (Prawirohardjo, 2006. hal;166).
Tindakan obstetrik
Persalinan diharapkan dapat terjadi dalam 3 jam, umumnya
dapat pervaginam.
(1) Seksio cesaria, dilakukan apabila:
(a) Janin hidup dan pembukaan belum lengkap
(b) Janin hidup, gawat janin tetapi persalinan pervaginam
tidak dapat dilaksanakan dengan segera
(c) Janin mati tetapi kondisi serviks tidak memungkinkan
persalinan pervaginam dapat berlangsung dalam waktu
(2) Partus pervaginam
(a) Partus pervaginam dilakukan apabila: janin hidup, gawat
janin, pembukaan lengkap dan bagian terendah didasar
panggul. Janin telah meninggal dan pembukaan serviks
> 2cm
(b) Pada kasus pertama, amniotomi (bila ketuban belum
pecah) kemudian percepat kala II dengan ekstrasi
forseps (vakum)
(c) Untuk kasus kedua, lakukan amniotomi (bila ketuban
belum pecah) kemudian akselerasi dengan 5 unit
oksitosin dalam dekstrose 5% atau RL, tetesan diatur
sesuai dengan kondisi kontraksi uterus
(d) Setelah persalinan, gangguan pembekuandarah akan
membaik dalam waktu 24 jam, kecuali bila jumlah
trombosit sangat rendah (perbaikan baru terjadi dalam
2-4 hari kemudian).
c) Ruptura uteri
Ruptura uteri adalah robekan atau diskontinuitas dinding rahim
akibat dilampauinya daya regang miometrium. Penyebab ruptura
uteri adalah disproporsi janin dan panggul, partus macet atau
traumatik (Prawirohardjo, 2006. hal;169).
Penanganan :
(1) Fasilitas polindes
Infus dan antibiotik, rujuk terencana
(2) Puskesmas
Stabilisasi penderita, tentukan derajat solusio, tentukan
kondisi janin, amniotomi dan akselerasi persalinan, dan
rujuk.
(3) Rumah sakit
Terapi aktif bila janin hidup (seksio cesaria)
Terapi konservatif bila janin meninggal (amniotomi, infus
3). Hipertensi dalam kehamilan, preeklampsia, dan eklampsia.
Hipertensi adalah tekanan darah sekurang-kurangnya 14 mmHg
sistolik atau 90 mmHg diastolik pada dua kali pemeriksaan berjarak
4-6 jam pada wanita yang sebelumnya normotensi.
Bila ditemukan tekanan darah tinggi (≥140/90 mmHg) pada ibu
hamil, lakukan pemeriksaan kadar protein urine dengan tes celup
urine atau protein urine 24 jam dan tentukan diagnosis.
a) Hipertensi kronik
Hipertensi tanpa proteinuria yang timbul dari sebelum kehamilan
dan menetap setelah persalinan
Diagnosis:
(1) Tekanan darah ≥ 140/90 mmHg
(2) Sudah ada riwayat hipertensisebelum hamil, atau diketahui
adanya hipertensi pada usia kehamilan < 20 minggu
(3) Tidak ada proteinuria
(4) Dapat disertai keterlibatan organ lain, seperti mata, jantung
dan ginjal.
b) Hipertensi gestasional
Hipertensi tanpa proteinuria yang timbul setelah kehamilan 20
minggu dan menghilang setelah persalinan.
Diagnosis:
(1) Tekanan darah ≥140/90 mmHg
(2) Tidak riwayat hipertensi sebelum hamil, tekanan darah normal
diusia kehamilan < 12 minggu
(3) Tidak ada proteinuria
(4) Dapat disertai tanda dan gejala preeklampsia, seperti nyeri ulu
hati dan trombositopenia
(5) Diagnosis pasti ditegakkan pascapersalinanan.
c) Preeklampsia dan Eklampsia
Diagnosis:
(1). Preeklampsia ringan
(a) Tekanan darah ≥140/mmHg pada usia kehamilan >20
(b) Tes celup urine menunjukan proteinuria 1+ atau
pemeriksaan protein kuantitatif menunjukkan hasil >300
mg/24 jam.
(2). Preeklampsia berat
(a) Tekanan darah >160/110 mmHg pada usia kehamilan
>20 minggu
(b) Tes celup urin menunjukkan proteinuria ≥2+ atau
pemeriksaan protein kuantitatif menunjukkan hasil >5
g/24 jam
(c) Atau disertai keterlibatan organ lain:
Trombositopenia (<100.000 sel/uL), hemolisis
mikroangiopati, Peningkatan SGOT/SGPT, nyeri
abdomen kuadran kanan atas, sakit kepala, skotoma
penglihatan, pertumbuhan janin terhambat,
oligohidramnion.
(d) Superimposed preeklampsia pada hipertensi kronik:
Ibu dengan riwayat hipertensi kronik (sudah ada
sebelum usia kehamilan 20 minggu). Tes celup urin
menunjukkan proteinuria >+1 atau trombosit <100.000
sel/uL pada usi kehamilan >20 minggu.
d). Eklampsia
(1) Kejang umum/dan koma
(2) Ada tanda dan gejala preeklampsia
(3) Tidak ada kemungkinan penyebab lain (misal epilepsi,
perdarahan subarakhnoid, dan meningitis).
4. Ketidaknyamanan yang lazim terjadi dalam kehamilan:
a. Pada kehamilan trimester pertama
Dengan adanya peningkatan hormon esterogen dan progesteron
dalam tubuh, maka akan muncul berbagai macam ketidaknyamanan
secara fisiologis pada ibu hamil seperti:
1) Mual dan muntah
Dasar anatomis dan fisiologis:
Penyebab yang pasti tidak diketahui, mungkin disebabkan oleh:
b) Relaksasi dan otot-otot halus
c) Metabolik: perubahan dalam metabolisme karbohidrat
berlebihan
d) Mekanisme kongesti, inflamas, distensi pergeseran, keracunan
histamin.
Cara meringankan atau mencegah:
a) Hindari bau atau faktor penyebab
b) Makan biskuit atau roti bakar sebelum bangun dari tempattidur
dipagi hari
c) Makan sedikit tapi sering
d) Duduk tegak setiap kali selesai makan
e) Hindari makanan yang berminyak dan bumbu merangsang
f) Makan makanan kering dan minum diantara waktu makan
g) Minum-minuman yang berkarbonat
h) Bangun tidur secara perlahan dan hindari melakukan gerakan
secara tiba-tiba
i) Menghindari gosok gigi segera setelah makan
j) Minum teh herbal
k) Istirahat sesuai kebutuhan dengan mengangkat kaki dan kepala
agak ditinggikan
l) Hirup udara segar, jalan-jalan, tidur dengan jendela terbuka,
pastikan cukup udara didalam rumah
2). Diare
Diare dapat dikurangi atau dicegah dengan cairan pengganti,
hindari makan makanan berserat tinggi, makan sedikit tapi sering.
3). Nocturia
Nocturia dapat dicegah dengan penjelasan tentang
sebab-sebabnya, kosongkan saat dorongan untuk BAK, perbanyak minum
pada siang hari, jangan kurangi minum malam hari kecuali sangat
mengganggu.
4). Garis-garis diperut
Garis-garis diperut dapat dicegah dengan menggunakan
emollien atau indikasi, gunakan pakaian yang menompang
5). Gatal-gatal
Gatal-gatal dapat dicegah dengan gunakan kompres, mandi
siram air jeruk.
6). Mengidam
Mengidam dapat dicegah dengan mendidik tentang bahaya
makan-makanan yang tidak baik, bahaslah rencana makanan yang
baik.
7). Kelelahan
Dapat dicegah dengan hindari makana yang mengandung
gas, mengunyah makanan secara sempurna, senam harian secara
teratur, pertahankan saat kebiasaan saat buang air.
8). Keputihan
Dapat dicegah dengan cara tingkatkan kebersihan, pakaian
dalam terbuat dari katun.
9). Keringat bertambah
Dapat dikurangi atau dicegah dengan menggunakan pakaian
yang tipis dan longgar, banyak minum, mandi secara teratur.
10). Sakit kepala
Dapat dicegah dengan biofeedback, teknik relaksasi,
memassase leher dan otot bahu, penggunaan bungkusan panas
atau es ke leher, istirahat, mandi air hangat.
11). Spider nevi (Pembuluh sarang laba-laba)
Dapat dicegah dengan meyakinkan ibu bahwa itu akan hilang
setelah selesai kehamilan.
b. Pada kehamilan trimester kedua
Trimester kedua sering disebut sebagai periode pancaran
kesehatan, pada trimester kedua biasanya ibu merasakan sehat dan
sudah terbiasa dengan kadar hormon yang tinggi, serta rasa nyaman
akibat kehamilan sudah mulai berkurang, ibu pun belum terlalu besar
sehingga belum dirasakan ibu sebagai beban. Ibu sudah menerima
kehamilannya dan dapat mulai menggunakan energi dan pikiranya
secara lebih konstruktif, pada trimester ini pula ibu dapat merasakan
seseorang diluar dirinya dan banyak ibu yang merasa terlepas rasa
kecemasan dan rasa tidak nyaman seperti:
1). Cloasma
Dapat dicegah dengan hindari sinar matahari yang berlebihan.
2). Edema dependen
Dapat dicegah dengan cara hindariposisi berbaring, hindari
posisi tegak untuk waktu lama, masa istirahat dalam posisi terlentang
samping kiri dengan kaki agak diangkat, angkat kaki ketika duduk
atau istirahat, latihan kaki ditekuk, hindari kaos kaki ketat.
3). Gusi berdarah
Dapat dicegah dengan cara berkumur dengan air hangat,
memeriksakan gusi secara teratur, menjaga kesehatan gigi.
4). Sulit tidur
Dapat dicegah dengan cara gunakan teknik relaksasi progresif,
mandi air hangat, minum-minuman hangat, hindari kegiatan yang
merangsang sebelum tidur.
5). Gatal-gatal
Gatal-gatal dapat dicegah dengan gunakan kompres, mandi
siram air jeruk.
6). Keputihan
Dapat dicegah dengan cara tingkatkan kebersihan, pakaian
dalam terbuat dari katun.
7). Keringat bertambah
Dapat dikurangi atau dicegah dengan menggunakan pakaian
yang tipis dan longgar, banyak minum, mandi secara teratur.
8). Kontisipasi
Dapat dicegah dengan cara tingkatkan intake cairan dengan
serat didalam diet, minum cairan dingin, istirahat cukup, senam,
buang air teratur, BAB setelah ada dorongan.
9). Kram pada kaki
Dapat dicegah dengan cara kurangi konsumsi susu, panaskan
10). Mati rasa dan rasa geli pada jari tangan dan kaki
Dapat cegah dengan jelaskan kemungkinan penyebab,
perhatikan postur tubuh yang benar, rebahkan diri.
11). Hiperventilasi (sesak napas)
Dapat dikurangi dengan cara menjelaskan penyebabnya, atur
pernafasan sehingga tetap dalam keadaan normal, berdiri dengan
tangan direntangkan diatas kepala kemudian ambil napas panjang,
berusaha napas diantara rusuk.
12). Panas dalam
Dapat dicegah dengan cara makan sedikit tapi sering, hindari
makanan berlemak, kunyah permen karet.
13). Perut kembung
Dapat dicegah dengan cara menghindari makanan yang
mengandung gas, mengunyah secara sempurna, senam secara
teratur, pertahankan kebiasaan BAB.
14). Sakit punggung atas bawah
Dapat dicegah dengan menggunakan mekanisme tubuh yang
baik untuk mengangkat benda, gunakan BH yang pas dan
menompang, berlatih dengan mengangkat panggul, hindari
menggunakan sepatu yang berhak tinggi, gunakan kasur keras untuk
tidur, gunakan bantal untuk meluruskan punggung.
15). Varicositas pada kaki/vulva
Dapat dicegah dengan meninggikan kaki, berbaring dengan
posisi tegak lurus, kaki tidak bersilang, hindari duduk atau berdiri
terlalu lama, istirahat dalam posisi berbaring miring kekiri, serta
hindari pakaian ketat ( Hani, 2011. hal;82).
c. Pada kehamilan trimester ketiga
Trimester ketiga biasanya disebut periode menunggu dan
waspada sebab pada saat itu ibu tidak sabar menunggu kehadiran
bayinya. Gerakan bayi dan membesarnya perut merupakan dua hal
yang mengingatkan ibu akan bayinya. Kadang-kadang ibu merasakan
khawatir bahwa bayinya akan lahir sewaktu-waktu. Ini menyebabkan ibu
terjadinya persalinan pada ibu. Sering kali ibu merasakan khawatir dan
takut kalau bayi yang akan dilahirkannya tidak normal. Kebanyakan ibu
juga akan bersikap melindungi bayinya dan akan menghindari orang
atau benda apa saja yang dianggap membahayakan bayinya. Seorang
ibu mungkin mulai merasa takut akan rasa sakit dan bahaya fisik yang
timbul pada waktu melahirkan.
Rasa tidak nyaman akibat kehamilan timbul kembali dan banyak
ibu yang merasa dirinya aneh dan jelek. Selain itu, ibu juga merasa
sedih karena akan berpisah dengan bayinya dan akan kehilangan
perhatian khusus yang diterima selama hamil.
Suami, keluarga dan tenaga kesehatan dapat memberikan
dukungan dengan memberikan keterangan tentang persalinan yang
akan ibu lalui dan itu hanyalah masalah waktu saja (Varney, 2006.
hal;132).
5. Perubahan Fisiologis pada Kehamilan
Perubahan fisiologi sebagian sudah terjadi segera setelah fertilisasi dan
terus berlanjut selama kehamilan (Sulin,2008.hal;.174). Secara fisiologis
perubahan-perubahan yang dapat terjadi selama kehamilan antara lain:
a. Uterus
b. Serviks
c. Ovarium
d. Vagina dan Perineum
e. Kulit
f. Payudara
g. Sistem Metabolik
h. Sistem Kardiovaskuler
i. Traktus Digestivus
j. Traktus Urinarius
k. Sistem Endokrin
l. Sistem Muskuloskeletal.
6. Tujuan ANC
Tujuan asuhan antenatal meliputi:
a. Memantau kemajuan kehamilan untuk memastikan kesehatan ibu dan
b. Meningkatkan dan mempertimbangkan kesehatan fisik, mental, dan
sosial ibu dan janin
c. Mengenali secara dini adanya ketidaknormalan atau komplikasi yang
mungkin terjadi selama hamil, termasuk riwayat penyakit secara umum,
kebidanan dan pembedahan
d. Mempersiapkan persalinan cukup bulan, melahirkan dengan selamat,
ibu maupun bayinya dengan trauma seminimal mungkin
e. Mempersiapkan ibu agar masa nifas berjalan normal dan pemberian ASI
eksklusif
f. Mempersiapkan peran ibu dan keluarga dalam menerima kelahiran bayi
agar dapat tumbuh kembang secara normal (Prawirohardjo, 2009.
hal;90).
7. Jadwal kunjungan ulang ANC
Jadwal kunjungan ulang ANC meliputi :
a. Satu kali pada trimester I
b. Satu kali pada trimester II
c. Dua kali pada trimester III
(Prawirohardjo, 2006. hal;90).
8. Pelayanan/asuhan standar minimal termasuk “10T”
a. Timbang berat badan dan ukur tinggi badan
b. Ukur tekanan darah
c. Nilai status Gizi (ukur LILA)
d. Ukur Tinggi fundus uteri
e. Tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ)
f. Skrining Status Imunisasi Tetanus dan berikan imunisasi Tetanus
Toksoid (TT) bila diperlukan
g. Beri tablet tambah darah (tablet besi)
h. Periksa laboratorium (rutin dan khusus)
i. Tatalaksana /penanganan khusus
j. Temu wicara (konseling)
9. Imunisasi TT
Tabel 2.1 waktu imunisasi TT
Antigen Interval
Sumber: Prawirohardjo. Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal. Jakarta: Yayasan Bina PustakaSarwono Prawirohardjo, 2006.
10. Pemeriksaan
Tabel 2.2 Pemeriksaan pada ibu hamil
Pemeriksaan fisik Pemeriksaan luar
pertama 2.Uterus 3.Adneksa 4.Bartholin 5.Skene 6.Uretra
Bila usia kehamilan <12
minggu
Sumber : Prawirohardjo. Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2006.
B. Persalinan 1. Pengertian
Persalinan dan kelahiran merupakan kejadian fisiologis yang normal.
Persalinan dan kelahiran normal adalah proses pengeluaran janin yang
terjadi pada kehamilan cukup bulan (37-42 minggu), lahir spontan dengan
presenteasi belakang kepala yang berlangsung dalam 18 jam, tanpa
komplikasi pada ibu maupun pada janin (Prawirohardjo, 2009. hal;109).
Persalinan adalah rangkaian proses yang berakhir dengan
pengeluaran hasil konsepsi oleh ibu (Varney, 2008. hal; 672).
Persalinan adalah proses dimana janin dan ketuban didorong keluar
melalui jalan lahir (Sumarah dkk, 2008. hal; 1).
Persalinan adalah proses dimana bayi, plasenta dan selaput ketuban
keluar dari uterus ibu (JNPK-KR, 2008. hal;39).
Jadi, persalinan adalah masa pengeluaran hasil konsepsi dimulai dari
kala I sampai kala IV.
2. Sebab-sebab mulainya persalinan
Bagaimana terjadinya persalinan belum diketahui dengan pasti,
sehingga menimbulkan beberapa teori yang berkaiatan dengan mulainya
kekuatan his. Dengan demikian dapat dikemukakan beberapa teori sebab
mulainya persalianan antara lain (Sumarah dkk, 2008. hal;3).
a. Teori keregangan
Otot rahim mempunyai kemampuan meregang dalam batas tertentu.
Setelah melewati batas waktu tersebut terjadi kontraksi sehingga
b. Teori penurunan progesteron
Proses penuaan plasenta terjadi mulai umur kehamilan 28 minggu,
dimana terjadi penimbunan jaringan ikat, pembuluh darah mengalami
penyempitan dan buntu. Produksi progesteron mengalami penurunan,
sehingga otot rahim lebih sensitif terhadap oksitosin, akibat otot rahim
mulai berkontraksi setelah tercapai tingkat penurunan progesteron
tertentu.
c. Teori oksitosin internal
Oksitosin dikeluarkan oleh kelenjar hipofise parst posterior, perubahan
keseimbangan esterogen dan progesteron dapat mengubah sensitivitas
otot rahim, sehingga sering terjadi kontraksi Braxton hiks. Menurunnya
konsentrasi progesteron akibat tuanya kehamilan maka oksitosin dapat
meningkatkan aktivitas, sehingga persalinan dimulai.
d. Teori prostaglandin
Konsentrasi prostaglandin meningakat sejak umur kehamilan 15
minggu, yang dikeluarkan oleh desidua. Pemberian prostaglandin pada
saat hamil dapat menimbulkan kontraksi otot rahim sehingga terjadi
persalinan.
e. Teori hipotalamus-pituitari dan galandula suprarenalis
Teori ini merupaka pada kehamilan dengan anensefolus sering terjadi
keterlambatan persalinan karena tidak terbentuk hipotalamus.
f. Teori berkurangnya nutrisi
Berkurangnya nutrisi pada janin dikemukakan oleh hippokrates untuk
pertama kalinya. Bila nutrisi pada janin berkurang maka hasil konsepsi
akan segera dikeluarkan.
g. Faktor lain
Tekanan pada ganglion servikal dari pleksus framkenhauser yang
terletak dibelakang serviks. Bila ganglion ini tertekan, maka kontraksi
uterus dapat dibangkitkan.
3. Tanda dan gejala persalinan
Tanda dan gejala persalinan yaitu sebagai berikut:
a. Penipisan dan pembukaan serviks
c. Keluar cairan lendir bercampur darah melalui jalan lahir (JNPK- KR,
2008. hal; 39).
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan
Faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan sebagai berikut:
a. Passage (jalan lahir)
Jalan lahir terdiri dari panggul ibu, yakni bagian tulang padat, dasar
panggul, vagina, dan introitus (lubang luar vagina).
b. Passenger (janin dan plasenta)
Janin bergerak sepanjang jalan lahir merupakan akibat interaksi
beberapa faktor, yakni ukuran kepala janin, presentasi, letak, sikap dan
posisi janin.karena plasenta juga melewati jalan lahir, maka dianggap
juga sebagai bagian dari passenger yang menyertai janin.
c. Power (kekuatan)
Kekuatan terdiri dari kekuatan ibu melakukan kontraksi involunter,
secara bersama untuk mengeluarkan kekuatan primer, menandai
dimulainya persalinan (Sumarah dkk, 2008. hal;23).
5. Tahapan Persalinan
Tahapan persalinan dibagi menjadi 4 tahap yaitu:
a. Kala I
Kala I adalah kala pembukaan yang berlangsung antara pembukaan nol
sampai lengkap (10 cm). Proses ini berlangsung kurang lebih 18-24 jam,
yang terbagi menjadi 2 fase (Sumarah dkk, 2008. hal;4).
1). Fase laten
Fase laten (8 jam) dari pembukaan 0 sampai pembukaan 3 cm
2). Fase aktif
Fase aktif ini masih dibagi menjadi 3 fase yaitu:
a) Fase akselerasi, dimana dalam waktu 2 jam pembukaan 3 cm
menjadi 4 cm
b) Fase dilatasi maksimal, yakni dalam waktu 2 jam pembukaan
berlangsung sangat cepat, dari pembukaan 4 cm menjadi 9 cm
c) Fase deselerasi, dimana pembukaan menjadi lambat kembali,
Penanganan/asuhan
1).Bantulah ibu dalam persalinan jika ia tampak gelisah, ketakukan,
dan kesakitan :
a) Berilah dukungan dan yakinkan dirinya
b) Berikan informasi mengenai proses dan kemajuan persalinan
c) Dengarkan keluhan ibu dan cobalah untuk lebih sensitif
terhadap perasaannya
2). Jika ibu tersebut tampak kesakitan, dukungan/asuhan yang dapat
diberikan :
a) Lakukan perubahan posisi
b) Lakukan sesuai dengan keinginan ibu, tetapi jika ibu ingin
ditempat tidur sebaiknya dianjurkan miring ke kiri
c) Sarankan ibu untuk berjalan
d) Ajaklah orang yang menemaninya (keluarga) untuk memijat
atau menggosok punggungnya, membasuh mukanya diantara
kontraksi
e) Ibu diperbolehkan melakukan aktivitas sesuai dengan
kesanggupannya
f) Ajarkan kepadanya teknik bernapas, ibu diminta untuk menarik
napas panjang, menahan napasnya sebentar kemudian
dilepaskan dengan cara meniup udara keluar sewaktu terasa
kontraksi
3). Penolong tetap menjaga hak privasi ibu dalam persalinan, antara
lain menggunakan penutup atau tirai, tidak menghadirkan orang
lain tanpa sepengetahuan dan seizin pasien
4). Menjelaskan kemajuan persalinan dan perubahan yang terjadi
serta prosedur yang akan dilaksanakan dan hasil-hasil
pemeriksaan
5). Membolehkan ibu untuk mandi dan membasuh sekitar
kemaluannya setelah BAK/BAB
6). Ibu bersalin biasanya merasa panas dan banyak keringat, atasi
dengan cara: gunakan kipas angin atau AC dalam kamar, gunakan
7). Untuk memenuhi kebutuhan energi dan mencegah dehidrasi,
berikan cukup minum
8). Sarankan ibu untuk berkemih sesering mungkin
(Prawirohardjo, 2011. hal;N-8)
Pemantauan
Tabel 2.3 Frekuensi minimal penilaian dan intervensi dala persalinan normal
Parameter Frekuensi pada fase laten Setiap 30-60 menit
Setiap 1 jam Setiap 30-60 menit
Setiap 30 menit Setiap 30 menit Setiap 4 jam Setiap 4 jam
Sumber : Prawirohardjo. Buku Panduan Pelayanan Kesehatan
Maternal dan Neonatal.Yayasan Bina Pustaka Sarwono
Prawirohardjo.2011
b. Kala II
Kala II ini dimulai dari pembukaan lengkap (10 cm) sampai bayi
lahir. Proses ini biasanya berlangsung 2 jam pada primi dan 1 jam pada
multi. Tanda dan gejala kala II yaitu sebagai berikut (Sumarah dkk,
2008. hal;6).
1) Gejala dan tanda kala II persalinan:
a) Ibu merasakan ingin meneran bersama terjadinya kontraksi.
b) Ibu merasakan adanya peningkatan tekanan pada vagina.
c) Perineum menonjol.
d) Vulva-vagina membuka.
e) Meningkatnya pengeluaran lender bercampur darah.
2) Tanda pasti kala II ditentukan melalui periksa dalam adalah:
a) Pembukaan serviks telah lengkap
b) Terlihatnya bagian kepala bayi melalui introitus vagina
Penanganan/asuhan
1) Memberikan dukungan terus menerus kepada ibu dengan:
mendampingi ibu agar merasa nyaman dan menawarkan minum,
mengipasi, serta memijati ibu.
2) Menjaga kebersihan diri : ibu tetap dijaga kebersihannya agar
terhindar dari infeksi, dan jika ada darah lendir atau cairan ketuban
segera dibersihkan.
3) Mengipasi dan masase untuk manambah kenyamanan bagi ibu.
4) Memberikan dukungan mental untuk mengurangi kecemasan atau
ketakutan ibu dengan cara: menjaga privasi ibu, penjelasan
tentang proses dan kemajuan persalinan, dan penjelasan tentang
prosedur yang akan dilakukan dan keterlibatan ibu.
5) Mengatur posisi ibu dalam mengedan dapat dengan posisi
sebagai berikut: jongkok, menungging, tidur miring, dan setengah
duduk.
6) Menjaga kandung kemih tetap kosong, ibu dianjurkan berkemih
sesering mungkin
7) Memberikan cukup minum : memberi tenaga dan mencegah
dehidrasi.
3) Kelahiran kepala bayi
a) Mintalah ibu mengedan atau memberikan sedikit dorongan saat
kepala bayi lahir
b) Letakkan satu tangan ke kepala bayi agar defleksi tidak terlalu
cepat
c) Menahan perineum dengan satu tangan lainnya jika diperlukan
d) Mengusap muka bayi untuk membersihkannya dari kotoran
lendir/darah
e) Periksa tali pusat :
(1) Jika tali pusat mengelilingi leher bayi dan terlihat longgar,
selipkan tali pusat melalui kepala bayi
(2) Jika lilitan tali pusat terlalu ketat, tali pusat diklem pada dua
tempat kemudian digunting diantara klem tersebut, sambil
4) Kelahiran Bahu dan Anggota Seluruhnya
a) Biarkan kepala bayi berputar dengan sendirinya
b) Tempatkan kedua tangan pada sisi kepala dan leher bayi
c) Lakukan tarikan lembut kebawah untuk melahirkan bahu depan
d) Lakukan tarikan lembut kebawah untuk melahirkan bahu
belakang
e) Selipkan satu tangan ke bahu dan lengan bagian belakang bayi
sambil menyangga kepala dan selipkan satu tangan lainnya ke
punggung bayi untuk mengeluarkan tubuh bayi seluruhnya
f) Letakkan bayi tersebut diatas perut ibu
g) Secara menyeluruh keringkan bayi, bersihkan matanya, dan nilai
pernapasan bayi :
(1) Jika bayi menangis atau bernapas (dada bayi terlihat naik
turun paling sedikit 30x/menit) tinggalkan bayi tersebut
bersama ibunya
(2) Jika bayi tidak bernapas dalam waktu 30 detik, mintalah
bantuan, dan segera mulai resusitasi bayi
h) Klem dan potong tali pusat
i) Pastikan bahwa bayi tetap hangat dan memiliki kontak kulit
dengan dada si ibu. Bungkus bayi dengan kain yang halus dan
kering, tutup dengan selimut, dan pastikan kepala bayi terlindung
dengan baik untukmenghindari hilangnya panas tubuh
(Prawirohardjo, 2011. hal;N-15 dan N-17).
c. Kala III
Kala II ini dimulai segera setelah bayi lahir sampai lahirnya
plasenta, yang berlangsung tidak lebih dri 30 menit (Sumarah dkk, 2008.
hal;7).
1) Manajemen aktif kala III
Penatalaksanaan aktif pada kala III membantu menghindarkan
terjadinya perdarahan pascapersalinan.
Penatalaksanaan aktif kala III meliputi :
a) Pemberian oksitosin dengan segera
c) Massase uterus segera setelah plasenta lahir.
Penanganan:
a) Memberikan oksitosin untuk merangsang uterus berkontraksi yang
juga mempercepat pelepasan plasenta: oksitosin dapat diberikan
dalam 2 menit setelah kelahiran bayi secara IM
b) Lakukan penegangan tali pusat terkendali (PTT) dengan cara:
(1) Satu tangan diketakkan pada korpus uteri tepat diatas simfisis
pubis. Selama kontraksi tangan mendorong korpus uteri
dengan gerakan dorso cranial kearah belakang dan ke arah
kepala ibu
(2) Tangan yang satu memegang tali pusat dengan klem 5-6 cm
didepan vulva
(3) Jaga tahanan ringan pada tali pusat dan tunggu adanya
kontraksi kuat (2-3 menit)
(4) Selama kontraksi, lakukan tarikan terkendali pada tali pusat
yang terus menerus, dalam tegangan yang sama dengan
tangan ke uterus.
c) PTT dilakukan hanya selama uterus berkontraksi. Tangan pada
uterus merasakan kontraksi, ibu dapat juga memberi tahu petugas
ketika ibu merasakan kontraksi. Ketika uterus tidak sedang
berkontraksi, tangan petugas dapat tepat berada pada uterus,
tetapi bukan melakukan PTT. Ulangi langkah-langkah PTT pada
setiap kontraksi sampai plasenta terlepas.
(1) Begitu plasenta terasa lepas, keluarkan dengan
menggerakkan tangan atau klem pada tali pusat mendekati
plasenta, keluarkan plasenta dengan gerakan kebawah dan
keatas sesuai dengan jalan lahir. Kedua tangan dapat
memegang plasenta dan perlahan memutar plasenta searah
jarum jam untuk mengeluarkan selaput ketuban.
(2) Segera setelah plasenta dan selaputnya dikeluarkan,
massase fundus agar menimbulkan kontraksi. Hal ini dapat
mengurangi pengeluaran darah dan mencegah perdarahan
postpartum. Jika uterus tidak berkontraksi kuat selama 10-15
kompresi bimanual dalam. Jika atonia uteri tidak teratasi
dalam waktu 1-2 menit , ikuti prosedur untuk perdarahan
postpartum.
d) Jika mengguankan manajemen aktif dan plasenta belum juga
lahir dalam waktu 15 menit, berikan oksitosin 10 unit IM, dosis
kedua dalam jarak waktu 15 menit dari pemberian oksitosin
dosis pertama.
e) Jika menggunakan manajemen aktif dan plasenta belum juga
lahir dalam waktu 30 menit:
(1) Periksa kandung kemih dan lakukan kateterisasi jika
kandung kemih penuh
(2) Periksa adanya tanda-tanda pelepasan plasenta
(3) Berikan oksitosin 10 IU dosis ketiga, dalam jarak waktu
15 menit dari pemberian oksitosin dosis pertama
(4) Siapkan rujukan jika tidak ada tanda-tanda pelepasan
plasenta
f) Periksa wanita tersebut secara seksama dan jahit semua
robekan pada serviks atau vagina atau perbaiki episiotomi
(Prawirohardjo, 2011. hal;N-19 – N-20).
d. Kala IV
Pada kala IV ini dimulai dari saat lahirnya plasenta sampai 2 jam
pertama postpartum (Sumarah dkk,2008.hal;8).
Penanganan :
1) Periksa fundus setiap 15 menit pada jam pertama dan setiap
20-30 menit selama jam kedua. Jika kontraksi tidak kuat, massase
uterus sampai menjadi keras.
2) Periksa tekanan darah, nadi, kandung kemih, dan perdarahan
setiap 15 menit pada jam pertama dan setiap 30 menit pada jam
kedua.
3) Anjurkan ibu makan, minum untuk mencegah dehidrasi.
4) Bersihkan perineum dan kenakan pakaian ibu yang bersih dan
5) Biarkan ibu beristirahat, ia telah bekerja keras melahirkan
bayinya. Bantu ibu pada posisi nyaman.
6) Biarkan bayi berada pada ibu untuk meningkatkan hubungan ibu
dangan bayi, sebagai permulaan menyusui bayinya
7) Bayi sangat siap segera setelah kelahiran. Hal ini sangat tepat
untuk memulai memberikan ASI, menyusui juga membantu
uterus berkontraksi.
8) Jika ibu ingin ke kamar mandi, ibu boleh bangun, pastikan ibu
dibantu karena masih dalam keadaan lemah dan pusing setelah
persalinan. Pastikan ibu sudah BAK dalam 3 jam postpartum
9) Ajari ibu atau keluarga tentang: bagaimana memeriksa fundus
dan menimbulkan kontraksi, dan tanda-tanda bahaya bagi ibu
dan bayi (Prawirohardjo, 2011. hal;N-21).
6. Kelainan pada Persalinan
Persalinan lama disebut juga “ distosia “, didefinisikan sebagai persalinan yang abnormal/sulit. Sebab-sebabnya dapat dibagi dalam 3
golongan berikut ini.
a. Kelainan tenaga (kelainan his)
His yang tidak normal dalam kekuatan atau sifatnya menyebabkan
kerintangan pada jalan lahir yang lazim terdapat pada setiap persalinan,
tidak dapat diatasi sehingga persalinan mengalami hambatan atau
kemacetan.
Jenis - jenis kelainan His
1). Inersia uteri
Disini his bersifat biasa dalam arti bahwa fundus berkontraksi
lebih kuat dan lebih dahulu dari pada bagian-bagian lain, peranan
fundus tetap menonjol. Kelainannya terletak dalam hal kontraksi
uterus lebih aman, singkat, dan jarang dari pada biasa. Keadaan
umum pada penderita biasanya baik dan rasa nyeri tidak seberapa.
Selama ketuban masih utuh umumnya tidak berbahaya, baik bagi ibu
maupun janin, kecuali persalinan berlangsung terlalu lama, dalam hal
terakhir ini morbiditas ibu dan mortalitas janin baik. Keadaan ini
kuat untuk waktu yang lama, dan hal itu dinamakan inersia uteri
sekunder.
Diagnosis inersia uteri paling sulit ditegakkan pada masa laten.
Kontraksi uterus yang disertai dengan rasa nyeri, tidak cukup untuk
menjadi dasar utama diagnosis bahwa persalinan sudah dimulai.
Untuk sampai pada kesimpulan ini diperlukan kenyataan bahwa
sebagai akibat kontraksi itu terjadi perubahan pada serviks yakni
pendataran dan atau pembukaan. Kesalahan yang sering dibuat ialah
mengobati seorang penderita untuk inersia uteri padahal persalinan
belum mulai (fase labour).
2). His terlampau kuat
His terlampau kuat atau disebut juga hypertonic uterine
contraction. Walaupun golongan coordinated hypertonic uterine
contraction bukan merupakan penyebab distosia. His yang terlalu
kuat dan terlalu efisien menyebabkan persalinan selesai dalam waktu
yang sangat singkat. Partus yang sudah selesai kurang dari 3 jam
dinamakan partus presipitatus yang ditandai oleh sifat his yang
normal, tonus otot diluar his juga biasa, kelainannya terletak pada
kekuatan his, khususnya vagina dan perineum. Bayi bisa mengalami
perdarahan dalam tengkorak karena bagian tersebut mengalami
tekanan kuat dalam waktu yang singkat.
3). Incoordinate uterine action
Disini sifat his berubah, tonus otot uterus meningkat, juga diluar
his, dan kontraksinya tidak berlangsung seperti biasa karena tidak
ada sinkronisasi kontraksi bagian-bagiannya. Tidak adanya
koordinasi antara kontraksi bagian atas, tengah, dan bawah
menyebabkan his tidak efisien dalam mengadakan pembukaan.
b. Kelainan janin
Persalinan dapar mengalami gangguan atau kemacetan karena
c. Kelainan jalan lahir
Kelainan dalam ukuran atau bentuk jalan lahir bisa menghalangi
kemajuan persalinan atau menyebabkan kemacetan.
Sebelum membicarakan kelainan his, ada baiknya diperhatikan
kontraksi uterus pada persalinan biasa. Secara singkat dapat
dikemukakan bahwa his yang normal mulai dari salah satu sudut di
fundus uteri yang kemudian menjalar merata simetris keseluruh korpus
uteri dengan adanya dominasi kekuatan pada fundus uteri dimana
lapisan otot uterus paling dominan, kemudian mengadakan relaksasi
secara merata dan menyeluruh hingga tekanan dalam ruang amnion
balik ke asalnya ± 10 mmHg.
d. Kelainan kala I
1). Fase laten memanjang
Friedman dan Sachtleben mendefinisikan fase laten
berkepanjangan apabila lama fase ini lebih dari 20 jam pada nulipara
dan 14 jam pada ibu multipara. Durasi rata-ratanya adalah 8,6 jam
(+2 SD 20,6 jam) rentangnya dari 1 sampai 44 jam. Dengan
demikian, lama fase laten sebesar 20 jam pada ibu nulipara
mencerminkan nilai maksimum secara statistik.
2). Fase aktif memanjang
Kemajuan persalinan pada ibu nulipara memiliki makna khusus
karena kurva-kurva memperlihatkan perubahan cepat dalam
kecuraman pembukaan serviks antara 3-4 cm. Dalam hal ini, fase
aktif persalinan dari segi kecepatan pembukaan serviks tertinggi,
secara konsistensi berawal saat serviks mengalami pembukaan 3-4
cm. Dengan demikian, pembukaan serviks 3-4 cm atau lebih, disertai
adanya kontraksi uterus dapat secara meyakinkan digunakan
sebagai batas awal persalinan aktif.
Secara spesifik ibu nulipara yang masuk ke fase aktif dengan
pembukaan 3-4 cm dapat diharapkan mencapai pembukaan 8
sampai 10 cm dalam 3 sampai 4 jam. Pengamatan ini mungkin
bermanfaat. Sebagai contoh, apabila pembukaan serviks mencapai 4
dalam 4 jam apabila persalinan spontan berlangsung normal. Namun,
kelainan persalinan fase aktif sering dijumpai.
Keterkaitan atau faktor lain yang berperan dalam persalinan yang
berkepanjangan dan macet adalah sedasi berlebihan, anestesia
regional dan malposisi janin, misalnya oksiput posterior persisten.
Pada persalinan berkepanjangan dan macet, Friedman
menganjurkan pemeriksaan fetopelvik untuk mendiagnosis
disproporsi sefalopelvik. Terapi yang dianjurkan untuk persalinan
yang berkepanjangan adalah penatalaksanaan menunggu,
sedangkan oksitosin dianjurkan untuk persalinan yang macet tanpa
disproporsi sefalopelvik.
Hauth dkk, melaporkan bahwa agar induksi atau akselerasi
persalinan dengan oksitosin efektif, 90 persen ibu mencapai 200
sampai 250 satuan Montevideo, dan 40 persen mencapai paling
sedikit 300 satuan Montevideo. Hasil- hasil ini mengisyaratkan bahwa
terdapat batas-batas minimal tertentu pada aktivitas uterus yang
harus dicapai sebelum dilakukan seksio cesaria atas indikasi distosia.
Oleh karena itu, American College of Obstetricians and
Gynecologists menyarankan bahwa sebelum ditegakkan diagnosis
kemacetan pada persalinan kala I, kedua kriteria ini harus terpenuhi.
a) Fase laten telah selesai, dengan serviks membuka 4 cm atau lebih
b) Sudah terjadi pola kontraksi uterus sebesar 200 satuan
Montevideo atau lebih dalam periode 10 menit selama 2 jam tanpa
perubahan pada serviks (Prawirohardjo, 2009. Hal;562-574).
e. Kala II memanjang
Upaya mengedan ibu menambah risiko pada bayi karena
mengurangi jumlah oksigen ke plasenta. Dianjurkan mengedan secara
spontan (mengedan dan menahan nafas terlalu lama tidak dianjurkan).
1) Jika malpresentasi dan tanda-tanda obstruksi bisa disingkirkan,
berikan infus oksitosin
2) Jika tidak ada kemajuan penurunan kepala: jika kepala tidak lebih
dari 1/5 diatas sympisis pubis, atau bagian tulang kepala di stasion
1/5-3/5 diatas sympisis pubis, atau bagian tulang kepala diantara stasion
(0) – (-2), lakukan ekstraksi vakum. Jika kepala lebih dari 3/5 diatas
sympisis pubis, atau bagian tulang kepala diatas stasion (-2), lakukan
seksio cesaria (Prawirohardjo, 2011. hal; M-56).
7. Induksi Persalinan
Induksi persalinan yaitu merangsang uterus untuk memulai terjadinya
persalinan.
a. Penilaian serviks
Keberhasilan induksi persalinan bergantung pada skor pelvis. Jika skor
≥ 6, biasanya induksi cukup dilakukan dengan oksitosin. Jika ≤ 5,
matangkan serviks lebih dahulu dengan prostaglandin atau kateter foley.
Tabel 2.4 penilaian serviks untuk induksi persalinan (Skor Bishop)
Faktor Skor 0 Skor 1 Skor 2 Skor 3
Bukaan (cm) Tertutup 1-2 3-4 Lebih dari 5
Panjang serviks (cm) > 4 3-4 1-2 < 1
Konsistensi Kenyal Rata-rata Lunak -
Posisi Posterior Tengah Anterior -
Turunnya kepala (cm dari spina iskiadika)
-3 -2 -1 +1, +2
Turunnya kepala (dengan palpasi abdominal menurut
sistem perlimaan)
4/5 3/5 2/5 1/5
Sumber : Prawirohardjo. Buku Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal. Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo. 2011
b. Oksitosin
1) Oksitosin digunakan secara hati-hati karena gawat janin dapat terjadi
dari hiperstimulasi. Walaupun jarang, ruptura uteri dapat pula terjadi,
lebih-lebih pada multipara. Senantiasa lakukan observasi ketat pada
pasien yang mendapat oksitosin.
2) Dosis efektif oksitosin bervariasi. Infus oksitosin dalam dekstrose
atau garam fisiologik, dengan tetesan dinaikkan secara gradual
sampai his adekuat. Pertahankan tetesan sampai persalinan.
3) Pantau tekanan darah, denyut nadi, dan kontraksi ibu, dan periksa
denyut jantung janin (DJJ)
5) Baringkan ibu hamil miring kiri
6) Catat semua pengamatan
a) Kecepatan infus oksitosin
b) Frekuensi dan lamanya kontraksi
c) Denyut jantung janin (DJJ) tiap 30 menit, dan selalu setelah
kontraksi. Apabila DJJ kurang dari 100x/menit, segera hentikan
infus
7) Infus oksitosin 2,5 unit dalam 500 cc dekstrose (atau gram fisiologik)
mulai dengan 10 tetes per menit
8) Naikkan kecepatan infus 10 tetes per menit tiap 30 menit sampai
kontraksi adekuat (3x/10’/40”) dan pertahankan sampai terjadi
kelahiran.
Tabel 2.5 Kecepatan infus oksitosin untuk induksi persalinan
Waktu sejak
Volume infus Total volume infus
9) Jika tidak terjadi hiperstimulasi (lama kontraksi lebih dari 60 detik)
atau lebih dari 4 kali kontraksi dalam 10 menit, hentikan infus dan
kurangi hiperstimulasi dengan:
a) Terbutalin 250 mcg IV pelan-pelan selama 5 menit, ATAU
b) Salbutamol 5 mg dalam 500 ml cairan (garam fisiologik atau
Ringer Laktat) 10 tetes per menit.
Tabel 2.6 Eskalasi cepat pada primigravida. Kecepatan infus oksitosin untuk
`induksi persalinan
Sumber : Prawirohardjo. Buku Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal. Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo. 2011.
10) Jika tidak tercapai kontraksi yang adekuat (3 kali tiap 10 menit
dengan lama lebih dari 40 detik) setelah infus oksitosin mencapai
60 tetes per menit:
a) Naikkan konsentrasi oksitosin menjadi 5 unit dalam 500 ml
dekstrose (atau garam fisiologik) dan sesuaikan kecepatan infus
b) Naikkan kecepatan infus 10 tetes per menit tiap 30 menit sampai
kontraksi adekuat (3 kali tiap 10 menit dengan lama lebih dari 40
detik) atau setelah infus oksitosin mencapai 60 tetes per menit.
10) Jika masih tidak tercapai kontraksi yang adekuat dengan kontraksi
yang lebih tinggi:
a) Pada multigravida, induksi dianggap gagal, lakukan seksio
cesaria
b) Pada primigravida, infus oksitosin bisa dinaikkan konsentrasinya
yaitu : 10 unit dalam 500 ml dekstrose (atau garam fisiologik) 30
tetes per menit. Naikkan 10 tetes tiap 30 menit sampai kontraksi
adekuat. Jika kontraksi tetap tidak adekuat setelah 60 tetes per
menit (60 mIU per menit), lakukan seksio cesaria (Prawirohardjo,
2011. hal;P-10 sampai P-14).
C. Bayi Baru Lahir 1. Pengertian
Masa neonatal adalah masa sejak lahir sampai dengan 4 minggu (28
hari) sesudah kelahiran (Prawirohardjo, 2009. hal;237).
Neonatus dini adalah bayi berusia 0-7 hari. Neonatus lanjut adalah bayi
berusia 7-28 hari (Muslihatun, 2010. hal;2).
Jadi, masa neonatus adalah bayi berumur 0 (baru lahir) sampai dengan
usia 1 bulan sesudah lahir.
2. Penilaian pertama bayi baru lahir
a. Bayi cukup bulan
b. Air ketuban jernih, tidak bercampur mekonium
c. Bayi menangis atau bernapas
d. Tonus otot bayi baik
3. Asuhan bayi baru lahir
a. Jaga kehangatan
b. Bersihkan jalan napas
c. Keringkan dan tetap jaga kehangatan
d. Potong dan ikat tali pusat tanpa membubuhi apapun, kira-kira 2 menit
e. Lakukan Inisiasi Menyusui Dini dengan cara kontak kulit bayi dengan
kulit ibu
f. Beri salep mata antibiotika tetrasiklin 1% pada kedua mata
g. Beri suntikan vitamin K1 1 mg IM, di paha kiri anterolateral setelah
Inisiasi Menyusui Dini
h. Beri imunisasi HB0 0,5 mL IM, dipaha kanan anterolateral, diberikan
kira-kira 1-2 jam setelah pemberian vitamin K1
(JNPK-KR, 2008. hal;126).
4. Aspek-aspek penting dari asuhan segera bayi yang baru lahir
a. Jagalah bayi agar tetap hangat
1) Pastikan bayi tersebut tetap hangat dan terjadi kontak antara kulit
bayi dengan kulit ibu
2) Gantilah handuk/kain yang basah, dan bungkus bayi tersebut dengan
selimut dan jangan lupa memastikan bahwa kepala telah terlindung
dengan baik untuk mencegah keluarnya panas tubuh
3) Pastikan bayi tetap hangat dengan memeriksa telapak bayi setiap 15
menit.
b. Kontak dini dengan ibu
1) Berikan bayi kepada ibunya secepat mungkin. Kontak dini antara ibu
dan bayi penting untuk: kehangatan, mempertahankan panas yang
benar pada bayi baru lahir, ikatan batin dan pemberian ASI.
2) Doronglah ibu untuk menyusui bayinya apabila bayi telah siap
(dengan menunjukan refleks rooting). Jangan paksakan bayi untuk
menyusu.
c. Pernapasan
Sebagian besar bayi akan bernapas secara spontan. Pernapasan bayi
sebaiknya diperiksa secara teratur untuk mengetahui adanya masalah.
1) Periksa pernapasan dan warna kulit bayi setiap 5 menit
2) Jika bayi tidak segera bernapas, lakukan hal-hal berikut:
a) Keringkan bayi dengan selimut atau handuk yang hangat
b) Gosokan punggung bayi dengan lembut
3) Jika bayi masih belum mulai bernapas setelah 60 detik mulai
4) Apabila bayi sianosis atau sukar bernapas berilah oksigen kepada
bayi dengan kateter nasal atau nasal prongs.
d. Perawatan mata
Obat mata eritromisin 0,5% atau tetrasiklin 1 % dianjurkan untuk
pencegahan penyakit mata karena klamidia (penyakit menular seksual).
Obat mata perlu diberikan pada jam pertama setelah persalinan, yang
lazim dipakai adalah larutan perak nitrat atau Neosporin dan langsung
diteteskan pada mata bayi segera setelah bayi lahir (Prawirohardjo,
2011. hal;N-31-N-32).
5. Tanda-tanda bayi baru lahir normal
Semua bayi baru lahir harus dinilai adanya tanda-tanda kegawatan atau
kelainan menunjukan suatu penyakit.
Tanda-tanda bayi baru lahir normal :
a. Berat badan : 2500-4000 gram
b. Panjang badan : 48-52 cm
c. Lingkar kepala : 33-35 cm
d. Llingkar dada : 30-38 cm
e. Denyut Jantung : 120-160 x/menit
f. Pernapasan : 40-60 x/menit
g. Kulit kemerahan dan licin karena jaringan dan adanya verniks kaseosa
h. Rambut lanugo terlihat, rambut kepala biasanya sudah sempurna
i. Kuku agak panjang dan lepas
j. Genetalia : jika perempuan labia mayora telah menutupi labia minora,
jika laki-laki testis sudah turun.
6. Kunjungan ulang
Menurut JNPK-KR, 2008. hal;137, mengatakan terdapat minimal tiga kali
kunjungan ulang bayi baru lahir:
a. Kunjungan I : pada usia 6-48 jam
b. Kunjungan II : pada usia 3-7 hari
c. Kunjungan III : pada usia 8-28 hari
7. Refleks Pada Bayi
a. Refleks menghisap ( sucking refleks )
Bayi akan melakukan gerakan menghisap ketika anda