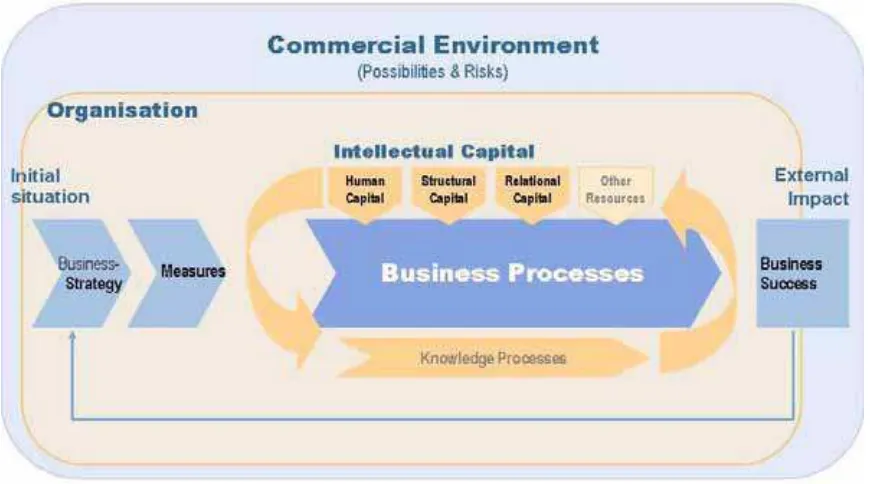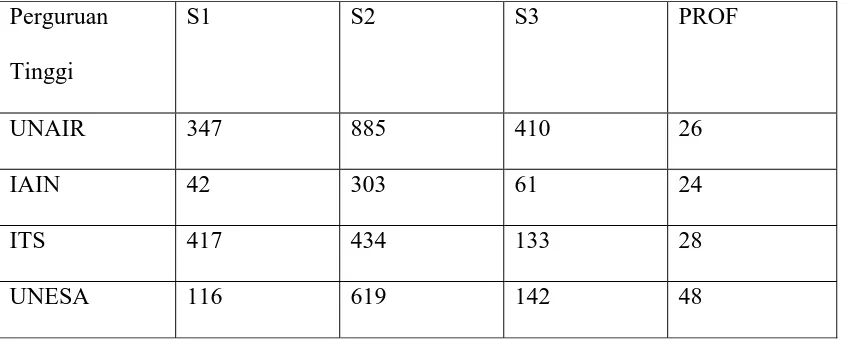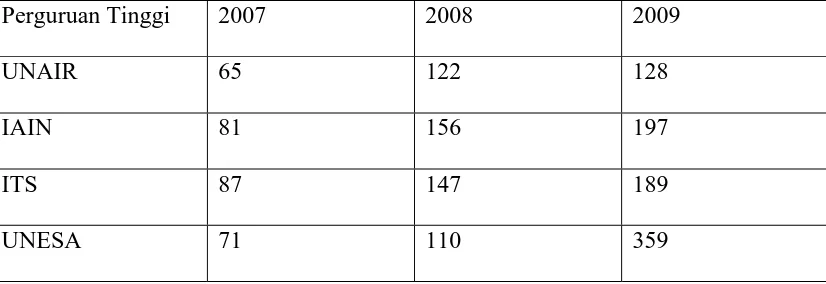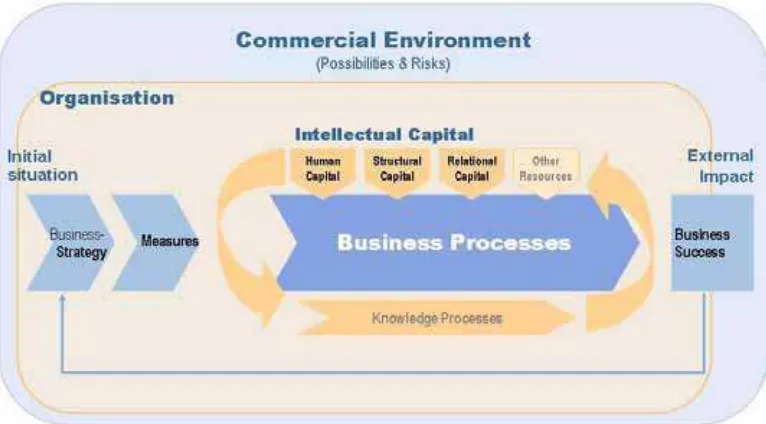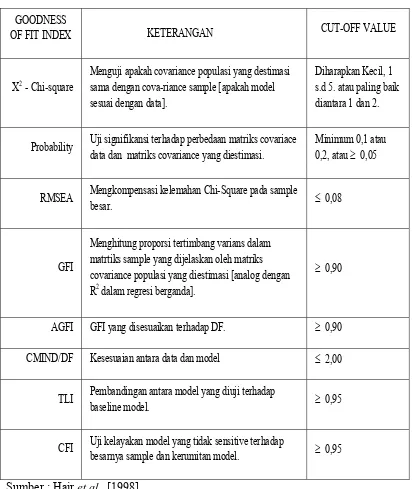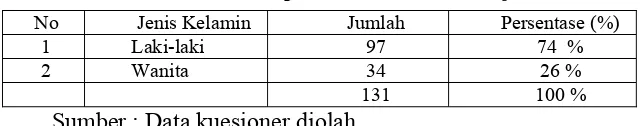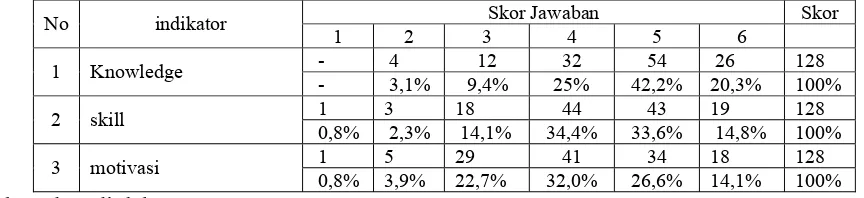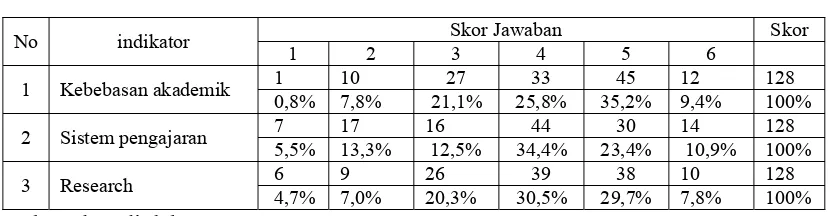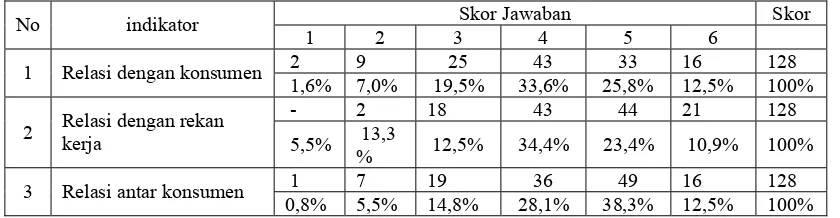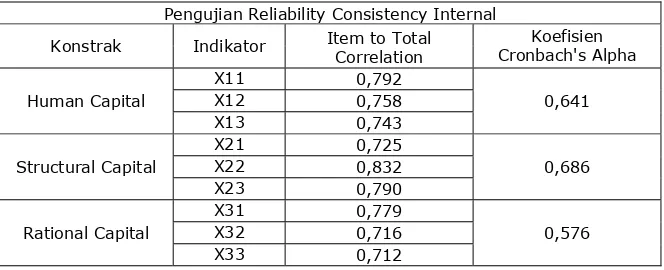SKRIPSI
ANALISIS INTELLECTUAL CAPITAL
STATEMENT PADA PERGURUAN TINGGI
NEGERI DI SURABAYA
(Studi pada mahasiswa perguruan tinggi negeri di Surabaya)
Yang diajukan
Indra Wirawan 0812010189 / FE /EM
Dsetujui untuk ujian skripsi oleh :
Pembimbing Utama
Drs.Ec.Gendut Sukarno,Ms Tanggal : ………..
NIP. 195907011987031001
Mengetahui
Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Jawa Timur
Drs. Rahman Amrullah Suwaidi, Ms
ANALISIS INTELLECTUAL CAPITAL
STATEMENT PADA PERGURUAN TINGGI
NEGERI DI SURABAYA
(Studi pada mahasiswa perguruan tinggi negeri di Surabaya)
SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Manajemen
Oleh: Indra Wirawan 0812010189 / FE / EM
FAKULTAS EKONOMI
Kata Pengantar
Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan Rahmat serta HidayahNya , sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi
dengan judul “Analisis Intellectual capital Statement Pada Perguruan Tinggi Negeri Di
Surabaya”.
Menyadari bahwa sepenuhnya penelitian ini tidak akan terselesaikan tanpa dukungan dan
bantuan dari beberapa pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih
yang sebesar-besarnya kepada :
1. Bpk Prof.Dr.Ir. Teguh Soedarto, MP., selaku Rektor Universitas Pembangunan
Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bpk Dr. Dhani Ichsanuddin N, MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi UPN
“Veteran”Jatim
3. Bpk Dr.Muhadjir Anwar,MM selaku ketua program jurusan Manajemen Fakultas
Ekonomi UPN “Veteran” Jatim.
4. Bpk Drs.Ec. Gendut Sukarno,Ms selaku dosen pembimbing yang telah mengarahkan
dan meluangkan waktu guna membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen di Fakultas Ekonomi UPN “Veteran “ Jatim yang telah memberikan
ilmunya.
6. Bapak, ibu, dan keluarga serta teman-teman yang telah ikhlas memberikan doa dan
restunya kepada penulis.
7. Seluruh keluarga besar kosagrah setiawan yang selalu memberi dukungan dan
semangat kepada penulis.
Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempuna , oleh karena itu kritik
dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati demi kesempurnaan
skripsi ini.
Surabaya,20 maret 2012
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ... i
DAFTAR ISI ... ii
DAFTAR TABEL ... v
DAFTAR GAMBAR ... vi
DAFTAR LAMPIRAN ... vii
ABSTRAKSI ... viii
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah... 1
1.2 Perumusan Masalah ... 15
1.3 Tujuan Penelitian ... 16
1.4 Manfaat Penelitian ... 16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu ... 17
2.2 Landasan Teori... 20
2.2.1 Pengertian Manajemen Sumberdaya manusia ... 20
2.2.6 Intellectual Capital ... ... 28
2.2.7 Human Capital ... 31
2.2.7.1. Knowledge ... 34
2.2.7.2. Slill ... 35
2..2.7.3 Motivasi ... 37
2.2.8 Structural Capital ... 39
2.2.8.1. kebebasan akademik ... 40
2.2.8.2 Sistim Pengajaran... 44
2.3 Hubungan Antar Variabel ... 50
2.3.1. Human Capitala sebagai pembentuk ICS... 50
2.3.2. Structural Capital sebagai pembentuk ICS ... 51
2.3.3 Relational Capital sebagai pembentuk ICS... 52
2.4. Kerangka Konseptual ... 53
2.5. Hipotesis... 55
BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel ... 56
3.1.2. Pengukuran Variabel... 59
3.2 Populasi dan Sampel ... 60
3.5.8. Uji Multicolliniery dan Singularity ... 66
3.5.9. Pengujian Model denagan Two Step Approach ... 66
3.5.10. Evaluasi Model ... 67
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 4.1 Deskriptif Objek Penelitian ... 72
4.1.1 Profil Universitas Negeri Surabaya ... 72
4.1.2 Profil Universitas Airlangga ... 74
4.1.3 Profil IAIN Sunan Ampel... 76
4.2. Analisis Karakteristik Responden ... 79
4.2.2 Deskripsi Human Capital... 81
4.2.3 Deskripsi Structural Capital... 83
4.2.4 Deskripsi Relational Capital ... ... 84
4.3 Analisis Data ... 85
4.3.1 Evaluasi Outlier ... 85
4.3.2 Evaluasi Reliabilitas ... 87
4.3.3 Evaluasi Validitas ... 88
4.3.4 Evaluasi Construct Reliability Dan Variance Extracted ... 89
4.3.5 Evaluasi Normalitas ... 90
4.3.6 Analisis Model SEM ... 91
4.4 Pembahasan... 95
4.4.1 Evaluasi Human Capital, Structural Capital, Relational Capital terhadap Intellectual Capital Statement ... 95
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan ... 102
5.2 Saran ... 102
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1.1 Data Jumlah Staff Pengajar Berdasar Pendidikan ... 13
Tabel 1.2 Data Jumlah Penelitian Dosen ... 14
Tabel 1.3 Top Brand Index PT.sari Ayu Martha Tilaar Tahun 2011 ... 6
Tabel 3.1 Goodness of Fit Indices ... 68
Tabel 4.1 Karakteristik responden berdasarkan Perguruan Tinggi ... 80
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan jenis kelamin ... 80
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan usia ... 81
Tabel 4.4 Frekuensi Hasil Jawaban Responden Mengenai Human Capital ... 81
Tabel 4.5 Frekuensi Hasil Jawaban Responden Mengenai Structural Capital ... 83
Tabel 4.6 Frekuensi Hasil Jawaban Responden Mengenai Relational capital ... 84
Tabel 4.7 Outlier Data ... 86
Tabel 4.8 Reliabilitas Data ... 87
Tabel 4.9 Validitas Data ... 88
Tabel 4.10 Construct Reliability dan Variance Extracted ... 89
Tabel 4.11 Normalitas Data ... 90
Tabel 4.12 Evaluasi Kriteria Goodness Of Fit Indices Model One-Step Approach - Base Model ... 92
Tabel 4.13 Evaluasi Kriteria Goodness of Fit Indices Model One- Step Approach – Modifikasi ... 93
Tabel 4.14 Frekuensi dan faktor loading Human Capital ... 95
Tabel 4.15 Frekuensi dan faktor loading structural capital ... 96
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1. Structural modal ICS... 8
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 : Kuesioner
Lampiran 2 : Tabulasi Jawaban Responden
Lampiran 3 : Hasil Uji Outlier
Lampiran 4 : Hasil Uji Validitas, Reliabilitas dan Normalitas
ANALISIS INTELLECTUAL CAPITAL
STATEMENT PADA PERGURUAN TINGGI
NEGERI DI SURABAYA
(Studi pada mahasiswa perguruan tinggi negeri di Surabaya)
Oleh : Indra WirawanABSTRAKSI
Persaingan global tidak saja terjadi di dunia industri dan perdagangan, tapi juga berlaku bagi dunia pendidikan. Tantangan bagi Perguruan Tinggi di Indonesia adalah tingkat persaingan yang makin tinggi baik antar Perguruan Tinggi lokal maupun Perguruan Tinggi Asing. Para penyelenggara Pendidikan dan pemakai lulusan yang tidak hanya menuntut lulusan berpengetahuan tetapi juga berketrampilan berkompetensi. Sebuah perguruan tinggi tidak lepas dari pemberlakuan dan penyempurnaan parangkat-perangkat intern.
Perguruan tinggi adalah tempat yang diharapkan dapat mencetak kader-kader pemimpin bangsa di masa mendatang sehingga dianggap dapat mempengaruhi perkembangan dan kemajuan negara itu sendiri. Alumni perguruan tinggi yang baik diharapkan tanggap akan permasalahan yang terjadi di masyarakat atau lingkungannya dan diharapkan dapat berani tampil untuk memberi solusinya.
Surabaya memiliki Lebih dari 80 perguruan tinggi, Dari sekian banyak perguruan tinggi yang ada di Surabaya hanya terdapat empat perguruan tinggi yeng berstatus negeri, yaitu Universitas Airlangga, Universitas Negeri Surabaya, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dan Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel. Keempat perguruan Tinggi negeri tersebet mempunyai spesifikasi dan kelebihan tersendiri, seperti Universitas Negeri Surabaya, Perguruan Tinggi ini ini merupakan Perguruan Tinggi yang mengutamakan program kependidikan, meskipun ada program lain non kependidikan. IAIN Sunan Ampel mempunyai karakteristik yang di dalam program pendidikannya mengutamakan program Islamic Studies,dan kriteria-kriteria lain pada perguruan tinggi negeri disurabaya.
Tujuan dari dari analisis Intellectual Capital Statement (ICS) adalah untuk mengetahui kekayaan intellectual sebuah organisasi, dalam hal ini adalah universitas. Hal ini dilakukan agar universitas tetap dapat mempertahankan eksistensinya. Pada penelitian ini dilakukan analisis untuk mengetahui variabel kritis ICS Universitas, yaitu Human Capital¸Streuctural Capital dan Relational Capital dapat mengevaluasi Intellectual Capital Statement pada perguruan tinggi negeri yang ada di Surabaya.
Penentuan sampel dilakukan berdasarkan konsep nonprobability sampling yaitu dengan purposive sampling. Pada konsep ini penulis menentukan kriteria responden yaitu anggota Himpunan mahasiswa, BEM atau organisasi mahasiswa yang ada di dalam setiap perguruan tinggi negeri di Surabaya.
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Proses Globalisasi yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, menuntut
dihormatinya norma dan nilai yang secara universal diterima oleh masyarakat dunia.
Hanya dengan menerima dan menghormati nilai dan norma universal tersebut kita
akan menjadi masyarakat madani dan dapat diterima sebagai anggaran masyarakat
global.
Persaingan global tidak saja terjadi di dunia industri dan perdagangan, tapi
juga berlaku bagi dunia pendidikan. Tantangan bagi Perguruan Tinggi di Indonesia
adalah tingkat persaingan yang makin tinggi baik antar Perguruan Tinggi lokal
maupun Perguruan Tinggi Asing. Para penyelenggara Pendidikan dan pemakai
lulusan yang tidak hanya menuntut lulusan berpengetahuan tetapi juga berketrampilan
berkompetensi. Sebuah perguruan tinggi tidak lepas dari pemberlakuan dan
penyempurnaan parangkat-perangkat intern.
Sistem manajemen perguruan tinggi yang diperlukan juga harus
memperhatikan perkembangan globalisasi di atas, sehingga tuntutan akan standar
mutu proses yang bersifat internasional harus menjadi perhatian pimpinan perguruan
tinggi.
Kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan perguruan tinggi sudah
dirasakan perlu menggunakan prinsip-prinsip manajemen yang modern dan
pendidikan dan sekaligus sebagai antisipasi perkembangan lembaga. yang semakin
besar, antisipasi perkembangan globalisasi, dan menyiapkan diri ke gerbang
persaingan internasional. Dengan demikian keunggulan untuk mendapatkan sebuah
pengakuan internasional terhadap mutu proses sebuah perguruan tinggi menjadi
penting. Untuk menghadapi pembaharuan dan transforrnasi global, semua pihak yang
terkait dalam pendidikan harus berubah menuju "Learning organization" melalui
dukungan dua faktor mendasar yaitu (1) pimpinan pendidikan (Educational Leaders)
sebagai pemegang komando dan pengendali, perannya berubah dari macho menjadi
maestro dan dari autorruts menjadi coaches dan (2) kemampuan melaksanakan "Self
Adjusting Participa-tion" yang harus dikuasai oleh semua anggota organisasi. Masih
Banyak anggota sebuah organisasi perguruan tinggi yang belum menyadari fungí
keberadaan masing-masing.
Dosen merupakan aset utama suatu institusi pendidikan tinggi, oleh karena
itu pentingnya pemahaman modal intelektual: kompetensi, komitmen dan
pengendalian pekerjaan bagi para dosen sehingga terbentuk kesiner-gisan, yang pada
akhirnya dapat menciptakan kualitas lulusan yang mampu bersaing di pasar tenaga
kerja sesuai harapan user.
Menyadari akan kelemahan di bidang mutu pendidikan, pemerintah
melakukan berbagai upaya, antara lain menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 19
tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Ditetapkannya Peraturan
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban
bangsa yang bermartabat.
Untuk menjamin mutu tersebut, ditetapkan lingkup Standar Nasional
Pendidikan yang meliputi: (1) Standar isi yang dituangkan dalam kriteria tentang
kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kom-petensi mata pelajaran, dan
silabus pem-belajaran yang harus dipenuhi oleh pe-serta didik pada jenjang dan jenis
pendidi-kan tertentu. (2) standar proses terkait dengan pelaksanaan pembelajaran
pada suatu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Dalam
netapkan standar ini perlu diperhatikan iklim kelas, kondisi peserta didik dan
me-todologi yang tepat. (3) Standar kompe-tensi lulusan yang berkualitas serta mampu
menghadapi tuntutan perubahan dan tantangan masa depan. Kompetensi lulusan ini
disesuaikan dengan tujuan pendidikan nasional (4) Standar pendidik dan tenaga
kependidikan, terkait dengan kriteria pendidikan prajabatan dan kelaya-kan fisik
maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Dalam standar ini diper-hatikan pula
kualitas dan kualifikasi tenaga. (5) Standar sarana dan prasarana yang terkait dengan
kriteria minimal ten-tang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah,
perpustakaan, labora-torium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan
berekreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses
pembelajaran, terma-suk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. (6)
Standar pengelolaan, ter-kait dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabu-paten/kota, provinsi, atau
Standar pem-biayaan pendidikan yang mengatur kom-ponen dan besarnya biaya
opersi satuan pendidikan yang berlaku selama satu ta-hun. (8) Standar penilaian
pendidikan yang terkait dengan standar mekanisme, prosedur dan instrument
penilaian hasil belajar peserta didik.
Perguruan tinggi adalah tempat yang diharapkan dapat mencetak kader-kader
pemimpin bangsa di masa mendatang sehingga dianggap dapat mempengaruhi
perkembangan dan kemajuan negara itu sendiri. Alumni perguruan tinggi yang baik
diharapkan tanggap akan permasalahan yang terjadi di masyarakat atau
lingkungannya dan diharapkan dapat berani tampil untuk memberi solusinya.
Adanya suatu perguruan tinggi yang baik di suatu tempat (negara / daerah)
bahkan kadang-kadang dapat dijadikan indikasi bahwa masyarakat di daerah tersebut
juga baik adanya. Lihat saja kota-kota di Indonesia yang mempunyai perguruan tinggi
yang terkenal maka masyarakat disekitarnya juga relatif akan dipengaruhi. Lihat saja
kota-kota berikut Depok (Universitas Indonesia), Bandung (Institut Teknologi
Bandung atau Unpad), Yogyakarta (Universitas Gadjahmada), Surabaya (ITS, Unair)
dan lain sebagainya.
Tetapi berbicara tentang perguruan tinggi, maka keberadaannya tidak bisa
dilepaskan dari keberadaan dan peran dosen-dosen di dalamnya. Karena
bagaimanapun juga kepada merekalah maka kinerja perguruan tinggi dapat
Berbeda dengan sekolah dasar dan menengah yang lebih banyak difokuskan
kepada proses belajar dan mengajar, dan mempersiapkan murid untuk bisa naik ke
jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Maka di perguruan tinggi karena dianggap
sebagai jenjang tertinggi suatu proses pendidikan, maka selain diutamakan pada
proses belajar – mengajar dan menyemaikan ilmu, tetapi juga kepada pencarian dan
pengembangan ilmu sendiri, yang mana dengan bekal ilmu dan pengetahuan tersebut
diharapkan dapat dijadikan alat untuk mendapatkan solusi permasalahan bagi
masyarakat.
Dalam proses pencarian dan pengembangan ilmu sendiri, maka dosen juga
dituntut untuk melakukan penelitian dan mempublikasikan hasil penelitiannya,
kecuali itu juga mampu berinteraksi dengan masyarakat dengan kompetensi yang
dimilikinya. Itulah esensi tri dharma perguruan tinggi.
Pemahaman seperti yang diuraikan di atas, saat ini juga telah disepakati oleh
pemerintah, yaitu memandang penting profesi dosen sehingga bahkan diberikan suatu
pengakuan khusus dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomer 37 Tahun
2009 tentang Dosen. Lihat pasal 1 ayat 1:Dosen adalah pendidik profesional dan
ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan
menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan,
Sebagaimana profesi lain yang diakui keberadaannya, misalnya profesi
dokter, maka agar dapat disebut pendidik profesional maka diperlukan proses
sertifikasi. Ini bahkan telah menjadi persyaratan utama yang diminta pemerintah
sebagaimana tercantum pada pasal 2. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik,
kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi
lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki
kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Jadi di jaman sekarang
ini, memiliki gelar akademik saja tidak mencukupi agar dapat disebut dosen
profesional.
Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Selain
itu Surabaya juga merupakan kota yang dipenuhi oleh mahasiswa, yang artinya di
Kota Surabaya ini memiliki banyak sekali perguruan Tinggi. Perguruan tinggi
tersebut ada yang berstatus negeri dan ada pula yang berstatus Swasta. Ada beberapa
perguruan Tinggi baik swasta maupun negeri di Surabaya yang menempati peringkat
10 besar Perguruan Tinggi terbaik di Indonesia,seperti Universitas Airlangga, UK
Petra, dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
Ketiga perguruan Tinggi tersebut merupuakan Perguruan Tinggi unggulan,
tidak hanya di tingkat nasional tapi juga ditingkat Internasional. Meskipun demikian,
bukan berarti perguruan tinggi lain yang ada di Surabaya tidak baik, banyak
Perguruan Tinggi yang ada di Surabaya yang memiliki kualiatas yang tidak kalah
Seperti contoh Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,
Perguruan Tinggi yang satu ini tidak kalah dengan Perguruan Tinggi lain yang
menjadi Perguruan Tinggi unggulan karena UPN “Veteran “ Jawa timur mempunyai
banyak fasilitas yang sangat memadai dan baru-baru ini mendapat penghargaan
sebagai 5 besar Perguruan Tinggi Swasta terbaik Jawa Timur.
Surabaya memiliki Lebih dari 80 perguruan tinggi, Dari sekian banyak
perguruan tinggi yang ada di Surabaya hanya terdapat empat perguruan tinggi yeng
berstatus negeri, yaitu Universitas Airlangga, Universitas Negeri Surabaya, Institut
Teknologi Sepuluh Nopember, dan Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel.
Keempat perguruan Tinggi negeri tersebet mempunyai spesifikasi dan kelebihan
tersendiri, seperti Universitas Negeri Surabaya, Perguruan Tinggi ini ini merupakan
Perguruan Tinggi yang mengutamakan program kependidikan, meskipun ada
program lain non kependidikan. IAIN Sunan Ampel mempunyai karakteristik yang di
dalam program pendidikannya mengutamakan program Islamic Studies,dan
kriteria-kriteria lain pada perguruan tinggi negeri disurabaya.
Dari beberapa perguruan tinggi yang ada di Surabaya, empat perguruan tinggi
negeri itu yang akan menjadi obyek penelitian dengan mengangkat tema “Analisis
Intellectual Capital Statement Terhadap perguruan Tinggi Negeri di Surabaya”.
Pada InCas (2008), diketahui bahwa ICS merupakan strategi manajemen yang
digunakan untuk menilai dan mengembangkan Intelectual capital (IC) yang ada
dari rangkaian bisnis prosesyang ada di universitas guna mencapai tujuan dari
universitas.
Gambar 1 Structural modal ICS
Sumber : InCas (2008) Intellectual Capital Statement made in Europe.
Pada gambar 1 terlihat bahwa Bisnis Proses (BP) merupakan rantai kegiatan
dalam organisasi . BP menggambarkan interaksi dari Human Capital, Structural
capital, Relational Capital. Sedangkan Business Succes (BS) merupakan hasil atau
ICS terdiri dari 3 elemen utama yaitu Human Capital (HC) , Structural Capital
(SC), Relational Capital (RC) (dalam Tjiptohadi,2003).
Human Capital merupakan kemampuan seseorang (dalam hal ini adalah
dosen) yang memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta mampu
menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki dalam pekerjaan.
Structural Capital merupakan kemampuan universitas dalam memenuhi
proses yang ada di dalamnya dan struktur yang mendukung dalam
menghasilkan kinerja Intellectual yang optimal.
Relational capital merupakan asset intangible yang membangun dan mengatur
hubungan baik dengan customer,karyawan, pemerintah, stakeholder, dan
competitor lainnya serta dengan mitra kerja yang dapat muncul dari bagian di
luar universitas untuk mendukung universitas.
Intellectual Capital merupakan aset maya suatu organisasi yang dapat digunakan
untuk menciptakan nilai bagi organisasi melalui kombinasi antara human capital,
structural capital, dan relational capital. Konsep Intellectual capital dari Ulrich,
Tjakraatmadja, dan Stewart hanya berfokus pada dimensi human capital dan belum
memasukkan dimensi structural capital. Kompetensi dan komitmen pada konsep
intellectual capital dari Ulriach dan Burr & Girardi masuk dalam human capital
karena kompetensi dan komitmen itu ada dan melekat pada dosen itu sendiri.
Menurut konsep intellectual capital dari Burr and Girardi (2002: 77) karena
organisasi apabila didukung dengan pemberian pengendalian pekerjaan atau otonomi
kerja yang memadai kepada pegawai.
Tujuan dari dari analisis Intellectual Capital Statement (ICS) adalah untuk
mengetahui kekayaan intellectual sebuah organisasi, dalam hal ini adalah universitas.
Hal ini dilakukan agar universitas tetap dapat mempertahankan eksistensinya. Pada
penelitian ini dilakukan analisis untuk mengetahui variabel kritis ICS Universitas,
yaitu Human Capital¸Streuctural Capital dan Relational Capital dapat mengevaluasi
Intellectual Capital Statement pada perguruan tinggi negeri yang ada di Surabaya.
Namun pada penelitian ini ada beberapa batasan penelitian yang digunakan yaitu
penelitian hanya dilakukan pada ruang lingkup perguruan tinggi negeri yang ada di
Surabaya, dan pengukurannya hanya berdasarkan indikator dari ICS universitas.
Perguruan tinggi adalah tempat yang diharapkan dapat mencetak kader-kader
pemimpin bangsa di masa mendatang sehingga dianggap dapat mempengaruhi
perkembangan dan kemajuan negara itu sendiri. Alumni perguruan tinggi yang baik
diharapkan tanggap akan permasalahan yang terjadi di masyarakat atau
lingkungannya dan diharapkan dapat berani tampil untuk memberi solusinya.
Tetapi berbicara tentang perguruan tinggi, maka keberadaannya tidak bisa
dilepaskan dari keberadaan dan peran dosen-dosen di dalamnya. Karena
bagaimanapun juga kepada merekalah maka kinerja perguruan tinggi dapat
seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta mampu menerapkan
pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki dalam pekerjaan
Berbeda dengan sekolah dasar dan menengah yang lebih banyak difokuskan
kepada proses belajar dan mengajar, dan mempersiapkan murid untuk bisa naik ke
jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Maka di perguruan tinggi karena dianggap
sebagai jenjang tertinggi suatu proses pendidikan, maka selain diutamakan pada
proses belajar – mengajar dan menyemaikan ilmu, tetapi juga kepada pencarian dan
pengembangan ilmu sendiri, yang mana dengan bekal ilmu dan pengetahuan tersebut
diharapkan dapat dijadikan alat untuk mendapatkan solusi permasalahan bagi
masyarakat.
Structural Capital merupakan kemampuan universitas dalam memenuhi proses
yang ada di dalamnya dan struktur yang mendukung dalam menghasilkan kinerja
Intellectual yang optimal. Struktural capital dipengaruhi oleh budaya akademik,
system pengajaran, dan penelitian (Andrew kok,2007), dan penelitian (Marr, Schiuma
dan Neely , 2004 ).
Sudah menjadi sesuatu yang sifatnya taken for granted bahwa struktur manajemen
lembaga pendidikan, khususnya perguruan tinggi (baik negeri maupun swasta) ditata
dengan pola seorang rektor, ketua, atau direktur, dibantu (pada lapis berikutnya) oleh
(umumnya) tiga orang dengan sebutan pembantu rektor, direktur atau ketua, yang
administrasi umum, serta kemahasiswaan.Entah kebetulan atau tidak, hampir tidak
pemah terdengar evaluasi kritis tentang pola manajemen seperti ini. Sebaliknya
desain ini justru dikembangkan terus ke bawah. Baik dalam konteks sebuah fakultas
(Dekan, Pembantu Dekan I,II, dan III), bahkan konon di tingkat pendidikan yang
lebih rendah, seperti Sekolah Menengah umum (SMU).
Selama ini dikenal apa yang disebut dengan Tri Dharma Pergaruan Tinggi, yang
meliputi pendidikan atau pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Tri
Dharma ini lazim dipahami sebagai fungsi utama Perguruan Tinggi. Atas dasar ini,
mestinya secara organisatoris, manajemen Perguruan Tinggi dipola atas dasar dharma
tersebut. Sehingga kalau seseorang diangkat sebagai rektor, yang bersangkutan patut
dibantu oleh beberapa orang yang basis orientasi fungsinya pencapaian ketiga dharma
itu. Kongkritnya, para pembantu rektor, direktur atau ketua, seharusnya berfungsi
untuk pendidikan dan pengajaran(bidang 1), penelitian(bidang 2), dan pengabdian
pada masyarakat (bidang 3).
Relational capital merupakan asset intangible yang membangun dan mengatur
hubungan baik dengan customer, karyawan, pemerintah, stakeholder, dan competitor
lainnya serta dengan mitra kerja yang dapat muncul dari bagian di luar universitas
untuk mendukung universitas. Relational Capital dipengaruhi oleh beberapa faktor
Relational capital sangat erat hubungannya dengan kompetensi sosial, dimana
dijelaskan bahwa kompetensi sosial adalah karakter sikap dan perilaku atau kemauan
dan kemampuan untuk membangun simpul-simpul kerja sama dengan orang lain
yang relatif bersifat stabil ketika menghadapi permasalahan di tempat kerja yang
terbentuk melalui sinergi antara watak, konsep diri, motivasi internal serta kapasitas
pengeta-huan sosial (Spencer & Spencer, 2003).
Pada pembahasan ini mencoba menganalisis Intellectual capital Statement
pada Perguruan Tinggi Negeri di Surabaya diukur dengan berbagai indikator yang
ada. Berikut ini merupakan data jumlah Staff Pengajar dan data jumlah penelitian
dosen di setiap Perguruan Tinggi Negeri di Surabaya yang merupakan cerminan dari
tinggi rendah Intellectual Capital Statement (ICS).
Tabel 1. Data jumlah staff pengajar berdasar pendidikan
Perguruan
Tinggi
S1 S2 S3 PROF
UNAIR 347 885 410 26
IAIN 42 303 61 24
ITS 417 434 133 28
UNESA 116 619 142 48
Tabel 2. Data jumlah penelitian dosen
Perguruan Tinggi 2007 2008 2009
UNAIR 65 122 128
IAIN 81 156 197
ITS 87 147 189
UNESA 71 110 359
Sumber : data perguruan tinggi negeri di Surabaya 2011
Dari data diatas dapat dijelaskan, pada tabel 1 jumlah staff pengajar yang
merupakan bagian dari human capital, didominasi oleh pengajar atau dosen yang
berpendidikan S2. Dari keempat perguruan tinggi negeri yang ada di Surabaya
hampir 50 % staff pengajar masih berpendidikan S2,sedangkan jumlah staff pengajar
yang berpendidikan S3 atau doktor dan juga guru besar atau profesor jauh berada
dibawahnya. Hal lain yang dapat kita lihat,bahwa disini kita masih menemui beberapa
staff pengajar yang masih berpendidikan S1 atau sarjana, padahal menurut aturan dari
Dikti seorang staff pengajar minimal harus berpendidikan S2.
Pada tabel yang 2 adalah gambaran bagian dari structural capital, kita bisa
lihat jumlah penelitian yang dilakukan oleh dosen dari setiap Perguruan Tinggi yang
ada di Surabaya. Data disini mulai tahun 2007-2009,dari data diatas dapat kita lihat
setiap tahun jumlah penelitian yang dilakukan oleh dosen mengalami peningkatan,
peningkatannya, karena hampir semua perguruan tinggi pada tahun 2008-2009
peningkatan jumlah penelitiannya menurun dari pada tahun 2007-2008.
Dari sedikit penjelasan tentang dimensi-dimensi yang berhubungan dengan
Intellectual Capital Statement yakni Human Capital, Structural Capital, dan
Relational Capital dapat diharapkan bila Human Capital, Structural Capital, dan
Relational Capital dapat mengevaluasi Intellectual Capital Statement pada
perguruan tinggi negeri yang ada di Surabaya.
Bertolak dari pemikiran bahwa Intellectual Capital Statement mutlak harus
diupayakan agar tetap tinggi maka diperlukan upaya-upaya untuk membangkitkan
potensi dari Human Capital serta membangun Structural Capital dan juga Relational
Capital. Keadaan di ataslah yang melatarbelakangi penulis untuk mengadakan
penelitian. Judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah “ANALISIS
INTELLECTUAL CAPITAL STATEMENT PADA PERGURUAN TINGGI
NEGERI DI SURABAYA.
1.2 Rumusan Masalah :
Berdasarkan uraian dan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka masalah
penelitian ini selanjutnya dapat dirumuskan sebagai berikut:
Apakah Human Capital (HC), Structural Capital (SC), dan Relational Capital
(RC) dapat mengevaluasi Intellectual Capital Statement (ICS) pada Perguruan Tinggi
1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Intellectual Capital Statement
pada Perguruan Tinggi negeri yang ada di Surabaya dari aspek Human Capital (HC),
Structural Capital (SC), dan Relational Capital (RC).
1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian ini bermanfaat baik secara empiris, praktis (policy), maupun
teoritis. Secara empiris, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literature
manajemen mengenai pengembangan teori yang berkaitan dengan peranan Human
Capital, Structural Capital, dan relational Capital dalam mengevaluasi Intellectual
Capital Statement. Secara praktis (policy), penelitian ini menyediakan informasi bagi
penelitian selanjutnya yaitu mengenai informasi apakah Human Capital, Structural
Capital, dan relational Capitaldapat mengevaluasi Intellectual Capital Statement
dalam ruang lingkup perguruan tinggi. Secara teoritis, penelitian ini menjelaskan
peran Intellectual Capital Statement dalam sebuah organisasi yaitu Universitas
Negeri yang ada di Surabaya. Hal ini dilakukan agar universitas dapat
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Penelitian Terdahulu
Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa
hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca
diantaranya :
1. Penelitian yang dilakukan oleh Umi Narimawati tahun 2006 dengan judul
Peranan Modal Intelektual Dosen Dalam Menciptakan Kualitas Lulusan
Menurutnya adalah Kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan
perguruan tinggi sudah dirasakan perlu menggunakan prinsip-prinsip manajemen
yang modern dan berorientasi pada mutu untuk memperbaiki dan menyempurnakan
kegiatan pendidikan dan sekaligus sebagai antisipasi perkembangan lembaga. yang
semakin besar, antisipasi perkembangan globalisasi, dan menyiapkan diri ke gerbang
persaingan internasional. Dengan demikian keunggulan untuk mendapatkan sebuah
pengakuan internasional terhadap mutu proses sebuah pergu-ruan tinggi menjadi
penting. Untuk menghadapi pembaharuan dan transforrnasi global, semua pihak yang
terkait dalam pendidikan harus berubah menuju "Learning organization" melalui
dukungan dua faktor mendasar yaitu (1) pimpinan pendidikan (Educational Leaders)
sebagai pemegang komando dan pengendali, perannya berubah dari macho menjadi
maestro dan dari autorruts menjadi coaches dan (2) kemampuan melaksanakan "Self
Masih Banyak anggota sebuah organisasi perguruan tinggi yang belum
menyadari fungí keberadaan masing-masing. Dosen merupakan aset utama suatu
institusi pendidikan tinggi, oleh karena itu pentingnya pemahaman modal intelektual:
kompetensi, komitmen dan pengendalian pekerjaan bagi para dosen sehingga
terbentuk kesiner-gisan, yang pada akhirnya dapat menciptakan kualitas lulusan yang
mampu bersaing di pasar tenaga kerja, sesuai harapan user.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Engkos Achmad Kuncoro tahun 2007 dengan
judul Analisis Pengaruh Lingkungan Terhadap Modal Intelektual Organisasi.
Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis seberapa
jauh pengaruh lingkungan (eksternal dan iklim organisasi) sebagai variabel
independen pada proses transformasi, kompetensi intelektual individu menjadi modal
intektual organisasi sebagai variabel dependen. Metode penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode survey dengan pendekatan kuantitatif . Penelitian
ini bertujuan untuk mengidentifikasikan dimensi lingkungan eksternal organisasi
Perguruan Tinggi swasta, khususnya uninersitas Bina Nusantara; Untuk mengetahui
seberapa signifikan pengaruh kompetensi intelektual individu dosen terhadap modal
intelektual organisasi; untuk menguji secara empirik seberapa signifikan pengaruh
lingkungan eksternal persaingan terhadap kompetensi intelektual individu menjadi
modal intelektual organisasi; untuk mengetahui adakah perbedaan pengaruh jabatan
akademik dosen,tingkat pendidikan dosen,dan pengalaman kerja dosen terhadap
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel eksogen Lingkungan
Eksternal (LE) memiliki pengaruh sebesar 56,5 % terhadap variabel intervening
Kompetensi Intelektual (KII), variabel eksogen Iklim Organisasi (IKO) sebesar
66,1% terhadap variabel intervening (KII), dan variabel intervening (KII) memiliki
pengaruh sebesar 60,9 % terhadap variabel endogen Modal intelektual Idividu.dari
hasil penelitian didapat simpulan yang dapat dijadikan referensi dari penelitian ini
sebagai berikut. Pertama model yang diajukan tidak FIT namun kemudian dikoreksi
menuju model yang paling FIT (>0,8).Kedua terdapat 2 modifikasi untuk
memperoleh model yang paling fit . Ketiga hipotesis diterima namun terdapat
hubungan kualitas (pengaruh dan positip), signifikan reliabel antara lingkungan
eksternal dan iklim organisasi terhadap intelektual individu dan modal intelektual
organisasi. Keempat terbentuknya beberapa hubungan korelasi positip[ terhadap
beberapa indikator sebagai nilai yang tersembunyi untuk menjaelaskan tercapainya
modem yang FIT.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Henny kusuma dewi, Fitria Meicelin Soplanot
tahun 2009 dengan judul Analisis Intellectual Capital Statement Dari Perguruan
Tinggi.
Tujuan dari Analisis Intellectual Capital Statement (ICS) adalah untuk
mengetahui kekayaan intelektual sebuah organisasi dalam hal ini yaitu universitas.
Hal ini dilakukan agar universitas dapat tetap mempertahankan eksistensinya. Pada
penelitian ini dilakukan analisis untuk mengetahui variabel kritis ICS universitas
Human Capital terdiri dari kompetensi, skill dan motivasi. Structural capital
terdiri dari kebebasan akademik, sistem pengajaran, dan research. Relational Capital
terdiri dari Relasi dengan konsumen, relasi dengan rekan kerja, dan relasi dengan
media.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah berdasarkan analisis SEM terhadap data
sampel yang ada maka dapat diketahui bahwa hasil penelitian menunjukkan tidak
semua indikator yang ada memberi pengaruh signifikan terhadap variabel ICS
universitas pada batas λ = 0,5 variabel yang paling kritis adalah kemampuan dosen
dalam bekerja sama dengan dosen di jurusan berbeda sedangkan pada batas λ = 0,4
variabel yang paling kritis adalah jumlah pelatihan yang diikuti dosen.
2.2 Landasan Teori
2.2.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia
Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari ilmu manajemen,
yang berarti merupakan suatu usaha untuk mengarahkan dan mengelola sumber daya
manusia di dalam suatu organisasi agar mampu berfikir dan bertindak sebagaimana
yang diharapkan organisasi. Organisasi yang maju tentu dihasilkan oleh
personil/pegawai yang dapat mengelola organisasi tersebut ke arah kemajuan yang
diinginkan organisasi, sebaliknya tidak sedikit organisasi yang hancur dan gagal
Menurut Hasibuan (2001 :10) manajemen sumber daya manusia adalah “ Ilmu
dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien,
membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat “. Sedangkan
menurut Simamora (2004 : 4) manajemen sumber daya manusia adalah ,”
pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan
individu anggota organisasi atau kelompok karyawan, juga menyangkut desain dan
implementasi sistem perencanaan, penyusunan karyawan, pengembangan karyawan,
pengelolaan karir, evaluasi kinerja, kompensasi karyawan dan hubungan
ketenagakerjaan yang baik.
Menurut Henry Simamora (1997 : 3), Manajemen Sumber Daya Manusia
adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan
pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok pekerja. Manajemen sumber
daya manusia juga mencakup desain dan implementasi system perencanaan,
penyusunan karyawan, pengembangan karyawan, pengelolaan karier, evaluasi
kinerja, kompensasi karyawan dan hubungan perburuhan yang mulus.
2.2.2 Teori Motivasi dalam Manajemen Sumber Daya Manusia
Salah satu aspek memanfaatkan pegawai ialah pemberian motivasi (daya
perangsang) kepada pegawai, dengan istilah populer sekarang pemberian kegairahan
bekerja kepada pegawai. Telah dibatasi bahwa memanfaatkan pegawai yang memberi
kemungkinan bermanfaat ke dalam perusahaan, diusahakan oleh pimimpin agar
kemungkinan itu menjadi kenyataan. Usaha untuk merealisasi kemungkinan tersebut
ialah dengan jalan memberikan motivasi. Motivasi ini dimaksudkan untuk
memberikan daya perangsang kepada pegawai yang bersangkutan agar pegawai
tersebut bekerja dengan segala daya dan upayanya (Manulang , 2002).
Menurut The Liang Gie Cs. (Matutina dkk ,1993) bahwa pekerjaan yang
dialakukan oleh seseorang manajer dalam memberikan inspirasi, semangat, dan
dorongan kepada orang lain (pegawai) untuk mengambil tindakan-tindakan.
Pemberian dorongan ini dimaksudkan untuk mengingatkan orang-orang atau pegawai
agar mereka bersemangat dan dapat mencapai hasil sebagaimana dikehendaki dari
orang tersebut. Oleh karena itu seorang manajer dituntut pengenalan atau pemahaman
akan sifat dan karateristik pegawainya, suatu kebutuhan yang dilandasi oleh motiv
dengan penguasaan manajer terhadap perilaku dan tindakan yang dibatasi oleh motiv,
maka manajer dapat mempengaruhi bawahannya untuk bertindak sesuai dengan
keinginan organisasi.
Menurut Martoyo (2000) motivasi pada dasarnya adalah proses untuk
mencoba mempengaruhi seseorang agar melakukan yang kita inginkan. Dengan kata
lain adalah dorongan dari luar terhadap seseorang agar mau melaksanakan sesuatu.
Dengan dorongan (driving force) disini dimaksudkan desakan yang alami untuk
hidup. Kunci yang terpenting untuk itu tak lain adalah pengertian yang mendalam
tentang manusia.
Motivasi berasal dari motive atau dengan prakata bahasa latinnya, yaitu
movere, yang berarti “mengerahkan”. Seperti yang dikatakan Liang Gie dalam
bukunya Martoyo (2000) motive atau dorongan adalah suatu dorongan yang menjadi
pangkal seseorang melakukan sesuatu atau bekerja. Seseorang yang sangat
termotivasi, yaitu orang yang melaksanakan upaya substansial, guna menunjang
tujuan-tujuan produksi kesatuan kerjanya, dan organisasi dimana ia bekerja.
Seseorang yang tidak termotivasi, hanya memberikan upaya minimum dalam hal
bekerja.
Konsep motivasi, merupakan sebuah konsep penting studi tentang kinerja
individual. Dengan demikian motivasi atau motivation berarti pemberian motiv,
penimbulan motiv atau hal yang menimbulkan dorongan atau keadaan yang
menimbulkan dorongan. Dapat juga dikatakan bahwa motivation adalah faktor yang
mendorong orang untuk bertindak dengan cara tertentu (Martoyo , 2000).
Manusia dalam aktivitas kebiasaannya memiliki semangat untuk mengerjakan
sesuatu asalkan dapat menghasilkan sesuatu yang dianggap oleh dirinya memiliki
suatu nilai yang sangat berharga, yang tujuannya jelas pasti untuk melangsungkan
Menurut Martoyo (2000) motivasi kinerja adalah sesuatu yang menimbulkan
dorongan atau semangat kerja. Menurut Gitosudarmo dan Mulyono (1999) motivasi
adalah suatu faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan atau
kegiatan tertentu, oleh karena itu motivasi sering kali diartikan pula sebagai faktor
pendorong perilaku seseorang. Setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang manusia
pasti memiliki sesuatu faktor yang mendorong perbuatan tersebut. Motivasi atau
dorongan untuk bekerja ini sangat penting bagi tinggi rendahnya produktivitas
perusahaan. Tanpa adanya motivasi dari para karyawan atau pekerja untuk bekerja
sama bagi kepentingan perusahaan maka tujuan yang telah ditetapkan tidak akan
tercapai. Sebaliknya apabila terdapat motivasi yang besar dari para karyawan maka
hal tersebut merupakan suatu jaminan atas keberhasilan perusahaan dalam mencapai
tujuannya.
2.2.3 Knowledge Based View (KBV)
Pandangan berbasis pengetahuan perusahaan/Knowledge Based View (KBV)
adalah ekstensi baru dari pandangan berbasis sumber daya perusahaan /Resource-Based View (RBV) dari perusahaan dan memberikan teoritis yang kuat dalam
mendukung modal intelektual. KBV berasal dari RBV dan menunjukkan bahwa
pengetahuan dalam berbagai bentuknya adalah kepentingan sumber daya (Grant,
Asumsi dasar teori berbasis pengetahuan perusahaan atau organisasi berasal dari
pandangan berbasis sumber daya perusahaan. Namun, pandangan berbasis sumber
daya perusahaan tidak memberikan pengakuan akan pengetahuan yang memadai.
Teori berbasis pengetahuan perusahaan atau organisasi menguraikan karakteristik
khas sebagai berikut:
Pengetahuan memegang makna yang paling strategis di organisasi.
Kegiatan dan proses produksi di perusahaan atau organisasi melibatkan
penerapan pengetahuan.
Individu-individu dalam organisasi tersebut yang bertanggung jawab
untukmembuat, memegang, dan berbagi pengetahuan
Pendekatan KBV membentuk dasar untuk membangun keterlibatan modal
manusia dalam kegiatan rutin perusahaan. Hal ini dicapai melalui peningkatan
keterlibatan karyawan dalam perumusan tujuan operasional dan jangka panjang
perusahaan atau organisasi. Dalam pandangan berbasis pengetahuan, perusahaan atau
organisasi mengembangkan pengetahuan baru yang penting untuk keuntungan
kompetitif dari kombinasi unik yang ada pada pengetahuan (Fleming 2001, Nelson
dan Winter 1982). Dalam era persaingan yang ada saat ini, perusahaan atau organisasi
sering bersaing dengan mengembangkan pengetahuan baru yang lebih cepat daripada
2.2.4 Knowledge-Based Theory
Mengidentifikasi dalam pengetahuan yang ditandai oleh kelangkaan dan sulit
untuk mentransfer dan mereplikasi, merupakan sebuah sumber daya penting untuk
mencapai keunggulan kompetitif (Nonaka I.,1995; I. Nonaka dan Takeuchi H., 1995).
Kapasitas dan keefektifan perusahaan dalam menghasilkan, berbagi dan
menyampaikan pengetahuan dan informasi menentukan nilai yang dihasilkan
perusahaan sebagai dasar keunggulan kompetitif perusahaan berkelanjutan dalam
jangka panjang. (Nonaka dan Takeuchi, 1995; Edvinsson dan Malone, 1997; Bontis,
2002; Choo dan Bontis, 2002).
2.2.5 Resources Based Theory / Resources Based View (RBV)
Belakangan ini muncul aliran baru dalam analisis keunggulan bersaing yang
dikenal dengan pendekatan berbasis sumber daya (resource-based view of the
firm/RBV). Ini dicirikan oleh keunggulan pengetahuan (knowledge/learningeconomy)
atau perekonomian yang mengandalkan aset-aset tak berwujud (intangible assets).
Resources Based Theory dipelopori oleh Penrose (1959) yang mengemukakan bahwa
sumber daya organisasi / perusahaan adalah heterogen, tidak homogen, jasa produktif
yang tersedia berasal dari sumber daya organisasi yang memberikan karakter unik
bagi tiap-tiap organisasi/ perusahaan. Teori RBV memandang organisasi sebagai
kumpulan sumber daya dan kemampuan (Penrose 1959; Wernerfelt, 1984).
Perbedaan sumber daya dan kemampuan organisasi dengan perusahaan atau
keuntungan kompetitif (Peteraf, 1993). Asumsi RBV yaitu bagaimana organisasi
dapat bersaing dengan organisasi lain untuk mendapatkan keunggulan kompetitif
dengan mengelola sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan kemampuan
organisasi. Sumber daya perusahaan atau organisasi dapat dibagi menjadi tiga macam
yaitu berwujud, tidak berwujud dan sumber daya manusia (Grant, 2002).
Kemampuan menunjukkan apa yang dapat dilakukan organisasi dengan sumber
dayanya (Amit dan Schoemaker, 1993).
Pendekatan RBV menyatakan bahwa organisasi dapat mencapai keunggulan
bersaing yang berkesinambungan dan memperoleh keuntungan superior dengan
memiliki atau mengendalikan aset-aset strategis baik yang berwujud maupun yang
tidak berwujud. Empat kriteria sumber daya sebuah organisasi mencapai keunggulan
kompetitif yang berkelanjutan, yaitu: (a) sumber daya harus menambah nilai positif
bagi organisasi, (b) sumber daya harus bersifat unik atau langka diantara calon
pesaing dan pesaing yang ada sekarang ini, (c) sumber daya harus sukar ditiru, dan
(d) sumber daya tidak dapat digantikan dengan sumber lainnya oleh perusahaan atau
organisasi pesaing (Barney 1991, 2001, 2007; Lewin and Phelan 1999; Wright,
McMahan, dan McWilliams 1992). Barney (1991) menyatakan bahwa dalam RBV,
organisasi tidak dapat berharap untuk membeli atau mengambil keunggulan
kompetitif berkelanjutan yang dimiliki oleh suatu organisasi lain, karena keunggulan
2.2.6 Pengertian Intellectual Capital
Ada banyak definisi berbeda mengenai Intellectual Capital. Intellectual Capital
adalah informasi dan pengetahuan yang diaplikasikan dalam pekerjaan untuk
menciptakan nilai (Williams, 2001 dalam Purnomosidhi, 2006). Intellectual Capital
dapat dipandang sebagai pengetahuan, dalam pembentukan, kekayaan intelektual dan
pengalaman yang dapat digunakan untuk menciptakan kekayaan (Stewart, 1997).
Intellectual Capital mencakup semua pengetahuan karyawan, organisasi dan
kemampuan mereka untuk menciptakan nilai tambah dan menyebabkan keunggulan
kompetitif berkelanjutan. Intellectual Capital telah diidentifikasi sebagai seperangkat
tak berwujud (sumber daya, kemampuan dan kompetensi) yang menggerakkan
kinerja organisasi dan penciptaan nilai (Bontis, 1998).
Pengertian lain Intellectual Capital atau modal intelektual adalah perangkat yang
diperlukan untuk menemukaan peluang dan mengelola ancaman dalam kehidupan.
Banyak pakar yang mengatakan bahwa modal intelektual sangat besar peranannya di
dalam menambah nilai suatu kegiatan. Berbagai perusahaan yang unggul dan meraih
banyak keuntungan adalah perusahaan yang terus menerus mengembangkan
sumberdaya manusianya (Ross, dkk, 1997). Manusia harus memiliki sifat proaktif
dan inovatif untuk mengelola perubahan lingkungan kehidupan (ekonomi, sosial,
politik, teknologi, hukum dll) yang sangat tinggi kecepatannya.
Mereka yang tidak beradaptasi pada perubahan yang super cepat ini akan dilanda
dengan tepat. Kini sungai yang dilayari adalah sebuah arung jeram yang
ketidakpastian jalannya perahu semakin tidak bisa diprediksi karena begitu
banyaknya rintangan yang tidak terduga. Dalam kondisi yang ditandai oleh perubahan
yang super cepat manusia harus terus memperluas dan mempertajam
pengetahuannya. dan mengembangkaan kretifitasnya untuk berinovasi.
Pada awal tahun 1920 psikolog banyak membicarakan konsep IQ (intelligence
Quotient) dengan asumsi bahwa mereka yang memiliki IQ yang tinggi akan memiliki
kemampuan untuk memecahkan permasalahan kehidupan. Orang yang memiliki IQ
yang tingi diduga akan cepat menguasai pengetahuan karena kecepatan daya pikir
yang dimilikinya. Namun selain memiliki angka kecerdasan yang tinggi, seseorang
baru akan memiliki pengetahuan yang luas apabila dia memiliki kebiasaan untuk
merenung tentang kejadian alam semesta ini dan mencari makna dari setiap fenomena
yang terjadi tersebut. Kebiasaan merenung dan merefleksikan sebuah fenomena inilah
yang membuat orang menjadi cerdas.
Intellectual Capital merupakan aset maya suatu organisasi yang dapat digunakan
untuk menciptakan nilai bagi organisasi melalui kombinasi antara human capital,
structural capital, dan relational capital. Konsep Intellectual capital dari Ulrich,
Tjakraatmadja, dan Stewart hanya berfokus pada dimensi human capital dan belum
memasukkan dimensi structural capital. Kompetensi dan komitmen pada konsep
intellectual capital dari Ulriach dan Burr & Girardi masuk dalam human capital
Menurut konsep intellectual capital dari Burr and Girardi (2002: 77) karena
kompetensi dan komitmen yang ada pada dosen akan mampu menciptakan nilai bagi
organisasi apabila didukung dengan pemberian pengendalian pekerjaan atau otonomi
kerja yang memadai kepada pegawai.
Pada InCas (2008), diketahui bahwa ICS merupakan strategi manajemen yang
digunakan untuk menilai dan mengembangkan Intelectual capital (IC) yang ada
dalam sebuah organisasi ,di dalam hal ini adalah universitas. ICS merupakan bagian
dari rangkaian bisnis proses yang ada di universitas guna mencapai tujuan dari
universitas.
Gambar 2 Structural modal ICS
Pada gambar 2 terlihat bahwa Bisnis Proses (BP) merupakan rantai kegiatan
dalam organisasi . BP menggambarkan interaksi dari Human Capital, Structural
capital, Relational Capital. Sedangkan Business Succes (BS) merupakan hasil atau
goal yang dicapai universitas (dalam InCas, 2008).
ICS terdiri dari 3 elemen utama yaitu Human Capital (HC) , Structural Capital
(SC), Relational Capital (RC) (dalam Tjiptohadi,2003). Adapun definisi dari 3
elemen utama tersebut adalah sebagai berikut :
Human Capital merupakan kemampuan seseorang (dalam hal ini adalah
dosen) yang memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta mampu
menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki dalam pekerjaan.
Structural Capital merupakan kemampuan universitas dalam memenuhi
proses yang ada di dalamnya dan struktur yang mendukung dalam
menghasilkan kinerja Intellectual yang optimal.
Relational capital merupakan asset intangible yang membangun dan mengatur
hubungan baik dengan customer,karyawan, pemerintah, stakeholder, dan
competitor lainnya serta dengan mitra kerja yang dapat muncul dari bagian di
luar universitas untuk mendukung universitas.
2.2.7 Pengertian Human Capital
Human Capital adalah kemampuan seseorang (dalam hal ini adalah dosen)
yang memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta mampu menerapkan pengetahuan
Manusia merupakan komponen yang sangat penting di dalam proses inovasi.
Manusia dengan segala kemampuannya bila dikerahkan keseluruhannya akan
menghasilkan kinerja yang luar biasa. Banyak pakar yang membicarakan masalah
inovasi. Pada umumnya para pakar sependapat bahwa proses inovasi itu memerlukan
adanya akumulasi pengetahuan.
Dalam konteks sebuah organisasi baru yang berbasis pada pengetahuan, ada
tiga komponen modal yang sangat menentukan kinerja organisasi. Modal ini adalah
sesuatu yang akhirnya memunculkan berbagai inovasi yang mendukung kinerja
organisasi.
Human Capital Theory dikembangkan oleh Becker (1964) yang
mengemukakan bahwa investasi dalam pelatihan dan untuk meningkatkan human
capital adalah penting sebagai suatu investasi dari bentuk-bentuk modal lainnya.
Tindakan strategis membutuhkan seperangkat sumber daya fisik, keuangan, human
atau organisasional khusus, sehingga keunggulan kompetitif ditentukan oleh
kemampuannya untuk memperoleh dan mempertahankan sumber daya (Wernerfelt,
1984).
Human Capital disini yang dimaksud adalah dosen, jika berbicara tentang
perguruan tinggi, maka keberadaannya tidak bisa dilepaskan dari keberadaan dan
peran dosen-dosen di dalamnya. Karena bagaimanapun juga kepada merekalah maka
Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama
mentransformasikan mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat. Berbeda dengan sekolah dasar dan menengah yang lebih banyak
difokuskan kepada proses belajar dan mengajar, dan mempersiapkan murid untuk
bisa naik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Maka di perguruan tinggi karena
dianggap sebagai jenjang tertinggi suatu proses pendidikan, maka selain diutamakan
pada proses belajar – mengajar dan menyemaikan ilmu, tetapi juga kepada pencarian
dan pengembangan ilmu sendiri, yang mana dengan bekal ilmu dan pengetahuan
tersebut diharapkan dapat dijadikan alat untuk mendapatkan solusi permasalahan bagi
masyarakat.
Sebagaimana profesi lain yang diakui keberadaannya, misalnya profesi
dokter, maka agar dapat disebut pendidik profesional maka diperlukan proses
sertifikasi. Ini bahkan telah menjadi persyaratan utama yang diminta pemerintah
sebagaimana tercantum pada pasal 2. Dalam proses pencarian dan pengembangan
ilmu sendiri, maka dosen juga dituntut untuk melakukan penelitian dan
mempublikasikan hasil penelitiannya, kecuali itu juga mampu berinteraksi dengan
masyarakat dengan kompetensi yang dimilikinya. Itulah esensi tri dharma perguruan
2.2.7.1 Knowledge
Knowledge bisa diartikan sebagai pengetahuan yang kita peroleh karena
masuknya informasi ke otak kita. Pengetahuan dapat disimpan sebagai memori.
Knowledge merupakan apa saja yang kita ketahui. Secara garis besar ada dua macam
kenowledge atau pengetahuan yaitu menurut Leksana TH (2003) 1.pengetauan fakta
merupakan pengetahuan berupa informasi yang kita terima sebagai kenyataan dan
2.pengetahuan eksperensial pemahaman yang kita peroleh berasal dari pengalaman
kita. Pengetahuan faktual bagi seorang akuntan misalnya berkaitan dengan double
entri pada book keeping. Pengetahuan eksperensial karakternya berbeda, lebih sulit
diajarkan karena sumbernya berasal dari pengalaman dan praktek. Contoh
pengetahuan eksperensial dari seorang akuntan adalah melewati masa kerja selama
puluhan tahun adalah pengetahuan untuk melindungi perusahaan agar bisa
memperoleh keringanan membayar pajak secara legal.
Dalam perguruan tinggi knowledge atau pengetahuan sangat mutlak
dibutuhkan, knowledge tidak hanya disalurkan tetapi juga dikembangkan melalui
adanya research atau penelitian yang terus dilakukan oleh civitas akademika. karena
dengan adanya knwledge seorang dosen mampu mengembangkan dan menyalurkan
ilmu yang dimilikinya kepada masyarakat. Kita sering mendengar istilah knowledge
is power, sebenarnya hal itu kurang tepat karena mereka yang memiliki knowledge
belum tentu memiliki power jika saja tidak ada action atau tindakan yang merupakan
2.2.7.2 Skill
Skill bisa diartikan sebagai keterampilan (how to) atau cara untuk melakukan
sesuatu. Landasan dari skill adalah pengalaman dan pembelajaran secara praktek
lapangan. Contoh seorang tukang las memiliki pengetahuan teknik mengelas (teori
mengelas) belum tentu menjadi tukang las yang jago.Skill memiliki karakter bisa
ditransfer dari individu ke individu lain dengan melalui proses pembelajaran yang
bertahap. Bagi seorang sekretaris misalnya penguasaanterhadap program aplikasi
word dan excel juga merupakan skill. Cara yang paling efektif untuk mentransfer skill
adalah dengan mengikut sertakan si pembelajar melakukan tahapan pekerjaan dan
membuatnya mempraktekkan tahapan pekerjaan tersebut dalam konteks pelatihan
lapangan dan melakukan pengulangan. Praktek dan pengulangan merupakan dua
kunci utama bagi seseorang untuk mengakuisisi skill yang baru.
Disamping skill juga ada beberapa istilah yang terdapat di dalam diri
seseorang yang masih dapat dibina atau ditingkatkan kemampuannya yaitu:
Habit biasa diterjemahkan sebagai kebiasaan, Habit juga sering dinyatakan
sebagai pembawaan asal diri kita. Ada ungkapan bahwa kita bisa mengubah habit
lama dan habit baru,anggapan ini mungkin memiliki maksud yang baik tetapi
sebenarnya kurang tepat. Sebagian besar habit kita muncul berasal dari kondisi
alamiah pembawaan kita. Sebagian besar habit bisa dikatakan sebagai talenta.Jika
anda memiliki habit seorang yang gigih atau mudah berempati atau kompetitif,maka
Habit mengendap dalam diri kita dan menjadi jati diri kita, habit itulah ynag
menjadikan diri kita apa adanya seperti sekarang ini. Habit muncul karena tempaan
pengalaman hidup,lingkungan dan karakter asal. Habit ini bisa diartikan sebagai pola
kecenderungan untuk berfikir, berperasaan dan bersikap.
Pengertian habit dengan behaviour (perilaku) sering diartikan sama padahal
dua kata ini memiliki pengertian yang berbeda. Behaviour muncul dari perwujudan
habit, Behaviour kita dilihat oleh orang lain sebagai ucapan dan perilaku kita.
Behaviour lebih merupakan tindak tanduk yang nampak di permukaaan. Secara
umum lebih susah merubah habit daripada behaviour, mengubah habit hanya bisa
dilakukan dengan dorongan diri dalam diri yangsangat kuat, dan atau karena adanya
suatu peristiwa atau kejadian penting dalam hidupnya sehingga membuat seseorang
ingin merubah nilai-nilai dirinya.
Attitude,Banyak manajer yang mempertimbangkan attitude untuk merekrut
karyawan baru. Attitude memiliki arti kecenderungan sikap. Attitude seseorang akan
sangat mempengaruhi cocok atau tidak peran seseorang dalam suatu pekerjaan.
Dalam suatu kepemimpinan, attitude para pemimpin memberi pengaruh yang
signifikan dalam mewujudkan atmosfir kerja yang kondusif. Attitud yang positif
memiliki kekuatan radiasi seperti medan magnet yang mampu mempengaruhi
lingkungan sekitarnya untuk berubah. Attitude dapat dibentuk dari proses pembinaan
yang kontinu atau terus menerus, pembinaan attitude akan lebih efektif jika dilakukan
2.2.7.3 Motivasi
Winardi (2002:1) menjelaskan istilah motivasi (motivation) berasal dari
perkataan bahasa Latin, yakni movere yang berarti menggerakkan (to move).
Diserap dalam bahasa Inggris menjadi motivation berarti pemberian motif,
penimbulan motif atau hal yang menimbulkan dorongan atau keadaan yang
menimbulkan dorongan. Selanjutnya Winardi (2002:33) mengemukakan, motivasi
seseorang tergantung kepada kekuatan motifnya. Berdasarkan hal tersebut diskusi
mengenai motivasi tidak bisa lepas dari konsep motif. Pada intinya dapat dikatakan
bahwa motif merupakan penyebab terjadinya tindakan. Steiner sebagaimana dikutip
Hasibuan (2003:95) mengemukakan motif adalah “suatu pendorong dari dalam untuk
beraktivitas atau bergerak dan secara langsung atau mengarah kepada sasaran akhir”.
Ali sebagaimana dikutip Arep dan Tanjung 2004:12) mendefinisikan motif sebagai
“sebab-sebab yang menjadi dorongan tindakan seseorang”.
Winardi (2002:33) menjelaskan, motif kadang-kadang dinyatakan orang
sebagai kebutuhan, keinginan, dorongan yang muncul dalam diri seseorang. Motif
diarahkan ke arah tujuan-tujuan yang dapat muncul dalam kondisi sadar atau dalam
kondisi di bawah sadar. Motif-motif merupakan “mengapa” dari perilaku. Mereka
muncul dan mempertahankan aktivitas, dan mendeterminasi arah umum perilaku
seorang individu.
Motivasi telah dirumuskan dalam sejumlah definisi yang berlainan. Walaupun
begitu, tentang substansinya tidak banyak berbeda. Istilah motivasi, menurut
melibatkan tiga komponen utama, yaitu (1) pemberi daya pada perilaku manusia
(energizing); (2) pemberi arah pada perilaku manusia (directing); (3) bagaimana
perilaku itu dipertahankan (sustaining). Campbell dalam Winardi (2002:4)
menyatakan bahwa motivasi berhubungan dengan (1) pengarahan perilaku, (2)
kekuatan reaksi setelah seseorang karyawan telah memutuskan arah
tindakan-tindakan tertentu, dan (3) persistensi perilaku, atau berapa lama orang yang
bersangkutan melanjutkan pelaksanaan perilaku dengan cara tertentu.
Menurut Mc. Donald, yang dikutip Oemar Hamalik (2003:158) motivasi
adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan timbulnya
perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Dengan pengertian ini, dapat dikatakan
bahwa motivasi adalah sesuatu yang kompleks. Motivasi akan menyebabkan
terjadinya suatu perubahan energi yang ada pada diri manusia, sehingga akan
bergayut dengan persoalan gejala kejiwaan, perasaan dan juga emosi, untuk
kemudian bertindak atau melakukan sesuatu.
Menurut Siti Sumarni (2005), Thomas L. Good dan Jere B. Braphy (1986)
mendefinisikan motivasi sebagai suatu energi penggerak dan pengarah, yang dapat
memperkuat dan mendorong seseorang untuk bertingkah laku. Ini berarti perbuatan
Motivasi adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas. Masih
dalam artikel Siti Sumarni (2005), motivasi secara harafiah yaitu sebagai dorongan
yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar, untuk melakukan suatu
tindakan dengan tujuan tertentu. Sedangkan secara psikologi, berarti usaha yang
dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tergerak melakukan sesuatu
karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya, atau mendapat kepuasan dengan
perbuatannya. (KBBI, 2001:756).
Dari beberapa pendapat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian
motivasi adalah keseluruhan daya penggerak baik dari dalam diri maupun dari luar
dengan menciptakan serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu
yang menjamin kelangsungan dan memberikan arah pada kegiatan sehingga tujuan
yang dikehendaki oleh subjek itu dapat tercapai.
2.2.8 Pengertian Structural Capital
Structural Capital merupakan kemampuan universitas dalam memenuhi proses
yang ada di dalamnya dan struktur yang mendukung dalam menghasilkan kinerja
Intellectual yang optimal.Struktural capital dipengaruhi oleh budaya akademik,system
pengajaran,dan penelitian (Andrew kok,2007), dan penelitian (Marr, Schiuma dan
Neely , 2004 ). Structural Capital terdiri dari beberapa indikator yang di dalamnya
bertujuan untuk meningkatkan kinerja dari pada organisasi itu sendiri (dalam hal ini
2.2.8.1 Kebebasan Akademik
Menurut PP No. 60 Tahun 1999, kebebasan akadernik merupakan kebebasan
yang dimiliki oleh anggota sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang
terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara
bertanggungjawab dan mandiri.Menurut Arthur Lovejoy yang dikutip oleh
Haryasetyaka (2004), kebebasan akademik adalah kebebasan seseorang atau seorang
peneliti di lembaga 11mu. pengetahuan untuk mengkaji persoalan serta mengutarakan
kesimpulannya baik melalui penerbitan atau perkuliahan tanpa campur tangan dari
penguasa politik atau keagamaan atau dan lembaga yang memperkerjakannya kecuali
apabila metode yang digunakannya tidak memadai atau bertentangan dengan etika
professional atau lembaga yang berwenang dalam bidang keilmuannya.
Menurut Nymeyer (1956) kebebasan akademik adalah kebebasan anggota
fakultas untuk mengajar pada suatu sekolah dengan pikirannya sendiri dan
mempromosikan spekulasi dan kesimpulan yang dibuat secara independen atau.
bebas dari apa yang mungkin institusi kehendaki. Dari definisi tersebut dapat dibaca
bahwa kebebasan akademik dilaksanakan olch lembaga ilmu pengetahuan. Jika kedua
definisi tersebut digabung maka lembaga pelaksana kebebasan akademik adalah
Perguruan Tinggi. Kebebasan akademik yang dilaksanakan oleh sivitas akademik
tidak bersifat mutlak atau absolut. Kebebasan tersebut harus memperhatikan etika
Jika kita mengacu kepada UU No. 39 Talum 1999 tentang HAM, maka
kebebasan akademik tidak dibenarkan bertentangan dengan nilai nilai agama,
kesusilaan, keterbitan, kepentingan umum dan keutuhan bangsa. Pelaksanaan
kebebasan akademik dapat dilakukan melalui berbagai media seperti melalui media
cetak, media elektronik, tatap muka atau bentuk media lainnya. Kebebasan akdemik
harus dipahami sebagai seperangkat hak dan kewajiban dengan tetap bertanggung
jawab dan akuntabel penuh kepada masyarakat. Mandiri, dapat diartikan marnpu
berbicara dengan bebas tentang masalah masalah etika, budaya, social, ekonomi dan
lain-lain secara mandiri.
Ada tiga konsep dasar bagi kebebasan akademik. Pertama, sebagai peneliti,
dosen harus bebas. Bagaimana mungkin penelitian dapat dilakukan tanpa kebebasan.
Kedua, sebagai pemikir asli, dosen harus bebas. Bagaimana mungkin seseorang dapat
menjadi pemikir asli, jika ia harus mematuhi hal hal yang telah berlaku di masa yang
lalu. Ketiga, sebagai penyebar gagasan kedua, dosen dalam beberapa hal mungkin
bebas, dan dalam beberapa hal mungkin tidak bebas. Oleh karena itu, dosen sebagai
guru/pengajar dijamin bebas dalam kelas jika mereka membahas tentang kajian ilmu
yang diajarkan dan menghindari materi materi yang tidak berkaitan dengan materi
pembelajaran.
Kebebasan akademik terdiri dari proteksi terhadap independensi intelektual
professor, peneliti dan mahasiswa dalam mencari atau menggali pengetahuan dan
mengekspresikan gagasan gagasan yang bebas darii turut campur legislator atau pihak
Ini berarti tidak ada kekolotan politik, ideology atau agama yang dibebankan
kepada professor, peneliti dan mahasiswa melalui bebagai cara. Juga pimpinan tidak
memasukkan kekolotan tersebut melalul pengontrolan budget universitas.
Dalam kondisi tertentu, kebebasan akademik bagi dosen sebagai pengajar
(untuk membedakan dosen sebagai peneliti dan pemikir asli) diperlukan tanpa
memperhatikan apa yang orangtua atau mahasiswa inginkan. Hal ini berlaku pada
sekolah negeri. Mahasiswa bebas belajar, mengambil, menyimpan data atau
pandangan yang diberikan dalam perkuliahan dan bebas menilai materi atau pendapat
tersebut. Mahasiswa mendapat perlakuan yang sama dalam pembelajaran serta tidak
boleh dipaksa dalam kelas maupun di lingkungan akademik untuk menerima
pendapat atau gagasan tentang filosofi, politik dan isu isu lain. Berikut ini adalah
beberapa aspek yang terkait dengan kebebasan akademik, antara lain adalah :
a. Budaya akademik
Budaya akademik berarti apa yang dipelajari oleh mahasiswa selama periode
waktu tertentu dari Universitas, Fakultas atau Jurusannya. Pengembangan budaya
akademik ini didasarkan atas dua tantangan yang selalu dihadapi oleh pendidikan
tinggi dalam penyelenggaraan pendidikannya yaitu tantangan yang bersifat internal
dan eksternal.
Budaya menulis dalam ruang lingkup budaya akademik perguruan tinggi berkaian
dengan aktivitas-akativitas seluruh stakeholder perguruan tinggi, yakni dosen sebagai