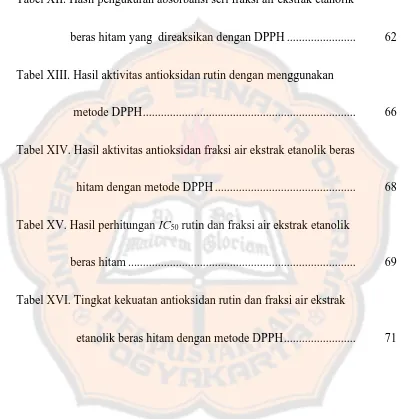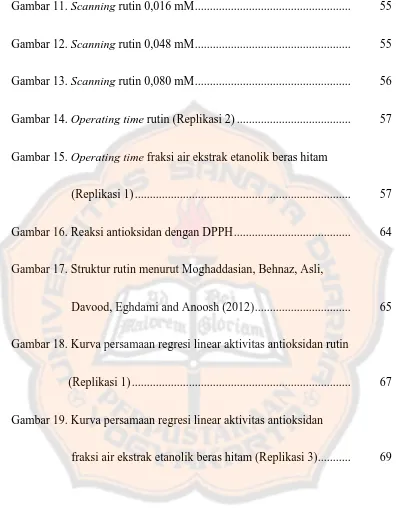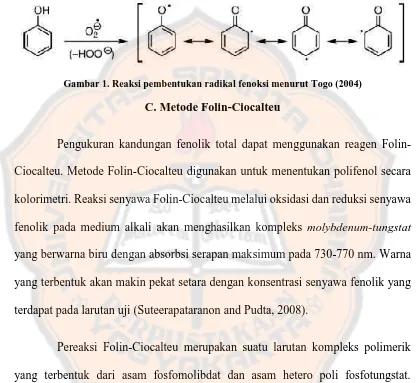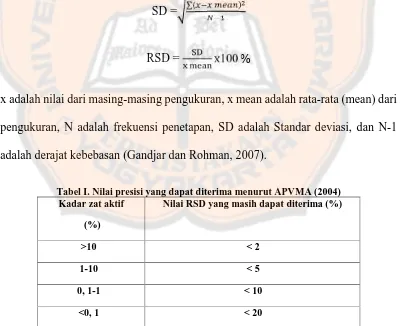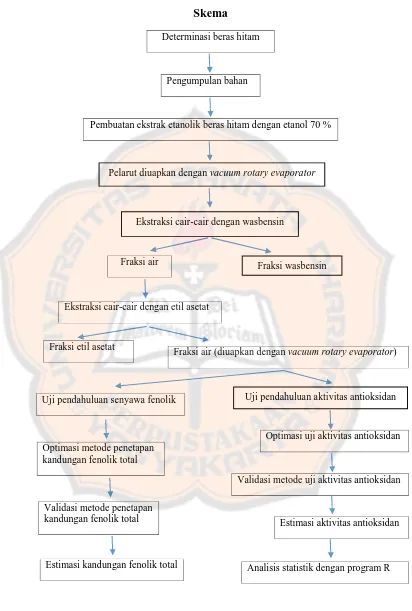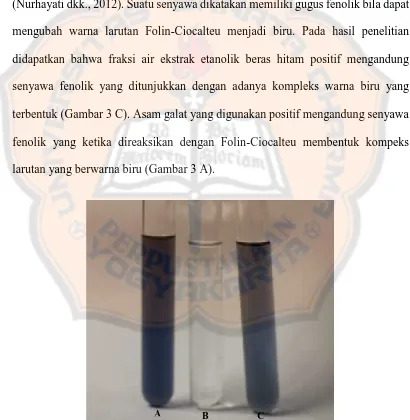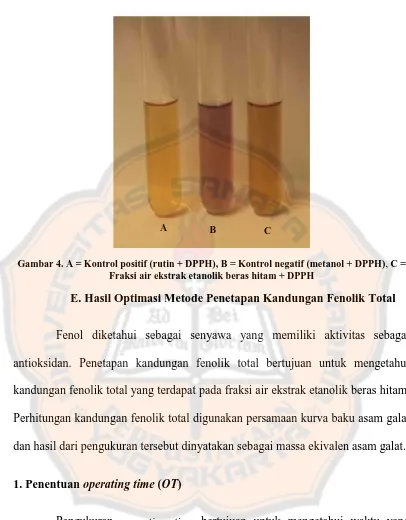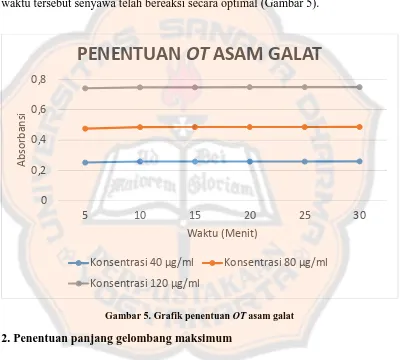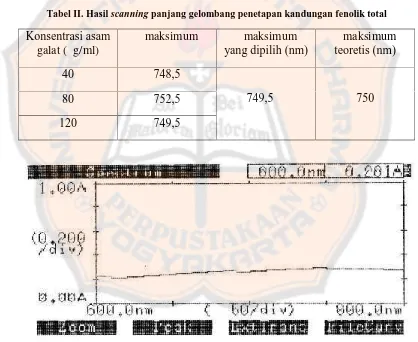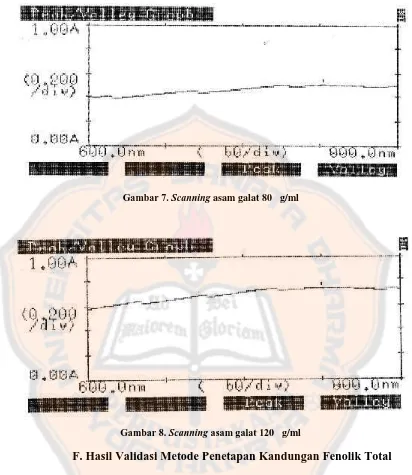PENETAPAN KANDUNGAN FENOLIK TOTAL FRAKSI AIR EKSTRAK ETANOLIK BERAS HITAM (Oryza sativa L. subsp. indica) DAN AKTIVITAS ANTIOKSIDAN DENGAN MENGGUNAKAN RADIKAL
1,1-DIFENIL-2-PIKRILHIDRAZIL (DPPH)
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Farmasi (S.Farm)
Program Studi Farmasi
Oleh:
Fendy
Nim: 098114133
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA
i
PENETAPAN KANDUNGAN FENOLIK TOTAL FRAKSI AIR EKSTRAK ETANOLIK BERAS HITAM (Oryza sativa L. subsp. indica) DAN AKTIVITAS ANTIOKSIDAN DENGAN MENGGUNAKAN RADIKAL
1,1-DIFENIL-2-PIKRILHIDRAZIL (DPPH)
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Farmasi (S.Farm)
Program Studi Farmasi
Oleh:
Fendy
Nim: 098114133
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA
iv
HALAMAN PERSEMBAHAN
Skripsi ini aku persembahkan untuk:
Tuhan Yang Maha Esa yang telah membukakan jalan kesempatan serta memberikan kekuatan, sehingga aku dikuatkan untuk menyelesaikan semua
masalah-masalah yang ku hadapi. DENGAN APAPUN . Doa ku akan selalu menyertai kalian berdua.
Abang ipar dan Kakak yang telah mempercayakan pada diri ku dan memberikan dorongan yang kuat baik dalam segi material maupun non material sehingga saya dapat berkuliah di Fakultas Farmasi yang ku cintai.
vii
PRAKATA
Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas cinta kasih, berkat,
izin dan peryertaan-Nya yang begitu besar, sehingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi yang berjudul “PENETAPAN KANDUNGAN FENOLIK TOTAL
FRAKSI AIR EKSTRAK ETANOLIK BERAS HITAM (Oryza sativa L.
subsp. indica) DAN AKTIVITAS ANTIOKSIDAN DENGAN
MENGGUNAKAN RADIKAL 1,1-DIFENIL-2-PIKRILHIDRAZIL
(DPPH) ” sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi demi memperoleh gelar Sarjana Farmasi (S.Farm.) di Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta.
Penulis menyadari bahwa penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat
terselesaikan karena adanya masukan, kritikan, diskusi, arahan, saran, dan
bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih
yang sebesar-besarnya kepada :
1. Ipang Djurnarko, M.Sc., Apt. selaku Dekan Fakultas Farmasi Universitas
Sanata Dharma Yogyakarta atas teladan seorang pemimpin yang diberikan.
2. Prof. Dr. C. J. Soegihardjo, Apt. selaku Dosen Pembimbing yang dengan
sabar memberikan bimbingan, memberikan banyak bantuan berupa saran,
pengarahan, dan hal-hal yang berkenaan dengan skripsi ini.
3. Yohanes Dwiatmaka, M.Si. selaku Dosen Penguji yang telah banyak
memberikan kritik dan saran yang membangun serta kesediaannya untuk
viii
4. Enade Perdana Istyastono, Ph. D., Apt. selaku Dosen Penguji yang telah
memberikan kritikan dan saran yang sangat bermanfaat bagi skripsi ini.
5. C.M.Ratna Rini Nastiti, M.Pharm., Apt. sebagai Kaprodi Fakultas Farmasi
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta atas teladan kepemimpinan, memberi
masukan, dan saran yang baik selama penulis berkuliah.
6. Rini Dwi Astuti, M.Sc., Apt. sebagai Kepala Laboratorium Fakultas Farmasi
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
7. Segenap laboran Laboratorium Farmakognosi_Fitokimia (Mas Wagiran),
Laboratorium Farmasi Fisika (Mas Agung), Laboratorium Kimia Analisis
Instrumental (Mas Bimo) dan Laboratorium Kimia Organik (Pak Parlan) atas
segala bantuan yang telah diberikan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua dosen dan karyawan Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma atas
pengalaman, masukan, keceriaan, semangat, dan persahabatan yang telah
diberikan.
9. Teman seperjuanganku Ignasius Andrenaldo terima kasih atas kerjasamanya,
kepercayaan, kesabaran, canda, saling memberikan semangat serta suka
maupun duka yang telah kita lewati bersama. Tanpa adanya hal-hal tersebut
skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik.
10. Teman-temanku Demas Ismanto, Eric Antonius, dan Is Sumitro atas
kebersamaan dan keakraban kita selama ini, serta sudah memberikan motivasi,
ix
11. Teman-temanku satu kos, Is Sumitro, Johanes Dharma dan Anthony Felix
yang sudah menjadi teman-teman ngobrol yang baik dan selalu berbagi cerita,
canda dan tawa bersama.
12. Rekan-rekan KKN alternatif 1 di Plosokuning II dan III terima kasih untuk
kebersamanan, serta kerjasama yang baik walapun hanya berlangsung dalam
waktu yang singkat.
13. Teman-taman angkatan 2009 yang bersama-sama berjuang dan mengisi
sebagian cerita hidupku, terima kasih atas kebersamaannya selama ini.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas segala bantuan,
semangat dan doa yang menyertai penulis dari awal penelitian hingga
diselesaikannya penulisan skripsi ini.
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi masih banyak
kekurangan dan jauh dari sempurna, karena keterbatasan wawasan dan
kemampuan. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati membuka diri menerima
kritik dan saran dari semua pihak, dengan segala kerendahan hati penulis
mengharapkan skripsi ini memberikan manfaat yang berarti bagi para pembaca.
Akhir kata, semoga skripsi ini berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan serta
dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang farmasi.
Yogyakarta, 02 Juli 2013
Penulis
x
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL... i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ... ii
HALAMAN PENGESAHAN... iii
HALAMAN PERSEMBAHAN ... iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ... v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBIKASI KARYA... vi
PRAKATA... vii
DAFTAR ISI... x
DAFTAR TABEL... xv
DAFTAR GAMBAR ... xvii
DAFTAR LAMPIRAN ... xix
INTISARI... xxi
ABSTRACT... xxii
BAB 1 PENGANTAR ... 1
A. Latar Belakang ... 1
xi
2. Keaslian penelitian ... 4
3. Manfaat penelitian ... 5
4. Tujuan umum dan khusus... 6
BAB II PENELAAHAN PUSTAKA... 7
A. Beras Hitam... 7
1. Sistematika beras hitam... 7
2. Gambaran umum beras hitam ... 8
3. Kandungan kimia beras hitam... 8
B. Senyawa Fenolik ... 9
C. Metode Folin-Ciocalteu ... 10
D. Radikal Bebas... 11
E. Antioksidan ... 13
F. Metode DPPH ... 15
G. Ekstraksi... 16
H. Spektrofotometri ... 17
I. Validasi Metode Analisis ... 19
J. Landasan Teori... 21
K. Hipotesis... 23
BAB III METODE PENELITIAN... 24
A. Jenis dan Rancangan Penelitian ... 24
B. Variabel Penelitian ... 24
xii
2. Variabel tergantung... 24
3. Variabel pengacau terkendali ... 24
4. Variabel pengacau tak terkendali ... 24
C. Definisi Operasional... 24
D. Bahan dan Alat Penelitian... 25
1. Bahan penelitian... 25
2. Alat penelitian ... 25
E. Tata Cara Penelitian ... 26
1. Determinasi beras hitam... 26
2. Pengumpulan bahan ... 26
3. Preparasi sampel... 26
4. Pembuatan fraksi air... 26
5. Pembuatan larutan DPPH, pembanding, dan uji ... 27
6. Uji pendahuluan ... 28
7. Optimasi metode penentuan kandungan fenolik total ... 29
8. Penetapan kandungan fenolik total ... 29
9. Optimasi metode uji aktivitas antioksidan ... 30
10. Pengujian aktivitas antioksidan... 31
F. Analisis Hasil ... 32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ... 35
A. Hasil Determinasi Beras Hitam... 35
B. Hasil Pengumpulan Bahan ... 35
xiii
1. Hasil ekstraksi sampel... 36
2. Hasil fraksinasi ekstrak ... 39
D. Hasil Uji Pendahuluan... 41
1. Uji pendahuluan senyawa fenolik ... 41
2. Uji pendahuluan aktivitas antioksidan ... 43
E. Hasil Optimasi Metode Penetapan Kandungan Fenolik Total .... 44
1. Penentuan operating time (OT)... 44
2. Penentuan panjang gelombang maksimum ... 45
F. Hasil Validasi Metode Penetapan Kandungan Fenolik Total .... 47
1. Presisi metode penetapan kandungan fenolik total ... 48
2. Linearitas metode penetapan kandungan fenolik total... 49
3. Spesifisitas metode penetapan kandungan fenolik total ... 50
G. Hasil Penetapan Kandungan Fenolik Total... 51
H. Hasil Optimasi Metode Uji Aktivitas Antioksidan ... 54
1. Penentuan panjang gelombang maksimum (λ max)... 54
2. Penentuan operating time (OT)... 56
I. Hasil Validasi Metode Uji Aktivitas Antioksidan ... 58
1. Presisi metode uji antioksidan... 58
2. Linearitas metode uji antioksidan ... 61
3. Spesifisitas metode uji antioksidan ... 63
J. Hasil Estimasi Aktivitas Antioksidan dengan Radikal DPPH .... 63
K. Hasil Analisis Statistik ... 71
xiv
A. Kesimpulan ... 73
B. Saran ... 73
DAFTAR PUSTAKA ... 74
LAMPIRAN ... 77
xv
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel I. Nilai presisi yang dapat diterima menurut APVMA (2004)... 20
Tabel II. Hasil scanning panjang gelombang penetapan kandungan fenolik total ... 46
Tabel III. Hasil pengukuran absorbansi asam galat ... 48
Tabel IV. Nilai RSD penetapan kandungan fenolik total (Replikasi 2).. 49
Tabel V. Nilai r penetapan kandungan fenolik total ... 50
Tabel VI. Kadar asam galat dengan absorbansinya setelah direaksikan dengan pereaksi Folin-Ciocalteu yang diukur pada panjang gelombang 749,5 nm... 52
Tabel VII. Hasil perhitungan kandungan fenolik total... 54
Tabel VIII. Scanning panjang gelombang maksimum DPPH ... 55
Tabel IX. Nilai RSD uji aktivitas antioksidan rutin ... 59
xvi
Tabel XI. Hasil pengukuran absorbansi seri rutin yang direaksikan dengan
DPPH ... 62
Tabel XII. Hasil pengukuran absorbansi seri fraksi air ekstrak etanolik
beras hitam yang direaksikan dengan DPPH ... 62
Tabel XIII. Hasil aktivitas antioksidan rutin dengan menggunakan
metode DPPH... 66
Tabel XIV. Hasil aktivitas antioksidan fraksi air ekstrak etanolik beras
hitam dengan metode DPPH ... 68
Tabel XV. Hasil perhitungan IC50rutin dan fraksi air ekstrak etanolik
beras hitam ... 69
Tabel XVI. Tingkat kekuatan antioksidan rutin dan fraksi air ekstrak
xvii
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1. Reaksi pembentukan radikal fenoksi menurut Togo (2004) . 10
Gambar 2. Skema jalannya penelitian... 34
Gambar 3. A = Kontrol positif (asam galat + Folin-Ciocalteu), B = Kontrol negatif (metanol:air 1:1 + Folin-Ciocalteu), C = Fraksi air ekstrak etanolik beras hitam + Folin-Ciocalteu... 42
Gambar 4. A = Kontrol positif (rutin + DPPH), B = Kontrol negatif (metanol + DPPH), C = Fraksi air ekstrak etanolik beras hitam + DPPH... 44
Gambar 5. Grafik penentuan OT asam galat ... 45
Gambar 6. Scanningasam galat 40 μ g/ml... 46
Gambar 7. Scanningasam galat 80 μ g/ml... 47
Gambar 8. Scanningasam galat 120 μ g/ml... 47
xviii
Gambar 11. Scanning rutin 0,016 mM... 55
Gambar 12. Scanning rutin 0,048 mM... 55
Gambar 13. Scanning rutin 0,080 mM... 56
Gambar 14. Operating time rutin (Replikasi 2) ... 57
Gambar 15. Operating time fraksi air ekstrak etanolik beras hitam (Replikasi 1) ... 57
Gambar 16. Reaksi antioksidan dengan DPPH... 64
Gambar 17. Struktur rutin menurut Moghaddasian, Behnaz, Asli, Davood, Eghdami and Anoosh (2012)... 65
Gambar 18. Kurva persamaan regresi linear aktivitas antioksidan rutin (Replikasi 1) ... 67
xix
DAFTAR LAMPIRAN
Halaman
Lampiran 1. Surat determinasi ... 77
Lampiran 2. Gambar beras hitam... 78
Lampiran 3. Perhitungan rendemen ... 79
Lampiran 4. Penimbangan uji kandungan fenolik total ... 81
Lampiran 5. Scanning kontrol asam galat... 82
Lampiran 6. Optimasi penentuan kandungan fenolik total ... 83
Lampiran 7. Penentuan kandungan fenolik total... 87
Lampiran 8. Data penimbangan untuk pengujian aktivitas antioksidan (DPPH) ... 93
Lampiran 9. Data konsentrasi bahan untuk pengujian aktivitas antioksidan ... 95
Lampiran 10. Scanning larutan ... 102
Lampiran 11. Penentuanλ maksimumoperating time (OT)... 106
Lampiran 12. Uji aktivitas antioksidan menggunakan radikal DPPH .... 114
xx
beras hitam ... 118
xxi
Intisari
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan fenolik total dan aktivitas antioksidan fraksi air ekstrak etanolik beras hitam (Oryza sativa L. subsp. indica). Kandungan fenolik total ditentukan dengan menggunakan reagen Folin-Ciocalteu dengan standar asam galat. Prinsip dari metode ini adalah terjadinya oksidasi senyawa fenolik dan reduksi pereaksi Folin-Ciocalteu yang akan menghasilkan larutan yang berwarna biru yang dapat diukur dengan spektrofotometer visibel pada panjang gelombang 749,5 nm. Pengujian aktivitas antioksidan dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif dengan menggunakan radikal 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH). Prinsip dari metode DPPH adalah adanya penurunan intensitas warna DPPH yang sebanding dengan konsentrasi senyawa antioksidan yang kemudian dinyatakan sebagai Inhibition Concentration 50 (IC50). IC50merupakan konsentrasi senyawa antioksidan yang digunakan untuk
menghambat 50 % radikal bebas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan fenolik total fraksi air ekstrak etanolik beras hitam adalah 5,1 ± 0,12 mg ekivalen asam galat per gram fraksi air ekstrak etanolik beras hitam. Fraksi air ekstrak etanolik beras hitam memiliki aktivitas antioksidan yang lemah dengan nilai IC50
187,0 ± 1,25μ g/ml.
Kata kunci: Antioksidan, Oryza sativa L. subsp. indica, fraksi air ekstak etanolik
xxii
ABSTRACT
The goal of the research was to determine total phenolic and antioxidant activity which is contained in the water fraction from ethanolic extracts of black rice (Oryza sativa L. subsp. Indica). Determination of total phenolic was using Folin-Ciocalteu reagent with the standard was gallic acid. The principle of the method is the oxidation of phenolic compounds, the reduction of reagent Folin-Ciocalteu, then the solution will become blue which can be measured by visible spectrophotometer at a wavelength 749.5 nm. The test of antioxidant activity was did qualitatively and quantitatively using radical 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH). The principle of the method is decreasing intensity of DPPH color which is comparable with the increasing the concentration of antioxidant compound and it is calculated as Inhibition Concentration 50 (IC50). IC50 is concentration of an
antioxidant compound to inhibit 50 % of free radicals. The result showed that total phenolic which is contained in the water fraction from ethanolic extracts of black rice was 5.1 ± 0.12 mg gallic acid equivalents per gram water fraction from ethanolic extract of black rice. The water fraction from ethanolic extracts of black rice showed weak antioxidant activity with the value of IC50 was 187.0 ± 1.25 μ g/ml.
Keyword: Antioxidant, Oryza sativa L. subsp. indica, water fraction from
BAB I
PENGANTAR
A. Latar Belakang
Setiap hari tubuh kita terpapar oleh sejumlah bahan kimia asing yang
dapat memberikan efek negatif bagi kesehatan, senyawa tersebut antara lain berupa
radikal bebas seperti asap rokok dan polusi (Olajire and Azeez, 2011). Radikal
bebas adalah molekul yang sangat reaktif karena memiliki elektron yang tidak
berpasangan pada orbital luarnya, sehingga dapat bereaksi dengan cara mengikat
elektron molekul sel tubuh (Kuntorini dan Astuti, 2010). Radikal bebas selain
berasal dari luar tubuh juga dapat diproduksi oleh tubuh secara normal sebagai hasil
dari metabolisme sel, akan tetapi sering kali terjadi ketidak seimbangan antara
radikal yang terbentuk dengan asupan antioksidan di dalam tubuh. Karena terjadi
ketidak seimbangan tersebut, sehingga menyebabkan radikal yang berasal dari
dalam atau luar tubuh dapat menyerang molekul sel yang ada di dalam tubuh seperti
protein, lemak, dan DNA dan apabila hal tersebut terus berlanjut dapat
menyebabkan berbagai penyakit degeneratif (Pollack and Leeuwenburgh, 1999).
Karena alasan tersebut maka dibutuhkan senyawa yang dapat menghambat efek
negatif dari radikal bebas. Senyawa tersebut kini kita kenal dengan antioksidan
(Olajire and Azeez, 2011). Senyawa antioksidan memiliki peranan yang penting
dalam kesehatan karena karakteristik utama dari senyawa ini adalah
Sumber antioksidan dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu
antioksidan alami dan antioksidan buatan atau sintetik. Sebagai contoh antioksidan
sintetik adalah butylated hydroxyanisol (BHA), butylated hydroxytoluene (BHT),
tertiary butylhydroquinone (TBHQ) dan ester dari asam galat contohnya propil
gallate (PG). Antioksidan alami biasanya ditemukan pada tanaman dan utamanya
merupakan senyawa fenolik. Sebagai contoh senyawa antioksidan alami adalah
tokoferol, flavonoid, dan asam fenolik (Pokorny, Yanishlieva and Gordon, 2001).
Karena antioksidan sintetik dapat berperan sebagai promotor penyakit kanker maka
antioksidan sintetik sudah mulai ditinggalkan (Olajire and Azeez, 2011).
Beras dikonsumsi secara luas dengan lebih dari setengah populasi yang
ada di dunia. Beras sendiri dibagi menjadi beberapa jenis antara lain beras putih dan
beras yang berwarna. Beras hitam digunakan sebagai supleman karena
mengandung antosianin dengan intensitas tinggi yang ada pada lapisan aleuron dan
dikarakterisasikan dengan warna ungu gelap (Chiang, Wu, Yeh, Chu, Lin and Lee,
2006). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ekstrak dari beras hitam dapat
digunakan sebagai antioksidan dan sebagai antiinflamasi (Hu, Zawistowski, Ling
and Kitts, 2003).
Ekstraksi beras hitam digunakan etanol karena etanol tidak beracun, dapat
terabsorbsi dengan baik, sehingga ekstraksi dapat berjalan dengan lebih baik,
kapang dan kuman sulit tumbuh dalam etanol diatas 20 %. Pemilihan fraksi air
didasarkan penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa beras hitam
Senyawa fenolik dapat digunakan untuk mengetahui aktivitas antioksidan
suatu tumbuhan. Kesimpulannya bahwa adanya hubungan antara kemampuan
antioksidan suatu tumbuhan dengan kandungan fenolik totalnya (Donovan, Meyer
and Waterhouse, 1998). Maka pada penelitian ini dilakukan penentuan kandungan
fenolik total dan pengujian aktivitas antioksidan fraksi air ekstrak etanolik beras
hitam yang diduga mengandung senyawa fenolik yang cukup tinggi.
Penentuan kandungan fenolik total dapat menggunakan metode
Folin-Ciocalteu yang akan membentuk kompleks berwarna biru bila bereaksi dengan
senyawa fenolik. Penentuan kandungan fenolik total digunakan standar asam galat
karena asam galat lebih stabil, selain itu asam galat juga merupakan senyawa
fenolik yang mempunyai aktivitas sebagai antioksidan. Hasil pengukuran senyawa
fenolik dinyatakan sebagai massa ekivalen asam galat (Nurhayati, Siadi dan
Herjono, 2012).
Salah satu metode yang cukup populer untuk menentukan aktivitas
antioksidan suatu senyawa adalah dengan menggunakan radikal
1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH). Melalui metode ini maka dapat mengetahui Inhibition
Concentration (IC50) suatu senyawa. IC50merupakan konsentrasi yang dibutuhkan
oleh substrat untuk menghambat 50 % radikal DPPH. DPPH merupakan metode
kolorimetri dan akan memberikan absorbansi maksimum pada waktu 30 menit dan
memiliki panjang gelombang maksimum 517 nm (Molyneux, 2004).
1. Permasalahan
a. Berapakah kadar fenolik total fraksi air ekstrak etanolik beras hitam yang
b. Berapakah nilai aktivitas antioksidan dari fraksi air ekstrak etanolik beras
hitam dengan menggunakan radikal DPPH yang dinyatakan dengan IC50?
2. Keaslian penelitian
Penelitian Chiang et al., (2006) yang berjudul “Antioxidant Effects of
Black Rice Extract through the Induction of Superoxide Dismutase and Catalase
Activities”. Menyatakan ekstrak beras hitam secara signifikan dapat menghambat
oksidasi LDL bila dibandingkan dengan ekstrak beras putih, menggunakan serbuk
beras hitam dan direflux dengan air destilasi selama lima hari pada suhu 80oC.
Penelitian Hu, Zawistowski, Ling and David (2003)yang berjudul “Black
Rice (Oryza sativa L. indica) Pigmented Fraction Suppresses both Reactive Oxygen
Species and Nitric Oxide in Chemical and Biological Model Systems”. Menyatakan
ekstraksi beras hitam dengan metanol dalam asam klorida 1 % kemudian
didapatkan ekstrak beras hitam. Kemampuan ekstrak tersebut di tunjukkan karena
kemampuannya mencegah human LDL oxidation in vitro, Effect of BRE (Black Rice
Extract) on Preventing Nitric Oxide Production in Lipopolysaccharida
(LPS)-Stimulated Macrophage Cells.
Penelitian Kaneda, Kobo and Sakurai (2006) yang berjudul“Antioxidative
Compounds in the Extracts of Black Rice Brans” beras hitam diekstrak dengan
menggunakan etanol 50 % kemudian pelarut diuapkan dengan evaporasi pada suhu
40-45oC. Pengukuran kandungan fenolik total dilakukan dengan metode
Reversed Phase Thin Layer Chromato-Graphy (TLC)-Scanning Densitometric
Method dan dilanjutkan dengan analisis menggunakan HPLC.
Penelitian Park, Sam, Kim and Chang (2008) yang berjudul“Isolation of
Anthocyanin from Black Rice and Screening of its Antioxidant Activities”. Sebanyak
0,5 g beras hitam direndam dengan 50 ml etanol yang mengandung 1 %
trifloroasetat kemudian ekstrak disaring dan divakum dengan rotary evaporator
pada suhu 30oC. Kemudian dilakukan pemurnian dengan menggunakan
kromatografi kolom.
Beda penelitian ini dengan yang sebelumnya yaitu, pada penelitian ini
pelarut yang digunakan adalah etanol, kemudian dilakukan fraksinasi lebih lanjut
dengan menggunakan wasbensin dan etil asetat. Fraksi air yang didapatkan dari
hasil fraksinasi etil asetat kemudian dilakukan pengukuran kandungan fenolik total
dengan metode Folin-Ciocalteu dan pengujian aktivitas antioksidan dengan metode
DPPH dan diukur menggunakan spektrofotometer UV-VIS.
3. Manfaat penelitian
a. Manfaat metodologis
Penelitian ini dapat dijadikan acuan sebagai metode penentuan kandungan
fenolik total dan uji aktivitas antioksidan menggunakan radikal DPPH suatu
tumbuhan.
b. Manfaat teoretis
Mendapatkan kadar fenolik total serta nilai IC50 dari fraksi air ekstrak
c. Manfaat praktis
Dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai potensi dari
aktivitas antioksidan beras hitam, sehingga dapat digunakan sebagai
pertimbangan untuk pemeliharaan kesehatan manusia.
4. Tujuan umum dan khusus
a. Tujuan umum Mengetahui kandungan fenolik total dan pengujian aktivitas
antioksidan fraksi air ekstrak etanolik beras hitam.
b. Tujuan khusus
1) Mengetahui kadar fenolik total fraksi air ekstrak etanolik beras
hitam berdasarkan nilai ekivalen asam galat.
2) Mengetahui aktivitas antioksidan dari fraksi air ekstrak etanolik
beras hitam dengan menggunakan radikal DPPH yang dinyatakan
BAB II
PENELAAHAN PUSTAKA
A. Beras Hitam
1. Sistematika beras hitam
Berikut sistematika beras hitam menurut UniProt (2013).
Kingdom : Plantae
Subkingdom : Tracheobionta
Superdivision : Spermatophyta
Division : Magnoliophyta
Class : Liliopsida
Subclass : Commelinidae
Order : Poales
Family : Poaceae
Genus : Oryza
2. Gambaran umum beras hitam
Beras hitam tergolong langka karena hanya terdapat di Asia. Beras ini
dikenal sebagai beras terlarang (forbidden rice) karena hanya dikonsumsi oleh
kalangan istana. Beras ini berwarna ungu mendekati hitam dikarenakan kulit ari dan
endosperm yang memproduksi antosianin dengan intensitas tinggi yang merupakan
senyawa dari flavonoid yang larut dalam air. Makin gelap warna beras
menunjukkan kandungan antioksidan juga makin tinggi (Ide, 2010).
Kandungan senyawa flavonoid pada beras hitam lima kali lipat bila
dibandingkan dengan senyawa flavonoid yang ada pada beras putih. Hasil
penelitian yang dipublikasikan oleh Journal of Nutrition tahun 2008 menyebutkan
ekstrak dari beras hitam dapat digunakan untuk mencegah aterosklerosis
(penyumbatan pembuluh darah jantung), menurunkan kadar trigliserida (lemak
darah) (Ide, 2010). Penelitian sebelumnya menunjukkan fraksi pigmen dari beras
hitam dapat menurunkan stres oksidatif, mencegah penyakit kardiovaskular, dan
dapat digunakan sebagai antiinflamasi (Wang, Han, Zhang, Xia, Zhu, Ma et al.,
2007).
3. Kandungan kimia beras hitam
Beras hitam merupakan makanan kesehatan yang mengandung antosianin
pada lapisan aleuron yang merupakan senyawa fenolik yang memiliki efek
antioksidan. Beras hitam memiliki kandungan antosianin yang lebih tinggi bila
dibandingkan dengan beras putih (Wang et al., 2007). Selain antosianin beras hitam
dibanding beras putih. Kandungan mineral yang terdapat pada beras hitam seperti
seperti Fe, Zn, Mn dan P (Kristamtini, Taryono, Basunanda, Murti, Supriyanta,
Widyayanti et al., 2012).
B. Senyawa Fenolik
Definisi umum mengenai senyawa fenolik adalah setiap komponen yang
mengandung cincin benzen dengan satu atau lebih gugus hidroksil. Contoh senyawa
fenolik adalah asam fenolik, flavonoid, tanin terkondensasi, kumarin, dan alkil
resorsinol (Dykes and Rooney, 2007). Selama dua dekade terjadi peningkatan
penelitian yang menunjukkan efek perlindungan oleh senyawa polifenol yang ada
pada tanaman. Efek tersebut antara lain antioksidan, antiinflamasi, antiproliferative,
antimutagenik, antimikrobial, antikarsinogenik, dan pencegahan terhadap penyakit
jantung (Ghosh and Konishi, 2007). Senyawa fenolik yang terdapat pada sayuran,
buah-buahan, rempah, dan obat herbal dapat digunakan untuk pencegahan terhadap
terjadinya penyakit kanker. Polifenol pada teh dan beberapa komponen yang
terdapat pada tanin menunjukkan efek sebagai antikarsinogenik (Chaisawvong and
Sangsrichan, 2009).
Senyawa antioksidan merupakan derivat dari senyawa fenol. Fenol
merupakan pendonor hidrogen yang baik yang dapat menjebak senyawa radikal
contohnya adalah superoxide anion yang berasal dari metabolisme sel atau dari asap
rokok, karena adanya penghambatan tersebut menyebabkan reaksi berantai dari
senyawa radikal tersebut dapat dihentikan. Radikal fenoksi yang terbentuk sebagai
efek resonansi. Karena alasan ini maka derivat dari fenol atau polifenol merupakan
donor hidrogen yang baik yang dapat menghambat reaksi yang terjadi oleh senyawa
radikal. Senyawa fenol juga disebut sebagai inhibitor radikal (Togo, 2004).
Gambar 1. Reaksi pembentukan radikal fenoksi menurut Togo (2004)
C. Metode Folin-Ciocalteu
Pengukuran kandungan fenolik total dapat menggunakan reagen
Folin-Ciocalteu. Metode Folin-Ciocalteu digunakan untuk menentukan polifenol secara
kolorimetri. Reaksi senyawa Folin-Ciocalteu melalui oksidasi dan reduksi senyawa
fenolik pada medium alkali akan menghasilkan kompleks molybdenum-tungstat
yang berwarna biru dengan absorbsi serapan maksimum pada 730-770 nm. Warna
yang terbentuk akan makin pekat setara dengan konsentrasi senyawa fenolik yang
terdapat pada larutan uji (Suteerapataranon and Pudta, 2008).
Pereaksi Folin-Ciocalteu merupakan suatu larutan kompleks polimerik
yang terbentuk dari asam fosfomolibdat dan asam hetero poli fosfotungstat.
Pereaksi ini terbuat dari air, natrium tungstat, natrium molibdat, asam fosfat, asam
klorida, litium sulfat, dan bromin. Penentuan kadar fenolik total dapat
menggunakan standar asam galat, karena asam galat lebih stabil apabila digunakan
sebagai standar. Asam galat juga merupakan senyawa fenol yang memiliki aktivitas
Prinsip dari metode Folin-Ciocalteu adalah kemampuan reduksi dari gugus
fungsional senyawa fenol. Oksidasi dan reduksi ion fenolat terjadi pada suasana
basa. Terjadinya reduksi kompleks fosfotungstat-fosfomolibdenum (reagen
Folin-Ciocalteu) akan merubah pereaksi tersebut menjadi berwarna biru. Warna yang
terbentuk akan makin pekat setara dengan meningkatnya kadar fenolik dalam
sampel. Penentuan kandungan fenolik total dapat ditentukan menggunakan reagen
Folin-Ciocalteu dengan standar asam galat dan hasil pengukuran dinyatakan
sebagai massa ekivalen asam galat (Arbianti, Utami, Kurmana and Sinaga, 2007).
D. Radikal Bebas
Radikal bebas didefinisikan sebagai suatu molekul atau fragmen molekul
yang mengandung satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan di dalam atom
atau orbital molekul. Elektron yang tidak berpasangan ini akan menyebabkan
radikal bebas ini bersifat reaktif (Valko, Leibfritz, Mocol, Cronin, Mazur and Telser,
2006). Karena sifat reaktif dari suatu senyawa radikal bebas, sehingga senyawa ini
dapat bereaksi dengan, protein, lipid, karbohidrat dan DNA. Radikal bebas akan
menyerang molekul stabil yang ada paling dekat di sekitarnya kemudian
mengambil elektron dari molekul tersebut. Karena molekul yang diserang radikal
bebas mengalami kehilangan elektronnya sendiri maka molekul itu dapat menjadi
radikal dan menyerang molekul stabil lainnya. Karena alasan inilah maka radikal
bebas dapat menyebabkan terjadinya reaksi yang berantai (Badarinath,
Mallikarjuna, Chetty, Ramkanth, Rajan and Gnanaprakash, 2010). Senyawa
fosfolipid terdapat pada semua membran biologis yang merupakan substrat yang
dengan reaksi autooksidasi. Mekanisme dari reaksi autooksidasi terdiri dari 3 tahap,
yaitu insiasi, propagasi dan terminasi (Pokorny et al., 2001).
Secara normal tubuh akan memproduksi radikal sebagai hasil dari
metabolisme sel. Radikal yang terbentuk dapat menjadi berbahaya karena tidak
adanya keseimbangan antara antioksidan dalam tubuh. Radikal yang terbentuk
dapat berupa derivat oksigen atau yang biasanya disebut dengan Reactive Oxygen
Species (ROS) dan derivat dari nitrogen yang disebut dengan Reactive Nitrogen
Species (RNS). Molekul dari derivat oksigen yang bersifat sebagai radikal reaktif,
yaitu superoxide anion radical, radical hydroxyl, peroxyl, dan alkoxyl, sedangkan
derivat oksigen yang tidak bersifat reaktif, yaitu hydrogen peroxide. Radikal bebas
yang berasal dari derivat nitrogen, yaitu nitric oxide dan peroxynitrite anion. Bila
ROS menyerang bagian sel dalam tubuh disebut dengan stres oksidatif (oxidative
strees), sedangkan bila RNS menyerang bagian sel dalam tubuh manusia disebut
stres nitrosatif (nitrosative strees) (Badarinath et al., 2010).
Stres oksidatif disebabkan karena sel tubuh memerlukan oksigen untuk
melakukan metabolisme di mitokondria. Hasil metabolisme tersebut selain
menghasilkan energi dalam bentuk adenosin triphosphate (ATP) juga
menghasilkan senyawa radikal ROS. Kelebihan ROS yang terbentuk dapat
menyebabkan terjadinya efek yang berbahaya, karena senyawa-senyawa tersebut
dapat merusak lipid seluler, protein dan DNA, kemudian akan mengubah fungsi
Stres nitrosatif disebabkan oleh nitric oxide yang merupakan radikal yang
dihasilkan dalam tubuh. Stres nitrosatif kemudian dapat mengubah struktur protein
dan menghambat fungsi normal protein tersebut. Ketika terjadinya proses inflamasi,
sel imun akan memproduksi superoxide anion radical dan nitric oxide. Pada
keadaan ini superoxide anion radical dan nitric oxide akan bereaksi membentuk
suatu produk dengan jumlah yang signifikan yang disebut dengan peroxynitrite
anion. Senyawa peroxynitrite anion merupakan agen oksidasi yang poten yang
dapat menyebabkan fragmentasi DNA dan oksidasi lipid (Valko et al., 2006).
E. Antioksidan
Antioksidan dalam dunia kesehatan memiliki peran yang sangat penting
karena senyawa tersebut secara klinis terbukti dapat mengurangi resiko terhadap
beberapa penyakit kronis seperti penyakit jantung dan diabetes. Karakteristik utama
dari senyawa antioksidan dalam pencegahan beberapa penyakit ini dikarenakan
kemampuan antioksidan dalam menangkap radikal bebas. Karena sifat reaktif dari
radikal bebas tersebut, sehingga dapat mengangguan fungsi normal sel dan dapat
menyebabkan terjadinya beberapa penyakit degeneratif. Karena adanya masalah
tersebut oleh karena itu, diperlukan suatu metode yang dapat mencegah terhadap
pengaruh buruk dari senyawa radikal bebas (Kuntorini dan Astuti, 2010).
Metode untuk mencegah terhadap pengaruh adanya radikal adalah dengan
menggunakan bahan spesifik yang dapat mencegah terjadinya radikal bebas atau
saat ini lebih dikenal dengan senyawa antioksidan. Antioksidan pertama kali
2001). Antioksidan sendiri merupakan senyawa kimia yang dapat menyumbangkan
satu atau lebih elektron kepada radikal bebas, sehingga radikal bebas tersebut
menjadi tidak reaktif dan reaksi berantai dapat dihentikan. Tubuh manusia
mempunyai cadangan antioksidan seperti glutation yang dapat melawan efek
negatif dari radikal bebas akan tetapi hanya tersedia dalam jumlah terbatas. Oleh
karena itu, diperlukan antioksidan eksogen yang dapat digunakan untuk mencegah
efek negatif dari radikal bebas. Penggunaan antioksidan saat ini makin meluas
dikarenakan meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai peran dari
antioksidan dalam mencegah berbagai penyakit seperti penyakit jantung,
aterosklerosis, kanker serta gejala penuaan yang ditimbulkan oleh senyawa radikal
bebas (Kuncahyo dan Sunardi, 2007).
Berdasarkan sumbernya antioksidan digolongkan menjadi dua tipe, yaitu
antioksidan sintetik dan antioksidan alami. Antioksidan sintetik yang cukup populer
dan merupakan senyawa fenolik adalah BHA, BHT, TBHQ dan ester dari asam galat
contohnya PG (Pokorny et al., 2001). Penggunaan antioksidan sintetik mulai
diwaspadai karena efek toksik yang mungkin ditimbulkan bila digunakan dalam
jangka waktu lama. Oleh karena itu, diperlukan alternatif lain dalam melawan
senyawa radikal bebas, yaitu dengan menggunakan antioksidan alami yang dinilai
lebih aman (Olajire and Azeez, 2011). Antioksidan alami sudah digunakan dalam
waktu yang lama. Antioksidan alami biasanya ditemukan pada tanaman dan
utamanya merupakan senyawa fenolik. Sebagai contoh senyawa antioksidan alami
adalah tokoferol, flavonoid, dan asam fenolik. Tokoferol dapat diklasifikasikan
yaitu α , β , ƴ , δ . Flavonoid merupakan senyawa fenolik yang terdapat pada tanaman
yang memiliki struktur dasar C6-C3-C6 dengan terikat pada dua cincin aromatis.
Contoh senyawa flavonoid adalah epigenin, antosianin, quersetin dan lain-lain
(Pokorny et al., 2001).
Beradasarkan mekanisme kerjanya antioksidan dibagi menjadi dua, yaitu
antioksidan enzimatik dan antioksidan non enzimatik. Antioksidan enzimatik
terdiri dari superoxide dismutase (SOD), glutathione peroxidase (GPx), catalase
(CAT), sedangkan antioksidan non enzimatik antara lain adalah ascorbic acid
(vitamin C),α -tocopherol (vitamin E), gluthathione (GSH), carotenoid, flavonoids,
dan antioksidan lainnya. Baik antioksidan enzimatik maupun antioksidan
non-enzimatik keduanya sama-sama berfungsi untuk mencegah terhadap pengaruh
buruk radikal bebas (Valko et al., 2006).
F. Metode DPPH
Pengujian aktivitas antioksidan suatu senyawa dapat menggunakan
metode DPPH. DPPH merupakan suatu radikal bebas yang stabil, kestabilan dari
radikal DPPH disebabkan oleh adanya delokalisasi pasangan elektron secara
menyeluruh. Biasanya senyawa antioksidan adalah senyawa fenol yang mempunyai
gugus hidroksi (-OH) yang dapat mendonorkan atom hidrogen kepada radikal
DPPH (Sulistiyowati, Cahyono dan Swastawati, 2013). Metode DPPH memberikan
serapan kuat pada panjang gelombang 517 nm yang menghasilkan warna violet
gelap. Prinsip dari metode DPPH adalah melalui donor elektron oleh senyawa
antioksidan menyebabkan elektron pada radikal DPPH menjadi berpasangan
kemudian akan terjadi pemudaran warna larutan DPPH yang sebanding dengan
jumlah elektron yang diambil. Makin kuat kemampuan senyawa antioksidan dalam
menangkal radikal DPPH maka warna yang dihasilkan juga akan makin memudar
(Kuncahyo dan Sunardi, 2007).
Pengujian senyawa antioksidan secara kuantitatif dapat menggunakan
metode DPPH karena uji senyawa antioksidan dengan metode tersebut cukup
sederhana, mudah, cepat, peka dan memerlukan sedikit sampel. Uji aktivitas
penangkapan radikal DPPH dapat dinyatakan dalam nilai IC50. Nilai IC50
menunjukkan konsentrasi senyawa antioksidan yang dibutuhkan untuk
menghambat 50 % radikal DPPH (Kuntorini dan Astuti, 2010). Makin kecil nilai
IC50 menunjukkan makin besarnya kemampuan antioksidan suatu senyawa yang
digunakan (Kristiana, Ariviani dan Khasanah, 2012).
G. Ekstraksi
Ekstraksi merupakan peristiwa perpindahan masa suatu zat aktif yang
semula berada di dalam sel kemudian akan ditarik oleh cairan penyari, sehingga zat
aktif dalam sampel tersebut dapat larut dalam cairan penyari. Penyarian simplisia
akan makin efektif bila permukaan serbuk simplisia yang bersentuhan dengan
cairan penyari makin luas, sehingga dengan demikian makin luas permukaan serbuk
simplisia maka proses penyarian juga akan makin baik. Cairan penyari yang
terus-menerus mendesak zat yang terkandung dalam simplisia tersebut (Depkes RI,
1986).
Maserasi berasal dari kata macerase yang berarti mengairi, melunakkan.
Maserasi merupakan cara ekstraksi yang paling sederhana, yaitu dengan
menghaluskan simplisia dengan dipotong-potong hingga berbentuk serbuk
kemudian disatukan dengan bahan pengekstraksi. Hasil rendaman tersebut
kemudian disimpan di tempat yang terlindung cahaya langsung dan dikocok
kembali. Lama waktu untuk melakukan maserasi berbeda-beda. Farmakope
Indonesia mencantumkan waktu maserasi dapat dilakukan antara 4-10 hari.
Berdasarkan pengalaman waktu maserasi yang paling memadai adalah lima hari.
Pada saat melakukan maserasi, sampel yang direndam dalam cairan penyari harus
dilakukan penggojokan berulang kira-kira dua sampai tiga kali sehari (Voigt, 1995).
Maserasi digunakan untuk menyari simplisia yang mengandung zat aktif
yang mudah larut dalam cairan penyari yang digunakan. Simplisia yang digunakan
juga tidak boleh mudah mengembang dalam cairan penyari. Cairan penyari yang
dapat digunakan dengan metode maserasi dapat berupa air, etanol, air-etanol atau
pelarut lain (Depkes RI, 1986).
H. Spektrofotometri
Spektrofotometer adalah suatu instrumen yang digunakan untuk
mengetahui serapan atau emisi radiasi elektromagnetik sebagai fungsi dari panjang
gelombang. Satuan yang digunakan untuk menyatakan panjang gelombang adalah
gelombang adalah lamda (λ ). Sinar ultraviolet mempunyai panjang gelombang
antara 200-400 nm, sedangkan visible mempunyai panjang gelombang antara
400-750 nm (Gandjar dan Rohman, 2007).
Absorbsi cahaya ultraviolet atau cahaya tampak akan mengakibatkan
terjadiya transisi elektron. Transisi elektron didefinisikan sebagai promosi elektron
dari orbital keadaan dasar yang berenergi rendah ke orbital keadaan tereksitasi yang
berenergi lebih tinggi. Panjang gelombang cahaya ultraviolet dan cahaya tampak
akan berbeda-beda untuk tiap senyawa tergantung pada mudahnya promosi elektron.
Makin besar energi yang dibutuhkan oleh molekul untuk mempromosikan elektron,
maka panjang gelombang yang diserap akan makin pendek. Sebaliknya makin kecil
energi yang dibutuhkan untuk promosi elektron maka panjang gelombang yang
diserap juga akan makin besar. Senyawa berwarna akan menyerap cahaya pada
daerah tampak dan memiliki elektron yang mudah untuk dipromosikan
dibandingkan senyawa yang tidak berwarna akan memiliki panjang gelombang
ultraviolet yang lebih pendek. Secara umum transisi elektron yang terlibat dalam
penyerapan radiasi ultraviolet dan visibel adalah elektron sigma, elektron phi, dan
elektron bukan ikatan atau non bonding electron (Fessenden dan Fessenden, 1995).
Pada analisis kuantitatif pengukuran dilakukan dengan menembakkan
berkas radiasi pada sampel yang digunakan. Radiasi yang diserap oleh cuplikan
kemudian dapat ditentukan dengan membandingkan antara sinar yang diteruskan
dengan sinar yang ditangkap. Penggunaan spektrofotometri visibel harus
1. Untuk senyawa yang tidak berwarna dapat dilakukan dengan mereaksikan
terlebih dahulu senyawa tersebut menjadi senyawa yang berwarna sehingga dapat
diukur.
2. Waktu operasional (operating time).
Tujuan menentukan operating time adalah untuk mengetahui waktu
pengukuran yang tepat hingga didapatkan absorbansi yang stabil.
3. Pemilihan panjang gelombang
Untuk analisis kuantitatif, panjang gelombang yang digunakan adalah
panjang gelombang yang memiliki absorbansi yang paling maksimal.
4. Pembuatan kurva baku
Kurva baku merupakan hubungan antara absorbansi (y) dan konsentrasi
(x). Kurva baku yang baik bila nilai koefisien korelasi (r) yang dihasilkan
mendekati +1 atau -1.
5. Pembacaan absorbansi sampel
Pengukuran absorbansi dengan spektrofotometer disarankan adalah antara
0,2-0,8 nm (Gandjar dan Rohman, 2007).
I. Validasi Metode Analisis
Paramater dalam melakukan analisis suatu metode antara lain mencakup
1. Presisi
Presisi atau ketepatan dalam suatu metode analisis dapat tercapai apabila
dalam satu seri pengukuran mempunyai selisih yang sangat kecil antara yang satu
dengan yang lain. Nilai presisi dinyatakan dalam Standar Deviation Relative (RSD)
atau yang biasa dikenal dengan koefisien variasi (CV) yang merupakan ukuran
ketepatan relatif dan umumnya dinyatakan dalam persen. Makin kecil nilai RSD
dari hasil pengukuran maka dapat dikatakan metode yang digunakan memiliki
presisi yang makin tepat. Rumus perhitungan SD dan RSD dijabarkan sebagai
berikut:
SD = ( )
RSD = x100%
x adalah nilai dari masing-masing pengukuran, x mean adalah rata-rata (mean) dari
pengukuran, N adalah frekuensi penetapan, SD adalah Standar deviasi, dan N-1
adalah derajat kebebasan (Gandjar dan Rohman, 2007).
Tabel I. Nilai presisi yang dapat diterima menurut APVMA (2004) Kadar zat aktif
(%)
Nilai RSD yang masih dapat diterima (%)
>10 < 2
1-10 < 5
0, 1-1 < 10
2. Linearitas
Linearitas adalah kemampuan suatu metode analisis memberikan respon
yang secara langsung atau dengan bantuan transformasi matematik yang baik,
proporsional terhadap konsentrasi analit dalam sampel. Linearitas dapat dinyatakan
dengan persamaam y = bx + a (Harmita, 2004). Menurut APVMA (2004) koefisien
korelasi yang baik bila r> 0,99.
3. Spesifisitas.
Adalah kemampuan suatu metode untuk mengukur analit yang digunakan
tanpa adanya intervensi dengan komponen lain yang ada di dalam campuran larutan
tersebut. Dengan adanya spesifisitas suatu metode, sehingga memungkinkan untuk
mencegah adanya senyawa lain yang bukan merupakan tujuan dari penelitian dapat
terdeteksi oleh instrumen yang digunakan (APVMA, 2004).
J. Landasan Teori
Radikal bebas adalah molekul atau fragmen molekul yang memiliki
elektron yang tidak berpasangan pada atom atau orbital molekul, sehingga senyawa
ini bersifat reaktif dan dapat menyerang molekul yang ada di dalam tubuh manusia
untuk mendapatkan pasangan elektron. Dalam tubuh radikal bebas dapat
menyerang protein, lipid, karbohidrat dan DNA, sehingga dapat menyebabkan
terjadinya beberapa penyakit seperti kanker, inflamasi, jantung, penuaan dini dan
penyakit degeneratif lainnya. Secara normal di dalam tubuh terbentuk radikal bebas
berbahaya bila tidak adanya keseimbangan antara radikal bebas yang terbentuk
dengan antioksidan dalam tubuh.
Berdasarkan sumbernya antioksidan dibagi menjadi dua, yaitu antioksidan
alami dan antioksidan sintetik. Antioksidan alami diperoleh dari tanaman dan
biasanya merupakan senyawa fenolik, sedangkan antioksidan sintetik sebagai
contohnya adalah BHA, BHT, TBHQ, dan propil galat. Penggunaan antioksidan
sintetik sudah mulai ditinggalkan karena antioksidan sintetik bila digunakan dalam
jangka waktu lama dapat menjadi promotor terhadap penyakit tumor dan kanker.
Berdasarkan mekanisme kerjanya antioksidan dibedakan menjadi dua, yaitu
antioksidan enzimatik dan antioksidan non enzimatik.
Beras hitam mengandung antosianin, protein, vitamin, mineral dan
kandungan serat yang tinggi. Kemampuan aktivitas antioksidan dari beras hitam
disebabkan karena kandungan fenolik yang terdapat pada beras hitam. Senyawa
fenolik bekerja dengan cara mereduksi radikal bebas, sehingga reaksi berantai dapat
dihentikan.
Penentuan kandungan fenolik total dapat menggunakan metode
Folin-Ciocalteu. Prinsip dari metode ini adalah dengan adanya oksidasi senyawa fenolik
dan reduksi kompleks fosfotungstat-fosfomolibdenum (reagen Folin-Ciocalteu)
yang menghasilkan kompleks berwarna biru. Warna yang terbentuk akan makin
Penentuan aktivitas antioksidan dapat menggunakan metode DPPH.
Prinsip dari metode DPPH adalah adanya reduksi radikal DPPH oleh senyawa
antioksidan yang menyebabkan pemudaran warna DPPH. Biasanya senyawa
antioksidan adalah senyawa fenol yang dapat mendonorkan elektronnya kepada
radikal DPPH. Kemampuan aktivitas antioksidan suatu senyawa makin meningkat
sebanding dengan penurunan intensitas warna larutan DPPH.
K. Hipotesis
Fraksi air ekstrak etanolik beras hitam memiliki kandungan senyawa
fenolik yang dinyatakan sebagai massa ekivalen asam galat per gram fraksi air
ekstrak etanolik beras hitam dan memiliki aktivitas antioksidan yang lebih besar
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Rancangan Penelitian
Penelitian yang dilakukan termasuk observasional dan eksperimental
dengan rancangan acak sederhana.
B. Variabel Penelitian
1. Variabel bebas berupa konsentrasi fraksi air ekstrak etanolik beras hitam.
2. Variabel tergantung berupa aktivitas antioksidan fraksi air ekstrak etanolik beras
hitam untuk menangkap radikal DPPH (% IC).
3. Variabel pengacau terkendali berupa tempat tumbuh, waktu pemanenan, dan
cara panen beras hitam.
4. Variabel pengacau tidak terkendali berupa cahaya matahari, cuaca, komposisi
senyawa dalam ekstrak, dan curah hujan.
C. Definisi Operasional
1. Ekstrak etanolik beras hitam adalah sari hasil proses maserasi beras hitam
dengan penyari etanol 70 % yang kemudian diuapkan dengan vacuum rotary
evaporator.
2. Fraksi air adalah hasil dari ekstrak etanolik yang dilarutkan dengan air hangat,
kemudian difraksinasi dengan menggunakan wasbensin. Fraksi air yang
didapatkan kemudian difraksinasi lebih lanjut menggunakan etil asetat,
3. Persen inhibition concentration (% IC) adalah persen yang menyatakan
kemampuan fraksi air ekstrak etanolik beras hitam untuk menangkap radikal
DPPH.
4. Inhibition concentration 50 (IC50) adalah nilai konsentrasi dari fraksi air ekstrak
etanolik beras hitam yang dapat menghasilkan penangkapan sebesar 50 %
radikal DPPH.
D. Bahan dan Alat Penelitian 1. Bahan penelitian
Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah beras hitam (Oryza sativa
L. subsp. indica) yang diperoleh di daerah Ledokwareng, Sardonoharjo, Ngaglik,
Sleman, Yogyakarta. akuades (Laboratorium Farmasi Fisika Fakultas Farmasi
Universitas Sanata Dharma); bahan kualitas pro analitik E. Merck meliputi:
metanol, bahan kualitas pro analitik Sigma Chem. Co., USA, yaitu: DPPH
(1,1-difenil-2 pikrilhidrazil), reagen Folin-Ciocalteu dan rutin, asam galat; bahan
kualitas teknis Brataco Chemica, yaitu wasbensin dan etil asetat; bahan kualitas
teknis CV. General Labora, yaitu aluminium foil.
2. Alat penelitian
Blender, neraca analitik (Scaltec SBC 22, BP 160P), vacuum rotary
evaporator (Janke & Kunkel), waterbath (labo-tech, Heraeus), vortex (Janke &
Kunkel), spektrofotometer UV-Vis (Perkin Elmer Lamda 20), corong Buchner,
oven, mikropipet 10-1000 µl; 1-10 ml (Acura 825, Socorex), tabung reaksi bertutup,
dan alat-alat gelas yang lazim digunakan di laboratorium analisis (Pyrex-Germany
E. Tata Cara Penelitian 1. Determinasi beras hitam
Determinasi beras hitam dilakukan di Laboratorium Biologi Farmasi,
Fakultas Farmasi USD menurut USDA (2012).
2. Pengumpulan bahan
Beras hitam diperoleh dari hasil pertanian di daerah Ledokwareng
Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman. Pengambilan beras hitam dengan kriteria berwarna
hitam segar dan pada saat usia sekitar 4-5 bulan.
3. Preparasi sampel
Sebanyak 100 g beras hitam segar, dibersihkan, lalu dikeringkan anginkan
pada suhu ruangan. Kemudian beras dihaluskan dengan blender. Beras yang telah
dihaluskan dituang ke dalam bejana maserasi, ditambah cairan penyari etanol
sampai terendam sempurna, dan dicampur homogen.
Campuran dimaserasi selama lima hari pada suhu ruangan. Filtrat
diperoleh melalui penyaringan menggunakan kertas saring dengan bantuan corong
Buchner dan pompa vakum. Ampas penyaringan diremaserasi dengan etanol
secukupnya selama lima hari. Kemudian filtratnya dicampurkan dengan filtrat
terdahulu. Keseluruhan filtrat yang diperoleh diuapkan pelarutnya hingga diperoleh
ekstrak etanolik beras hitam.
4. Pembuatan fraksi air
Ekstrak etanolik beras hitam ditambah 300 ml air hangat dan dilakukan
wasbensin (1:1 v/v), kemudian didiamkan sampai terpisah sempurna. Fase air akan
berada pada bagian bawah, sedangkan fase wasbensin berada pada bagian atas.
Dari hasil ekstraksi cair-cair tersebut diperoleh dua fraksi, yaitu fraksi
wasbensin dan fraksi air. Selanjutnya, fraksi air diekstraksi lagi menggunakan etil
asetat dengan perbandingan larutan fraksi air : etil asetat (1:1 v/v), sehingga
didapatkan fraksi air dan etil asetat. Setelah dipisahkan fraksi air diuapkan dengan
vacuum rotary evaporator. Lalu fraksi yang telah kering digunakan untuk analisis
lebih lanjut.
5. Pembuatan larutan DPPH, pembanding, dan uji
a. Larutan uji untuk penentuan kandungan fenolik total
Sebanyak 9,5 mg fraksi air ditimbang, kemudian diencerkan dengan metanol
p.a sampai 10 ml, sehingga didapatkan konsentrasi sebesar 950 μ g/ml.
b. Pembuatan larutan asam galat
Sebanyak 25 mg asam galat ditimbang dan diencerkan dengan metanol p.a :
aquadest (1:1) sampai 50 ml sehinggga didapatkan konsentrasi 500 μ g/ml. Diambil
sebanyak 2; 3; 4; 5; 6 ml larutan tersebut kemudian diencerkan dengan metanol p.a :
aquadest (1:1) hingga 25 ml kemudian akan diperoleh larutan asam galat dengan
konsentrasi 40; 60; 80; 100; 120 μ g/ml.
c. Pembuatan larutan DPPH
Sejumlah DPPH dilarutkan ke dalam metanol p.a, sehingga diperoleh
larutan DPPH dengan konsentrasi 0,4 mM. Larutan tersebut ditutup dengan
d. Pembuatan larutan stok rutin
Sebanyak 2,5 mg stok rutin ditimbang dan ditambahkan metanol p.a
hingga 10 ml.
e. Pembuatan larutan seri
Diambil 0,5; 1,0; 1,5; 2, dan 2,5 larutan stok rutin dan diencerkan dengan
metanol p.a hingga 25 ml pada labu ukur, sehingga akan diperoleh larutan dengan
konsentrasi 5; 10; 15; 20; 25μ g/ml.
f. Pembuatan larutan uji aktivitas antioksidan dari ekstrak beras hitam
Sebanyak 25 mg ekstrak ditimbang dan dilarutkan dengan metanol p.a
sampai 25 ml dan didapatkan konsentrasi 1 mg /ml. Dari larutan tersebut diambil
sebanyak 0,5; 1; 1,5; 2 dan 2,5 ml lalu ditambahkan dengan metanol p.a hingga 10
ml, sehingga didapat konsentrasi 50; 100; 150; 200; 250μ g/ml.
6. Uji pendahuluan
a. Uji fenolik
Sejumlah 0,5 ml larutanuji 950 μ g/ml dan larutan pembandingasam galat
120 μ g/mldimasukkan masing-masing dalam tabung reaksi dan ditambahkan 2,5
ml larutan reagen Folin-Ciocalteu yang diencerkan dengan aquadest (1/10 v/v).
Larutan tersebut kemudian ditambahkan dengan 7,5 ml natrium bikarbonat 1M.
Setelah 10 menit warna larutan diamati.
b. Uji pendahuluan aktvitas antioksidan
Sebanyak 1 ml larutan DPPH dimasukkan dalam masing-masing 3 tabung
reaksi. Pada masing-masing tabung reaksi kemudian ditambahakan dengan 1 ml
larutan uji konsentrasi 150 µg/ml. Selanjutnya, diencerkan dengan 3 ml metanol p.a.
Larutan tersebut divortex 30 detik. Setelah 30 menit diamati perubahan warna yang
terjadi.
7. Optimasi metode penentuan kandungan fenolik total
a. Penentuan operating time (OT)
Dibuat larutan baku asam galat konsentrasi 40; 80; dan 120 µg/ml dan
masing-masing larutan diambil 0,5 ml dan ditambahkan dengan 5 ml reagen
Folin-Ciocalteu yang diencerkan dengan aquadest (1:1). Kemudian larutan tersebut
ditambahakan dengan 4 ml larutan natrium bikarbonat 1 M. Absorbansinya diukur
pada panjang gelombang 750 nm selama 30 menit. Pengerjaan dilakukan tiga kali
replikasi. Operating time tercapai ketika absorbansi larutan telah stabil.
b. Penentuan panjang gelombang maksimum
Dibuat larutan baku asam galat dengan konsentrasi 40; 80; dan 120 µg/ml
dan masing-masing diambil sebanyak 0,5 ml dan ditambahkan dengan 5 ml reagen
Folin-Ciocalteu yang telah diencerkan dengan air (1:1) kemudian larutan
ditambahkan 4 ml larutan natrium karbonat 1M. Didiamkan selama OT kemudian
diukur absorbansinya pada panjang gelombang 600-800 nm.
8. Penetapan kandungan fenolik total
a. Pembuatan kurva baku asam galat
Sebanyak 0,5 mL larutan asam galat 40; 60; 80; 100; dan 120 µg/ml
(1:10 v/v). Larutan selanjutnya ditambah dengan 4,0 ml natrium bikarbonat 1M.
larutan didiamkan selama OT, absorbansinya diukur pada panjang gelombang
maksimum terhadap blanko yang terdiri atas akuades : metanol p.a. (1:1), reagen
Folin-Ciocalteu, dan larutan natrium bikarbonat 1M. Pengerjaan dilakukan 3 kali.
b. Validasi metode penetapan kandungan fenolik total
Hasil dari prosedur 10 a divalidasi berdasarkan parameter presisi (% RSD),
linearitas (nilai r) serta spesifisitas (spektra kontrol).
c. Estimasi kandungan fenolik total larutan uji
Diambil 0,5 ml larutan uji 950 µg/ml, lalu dimasukkan ke dalam labu ukur
10 ml, dan dilanjutkan sebagaimana perlakuan pada pembuatan kurva baku asam
galat. Kandungan fenolik total dinyatakan sebagai massa ekivalen asam galat (mg
ekivalen asam galat per gram fraksi air). Dilakukan tiga kali replikasi.
9. Optimasi metode uji aktivitas antioksidan
a. Penentuan panjang gelombang maksimum
Pada tiga labu ukur 10 ml, dimasukkan masing- masing 0,4; 1,2; dan 2 ml
larutan DPPH 0,4 mM. Tiap labu ukur tersebut ditambahkan metanol p.a hingga
tanda batas, sehingga didapatkan konsentrasi DPPH sebesar 0,016; 0,048; dan
0,080 mM. Larutan tersebut divortex 30 detik. Larutan kemudian didiamkan selama
30 menit. Lalu dilakukan pengukuran absorbansinya dengan spektrofotometer
b. Penentuan operating time (OT)
Sejumlah larutan DPPH 0,4 mM dimasukkan ke dalam labu ukur sebanyak tiga
buah berukuran 5 ml. Kemudian masing-masing labu ukur ditambahkan dengan 1
ml larutan pembanding rutin 5; 15; dan 25 µg/ml kemudian ditambahkan metanol
p.a hingga tanda batas. Larutan tersebut divortex selama 30 detik. Setelah itu diukur
absorbansinya dengan spektrofotometri visible pada panjang gelombang hasil
pengukuran selama 1 jam. Perlakuan ini juga dilakukan untuk mencari OT dari
larutan uji fraksi air pada konsentrasi 50, 150, dan 250 µg/ml.
10. Pengujian aktivitas antioksidan
a. Pengukuran absorbansi larutan kontrol
Pada labu takar 5,0 ml, dimasukkan sebanyak 1,0 ml larutan DPPH 0,4
mM kemudian ditambahkan metanol p.a hingga tanda batas. Larutan tersebut
diukur absorbansinya pada saat OT dan panjang gelombang serapan maksimum.
Pengerjaan dilakukan sebanyak tiga kali. Larutan ini digunakan sebagai larutan
kontrol untuk menguji larutan pembanding dan larutan uji.
b. Pengukuran absorbansi larutan pembanding dan uji
Sebanyak 1,0 ml larutan DPPH 0,4 mM dimasukkan ke dalam
masing-masing labu ukur 5,0 ml kemudian ditambah dengan 1,0 ml larutan pembanding 5;
10; 15; 20; 25 μ g/ml dan larutan uji 50; 100; 150; 200; 250 μ g/ml. Selanjutnya,
tambahkan metanol p.a hingga tanda batas. Larutan tersebut kemudian divortex
spektrofotometer visibel pada panjang gelombang maksimum. Pengerjaan
dilakukan sebanyak tiga kali.
c. Validasi metode uji aktivitas antioksidan
Hasil dari prosedur 7 a dan b divalidasi berdasarkan parameter presisi (%
RSD), linearitas (nilai r) serta spesifisitas (spektra kontrol).
d. Prosedur 8 a dan b kemudian dihitung % IC dan IC50untuk rutin dan
fraksi air ekstrak etanolik beras hitam.
F. Analisis Hasil
Kandungan fenolik total dalam fraksi air ekstrak etanolik beras hitam
dihitung sebagai massa ekivalen asam galat per gram fraksi air ekstrak etanolik
beras hitam. Nilai absorbansi larutan uji dimasukkan ke dalam persamaan kurva
baku asam galat, sehingga diperoleh nilai ekivalensi larutan uji terhadap asam galat.
Kemudian dilakukan perhitungan lebih lanjut berdasarkan rumus di bawah.
Kandungan fenolik total
=
Aktivitas penangkapan radikal DPPH (% IC) dihitung dengan rumus :
% IC = 100 %
Data aktivitas dianalisis dan dihitung nilai IC50 melalui persamaan
regresi linear dengan sumbu x adalah konsentrasi larutan uji maupun larutan
bermakna antara IC50 antara larutan pembanding dan larutan uji kemudian
Skema Determinasi beras hitam
Pengumpulan bahan
Pembuatan ekstrak etanolik beras hitam dengan etanol 70 %
Gambar 2. Skema jalannya penelitian
Fraksi air
Ekstraksi cair-cair dengan etil asetat
Fraksi air (diuapkan dengan vacuum rotary evaporator) Fraksi etil asetat
Uji pendahuluan senyawa fenolik
Optimasi uji aktivitas antioksidan Optimasi metode penetapan
kandungan fenolik total
Validasi metode uji aktivitas antioksidan
Validasi metode penetapan
kandungan fenolik total Estimasi aktivitas antioksidan
Estimasi kandungan fenolik total Analisis statistik dengan program R Ekstraksi cair-cair dengan wasbensin
Pelarut diuapkan dengan vacuum rotary evaporator
Fraksi wasbensin
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Determinasi Beras Hitam
Langkah awal untuk melakukan suatu penelitian adalah dengan melakukan
determinasi. Determinasi bertujuan untuk memastikan kebenaran identitas beras
yang akan digunakan dalam penelitian, sehingga dapat menghindari kemungkinan
kesalahan dalam pengambilan sampel beras hitam. Determinasi beras hitam
dilakukan di Laboratorium Farmakognosi Fitokimia, Fakultas Farmasi Universitas
Sanata Dharma pada tanggal 14 Mei 2013 berdasarkan acuan dari USDA (2012).
Hasil determinasi menunjukkan bahwa memang benar beras yang digunakan adalah
(Oryza sativa L.). Hasil determinasi juga dikuatkan dengan adanya surat
determinasi beras (1 lampiran) yang disetujui oleh Laboratorium Kebun Tanaman
Obat Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
B. Hasil Pengumpulan Bahan
Beras yang digunakan diperoleh langsung dari distributor beras hitam di
daerah Ledokwareng, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta pada tanggal 26
Januari 2013. Beras hitam yang digunakan dalam penelitian ini merupakan beras
hitam budidaya yang ditanam melalui pertanian secara organik dan dikonsumsi oleh
masyarakat setempat. Beras hitam yang baik memiliki kriteria sebagai berikut yaitu,
bulan. Pemanenan dilakukan pada usia 4-5 bulan dikarenakan baik dari segi ukuran
dan warna beras hitam yang dihasilkan sudah cukup optimal. Makin pekat warna
beras hitam yang digunakan menunjukkan bahwa makin banyak pula metabolit
sekunder yang dihasilkan oleh beras hitam tersebut. Pemanenan dilakukan pada
musim kemarau dikarenakan beras merupakan makanan pokok bagi bangsa
Indonesia yang lazim digunakan masyarakat dalam bentuk beras kering. Beras yang
digunakan dalam bentuk kering untuk menghindari terhadap kelembaban, sehingga
dapat mencegah pertumbuhan mikroorganisme yang dapat menyebabkan terjadinya
penguraian metabolit sekunder yang ada dalam beras hitam yang digunakan. Selain
itu pemanenan dilakukan pada musim kemarau dikarenakan pada musim kemarau
beras hitam akan menyerap sinar matahari lebih banyak, sehingga menyebabkan
terbentuknya biosintesis metabolit sekunder pada beras hitam.
Beras hitam yang digunakan berumur 4-5 bulan dikarenakan metabolit
sekunder yang terkandung dalam beras hitam sudah cukup maksimal. Beras hitam
yang digunakan dalam kondisi baik, tidak berjamu, bebas dari serangga, kering,
tidak busuk, tidak terdapat pewarna, dan tidak terdapat bekas ulat. Kondisi pada
saat pengambilan sampel beras hitam harus diperhatikan karena kondisi yang tidak
baik dapat menyebabkan terjadinya perubahan kandungan kimia pada beras hitam.
C. Hasil Preparasi Sampel
1. Hasil ekstraksi sampel
Beras hitam yang akan digunakan sebelumnya dilakukan sortasi basah
partikel-partikel halus yang melekat pada sampel. Setelah itu beras hitam
dikeringkan pada di ruangan terbuka dan diangin-anginkan dengan tujuan
mencegah terhadap paparan cahaya matahari langsung yang dapat menyebabkan
penurunan aktivitas senyawa antioksidan pada sampel karena radiasi dari sinar
matahari. Setelah itu sampel beras hitam diblender untuk mendapatkan ukuran
partikel beras hitam yang lebih kecil, sehingga dengan begitu akan meningkatkan
luas permukaan sampel. Karena ukuran partikel sampel yang kecil dan luas
permukaan sampel yang besar, sehingga ketika diekstraksi dengan cairan penyari
maka kontak antara cairan penyari dengan sampel lebih besar dan efektivitas
penyarian akan lebih baik (Depkes RI, 1986). Efisiensi ekstraksi ini dapat
disebabkan karena makin banyak kontak antara sampel dengan cairan penyari,
sehingga memudahkan cairan penyari untuk menembus membran sel beras hitam
dan memungkinkan cairan penyari akan menarik senyawa kimia yang terdapat pada
beras hitam tersebut.
Ekstraksi menggunakan pelarut didasarkan pada kelarutan komponen yang
akan diekstraksi pada suatu sampel (Kristiana dkk., 2012). Pada penelitian ini
pelarut yang digunakan sebagai penyari adalah etanol. Pemilihan etanol sebagai
pelarut dikarenakan etanol lebih aman jika digunakan, selain itu harga etanol juga
lebih murah jika dibandingkan dengan pelarut metanol. Etanol juga merupakan
penyari yang efektif dan dapat mengekstraksi hampir semua senyawa bahan alam
yang terdapat pada tumbuhan (Kuntorini dan Astuti, 2010). Selain itu etanol bersifat
netral, tidak beracun, absorbsinya baik, kapang dan kuman sulit tumbuh pada
untuk melakukan ekstraksi adalah dengan cara maserasi. Metode tersebut dipilih
karena dapat dilakukan dengan cukup sederhana, tidak memerlukan peralatan
khusus dan tidak melibatkan pemanasan (Kuntorini dan Astuti, 2010). Bila
dibandingkan dengan metode ekstraksi seperti infundasi dan sokletasi yang
melibatkan pemanasan maka metode maserasi lebih disarankan. Secara umum
senyawa aktif dalam beras hitam tidak tahan terhadap pengaruh pemanasan oleh
karena itu, dengan metode maserasi yang tidak melibatkan pemanasan dapat
mencegah kemungkinan rusaknya metabolit aktif beras hitam. Metode maserasi
juga menggunakan jumlah pelarut yang lebih sedikit bila dibandingkan dengan
menggunaan metode perkolasi yang memerlukan banyak pelarut. Selain itu, dengan
menggunakan metode maserasi kontak antara cairan penyari juga lebih lama bila
dibandingkan dengan metode perkolasi, sehingga penyarian metabolit sekunder
dalam beras hitam juga akan lebih maksimal.
Maserasi dilakukan dengan merendam sejumlah serbuk ke dalam cairan
penyari selama lima hari kemudian dilakukan remaserasi ulang selama lima hari
lagi terhadap ampas hasil penyarian pertama. Remaserasi ini dimaksudkan untuk
memaksimalkan proses penyarian terhadap senyawa-senyawa dalam beras hitam
yang kemungkinan tidak ikut tersari karena sudah terjadi peristiwa kejenuhan dari
cairan penyari yang digunakan dalam proses ekstraksi. Waktu maserasi dilakukan
selama lima hari dikarenakan waktu tersebut merupakan waktu optimal dalam
melakukan maserasi. Selama proses maserasi berlangsung sampel tersebut dikocok
berulang-ulang kira-kira 2-3 kali sehari agar membantu dalam proses maserasi lebih