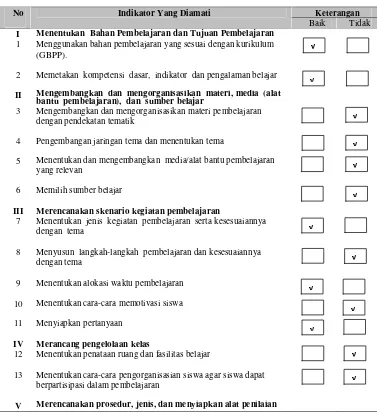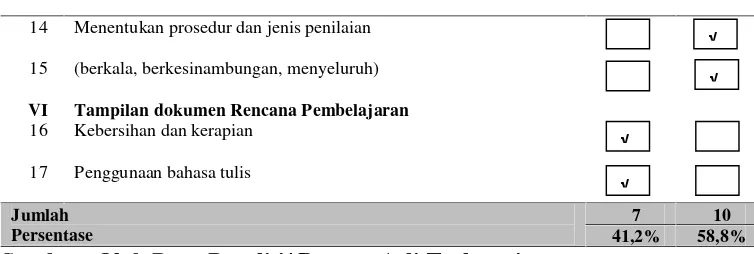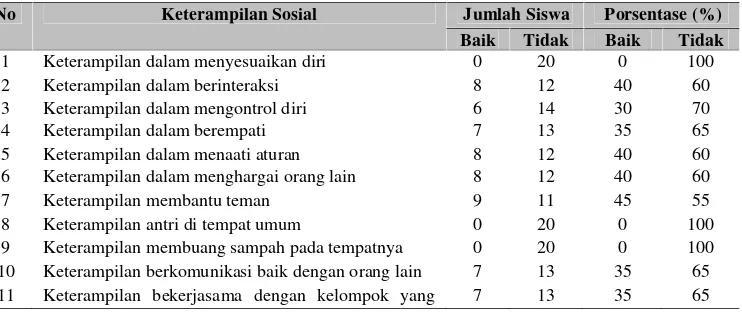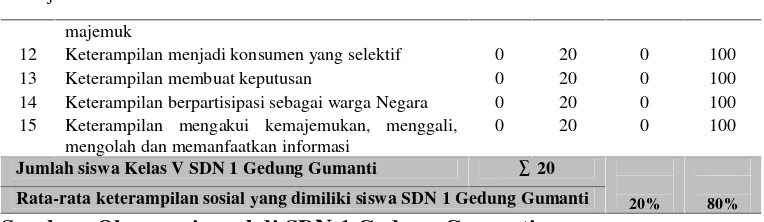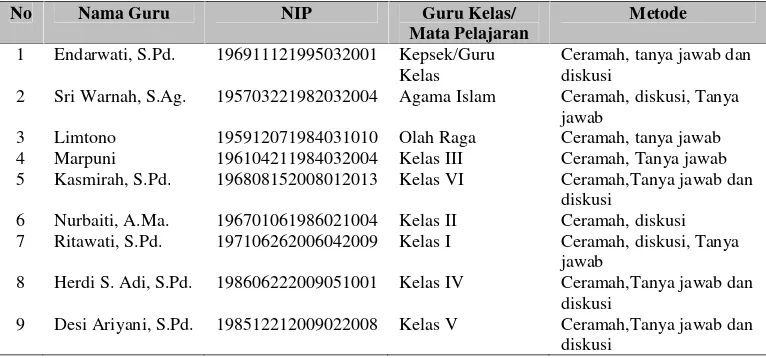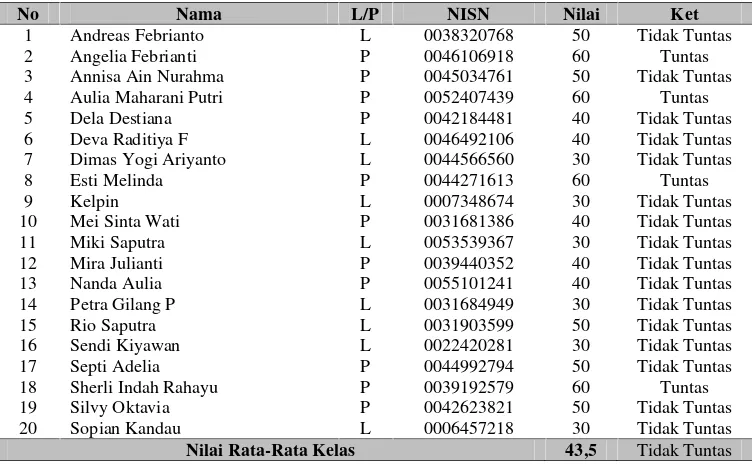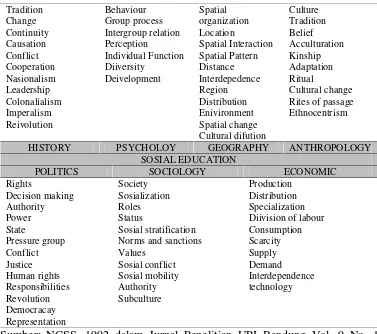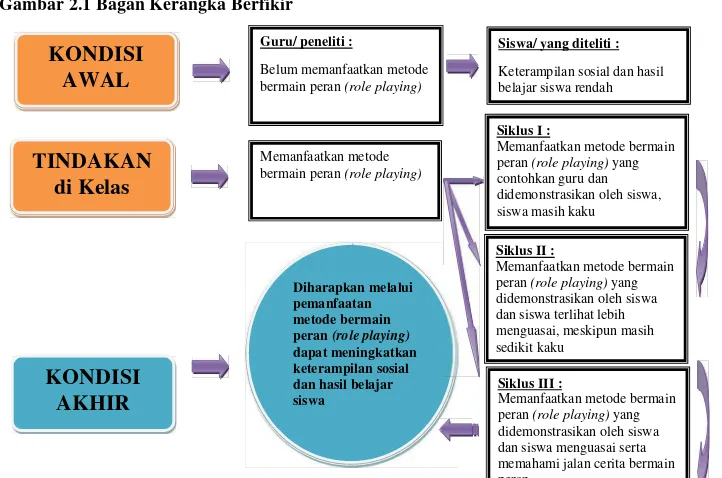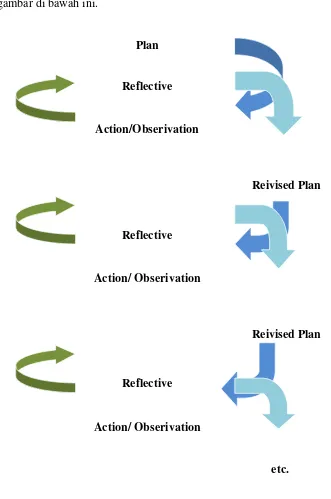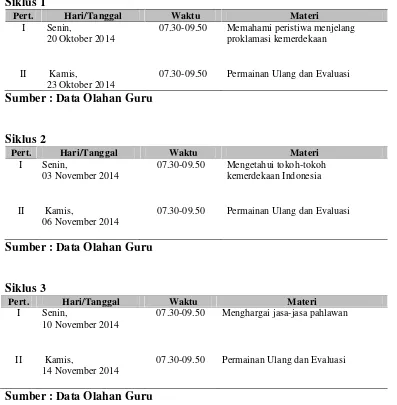IMPROVING OF SOCIAL SKILL AND STUDENTS ACHIEVEMENT THROUGH ROLE PLAY METHOD
By:
Marzius Insani
The aims of this research were improving of social skill and students achievement by using role play method. The method which was used in this research was class room action research. This research was conducted at SDN 1 Gedung Gumanti, Pesawaran and subject research was students of grade V in the first semester in academic year 2014/2015. This research was conducted in 3 cycle. Data collecting technique used observation sheet, interview, and test the analysis of the data used qualitative descriptive. The result showed that social skill of the students improved before cycle was 37,5%, after treatments in cycle III improved 86%, and average of student score had improvement from 43,5 before cycling, and 82,5 after treatment in cycle III. In short, role play method could be used as an interesting learning method for students so that it could be achieved the goal in learning like social skill and students achievement.
PENINGKATAN KETERAMPILAN SOSIAL DAN HASIL BELAJAR SISWA DENGAN MENGGUNAKAN METODE
BERMAIN PERAN (ROLE PLAYING) Oleh :
MARZIUS INSANI
Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan keterampilan sosial dan hasil belajar siswa dengan metode bermain peran (role playing). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian tindakan dilaksanakan di SD Negeri 1 Gedung Gumanti Kabupaten Pesawaran dengan subyek penelitian siswa kelas V semester ganjil tahun pelajaran 2014/2015. Penelitian dilaksanakan dalam tiga siklus. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik lembar observasi, lembar wawancara, dan tes. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian keterampilan sosial siswa mengalami peningkatan dari sebelum tindakan siklus sebesar 37,5%, setelah tindakan siklus III meningkat menjadi 86% dan rata-rata hasil belajar siswa mengalami peningkatan dari sebelum tindakan siklus sebesar 43,5, setelah tindakan siklus III meningkat menjadi 82,5. Kesimpulannya metode bermain peran dapat dikemas menjadi pembelajaran yang sangat menarik oleh siswa sehingga dapat mengasilkan tujuan pembelajaran yang diinginkan salah satunya adalah keterampilan sosial dan hasil belajar siswa.
BERMAIN PERAN (
ROLE PLAYING
)
Oleh
MARZIUS INSANI
Tesis
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
MAGISTER PENDIDIKAN IPS
Pada
Program Pascasarjana Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung
PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER PENDIDIKAN IPS
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
BERMAIN PERAN (
ROLE PLAYING
)
(Tesis)
Oleh
MARZIUS INSANI
PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER PENDIDIKAN IPS
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
Gambar Halaman
2.1. Bagan Kerangka Berfikir... 55
3.1 Bagan Kurt Lewins Prosedur Siklus Penelitian Tindakan... 59
3.2 Grafik Pengukuran dalam Merencanakan Pembelajaran... 87
3.3 Grafik Pengukuran dalam Melaksanakan Pembelajaran ... 88
3.4 Grafik Pengukuran Keterampilan Sosial Siswa... 89
4.1 Guru Memberikan Penjelasan Umum Mengenai Metode Bermain Peran(Role Playing)... 102
4.2 Guru Mengarahkan Siswa Untuk Memerankan Tokoh Yang Terdapat Dalam Skenario ... 102
4.3 Siswa Memulai Kegitan Pembelajaran Dengan Metode Bermain Peran (Role Playing)... 103
4.4 Grafik Evaluasi Perencanaan Pembelajaran Siklus I... 124
4.5 Grafik Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran Siklus I ... 127
4.6 Grafik Keterampilan Sosial Siswa Siklus I ... 129
4.7 Grafik Skor Rata-Rata Hasil Belajar Pada Siklus I ... 134
4.8 Siswa Mendengarkan Dengan Seksama Penjelasan Dari Guru Mengenai Metode Bermain Peran(Role Playing)... 147
4.9 Siswa Memulai Kegiatan Pembelajaran Dengan Metode Bermain Peran (Role Playing)... 147
4.10 Grafik Evaluasi Perencanaan Pembelajaran Siklus II ... 169
4.11 Grafik Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II... 172
4.12 Grafik Keterampilan Sosial Siswa Siklus II ... 175
4.13 Grafik Skor Rata-Rata Hasil Belajar Pada Siklus II... 180
4.14 Guru Memberikan Penjelasan Umum Mengenai Metode Bermain Peran (Role Playing)... 191
4.15 Siswa Memulai Kegiatan Pembelajaran Dengan Metode Bermain Peran (Role Playing)... 192
4.16 Grafik Evaluasi Perencanaan Pembelajaran Siklus III ... 203
4.17 Grafik Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran Siklus III ... 206
4.18 Grafik Keterampilan Sosial Siswa Siklus III... 209
4.19 Grafik Skor Rata-Rata Hasil Belajar Pada Siklus III ... 214
Halaman
DAFTAR TABEL ... i
DAFTAR GAMBAR ... ii
I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah ... 1
1.2 Identifikasi Masalah ... 14
1.3 Batasan Masalah ... 15
1.4 Rumusan Masalah ... 15
1.5. Tujuan Penelitian ... 16
1.6 Manfaat Penelitian ... 16
1.6.1 Secara Akademis ... 16
1.6.2 Secara Praktis ... 17
1.7 Ruang Lingkup Penelitian ... 18
1.7.1 Lingkung Kawasan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) ... 18
1.7.2 Objek Penelitian ... 20
1.7.3 Subjek Penelitian ... 20
1.7.4 Wilayah Penelitian ... 20
1.7.5 Waktu Penelitian ... 20
II. TINJUAN PUSTAKA 2.1 Keterampilan Sosial(Social Skill)...21
2.2 Hasil Belajar...24
2.3 Metode Bermain Peran (Role Playing Method) ...26
2.4 Belajar dan Pembelajaran...31
2.4.1 Teori Belajar Konstruktivisme...33
2.4.2 Teori Belajar Kognitivisme...35
2.5 Pembelajaran Afektif ...38
2.6 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)...40
2.6.1 Pembelajaran IPS Sekolah Dasar (SD) ...45
2.6.2 Dimensi Keterampilan(Skill)Dalam Pembelajaran IPS SD...46
2.6.3 Tujuan Pembelajaran IPS SD ...48
2.6.4 Ruang Lingkup Pembelajaran IPS SD ...49
2.7 Penelitian yang Relevan...50
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian ...64
3.4 Jadwal Penelitian...64
3.5 Lama Tindakan dan Indikator Keberhasilan ...65
3.5.1 Lama Tindakatan ...65
3.5.2 Indikator Keberhasilan ...67
3.6 Subjek dan Objek Penelitian ...68
3.6.1 Subjek Penelitian ...68
3.6.2 Objek Penelitian ...69
3.7 Operasional/ Skenario Penelitian Tindakan ...69
3.7.1 Metode Bermain Peran(role playing) ...70
3.7.2 Keterampilan Sosial(social skill)...70
3.7.3 Hasil Belajar...70
3.8 Teknik Pengumpulan Data ...70
3.8.1 Wawancara ...71
3.8.2 Dokumentasi ...72
3.8.3 Tes Hasil Belajar ...73
3.9 Instrumen Penelitian...74
3.9.1 Validitas ...84
3.9.2 Reliabilitas ...84
3.9.3 Tingkat Kesukaran ...85
3.9.4 Daya Pembeda...85
3.10 Pengukuran Keberhasilan...86
3.10.1 Pengukuran Guru dalam Merencanakan Pembelajaran ...86
3.10.2 Pengukuran Guru dalam Melaksanakan Pembelajaran...87
3.10.3 Pengukuran Keterampilan Sosial Siswa ...88
3.10.4 Pengukuran Ketuntasan Hasil Belajar...90
3.11 Teknik Analisis Data...90
3.11.1 Kategorisasi Data ...92
3.11.2 Validasi Data ...92
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 4.1 Hasil Penelitian ...94
4.1.1 Profil SD Negeri 1 Gedung Gumanti Pesawaran...94
4.1.2 Siklus I ...95
4.1.2.1 Perencanaan ...95
4.1.2.2 Pelaksanaan Tindakan...101
4.1.2.3 Observasi dan Evaluasi ...118
4.1.2.4 Analisis dan Refleksi ...134
4.1.2.5 Rekomendasi Perbaikan ...136
4.1.3 Siklus II ...138
4.1.3.1 Perencanaan ...138
4.1.3.2 Pelaksanaan Tindakan...146
4.1.3.3 Observasi dan Evaluasi ...164
4.1.3.4 Analisis dan Refleksi ...181
4.1.4.3 Observasi dan Evaluasi ...199
4.1.4.4 Analisis dan Refleksi ...214
4.1.4.5 Rekomendasi Perbaikan ...216
4.2. Pembahasan Hasil Penelitian ...217
4.2.1 Perencanaan Tindakan ...217
4.2.2 Pelaksanaan Tindakan...220
4.2.3 Keterampilan Sosial Siswa...226
4.2.4 Hasil Belajar Siswa ...232
4.3 Keterbatasan Penelitian...243
V. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan ...244
5.2 Saran...244
DAFTAR PUSTAKA ...246
MOTO
“
Allah tidak menutup mata-Nya
untuk kita yang berjuang
menuntut ilmu
”
Puji syukur kekhadirat Allah SWT dengan ketulusan dan keikhlasan serta
kerendahan hati kupersembahkan karya sederhana ini sebagai bakti dan sayangku
kepada :
Teristimewa pada BapakkuMuhammad DarwisdanIbuku Sanariah, yang selalu memberikan cinta, kasih sayang yang tak henti-henti, dukungan,
kesabaran dan do’a yang tulus dan ikhlas dalam setiap sujudmu.
Istriku tercinta Ira Desma Yeni, S.Pd. dan Anakku yang sangat-sangat aku sayangi dan aku banggakan Nizam Insan Islami yang selalu memberiakan semangat serta doa yang selalu dipanjatkan dalam setiap doanya.
Adik-adikku tersayang, Dira Febriantadan Dedi Satria yang dengan kasih dan kesabarannya yang selalu mendukung dan mendoakan keberhasilanku
Keluarga besar yang tak henti-hentinya memberikan doa dan dukungannya
terhadap keberhasilanku
Para pendidik dan Almamater tercinta FKIP Universitas Lampung yang telah
mendewasakanku dalam berfikir, bersikap, dan bertindak, serta segenap yang
Penulis bernama Marzius Insani, dilahirkan di Desa Hajimena
Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, pada tanggal 19
Maret 1987, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari
pasangan Bapak Muhammad Darwis, dan Ibu Sanariah.
Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis antara lain:
1. SDN 2 Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan diselesaikan
pada tahun 2000.
2. SMPN 1 Natar Kabupaten Lampung Selatan diselelesaikan pada tahun 2003.
3. SMAN 1 Natar Kabupaten Lampung Selatan diselelesaikan pada tahun 2005.
4. S1 Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan
Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Lampung
diselesaikan pada tahun 2010.
5. Tahun 2013 Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Pascasarjana
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah yang telah melimpahkan
rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan
judul “Peningkatan Keterampilan Sosial dan Hasil Belajar Siswa dengan Menggunakan Metode Bermain Peran(Role Playing)”.
Tesis ini di buat untuk memenuhi persyaratan dalam rangka memperoleh gelar
Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial pada Program Pascasarjana
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lampung.
Proses penulisan tesis ini tidak terlepas dari hambatan yang datang baik dari luar
maupun dari dalam diri penulis sendiri, penulisan tesis ini pun tidak lepas dari
bimbingan, bantuan serta petunjuk dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis
ingin mengucapkan terima kasih kepada :
1. Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. selaku Rektor Universitas Lampung
2. Prof. Dr. Sudjarwo, M.S. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Lampung
sekaligus pembahas yang selalu memberikan saran dan masukan serta
bimbingan yang kepada saya.
3. Prof. Dr. Hi. Bujang Rahman, M. Si. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan
pembimbing I Penulisan Tesis.
5. Dr. Risma M. Sinaga, M.Hum. selaku pembimbing II penulisan tesis.
6. Dr. Hi. Thoha B.S Jaya, M.S. selaku pembahas II yang selalu memberikan
bimbingan, masukan dan kritikan yang membangun.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Magister Pendidikan Ilmu
Pengetahuan Sosial FKIP Universitas Lampung.
8. Rekan-rekan angkatan 2013 Program Pascasarjana Magister Pendidikan Ilmu
Pengetahuan Sosial FKIP Unila.
9. Serta kepada semua pihak yang telah membantu hingga selesainya penulisan
tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
Semoga amal baik yang Bapak, Ibu, Saudara berikan, akan selalu mendapat
pahala dari Allah tuhan yang maha kuasa. Akhir kata dengan kerendahan hati,
penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat.
Bandar Lampung, Oktober 2015 Penulis,
I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Pendidikan dasar bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar
kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi,
anggota masyarakat, warga negara serta mempersiapkan peserta didik untuk
mengikuti pendidikan menengah (PP No. 28 Tahun 1990). Berdasarkan tujuan
pendidikan dasar, diharapkan peserta didik dapat memiliki bekal kemampuan
dasar dalam mengembangkan potensinya baik dari aspek pribadi, sosial, karir
dan akademik.
Pada dasarnya setiap peserta didik memiliki potensi dalam dirinya oleh karena
itu guru sebagai ujung tombak pendidikan perlu mencari cara untuk menggali
dan mengembangkan seluruh potensi yang ada dalam diri peserta didik.
Pengembangan potensi peserta didik di sekolah merupakan tanggung jawab
seluruh warga sekolah salah satunya adalah guru. Menurut Desmita (2010: 35)
anak usia sekolah dasar berada dalam dua masa perkembangan yaitu masa
kanak-kanak tengah (6-9 tahun), dan masa kanak-kanak akhir (10-12 tahun).
Siswa kelas V Sekolah Dasar berada pada masa kanak-kanak akhir yaitu
suatu kelompok dan merasa tidak puas bila tidak bersama teman-temannya
(Hurlock, 1980: 155).
Tentunya keinginan untuk dapat diterima oleh suatu kelompok tertentu
seorang peserta didik harus mengembangkan seluruh potensi yang ada pada
dirinya. Potensi yang dimaksud salah satunya adalah keterampilan sosial yang
merupakan kemampuan individu untuk berinteraksi dengan individu lainya.
Interaksi dengan teman memiliki banyak keuntungan bagi perkembangan
keterampilan sosial anak, di antaranya mengatasi konflik, menentukan
perilaku yang dapat diterima, dan menampilkan berbagai variasi perilaku yang
dapat diterima oleh teman.
Sekolah dasar sebagai institusi formal tidak hanya berperan dalam
mengembangkan kemampuan akademik saja namun juga kemampuan lainnya
salah satunya adalah keterampilan sosial. Hal ini sejalan dengan yang
diutarakan oleh Yustiana (1999:54) bahwa kemampuan dasar yang harus
dimiliki anak tidak terbatas pada kemampuan membaca, menulis dan
berhitung tetapi juga kemampuan intelektual, pribadi dan sosial. Pentingnya
siswa menguasai keterampilan sosial tidak diikuti dengan penyusunan
program pendidikan yang dapat mengembangkan tujuan tersebut. Program
pendidikan hendaknya tidak hanya berbasis pada penguasaan akademik, tetapi
program pendidikan juga mempunyai berbagai tujuan salah satunya adalah
penguasaan keterampilan yang diperlukan oleh siswa dalam kehidupannya.
Dewasa ini, pelaksanaan pendidikan bagi anak sekolah dasar masih banyak
hafalan dan tidak memberi kesempatan bagi anak untuk mendapat ajaran
sambil bermain, padahal bermain bagi anak merupakan kebutuhan mutlak
sesuai dengan karakteristik perkembangannya. Anak menjadi tidak
memperoleh keterampilan mental yang diperlukan pada taraf pengetahuan
yang lebih tingggi (Semiawan, 1984: 36). Berdasarkan studi pendahuluan
yang peneliti lakukan dengan mengamati pembelajaran guru kelas V SD
Negeri 1 Gedung Gumanti dengan metode ceramah di dapatkan hasil sebagai
berikut.
Tabel 1.1 Pengamatan Awal Guru dalam Merencanakan Pembelajaran
No Indikator Yang Diamati Keterangan
Baik Tidak
I Menentukan Bahan Pembelajaran dan Tujuan Pembelajaran
1 Menggunakan bahan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum (GBPP).
2 Memetakan kompetensi dasar, indikator dan pengalaman belajar
II Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media (alat bantu pembelajaran), dan sumber belajar
3 Mengembangkan dan mengorganisasikan materi pembelajaran dengan pendekatan tematik
4 Pengembangan jaringan tema dan menentukan tema
5 Menentukan dan mengembangkan media/alat bantu pembelajaran yang relevan
6 Memilih sumber belajar
III Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran
7 Menentukan jenis kegiatan pembelajaran serta kesesuaiannya dengan tema
8 Menyusun langkah-langkah pembelajaran dan kesesuaiannya dengan tema
9 Menentukan alokasi waktu pembelajaran ……
10 Menentukan cara-cara memotivasi siswa
11 Menyiapkan pertanyaan
IV Merancang pengelolaan kelas
12 Menentukan penataan ruang dan fasilitas belajar
13 Menentukan cara-cara pengorganisasian siswa agar siswa dapat berpartisipasi dalam pembelajaran
V Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian
14 Menentukan prosedur dan jenis penilaian
15 (berkala, berkesinambungan, menyeluruh)
VI Tampilan dokumen Rencana Pembelajaran
16 Kebersihan dan kerapian
17 Penggunaan bahasa tulis
Jumlah Persentase
7 10 41,2% 58,8%
Sumber: Olah Data Peneliti/ Borang Asli Terlampir
Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukan bahwa kemampuan guru pada
tahap pengamatan awal di kelas V SD Negeri 1 Gedung Gumanti dalam
merencanakan pembelajaran masih sangat rendah yaitu hanya sebesar 41,2%.
Hal ini juga kemudian berpengaruh terhadap kemampuna guru atau
kesuksesan guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Berikut data
awal keberhasilan guru dalam melaksanakan pembelajaran.
Tabel 1.2 Pengamatan Awal Guru dalam Melaksanakan Pembelajaran
No Indikator Yang Diamati Keterangan
Baik Tidak
I Prapembelajaran
1 Kesiapan ruang, alat pembelajaran, dan media
2 Memeriksa kesiapan siswa
II Membuka pembelajaran
4 Melakukan kegiatan apersepsi
5 Menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan rencana kegiatan
III Kegiatan Inti Pembelajaran
6 Penguasaan materi pelajaran
7 Pendekatan/strategi pembelajaran
8 Pemanfaatan sumber belajar /media pembelajaran
9 Pembelajaran yang memicu dan memelihara keterlibatan siswa
10 Penilaian proses dan hasil belajar
11 Penggunaan bahasa
IV Penutup
12 Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan melibatkan siswa
13 Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan, atau kegiatan, atau tugas sebagai bagian remidi/pengayaan
Jumlah Persentase (%)
3 10 23,1% 76,9%
Sumber: Olah Data Peneliti/ Borang Asli Terlampir
Berdasarkan data pada tabel di atas kemampuan guru dalam melaksanakan
pembelajaran di dalam kelas masih belum maksimal, salah satu penyebabnya
ialah perencanaan pembelajaran yang kurang baik. Sehingga rangkaian
pembelajaran ini berpengaruh juga terhadap hasil yang ingin dicapai dalam
proses pembelajaran. Melalui observasi di SDN 1 Gedung Gumanti terdapat
beberapa identifikasi mengenai perilaku siswa yang mencerminkan masih
rendahnya keterampilan sosial siswa. Bentuk keterampilan sosial yang masih
rendah tersebut mengakibatkan siswa berperilaku seperti mencorat-coret
fasilitas sekolah, berkelahi, saling mengejek, meminjam alat tulis tanpa izin,
berbicara kasar, berperilaku jahil di kelas, mengobrol ketika belajar, terlambat
masuk kelas, membolos pada saat mata ajaran tertentu, bermusuhan, dan
mencontek. Peneliti menyajikan data mengenai keterampilan sosial yang
dikuasai oleh siswa kelas V SDN 1 Gedung Gumanti melalui lembar observasi
sebagai berikut.
Tabel 1.3 Keterampilan Sosial Siswa Kelas V SDN 1 Gedung Gumanti
No Keterampilan Sosial Jumlah Siswa Porsentase (%) Baik Tidak Baik Tidak
1 Keterampilan dalam menyesuaikan diri 0 20 0 100 2 Keterampilan dalam berinteraksi 8 12 40 60 3 Keterampilan dalam mengontrol diri 6 14 30 70
4 Keterampilan dalam berempati 7 13 35 65
5 Keterampilan dalam menaati aturan 8 12 40 60 6 Keterampilan dalam menghargai orang lain 8 12 40 60
7 Keterampilan membantu teman 9 11 45 55
8 Keterampilan antri di tempat umum 0 20 0 100 9 Keterampilan membuang sampah pada tempatnya 0 20 0 100 10 Keterampilan berkomunikasi baik dengan orang lain 7 13 35 65 11 Keterampilan bekerjasama dengan kelompok yang 7 13 35 65
majemuk
12 Keterampilan menjadi konsumen yang selektif 0 20 0 100 13 Keterampilan membuat keputusan 0 20 0 100 14 Keterampilan berpartisipasi sebagai warga Negara 0 20 0 100 15 Keterampilan mengakui kemajemukan, menggali,
mengolah dan memanfaatkan informasi
0 20 0 100
Jumlah siswa Kelas V SDN 1 Gedung Gumanti ∑ 20
20% 80%
Rata-rata keterampilan sosial yang dimiliki siswa SDN 1 Gedung Gumanti
Sumber: Observasi awal di SDN 1 Gedung Gumanti
Hasil observasi awal menunjukan bahwa dari lima belas indikator yang
peneliti munculkan, hanya delapan indikator yang muncul/ yang terlihat pada
siswa SDN 1 Gedung Gumanti hal ini disebabkan salah satunya yaitu metode
yang tidak tepat serta materi yang tidak memunculkan keterampilan yang
ingin diukur. Sedangkan kedelapan indikator yang muncul merupakan
cerminan dari tema atau materi pembelajaran yang diajarkan oleh guru.
Kedelapan indikator yang muncul tersebut peneliti tuangkan pada tabel 2 di
bawah ini.
Tabel 1.4 Keterampilan Sosial Siswa Yang Terlihat Pada Tahap Observasi Awal
No Keterampilan Sosial Jumlah Siswa Porsentase (%) Baik Tidak Baik Tidak
1 Keterampilan dalam berinteraksi 8 12 40 60 2 Keterampilan dalam mengontrol diri 6 14 30 70
3 Keterampilan dalam berempati 7 13 35 65
4 Keterampilan dalam menaati aturan 8 12 40 60 5 Keterampilan dalam menghargai orang lain 8 12 40 60
6 Keterampilan membantu teman 9 11 45 55
7 Keterampilan berkomunikasi baik dengan orang lain 7 13 35 65 8 Keterampilan bekerjasama dengan kelompok yang
majemuk
7 13 35 65
Jumlah siswa Kelas V SDN 1 Gedung Gumanti ∑ 20
37,5% 62,5%
Rata-rata keterampilan sosial yang dimiliki siswa SDN 1 Gedung Gumanti
Sumber: Olah data observasi awal di SDN 1 Gedung Gumanti
Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukan bahwa keterampilan sosial
rata-rata keterampilan sosial dari 20 siswa hanya 37,5 % menunjukan siswa baik
dalam penguasaan keterampilan sosial sedangkan 62,5 % menunjukan siswa
tidak menguasai keterampilan sosial yang seharusnya dimiliki sebagai bekal
dasar berinteraksi dalam kehidupan. Kategori keterampilan sosial tersebut
peneliti klasifikasikan berdasarkan pendapat Suryabrata (2012: 10) yang
menyatakan bahwa kriteria interpretasi keterampilan sosial tergolong dalam
tiga skor persentase, yaitu (1) 0%-40% kurang baik, (2) 41%-70% cukup baik,
dan (3) 71%-100% kriteria baik. Fenomena mengenai rendahnya keterampilan
sosial siswa sekolah dasar dapat menimbulkan perilaku anti sosial, di
antaranya anak mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan
lingkungan kelas yang baru di masukinya khususnya untuk anak kelas V
seperti yang terjadi di SDN 1 Gedung Gumanti Kecamatan Tegineneg
Kabupaten Pesawaran. Keterampilan sosial yang tidak dikuasai anak akan
mempengaruhi proses belajar, mengajar serta iklim yang ada di suatu kelas
(psychological athmosphere). Banyak anak yang tidak pernah belajar tentang sikap apa yang dapat diterima di lingkungannya. Anak-anak yang kurang
memiliki keterampilan sosial sangat memungkinkan untuk ditolak oleh rekan
yang lain. Anak yang tidak mampu bekerjasama, tidak mampu menyesuaikan
diri, tidak mampu berinteraksi dengan baik, tidak dapat mengontrol diri, tidak
mampu berempati, tidak mampu menaati aturan serta tidak mampu
menghargai orang lain akan sangat mempengaruhi perkembangan anak
lainnya.
Melihat dampak yang ditimbulkan dari kurangnya keterampilan sosial pada
keterampilan sosial. Keterampilan sosial pada anak usia sekolah dasar
merupakan cara anak dalam melakukan interaksi, baik dalam hal bertingkah
laku maupun dalam hal berkomunikasi dengan orang lain, sehingga dapat
bermanfaat bagi kehidupannya baik di lingkungan keluarga maupun
masyarakat sekitarnya. Sebagaimana dikemukakan Nurlaela (2011: 6)
pentingnya keterampilan sosial dimiliki oleh anak akan menjadikannya
sebagai individu yang dapat berperilaku sesuai dengan tuntutan lingkungan
sosialnya, sehingga anak dapat diterima dalam lingkungan atau kelompoknya.
Selain itu, siswa dengan perilaku sosial yang positif pada umumnya menerima
lebih banyak perhatian dari guru dan memiliki rata-rata yang tinggi dalam
kesuksesan akademik (Cartledge & Millburn,1986: 4).
Terbinanya keterampilan sosial pada diri anak akan memunculkan penerimaan
teman sebaya, penerimaan dari guru, dan sukses dalam belajarnya.
Rangsangan yang diberikan kepada anak usia dini tentunya harus sesuai
dengan perkembangan mereka. Tahap perkembangan ini dapat ditinjau dari
berbagai aspek seperti kognitif, bahasa, emosi, sosial, fisik. Proses
penyampaiannya pun harus sesuai dengan dunia anak, yaitu dengan bermain
sebab bermain merupakan salah satu sarana belajar bagi mereka. Bermain
merupakan proses mempersiapkan diri untuk memasuki dunia selanjutnya.
Bermain juga merupakan cara bagi anak untuk memperoleh pengetahuan
tentang segala sesuatu. Bermain akan menumbuhkan anak untuk melakukan
eksplorasi, melatih pertumbuhan fisik serta imajinasi, memberikan peluang
mengembangkan kemampuan berbahasa dan menambah kata-kata, serta
membuat belajar yang dilakukan sebagai belajar yang sangat menyenangkan.
Bermain juga merupakan salah satu cara belajar yang dapat membuat siswa
belajar mengalami perubahan baik dalam pengetahuan, pemahaman,
ketrampilan, nilai dan sikap. Peningkatan kualitas mutu pendidikan dan
pengembangan proses pembelajaran merupakan masalah yang selalu menuntut
perhatian. Perbedaan tingkat kemampuan siswa yang satu dengan yang
lainnya terhadap materi pembelajaran menuntut seorang guru melakukan
inovasi-inovasi dalam pembelajaran sehingga tidak sekedar menyajikan
materi, tetapi juga perlu menggunakan metode yang sesuai, disukai, dan
mempermudah pemahaman siswa.
Salah satu metode yang diduga dapat mempermudah siswa untuk
mendapatkan hasil yang diinginkan adalah dengan metode bermaian peran.
Ahman (1998: 65) melakukan penelitian mengenai efektifitas bermain peran
sebagai model bimbingan dalam mengembangkan keterampilan sosial anak
berkemampuan unggul. Temuan penelitiannya menunjukkan bahwa metode
bermain peran efektif untuk dijadikan metode bimbingan dalam
mengembangkan keterampilan sosial anak berkemampuan unggul. Bermain
peran dalam dimensi proses telah membantu siswa memperoleh pengalaman
berharga melalui aktivitas interaksional dengan teman-temannya. Anak belajar
memberi masukan atas peran orang lain, dan menerima masukan dari orang
lain dan dapat menimba pengalaman mengenai cara-cara menghadapi
prinsip-prinsip demokrasi. Sedangkan dimensi produk, bermain peran
diharapkan dapat mereduksi bahkan menyembuhkan kebiasaan buruk anak
seperti berkelahi, bermalas-malasan, berbicara kasar, mencontek, dan
lain-lain.
Berdasarkan survey di SDN 1 Gedung Gumanti metode belajar yang
dipergunakan oleh guru-guru di didominasi oleh metode ceramah, tanya jawab
dan diskusi saja. Metode belajar yang digunakan oleh guru cendrung monoton
dan kurang bervariatif sehingga tujuan yang ingin dicapai kurang dapat
terealisasi dengan baik. Gejala ini sekaligus menggambarkan bahwa
penggunaan metode belajar masih terbatas pada satu atau dua metode
mengajar saja, belum meluas dan mencakup penggunaan metode secara luas
dan banyak variasinya. Implikasi keadaan ini mengakibatkan apa yang
diharapkan dari proses belajar belum mencapai taraf optimal. Peneliti
menyajikan data dalam bentuk tabel seperti di bawah ini yaitu metode yang
dipergunakan oleh guru di SDN 1 Gedung Gumanti.
Tabel 1.5 Metode Belajar Yang Dipergunakan Oleh Guru-Guru SDN 1 Gedung Gumanti
No Nama Guru NIP Guru Kelas/ Mata Pelajaran
Metode
1 Endarwati, S.Pd. 196911121995032001 Kepsek/Guru Kelas
Ceramah, tanya jawab dan diskusi
2 Sri Warnah, S.Ag. 195703221982032004 Agama Islam Ceramah, diskusi, Tanya jawab
3 Limtono 195912071984031010 Olah Raga Ceramah, tanya jawab 4 Marpuni 196104211984032004 Kelas III Ceramah, Tanya jawab 5 Kasmirah, S.Pd. 196808152008012013 Kelas VI Ceramah,Tanya jawab dan
diskusi
6 Nurbaiti, A.Ma. 196701061986021004 Kelas II Ceramah, diskusi 7 Ritawati, S.Pd. 197106262006042009 Kelas I Ceramah, diskusi, Tanya
jawab
8 Herdi S. Adi, S.Pd. 198606222009051001 Kelas IV Ceramah,Tanya jawab dan diskusi
10 Dina Patmawati Honorer Muatan Lokal Ceramah, Tanya jawab 11 Ira Desma Yeni,
S.Pd.
Guru Tidak Tetap Bahasa Inggris Ceramah,Tanya jawab dan diskusi
Sumber: Observasi awal di SDN 1 Gedung Gumanti
Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukan bahwa semua guru di SDN 1
Gedung Gumanti masih menggunakan metode ceramah, metode tanya jawab,
dan metode diskusi saja kesemua metode tersebut tergolong metode yang
masih tradisional/ konvensional. Metode memang mempunyai andil yang
cukup besar dalam kegiatan pembelajaran. Kemampuan yang diharapkan
dimiliki anak didik, akan ditentukan oleh kerelevansian penggunaan metode
dengan tujuan. Pembelajaran IPS di SDN 1 Gedung Gumanti belum optimal
disebabkan oleh kurang maksimalnya guru IPS dalam memanfaatkan maupun
memberdayakan sumber pembelajaran, karena dalam proses pembelajaran IPS
cenderung masih berpusat pada guru, berpusat pada buku, dan monomedia.
Proses pelaksanaan pembelajaran yang terjadi masih kurang maksimal dan
kurang memadai, antara lain karena pelaksanaannya kurang sesuai dengan
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah dibuat dimana proses
pembelajaran masih cenderung menggunakan metode yang kurang bervariasi.
Penerapan metode pembelajaran yang kurang bervariasi yakni antara lain
masih menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan diskusi saja sehingga
siswa memiliki kecenderungan bersifat pasif. Pembelajaran yang diterapkan
kurang dapat memotivasi siswa untuk terlibat secara aktif dan langsung
mendapatkan pengalaman belajar. Kondisi tersebut selain berpengaruh
terhadap keterampilan sosial siswa juga berpengaruh terhadap perolehan hasil
Gedung Gumanti peneliti dapatkan dari tes awal yang peneliti lakukan pada
saat studi pendahuluan dan hasil tes tersebut peneliti olah dan tuangkan pada
tabel di bawah ini.
Tabel 1.6 Nilai Tes Awal Hasil Belajar Siswa Pada Saat Pra Penelitian
No Nama L/P NISN Nilai Ket
1 Andreas Febrianto L 0038320768 50 Tidak Tuntas 2 Angelia Febrianti P 0046106918 60 Tuntas 3 Annisa Ain Nurahma P 0045034761 50 Tidak Tuntas 4 Aulia Maharani Putri P 0052407439 60 Tuntas 5 Dela Destiana P 0042184481 40 Tidak Tuntas 6 Deva Raditiya F L 0046492106 40 Tidak Tuntas 7 Dimas Yogi Ariyanto L 0044566560 30 Tidak Tuntas
8 Esti Melinda P 0044271613 60 Tuntas
9 Kelpin L 0007348674 30 Tidak Tuntas
10 Mei Sinta Wati P 0031681386 40 Tidak Tuntas 11 Miki Saputra L 0053539367 30 Tidak Tuntas 12 Mira Julianti P 0039440352 40 Tidak Tuntas 13 Nanda Aulia P 0055101241 40 Tidak Tuntas 14 Petra Gilang P L 0031684949 30 Tidak Tuntas 15 Rio Saputra L 0031903599 50 Tidak Tuntas 16 Sendi Kiyawan L 0022420281 30 Tidak Tuntas 17 Septi Adelia P 0044992794 50 Tidak Tuntas 18 Sherli Indah Rahayu P 0039192579 60 Tuntas 19 Silvy Oktavia P 0042623821 50 Tidak Tuntas 20 Sopian Kandau L 0006457218 30 Tidak Tuntas
Nilai Rata-Rata Kelas 43,5 Tidak Tuntas
Sumber: Data Olahan Peneliti/ Borang Terlampir
Tes tersebut menunjukan nilai rata-rata 20 siswa diperoleh skor 43,5 hanya 4
siswa yang tuntas dalam pembelajaran atau hanya 20% siswa tuntas,
sedangkan sisanya atau 80% tidak tuntas.. Hal ini belum mencapai kriteria
keberhasilan minimal (KKM) dalam proses pembelajaran yang ditetapkan di
SDN 1 Gedung Gumanti adalah 80% siswa tuntas dalam pembelajaran.
Metode yang mungkin dapat menjadi salah satu alternatif untuk memecahkan
berbagai persoalan di atas adalah metode bermain peran (role playing) yang merupakan bentuk metode mengajar dengan mendramakan atau memerankan
cara tingkah laku di dalam hubungan sosial. Bermain peran lebih menekankan
di dalam mendramakan masalah-masalah hubungan sosial (Zuhairini, dkk.
1983: 101-102). Metode bermain peran (role playing) dalam beberapa penelitian yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa menunjukkan bahwa
bermain peran sangat baik dalam mengatasi kesulitran-kesulitan anak dalam
mengembangkan berbagai keterampilan yang diperlukan khususnya
keterampilan sosial.
Menurut Fleet dalam Hurlock (2000: 43) bermain peran merupakan intervensi
yang dikembangkan yang berkaitan dengan penggunaan sistematis dari
metode bermain oleh seorang konselor untuk membawa peningkatan dalam
kemampuan siswa sampai penampilan yang optimal di sekolah. Bermain
peran juga meliputi penggunaan bermain secara sistematis untuk mengatasi
kesulitan-kesulitan anak, mengembangkan pola perilaku adaptif,
mengendalikan diri siswa yang agresifnya tinggi, meningkatkan kemampuan
berempati, dapat mengelola emosi, dapat menjadi individu yang bertanggung
jawab, memilikiinterpersonal skillyang baik dan dapat memecahkan masalah secara efektif dan bijaksana. Penjelasan Fleet tersebut menunjukan bahwa
metode bermain peran(role playing)sangat membantu siswa mengembangkan kemampuannya baik kognitif, afektif maupun psikomotorik. Keterampilan
sosial merupakan bekal utama dalam berinteraksi, keterampilan ini dapat kita
kembangkan di sekolah dengan menggunakan berbagai cara atau metode
pembelajaran salah satunya dalam penelitian ini adalah metode bermain peran
(role playing).
Gumanti. Pembelajaran ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan
sosial dan hasil belajar siswa. Keunggulan pembelajaran ini dapat
meningkatkan keaktifan siswa, meningkatkan rasa tanggung jawab dan
bekerja sama antara sesama siswa, guru ataupun komponen-komponen lainnya
yang terkait. Hal ini didasarkan pada karakteristik model pembelajaran yang
sesuai dengan karakteristik mata pelajaran IPS, dimana mata pelajaran IPS
merupakan mata pelajaran yang membutuhkan suatu pemahaman mendalam
sehingga dibutuhkan keaktifan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran.
1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dalam
penelitian ini sebagai berikut.
1.2.1 Metode yang digunakan oleh guru-guru di SDN 1 Gedung Gumanti
masih cendrung kurang bervariatif sehingga input yang didapatkan
oleh siswa masih sangat sedikit.
1.2.2 Keterampilan sosial yang dikuasai oleh siswa kelas V SDN 1 Gedung
Gumanti tergolong masih rendah hal ini mengakibatkan terganggunya
perkembangan sosial anak.
1.2.3 Hasil belajar ilmu pengetahuan sosial (IPS) siswa kelas V SDN 1
Gedung Gumanti tergolong masih rendah hal ini tidak terlepas dari
penggunaan metode konvensional seperti ceramah, tanya jawab dan
1.2.4 Skenario pembelajaran belum dirancang secara baik hal ini
dikarenakan tidak ada persiapan yang matang dari guru mata pelajaran
untuk mengajar di dalam kelas.
1.2.5 Tujuan pembelajaran masih berorientasi pada peningkatan kognitif saja
padahal pondasi utama dalam pendidikan adalah pada pembentukan
sikap mental yang baik bagi peseta didik.
1.3 Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di
atas maka tidak semua masalah tersebut akan diteliti dalam penelitian ini.
Agar penelitian tidak meluas maka peneliti perlu membatasi masalah yang
akan dikaji, yaitu pada peningkatan keterampilan sosial dan hasil belajar siswa
dengan menggunakan metode bermain peran (role playing) pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial (IPS) siswa kelas V SDN 1 Gedung
Gumanti Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran semester ganjil tahun
ajaran 2014/2015.
1.4 Rumusan Masalah
Agar tidak terjadi salah penafsiran maka diperlukan rumusan masalah guna
menyusun langkah-langkah berikutnya. Berdasarkan latar belakang masalah
dan identifikasi masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut.
1.4.1 Bagaimanakah keterampilan sosial siswa dalam pembelajaran ilmu
pengetahuan sosial (IPS) dengan menggunakan metode bermain peran
1.4.2 Bagaimanakah hasil belajar siswa dalam pembelajaran ilmu
pengetahuan sosial (IPS) dengan menggunakan metode bermain peran
(role playing)?
1.5 Tujuan Penelitian
Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai
berikut.
1.5.1 Meningkatkan keterampilan sosial siswa dalam pembelajaran ilmu
pengetahuan sosial (IPS) dengan menggunakan metode bermain peran
(role playing).
1.5.2 Meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran ilmu
pengetahuan sosial (IPS) dengan menggunakan metode bermain peran
(role playing).
1.6 Manfaat Penelitian
Hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat berguna baik secara
akademis, maupun secara praktis.
1.6.1 Secara Akademis
a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para pengelola pendidikan
pada umumnya dan pendidikan ilmu pengetahuan sosial pada
khususnya di tingkat sekolah dasar maupun tingkat sekolah
b. Memberikan manfaat bagi guru ilmu pengetahuan sosial yaitu
dengan memberi wawasan baru tentang metode-metode dalam
pembelajaran.
1.6.2 Secara Praktis A. Bagi siswa
a. Mengembangkan kecerdasan keterampiloan sosial siswa dan
meningkatkan hasil belajar siswa.
b. Peningkatan atau perbaikan kinerja guru dan siswa di sekolah.
c. Peningkatan atau perbaikan masalah-masalah pendidikan anak
di sekolah.
d. Peningkatan dan perbaikan kualitas dalam penerapan
kurikulum dan pengembangan kompetensi siswa di sekolah.
B. Bagi Guru
a. Membantu guru memperbaiki mutu pembelajaran.
b. Meningkatkan profesionalitas guru.
c. Meningkatkan rasa percaya diri guru.
d. Memungkinkan guru secara aktif mengembangkan
pengetahuan dan keterampilannya.
C. Bagi Sekolah
a. Meningkatkan mutu isi, masukan, proses, dan hasil pendidikan
b. Membantu guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam
mengatasi masalah pembelajaran dan pendidikan di dalam dan
luar kelas.
c. Meningkatkan sikap profesional pendidik dan tenaga
kependidikan.
d. Menumbuh-kembangkan budaya ilmiah di lingkungan sekolah,
untuk proaktif dalam melakukan perbaikan mutu
pendidikan/pembelajaran secara berkelanjutan.
e. Memberikan nilai tambah(value added)yang positif bagi sekolah.
f. Menjadi alat evaluator dari program dan kebijakan pengelolaan
sekolah yang sudah berjalan.
1.7 Ruang Lingkup Penelitian
1.7.1 Lingkup Kawasan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
Woolover dan Scoot merumuskan lima kawasan (perspektif) dalam
mengajarkan ilmu pengetahuan sosial (IPS) sebagai berikut.
a. IPS diajarkan sebagai pewarisan nilai kewarganegaraan
(citizenship transmission).
b. IPS diajarkan sebagai pendidikan ilmu-ilmu sosial.
c. IPS diajarkan sebagai cara berpikir reflektif(reflective inquiry). d. IPS diajarkan sebagai pengembangan pribadi siswa.
e. IPS diajarkan sebagai proses pengambilan keputusan dan tindakan
Kelima kawasan ilmu pengetahuan sosial (IPS) tersebut tidak berdiri
masing-masing, bisa saja ada yang merupakan gabungan perspektif
yang lain. Kawasan IPS dalam penelitian ini yaitu IPS sebagai
pengembangan pribadi siswa yang bertujuan untuk mengembangkan
seluruh potensi siswa baik yang berkaitan dengan keterampilan personal
maupun interpersonal. Alasannya adalah bahwa metode bermain peran
(role playing) merupakan cara yang menurut peneliti dianggap tepat
karena metode ini memiliki tujuan untuk melatih anak-anak agar
mereka mampu menyelesaikan masalah-masalah sosial-psikologis; dan
melatih anak-anak agar mereka dapat bergaul dan memberi
kemungkinan bagi pemahaman terhadap orang lain beserta masalahnya.
Siswa yang potensinya tersalurkan secara baik akan memiliki
kepercayaan diri yang tinggi. Oleh karena itu, IPS juga dituntut untuk
mengembangkan supaya siswa mudah bekerja sama dengan yang lain,
mampu merancang sebuah tujuan dan merealisasikannya, serta
memiliki kemampuan memecahkan persoalan secara baik. Tujuan IPS
ini sangat relevansi dengan input yang diharapkan dari penggunaan
metode bermain peran terhadap keterampilan sosial dan bhasil belajar
siswa yaitu pembentukan mental, jiwa, dan fisik anak supaya menjadi
anggota masyarakat produktif untuk mengembangkan potensi siswa
tersebut maka pendekatan guru harus lebih bersifat a child centered
1.7.2 Objek Penelitian
Objek penelitian ini adalah metode bermain peran (role playing)dalam peningkatan keterampilan sosial dan hasil belajar siswa.
1.7.3 Subjek Penelitian
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa dan guru kelas V SD Negeri 1
Gedung Gumanti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran tahun
ajaran 2014-2015.
1.7.4 Wilayah Penelitian
Wilayah yang dipilih oleh peneliti untuk melakukan penelitian adalah
Desa Margodadi Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.
1.7.5 Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran
II. KAJIAN PUSTAKA
2.1 Keterampilan Sosial(Social Skill)
Keterampilan sosial merupakan perilaku yang perlu dipelajari, karena
memungkinkan individu dapat berinteraksi, memperoleh respon positif atau
negatif Cartledge dan Milburn (1986: 143-149). Karena itu keterampilan
sosial merupakan kompetensi yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap
orang termasuk di dalamnya peserta didik, agar dapat memelihara hubungan
sosial secara positif dengan keluarga, teman sebaya, masyarakat dan pergaulan
di lingkungan yang lebih luas. Menurut Maryani (2011: 18) keterampilan
sosial merupakan kemampuan untuk menciptakan hubungan sosial yang serasi
dan memuaskan berbagai pihak, dalam bentuk penyesuaian terhadap
lingkungan sosial dan memecahkan masalah sosial. Tim Broad-Based Education menyatakan keterampilan sosial sebagai keterampilan berkomunikasi dengan empati dan keterampilan bekerjasama.
Komunikasi bukan hanya menyampaikan pesan, tetapi di dalamnya ada
keinginan menimbulkan kesan yang baik untuk menumbuhkan keharmonisan
maupun kesinambungan hubungan, serta solusi terhadap suatu permasalahan.
Selanjutnya Cadler menjelaskan pentingnya keterampilan sosial
Keterampilan sosial sangat diperlukan dan harus jadi prioritas dalam mengajar. Mengajar bukan hanya sekedar mengembangkan keterampilan akademik. Hak yang sangat penting dalam mengembangkan keterampilan sosial adalah mendiskusikan sesama guru atau orang tua tentang keterampilan sosial apa yang menjadi prioritas, memilih satu keterampilan sosial, mempraktikan, merefleksi dan ahirnya mereview serta mempraktikannya kembali setelah diperbaiki, merefleksi dan seterusnya sampai betul-betul terkuasai oleh peserta didik (Maryani, 2011: 19).
Chaplin dalam Suhartini (2004: 18) berpendapat bahwa keterampilan sosial
merupakan bentuk perilaku, perbuatan dan sikap yang ditampilkan oleh
individu ketika berinteraksi dengan orang lain disertai dengan ketepatan dan
kecepatan sehingga memberikan kenyamanan bagi orang yang berada
disekitarnya. Peningkatan perilaku sosial cenderung paling menyolok pada
masa kanak-kanak awal. Hal ini disebabkan oleh pengalaman sosial yang
semakin bertambah pada anak-anak mempelajari pandangan pihak lain
terhadap perilaku mereka dan bagaimana pemandangan tersebut
mempengaruhi tingkatan penerimaan kelompok teman sebaya akan tetapi, ada
beberapa bentuk perilaku yang tidak sosial atau antisosial. Sejauh mana
terjadinya peningkat-an perilaku sosial akan bergantung pada tiga hal.
Pertama, seberapa kuat keinginan anak untuk di terima secara sosial; kedua
pengetahuan mereka tentang cara memperbaiki perilaku; dan ketiga,
kemampuan intelektual yang semakin berkembang yang memungkinkan
pemahaman hubungan antara perilaku mereka dengan penerimaan sosial.
Keterampilan sosial atau disebut juga prososial behavior mencakup perilaku-perilaku sebagai berikut.
karena suatu masalah dan mengungkapkan perasaan orang lain yang sedang mengalami konflik sebagai bentuk bahwa anak menyadari perasaan yang dialami orang lain; (b) kemurahan hati atau kedermawanan di dalamnya anak-anak berbagi dan memberikan suatu barang miliknya pada seseorang; (c) kerjasama yang didalamnya anakanak mengambil giliran atau bergantian dan menuruti perintah secara sukarela tanpa menimbulkan per-tengkaran; dan (d) memberi bantuan yang di dalamnya anak-anak membantu seseorang untuk melengkapi suatu tugas dan membantu seseorang yang membutuhkan (Beaty, 1998: 147).
Keterampilan sosial dapat dikelompokan dalam empat bagian, namun
keempat bagian tersebut saling berkaitan. Keempat bagian tersebut sebagai
berikut.
1. Keterampilan dasar berinteraksi: berusaha untuk saling mengenal, ada kontak mata, berbagai informasi atau material.
2. Keterampilan komunikasi: mendengar dan berbicara secara bergiliran, melembutkan suara (tidak membentak), menyakinkan orang untuk mengemukakan pendapat, mendengarkan sampai orang tersebut menyelesaikan pembicaraannya.
3. Keterampilan membangun tim/kelompok: mengakomodasi pendapat orang, bekerjasama, saling menolong dan saling memperhatikan.
4. Keterampilan menyelesaikan masalah: mengendalikan diri, empati, memikirkan orang lain, taat terhadap kesepakatan, mencari jalan keluar dengan berdiskusi, respek terhadap pendapat yang berbeda (Maryani, 2011: 20).
Keterampilan sosial di Amerika Serikat dirumuskan oleh ASCD (Association for Supervicion Curriculum Development) meliputi keterampilan hidup
(lifeskill) antara lain sebagai berikut. 1. Keterampilan berfikir dan bernalar.
2. Keterampilan bekerja dengan orang lain.
3. Keterampilan pengendalaian diri.
Keterampilan sosial adalah kemampuan untuk mengenal bahasa-bahasa
simbol, antri di tempat-tempat umum, membuang sampah pada tempatnya,
berkomunikasi dengan baik dengan orang lain, berejasama dengan kelompok
yang majemuk, menjadi konsumen yang selektif, membuat keputusan,
berpartisipasi sebagai warga negara, mengakui kemajemukan, menggali,
mengolah dan memanfaatkan informasi (Supriatna, 2007: 130).
2.2 Hasil Belajar
Hasil belajar merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran. Sudjana
(2009: 3) mendefinisikan hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah
perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang lebih luas
mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dimyati dan Mudjiono
(2006: 3-4) juga menyebutkan hasil belajar merupakan hasil suatu interaksi
tindak belajar dan tindak mengajar. Menurut Suryosubroto (1997: 2) hasil
belajar adalah penilaian tentang kemajuan siswa dalam segala hal yang
dipelajari di sekolah yang menyangkut pengetahuan dan keterampilan yang
dinyatakan sesudah penilaian. Menurut Hamalik (2005: 43) hasil belajar
adalah perubahan tingkah laku yang diharapkan, yang nantinya dimiliki siswa
setelah dilaksanakannya kegiatan belajar mengajar. Jika dilihat dari sisi guru,
tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Sebaliknya jika
dilihat dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya pengajaran dari
Bloom menyebutkan enam jenis perilaku ranah kognitif sebagai berikut.
a. Pengetahuan, mencapai kemampuan ingatan tentang hal yang telah dipelajari dan tersimpan dalam ingatan. Pengetahuan itu berkenaan dengan fakta, peristiwa, pengertian kaidah, teori, prinsip, atau metode.
b. Pemahaman, mencakup kemampuan menangkap arti dan makna tentang hal yang dipelajari.
c. Penerapan, mencakup kemampuan menerapkan metode dan kaidah untuk menghadapi masalah yang nyata dan baru. Misalnya, menggunakan prinsip.
d. Analisis, mencakup kemampuan merinci suatu kesatuan ke dalam bagian-bagian sehingga struktur keseluruhan dapat dipahami dengan baik. Misalnya mengurangi masalah menjadi bagian yang telah kecil.
e. Sintesis, mencakup kemampuan membentuk suatu pola baru. Misalnya kemampuan menyusun suatu program.
f. Evaluasi, mencakup kemampuan membentuk pendapat tentang beberapa hal berdasarkan kriteria tertentu. misalnya, kemampuan menilai hasil ulangan (Dimyati dan Mudjiono, 2006: 26-27).
Berdasarkan pengertian hasil belajar di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil
belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima
pengalaman belajarnya. Kemampuan-kemampuan tersebut mencakup aspek
kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil belajar dapat dilihat melalui kegiatan
evaluasi yang bertujuan untuk mendapatkan data pembuktian yang akan
menunjukkan tingkat kemampuan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran.
Hasil belajar yang diteliti dalam penelitian ini adalah hasil belajar kognitif IPS
yang mencakup dua tingkatan yaitu pengetahuan (C1), pemahaman (C2).
Instrumen yang digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa pada aspek
kognitif adalah tes.
Hasil belajar sebagai salah satu indikator pencapaian tujuan pembelajaran di
sendiri. Sugihartono, dkk, (2007: 76-77) menyebutkan faktor-faktor yang
mempengaruhi hasil belajar sebagai berikut.
a. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang
belajar. Faktor internal meliputi, faktor jasmaniah dan faktor psikologis.
b. Faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar individu. Faktor eksternal
meliputi, faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat.
Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar di atas, peneliti
menggunakan faktor eksternal berupa penggunaan metode bermain peran (role playing). Pelaksanaan metode bermain peran (role playing) ini menuntut keterlibatan siswa secara aktif dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial
(IPS).
2.3 Metode Bermain Peran (Role Playing Method)
Bermain peran (role playing) adalah metode pembelajaran yang diarahkan untuk bermain peran dan menciptakan situasi tertentu sesuai dengan peristiwa
yang ingin disimulasikan (Maryani, 2011: 38). Sedangakan Sanjaya (2008:
161) mendefinisikan bermain peran (Role playing) merupakan metode pembelajaran sebagai bagian dari simulasi yang diarahkan untuk mengkreasi
peristiwa sejarah, peristiwa aktual atau kejadian yang akan datang. Metode
bermain peran (role playing) ini dikategorikan sebagai metode belajar yang berumpun kepada metode perilaku yang diterapkan dalam kegiatan
pengembangan. Karakteristiknya adalah adanya kecenderungan memecahkan
tugas belajar dalam sejumlah perilaku yang berurutan, konkret dan dapat
khayalan, fantasi, make belive, atau simbolik. Menurut Piaget, awal main peran dapat menjadi bukti perilaku anak. Beliau menyatakan bahwa bermain
peran ditandai oleh penggunaan cerita pada objek dan mengulang perilaku
menyenangkan yang diingatnya. Piaget menyatakan bahwa keterlibatan anak
dalam main peran dan upaya anak mencapai tahap yang lebih tinggi
dibandingkan dengan anak lainnya disebut sebagai collective symbolism. Beliau juga menerangkan percakapan lisan yang anak lakukan dengan diri
sendiri sebagaiidiosyncratic soliloquies.
Bermain peran adalah mendramatisasikan cara bertingkah laku orang-orang
tertentu dalam posisi yang membedakan peranan masing-masing dalam suatu
organisasi atau kelompok di masyarakat (Nawawi, 1993: 295). Jadi, secara
singkat metode bermain peran adalah cara atau jalan untuk mendramatisasikan
cara bertingkah laku orang-orang tertentu didalam posisi yang membedakan
peranan masing-masing. Apabila ditinjau secara istilah, metode bermain peran
adalah bentuk metode mengajar dengan mendramakan memerankan cara
bertingkah laku dalam hubungan sosial, yang lebih menekankan pada
kenyataan-kenyataan dimana para murid diikutsertakan dalam memainkan
peranan di dalam mendramakan masalah-masalah hubungan sosial. Metode ini
kadang-kadang disebut dengan dramatisasi (Zuhairini, dkk, 1983: 101-102).
Metode bermain peran (role playing) anak diberi kesempatan untuk mengembangkan imajinasinya dalam memerankan seorang tokoh atau
benda-benda tertentu dengan mendapat ulasan dari guru agar mereka menghayati
diberi kebebasan untuk menggunakan benda-benda sekitarnya dan
mengkhayalkannya jika benda tersebut diperlukan dalam memerankan tokoh
yang dibawakan. Contoh kegiatan ini misalnya anak memerankan bagaimana
Bapak tani mencangkul sawahnya, bagaimana kupu-kupu yang menghisap
madu bunga, bagaimana gerakan pohon yang ditiup angin, dan sebagainya
(Kartini, 2007: 32). Dawson mengemukakan bahwa simulasi merupakan suatu
istilah umum berhubungan dengan menyusun dan mengoperasikan suatu
model yang mereplikasi proses-proses perilaku (Dimyati dan Mudjiono, 1992:
80). Sedangkan Ali mengemukakan bahwa metode simulasi adalah suatu cara
pengajaran dengan melakukan proses tingkah laku secara tiruan (Ali, 1996:
83).
Metode pengajaran simulasi terbagi menjadi 3 kelompok sebagai berikut.
Sosiodrama: semacam drama sosial berguna untuk menanamkan kemampuan menganalisa situasi sosial tertentu, Psikodrama: hampir mirip dengan sosiodrama. Perbedaan terletak pada penekannya. Sosia drama menekankan kepada permasalahan sosial, sedangkan psikodrama menekankan pada pengaruh psikologisnya dan Role-Playing: role playing atau bermain peran bertujuan menggambarkan suatu peristiwa masa lampau (Ali, 1996: 83).
Moedjiono & Dimyati juga membagi metode pengajaran simulasi menjadi 3
kelompok sebagai berikut.
tempat dan/ atau waktu tertentu, dan Sosiodrama (sociodrama) yakni suatu pembuatan pemecahan masalah kelompok yang dipusatkan pada suatu masalah yang berhubungan dengan relasi kemanusiaan. Sosiodrama memberikan kesempatan kepada siswa untuk menentukan alternatif pemecahan masalah yang timbul dan menjadi perhatian kelompok (Dimyati dan Mudjiono, 1992: 80).
Tahapan-tahapan pembelajaran dengan model bermain peran (role playing)
meliputi beberapa tahap sebagai berikut.
a. Penjelasan umum b. Memilih para pelaku c. Menentukan observer d. Menentukan jalan cerita e. Pelaksanaan (main) f. Diskusi dan penilaian g. Permainan ulang h. Diskusi dan penelaahan
i. Generalisasi (Hidayati, dkk. 2008: 37).
Selain tahapan-tahapan di atas yang telah dikemukakan oleh Hidayati, dkk.
Maryani juga menjelaskan tahapan-tahapan yang dapat diterapkan dalam
pembelajaran bermain peran(role playing)sebagai berikut.
a. Menentukan peristiwa/topik yang akan dijadikan tema kegiatan bermain peran(role playing)dan apa tujuannya.
b. Guru membuat skenario bermain peran (role playing), termasuk di dalamnya ruang dan waktu.
c. Guru memberikan gambaran situasi yang ingin disimulasikan bila perlu putarkan film tentang peristiwa tertentu.
d. Membentuk kelompok dan menetapkan pemain yang akan terlibat dalam simulasi.
e. Setiap anak membaca dan menghayati skenario, serta meyakini kapan peran tokoh harus muncul dan bagaimana penghayatan nilai serta perilakunya.
f. Membuat setting ruang sesuai peristiwa yang akan dikreasikan. g. Melaksanakan simulasi.
h. Melakukan penilaian.
Kelebihan metode bermain peran(role playing)antara lain sebagai berikut. 1. Siswa merasa tertarik perhatiannya pada ajaran, karena masalah-masalah
sosial sangat berguna bagi mereka.
2. Siswa dengan berperan seperti orang lain, maka ia dapat menempatkan diri seperti watak orang lain itu.
3. Siswa dapat merasakan perasaan orang lain dan dapat menghargai pendapat orang lain sehingga menumbuhkan sikap saling pengertian, tenggang rasa, toleransi dan cinta kasih terhadap orang lain (Roestiyah, 2001: 92).
Kekurangan metode bermain peran(role playing)antara lain sebagai berikut. 1. Jika guru tidak menguasai tujuan instruksional pembelajaran, maka model
bermain peran tidak akan berhasil.
2. Apabila guru tidak memahami langkah-langkah pelaksanaan model ini, maka akan mengacaukan berlangsungnya bermain peran, karena yang memegang peranan atau penonton tidak tahu arah bersama.
3. Dengan adanya model bermain peran, dapat menumbuhkan prasangka buruk, ras diskriminasi, balas dendam, sehingga menyimpang dari tujuan semula (Roestiyah, 2001: 92).
Kelebihan dan kekurangan dari motode bermain peran (role playing)tersebut dapat dijadikan bahan acuan peneliti untuk menerapkan motode bermain peran
(role playing) pada penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan kutipan tersebut, berarti metode bermain peran adalah metode pembelajaran yang di
dalamnya menampakkan adanya perilaku pura-pura dari siswa yang terlihat
dan/ atau peniruan situasi dari tokoh-tokoh sejarah sedemikian rupa. Metode
bermain peran dengan demikian dapat diartikan sebagai metode yang
melibatkan siswa untuk pura-pura memainkan peran/ tokoh yang terlibat
dalam proses sejarah. Pembelajaran akan lebih menyenangkan bila didukung
oleh seorang guru yang aktif. Strategi pembelajaran yang digunakan guru yang
aktif itu sangat berivariasi, dinamis, tidak monoton, senantiasa disesuaikan
Pembelajaran yang menyenangkan dapat dilakukan dengan berbagai cara/
metode oleh karenanya guru tidak mempunyai alasan guna mencapai tujuan
pembelajaran.
2.4 Belajar dan Pembelajaran
Belajar pada hakikatnya adalah suatu aktivitas yang mengharapkan perubahan
tingkah laku (behavioral change) pada individu yang belajar (Tasrif, 2008: 103). Sedangkan menurut Trianto yang mengutip dari Anthony Robbins
belajar adalah proses menciptakan hubungan antara sesuatu (pengetahuan)
yang sudah dipahami dan sesuatu (pengetahuan) yang baru (Trianto, 2009:
15). Belajar merupakan proses manusia untuk mencapai berbagai kompetensi,
keterampilan dan sikap. Gagne memberikan beberapa definisi tentang belajar
yaitu (1) belajar adalah suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam
pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku. (2) belajar adalah
pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh dari instruksi (Gagne, 1988:
66).
Sedangkan menurut Hilgrad dan Bower dalam Gredler (1997: 13) belajar (to learn) memiliki arti 1) to gain knowledge, comprehension, or mastery of trough experience or study, 2) to fix in the mind or memory; memorize, 3) to acquire trough experience; 4) to become in forme of to find out. Menurut definisi tersebut, belajar memiliki pengertian memperoleh pengetahuan atau
menguasai pengetahuan melalui pengalaman, mengingat, menguasai
demikian memiliki arti dasar adanya aktivitas atau kegiatan dan penguasaan
tentang sesuatu.
Belajar dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti bahan yang dipelajari, faktor
instrumental, lingkungan dan kondisi individual si pelajar. Faktor-faktor
tesebut sebaiknya diatur sedemikian rupa, agar mempunyai pengaruh yang
membantu tercapainya hasil dan kompetensi secara optimal. Pada dasarnya,
belajar merupakan masalah bagi setiap orang. Ketika anak belajar maka
pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan, nilai, sikap dan tingkah laku dan
semua semua perbuatan manusia terbentuk, disesuaikan dan dikembangkan.
Peneliti menyimpulkan dari berbagai pandangan para ahli bahwa belajar selalu
melibatkan tiga hal pokok yaitu adanya perubahan tingkah laku, perubahan
relatif, bersifat permanen dan perubahan tersebut disebabkan oleh interaksi
dengan lingkungan.
Istilah pembelajaran merupakan padanan dari kata dalam bahasa Inggris in-struction, yang berarti proses membuat orang belajar. Tujuannya adalah membantu orang belajar, atau memanipulasi (merekayasa) lingkungan
sehingga memberikan kemudahan bagi orang yang belajar. Gagne
mendefinisikan pembelajaran sebagai suatu rangkaian events (kejadian, peristiwa, kondisi, dan sebagainya) yang sengaja dirancang untuk
mempengaruhi siswa (pembelajar), sehingga proses belajarnya dapat
berlangsung dengan mudah (Tasrif, 2008: 104). Menurut Dimyati dan
Mujiono (2006: 175) pembelajaran adalah suatu kegiatan agar proses belajar
dapat tercapai secara efektif dan efesien. Pembelajaran akan menghasilkan
suatu kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar. Pembelajaran dengan
demikian adalah kegiatan aplikatif dari belajar, sebagai usaha untuk
menghasilkan tujuan belajar, yaitu perubahan perilaku manusia berdasarkan
pengetahuan, pemahaman yang telah diperolehnya.
Menurut Trianto (2009: 17) pembelajaran hakikatnya adalah usaha sadar dari
seorang guru untuk membelajarkan siswanya (mengarahkan interaksi siswa
dengan sumber belajar lainnya) dalam rangka mencapai tujuan yang
diharapkan. Pendapat di atas menunjukan bahwa pembelajaran adalah sebuah
proses interaksi antara guru, siswa dan sumber belajar lainnya yang beritrekasi
secara intens untuk memperoleh pengetahuan sebagai tujuan belajar.
Pembelajaran mengacu pada segala kegiatan yang dirancang untuk
mendukung proses belajar yang ditandai dengan adanya perubahan perilaku
individu yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ciri-ciri pembelajaran
adalah kegiatannya mendukung proses belajar siswa, adanya interaksi antara
individu dengan sumber belajar, serta memiliki komponen-komponen tujuan,
materi, proses dan evaluasi yang saling berkaitan. Peneliti menyimpulkan dari
berbagai defenisi yang dikemukakan oleh ahli bahwa pembelajaran
merupakan penerapan prinsip serta teori belajar.
2.4.1 Teori Belajar Konstruktivisme
Penelitian ini dilandasi oleh suatu pendekatan konstruktivistik, menurut
pandangan konstruktivistik belajar adalah menekankan pada peran aktif
informasi. Constructivim approach is a view that emphasizes the active role of learner in building understanding and making sense of information(Woolfolk, 2004: 313).
Konstruktivis adalah salah satu filsafat pengetahuan yang menekankan
bahwa pengetahuan kita adalah konstruksi diri kita sendiri. Pandangan
konstruktivisme dalam pembelajaran mengatakan bahwa anak-anak
diberi kesempatan agar menggunakan strategi sendiri dalam belajar
secara sadar, sedangkan guru yang membimbing siswa ke tingkat
pengetahuan yang lebih tinggi (Suparno, 1997: 29).
Prinsip-prinsip teori konstruktivisme menurut driver sebagai berikut.
1. Pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri baik secara personil maupun secara sosial.
2. Pengetahuan tidak dapat dipendahkan dari guru ke siswa, kecuali dengan keaktifan siswa sendiri untuk menalar.
3. Secara aktif melakukan konstruksi terus-menerus, sehingga selalu terjadi perubahan menuju konsep yang lebih rinci, lengkap serta sesuai dengan konsep ilmiah.
4. Guru hanya sekedar menyediakan sarana dan situasi agar proses konstruksi siswa berjalan dengan mulus (Suparno, 1997: 49).
Implikasi dari teori konstruktivisme dalam pendidikan anak sebagai
berikut.
1. Tujuan pendidikan menurut teori belajar konstruktivisme adalah menghasilkan individu atau anak yang memiliki kemampuan berfikir untuk menyelesaikan setiap persolan yang dihadapi.
2. Kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi oleh peserta didik. Selain itu, latihan memecahkan masalah seringkali dilakukan melalui belajar kelompok dengan menganalisis masalah dalam kehidupan sehari-hari.
Berdasarkan teori konstruktivisme tugas guru adalah guru tidak hanya
sekedar memberikan pengetahuan kepada siswa tetapi melakukan
kegiatan yang memungkinkan siswa membangun sendiri
pengetahuannya, menginterpretasikan, mencari kejelasan dan bersikap
kritis sesuai dengan dunia nyata siswa. Teori konstruktivisme sesuai
dengan strategi pembelajaran bermain peran (role playing), dimana peran guru sebagai fasilitator dan motivator pada siswa bukan sebagai
pemberi informasi saja. Kemudian siswa diharapkan mampu
membangun atau mengkonstruksikan dirinya sesuai dengan dunia nyata
siswa.
2.4.2 Teori Belajar Kognitif
Aliran kognitif mulai muncul pada tahun 60-an sebagai gejala
ketidakpuasan terhadap konsep manusia menurut behaviorisme.
Menurut teori kognitivisme manusia tidak memberikan respon secara
otomatis kepada stimulus yang dihadapkan kepadanya karena manusia
adalah mahluk yang aktif yang dapat menafsirkan lingkungan dan dapat
merubahnya (Herpratiwi, 2009: 19). Ciri-ciri aliran kognitif adalah
mementingkan apa yang ada di dalam diri manusia, mementingkan
keseluruhan dari pada bagian-bagian, mementingkan peranan kognitif,
mementingkan waktu sekarang, dan mementingkan pembentukkan
Implikasi teori kognitivisme terhadap proses pembelajaran adalah untuk
meningkatkan kemampuan berfikir siswa, dan membantu siswa menjadi
pembelajar yang sukses, maka guru yang menganut paham
kognitivisme banyak melibatkan siswa dalam kegiatan dimana faktor
motivasi, kemampuan problem solving, model belajar sering ditekankan. Proses belajar dalam kognitivisme tidak lagi dipandang
sebagai pembentukan perilaku yang diperoleh dari hubungan S-R secara
kaku, dan adanya penguatan-penguatan, tetapi mencakup fungsi
pengalaman perseptual dan proses kognitif yang meliputi ingatan,
pengolahan informasi dan sebagainya.
Piaget merupakan salah seorang tokoh yang disebut sebagai pelopor
aliran konstruktivisme. Salah satu sumbangan pemikirannya yang
banyak digunakan sebagai rujukan untuk memahami perkembangan
kognitif individu yaitu teori tentang tahapan perkembangan individu.
Menurut Piaget dalam Suparno (2001: 56) bahwa perkembangan
kognitif individu meliputi empat tahap antara lain sebagai berikut. (1)
Sensory motor; (2) pre operational; (3) concrete operational dan (4)
formal operational. Pemikiran lain dari Piaget tentang proses rekonstruksi pengetahuan individu yaitu asimilasi dan akomodasi.
Belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap
perkembangan kognitif siswa. Siswa hendaknya diberi kesempatan
untuk melakukan eksperimen dengan obyek fisik, yang ditunjang oleh
Guru hendaknya banyak memberikan rangsangan kepada siswa agar
mau berinteraksi denga