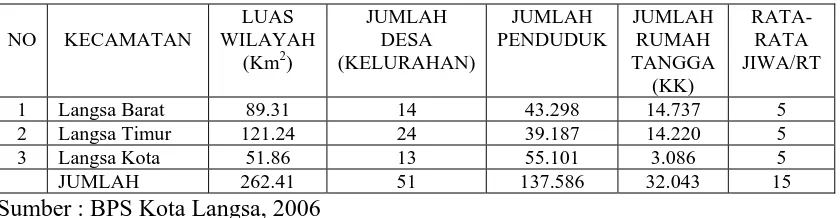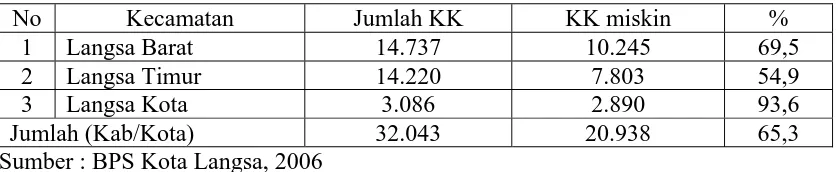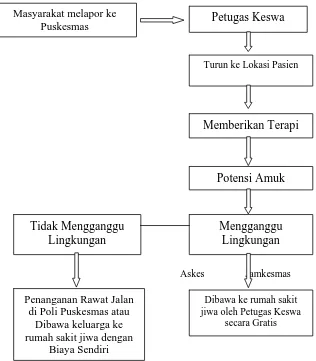PERILAKU MASYARAKAT DALAM PENANGANAN GANGGUAN JIWA DI KOTA LANGSA
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TESIS
OLEH : IDWAR 077033013/IKM
PROGRAM STUDI S2 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA M E D A N
PERILAKU MASYARAKAT DALAM PENANGANAN GANGGUAN JIWA DI KOTA LANGSA
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TESIS
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Magister Kesehatan (M.Kes) dalam Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat
Minat Studi Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku pada Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Sumatera Utara
Oleh : IDWAR 077033013/IKM
PROGRAM STUDI S2 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA M E D A N
Judul Tesis : PERILAKU MASYARAKAT DALAM PENANGANAN GANGGUAN JIWA DI KOTA LANGSA PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
Nama Mahasiswa : Idwar Nomor Induk Mahasiswa : 077033013
Program Studi : S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat
Minat Studi : Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku
Menyetujui Komisi Pembimbing :
(Dr. Fikarwin Zuska) (Dra. Syarifah, M.S)
Ketua Anggota
Ketua Program Studi Dekan
(Dr. Drs. Surya Utama, M.S) (Dr. Drs. Surya Utama, M.S)
Telah diuji pada
Tanggal : 15 Maret 2010
PANITIA PENGUJI TESIS
Ketua : Dr. Fikarwin Zuska Anggota : 1. Dra. Syarifah, M.S
PERNYATAAN
PERILAKU MASYARAKAT DALAM PENANGANAN GANGGUAN JIWA DI KOTA LANGSA
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TESIS
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah
diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam
naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.
Medan, Februari 2010
ABSTRAK
Gangguan kesehatan jiwa masyarakat akibat konflik dan bencana alam di kota Langsa mengalami peningkatan yang cukup besar, hal ini merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh tenaga kesehatan dalam melakukan penanganan secara terpadu dan komprehensif. Di kota Langsa pemanfaatan sarana pelayanan kesehatan jiwa belum mengatasi masalah gangguan jiwa di masyarakat.
Penelitian ini dilakukan dalam bentuk penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik content analisis. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis perilaku masyarakat dalam menangani penderita gangguan jiwa di Kota Langsa, dan informan dari penelitian ini terdiri dari keluarga, tokoh masyarakat dan tenaga kesehatan.
Hasil penelitian perilaku masyarakat dalam penanganan penderita gangguan jiwa hampir sama. Persepsi di masyarakat bahwa gangguan jiwa terjadi karena “guna-guna” (personalistik), sehingga tindakan awal pencarian pengobatan secara tradisional dengan menggunakan dukun. Pengobatan dengan berbagai dukun ternyata tidak memberikan kesembuhan, kemudian masyarakat menggunakan sistem medis modern, yaitu berobat ke sarana kesehatan. Pengobatan dengan medis modern memberikan kesembuhan, tetapi setelah penderita gangguan jiwa kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat kembali mengalami kekambuhan. sehingga pada akhirnya penanganan terakhir yang dilakukan oleh keluarga adalah dengan merantai, mengurung di kamar dan memasung.
Disarankan kepada petugas kesehatan perlu peningkatan kerjasama dengan keluarga penderita gangguan jiwa tentang cara-cara perawatan ataupun penanganan penderita gangguan jiwa, sehingga setelah penderita kembali ke rumah metode perawatan dapat dilanjutkan oleh keluarga. Selain itu dilakukan peningkatan penyuluhan kepada masyarakat, agar dapat mengubah stigma terhadap penderita gangguan jiwa.
ABSTRACT
Mental health disorder in the community resulted from military conflict and natural disaster in the area of Langsa city has been increased that becomes a challenge faced by the health workers in doing an integrated and comprehensive in handling it. Utilization of mental health care facilities had not overcome the problem of mental disorder in the community of Langsa city.
This is qualitative research with content analysis. The objective of this research was to analyze the behavior of community in managing the skizofrenia patient in Langsa city. The technique in data collection used observation and in-depth interview, and informants of this study consisted of families, community leaders and officers of health
The result of the research showed that the behavior of community in managing the skizofrenia patient were almost similar. The perception of the community regarding the skizofrenia were caused by magician influence (personalistic) and usually they seek out the help form magician. The treatment using modern medical may caused the recovery, and being returning to his families, the disease again. Consequently, seeing the disease suffered, the families put the sufferer on the chain and even put the sufferer on special room.
It is suggested for health officers to maintain good cooperation with the families of the sufferer related to the ways to manage the patient. It is intended that being returned home, the methode can be applied by the families. In addition, health officers should give counseling for the community, especially for the surrounding people of the patient, to the change the stigma of the people to the patient and to treat the patient well to prevent the incurrence.
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat
dan rahmat serta pertolonganNya yang berlimpah sehingga penulis dapat
menyelesaikan penelitian dan penyusunan tesis ini dengan judul “Perilaku
Masyarakat dalam Penanganan Gangguan Jiwa di Kota Langsa Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam Tahun 2009”.
Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan akademik untuk
menyelesaikan pendidikan pada Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Minat
Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas
Sumatera Utara.
Dalam menyusun tesis ini, penulis mendapat bantuan, dorongan dan
bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan
terima kasih dan penghargaan kepada Rektor Universitas Sumatera Utara, yaitu
Prof. Dr.dr.Syahril Pasaribu, DTM&H, M,Sc (CTM), Sp.A(K).
Selanjutnya kepada Dr. Drs. Surya Utama, M.S, selaku Dekan Fakultas
Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara dan Ketua Program Studi S2 Ilmu
Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara,
dan juga kepada Dr. Drs. R. Kintoko Rochadi, M.K.M, selaku Sekretaris Program
Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas
Terima kasih penulis ucapkan kepada Dr. Fikarwin Zuska, selaku ketua
komisi pembimbing dan Dra. Syarifah, M.S, selaku anggota komisi pembimbing
yang dengan penuh perhatian dan kesabaran membimbing, mengarahkan dan
meluangkan waktu untuk membimbing penulis mulai dari proposal hingga penulisan
tesis selesai.
Terima kasih penulis ucapkan kepada Dr. Drs. R. Kintoko Rochadi, M.K.M
dan Ferry Novliadi, S.Psi, M.Psi, selaku penguji tesis yang dengan penuh perhatian
dan kesabaran membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktu untuk
membimbing penulis mulai dari proposal hingga penulisan tesis ini.
Selanjutnya terima kasih juga kepada Junaidi, S.K.M, M.Kes selaku Kepala
Dinas Kesehatan Kota Langsa yang telah memberikan izin kepada penulis untuk
melakukan penelitian di Puskesmas Wilayah Kota Langsa.
Terima kasih juga kepada para dosen dan staf di lingkungan Program Studi S2
Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera
Utara.
Ucapan terima kasih yang tulus dan ikhlas kepada Ayahanda (Alm) Ishaq Bin
Budiman dan (Alm) Khomariah Binti Thahir atas segala jasanya sehingga penulis
selalu mendapatkan pendidikan terbaik
Teristimewa buat istri tercinta Cut Soraya, S.K.M. dan ananda tersayang
Cut Idsy Sona Pasha, Muammar Afdhally dan Muammar Afdhylla yang penuh
menunggu, memotivasi dan memberikan dukungan moril agar bisa menyelesaikan
pendidikan ini.
Akhirnya penulis menyadari atas segala keterbatasan, untuk itu saran dan
kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini, dengan
harapan semoga tesis ini bermanfaat bagi pengambil kebijakan di bidang kesehatan
dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi penelitian selanjutnya.
Medan, Februari 2010
Penulis
RIWAYAT HIDUP
Idwar lahir pada tanggal 17 Agustus 1971 di Kota Sigli, anak ketiga dari tujuh
bersaudara dari pasangan Ayahanda (Alm) Ishaq Bin Budiman dan Ibunda (Alm)
Khamariah Binti Thahir.
Pendidikan formal penulis, dimulai dari pendidikan sekolah dasar di Sekolah
Dasar Negeri Nyong Lueng Putu selesai tahun 1983, Sekolah Menengah Pertama di
SMP Negeri Lueng Putu selesai tahun 1986, Sekolah Menengah Umum Negeri I
Lueng Putu selesai tahun 1989, Program Akademi Keperawatan Fakinah Banda Aceh
selesai tahun 1994, melanjutkan S-1 di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas
Padjadjaran Bandung selesai tahun 2000.
Mulai bekerja sebagai perawat di Rumah Sakit Tengku Fakinah Banda Aceh
tahun 1994 sampai 1996 sebagai karyawan biasa, kemudian bekerja pada Akademi
Keperawatan Cut Nyak Dien Langsa pada mulai 1 Maret 1996 sampai 2010. Sebagai
Pegawai Negeri Sipil di Poltekkes Nanggroe Aceh Darussalam pada tahun 2001.
Pada tanggal 13 Januari tahun 2001, penulis menikah dengan Cut Soraya,
S.K.M. anak kelima dari lima bersaudara anak dari Bapak Rusli dengan Syarifah
Hamidah, dan penulis dikaruniai tiga orang putra/putri bernama Cut Isdy Sona Pasha,
Muammar Afdhylla dan Muammar Afdhally.
Tahun 2007 penulis mengikuti pendidikan lanjutan di Program Studi S2 Ilmu
Kesehatan Masyarakat, minat Studi Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Fakultas
DAFTAR ISI BAB III METODE PENELITIAN 3.1. Jenis Penelitian... 19
3.2. Lokasi dan waktu penelitian... 20
3.3. Pemilihan Informan... 20
3.4. Metode Pengumpulan Data ... 22
3.5. Prosedur Penelitian ... 23
3.6. Metode Analisis Data... 25
BAB IV HASIL PENELITIAN 4.1. Gambaran Umum Kota Langsa... 27
4.1.1 Letak Geografis dan Kependudukan... 27
4.1.2. Pendidikan dan Sosial Ekonomi ... 28
4.2. Objek Penelitian ... 30
4.2.1. Miah ... 30
4.2.2. Aini... 33
BAB V PEMBAHASAN
5.1. Penyebab Gangguan Jiwa ... 43
5.2. Perilaku Masyarakat Dalam Penanganan Penderita Gangguan Jiwa ... 47
5.2.1. Mengurung ... 50
5.2.2. Merantai ... 53
5.2.3. Memasung ... 55
5.3. Penanganan Penderita Gangguan Jiwa Oleh Pemerintah.... 61
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 6.1. Kesimpulan ... 71
6.2. Saran ... 72
DAFTAR PUSTAKA ... 74
DAFTAR TABEL
Nomor Judul Halaman
1 Luas Wilayah, Jumlah Desa, Jumlah Penduduk, Jumlah
Rumah Tangga dan Rata-Rata Jiwa/RT... 28
DAFTAR GAMBAR
Nomor Judul Halaman
4.1 Miah ... 33
4.2 Aini, Rantai dan Gubuknya... 38
4.3 Iya, Rumah Orangtuanya dan Pohon Kapuk... 42
DAFTAR LAMPIRAN
Nomor Judul Halaman
1. Pedoman Wawancara... 77
2. Surat Izin Penelitian dari Dekan FKM USU Medan... 79
3. Surat Balasan Izin Penelitian dari Dinas Kesehatan Kota Langsa Provinsi Nangroe Aceh Darussalam... 80
4. Field Note... 81
5. Photo-photo Subjek Penelitian :... 98
- Miah dikurung... 97
- Nur’aini dirantai... 99
ABSTRAK
Gangguan kesehatan jiwa masyarakat akibat konflik dan bencana alam di kota Langsa mengalami peningkatan yang cukup besar, hal ini merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh tenaga kesehatan dalam melakukan penanganan secara terpadu dan komprehensif. Di kota Langsa pemanfaatan sarana pelayanan kesehatan jiwa belum mengatasi masalah gangguan jiwa di masyarakat.
Penelitian ini dilakukan dalam bentuk penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik content analisis. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis perilaku masyarakat dalam menangani penderita gangguan jiwa di Kota Langsa, dan informan dari penelitian ini terdiri dari keluarga, tokoh masyarakat dan tenaga kesehatan.
Hasil penelitian perilaku masyarakat dalam penanganan penderita gangguan jiwa hampir sama. Persepsi di masyarakat bahwa gangguan jiwa terjadi karena “guna-guna” (personalistik), sehingga tindakan awal pencarian pengobatan secara tradisional dengan menggunakan dukun. Pengobatan dengan berbagai dukun ternyata tidak memberikan kesembuhan, kemudian masyarakat menggunakan sistem medis modern, yaitu berobat ke sarana kesehatan. Pengobatan dengan medis modern memberikan kesembuhan, tetapi setelah penderita gangguan jiwa kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat kembali mengalami kekambuhan. sehingga pada akhirnya penanganan terakhir yang dilakukan oleh keluarga adalah dengan merantai, mengurung di kamar dan memasung.
Disarankan kepada petugas kesehatan perlu peningkatan kerjasama dengan keluarga penderita gangguan jiwa tentang cara-cara perawatan ataupun penanganan penderita gangguan jiwa, sehingga setelah penderita kembali ke rumah metode perawatan dapat dilanjutkan oleh keluarga. Selain itu dilakukan peningkatan penyuluhan kepada masyarakat, agar dapat mengubah stigma terhadap penderita gangguan jiwa.
ABSTRACT
Mental health disorder in the community resulted from military conflict and natural disaster in the area of Langsa city has been increased that becomes a challenge faced by the health workers in doing an integrated and comprehensive in handling it. Utilization of mental health care facilities had not overcome the problem of mental disorder in the community of Langsa city.
This is qualitative research with content analysis. The objective of this research was to analyze the behavior of community in managing the skizofrenia patient in Langsa city. The technique in data collection used observation and in-depth interview, and informants of this study consisted of families, community leaders and officers of health
The result of the research showed that the behavior of community in managing the skizofrenia patient were almost similar. The perception of the community regarding the skizofrenia were caused by magician influence (personalistic) and usually they seek out the help form magician. The treatment using modern medical may caused the recovery, and being returning to his families, the disease again. Consequently, seeing the disease suffered, the families put the sufferer on the chain and even put the sufferer on special room.
It is suggested for health officers to maintain good cooperation with the families of the sufferer related to the ways to manage the patient. It is intended that being returned home, the methode can be applied by the families. In addition, health officers should give counseling for the community, especially for the surrounding people of the patient, to the change the stigma of the people to the patient and to treat the patient well to prevent the incurrence.
BAB I PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang
Tesis ini mengkaji tentang perilaku keluarga dalam penanganan penderita
gangguan jiwa (skizofrenia). Sampai saat ini penanganan penderita gangguan jiwa
masih sangat bervariasi di masyarakat. Pada umumnya keluarga-keluarga yang
memiliki anggota keluarga yang terkena penyakit gangguan jiwa akan menangani
sesuai dengan persepsi masing-masing dan merasa apa yang telah mereka lakukan
adalah sebuah upaya maksimal untuk dapat menyembuhkan si penderita.
Selain perilaku masyarakat dalam penanganan penderita gangguan jiwa, maka
tindakan atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini departemen
kesehatan, juga menjadi bagian dari kajian. Pengkajian upaya penanganan penderita
gangguan jiwa dari sisi departemen kesehatan (baik instansi Rumah Sakit Jiwa dan
Puskesmas) dikarenakan instansi tersebut juga memiliki tanggung jawab untuk
memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Ada beberapa alasan yang menjadi bahan pertimbangan sehingga tesis ini
memilih perilaku masyarakat dengan subjek penelitian penderita gangguan jiwa.
Gangguan jiwa adalah masalah kesehatan masyarakat. Sampai saat ini ada
kecenderungan penderita dengan gangguan jiwa jumlahnya mengalami peningkatan.
Hasil studi Bank Dunia menunjukkan, global burden of disease akibat masalah
kanker (5,8 persen), penyakit jantung (4,4 persen), atau malaria (2,6 persen)
(http://www.gizi.net, 2001).
Hasil Survey Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) yang dilakukan Badan
Litbang Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 1995, memperkirakan
terdapat 264 dari 1000 anggota Rumah Tangga menderita gangguan kesehatan jiwa.
Dalam kurun waktu enam tahun terakhir ini, jumlah tersebut dapat dipastikan
meningkat karena krisis ekonomi dan gejolak-gejolak lainnya diseluruh daerah.
Bahkan masalah dunia internasionalpun akan ikut memicu terjadinya peningkatan
tersebut (http://faperta.ugm.ac.id, 2002).
Angka itu menunjukkan jumlah penderita gangguan kesehatan jiwa di
masyarakat sangat tinggi, yakni satu dari empat penduduk Indonesia menderita
kelainan jiwa, mulai dari rasa cemas, depresi, stres, penyalahgunaan obat, kenakalan
remaja sampai skizofrenia. Bukti lainnya, berdasarkan data statistik bahwa angka
penderita gangguan kesehatan jiwa memang mengkhawatirkan. Secara global, dari
sekitar 450 juta orang yang mengalami gangguan mental, sekitar satu juta orang di
antaranya meninggal dunia karena bunuh diri setiap tahunnya. Angka ini lumayan
kecil jika dibandingkan dengan upaya bunuh diri para penderita kejiwaan yang
mencapai 20 juta jiwa setiap tahunnya (Azwar, 2002).
Hasil penelitian Harvard dan International Organization for Migration (IOM)
pada tahun 2007 terhadap masyarakat yang terkena dampak konflik di 14 kabupaten
mengalami gejala depresi, 10 % gejala Post Traumatic Stress Disorder dan 3%
dengan gejala kecemasan lainnya.
Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Provinsi NAD (2007), bahwa masyarakat
yang terindikasi gangguan jiwa sebanyak 1.677 jiwa (31,12%) termasuk kategori
berat, 1.591 jiwa (29,52%) dengan gangguan neurotic dan 1.190 jiwa (22,98%)
dengan psikotik akut serta sebanyak 334 jiwa (6,20%) dengan depresi. Data tersebut
menunjukkan bahwa masih tinggi kasus gangguan jiwa di Nanggroe Aceh
Darussalam.
Gangguan jiwa merupakan kumpulan dari keadaan-keadaan yang tidak normal,
baik fisik maupun mental. Keabnormalan tersebut terdiri dari gangguan jiwa
(neurosa) dan sakit jiwa (psikosa). Keabnormalan terlihat dalam berbagai gejala yang terpenting diantaranya adalah ketegangan, rasa putus asa, murung, gelisah, cemas,
perbuatan-perbuatan yang terpaksa (convulsive), histeri, rasa lemah dan tidak mampu
mencapai tujuan, takut, pikiran-pikiran buruk, dan sebagainya. Menurut Darajat,
orang yang terkena gangguan jiwa masih mengetahui dan merasakan kesukarannya
dan masih hidup dalam alam kenyataan pada umumnya, sedangkan penderita psikosa
tidak ada integritas dan mereka hidup jauh dari alam kenyataan (Yosep, 2007).
Hasil studi memperlihatkan bahwa 20-24 % pasien yang datang berobat ke
pelayanan primer memperlihatkan sedikitnya satu gejala gangguan jiwa. Golberg
and Huxley (1992) menyebutkan bahwa prevalensi populasi dewasa yang mengalami
sedangkan yang berobat ke pelayanan tersier (Rumah Sakit Jiwa) hanya 23,5/1000
penduduk.
Dalam pengobatan penderita gangguan jiwa terdapat perbedaan pada setiap
masyarakat. Sebagian masyarakat New Guinea misalnya, penderita gangguan jiwa
dianggap kerasukan setan, karena itu perlu diobati dengan cara kaki dan tangannya
diikat dan kemudian diasapi sampai muntah. Di Nigeria, sebagian penderita
gangguan jiwa tinggal di rumah shaman atau dukun selama 3-4 bulan dan penderita
dirawat oleh saudaranya yang tinggal bersama si pasien di rumah dukun. Biasanya si
pasien dibelenggu dan diberi ramu-ramuan dan dukun memberikan korban binatang
pada roh gaib. Apabila si pasien sembuh, lalu diadakan upacara ditepi sungai dengan
diikuti korban darah binatang sebagai simbol membersihkan si pasien dari sakitnya
atau kelahiran kembali (Sudarti, 1986).
Akibatnya, banyak penanganan pasien gangguan jiwa yang dilakukan secara
mandiri oleh keluarga dengan cara yang tidak tepat sesuai dengan prosedur
kesehatan. Sebagai contoh, sebagian warga masyarakat di Aceh melakukan
pemasungan, mengurung penderita gangguan jiwa dan memperlakukan pasien dengan
tidak manusiawi bahkan ada keluarga dengan sengaja membuang anggota keluarga
yang mengalami gangguan jiwa karena dianggap aib. Demikian juga ketika keluarga
mengetahui salah satu anggotanya mulai menampakkan gejala gangguan jiwa, maka
oleh sebagian kalangan ia dianggap kemasukan roh halus. Untuk kasus semacam ini,
masyarakat memilih membawanya ke dukun, bukan ke dokter jiwa
Di Indonesia penanganan gangguan jiwa dilakukan dengan cara dipasung oleh
sebagian kalangan. Bahkan keluarga dengan sengaja mendislokasi anggota keluarga
yang mengalami gangguan jiwa karena dianggap aib. Demikian juga ketika keluarga
mengetahui salah satu anggotanya mulai menampakkan gejala gangguan jiwa,
dianggap kemasukan roh halus. Masyarakat memilih membawanya ke dukun, bukan
ke dokter jiwa (http://www.depkes.go.id,2006).
Menurut Dinkes Prov. NAD tahun 2007, pemerintah telah melakukan berbagai
upaya untuk menanggulangi kesehatan jiwa masyarakat dan mulai dirintis pada tahun
2002 karena dikhawatirkan terjadi kecenderungan peningkatan kasus gangguan
psikologis di masyarakat akibat adanya konflik yang berkepanjangan. Kegiatan awal
yang dilakukan adalah pelatihan tenaga dokter dan perawat untuk mampu melakukan
deteksi dini gangguan jiwa di masyarakat, mampu memberikan terapi sesuai
kewenangannya dan memberikan konseling kepada klien yang dipastikan mengalami
gangguan. Kondisi pasca tsunami ternyata membuktikan bahwa trend kejadian
gangguan jiwa dan psikososial semakin meningkat.
Menurut Dinkes Prov. NAD tahun 2007, kegiatan ini diawali dengan kajian
kondisi masyarakat yang tinggal didaerah konflik dan kondisi masyarakat yang
terkena bencana tsunami. Awal Juli tahun 2006 melalui lokakarya, seminar dan
desiminasi, hasil kajian tentang kesehatan jiwa masyarakat di Provinsi NAD, maka
ditetapkan suatu pendekatan Community Mental Health Nursing (CHMN) yaitu suatu
pendekatan asuhan keperawatan jiwa masyarakat yang dapat dilakukan oleh perawat
kesehatan jiwa maupun psikiatri atau dokter spesialis kesehatan jiwa (Dinkes Prov.
NAD, 2007).
Seperti diketahui, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia
(PDSKJI) menjelaskan bahwa saat ini hanya tersedia sekitar 500 tenaga medis,
seperti dokter jiwa, yang menangani 2.500 pasien. Artinya setiap dokter jiwa
menangani 5 pasien gangguan jiwa, sehingga pemantauannya lebih menjadi tidak
maksimal (Depkes RI, 2006).
Menurut Profil Dinkes Kota Langsa tahun 2007, hal ini dapat dilihat dari data
kasus yang sudah mendapatkan tindakan asuhan keperawatan oleh petugas
Community Mental Health Nursing (CMHN) adalah hanya 3.656 kasus (47%) (Profil
Dinkes Provinsi NAD, 2007). Di Kota Langsa tahun 2006 diketahui bahwa jumlah
penderita gangguan jiwa yang ditangani oleh CHMN sebanyak 42%.
Saat ini jumlah pasien yang dipasung sekitar 133 orang dan sebanyak 62 kasus
yang ditangani sudah dilepas dari pasungannya (Dinkes Prov. NAD, 2007). Kepala
Rumah Sakit Jiwa (RSJ) NAD, Saifuddin memperkirakan saat ini terdapat sekitar 100
orang penderita gangguan jiwa yang bertahun-tahun terpasung akibat kondisi
keuangan keluarganya memprihatinkan. Faktor kemiskinan dan rendahnya
pendidikan keluarga merupakan salah satu penyebab pasien gangguan jiwa berat
hidup terpasung. Para penderita gangguan jiwa berat yang terpasung itu di antaranya
banyak ditemukan di Kabupaten Bireuen, Pidie, Pidie Jaya dan Aceh Utara serta
Di Kota langsa pada tahun 2006 dijumpai sebanyak 116 kasus penderita
gangguan jiwa dan yang sudah ditanggani 57 kasus sementara jumlah kasus yang
dipasung sebanyak 3 orang (Dinkes Kota Langsa, 2007).
Berdasarkan wawancara dengan petugas kesehatan jiwa yang telah terlatih di
Kota Langsa bulan Mei 2007, salah satu penyebab masih tingginya penanganan
pengobatan jiwa dengan cara dipasung adalah karena tingkat sosial ekonomi dan
pendidikan masyarakat yang masih rendah serta kekhawatiran keluarga terhadap
perilaku pasien dengan gangguan jiwa, salah satunya adalah perilaku mengamuk dan
melukai orang lain. Sementara untuk membawa mereka ke rumah sakit, tidaklah
mungkin karena biaya dan tempat pelayanan kesehatan yang sulit dijangkau.
Berdasarkan paparan di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang perilaku
masyarakat dalam penanganan gangguan jiwa di Kota Langsa Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam.
1.2. Permasalahan
Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian
yaitu bagaimanakah masyarakat Aceh baik keluarga atau pemerintah menangani
pasien gangguan jiwa yang semakin lama semakin meningkat. Yang dipicu oleh
konflik dan modernisasi serta keterbatasan fasilitas yang tidak merata, walaupun
1.3. Tujuan Penelitian
Untuk menganalisis perilaku masyarakat Aceh baik keluarga atau pemerintah
dalam menangani pasien gangguan jiwa yang semakin lama semakin meningkat, yang
dipicu oleh konflik dan modernisasi serta keterbatasan fasilitas yang tidak merata
walaupun alokasi dana dan pelatihan sudah sering dilakukan, dalam penanganan
penderita gangguan jiwa di Kota Langsa.
1.4. Manfaat Penelitian
1.4.1. Sebagai bahan informasi bagi lokasi penelitian tentang perilaku
masyarakat Kota Langsa dalam penanganan penderita gangguan jiwa.
1.4.2. Sebagai bahan masukan bagi institusi pendidikan dalam melakukan
penelitian kualitatif tentang perilaku masyarakat dalam penanganan
penderita gangguan jiwa.
1.4.3. Sebagai bahan masukan bagi petugas kesehatan terutama dokter dan
perawat jiwa agar mengetahui cara-cara masyarakat dalam penanganan
penderita dan dapat meningkatkan asuhan keperawatan terutama di
BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Perilaku
Perilaku manusia merupakan hasil dari pada segala macam pengalaman serta
interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan,
sikap dan tindakan. Perilaku merupakan respons/reaksi seorang individu terhadap
stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya, (Sarwono, 2007.
Perilaku adalah suatu reaksi psikis seseorang terhadap lingkungannya. Dari
batasan ini dapat diuraikan lagi bahwa reaksi manusia dapat berbentuk
macam-macam yang pada hakekatnya digolongkan menjadi dua yakni dalam bentuk pasif
(tanpa tindakan nyata atau abstrak) dan dalam bentuk aktif (dengan tindakan konkrit).
Pada dasarnya perilaku dapat diamati melalui sikap dan tindakan juga dalam sikap
potensial yakni dalam bentuk pengetahuan, motivasi dan persepsi (Notoatmodjo,
2003).
Perilaku manusia merupakan hasil daripada segala macam pengalaman serta
interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan,
sikap dan tindakan (Sarwono, 2004).
Umumnya perilaku dapat diramalkan jika kita tahu bagaimana orang
menangkap (mempersiapkan) situasi dan apa yang penting baginya. Sementara
perilaku mungkin tidak tampak rasional bagi orang luar, ada alasan untuk menyakini
oleh mereka. Sering seorang pengamat melihat perilaku sebagai tak rasional karena
pengamat itu tidak mempunyai akses ke informasi yang sama atau tidak
mempersepsikan lingkungannya dengan cara yang sama (Robbins, 2001).
Skiner dalam Notoatmodjo (2003) seorang ahli psikologi, merumuskan bahwa
perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus (rangsangan dari
luar). Oleh karena itu perilaku ini terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap
organisme, dan kemudian organisme tersebut merespon.
Dilihat dari bentuk respons terhadap stimulus ini, maka perilaku dapat
dibedakan menjadi dua :
1. Perilaku tertutup (covert behavior)
Respons seorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup
(covert). Respons atau reaksi terhadap stimulus ini masih terbatas pada perhatian,
persepsi, pengetahuan atau kesadaran dan sikap yang terjadi pada orang yang
menerima stimulus tersebut, dan belum dapat diamati secara jelas oleh orang lain.
Oleh sebab itu disebut covert behavior atau unobservable behavior.
2. Perilaku terbuka (overt behavior)
Respons seorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau
terbuka. Respons terhadap stimulus tersebut jelas dalam bentuk tindakan atau
praktek (practice) yang dengan mudah dapat diamati atau dilihat oleh orang lain.
2.2. Penanganan Gangguan Jiwa
Masalah gangguan jiwa merupakan perubahan pada fungsi jiwa yang
menyebabkan adanya gangguan pada fungsi jiwa, yang menimbulkan penderitan pada
individu dan atau hambatan dalam melaksanakan peran sosial (Depkes, 2003).
Istilah-istilah perilaku abnormal, perilaku maladaptive, gangguan mental, psikopatologi,
gangguan emosional, gangguan kejiwaan, gangguan perilaku. Gangguan mental dan
ketidakwarasan sering dipakai bergantian dan secara umum menunjuk pada gejala
yang sama. Gangguan mental menunjuk pada semua bentuk perilaku abnormal mulai
dari yang ringan sampai dengan yang melumpuhkan (Badran, 2005).
Gangguan jiwa adalah suatu kondisi kesehatan yang ditandai dengan adanya
perubahan dalam berfikir, suasana hati, atau perilaku (atau gabungan darinya) yang
berkaitan dengan distress dan/atau kerusakan fungsi. Sedangkan kesakitan jiwa
merupakan suatu istilah yang secara umum mengacu pada setiap gangguan jiwa yang
terdiagnosis. Penderita kesakitan jiwa mengalami gangguan organik atau metabolik
(biokimia) yang menghambat mereka untuk berfungsi secara efektif dan bahagia di
dalam masyarakat (McKenzie dkk,2007).
Menurut Maramis (2007), gangguan mental, disebut juga gangguan mental,
atau gangguan jiwa, adalah gangguan yang mengenai satu atau lebih fungsi mental.
Gangguan mental adalah gangguan otak yang ditandai oleh terganggunya emosi,
proses berpikir, perilaku dan persepsi (penangkapan panca indera). Penyakit mental
mental pada mengenai setiap orang, tanpa mengenai umur, ras, agama, maupun staus
sosiap-ekonomi. Penyakit mental bukan disebabkan oleh kelemahan pribadi.
Untuk dapat memahamki lebih baik terhadap bagaimana dikatakan gangguan
jiwa, maka ada baiknya untuk memahami bagaimana sebenarnya dikatakan seseorang
yang sehat jiwa. Kesehatan Jiwa adalah suatu kondisi yang memungkinkan
perkembangan fisik, intelektual dan emosional yang optimal dari seseorang dan
perkembangan itu berjalan selaras dengan keadaan orang lain. Makna kesehatan jiwa
mempunyai sifat-sifat yang harmonis (serasi) dan memperahtinkan semua segi-segi
dalam kehidupan manusia dan dalam hubungannya dengan manusia lain. Jadi dapat
disimpulkan bahwa keshatan jiwa adalah bagian integral dari kesehatan dan
merupakan kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, mental dan sosial
individu secara optimal dan yang selaras dengan perkembangan orang lain.
2.3. Penggolongan
Penggolongan gangguan jiwa, berdasarkan International Classification of
Diseases (IcD-X0 antara lain :
1. Gangguna mental organik
2. gangguan mental dan perilaku akibat gangguan mental simptomatik
3. Skizofrenia
4. Gangguan suasana perasaan seperti depresi, mania.
5. Ansietas (kecemasan)
7. Gangguan keperibadian dan perilaku masa dewasa
8. Retardasi mental
9. Gangguan brevaza, gangguan membaca, gangguan berhitung, autisme masa kayak
10.Gangguan hiperkinetik, gangguan tingkah laku (Depkes, 2003)
Pedoman diagnostic dari PPDGJ-III disusun berdasarkan atas jumlah dan
keseimbangan gejala-gejala yang biasnya ditemtukan pada kebanyakann kasus untuk
dapat menegakkan statu diagnosis pasti.
Gangguan mental organik adalah gangguan mental yang berkaitan dengan
penyakit / ganguan sistematik atau otak yang dapat didagnostik sendiri. Gambaran
utama gangguan mental organik adalah :
1. Gangguan fungsi kognitif, misalnya memori, daya piker, daya relajar.
2. Gangguan sensorium, misalnya gangguan kesadaran dan perhatian.
3. Sindrom dengan manifestasi yang menonjol dalam bidang persepsi, isi pikiran
dan Susana perasaan dan emosi (Maslim, 2003)
Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat merupakan gangguan
yang bervariasi luas dan berbeda keparahannya (dari intoksisasi tanpa komplikasi dan
penggunaan yang merugikan sampai ganguan psikotik yang jelas dan demensi, tetapi
semua itu diakibatkan olah karena penggunan satu atau lebih zat psikoaktif.
Skizofrenia adalah sekelompok gangguan psikotik dengan gangguan ndasar
pada kepribadian, distorsi khas proses pikir, Madang-kadnag mempunyai perasaan
afek abnormal yang terpadu dengan situasi nyata atau sebenarnya dan autismo
(Mansjoer, 2001).
Belait (2006) mengemukakan skizofrenia adalah suatu gangguan jira berat yang
ditandai dengan penurunan atau ketidakmampuan berkomunikasi, gangguan realitas
(halusinasi atau waham), afek yang tidak wajar atau tumpul, gangguan kognitif
(tidak mampu berpikir abstrae) serta mengalami kesukaran melakukan aktivitas
sehari-hari.
Gangguan suasana perasaan merupakan kelainan fundamental dari kelompok
gangguan yang dialami diantaranya perubahan suasana perasaan (mood) atau afek,
biasanya kearah depresi (dengan atau tanpa adanya anxietas yang menyertainya) atau
kearah elasi (suasana perasaan yang meningkat)
Gangguan neurotic, gangguan somatofrom dan gangguan terkait stress,
dikelompokkan menjadi satu dengan alasan bahwa dalam sejarahnya ada hubungan
dengan perkembangan konsep neurorsis dan berbagai kemungkinan penyebab
psikologis.
Ganggguan ansietas lainnya adalah sebagai berikut :
1. Manifestasi ansietas merupakan gejala utama dan tidak terbatas pada situasi
lingkungan tetentu saja.
2. Dapat disertai gejala-gejala depresi dan obsesif, bahkan juga beberapa unsur dari
ansietes fobia, asal saja jela bersifat sekunder atau ringan (Maslim, 2003)
Gangguan disosiasit fdengan gejala utama adanya kehilangan (sebagian atau
a. Ingatan masa lalu
b. Kesadaran identitias dan pengindraan segera
c. Kontrol terhadap gerakan tubuh
Gangguan somatoform memiliki ciri utama yakni adanya keluhan gejala fisik
yagn berulang-ulang disertai dengan permintaan pemeriksaan medik.
Menurut Suliswati (2005), gangguan jiwa dapat disebabkan oleh berbagai
faktor sebagai berikut:
1. Suasana rumah, (antara lain sering bertengkar, salah pengertian di antara anggota
keluarga, kurang kebahagiaan dan kepercayaan di antara anggota keluarga).
Sehingga dapat menimbulkan efek yang tidak diinginkan pada pada seorang
individu.
2. Pengalaman masa kanak-kanak. Kasih sayang yang cukup, bimbingan yang
sesuai, memberikan semangat dan disiplin merupakan hal yang penting untuk
pertumbuhan yang sehat dari seseorang. Bila tidak memadai dan terdapat
pengalaman yang tidak menyenangkan secara berulang pada masa kanak, dapat
menyebabkan gangguan jiwa pada kehidupan dewasa.
3. Faktor keturunan. Pada beberapa kasus gangguan jiwa, kemungkinan
didapatkannya anggota keluarga yang menderita penyakit yang sama. Pada kasus
gangguan jiwa yang lain, tidak ditemukan seorang pun dalam keluarganya dengan
gangguan yang serupa. Kecenderungan untuk berkembangnya suatu gangguan
jiwa dapat diturunkan pada seorang individu, tetapi apakah orang tersebut akan
4. Perubahan dalam otak. Setiap perubahan dalam struktur/fungsi otak dapat
menyebabkan gangguan jiwa. Perubahan biokimiawi pada sel-sel adalah
penyebab yang umum pada gangguan psikotik.
5. Faktor lain. Bila seorang individu tidak mendapat kesempatan yang cukup untuk
hidup sebagai anggota masyarakat yang diterima, dihargai, kemiskinan,
pengganguran, ketidakadilan, ketidakamanan, persaingan yang berat, diskriminasi
sosial dapat menimbulkan gangguan jiwa.
Adapun ciri-ciri gangguan jiwa (Suliswati dkk, 2005), meliputi:
1. Perubahan yang berulang dalam pikiran, daya ingat, persepsi yang bermanifestasi
sebagai kelainan bicara dan perilaku.
2. Perubahan ini menyebabkan tekanan batin dan penderitaan pada individu dan
orang lain dilingkungannya.
3. Perubahan perilaku, akibat dari penderitaan ini menyebabkan gangguan dalam
kegiatan sehari-hari, efisiensi kerja dan hubungan dengan orang lain.
Dalam pemberian pelayanan terhadap pasien gangguan jiwa, tujuan pengobatan
gangguan jiwa adalah (1) mengurangi gejala, (2) memperbaiki fungsi sosial dan
personal, (3) mengembangkan dan menguatkan dan memperkuat ketrampilan
penyesuaian diri, (4) meningkatkan perilaku yang membuat hidup seseorang lebih
baik (McKenzie,dkk,2007).
Menurut Hawari (2001) untuk pengobatan penderita gangguan jiwa telah
dikembangkan terapi yang komprehensif dan holistik, yang meliputi terapi dengan
Keluarga adalah merupakan kelompok primer yang paling penting dalam masyarakat. Keluarga merupakan sebuah group yang terbentuk dari penghubungan
laki-laki dan perempuan. Penghubungan tersebut sedikit banyak berlangsung lama
untuk menciptakan dan membesarkan anak-anak. Jadi keluarga dalam bentuk yang
murni merupakan satu kesatuan sosial yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak
yang belum dewasa. Satuan ini mempunyai sifat-sifat tertentu yang sama dimana saja
dalam satuan masyarakat manusia (Ahmadi, 1999).
Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya mengembangkan
kesehatan mental anak. Perawatan orang tua yang penuh kasih sayang dan pendidikan
tentang nilai-nilai kehidupan, baik agama maupun sosial budaya, yang diberikannya
merupakan faktor yang kondusif untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi dan
anggota masyarakat yang sehat. Agama memberikan petunjuk tentang tugas dan
fungsi orang tua dalam merawat dan mendidik anak, agar dalam hidupnya berada
dalam jalan yang benar, sehingga terhindar dari malapetaka kehidupan, baik di dunia
ini maupun di akhirat kelak (kandungan Alquran, Surat Attahrim:6). Rasulullah saw.
dalam salah satu hadisnya bersabda, "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah
(tauhiidulllah), karena orang tuanyalah anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi" (H.R. Bukhari & Muslim, dalam Panitia Mudzakarah Ulama, 1988) (Yusuf,
2005).
Tingkat ekonomi yang baik memungkinkan anggota keluarga untuk
memperoleh kebutuhan yang lebih misalnya di bidang pendidikan, kesehatan,
maka menjadi hambatan dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Keadaan
sosial ekonomi (kemiskinan, orang tua yang bekerja atau penghasilan rendah) yang
memegang peranan penting dalam meningkatkan status kesehatan keluarga. Jenis
pekerjaan orang tua erat kaitannya dengan tingkat penghasilan dan lingkungan kerja,
dimana bila penghasilan tinggi maka pemanfaatan pelayanan kesehatan dan
pencegahan penyakit juga meningkat, dibandingkan dengan penghasilan rendah akan
berdampak pada kurangnya pemanfaatan pelayanan kesehatan dalam hal
pemeliharaan kesehatan karena daya beli obat maupun biaya transportasi dalam
mengunjungi pusat pelayanan kesehatan.(Zacler, dalam Notoatmodjo, 1997).
Pendapatan merupakan ukuran yang sering digunakan untuk melihat kondisi
status sosial ekonomi pada suatu kelompok masyarakat. Semakin baik kondisi
ekonomi masyarakat semakin tinggi persentase yang menggunakan jasa kesehatan.
Data Survey Kesehatan Nasional tahun (1992), memperlihatkan rata-rata penggunaan
pelayanan kesehatan berhubungan dengan meningkatnya pendapatan, baik pada pria
maupun wanita, oleh karena itu status sosial ekonomi berhubungan dengan kondisi
BAB 3
METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian
Penelitian ini mengkaji tentang perilaku masyarakat dalam penanganan
penderita gangguan jiwa. Pengambilan keputusan oleh masyarakat dalam
penanganan penderita gangguan jiwa dipengaruhi persepsi. Persepsi yang dimiliki
bervariasi pada setiap orang dan terkait dengan penghayatan subjektif. Oleh sebab itu,
pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2006)
penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang memungkinkan peneliti
memahami permasalahan individu secara lebih mendalam dan kompleks,
memberikan gambaran secara holistik, disusun dari kata-kata, mendapatkan informasi
rinci yang diperoleh dari informan dan berada dalam setting alamiah.
Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan pendekatan fenomenologi, karena
Pendekatan fenomenologi menaruh minat pada ‘dunia kehidupan (life world)’ pribadi
individu dan kelompok, serta bagaimana life world tersebut mempengaruhi motif,
tindakan, serta komunikasi mereka (Daymon, 2001:218). Pendekatan fenomenologi
untuk melihat bahwa kenyataan bukanlah seperti apa yang tampak, tetapi kenyataan
ada di masing-masing kepala individu. Dalam penelitian ini fenomena yang ini digali
adalah fenomena penanganan penderita gangguan jiwa yang dilakukan oleh
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian dilakukan di wilayah Pemerintahan Kota Langsa, dengan alasan:
belum pernah dilakukan penelitian sejenis, banyak penderita gangguan jiwa yang
melakukan pemeriksaan dengan menggunakan jasa pengobatan tradisional. Lokasi
penelitian ini juga sangat dipahami oleh peneliti, sehingga akan memudahkan bagi
peneliti untuk melakukan wawancara mendalam (indeph interview) dan pengamatan
(observation) pada setiap kasus yang menjadi subjek penelitian.
Penelitian telah berlangsung sejak Februari 2009 sampai dengan Januari 2010.
3.3. Pemilihan Informan
Menurut Lincoln dan Guba (dalam Moleong, 2002) pada peradigma alamiah,
peneliti mulai dengan asumsi bahwa konteks itu kritis sehingga masing-masing
konteks itu ditangani dari segi konteksnya sendiri. Oleh karena itu, sampling ini
bertujuan untuk merinci kekhususan yang ada ke dalam ramuan konteks yang unik
sehingga digunakan teknik snow ball. Informan dipilih berdasarkan kriteria tertentu
yang telah ditetapkan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.
Penelitian ini mengambil objek penelitian sebanyak 3 orang penderita
gangguan jiwa yang secara langsung dirawat dan ditangani oleh keluargnya.
Pengambilan objek penelitian sebanyak 3 orang berdasarkan suatu pemikiran bahwa
dalam penelitian kualitatif menuntut suatu kedalaman penggalian informasi yang
berkaitan dengan objek atau permasalahan penelitian, oleh sebab itu tidak
Informan awal dalam penelitian ini adalah orangtua atau keluarga yang dapat
memberi informasi atau keterangan yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan penelitian.
Satuan analisisnya adalah keluarga dimana salah satu anggota keluarganya
mengalami gangguan jiwa di wilayah Pemerintahan Kota Langsa yang tercatat di
lokasi penelitian. Selain orangtua maka informan juga orang-orang terdekat yang
turut serta membantu atau mengetahui cara-cara penanganan yang diterima objek
penelitian tersebut. Sehingga, selain orangtua penderita gangguan jiwa, informan
selanjutnya adalah orang-orang yang dapat menjelaskan dan memberi keterangan atas
pertanyaan-pertanyaan yang terus berkembang di lapangan.
Informan lanjutan tersebut dapat tetangga, petugas kesehatan, dukun bahkan
pemilik warung yang cukup mengenal objek penelitian. Jadi tidak menutup
kemungkinan akan terus bertambahnya jumlah informan. Bertambahnya jumlah
informan didasarkan hasil analisis yang dilakukan dari setiap wawancara mendalam
yang dilakukan dengan orangtua maupun saudara, juga pengamatan terhadap objek
penelitian itu sendiri.
Hasil wawancara dan pengamatan dituangkan ke dalam bentuk ‘field note’
dan dianalisis. Analisis terus berlangsung sehingga jumlah informan lanjutan terus
bertambah sesuai dengan kebutuhan data penelitian. , sesuai kebutuhan-kebutuhan
akan informasi lanjutan untuk melengkapi data yang ada juga sebagai suatu proses
3.4. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data penelitian adalah wawancara mendalam secara
langsung terhadap infoman. Wawancara dilakukan terhadap informan dengan
mendatangi informan ke tempat tinggalnya. Observasi dilakukan terhadap objek
penelitian yang berkaitan dengan tingkah laku dan segala tindakan ataupun perlakuan
yang diterimanya.
Uji keabsahan data dilakukan dengan tehnik triangulasi data. Peneliti akan
memastikan bahwa catatan harian wawancara dengan informan dan catatan harian
observasi telah terhimpun. Kemudian dilakukan uji silang terhadap materi
catatan-catatan harian, untuk memastikan tidak ada informasi yang bertentangan antara
catatan harian wawancara dan catatan harian observasi. Jika ada perbedaan informasi
atau informasi tidak relevan, peneliti akan menelusuri sumber perbedaan tersebut dan
mengonfirmasi perbedaan tersebut pada informan dan sumber-sumber lainnya.
Proses trianggulasi dilakukan terus-menerus sepanjang proses mengumpulkan
data dan analisis data, sampai suatu saat peneliti yakin bahwa sudah tidak ada lagi
perbedaan-perbedaan, dan tidak ada lagi yang perlu dikonfirmasikan kepada informan
(Bungin, 2007:252)
Penelitian menggunakan data primer yaitu wawancara menggunakan pedoman
wawancara yang telah disusun dan data sekunder diperoleh dari Pemerintah Kota
Langsa. Bentuk pertanyaan yang digunakan pada umumnya adalah pertanyaan
terbuka, yang memungkinkan informan bebas mengekspresikan diri, menentukan
mereka pikir penting dan informasi penting yang sebelumya tidak terpikir oleh
peneliti.
Tehnik pengumpulan data dengan menggunakan alat bantu yaitu alat tulis,
‘note book’ dan kamera. Data hasil pengamatan dan wawancara umumnya langsung ditulis di tempat penelitian dalam bentuk tulisan-tulisan singkat. Tulisan-tulisan
singkat ini kemudian dikembangkan ke dalam bentuk ‘field note’ yang lebih rinci dan
lengkap.
Alat perekam tidak selalu digunakan dalam pengumpulan data, untuk
menghindarkan kecemasan atau kecanggungan informan dalam memberikan
jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Namun, sesekali alat perekam akan
digunakan untuk merekam jalannya wawancara (setelah mendapat persetujuan dari
informan dalam penggunaannya di lapangan), sehingga semua data penting yang
diungkapkan informan tidak ada yang hilang.
3.5. Prosedur Penelitian 1. Tahap Persiapan
Peneliti melakukan penyusunan pedoman wawancara berupa pertanyaan dasar
yang mencakup aspek kehidupan, latar belakang, pengetahuan gangguan jiwa dan
pandangan dalam menangani gangguan jiwa. Setelah itu peneliti menghubungi
puskesmas terdekat dan pengelola Community Mental Health Nursing (CMHN)
untuk mendapatkan informasi tentang individu yang dapat menjadi informasi
Kemudian menjumpai informan selanjutnya, begitu seterusnya sampai didapat
informan yang dianggap layak dan sesuai dengan kriteria subjek. Peneliti
kemudian memperkenalkan diri dan meminta kesediaan calon informan tersebut
untuk terlibat dalam penelitian yang dilakukan dalam bentuk menjawab
pertanyaan terbuka yang diajukan. Mengingat topik yang akan dibicarakan adalah
yang sensitif, peneliti menjelaskan terlebih dahulu mengenai informasi yang ingin
digali dari calon informan. Setelah membangun rapport dan memperoleh
kesediaan calon informan untuk terlibat dalam penelitian ini, peneliti kemudian
meminta kesediaan informan untuk bertemu/menentukan jadwal wawancara.
2. Tahap Pelaksanaan
Setelah diadakan kesepakatan waktu dan tempat, maka peneliti mulai melakukan
wawancara. Tahap pelaksanaan penelitian, diawali dengan mempersiapkan
peralatan yang dibutuhkan, mendatangi tempat dan waktu yang sebelumnya telah
disepakati bersama. Setelah itu, wawancara dilakukan berkaitan dengan latar
belakang kehidupan, pengalaman dan hal-hal yang berkaitan tentang perilaku
masyarakat dalam penangganan gangguan jiwa. Untuk memudahkan proses
pencatatan data, peneliti menggunakan alat rekam sebagai alat bantu, agar data
yang diperoleh dapat lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi
sebelum wawancara dimulai, peneliti meminta izin kepada informan untuk
merekam pembicaraan/wawancara yang dilakukan. Setelah keseluruhan
wawancara selesai dilakukan, peneliti membuat verbatim dari wawancara
Data yang dikumpulkan adalah semua hasil diskusi dan observasi yang
menggambarkan situasi, perangai dan ekspresi para peserta dan ungkapan lokal
yang relevan dengan permasalahan.
3. Hambatan-Hambatan
Dalam pelaksanaan penelitian ini terdapat beberapa hambatan di dalam
pengumpulan data-data yang diperlukan. Informasi yang ingin digali meliputi
informasi tentang masa lalu dari subjek penelitian, ada subjek penelitian yang
telah menderita penyakit gangguan jiwa cukup lama, sehingga wawancara harus
dilakukan dengan sabar sampai informan betul-betul dapat mengingatnya
kembali. Melalui cerita-cerita di masa lalu ini kemudian diperoleh informan
lanjutan, tetapi informan tersebut ada yang sudah tidak berada di tempat tersebut
sehingga peneliti harus menelusuri atau mencari informasi dimana
keberadaannya. Seperti dukun yang telah menangani penderita gangguan jiwa,
ada beberapa dukun yang sudah mencoba mengobati subjek penelitian, dukun
yang ingin dituju untuk menggali informasi darinya ternyata telah pindah,
sehingga peneliti harus kembali mewawancarai orangtua subjek penelitian dan
bertanya dukun yang lain yang pernah mengobati subjek penelitian.
3.6. Metode Analisis Data
Hal yang ingin dicapai dalam melakukan analisis data kualitatif adalah
menganalisis proses berlangsungnya suatu fenomena dan memperoleh gambaran
tuntas terhadap proses tersebut, serta menganalisis makna yang ada dibalik informasi,
jawaban-jawaban yang diberikan oleh informan. Penganalisisan data dilakukan
dengan tehnik “on going analysis” yaitu analisis yang terjadi di lapangan berdasarkan
data-data yang diperoleh.
Sedangkan metode analisis data menggunakan metode Analisis Domain yang
dikemukakan oleh Spradley dalam Faisal (1990) yaitu tehnik analisis dengan
memberikan makna atau arti pada kata, kalimat atau ucapan sebagai alasan yang
digunakan informan ketika menetapkan suatu bentuk persepsi atau pandangannya
BAB 4
HASIL PENELITIAN
4.1. Gambaran Umum Kota Langsa 4.1.1. Letak Geografis dan Kependudukan
Kota Langsa merupakan bagian dari Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Kota Langsa berdiri pada tahun 2001 yang merupakan pemekaran wilayah dari
Kabupaten Aceh Timur. Memiliki 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Langsa Barat,
Langsa Timur dan Langsa Kota. Terletak pada 04o24’35,68” – 04o33’47,03” Lintang
Utara dan 97o53’14,59” – 98o04’42,16” Bujur Timur. Luas wilayah keseluruhan
262,41 km2, panjang garis pantai 16 km dengan batasan wilayah :
- Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka
- Sebelah timur berbatasan dengan Kec. Manyak Paryd Kab. Aceh Tamiang
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur
- Sebelah barat berbatasan dengan Kec. Birem Bayeum Kab. Aceh Timur
Luas wilayah, jumlah desa, jumlah penduduk, jumlah rumah tangga serta rata-rata
Tabel 1. Luas Wilayah, Jumlah Desa, Jumlah Penduduk, Jumlah Rumah Tangga dan Sumber : BPS Kota Langsa, 2006
Dari Tabel 1 di atas terlihat bahwa kecamatan yang paling padat penduduknya
adalah kecamatan Langsa Kota. Dan, rata-rata rumah tangga memiliki anggota
keluarga sebesar 5 orang.
4.1.2. Pendidikan dan Sosial Ekonomi
Kemampuan baca tulis tercermin dari angka melek huruf penduduk yang
dalam hal ini didefenisikan penduduk usia 10 tahun ke atas yang dapat membaca dan
menulis huruf latin. Persentase penduduk Kota Langsa yang berumur 10 tahun ke atas
yang dapat membaca huruf latin di Kota Langsa tahun 2004 sebesar 24,76%.
Sedangkan penduduk Kota Langsa paling banyak berpendidikan SMU/SLTA, untuk
laki-laki sebanyak 17.680 jiwa dan perempuan sebesar 15.929 jiwa. Namun yang
tingkat pendidikannya SD/MI juga banyak yaitu sebesar 13.393 jiwa untuk laki-laki
dan sebesar 15.267 untuk perempuan (Dinkes dan Kesos, 2006:8).
Dari angka-angka di atas terlihat bahwa tingkat pendidikan masyarakat Kota
Langsa sangat rendah, tingkat pendidikan yang pernah dicapai adalah SMU/SLTA.
Jumlah penduduk miskin di Kota Langsa dari tahun ke tahun terjadi
peningkatan, hal ini disebabkan karena terjadinya bencana alam di beberapa wilayah
di Propinsi NAD, dimana terjadi perpindahan penduduk dan rendahnya lahan
pekerjaan yang disebabkan belum pulihnya kembali situasi dan kondisi pasca
bencana alam, sehingga angka penggangguran masih cukup tinggi. Jumlah persentase
keluarga miskin di Kota Langsa dapat dilihat pada Tabel 2 berikut :
Tabel 2. Persentase KK Miskin di Kota Langsa Tahun 2006
No Kecamatan Jumlah KK KK miskin %
1 Langsa Barat 14.737 10.245 69,5
2 Langsa Timur 14.220 7.803 54,9
3 Langsa Kota 3.086 2.890 93,6
Jumlah (Kab/Kota) 32.043 20.938 65,3
Sumber : BPS Kota Langsa, 2006
Dari sejumlah 32.043 rumah tangga yang ada di Kota Langsa, terdapat sebesar
20.938 keluarga yang termasuk dalam keluarga miskin. Hal ini menunjukkan bahwa
di Kota Langsa jumlah keluarga miskin masih cukup besar yaitu sebesar 65,3%.
Angka ini cukup tinggi telah melebihi 50% dari jumlah penduduk sehingga dapat
dikatakan rata-rata penduduk Kota Langsa berada pada garis kemiskinan.
Hal ini dapat menjadi pemicu peningkatan penderita gangguan jiwa. Menurut
Nurdin F. Joes (Kabag Humas Pemerintah Aceh) kepada Harian Serambi (11 Maret
2009) mengatakan bahwa hampir 15.000 orang dari 4,2 juta penduduk Aceh
menderita penyakit gangguan jiwa, sehingga dengan jumlah yang demikian besar
harus dibangun sebanyak 2 buah RSJ untuk dapat menangani seluruh jumlah
penderita gangguan jiwa.
4.2. Objek Penelitian 4.2.1. Miah
Miah adalah anak pertama dari keluarga bapak Abdul Salam. Sudah sejak 12
tahun yang lalu (sejak 1998) Miah menderita gangguan jiwa. Saat ini Miah telah
berusia 25 tahun. Menurut ibunya, sejak kecil Miah tumbuh seperti anak lainnya,
bersekolah dan bermain bersama temannya. Ibu sama sekali tidak mempunyai
bayangan bahwa suatu saat Miah akan menderita gangguan jiwa seperti saat ini.
Ibu Miah menuturkan bahwa ketika Miah baru menyelesaikan pendidikan
SMA, ada seorang pria yang mempunyai perhatian yang khusus pada diri anaknya.
Miah berkenalan dengan pria ini (sebut saja bernama Agus) pada sebuah acara pesta.
Miah dan Agus saat ini sama-sama menjadi panitia penyelenggaraan pesta di
desanya. Agus kemudian melakukan pendekatan kepada keluarga Miah, karena dia
sangat mencintai Miah. Namun, Miah dan keluarganya kurang memberikan respon
atas perhatian Agus karena Miah sendiri sudah memiliki pria idaman hati (sebut saja
namanya Joko), Joko memiliki pekerjaan tetap sedangkan Agus tidak. Agus sangat
kecewa dan sempat mengeluarkan kata-kata “Miah hanya untuk saya, tidak boleh
untuk pria lain”.
Hubungan Miah dengan Joko sempat berjalan setahun, namun keluarga Joko
hubungan dengan Miah. Sejak hubungan Miah dengan Joko berakhir, Miah jadi
sering duduk melamun sendiri, dan bertingkah laku yang aneh seperti memukul orang
dan berjalan sendirian tanpa tujuan.
Orangtua Miah membawa anaknya berobat secara tradisional ke paranormal
(dukun) tetapi sampai saat ini tidak satupun dukun yang dapat menyembuhkan
penyakit Miah. Menurut Dukun yang menangani Miah mengatakan dia terkena
“guna-guna” dan dukun yang mengirim “guna-guna” tersebut sangat sakti melebihi
kesaktiannya sehingga tidak mampu untuk mengobati Miah. Sampai saat ini sudah
ada sekitar 60 orang paranormal yang didatangi orangtua Miah untuk dapat
menyembuhkan anaknya, tetapi tidak satupun yang berhasil.
Orangtua Miah bahkan pernah memberikan semacam pengumuman kepada
penduduk setempat, bahwa jika ada yang dapat menyembuhkan putrinya maka
sebidang tanah milik keluarga tersebut akan diberikan sebagai upah untuk
menyembuhkan Miah. Sampai saat ini jika ditotal biaya pengobatan Miah yang sudah
dikeluarkan oleh keluarganya untuk pengobatan secara tradisional sebesar Rp.
14.000.000.-
Orangtua Miah juga telah membawa anaknya berobat ke rumah sakit. Miah
sempat tinggal di rumah sakit jiwa selama sebulan. Namun orangtuanya kemudian
membawa Miah pulang karena selama dirawat di RSJ tubuh Miah menjadi kurus dan
wajahnya membengkak akibat dipukuli oleh teman-temannya sesama penghuni RSJ.
Akhirnya Miah dibawa pulang dan dikurung di sebuah kamar di dalam rumah
Keadaan kamar tempat tinggal Miah cukup pengap dan gelap karena jendela
ditutup rapat dan tidak memiliki ventilasi. Kamar berukuran 2½ x 3 meter tersebut
berlantai semen, di atas lantai tersebut diletakkan beberapa lembar kardus bekas
tempat/kotak mie instant. Kardus tersebut menjadi alas bagi Miah untuk tidur. Di
sudut kamar ada sebuah lubang kecil berukuran 3½ inci, lubang tersebut menjadi
tempat bagi Miah untuk buang air kecil. Setiap pagi hari ayahnya menyiram lubang
tersebut, jika hendak buang air besar maka Aini biasanya akan mengedor pintu
kamarnya.
Sehari-harinya Miah tinggal di dalam kamar tersebut, dalam ruangan yang
sempit, gelap, pengap dengan aroma yang ‘sungguh’ kurang sedap. Pada
waktu-waktu tertentu, Miah suka menggedor pintu kamarnya dan berteriak-teriak minta
keluar, tetapi pada waktu tertentu lainnya, yang terdengar hanya rintihan-rintihan
halus, seolah-olah menyuarakan keletihan dan rasa putus asa yang dalam karena
terkurung.
Saat ini tidak adalagi tindakan pengobatan yang dilakukan untuk dapat
menyembuhkan Miah dari penyakit gangguan jiwa yang dideritanya. Orangtuanya
terlihat putus asa dan pasrah dengan kondisi yang dialami anaknya. Ayah Miah
merasa segala upaya telah dilakukan untuk mengakhiri penderitaan Miah, tetapi
semua mengalami kebuntuan. Membawa dan menitipkan Miah ke RSJ merupakan
sebuah pengalaman pahit, Miah menjadi bulan-bulanan pukulan teman satu kamar.
Kamar rawat inap yang sempit dan tingkat hunian melebihi kapasitas serta
korban. Membawa Miah ke dukun juga tidak memberikan hasil yang
menggembirakan, rata-rata dukun yang dikunjungi menyerah untuk mengobatinya.
Keadaan Miah dapat terlihat pada Gambar 4.1 berikut :
Gambar 4.1. Miah
4.2.2. Aini
Aini adalah anak ketiga dari enam bersaudara. Bersama saudara dan
orangtuanya tinggal di Desa Lhok Banie . Saat ini Aini berusia 23 tahun. Aini
memiliki pendidikan sekolah dasar. Menurut Ayah Aini, sejak kecil anaknya tumbuh
dan bertingkah laku seperti anak-anak lainnya, tidak ada hal-hal aneh atau tidak wajar
yang dilakukan Aini. Karena perekonomian keluarga yang cukup sulit maka
pendidikan Aini hanya sampai SD saja.
Pada awalnya ayah Aini bekerja sebagai nelayan di desa Pusong pada sebuah
pulau kecil, dengan sebuah boat kecil yang dimilikinya dari bantuan BRR-NAD.
merelokasikan penduduk pulau tersebut ke desa Lhok Banie. Desa Lhok Banie bukan
desa di tepi pantai sehingga ayah Aini tidak bias meneruskan pekerjaan sebagai
nelayan. Oleh karenanya beliau memutuskan bekerja sebagai tukang bangunan dan
sesekali bekerja serabutan (mocok-mocok).
Pada tahun 2004 Aini di bawa oleh salah seorang tetangganya untuk bekerja
sebagai Pembantu Rumah Tangga di kota Medan. Selama 2 tahun bekerja sebagai
PRT Aini selalu berkomunikasi dengan keluarganya, dia mengabari keadaannya dan
keluarga majikannya. Keluarga majikan Aini cukup baik, memperlakukannya seperti
keluarga sendiri, tidak ada keluhan yang disampaikan Aini ke orangtuanya.
Pada tahun 2006 Aini berkenalan dengan seorang pria (Johan) yang baru
bekerja sebagai supir di rumah majikannya. Enam bulan hubungan mereka terjalin
dengan baik. Aini yang sudah merasa yakin bahwa Johan akan bertanggung jawab
dan segera menikahinya akhirnya melakukan hubungan yang cukup jauh layaknya
suami istri. Merasa telah membuat suatu kesalahan dan khawatir akan hamil, Aini
meminta agar Johan segera menikahinya, tetapi harapan tinggal harapan, Johan selalu
menghindar bahkan akhirnya pergi tanpa diketahui kemana. Sejak itu Aini menjadi
anak yang pendiam dan berwajah murung.
Aini yang merasa bersalah dan tetap khawatir hamil akhirnya pamit pada
majikannya untuk pulang sebentar ke desanya menjenguk keluarganya. Kepada kakak
iparnya Aini menceritakan semua kejadian yang menimpa dirinya selama menjadi
PRT di kota Medan dan meminta kakak iparnya untuk tidak menceritakan kepada
pemarah dan memukul siapa saja yang ada disekitarnya, termasuk memukul dirinya
sendiri, suka memecahkan piring dan suka berbicara serta tertawa sendiri. Apa yang
dibicarakannya selalu kacau dan tidak jelas.
Ayah Aini merasa anaknya terkena guna-guna, tetapi atas desakan keluarga
lainnya pada Mei 2007 Aini dibawa ke Banda Aceh untuk berobat di rumah sakit
jiwa. Selama hampir 2 bulan di RSJ keadaan Aini mengalami perubahan menuju
kesembuhan, kemudian orangtua membawa pulang ke Langsa. Setelah kembali dari
rumah sakit jiwa, Aini sempat bekerja menjadi pembantu (cleaning service) di sebuah
warung nasi di Kota Langsa. Empat bulan bekerja di warung nasi, perilaku Aini
baik-baik saja, Ibu Nunik yang menjadi majikannya menuturkan :
…..”dia (Aini) kerjanya bagus, empat bulan di warung ini gak ada masalah. Kerjanya setiap hari membersihkan lantai, meja makan, dan rak tempat meletakkan makanan yang dijual. Ya namanya warung, kerjanya banyak dari pagi, siang bahkan sampe malam, gaji Aini juga lumayan kok. Cuma setelah empat bulan kerja, tiba-tiba dia minta berhenti kerja. Aku heran juga dan merasa keberatan karena Aini anak yang rajin, penurut dan bersih, pakaiannya sopan dan rapi”.
Empat bulan setelah bekerja sebagai pembantu di warung nasi, Aini mulai
menunjukkan perilaku yang aneh, setiap hari memberikan sebuah nasi bungkus
jatahnya ke anak-anak yang dijumpainya di depan warung nasi dan ketika gajian
maka Aini membelanjakan gaji untuk membeli pakaian anak-anak dan
membagikannya ke anak-anak di jalanan. Ibu Upik yng menjadi tukang masak
makanan di warung ibu Nunik, bercerita tentang Aini :
sudah lebih tiga bulan kerja di warung, sikapnya agak berubah, dia sering murung dan duduk sendirian. Aini pernah cerita kalo dulu juga dia pernah jadi pembantu, majikannya yang dulu katanya baik, gak suka marah-marah dan nyuruh-nyuruh. Di warung makan ini, majikannya suka marah dan nyuruh-nyuruh, dia bilang mau berhenti saja tapi gak dikasi sama ibu Nunik”.
Khawatir penyakit mengamuk Aini kambuh lagi, ayahnya kemudian
membawanya pulang ke rumah mereka. Setelah di rumah ayah Aini mengobati Aini
ke Paranormal, tetapi tidak ada yang bisa menyembuhkan bahkan penyakit Aini
semakin parah.
Saat ini Aini tinggal disebuah gubuk yang dibangun dekat rumah
orangtuanya. Makan, minum dan tidur dilakukan Aini di dalam gubuk tersebut
dengan kaki yang dirantai besi.
Jika melihat gubuk Aini, terasa nuansa ‘pengucilan’ oleh keluarganya.
Khawatir Aini mengamuk dan melukai anggota keluarnga merupakan sebuah alasan
penempatan Aini ke dalam gubuk tersebut. Tetapi, gubuk tersebut bukan sebuah
tempat yang layak huni untuk manusia. Gubuk yang kecil dengan bangunan dari
bahan papan, berlantai papan yang dialasi oleh tikar usang dan beberapa helai
potongan kardus, merupakan sebuah tempat yang cukup prihatin. Gubuk ini tidak
memiliki pintu, tetapi sebuah lubang berukuran 75 x 100 cm yang merupakan akses
bagi Aini untuk keluar dan masuk gubuknya.
Keterbatasan pergerakan menyebabkan Aini lebih sering duduk di depan
‘pintu’ gubuknya, memandang orang yang lewat dengan tatapan kosong. Terkadang
luarnya. Jika anggota keluarga melihat penampilan Aini yang kurang sopan, maka
anggota keluarga akan mengingatkan atau memakaikan pakaian Aini dengan benar.
Aini makan di dalam gubuknya, makanan diantar anggota keluarganya ke
dalam gubuk Aini. Buang air kecil dilakukan Aini di gubuknya, untuk mandi dan
buang air besar biasanya Aini mengatakannya kepada ayahnya, kemudian Aini
dibawa ke kamar mandi yang letaknya tersendiri atau di luar dari rumah induknya.
Ketika mandi atau buang air besar pun, rantai besi di kaki Aini tetap terpasang dan
menyertainya kemanapun pergi, ayahnya memegang ujung lainnya dari rantai besi
tersebut dan menguncinya pada salah satu tiang kamar mandi.
Untuk lebih dapat memahami keadaan Aini dapat terlihat pada Gambar 4.2
berikut :
4.2.3. Iyan
Iyan saat ini telah berusia 23 tahun, merupakan anak kedua dari empat orang
bersaudara. Tinggal bersama orangtua dan kedua saudaranya di Idi Cut. Ayah Iyan
hanya memiliki pekerjaan “mocok-mocok” yang memberikan penghasilan tidak tetap
setiap bulannya, ibunya hanya seorang ibu rumah tangga yang sehari-hari bekerja
mengurus rumah tangga dan keperluan Iyan. Abang tertua di keluarga Iyan yang saat
ini telah berusia 25 tahun dan tinggal bersama dengan mereka juga belum memiliki
perkerjaan yang memberikan penghasilan tetap setiap bulannya. Adik Iyan saat ini
berusia 15 tahun dan menjadi pelajar pada sebuah SMP di Idi Cut, sedangkan adik
Iyan yang paling kecil telah tiada.
Iyan menderita gangguan jiwa sejak berusia 16 tahun dan saat itu masih
pelajar kelas 2 pada sebuah SMA di kotanya. Saat itu propinsi Aceh masih berstatus
Daerah Operasional Militer. Pada masa kecil Iyan tumbuh seperti anak-anak
seusianya, tidak ada tanda-tanda atau kelainan yang menunjukkan terjadinya
gangguan jiwa. Namun, ketika ia berusia 16 tahun, Iyan pernah dipukul oleh seorang
tentara (TNI), serta saat itu sedang terjadi konflik antara Gerakan Aceh Merdeka
(GAM) dengan penduduk setempat yang bersuku Jawa, dimana banyak penduduk
bersuku Jawa yang dibunuh oleh tentara GAM. Ayah Iyan juga bersuku Jawa,
sehingga setiap hari dia dirundung perasaan cemas akan keselamatan ayah dan
keluarganya. Kecemasan Iyan setiap hari semakin bertambah karena dia beberapa kali