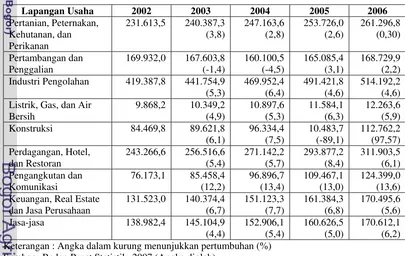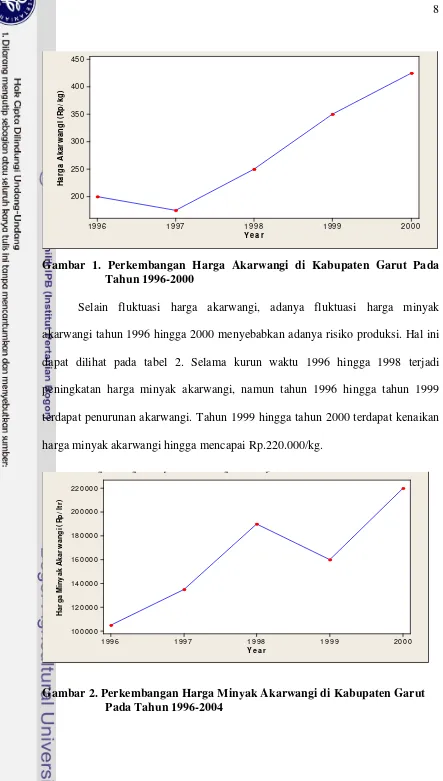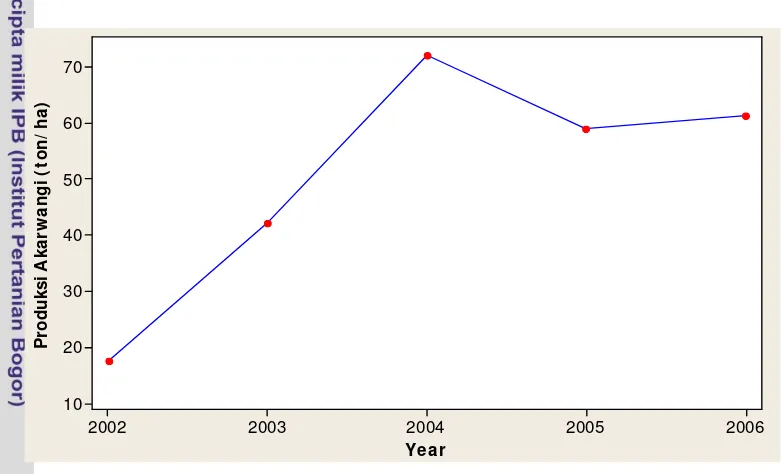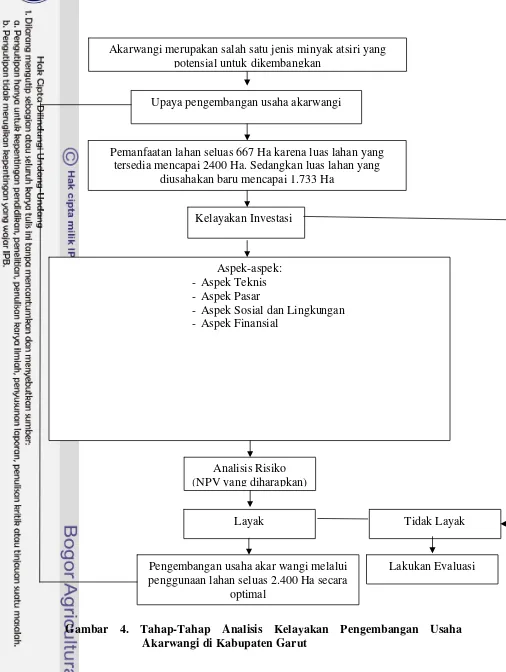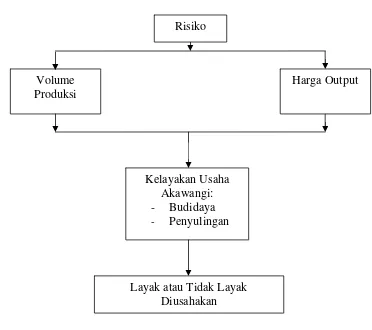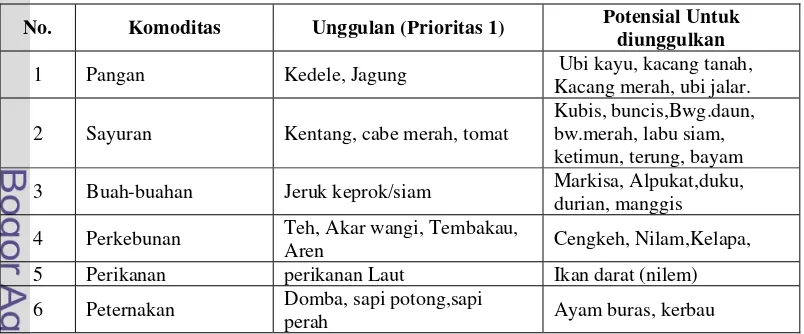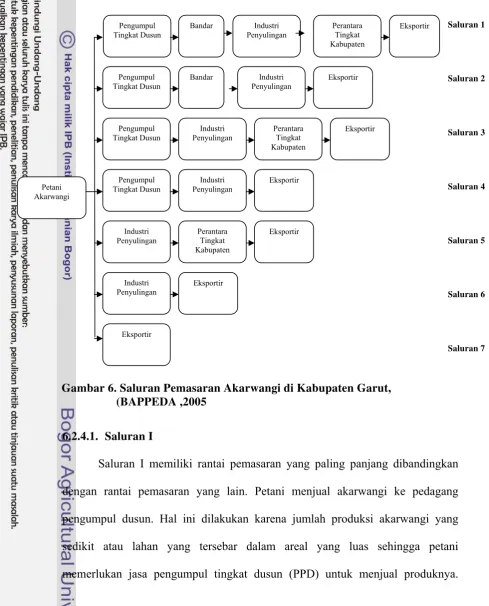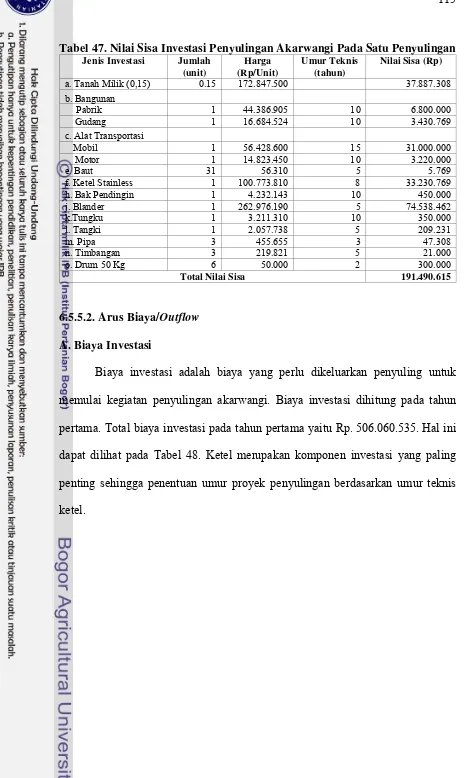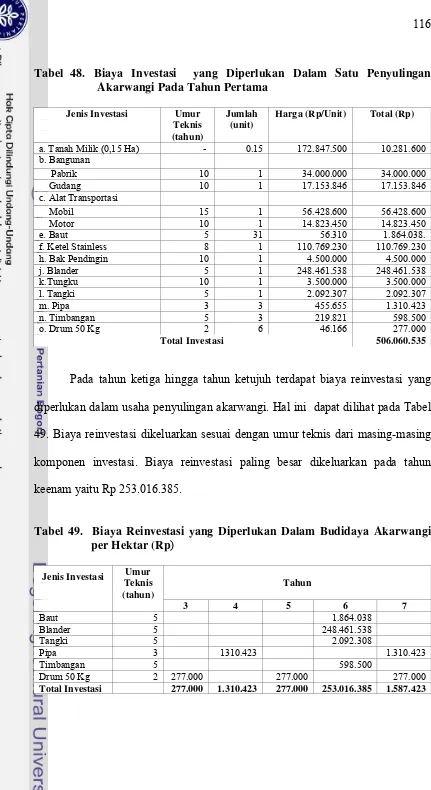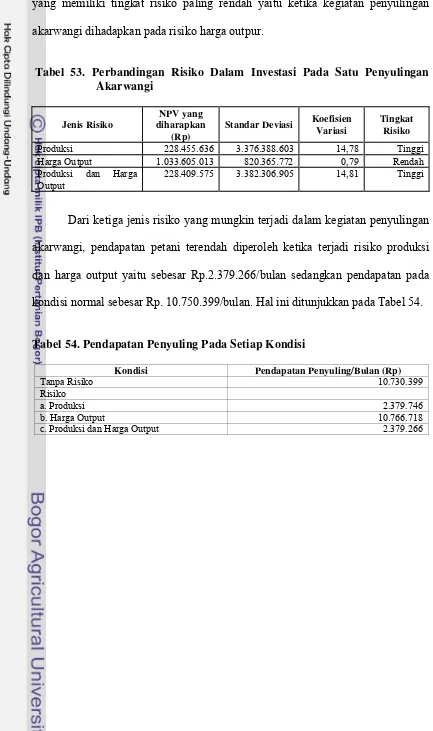Oleh: NIA ROSIANA
A14104045
PROGRAM STUDI MANAJEMEN AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN
RINGKASAN
NIA ROSIANA. Kelayakan Pengembangan Usaha Akarwangi (Andropogon zizanoid) pada Kondisi Risiko di Kabupaten Garut. Di Bawah Bimbingan ANNA FARIYANTI.
Sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Hal ini ditunjukkan oeh besarnya kontribusi sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan menurut lapangan usaha terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang berada pada urutan ketiga pada tahun 2002 sampai 2006 setelah industri pengolahan dan perdagangan, hotel, dan restoran. Dalam jangka panjang, pengembangan lapangan usaha pertanian difokuskan pada produk-produk olahan hasil pertanian yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Salah satu lapangan usaha yang memberikan nilai tambah dan kontribusi terhadap PDB yaitu tanaman perkebunan. Salah satu olahan tanaman perkebunan penghasil minyak aromatik adalah minyak atsiri. Tahun 2003 sampai 2006, ekspor minyak atsiri menunjukan trend yang meningkat. Salah satu jenis minyak atsiri yang dapat dikembangkan adalah akarwangi. Hal ini dikarenakan Indonesia menjadi salah satu negara pengekspor utama minyak akarwangi di pasar dunia. Akar wangi sebagai salah satu tanaman perkebunan yang berekonomis tinggi selayaknya terus dikembangkan agar dapat meningkatkan pendapatan petani, peningkatan kesempatan kerja, dan peningkatan penerimaan devisa.
Akarwangi merupakan salah satu komoditas perkebunan unggulan Kabupaten Garut yang memiliki arti penting bagi perekonomian daerah. Hal ini dikarenakan 89 persen produksi minyak akarwangi Indonesia dihasilkan dari Kabupaten Garut (Bappeda Kab.Garut, 2005). Hal ini didukung oleh potensi areal seluas 2.400 Ha sedangkan realisasi luas tanam baru mencapai 1.733 Ha pada tahun 2006 yang tersebar di empat kecamatan yaitu Kecamatan Leles, Kecamatan Samarang, Kecamatan Bayongbong, dan Kecamatan Cilawu. Hal ini mengindikasikan areal penanaman seluas 667 Ha belum termanfaatkan dan masih berpotensi untuk dikembangkan.
Dalam melakukan pengembangan usaha akarwangi diperlukan modal yang besar untuk mendukung kegiatan usaha tersebut. Kendala lain yaitu dalam melakukan budidaya dan penyulingan yaitu adanya fluktuasi harga output dan volume produksi. Fluktuasi produksi akarwangi dan minyak akarwangi diindikasikan oleh adanya risiko dalam kegiatan budidaya dan penyulingan akarwangi. Selain adanya risiko produksi, kegiatan budidaya dan penyulingan dihadapkan pada risiko harga output. Harga akarwangi dan minyak akarwangi pada setiap kondisi berbeda. Hal ini mengindikasikan adanya fluktuasi harga output yang menimbulkan adanya risiko harga output. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan usaha akarwangi di Kabupaten Garut dan menganalisis dampak adanya risiko volume produksi dan harga output terhadap kelayakan usaha akarwangi di Kabupaten Garut
kelayakan usaha dapat dilihat dari NPV (NetPresent Value), Net B/C (Net Benefit/Cost, IRR (Internal Rate Return, dan PP (Payback period). NPV dari setiap risiko pada kondisi tertinggi, normal, dan terendah akan diperoleh NPV yang diharapkan. Dalam hal ini, pendapatan petani dan penyuling setiap bulannya akan diketahui dari nilai NPV yang diharapkan. Selain NPV yang diharapkan, penilaian dan tingkat risiko yang terjadi pada pengusahaan akarwangi dapat lihat dari standar deviasi dan koefisien variasi kemudian dapat disimpulkan apakah pengusahaan akarwangi layak atau tidak untuk diusahakan.
Analisis aspek teknis dapat dilihat dari keadaan geografis, sumberdaya produksi, letak pasar, fasilitas penunjang, teknik budidaya, teknik penyulingan, dan produk akarwangi. Analisis aspek pasar dapat dilihat dari permintaan, penawaran, pemasaran, dan harga. Sedangkan aspek sosial dan lingkungan dapat dilihat dari manfaat yang secara langsung dan tidak langsung dirasakan oleh stakeholders.
Analisis aspek finansial pada kondisi normal baik pada kegiatan budidaya maupun penyulingan layak untuk dijalankan. Hal ini sesuai dengan kriteria kelayakan investasi.. Pendapatan petani dan penyuling per bulannya yaitu Rp.38.727 dan Rp.10.730.399. Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan petani masih rendah dibandingkan dengan penyuling. NPV normal pada kegatan budidaya dan penyulingan akarwangi yaitu Rp.1.394.179 dan Rp.1.030.118.304. Sedangkan IRR, Net B/C, dan payback period pada kegiatan budidaya yaitu 13%, 1,08, dan 2 tahun 5 bulan. IRR, Net B/C, dan payback period pada kegiatan penyulingan yaitu 99%, 4,98, dan 3 tahun 6 bulan. Kegiatan budidaya akarwangi dari ketiga jenis risiko yang mungkin dihadapi yaitu risiko produksi, risiko harga output, dan risiko produksi dan harga output masing- masing menghasilkan NPV yang diharapkan yaitu sebesar Rp.929.040, Rp.590.913, dan Rp.2.220.063. Sedangkan koefisien variasi dari ketiga jenis risiko yaitu 5,65 dan 31,02 serta 10,10. Berdasarkan ketiga jenis risiko pada kegiatan budidaya yang memiliki tingkat risiko paling rendah yaitu risiko harga produksi karena nilai koefisien variasi yang paling rendah. Kegiatan penyulingan akarwangi dari ketiga jenis risiko yang mungkin dihadapi yaitu risiko produksi, risiko harga output, dan risiko produksi dan harga output masing- masing menghasilkan NPV yang diharapkan yaitu sebesar Rp.228.455.638, Rp.1.033.605.013, dan Rp.228.409.575. Sedangkan koefisien variasi dari ketiga jenis risiko yaitu 14,78 dan 0,79 serta 14,81. Berdasarkan ketiga jenis risiko pada kegiatan budidaya yang memiliki tingkat risiko paling rendah yaitu risiko harga output karena nilai koefisien variasi yang paling rendah.
KELAYAKAN PENGEMBANGAN USAHA AKARWANGI (Andropogon zizanoid) PADA KONDISI RISIKO
DI KABUPATEN GARUT
SKRIPSI
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
SARJANA PERTANIAN
pada
Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor
Oleh : NIA ROSIANA
A14104045
PROGRAM STUDI MANAJEMEN AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN
Kabupaten Garut
Nama : Nia Rosiana
NRP : A14104045
Menyetujui, Dosen Pembimbing
Dr.Ir.Anna Fariyanti, MS NIP. 131 918 115
Mengetahui,
Dekan Fakultas Pertanian
Prof.Dr.Ir.Didy Sopandie, M.Agr NIP. 131 124 019
Puji syukur kita panjatkan ke hadapan Illahi Rabb yang selalu memberikan
lindungan dan limpahan rahmatNya sehingga penulis akhirnya dapat
menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Shalawat serta salam kita panjatkan
kepada Nabi Besar Muhamad SAW, keluarganya, para sahabat, dan semoga sampai
kepada kita selaku umatnya.
Skripsi ini merupakan salah satu bukti kepedulian penulis terhadap dunia
pertanian Indonesia. Selain itu, skripsi ini merupakan bukti kecintaan penulis
terhadap tanah kelahiran penulis yang terus menerus mengalami perkembangan
khususnya di dunia pertanian. Skripsi ini berjudul “Kelayakan Pengembangan
Usaha Akarwangi (Andropogon zizanoid) pada Kondisi Risiko di Kabupaten Garut”. Skripsi ini berisi mengenai analisis kelayakan pengembangan usaha
akarwangi melalui pemanfaatan lahan seluas 667 Ha yang belum digunakan. Hal
dilakukan dengan menganalisis kelayakan pengembangan usaha pada kondisi
normal dan kondisi adanya risiko.
Hasil akhir dari semua analisis yang dilakukan adalah sebagai bahan
pertimbangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Garut dalam menetapkan
kebijakan pengembangan usaha akarwangi dengan memperhatikan risiko yang
mungkin terjadi pada kegiatan pengembangan usaha akarwangi. Bagi masyarakat
yang akan melakukan usaha akarwangi dapat mengetahui berapa besar keuntungan
yang didapatkan terkait dengan penanaman modal pada usaha ini. Selain itu,
melalui penulisan skripsi ini, penulis mampu mengembangkan daya analisis
kelayakan uasaha berdasarkan konsep studi kelayakan usaha.
Akhirnya saya sebagai penulis mengucapkan terima kasih kepada semua
maaf atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis
mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak. Selamat membaca
semoga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya serta dapat menambah
pengetahuan bagi pembaca.
Bogor, Mei 2008
Penulis dilahirkan di Kabupaten Garut pada tanggal 3 September 1986 dari
pasangan Tato Sumarto dan Tati Sunarti. Penulis merupakan anak kedua dari tiga
bersaudara.
Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak Kemala
Bhayangkari Kabupaten Garut tahun 1992. Kemudian penulis menyelesaikan
studi di SDN 1 Kamojang Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung pada tahun 1998.
Penulis menempuh pendidikan lanjutan pertama di SLTPN 2 Garut dan
menyelesaikan studi tahun 2001. Kemudian menyelesaikan pendidikan menengah
atas di SMUN 1 Garut tahun 2004. Penulis diterima sebagai mahasiswa Institut
Pertanian Bogor (IPB) melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI) pada
tahun 2004 di Program Studi Manajemen Agribisnis, Fakultas Pertanian.
Selama menjadi mahasiwa, penulis aktif di berbagai kegiatan dan
organisasi kemahasiswaan baik intra maupun ekstra kampus. Di organisasi intra
kampus, penulis pernah aktif sebagai Anggota Biro Pers dan Jurnalistik MISETA
IPB tahun 2006-2007. selain itu, tahun 2005-2006 menjadi anggota pada Unit
Kegiatan Mahasiswa (UKM) Merpati Putih. Tahun 2005-2006 menjadi Anggota
dalam Marketing Community IPB. Tahun 2006-2007 menjadi Executive Secretary II International Association and Related Science Agriculture of Student
(IAAS) IPB.
Organisasi ekstra kampus yang diikuti yaitu anggota Asgar Muda
Indonesia Tahun 2006 hingga sekarang. Tahun 2004 – sekarang menjadi anggota
di Organisasi Mahasiwa Daerah (OMDA) Kabupaten Garut (HIMAGA). Penulis
kegiatan kepanitiaan di lingkar kampus IPB dan menjadi master of ceremony
(MC) dalam berbagai kegiatan. Selain itu, penulis aktif mengirimkan berbagai
esai ke universitas-universitas di Indonesia.
Prestasi-prestasi yang pernah diraih penulis selama menjadi mahasiswa di
IPB yaitu, Co Host Melancong Yuk di SCTV tahun 2007, juara II presenter berita
yang diselenggarakan BEM KM IPB bekerjasama dengan SCTV tahun 2007,
Juara II presenter berita Tahap Persiapan Bersama (TPB) IPB tahun 2004, Juara
III kegiatan presentasi business plan kewirausahaan tahun 2006, Juara III Lomba Karya Ilmiah TPB IPB tahun 2004 dan finalis tahun 2006, Juara VI lomba
menulis surat untuk menteri pertanian Indonesia tahun 2007, dan lainnya.
Selain aktif di organisasi dan kegiatan kemahasiswaan, penulis juga
menjadi asisten dosen untuk kegiatan praktikum pada mata kuliah kewirausahaan
selama satu semester pada tahun 2008. Tahun 2007 penulis mengikuti kegiatan
Oleh: NIA ROSIANA
A14104045
PROGRAM STUDI MANAJEMEN AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN
RINGKASAN
NIA ROSIANA. Kelayakan Pengembangan Usaha Akarwangi (Andropogon zizanoid) pada Kondisi Risiko di Kabupaten Garut. Di Bawah Bimbingan ANNA FARIYANTI.
Sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Hal ini ditunjukkan oeh besarnya kontribusi sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan menurut lapangan usaha terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang berada pada urutan ketiga pada tahun 2002 sampai 2006 setelah industri pengolahan dan perdagangan, hotel, dan restoran. Dalam jangka panjang, pengembangan lapangan usaha pertanian difokuskan pada produk-produk olahan hasil pertanian yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Salah satu lapangan usaha yang memberikan nilai tambah dan kontribusi terhadap PDB yaitu tanaman perkebunan. Salah satu olahan tanaman perkebunan penghasil minyak aromatik adalah minyak atsiri. Tahun 2003 sampai 2006, ekspor minyak atsiri menunjukan trend yang meningkat. Salah satu jenis minyak atsiri yang dapat dikembangkan adalah akarwangi. Hal ini dikarenakan Indonesia menjadi salah satu negara pengekspor utama minyak akarwangi di pasar dunia. Akar wangi sebagai salah satu tanaman perkebunan yang berekonomis tinggi selayaknya terus dikembangkan agar dapat meningkatkan pendapatan petani, peningkatan kesempatan kerja, dan peningkatan penerimaan devisa.
Akarwangi merupakan salah satu komoditas perkebunan unggulan Kabupaten Garut yang memiliki arti penting bagi perekonomian daerah. Hal ini dikarenakan 89 persen produksi minyak akarwangi Indonesia dihasilkan dari Kabupaten Garut (Bappeda Kab.Garut, 2005). Hal ini didukung oleh potensi areal seluas 2.400 Ha sedangkan realisasi luas tanam baru mencapai 1.733 Ha pada tahun 2006 yang tersebar di empat kecamatan yaitu Kecamatan Leles, Kecamatan Samarang, Kecamatan Bayongbong, dan Kecamatan Cilawu. Hal ini mengindikasikan areal penanaman seluas 667 Ha belum termanfaatkan dan masih berpotensi untuk dikembangkan.
Dalam melakukan pengembangan usaha akarwangi diperlukan modal yang besar untuk mendukung kegiatan usaha tersebut. Kendala lain yaitu dalam melakukan budidaya dan penyulingan yaitu adanya fluktuasi harga output dan volume produksi. Fluktuasi produksi akarwangi dan minyak akarwangi diindikasikan oleh adanya risiko dalam kegiatan budidaya dan penyulingan akarwangi. Selain adanya risiko produksi, kegiatan budidaya dan penyulingan dihadapkan pada risiko harga output. Harga akarwangi dan minyak akarwangi pada setiap kondisi berbeda. Hal ini mengindikasikan adanya fluktuasi harga output yang menimbulkan adanya risiko harga output. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan usaha akarwangi di Kabupaten Garut dan menganalisis dampak adanya risiko volume produksi dan harga output terhadap kelayakan usaha akarwangi di Kabupaten Garut
kelayakan usaha dapat dilihat dari NPV (NetPresent Value), Net B/C (Net Benefit/Cost, IRR (Internal Rate Return, dan PP (Payback period). NPV dari setiap risiko pada kondisi tertinggi, normal, dan terendah akan diperoleh NPV yang diharapkan. Dalam hal ini, pendapatan petani dan penyuling setiap bulannya akan diketahui dari nilai NPV yang diharapkan. Selain NPV yang diharapkan, penilaian dan tingkat risiko yang terjadi pada pengusahaan akarwangi dapat lihat dari standar deviasi dan koefisien variasi kemudian dapat disimpulkan apakah pengusahaan akarwangi layak atau tidak untuk diusahakan.
Analisis aspek teknis dapat dilihat dari keadaan geografis, sumberdaya produksi, letak pasar, fasilitas penunjang, teknik budidaya, teknik penyulingan, dan produk akarwangi. Analisis aspek pasar dapat dilihat dari permintaan, penawaran, pemasaran, dan harga. Sedangkan aspek sosial dan lingkungan dapat dilihat dari manfaat yang secara langsung dan tidak langsung dirasakan oleh stakeholders.
Analisis aspek finansial pada kondisi normal baik pada kegiatan budidaya maupun penyulingan layak untuk dijalankan. Hal ini sesuai dengan kriteria kelayakan investasi.. Pendapatan petani dan penyuling per bulannya yaitu Rp.38.727 dan Rp.10.730.399. Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan petani masih rendah dibandingkan dengan penyuling. NPV normal pada kegatan budidaya dan penyulingan akarwangi yaitu Rp.1.394.179 dan Rp.1.030.118.304. Sedangkan IRR, Net B/C, dan payback period pada kegiatan budidaya yaitu 13%, 1,08, dan 2 tahun 5 bulan. IRR, Net B/C, dan payback period pada kegiatan penyulingan yaitu 99%, 4,98, dan 3 tahun 6 bulan. Kegiatan budidaya akarwangi dari ketiga jenis risiko yang mungkin dihadapi yaitu risiko produksi, risiko harga output, dan risiko produksi dan harga output masing- masing menghasilkan NPV yang diharapkan yaitu sebesar Rp.929.040, Rp.590.913, dan Rp.2.220.063. Sedangkan koefisien variasi dari ketiga jenis risiko yaitu 5,65 dan 31,02 serta 10,10. Berdasarkan ketiga jenis risiko pada kegiatan budidaya yang memiliki tingkat risiko paling rendah yaitu risiko harga produksi karena nilai koefisien variasi yang paling rendah. Kegiatan penyulingan akarwangi dari ketiga jenis risiko yang mungkin dihadapi yaitu risiko produksi, risiko harga output, dan risiko produksi dan harga output masing- masing menghasilkan NPV yang diharapkan yaitu sebesar Rp.228.455.638, Rp.1.033.605.013, dan Rp.228.409.575. Sedangkan koefisien variasi dari ketiga jenis risiko yaitu 14,78 dan 0,79 serta 14,81. Berdasarkan ketiga jenis risiko pada kegiatan budidaya yang memiliki tingkat risiko paling rendah yaitu risiko harga output karena nilai koefisien variasi yang paling rendah.
KELAYAKAN PENGEMBANGAN USAHA AKARWANGI (Andropogon zizanoid) PADA KONDISI RISIKO
DI KABUPATEN GARUT
SKRIPSI
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
SARJANA PERTANIAN
pada
Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor
Oleh : NIA ROSIANA
A14104045
PROGRAM STUDI MANAJEMEN AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN
Kabupaten Garut
Nama : Nia Rosiana
NRP : A14104045
Menyetujui, Dosen Pembimbing
Dr.Ir.Anna Fariyanti, MS NIP. 131 918 115
Mengetahui,
Dekan Fakultas Pertanian
Prof.Dr.Ir.Didy Sopandie, M.Agr NIP. 131 124 019
Puji syukur kita panjatkan ke hadapan Illahi Rabb yang selalu memberikan
lindungan dan limpahan rahmatNya sehingga penulis akhirnya dapat
menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Shalawat serta salam kita panjatkan
kepada Nabi Besar Muhamad SAW, keluarganya, para sahabat, dan semoga sampai
kepada kita selaku umatnya.
Skripsi ini merupakan salah satu bukti kepedulian penulis terhadap dunia
pertanian Indonesia. Selain itu, skripsi ini merupakan bukti kecintaan penulis
terhadap tanah kelahiran penulis yang terus menerus mengalami perkembangan
khususnya di dunia pertanian. Skripsi ini berjudul “Kelayakan Pengembangan
Usaha Akarwangi (Andropogon zizanoid) pada Kondisi Risiko di Kabupaten Garut”. Skripsi ini berisi mengenai analisis kelayakan pengembangan usaha
akarwangi melalui pemanfaatan lahan seluas 667 Ha yang belum digunakan. Hal
dilakukan dengan menganalisis kelayakan pengembangan usaha pada kondisi
normal dan kondisi adanya risiko.
Hasil akhir dari semua analisis yang dilakukan adalah sebagai bahan
pertimbangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Garut dalam menetapkan
kebijakan pengembangan usaha akarwangi dengan memperhatikan risiko yang
mungkin terjadi pada kegiatan pengembangan usaha akarwangi. Bagi masyarakat
yang akan melakukan usaha akarwangi dapat mengetahui berapa besar keuntungan
yang didapatkan terkait dengan penanaman modal pada usaha ini. Selain itu,
melalui penulisan skripsi ini, penulis mampu mengembangkan daya analisis
kelayakan uasaha berdasarkan konsep studi kelayakan usaha.
Akhirnya saya sebagai penulis mengucapkan terima kasih kepada semua
maaf atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis
mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak. Selamat membaca
semoga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya serta dapat menambah
pengetahuan bagi pembaca.
Bogor, Mei 2008
Penulis dilahirkan di Kabupaten Garut pada tanggal 3 September 1986 dari
pasangan Tato Sumarto dan Tati Sunarti. Penulis merupakan anak kedua dari tiga
bersaudara.
Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak Kemala
Bhayangkari Kabupaten Garut tahun 1992. Kemudian penulis menyelesaikan
studi di SDN 1 Kamojang Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung pada tahun 1998.
Penulis menempuh pendidikan lanjutan pertama di SLTPN 2 Garut dan
menyelesaikan studi tahun 2001. Kemudian menyelesaikan pendidikan menengah
atas di SMUN 1 Garut tahun 2004. Penulis diterima sebagai mahasiswa Institut
Pertanian Bogor (IPB) melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI) pada
tahun 2004 di Program Studi Manajemen Agribisnis, Fakultas Pertanian.
Selama menjadi mahasiwa, penulis aktif di berbagai kegiatan dan
organisasi kemahasiswaan baik intra maupun ekstra kampus. Di organisasi intra
kampus, penulis pernah aktif sebagai Anggota Biro Pers dan Jurnalistik MISETA
IPB tahun 2006-2007. selain itu, tahun 2005-2006 menjadi anggota pada Unit
Kegiatan Mahasiswa (UKM) Merpati Putih. Tahun 2005-2006 menjadi Anggota
dalam Marketing Community IPB. Tahun 2006-2007 menjadi Executive Secretary II International Association and Related Science Agriculture of Student
(IAAS) IPB.
Organisasi ekstra kampus yang diikuti yaitu anggota Asgar Muda
Indonesia Tahun 2006 hingga sekarang. Tahun 2004 – sekarang menjadi anggota
di Organisasi Mahasiwa Daerah (OMDA) Kabupaten Garut (HIMAGA). Penulis
kegiatan kepanitiaan di lingkar kampus IPB dan menjadi master of ceremony
(MC) dalam berbagai kegiatan. Selain itu, penulis aktif mengirimkan berbagai
esai ke universitas-universitas di Indonesia.
Prestasi-prestasi yang pernah diraih penulis selama menjadi mahasiswa di
IPB yaitu, Co Host Melancong Yuk di SCTV tahun 2007, juara II presenter berita
yang diselenggarakan BEM KM IPB bekerjasama dengan SCTV tahun 2007,
Juara II presenter berita Tahap Persiapan Bersama (TPB) IPB tahun 2004, Juara
III kegiatan presentasi business plan kewirausahaan tahun 2006, Juara III Lomba Karya Ilmiah TPB IPB tahun 2004 dan finalis tahun 2006, Juara VI lomba
menulis surat untuk menteri pertanian Indonesia tahun 2007, dan lainnya.
Selain aktif di organisasi dan kegiatan kemahasiswaan, penulis juga
menjadi asisten dosen untuk kegiatan praktikum pada mata kuliah kewirausahaan
selama satu semester pada tahun 2008. Tahun 2007 penulis mengikuti kegiatan
Puji syukur selayaknya kita panjatkan ke hadirat Allah SWT.
Alhamdulilah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada
waktunya. Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini banyak pihak yang
telah membantu memberikan bantuan, dukungan, dan doa yang akan selalu
penulis kenang dan syukuri. Sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT,
penulis mengucapkan terima kasih kepada:
1. Kedua orangtuaku tersayang Bpk. Tato Sumarto dan Ibu Tati Sunarti. Terima
kasih atas bimbingan, doa, dan kasih sayang apih dan mamah. Kakakku Dian
Kusumasari dan adikku Arief Prasetyo.
2. Dr. Ir. Anna Fariyanti, MS selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan
kasih sayang dan kesabarannya dalam membimbing penulis.
3. Tanti Novianti, SP, MSi selaku Dosen Penguji Utama yang telah memberikan
bimbingan dan masukannya dalam ujian sidang skripsi penulis
4. Eva Yolynda Aviny, SP, MM selaku Dosen Penguji Wakil Departemen yang
telah memberi masukan dan bmbingannya dalam ujian skripsi penulis
5. Feryanto William Karo-Karo, SP atas bimbingan, dukungan, dan perhatiannya
selama ini
6. Teman-teman USA (Sriwel. Chiemay, Melly, Ine, dan Icank) atas
persahabatan dan kebersamaannya selama ini
7. Bapak Haeruman, Kepala Bidang Tanaman Semusim, Dinas Tanaman Pangan
dan Perkebunan Kabupaten Garut yang telah memberikan dukungan serta
8. H. Ede Kadarusman sebagai key informan dalam pengambilan data akarwangi di Kabupaten Garut
9. Dr. Ir. Bayu Krisnamurthi selaku Pembimbing Akademik yang telah
memberikan arahan dan semangat selama penulis menempuh studi di IPB
10. Seluruh Dosen Manajemen Agribisnis yang telah menyumbangkan ilmunya
kepada penulis.
11. Seluruh Staf Manajemen Agribisnis terutama Mba Dian dan Mba Dewi yang
telah memberikan kemudahan dalam segala hal yang menyangkut administrasi
selama penulis menempuh studi di IPB
12. Sri Maryati yang telah berkenan menjadi pembahas seminar hasil penelitian
penulis
13. Taufik dan Doni, terima kasih atas persahabatan kita selama ini.
14. Dinna Sabriani, teman sharing terutama ketika proses penulisan skripsi.
15. Teman-teman satu bimbingan skripsi (Chika Idol, Tedjo, Dinna, Chiemay,
Mba Nina, dan Sevia)
16. Teman-teman satu bimbingan akademik (Chiemay, Nunik, Viona, Ichank,
Loci, dan Dwita)
17. Teman-teman asrama 388 (Ari Phobe, Marlina, Rahmi Sari, dan Yola)
18. Teman-teman KKP di Desa Tonjong, Kabupaten Brebes (Mira, Citta, Morin,
Azis, dan Indah) yang memberi kenangan manis di tempat KKP
19. Nurani, Iwan, Yuli, Irub, dan teman-teman HIMAGA (Himpunan Mahasiswa
Garut) lainnya atas kebersamaan dan rasa persaudaraannya
20. Ipunk, Pretty, Nunik, dan Nanik yang telah memberi semangat di akhir-akhir
22. Teman-teman Pondok As-salamah (Niken, Novi, Sri, Venti, Intan, dan Eka)
atas rasa persaudaraan dan kebersamaannya
23. Mas Ipul, Mas Yudhi, dan Mas Budi yang telah memberikan pelajaran hidup
selama “Melancong” ke Solok Selatan
24. Kang Goris, Kang Ariel, dan teman-teman Asgar Muda lainnya yang telah
memberikan informasi mengenai akarwangi dan segala sesuatunya
25. Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi dan dukungan selama
penulis menyelesaikan studi di IPB yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat.
Bogor, Mei 2008
DAFTAR ISI
Halaman DAFTAR TABEL ...xviii DAFTAR GAMBAR ...xxi DAFTAR LAMPIRAN ...xxii
I. PENDAHULUAN ...1 1.1. Latar Belakang ...1 1.2. Perumusan Masalah ...6 1.3. Tujuan Penelitian ...11 1.4. Kegunaan Penelitian ...11
II. TINJAUAN PUSTAKA ...13 2.1. Gambaran Umum Akarwangi……….…………13
2.1.1. Budidaya Akar Wangi ...14 2.1.2. Penyulingan Akar Wangi ...17 2.2. Studi Kelayakan Proyek... 20 2.3. Hasil Penelitian Terdahulu ...20
III. KERANGKA PEMIKIRAN...24 3.1. Kerangka Teoritis...24
3.1.1. Studi Kelayakan Usaha ...24 3.1.2. Aspek-Aspek Studi Kelayakan ...27 3.1.3. Konsep Nilai waktu Uang... 29 3.1.4. Kriteria Kelayakan Investasi...30 3.1.5. Risiko Dalam Investasi.……….…..32 3.2. Kerangka Operasional ...36
xv IV. METODOLOGI PENELITIAN ...41
4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian ...41 4.2 Jenis dan Sumber Data ...41 4.3. Teknik Pengambilan Responden ...42 4.4. Pengolahan dan Analisis Data ...45 4.4.1. Analisis Aspek Teknis ...45 4.4.2. Analisis Aspek Pasar ...45 4.4.3. Analisis Aspek Sosial ...46 4.4.4. Analisis Aspek Finansial ...46 4.4.5. Penilaian Risiko dalam Investasi... .49 4.5. Asumsi Dasar...52
V. GAMBARAN UMUM ... 565.1. Karakteristik Wilayah ... 56
xvi 5.3. Risiko Budidaya ...71
5.3.1. Risiko Produksi ...71 5.3.2. Risiko Harga Output ...74 5.4. Risiko Penyulingan ...75 5.4.1. Risiko Produksi ...75 5.4.2. Risiko Harga Output ...77
VI. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 80 6.1. Analisis Aspek Teknis ... 80
6.1.1. Keadaan Geografis ... 80 6.1.2. Sumberdaya Produksi ... 80 6.1.3. Letak Pasar ... 83 6.1.4. Fasilitas Penunjang ... 83 6.1.5. Teknik Budidaya ... 88 6.1.6. Teknik Penyulingan ... 89 6.1.7. Produk akarwangi ... 91 6.2. Analisis Aspek Pasar ... 91 6.2.1. Permintaan ... 91 6.2.2. Penawaran ... 92 6.2.3. Harga ... 93 6.2.4. Pemasaran ... 93 6.3. Analisis Aspek Sosial dan Lingkungan ... 98 6.4. Risiko Usaha ... 99 6.5. Analisis Aspek Finansial ... 100
xvii 6.5.7. Kelayakan Finansial Penyulingan Akarwangi Pada Kondisi Risiko ... 122 6.5.8. Penilaian dan Perbandingan Risiko Penyulingan Akarwangi ... 124
VII. KESIMPULAN DAN SARAN ... 126 7.1. Kesimpulan ... 126 7.2. Saran ... 127
DAFTAR TABEL
Nomor Halaman
1. Perkembangan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000
menurut Lapangan Usaha Tahun 2002-006 ...1 2. Perkembangan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000
menurut Lapangan Usaha Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan
Tahun 2002-2006 ...2 3. Perkembangan Ekspor-Impor Tanaman Perkebunan, Tahun 2003-2006 ...3 4. Perbandingan Ekspor dan Impor Tanaman Perkebunan Penghasil
Minyak Aromatik Indonesia, Tahun 2003-2006 ...4 5. Negara-Negara Pengekspor Minyak Atsiri, Tahun 2002 ...4 6. Negara-Negara Pengimpor Minyak Atsiri, Tahun 2002 ...5 7. Jenis Minyak Atsiri yang Diusahakan di Provinsi Jawa Barat, Tahun 2004...5 8. Perkembangan Luas Lahan dan Produksi Akar Wangi di Jawa Barat,
Tahun 2002-2006 ...6 9. Penyebaran Luas Tanam Akarwangi di Kabupaten Garut ...7 10. Daerah Penanaman Akarwangi di Kabupaten Garut ...41 11. Pembagian Sampel Secara Proporsional di Kabupaten Garut ...43 12. Jumlah dan Persentase Responden Petani/Penyuling Akarwangi ...44 13. Peluang Setiap Kondisi Pada Kegiatan Budidaya dan
Penyulingan Akarwangi ...51 14. Luas Lahan Berdasarkan Ketinggian ...57 15. Luas Tanah Menurut Penggunaannya di Kabupaten Garut Tahun 2004 ...58 16. Jenis Tanah di Kabupaten Garut ...59 17. Komoditas Unggulan Kabupaten Garut ...64 18. Jumlah dan Persentase Responden Petani dan Penyuling Berdasarkan
Umur di Kabupaten Garut ...66 19. Jumlah dan Persentase Responden Petani dan Penyuling Berdasarkan
Tingkat Pendidikan di Kabupaten Garut ...67
20. Jumlah dan Persentase Responden Petani dan Penyuling Berdasarkan
Jumlah Tanggungan Keluarga di Kabupaten Garut ...67 21. Jumlah dan Persentase Responden Petani dan Penyuling Berdasarkan
xix Pengalaman Bertani di Kabupaten Garut ...68
23. Jumlah dan Persentase Petani Berdasarkan Luas Lahan yang Digunakan
untuk Penanaman Akarwangi di Kabupaten Garut ...69 24. Jumlah dan Persentase Penyuling Berdasarkan Luas Lahan yang Digunakan
untuk Penyulingan Akarwangi di Kabupaten Garut ...69 25. Jumlah dan Persentase Petani Akarwangi Berdasarkan Status Kepemilikan
Lahan di Kabupaten Garut ...70 26. Jumlah dan Persentase Penyuling Akarwangi Berdasarkan Status Kepemilikan
Lahan di Kabupaten Garut ...70 27. Produksi dan Peluang Produksi Budidaya Akarwangi Pada Setiap Kondisi ...72 28 . Produksi dan Peluang Harga Output Budidaya Akarwangi Pada Setiap
Kondisi ...74 29. Produksi dan Peluang Harga Output penyulingan Akarwangi Pada Setiap
Kondisi ...76 30. Produksi dan Peluang Harga Output Penyulingan Minyak Akarwangi
Pada Setiap Kondisi ...77 31. Input dan Output Budidaya Akarwangi ...88 32. Input dan Output Penyulingan Akarwangi ...90 33. Perkembangan Produksi Akarwangi Provinsi Jawa Barat (ton,
Tahun 2002-2006 ...92 34. Perkembangan Luas Lahan Tanaman Akarwangi (ha) di Jawa Barat,
Tahun 2002-2006 ...92 35. Produksi Akarwangi Dalam 1 Ha dan Minyak Akarwangi
Dalam Satu Penyulingan/Tahun Pada Setiap Kondisi ...100 36. Harga Output Akarwangi dan Minyak Akarwangi Pada Setiap Kondisi ...100 37. Penerimaan Petani Akarwangi Pada Kondisi Tanpa Risiko Per Hektar ...102 38. Nilai Sisa Investasi Budidaya Akarwangi per Hektar...103 39. Biaya Investasi yang Diperlukan Pada Tahun Pertama Dalam
Budidaya Akarwangi per Hektar ...103 40. Biaya Reinvestasi yang Diperlukan Dalam Budidaya Akarwangi per Hektar ...104 41. Biaya Variabel dan Biaya Tetap yang Diperlukan Pada Kegiatan
xx Nomor Halaman
43. Kriteria Kelayakan Investasi Budidaya Setiap Kondisi Pada Tingkat DF (8%) ...112 44. Perbandingan Risiko Dalam Investasi Budidaya Akarwangi ...113 45. Pendapatan Petani Pada Setiap Kondisi ...113 46. Penerimaan Penyuling Akarwangi Pada Kondisi Tanpa Risiko
Dalam Satu Penyulingan ...114 47. Nilai Sisa Investasi Penyulingan Akarwangi Pada Satu Penyulingan ...115 48. Biaya Investasi yang Diperlukan Dalam Satu Penyulingan Akarwangi
Pada Tahun Pertama ...116 49. Biaya Reinvestasi yang Diperlukan Dalam Budidaya Akarwangi
per Hektar (Rp) ...116 50. Biaya Variabel dan Biaya Tetap yang Diperlukan Pada Kegiatan
Penyulingan Akarwangi Dalam Satu Penyulingan ...120 51. Total Penerimaan Penyuling Akarwangi Pada Kondisi Risiko
Nomor Halaman 1. Perkembangan Harga Akarwangi di Kabupaten Garut Pada
Tahun 1996-2000...8 2. Perkembangan Harga Minyak Akarwangi di Kabupaten Garut
Pada Tahun 1996-2004...8 3. Perkembangan Produksi Akar Wangi di Jawa Barat Tahun 2002-2006...9 3. Tahap-Tahap Analisis Kelayakan Pengembangan Usaha Akarwangi
DAFTAR LAMPIRAN
Nomor Halaman
1. Cashflow Budidaya Akarwangi pada kondisi Normal pada Lahan 1 Ha ...131 2. Cashflow Risiko Produksi Pada Budidaya Akarwangi Kondisi Tertinggi ...132 3. Cashflow Risiko Produksi Pada Budidaya Akarwangi Kondisi Terendah ...133 4. Cashflow Risiko Harga Output Tertinggi Pada Budidaya Akarwangi ...134 5. Cashflow Risiko Harga Output Terendah Pada Budidaya Akarwangi ...135 6. Cashflow Risiko harga Output Terendah Dengan Produksi Terendah ...136 7. Tingkat Risiko Produksi, Harga, dan Gabungan Pada Budidaya Akarwangi ...137 8. Cashflow Penyulingan Kondisi Normal ...138 9. Cashflow Risiko penyulingan Kondisi Produksi Tertinggi ...140 10.Cashflow Risiko penyulingan Kondisi Produksi Terendah ...142 11.Cashflow Risiko Penyulingan Kondisi harga Output Tertinggi ...144 12.Cashflow Risiko Penyulingan Kondisi harga Output Terendah ...146 13.Cashflow Risiko Penyulingan Kondisi Gabungan Tertinggi ...148 14.Cashflow Risiko Penyulingan Kondisi Gabungan Terendah...150 15.Tingkat Risiko Produksi, Harga, dan Gabungan pada Penyulingan
I. Latar Belakang
Sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan mempunyai
peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Salah satunya
sebagai sumber penerimaan negara. Hal ini ditunjukkan pada Tabel 1 yaitu
besarnya kontribusi sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan
menurut lapangan usaha terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang berada
pada urutan ketiga pada tahun 2002 sampai 2006 setelah industri pengolahan dan
perdagangan, hotel, dan restoran.
Tabel 1. Perkembangan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Lapangan Usaha Tahun 2002-2006 (Miliar Rupiah)
Lapangan Usaha 2002 2003 2004 2005 2006
Pertanian, Peternakan, Industri Pengolahan 419.387,8 441.754,9
(5,3) Listrik, Gas, dan Air
Bersih
Konstruksi 84.469,8 89.621,8
(6,1)
Jasa-jasa 138.982,4 145.104,9
(4,4) Keterangan : Angka dalam kurung menunjukkan pertumbuhan (%)
2
Dalam jangka panjang, pengembangan lapangan usaha pertanian
difokuskan pada produk-produk olahan hasil pertanian yang memberikan nilai
tambah bagi perekonomian nasional, seperti pengembangan agroindustri. Salah
satu lapangan usaha pertanian yang berorientasi ekspor dan mampu memberikan
nilai tambah adalah tanaman perkebunan. Hal ini terlihat pada kontribusi tanaman
perkebunan menurut lapangan usaha terhadap PDB. Tanaman perkebunan
menurut lapangan usaha tahun 2002 sampai 2006 memberikan kontribusi terbesar
kedua setelah tanaman bahan makanan setiap tahunnya. Hal ini ditunjukan pada
Tabel 2.
Tabel 2. Perkembangan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Lapangan Usaha Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan Tahun 2002-2006 (Miliar Dolar)
Lapangan Usaha Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan
Perikanan
2002 2003 2004 2005 2006
Tanaman Bahan
Tanaman Perkebunan 36.585,6 38.693,9
(5,8)
Kehutanan 17.986,5 17.213,7
(-4,3)
Perikanan 33.082,3 34.667,9
(4,8) Keterangan : Angka dalam kurung menunjukkan pertumbuhan (%)
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2007 (Angka diolah)
Persentase nilai PDB tanaman perkebunan berfluktuasi pada kurun waktu
2002 hingga tahun 2006. Hal ini tidak terlepas dari besarnya persentase ekspor
tanaman perkebunan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dari
11.974.201.918 kg pada tahun 2003 menjadi 18.579.806.335 kg pada tahun 2006.
Tabel 3. Perkembangan Ekspor-Impor Tanaman Perkebunan, Tahun 2003-2006
Tahun Volume (Kg)
Ekspor Impor Neraca
2003 11.974.201.918 2.088.748.566 9.885.453.352
2004 15.556.889.495 Keterangan : Angka dalam kurung menunjukkan pertumbuhan (%)
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2007 (Angka diolah) *) Angka Sementara
Minyak aromatik merupakan salah satu olahan tanaman perkebunan.
Minyak aromatik memiliki aroma yang kuat karena sifatnya yang mudah
menguap pada suhu ruang. Minyak aromatik banyak digunakan untuk bahan dasar
wewangian dan minyak gosok. Salah satu olahan tanaman perkebunan penghasil
minyak aromatik adalah minyak atsiri dan minyak jarak. Minyak jarak yang
dimanfaatkan dalam berbagai industri seperti: sabun, pelumas, minyak rem dan
hidrolik, cat, pewarna, plastik tahan dingin, pelindung (coating), tinta, malam dan semir, nilon, farmasi, dan parfum. Tahun 2003 sampai 2006, ekspor minyak
atsiri menunjukan trend yang meningkat. Sedangkan volume ekspor minyak jarak
menunjukan adanya fluktuasi. Volume ekspor minyak atsiri lebih besar setiap
tahunnya dibandingkan dengan minyak jarak. Hal ini menunjukan permintaan
minyak atsiri lebih besar dibandingkan dengan minyak jarak. Hal ini dapat dilhat
4
Tabel 4. Perbandingan Ekspor dan Impor Tanaman Perkebunan Penghasil Minyak Aromatik Indonesia, Tahun 2003-2006 (Kg)
Tahun
2003 1.967.736 321.333 200.622 2.489.689
2004 3.230.401 Keterangan : Angka dalam kurung menunjukkan pertumbuhan (%)
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2007 (Angka diolah) *) Termasuk Bahan Baku Minyak Aromatik
**) Angka Sementara
Pasar minyak atsiri sangat potensial bagi Indonesia. Indonesia menjadi
salah satu negara pengekspor minyak atsiri dunia yang berada pada urutan ketiga
di dunia. Ekspor minyak atsiri Indonesia tahun 2002 menghasilkan nilai sebesar
US$ 47.940.000 atau 17,6 persen dari total nilai ekspor minyak atsiri di pasar
dunia. Hal ini dapat ditunjukkan pada Tabel 5.
Tabel 5. Negara-Negara Pengekspor Minyak Atsiri Dunia, Tahun 2002
Negara pengekspor Nilai (Ribuan US$) (%)
Perancis 93.842 34,5
China 50.517 18,6
Indonesia 47.940 17,6
USA 34.011 12,5
Inggris 24.346 8,9
Singapura 21.090 7,9
Total 271.746 100
Berdasarkan nilai impor tahun 2002, permintaan terhadap minyak atsiri
dari semua negara pengimpor cukup tinggi. Indonesia hanya menghasilkan nilai
US$ 47.940.000 padahal total nilai impor minyak atsiri dari negara- negara
pengimpor mencapai US$ 354.496.000. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 6.
Tabel 6. Negara-Negara Pengimpor Minyak Atsiri Dunia, Tahun 2002
Negara pengimpor Nilai (Ribuan US$) (%)
USA 120.220 33,9
Perancis 87.573 24,7
Inggris 48.149 13,6
Swiss 36.237 10,2
Jerman 32.906 9,3
Spanyol 29.411 8,6
Total 354.496 100
Sumber: ITC/Comtrade Statistic, 2003
Minyak atsiri dihasilkan dari proses pengolahan secara penyulingan dari
tanaman atsiri. Berbagai jenis minyak atsiri dikembangkan di Indonesia salah
satunya minyak akarwangi yang dikembangkan di Provinsi Jawa Barat. Tahun
2004, produktivitas tanaman akarwangi paling rendah bila dibandingkan dengan
jenis tanaman penghasil minyak atsiri lain. Hal ini dapat ditunjukkan pada Tabel
7.
Tabel 7. Jenis Minyak Atsiri yang Diusahakan di Provinsi Jawa Barat, Tahun 2004
No Komoditas Luas Areal (Ha) Produksi (Ton) Produktivitas(Kg/Ha)
1. Akarwangi 2.250,00 72,00 32,00
6
Perkembangan luas lahan di Jawa Barat tahun 2000 hingga 2006
berfluktuatif. Tahun 2004 merupakan tahun yang memiliki luas lahan terbesar
yaitu 32 kg/Ha dan 2.250 Ha. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 8. Akar wangi
sebagai salah satu tanaman perkebunan yang bernllai ekonomis tinggi selayaknya
terus dikembangkan agar dapat meningkatkan pendapatan petani, peningkatan
kesempatan kerja, dan peningkatan penerimaan devisa.
Tabel 8. Perkembangan Luas Lahan Akar Wangi di Jawa Barat, Tahun 2002-2006
Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, 2006
1.2. Perumusan Masalah
Akarwangi merupakan salah satu komoditas perkebunan unggulan
Kabupaten Garut yang memiliki arti penting bagi perekonomian daerah. Sekitar
89 persen produksi minyak akarwangi Indonesia dihasilkan dari Kabupaten Garut
(Bappeda Kabupaten Garut, 2005). Hal ini didukung oleh potensi areal seluas
2.400 Ha dan realisasi luas tanam mencapai 1.733 Ha pada tahun 2006 yang
tersebar di empat kecamatan. Hal ini ditunjukkan pada Tabel 9.
Tabel 9. Penyebaran Luas Tanam Akarwangi di Kabupaten Garut
No Kecamatan Potensi Areal (Ha)
Penanaman akarwangi dan pemberian izin usaha penyulingan minyak
akarwangi diatur dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat
No.249/A.II/5/SK/1974 dan SK Bupati Garut No.125/HK.021.1?SK/1978 jo. SK
Bupati Garut No.191/HK.021.1/SK/1978. Berdasarkan SK tersebut, luas lahan
penanaman akarwangi di Kabupaten Garut tidak boleh melebihi 2.400 Ha.
Namun, pada tahun 2006 realisasi luas lahan yang digunakan untuk menanam
akarwangi baru mencapai 1.733 Ha. Oleh karena itu, masih tersedia potensi lahan
yang dapat dikembangkan sesuai dengan SK.Bupati KDH Garut
No.520/SK.196-HUK/90 tentang penanaman dan penyulingan akarwangi di Kabupaten Garut
seluas 2.400 Ha yang tersebar di empat kecamatan.
Meskipun prospek akarwangi cukup cerah, namun pada kenyataannya di
lapangan upaya pengembangan usaha akarwangi masih mengalami kendala.
Pengusahaan budidaya akarwangi masih dijalankan secara sederhana/tradisional
oleh petani dan luas lahan yang diusahakan baru mencapai 1.733 Ha. Padahal
potensi areal mencapai 2.400 Ha sesuai dengan SK Bupati KDH Garut
No.520/SK.196-HUK/90. Hal ini mengindikasikan areal penanaman seluas 667
Ha belum termanfaatkan dan masih berpotensi untuk dikembangkan. Selain itu,
dibutuhkan modal yang besar dalam melakukan pengembangan usaha akarwangi.
Kendala lain yaitu dalam melakukan budidaya dan penyulingan yaitu adanya
fluktuasi harga dan produksi. Gambar 1 merupakan gambar yang menunjukkan
8
Gambar 1. Perkembangan Harga Akarwangi di Kabupaten Garut Pada Tahun 1996-2000
Selain fluktuasi harga akarwangi, adanya fluktuasi harga minyak
akarwangi tahun 1996 hingga 2000 menyebabkan adanya risiko produksi. Hal ini
dapat dilihat pada tabel 2. Selama kurun waktu 1996 hingga 1998 terjadi
peningkatan harga minyak akarwangi, namun tahun 1996 hingga tahun 1999
terdapat penurunan akarwangi. Tahun 1999 hingga tahun 2000 terdapat kenaikan
harga minyak akarwangi hingga mencapai Rp.220.000/kg.
Selain adanya risiko harga, terdapat risiko produksi yang menyebabkan
berfluktuasinya produksi akarwangi dan minyak akarwangi. Gambar 3
menunjukkan bahwa terdapat risiko produksi akarwangi. Tahun 2002 hingga
tahun 2004 terjadi peningkatan produksi akarwangi. Namun, tahun 2004 hingga
2005 terdapat penurunan produksi. Tahun 2005 hingga tahun 2006 terdapat
peningkatan produksi meskipun peningkatannya cenderung kecil.
Gambar 3. Perkembangan Produksi Akar Wangi di Jawa Barat, Tahun 2002-2006
Perkembangan harga akarwangi dan minyak akarwangi, pada dasarnya
menunjukkan berfluktuasinya harga dari tahun ke tahun. Harga akarwangi
tertinggi sebesar Rp.425/kg dan terendah Rp. 175/kg Sedangkan harga minyak
akarwangi tertinggi sebesar yaitu Rp. 220.000/kg dan harga minyak akarwangi
terendah sebesar Rp. 105.000/kg harga terendah. Data terakhir yang diperoleh dari
kegiatan survei diperoleh informasi bahwa harga tertinggi pada tahun 2007 yang
10
diterima oleh penyuling adalah sebesar Rp.582.000/kg dan terendah Rp.
466.923/kg.
Kendala-kendala yang dihadapi menjadi tantangan bagi Pemerintah
Daerah Kabupaten Garut untuk berupaya mengembangkan tanaman akarwangi.
Hal ini dikarenakan akarwangi menjadi salah satu komoditas unggulan tanaman
perkebunan di Kabupaten Garut. Pengembangan usaha akarwangi merupakan
bagian dari strategi pembangunan pertanian yang berwawasan agribisnis dan
agroindustri (Bappeda Kabupaten Garut,1994).
Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas, maka
pengembangan usaha akarwangi, yang terdiri dari kegiatan budidaya dan
penyulingan di Kabupaten Garut dilakukan dengan memanfaatkan lahan yang
belum diusahakan seluas 667 Ha. Hal ini sesuai dengan kebijakan Pemerintah
Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Garut yaitu luas areal penanaman maksimal
2.400 Ha yang baru termanfaatkan seluas 1.733 Ha. Lahan yang belum
diusahakan tersebut diharapkan dapat digunakan secara optimal. Oleh karena itu,
perlu dilakukan studi kelayakan pengembangan usaha yang memperhatikan aspek
budidaya dan pasca panen yakni kegiatan penyulingan. Penyulingan dapat
dikatakan sebagai kegiatan yang tidak terpisahkan dari kegiatan usaha akarwangi.
tanaman akar wangi akan diolah lebih lanjut menjadi minyak akar wangi yang
dilakukan oleh beberapa petani penyuling yang memiliki modal yang relatif besar
bila dibandingkan dengan petani lainnya. Perhitungan atau penilaian dilakukan
agar menghindari kerugian dalam penanaman modal yang terlalu besar dan
wangi. Selain itu, studi kelayakan usaha akarwangi di Kabupaten Garut
diperlukan untuk meminimalkan risiko dalam pengembangan usaha.
Dengan melakukan analisis kelayakan usaha maka dapat membandingkan
antara tingkat keuntungan yang diperoleh pada kondisi normal dengan kondisi
risiko. Dengan demikian, diharapkan hasil studi kelayakan usaha ini dapat
memberikan informasi kepada investor untuk menarik minatnya menanamkan
modal pada usaha akarwangi.
Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Apakah usaha akarwangi di Kabupaten Garut layak diusahakan?
2. Bagaimana dampak adanya risiko volume produksi dan harga output terhadap
kelayakan usaha akarwangi?
1.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:
1. Menganalisis kelayakan usaha akarwangi di Kabupaten Garut
2. Menganalisis dampak adanya risiko volume produksi dan harga output
terhadap kelayakan usaha akarwangi di Kabupaten Garut.
1.4. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta masukan bagi
berbagai pihak yang berkepentingan, yaitu :
1. Bagi petani dan penyuling akarwangi, penelitian ini memberikan alternatif
dalam meminimalkan risiko yang terjadi dalam pengembangan usaha
12
2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, hasil penelitian ini dapat dijadikan
bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan yang terkait dengan
pengembangan usaha akarwangi.
3. Bagi investor/masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu
referensi dalam mempertimbangkan penanaman modal di usaha akarwangi.
4. Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk mengembangkan daya analisis
2.1. Gambaran Umum Akarwangi
Tanaman akarwangi (Vetiveria zizanioides) termasuk keluarga graminae, berumpun lebat, akar tinggal, bercabang banyak, dan berwarna kuning pucat atau
abu-abu sampai merah tua. Tanaman ini ditemukan tumbuh secara liar, setengah
liar, dan sengaja ditanam di berbagai negara yang beriklim tropis dan subtropics
(Kanisius, 1995).
Tanaman akarwangi diproses melalui penyulingan yang akan
menghasilkan minyak akarwangi (minyak atsiri). Minyak atsiri merupakan salah
satu bahan pewangi yang potensial. Biasanya dipakai secara luas untuk pembuatan
parfum, bahan kosmetika, dan sebagai bahan pewangi sabun. Minyak atsiri selain
berfungsi sebagai zat pengikat (fiksatif), juga memberikan wangi menyenangkan,
tahan lama, dan keras. Pemakaiannya harus memperhatikan dosis karena baunya
yang keras. Jika dosisnya berlebihan akan memberikan kesan bau yang tidak enak.
Oleh karena itu, penggunaan minyak akar wangi ini dicampur dengan nilam,
minyak mawar, dan minyak “sandalwood”.
Seiring dengan peningkatan kebutuhan terhadap produk-produk
wewangian, maka kebutuhan terhadap minyak akarwangi pun cenderung
bertambah. Penghasil utama minyak akarwangi di Indonesia adalah Kabupaten
Garut. Minyak akarwangi Indonesia di luar negeri dikenal dengan nama “Java Vetiver Oil”. Tanaman ini biasanya diusahakan di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Cimanuk dan di lereng-lereng berbukit dan bergelombang. Akarwangi
14
Akan tetapi, ketinggian optimum yang menghasilkan produktivitas tertinggi
adalah sekitar 600-1.500 meter di atas permukaan laut.
Tanah yang sesuai untuk menanam akarwangi adalah di tanah yang
berpasir atau pada tanah abu vulkanik. Pada tanah tersebut akar tanaman akan
menjadi lebat dan panjang. Selain itu, tanaman akarwangi masih dapat tumbuh di
tanah-tanah liat yang mengandung air. Namun kelemahan tanah ini adalah sulit
dicabut dan pertumbuhan akar menjadi terhambat.
Derajat kemasaman tanah (pH) yang cocok bagi pertumbuhan tanaman
akarwangi sekitar 6-7. Tanah yang terlalu masam atau dibawah 5,5 akan
menyebabkan tanaman akarwangi menjadi kerdil sehingga akarnya akan
berbentuk kurus dan berukuran kecil. Penanaman akarwangi sekaligus dapat
berfungsi sebagai usaha konservasi tanah dan air, karena kelebatan akarnya
mencapai + 50 cm. maka akarwangi dapat ditanam di pematang-pematang sawah
untuk menghindari atau mengendalikan kerusakan pematang-pematang sawah.
Pertumbuhan tanaman akarwangi pun didukung oleh adanya sinar
matahari yang jatuh secara langsung. Maka, bila tanaman akarwangi ditanam
ditempat yang teduh akan berpengaruh tidak baik terhadap pertumbuhan sistem
akar dan mutu minyak pun akan menurun.
2.1.1. Budidaya Akar Wangi 2.1.1.1. Pembibitan
Tanaman akarwangi dapat diperbanyak secara vegetatif, yaitu
menggunakan bonggol-bonggol akarnya. Bonggol tersebut didapatkan dari
pecahan bonggol memiliki mata tunas. Kemudian bonggol dapat langsung
ditanam di kebun (Kanisius, 1995).
Kebutuhan bonggol bibit untuk lahan satu hektar sekitar dua ton dengan
jarak tanam antara 0,75 x 0,75 meter atau 1 x 1 meter tergantung tingkat
kesuburan tanah. Satu lubang tanam dibutuhkan 2-3 bonggol bibit.
2.1.1.2.Penanaman
Tahap pertama yang perlu diperhatikan adalah persiapan lahan. Meskipun
akar wangi pada dasarnya kurang membutuhkan pengolahan tanah, namun tanah
yang menjadi media tanam akarwangi perlu diolah terlebih dahulu. Pengolahan
tanah tersebut dilakukan dengan pencangkulan. Dengan cara ini, tanah yang
semula berada di bagian bawah akan berada di permukaan dan mendapat cahaya
matahari, sekaligus rumput dan tumbuhan pengganggu lainnya akan mati.
Pada fase awal pertumbuhan, tanaman akarwangi membutuhkan air yang
cukup. Oleh karena itu, waktu tanam sebaiknya diusahakan pada permulaan
musim hujan, yaitu bulan Oktober-November Penanaman bibit akarwangi
dilakukan dengan cara memasukkan bonggol siap tanam ke dalam lubang tanam
yang telah dibuat, kemudian ditutup kembali dan tanah di sekitarnya agak
dipadatkan. Jarak tanam pada tanah yang subur adalah 1 x 1 meter, sedangkan
pada tanah yang kurang subur 0,76 x 0,75 meter. Lokasi penanaman akar wangi
pada lahan miring perlu dibuat terasering.
2.1.1.3.Pemeliharaan
Pemeliharaan akarwangi meliputi: penyulaman, penyiangan,
16
minggu setelah tanam, hendaknya diadakan pemeriksaan ke kebun akarwangi. Hal
ini untuk melihat akar wangi yang tidak tumbuh atau bahkan mati agar dilakukan
penyulaman. Kegiatan ini untuk mengetahui jumlah tanaman yang sesungguhnya
dan akan digunakan untuk memprediksi produk yang dihasilkan (Kanisius, 1995).
Kegiatan yang dilakukan dalam pemeliharaan akarwangi yaitu
penyiangan. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah datangnya hama yang
biasanya menjadikan gulma lain sebagai tempat persembunyian, sekaligus untuk
memutus daur hidup hama. Tindakan penyiangan dilakukan pada umur tiga bulan
sejak tanam dan pada awal maupun akhir musim penghujan.
Tanaman akarwangi tidak tahan terhadap tanah yang tergenang air. Oleh
karena itu, perlu dilakukan pembumbunan agar aerasi dan drainase dapat diatur
dengan baik. Kegiatan ini dilakukan bersamaan dengan kegiatan penyiangan.
Setelah dilakukan kegiatan penyiangan, yang perlu diperhatikan adalah kegiatan
pemupukan. Pertumbuhan akarwangi akan terganggu apabila kondisi tanah tidak
subur. Pemupukan dilakukan biasanya dilakukan dua kali dalam satu tahun. Pada
umur tiga bulan, pupuk yang diberikan untuk lahan seluas satu hektar adalah lima
ton pupuk kandang, 100 kg urea, 50 kg TSP, dan 50 kg KCL. Sedangkan pada
bulan ke sembilan dilakukan pemupukan dengan dosis yang berbeda yaitu lima
ton pupuk kandang, 50 kg urea, 25 kg TSP, dan 25 kg KCL. Cara pemberian
pupuk adalah dengan memasukan pupuk ke dalam lubang melingkar sedalam 10
Setelah tanaman berumur + 6 bulan dilakukan pemangkasan daun untuk
mendapatkan akar yang rimbun dan panjang. Pemangkasan ini dilakukan tga
bulan atau enam bulan sekali pada daerah dataran tinggi. Sedangkan pada dataran
rendah tidak perlu dilakukan pemangkasan karena akan menurunkan hasil
produksi.
2.1.1.4. Pemanenan
Waktu pemanenan akar wangi bergantung pada musim dan penggunaan
tanah. Kondisi tanaman dan kandungan minyak masih sedikit apabila dipanen
terlalu dini. Namun apabila panen terlambat akan mengakibatkan akar layu dan
mengering sehingga sebagian minyak akan hilang. Oleh karena itu, umur yang
paling baik untuk melakukan pemanenan adalah antara 1,5 -2 tahun (Kanisius,
1995).
Pemanenan dilakukan dengan menggunakan cangkul. Pencabutan tanaman
harus dilakukan secara hati-hati agar akar tidak putus dan tertinggal di dalam
tanah. Akar yang baru dipanen harus dibersihkan dari tanah yang masih melekat
dan dipotong di bawah bonggolnya. Sedangkan daun akar wangi dapat dijadikan
kompos dan bonggolnya sendiri dapat dijadikan bibit untuk penanaman masa
berikutnya kemudian hasil panen tersebut disuling.
2.1.2. Penyulingan Akar Wangi
Minyak atsiri yang berasal dari tanaman akar wangi dapat diperoleh
melalui tiga cara, yaitu: pengempaan, ekstraksi menggunakan pelarut, dan
penyulingan. Dari ketiga cara tersebut, yang erat kaitannya untuk mendapatkan
18
Penyulingan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan minyak atsiri
dengan cara mendidihkan bahan baku yang dimasukkan ke dalam suatu ketel dan
mengalirkan uap jenuh dari ketel pendidih air ke dalam ketel penyulingan. Dalam
hal ini terdapat tiga jens penyulingan yaitu: 1) penyulingan dengan air,
2)penyulingan dengan air dan uap, 3) penyulingan dengan uap
2.1.2.1. Penyulingan dengan air
Prinsip kerja penyulingan dengan air dimulai dengan pengisian air pada
ketel penyulingan kemudian dipanaskan. Sebelum air mendidih, bahan baku
dimasukkan ke dalam ketel penyulingan. Dengan demikian penguapan air dan
minyak atsiri berlangsung secara bersamaan. Penyulingan ini disebut penyulingan
langsung. Penyulingan ini merupakan cara tertua dan sangat mudah dilaksanakan.
Namun, kualitas minyak atsiri yang dihasilkan cukup rendah (Kanisius, 1995)..
2.1.2.2. Penyulingan dengan air dan uap
Penyulingan ini relatif lebih maju dibandingkan penyulingan dengan air.
Prinsip kerja yang dilakukan adalah dimulai dengan ketel penyulingan diisi air
sampai batas saringan. Bahan baku diletakkan di atas saringan sehingga tidak
berhubungan langsung dengan air yang mendidih, tetapi akan berhubungan
dengan uap air. Penyulingan ini disebut penyulingan tidak langsung. Air yang
menguap akan membawa partikel-partikel minyak atsiri dan dialirkan melalui pipa
ke alat pendingan sehingga terjadi pengembunan dan uap air yang bercampur
minyak atsiri tersebut akan mencair kembali. Selanjutnya dialirkan ke alat
pemisah untuk memisahkan minyak atsiri dari air. Kualitas yang dihasilkan cukup
2.1.2.3. Penyulingan dengan uap
Penyulingan dengan cara ini memerlukan modal yang relatif besar
dibandingkan cara-cara yang sebelumnya. Namun, kualitas minyak atsiri yang
dihasilkan jauh lebih sempurna. Prinsip kerja penyulingan seperti ini hampir sama
dengan cara menyuling dengan air dan uap tetapi antara ketel uap dan ketel
penyulingan harus terpisah. Ketel uap yang berisi air dipanaskan, lalu uap tersebut
dialirkan ke ketel penyulingan yang berisi bahan baku, partikel-partikel minyak
pada bahan baku terbawa bersama uap dan dialirkan ke alat pendingin. Di dalam
alat pendingin itulah terjadi proses pengembunan, sehingga uap air yang
bercampur minyak akan mengembun dan mencair kembali. Selanjutnya dialirkan
ke alat pemisah yang akan memisahkan minyak atsiri dari air (Kanisius, 1995)..
Mengingat produksi minyak akarwangi di Indonesia hampir seluruhnya
diekspor, maka pemerintah telah menetapkan persyaratan ekspor. Warna
akarwangi yang didayaratkan yaitu kecoklat-coklatan sampai kemerah merahan.
berat jenis pada suhu 25 derajat celcius,bilangan ester antara 5-25
Umumnya minyak akarwangi yang baik ditandai oleh berat jenis dan
putaran optik yang tinggi. Komponen penting lainnya adalah vetiverol. Menurut
Santoso (1993), peningkatan kadar vetiverol di dalam minyak akar wangi akan
20
2.2. Studi Kelayakan Proyek
Tahapan pertama dalam kegiatan proyek adalah identifikasi gagasan
proyek, yaitu menganalisis gagasan, ide, atau saran-saran mengenai rencana
proyek yang akan dilaksanakan. Setelah analisis pendahuluan dilakukan, maka
analisis lebih rinci dilakukan yang disebut dengan istilah studi kelayakan. Studi
kelayakan akan memberikan informasi yang cukup untuk melaksanakan proyek
tersebut. Studi kelayakan akan memberikan kesempatan untuk menyusun proyek
agar bias sesuai dengan lingkungan fisik dan sosialnya, serta dapat memastikan
bahwa proyek tersebut akan memberikan hasil yang optimal (Herjanto, 1999).
2.3. Hasil Penelitian Terdahulu
Penelitian yang dilakukan Damanik (2003) di Kecamatan Samarang,
Kabupaten Garut, Jawa Barat. Data aspek sosial ekonomi diambil dari 120 petani
akarwangi dan 22 pabrik penyuling akarwangi. Percobaan lapangan dilaksanakan
pada lahan seluas tiga hektar. Metode penelitian yang digunakan yaitu rancangan
acak kelompok dengan tiga pola tanam dan dua ulangan. Perlakuan yang dicoba
adalah pola tanam petani, pola tanam introduksi, dan pola tanam konservasi.
Parameter yang diamati adalah berat akar, kadar minyak, tingkat erosi, tingkat
produktivitas, dan kelayakan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari
ketiga pola yang diteliti ternyata pola konservasi mempunyai berat akar yang lebih
tinggi yaitu 0,74 kg, sedangkan pola petani 0,60 kg dan pola introduksi 0,50 kg.
Hasil analisis kadar minyak ketiga pola menunjukkan bahwa kadar minyak pola
konservasi dan pola petani tidak berbeda nyata yaitu 2,60 persen dan 2,25 persen,
sedangkan pola introduksi hanya 1,25 persen. Dari kedua parameter di atas (berat
dibandingkan dengan pola lainnya. Tingkat erosi yang terjadi di pertanaman
akarwangi adalah: (a) pola petani 26,20 ton/ha, (b) pola introduksi 19,40 ton/ha,
dan (c) pola konservasi 17,80 ton/ha. Tingkat produktivitas yang dicapai dari
ketiga pola usahatani tersebut yaitu (a) pola petani sebesar 16.000 kg/ ha/tahun,
(b) pola introduksi 15.000kg/ha/tahun, dan (c) pola konservasi 18.000kg/ha/tahun.
Dari ketiga pola tersebut yang tertinggi adalah pola konservasi, tetapi analisis
kelayakan ekonomi pada ketiga pola adalah : Pola konservasi : B/C ratio 3,26,
NPV Rp 7.852.000, dan IRR 18,75 persen; Pola introduksi : B/C ratio 2,03, NPV
Rp 5.089.000, dan IRR 18,75 persen; Pola petani : B/C ratio 3,60, NPV
Rp7.130.000, dan IRR 18,50 persen. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa
usaha tersebut layak untuk dilaksanakan.
Penelitian yang dilakukan oleh Khairunnisa (2004) mengenai perencanaan
kelayakan pengembangan usaha budidaya lebah madu (Apis mellifera) di Jawa Timur dilihat tingkat kelayakannya berdasarkan aspek-aspek kelayakan usaha.
Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pengembangan usaha tersebut layak
untuk dikembangkan berdasarkan aspek teknis, aspek manajemen, aspek sosial
dan lingkungan, dan aspek finansial.
Pola pengembangan usaha yang dilakukan adalah dengan menetapkan
empat skenario. Skenario pertama yaitu pengembangan usaha menggunakan
pakan lebah tanaman sepanjang tahun (12 bulan) dan menggunakan pengemasan
madu. Skenario kedua yaitu pengembangan usaha menggunakan pakan lebah
tanaman sepanjang tahun (12 bulan) dan tanpa menggunakan pengemasan madu.
Skenario ketiga yaitu pengembangan usaha menggunakan pakan lebah tanaman
22
Skenario keempat yaitu pengembangan usaha menggunakan pakan lebah tanaman
semusim (7 bulan), stimulasi pada saat paceklik (5 bulan), dan tanpa pengemasan
madu. Berdasarkan keempat skenario tersebut, skenario pertama paling layak
untuk dijalankan karena NPV bernilai positif, nilai Net B/C > 1, IRR lebih dari
tingkat diskonto (60%), dan payback period paling cepat yaitu 1 tahun 10 bulan 6 hari. Selain itu, adanya perubahan tingkat diskonto sebesar 14 persen dari keempat
skenario tidak didapatkan NPV negative sehingga keempat skenario tersebut dapat
dijalankan.
Penelitian yang dilakukan oleh Dolly (2006) mengenai analisis kelayakan
investasi pengusahaan pembibitan duria (Durio zibhetinus) di CV.Milad Perkasa Rancamaya Bogor menghasilkan beberapa kesimpulan. Analisis dilakukan pada
ketiga pola. Pola pertama bahwa bibit dijual seluruhnya untuk proyek gerakan nasional rehabilitasi hutan dan lahan (GNRHL). Pola kedua bibit dijual langsung ke konsumen. Pola ketiga bahwa bibit 50 persen dijual ke GNRHL dan 50 persen dijual langsung ke konsumen. Dari ketiga pola tersebut, pola kedua paling layak
untuk dijalankan karena NPV bernilai positif, Net B/C > 1, IRR > discount rate,
pay back periode paling cepat. Selain itu, switching value dengan parameter penurunan penjualan dan peningkatan biaya dilakuakn pada ketiga pola. Pola
kedua paling sensitif terhadap kedua parameter yang digunakan.
Penelitian yang dilakukan Sukarman (2007) mengenai risk management, suatu kebutuhan bagi pengelolaan perbankan yang sehat menghasilkan beberapa
kesimpulan. Bagi perbankan, penerapan pengelolaan risiko menyebabkan
bertambahnya biaya, jumlahn pegawai, waktu, dan mengurangi inisiatif untuk
gilirannya akan mempengaruhi performanya. Krisis tahun 1997 yang berdampak
hingga sekarang dan berbagai kecurangan menyebabkan trauma akan berulangnya
krisis ini. Namun, penerapan berbagai peraturan termasuk pengelolaan risiko
perbankan dan perekonomian nasional akan segera membaik sehingga risiko
bisnis juga berkurang. Hal ini akan mendorong perbankan untuk melanjutkan
intermediasinya karena pertumbuhan suatu ekonomi suatu negara memerlukan
III. KERANGKA PEMIKIRAN
3.1. Kerangka Teoritis
Pada bagian ini dijelaskan tentang konsep dan teori yang berhubungan
dengan penelitian kelayakan pengembangan usaha akarwangi (Andropogon zizanoid) pada kondisi risiko di Kabupaten Garut yaitu studi kelayakan usaha, aspek-aspek studi kelayakan, konsep nilai waktu uang, kriteria kelayakan
investasi, dan risiko dalam investasi.
3.1.1 Studi Kelayakan Usaha
Proyek ialah suatu keseluruhan aktivitas yang menggunakan
sumber-sumber untuk mendapatkan kemanfaatan (benefit) atau suatu aktivitas yang mengeluarkan uang dengan harapan untuk menghasilkan hasil (returns) di waktu yang akan datang, yang dapat direncanakan, dibiayai, dan dilaksanakan sebagai
satu unit (Kadariah et al, 1999). Studi kelayakan proyek adalah penelitian tentang dapat atau tidaknya suatu proyek (biasanya merupakan proyek investasi)
dilaksanakan dengan berhasil (Husnan dan Muhamad.2000).
Menurut Kadariah et al (1999), tujuan analisis suatu usaha adalah untuk memperbaiki pemilihan investasi karena sumber-sumber yang tersedia bagi
pembangunan terbatas. Oleh karena itu, perlu diadakan pemilihan antara berbagai
macam proyek. Kesalahan dalam memilih proyek dapat mengakibatkan
pengorbanan terhadap sumber-sumber yang langka. Studi kelayakan usaha sangat
perlu dilakukan untuk menentukan apakah dan sampai berapa jauhkah proyek
Sumber tersebut dapat ditingkatkan dengan cara menginvestasikan sebagian
sumber yang tersedia pada saat ini. Melalui investasi tersebut,
sumber-sumber itu menjadi modal yang merupakan salah satu faktor produksi yang
menghasilkan barang dan jasa untuk dikonsumsi di waktu yang akan datang.
Secara umum studi kelayakan mencakup aspek pasar, aspek teknik, aspek
manajemen, aspek ekonomi dan sosial (Husnan dan Muhamad.2000). Menurut
Kadariah et al (1999), bahwa setiap aspek tersebut terdapat suatu macam analisis yang menitikberatkan aspek itu. Tetapi dalam rangka ilmu evaluasi proyek
biasanya hanya ditekankan dua macam analisis yaitu analisis finansial dan analisis
ekonomis. Analisis finansial merupakan analisis dimana proyek dilihat dari sudut
badan-badan atau orang-orang yang menanam modalnya dalam proyek atau yang
berkepentingan langsung dalam proyek. Analisis ekonomis merupakan analisis
dimana proyek dilihat dari sudut perkonomian secara keseluruhan. Dalam
penelitian ini, analisis yang digunakan adalah analisis finansial.
Menurut Kadariah et al (1999), benefit proyek dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: direct benefit, indirect benefit, dan intangible benefit. Direct benefit dapat berupa kenaikan dalam output fisik atau kenaikan nilai output yang disebabkan
oleh adanya perbaikan kualitas, perubahan lokasi, perubahan dalam waktu
penjualan, penurunan kerugian, dan penurunan biaya. Kenaikan dalam nilai output
dapat disebabkan oleh kenaikan produk fisik, perbaikan mutu produk, perbaikan
dalam lokasi dan waktu penjualan, dan perubahan dalam bentuk. Sedangkan
penurunan biaya dapat berupa keuntungan dari mekanisasi, penurunan biaya
26
terdiri dari multiplier effect dari proyek, benefit yang disebabkan karena adanya
economic of scale, dari benefit yang ditimbulkan karena adanya dynamic secondary effects berupa perubahan dalam produktivitas tenaga kerja yang disebabkan oleh perbaikan kesehatan atau keahlian. Intangible benefit suatu proyek adalah benefit yang sulit dinilai dengan uang, seperti: perbaikan lingkungan hidup, perbaikan pemandangan karena adanya suatu taman, perbaikan
distribusi pendapatan, integrasi nasional, pertahanan nasional, dan lain
sebagainya.
Biaya dan manfaat yang dirasakan dalam menjalankan suatu proyek
ditentukan oleh laju inflasi. Semakin cepat laju inflasi maka semakin besar pula
ukuran benefit yang dinyatakan dalam uang atas dasar harga yang berlaku. Di lain pihak, terjadinya inflasi akan mempengaruhi ukuran biaya. Namun, biasanya
benefit dari suatu proyek lebih besar daripada biayanya. Jika tidak, maka proyek tersebut harus ditolak. Oleh karena itu, inflasi akan membesarkan benefit bersih yang diukur atas dasar harga yang berlaku. Selain itu, terdapat beberapa pedoman
untuk menentukan panjangnya umur proyek (Kadariah et al, 1999), antara lain: a. Ukuran umum yang dapat diambil suatu periode (jangka waktu) yaitu sama
dengan umur ekonomis dari proyek. Umur ekonomis suatu aset ialah jumlah
tahun selama pemakaian aset tersebut dapat meminimumkan biaya.
b. Proyek-proyek yang mempunyai investasi modal yang besar lebih mudah
untuk menggunakan umur teknis daripada umur-umur pokok investasi. Dalam
hal ini untuk proyek-proyek tertentu umur teknis dari unsur-unsur pokok
investasi adalah lama tetapi umur ekonomisnya dapat jauh lebih pendek