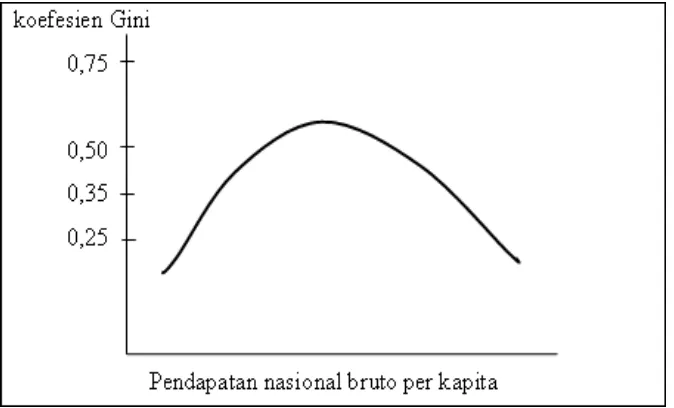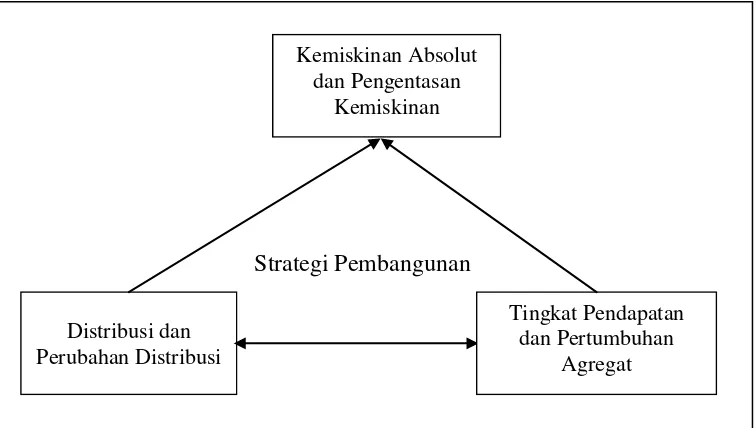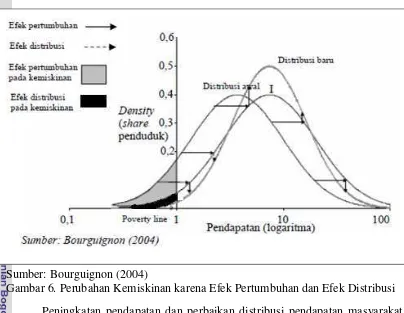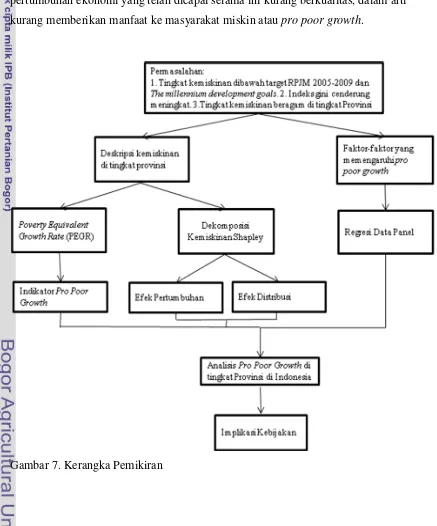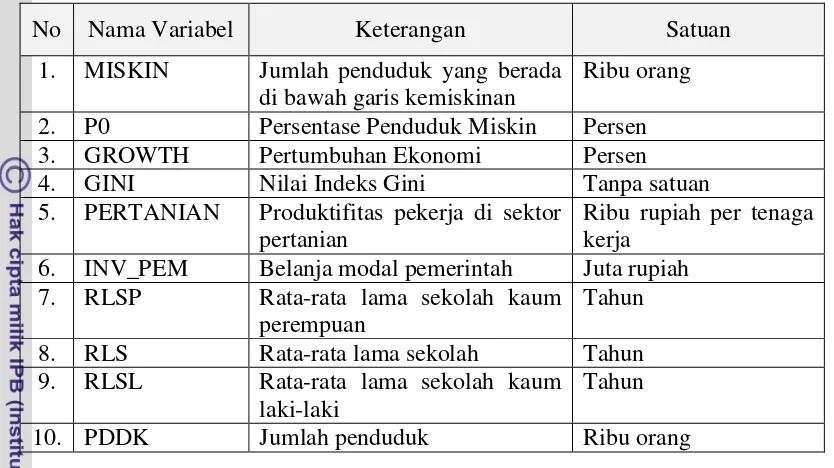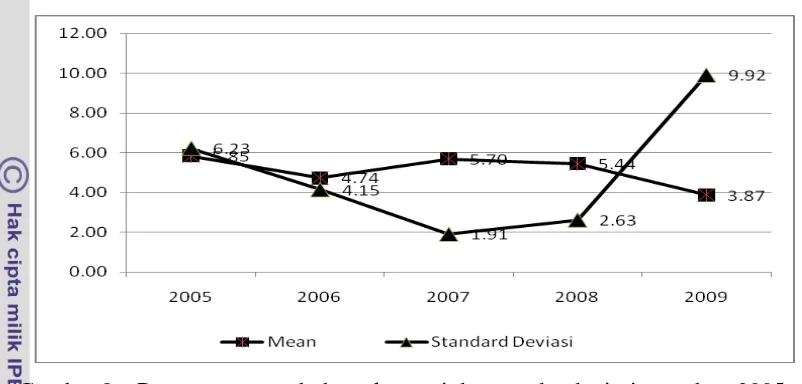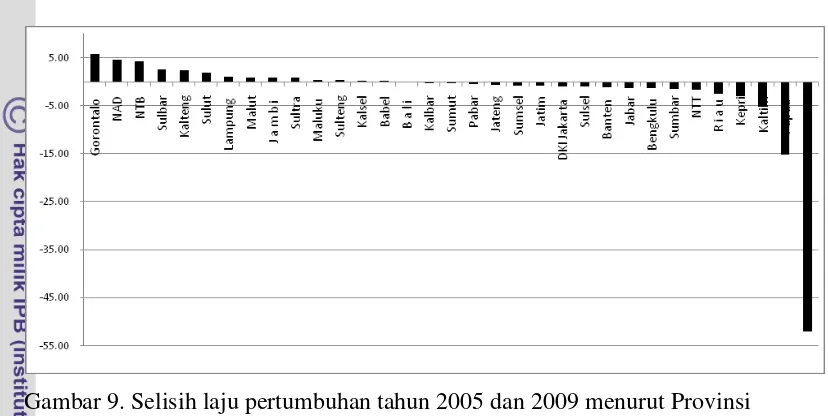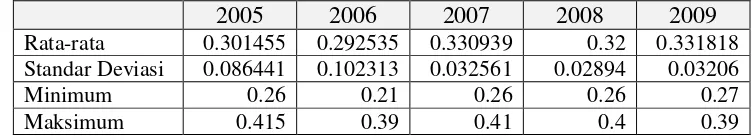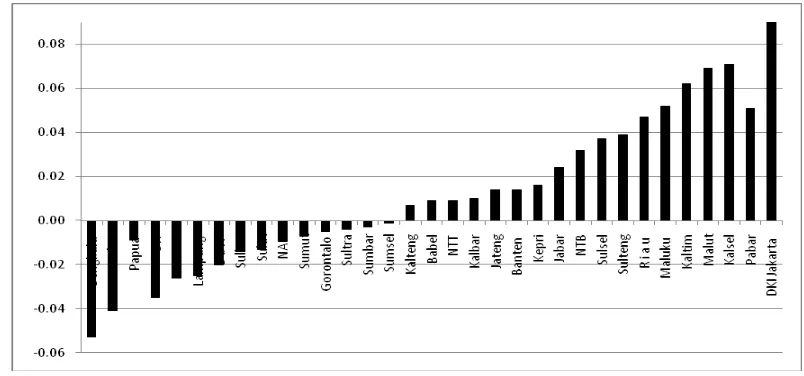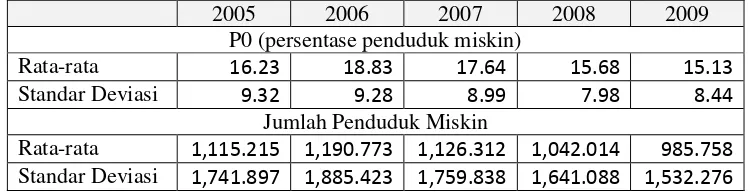ATIK MAR’ATIS SUHARTINI
NRP: 151090274
SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis Pro Poor Growth Tingkat Provinsi di Indonesia adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir tesis ini.
ATIK MAR’ATIS SUHARTINI: Pro Poor Growth at Province Level in
Indonesia. Under supervision of NUNUNG NURYARTONO and
LUKYTAWATI ANGGRAENI.
Economic growth should provide benefits to the poor, so they have opportunities to improve their economic condition or called pro poor growth. The purpose of this study: to analyze the growth and distribution effect of poverty reduction by province, to analyze pro poor growth by province, and determine factors that influenced pro poor growth or poverty reduction. The main data which used in this research is annual income percapita data during 2005-2009 from national economic and social surveys at household level. The research methods are descriptive analysis, shapley decomposition of poverty analysis, poverty equivalent growth rate (PEGR) and panel data analysis. Study shows that during 2005-2009, economic growth tends to decline with increasing income inequality, and affects diversity of poverty reduction in province level. The economic growth is not yet pro poor growth at first periode (2005-2006), and pro poor growth at 2007-2009 periode. Econometric analysis with REM (Random Effect Model) determines that agriculture productivity, education (average of school) and population significantly influence poverty reduction (pro poor growth). Higher agriculture productivity and better education are significant in reducing poverty. In contrast, increasing population means increasing poverty.
The advice can be given as follows: the government, especially local government not only geting high growth in their development, but also pay attention to reduce income inequality. Improving the welfare of the poor can be done by increasing agricultural productivity with revitalization of agriculture. Education or human capital of the poor needs to be increased given the positive impact on poverty alleviation. Finally, controlling the population growth rate needs to be intensified related increasing in basic needs and jobs that must be fulfilled as a consequence population growth.
ATIK MAR’ATIS SUHARTINI: Pro Poor Growth Tingkat Provinsi di Indonesia. Dibimbing oleh NUNUNG NURYARTONO dan LUKYTAWATI ANGGRAENI.
Upaya pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan telah dilakukan sejak Pelita III dan menjadi agenda utama dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) tahun 2005-2009 melalui ‘triple track strategy’ program pembangunan pro growth, pro job dan pro poor. Hingga tahun 2009, kemiskinan cenderung menurun hingga 14,15 persen, walaupun masih di bawah target RPJM 2005-2009 sebesar 8,2 persen dan target Deklarasi Milenium PBB sekitar 7 persen. Sedangkan indeks gini sebagai ukuran ketimpangan pendapatan, hingga tahun 2009 menunjukkan kecenderungan meningkat menjadi 0,37 yang sebelumnya sebesar 0,36 tahun 2005.
Pertumbuhan ekonomi seharusnya lebih memberikan manfaat kepada penduduk miskin dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki keadaan ekonominya, atau pertumbuhan ekonomi yang bersifat pro poor growth. Pro poor growth dengan titik berat pada penduduk miskin, akan memperbaiki kesejahteraannya dan distribusi pendapatan akan lebih merata (equity aspects), dimana aspek ini akan memperkuat dampak pertumbuhan terhadap pengentasan kemiskinan (Kakwani dan Pernia, 2000 dan Grimm, et al., 2007). Suparno (2010) menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum bersifat pro poor growth pada periode 2002-2005 dan pro poor growth periode 2005-2009. Akan tetapi derajat pro poor growth di tingkat provinsi bisa berbeda satu sama lain.
Berdasarkan uraian tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis gambaran pertumbuhan ekonomi, distibusi pendapatan dan kemiskinan di tingkat provinsi di Indonesia, menganalisis efek pertumbuhan dan efek distribusi terhadap perubahan kemiskinan di tingkat provinsi di Indonesia, menganalisis derajat Pro poor growth di tingkat provinsi di Indonesia, dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi Pro poor growth di tingkat provinsi di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan data utama berupa data konsumsi rumah tangga hasil Susenas Konsumsi Panel selama tahun 2005-2009, yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Dinamika pertumbuhan ekonomi, distribusi pedapatan dan kemiskinan dianalisis dengan metode desktiptif melalui nilai rata-rata, standar eviasi dan analisis kuadran. Metode dekomposisi kemiskinan Shapley digunakan untuk menganalisis efek pertumbuhan dan efek distribusi terhadap perubahan kemiskinan. Poverty Equivalent Growth Rate (PEGR) merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung derajat manfaat pertumbuhan terhadap penduduk miskin. Sedangkan faktor-faktor yang memengaruhi pro poor growth dianalisis dengan menggunakan regresi data panel.
fenomena ketimpangan di tingkat provinsi yang semakin tinggi. Sedangkan rata-rata dan standar deviasi dari persentase dan jumlah penduduk miskin, selama tahun 2005-2009 cenderung menurun. Pertumbuhan ekonomi yang cepat disertai dengan perbaikan distribusi pendapatan, menghasilkan kemiskinan di bawah rata-rata terjadi di provinsi Jambi, Bangka Belitung dan Kalimantan Tengah.
Pada awal periode 2005-2006, baik efek pertumbuhan maupun efek distribusinya berpotensi meningkatkan kemiskinan. Sehingga secara total memiliki net effect meningkatkan kemiskinan. Sedangkan pada akhir periode 2008-2009, baik efek pertumbuhan maupun efek distribusi keduanya berdampak pada pengurangan kemiskinan. Selain itu semakin banyak jumlah provinsi yang memiliki efek pertumbuhan dan efek distribusi menurunkan kemiskinan di akhir periode.
Pada awal periode 2005-2006, pertumbuhan ekonomi bersifat anti pro poor growth yang berarti penduduk miskin tidak merasakan manfaat pertumbuhan. Sebaliknya pada akhir periode 2008-2009, pertumbuhan ekonomi telah bersifat pro poor growth yang berarti penduduk miskin merasakan manfaat pertumbuhan lebih besar daripada penduduk tidak miskin. Demikian juga jumlah provinsi yang semakin banyak di akhir periode dengan pertumbuhan ekonomi yang telah bersifat pro poor growth.
Berdasarkan hasil estimasi regresi data panel, produktivitas sektor pertanian, rata-rata lama sekolah baik total ataupun menurut jenis kelamin laki-laki maupun perempuan, dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin. Produktifitas sektor pertanian dan rata-rata lama sekolah baik total ataupun menurut jenis kelamin memiliki pengaruh negatif, yang berarti peningkatan produktifitas sektor pertanian dan peningkatan rata-rata lama sekolah akan menurunkan kemiskinan. Sedangkan jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin, yang berarti peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan jumlah penduduk miskin.
Saran yang dapat diberikan diantaranya sebagai berikut: pemerintah khususnya di daerah hendaknya tidak hanya mengejar pertumbuhan yang tinggi dalam pembangunan, akan tetapi juga pemerataan pendapatan dalam rangka pengentasan kemiskinan. Peningkatan kesejahteraan penduduk miskin dalam rangka pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan meningkatkan produktifitas sektor pertanian melalui revitalisasi pertanian. Pendidikan atau human capital penduduk miskin juga perlu ditingkatkan mengingat pengaruhnya yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Selain itu, kontrol terhadap laju pertumbuhan penduduk perlu digalakkan kembali terkait peningkatan kebutuhan dasar dan lapangan pekerjaan yang harus terpenuhi sebagai konsekuensi pertambahan jumlah penduduk.
©Hak Cipta milik IPB, Tahun 2011 Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
ATIK MAR’ATIS SUHARTINI
Tesis
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada
Program Studi Ilmu Ekonomi
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Judul Tesis : Pro poor Growth Tingkat Propinsi di Indonesia Nama : Atik Mar’atis Suhartini
NRP : H151090274
Disetujui Komisi Pembimbing
Dr. Ir. R. Nunung Nuryartono, M.Si
Ketua Anggota
Dr. Lukytawati Anggraeni, SP, M.Si
Diketahui
Ketua Program Studi Dekan Sekolah Pascasarjana
Ilmu Ekonomi
Dr. Ir. Nunung Nuryartono, M.Si Dr. Ir. Dahrul Syah, M. Sc, Agr.
Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas ijin dan ridho-Nya penulis mampu untuk dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Tema yang dipilih untuk penelitian ini adalah “Pro Poor Growth tingkat Provinsi di
Indonesia”, yang pelaksanaannya dimulai pada Bulan Nopember 2010.
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Nunung Nuryartono,Ph.D selaku ketua komisi pembimbing dan Ibu Lukytawati Anggraeni, Ph.D selaku anggota komisi pembimbing atas arahan dan masukan dalam menyusun tesis ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Dr. Ali Said, MA atas kesediaannya menjadi penguji luar komisi, dan Tanti Novianti, M.Si selaku perwakilan Program Studi Ilmu Ekonomi. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada para dosen pengajar dan pengelola Program Studi Ilmu Ekonomi Sekolah Pascasarjana IPB. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Kepala Badan Pusat Statistik dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Statistik yang telah memberikan kesempatan dan dukungan untuk melanjutkan pendidikan Program Magister pada Program Studi Ilmu Ekonomi di Sekolah Pasca Sarjana IPB.
Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih yang tak terkira kepada Eko Puji Santoso (suami), Muhammad Iqbal Wicaksana (anak pertama), Muhammad Akbar (anak kedua) dan seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan yang luar biasa, berupa moril dan materiil dari awal perkuliahan hingga penyelesaian tesis ini.
Akhirnya, besar harapan penulis agar tesis ini dapat menghasilkan penelitian yang bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi pembangunan di Indonesia khususnya dalam hal poverty reduction, serta bermanfaat bagi dunia pendidikan.
Bogor , Juni 2011 Penulis,
Achyari dan ibu Marsini. Penulis merupakan putri kedua dari tiga bersaudara. Penulis juga telah menikah dengan Eko Puji Santoso dan dikaruniai dua orang putra: Muhammad Iqbal Wicaksana dan Muhammad Akbar.
Penulis menamatkan sekolah dasar pada SDN Pagotan II tahun 1990, kemudian melanjutkan ke SMPN 1 Geger dan lulus pada tahun 1993. Pada tahun yang sama diterima di SMAN 1 Geger dan lulus pada tahun 1996, kemudian melanjutkan ke Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) Jakarta dan berhasil menamatkan Program Diploma IV pada tahun 2000.
xi
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL... xiii
DAFTAR GAMBAR... xiv
DAFTAR LAMPIRAN... xv
I PENDAHULUAN... 1
1.1 Latar Belakang... 1
1.2 Perumusan Masalah... 7
1.3 Tujuan Penelitian... 9
1.4 Manfaat Penelitian... 9
1.5 Ruang Lingkup... 10
II TINJAUAN PUSTAKA... 11
2.1 Pertumbuhan Ekonomi... 11
2.2 Kemiskinan... 13
2.3 Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan... 16
2.4 Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan... 17
2.5 Pro Poor Growth... 19
2.6 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pro Poor Growth... 23
2.7 Tinjauan Empiris... 26
2.8 Kerangka Penulisan... 31
2.9 Hipotesis Penelitian... 34
III METODE PENELITIAN... 35
3.1 Jenis dan Sumber Data... 35
3.2 Metode Analisis... 35
3.2.1 Analisis Deskriptif... 36
3.2.2 Dekomposisi Kemiskinan Shapley... 37
3.2.3 Poverty Equivalent Growth Rate (PEGR)... 38
xii
IV DINAMIKA PERTUMBUHAN, DISTRIBUSI PENDAPATAN
DAN KEMISKINAN... 55
4.1 Pertumbuhan Ekonomi... 55
4.2 Distribusi Pendapatan... 58
4.3 Kemiskinan... 61
4.4 Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi... 64
4.5 Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan... 66
4.6 Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan... 69
V PRO POOR GROWTH... 73
5.1 Dekomposisi Kemiskinan... 73
5.2 Poverty Equivalent Growth Rate (PEGR) ... 79
5.3 Dekomposisi Kemiskinan Shapley dan PEGR... 85
VI FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEMISKINAN... 89
6.1 Analisis Model Regresi Data Panel... 89
6.2 Faktor yang Memengaruhi Pro Poor Growth dengan Pendekatan Poverty Reduction... 92
6.2.1 Produktifitas Sektor Pertanian... 92
6.2.2 Tingkat Pendidikan... 94
6.2.3 Jumlah Penduduk... 97
6.2.4 Pengeluaran Pemerintah untuk Investasi Publik atau Investasi Pemerintah dan Ketimpangan Pendapatan... 98
VII KESIMPULAN DAN SARAN... 105
7.1 Kesimpulan... 105
7.2 Implikasi Kebijakan... 105
7.3 Saran Penelitian Lebih Lanjut... 106
xiii
DAFTAR TABEL
1. Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia dan Persentasenya Tahun 1976-2010...
3 2. Persentase Penduduk Miskin di Indonesia menurut Provinsi Tahun
2008 dan 2009 serta Selisihnya...
6
3. Variabel yang digunakan dalam penelitian dan
keterangannya...
54 4. Ukuran Statistik Deskriptif Indeks Gini di Indonesia tahun
2005-2009... 59 5. Ukuran Statistik Deskriptif P0 dan Jumlah Penduduk Miskin di
Indonesia tahun 2005-2009... 63 6. Pembagian Provinsi menurut Nilai Rata-rata Persentase Penduduk
Miskin (P0), Rata-rata Indeks Gini dan Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi (Growth), Tahun 2005-2009... 70 7. Jumlah Provinsi menurut Efek Pertumbuhan dan Efek Distribusi
dalam Dekomposisi Kemiskinan Shapley Periode 2005-2009... 86 8. Jumlah Provinsi menurut Kriteria Pro Poor Growth Periode
2005-2009... 87 9. Hasil Regresi Data Panel Faktor yang Memengaruhi Pro Poor
Growth (dengan pendekatan Jumlah Penduduk Miskin) dengan Tiga
xiv
1. Perkembangan Pertumbuhan PDB Riil Atas Dasar Harga Konstan 2000... 2 2. Perkembangan Nilai Indeks Gini Tahun 2002-2009... 5 3. Pertumbuhan ekonomi dan persentase penduduk miskin tahun
2002-2009... 5 4. Kurva U Terbalik Kuznets (Inverted U Curve Hypothesis) ... 17 5. Hubungan antara Kemiskinan, Tingkat Pendapatan Agregat dan
Distribusi Pendapatan... 21 6. Perubahan Kemiskinan karena Efek Pertumbuhan dan Efek
Distribusi... 22 7. Kerangka Penulisan... 33 8. Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi dan Standar Deviasinya Tahun
2005-2009... 56 9. Selisih Laju Pertumbuhan Tahun 2005 dan 2009 menurut
Provinsi... 58 10. Selisih Indeks Gini Tahun 2005 dan 2009 menurut Provinsi... 61 11. Efek pertumbuhan, efek distribusi dan net effect pengurangan
kemiskinan periode 2005-2006 hingga 2008-2009...
74
12. Nilai PEGR dan Growth Nasional Periode 2005-2006 hingga
xv
DAFTAR LAMPIRAN
1. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Provinsi di Indonesia Tahun
2005-2009 (persen) ... 116 2. Selisih Pertumbuhan Ekonomi Menurut Provinsi di Indonesia
Tahun 2005-2009 (persen) ... 117 3. Nilai Indeks Gini Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2009..
118 4. Selisih Nilai Indeks Gini Menurut Provinsi di Indonesia Tahun
2005-2009... 119 5. Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi di Indonesia
Tahun 2005-2009... 120 6. Selisih Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi di
Indonesia Tahun 2005-2009... 121 7. Grafik Kuadran antara Persentase Penduduk Miskin (P0) dan
Pertumbuhan Ekonomi menurut Provinsi di Indonesia Tahun
2005-2009... 122 8. Grafik Kuadran antara Persentase Penduduk Miskin (P0) dan
Distribusi Pendapatan (Indeks Gini) menurut Provinsi di Indonesia
Tahun 2005-2009... 124 9. Keterangan Kuadran... 127 10. Provinsi menurut Persentase Penduduk Miskin (P0) dan
Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2005-2009... 129 11. Provinsi menurut Persentase Penduduk Miskin (P0) dan Indeks
Gini Tahun 2005-2009... 130 12. Nilai Rata-rata Persentase Penduduk Miskin (P0), Pertumbuhan
Ekonomi (Growth) dan Indeks Gini menurut Provinsi Tahun
2005-2009... 131 13. Nilai Efek Pertumbuhan (Growth Effects) dan Efek Distribusi
(Distribution Effects) berdasarkan Dekomposisi Kemiskinan
Shapley menurut Provinsi Periode 2005-2006... 132 14. Nilai Efek Pertumbuhan (Growth Effects) dan Efek Distribusi
(Distribution Effects) berdasarkan Dekomposisi Kemiskinan
Shapley menurut Provinsi Periode 2006-2007... 133 15. Nilai Efek Pertumbuhan (Growth Effects) dan Efek Distribusi
xvi
(Distribution Effects) berdasarkan Dekomposisi Kemiskinan
Shapley menurut Provinsi Periode 2008-2009... 135 17. Nilai Poverty Equivalent Growth Rate (PEGR), Pertumbuhan
Ekonomi Aktual dan Sifat Pertumbuhan menurut Provinsi Periode
2005-2006... 136 18. Nilai Poverty Equivalent Growth Rate (PEGR), Pertumbuhan
Ekonomi Aktual dan Sifat Pertumbuhan menurut Provinsi Periode
2006-2007... 137 19. Nilai Poverty Equivalent Growth Rate (PEGR), Pertumbuhan
Ekonomi Aktual dan Sifat Pertumbuhan menurut Provinsi Periode
2007-2008... 138 20. Nilai Poverty Equivalent Growth Rate (PEGR), Pertumbuhan
Ekonomi Aktual dan Sifat Pertumbuhan menurut Provinsi Periode
2008-2009... 139 21. Output Stata untuk Model pertama dengan variabel Rata-rata Lama
Sekolah Total (RLS) ... 140 22. Output Stata untuk Model kedua dengan variabel Rata-rata Lama
Sekolah Perempuan (RLSP) ... 143 23. Output Stata untuk Model ketiga dengan variabel Rata-rata Lama
I.
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Ketimpangan yang besar dalam distribusi pendapatan dan tingkat
kemiskinan merupakan dua masalah besar di banyak Negara Sedang Berkembang
(NSB), tidak terkecuali Indonesia. Pada awal pemerintahan Orde Baru para
pembuat kebijakan dan perencana pembangunan ekonomi di Indonesia percaya
bahwa proses pembangunan ekonomi yang pada awalnya hanya terpusat di Jawa
dan hanya di sektor-sektor tertentu saja, yaitu sektor yang mempunyai Nilai
Tambah (NTB) yang tinggi, pada akhirnya akan menghasilkan apa yang dimaksud
dengan trickle down effects. Hasil pembangunan melalui pencapaian pertumbuhan
yang tinggi di sektor-sektor tersebut, akan menetes ke sektor-sektor dan wilayah lain di Indonesia (Tambunan, 2009). Proses trikle down effects terjadi ketika
manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh semua kelompok penduduk,
termasuk penduduk miskin melalui penciptaan lapangan pekerjaan sehingga
memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kesejahteraannya.
Namun demikian, sejarah menunjukkan bahwa sejak Pelita I tahun 1969
dilaksanakan, efek menetes ke bawah dari proses pembangunan atau trickle down
effects tersebut kecil dan proses mengalir ke bawah sangat lambat. Nilai rata-rata
laju pertumbuhan ekonomi per tahun mencapai di atas 7 persen sampai krisis
tahun 1997, tetapi dengan tingkat ketimpangan yang semakin besar dan bahkan
jumlah penduduk miskin yang meningkat setelah krisis (Tambunan, 2009).
Gambar 1. menunjukkan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi hingga
tahun 1997, sebelum keadaan perekonomian yang memburuk akibat krisis
sehingga pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sampai -13,13 persen.
Selanjutnya, perekonomian Indonesia kembali membaik dan tumbuh rata-rata
Gambar 1. Perkembangan Pertumbuhan PDB Riil Atas Dasar Harga Konstan 2000
Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama masa Orde Baru
telah memberikan kontribusi yang besar terhadap pengurangan jumlah penduduk
miskin. Selama tahun 1976 sampai tahun 1996 tingkat kemiskinan mengalami
penurunan yang cukup signifikan, yaitu dari 40 persen menjadi 17 persen. Akan
tetapi krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan Juli tahun 1997,
menyebabkan jumlah penduduk miskin kembali mengalami peningkatan. Hal ini
mengindikasikan bahwa pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi
merupakan suatu faktor yang penting bagi penurunan kemiskinan, meskipun
3
Perkembangan persentase penduduk miskin di Indonesia hingga tahun
2009 terlihat pada Tabel 1. berikut.
Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia dan Persentasenya Tahun 1976-2010 Tahun Jumlah Penduduk Miskin (juta) Persentase Penduduk Miskin (%) Tahun Jumlah Penduduk Miskin (juta) Persentase Penduduk Miskin (%)
1976 54,20 40,1 2000 38,70 19,14
1978 47,20 33,30 2001 37,90 18,41
1980 42,30 28,60 2002 38,40 18,20
1981 40,60 26,90 2003 37,30 17,42
1984 35,00 21,60 2004 36,10 16,66
1987 30,00 17,40 2005 35,10 15,97
1990 27,20 15,10 2006 39,30 17,75
1993 25,90 13,70 2007 37,17 16,58
1996 34,01 17,47 2008 34,96 15,42
1998 49,50 24,23 2009 32,53 14,15
1999 47,97 23,43 2010 31,02 13,33
Sumber: BPS, STATISTIK INDONESIA
Peningkatan persentase penduduk miskin yang cukup tajam terjadi pada
tahun 1999 karena krisis ekonomi, yaitu sebesar 26 persen. Banyaknya PHK yang
terjadi dan menurunnya daya beli masyarakat, menyebabkan meningkatnya
jumlah penduduk miskin. Persentase ini masih berada di atas 17 persen hingga
tahun 2003, dan secara perlahan mengalami penurunan hingga sebesar 15,97
persen pada tahun 2005. Pada tahun 2006 persentase jumlah penduduk miskin
kembali mengalami peningkatan sebesar 17,75 persen, dan penyebab utama
peningkatan ini karena peningkatan harga beras sebesar 33 persen (sebagai
dampak larangan impor beras) dan kenaikan harga BBM (World Bank, 2006).
Walaupun sempat mendapat goncangan eksternal dengan adanya krisis global
tahun 2008, persentase penduduk miskin terus mengalami penurunan hingga pada
tahun 2009 mencapai 14,15 persen dan sebesar 13,33 persen pada tahun 2010.
Pencapaian tingkat kemiskinan sebesar 14,15 persen di tahun 2009 ini
masih berada di bawah target kemiskinan dalam RPJM 2005-2009, yaitu sebesar
8,2 persen. Selain itu, tingkat kemiskinan tersebut juga masih jauh dari target
Deklarasi Milenium PBB yang ditandatangani pada KTT Milenium PBB tahun
2000. Salah satu tujuan dari Deklarasi Milenium PBB (The Millenium
dunia yang berpenghasilan kurang dari satu dolar per hari, yang berarti
mengurangi separuh dari jumlah penduduk miskin di dunia pada tahun 2015.
Tingkat kemiskinan sebesar 13,33 persen tahun 2010, berarti harus dikurangi
menjadi sekitar 7 persen pada tahun 2015.
Pengentasan kemiskinan yang cepat, berkaitan erat dengan strategi ‘pro
poor growth’, yaitu strategi pencapaian pertumbuhan ekonomi yang mendorong
peningkatan pendapatan dari masyarakat miskin (Grimm, et al., 2007). Pro poor
growth dengan titik berat pada masyarakat miskin, akan memperbaiki
kesejahteraan masyarakat miskin dan distribusi pendapatan akan lebih merata
(aspek ekuitas atau equity aspects). Aspek ekuitas dari pro-poor growth ini akan
memperkuat dampak pertumbuhan terhadap pengentasan kemiskinan (Kakwani
dan Pernia, 2000). Berkurangnya ketimpangan pendapatan atau aspek ekuitas
secara langsung akan mengurangi kemiskinan, hal ini kemudian akan memberikan
dampak meningkatkan kemampuan pertumbuhan ekonomi terhadap pengentasan
kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan yang selanjutnya mempercepat
pengentasan kemiskinan (Grimm, et al., 2007).
Ketimpangan pendapatan secara nasional berdasarkan ukuran indeks gini
menunjukkan adanya kecenderungan untuk meningkat hingga tahun 2009 atau
distribusi pendapatan yang semakin tidak merata (Gambar 2). Pencapaian
pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan penurunan indeks gini, berarti
peningkatan pendapatan yang telah dicapai tidak dibarengi dengan pemerataan
pendapatan diantara kelompok masyarakat secara baik. Tingkat kemiskinan pada
tahun 2009 ternyata masih jauh dari target RPJM tahun 2005-2009 maupun dari
The Millenium Development Goals, dan bahkan adanya kecenderungan nilai
indeks gini untuk meningkat, menunjukkan kemiskinan maupun ketimpangan
5
Gambar 2. Perkembangan Nilai Indeks gini Tahun 2002-2009
Sejak Pelita III, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk
mengurangi jumlah penduduk miskin dan ketimpangan pendapatan. Komitmen
pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan juga tercantum dalam RPJM
(Rencana Pembangunan Jangka Menengah) tahun 2005-2009 yang disusun
berdasarkan Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK). Keseriusan
pemerintah terhadap penanganan permasalahan ketimpangan pendapatan dan
kemiskinan di Indonesia melalui pembangunan yang Pro Growth, Pro Job dan
Pro Poor, diwujudkan melalui berbagai program pengentasan kemiskinan.
Persentase jumlah penduduk miskin secara nasional menurun hingga mencapai
14,15 persen tahun 2009 dan 13,33 persen tahun 2010, yang sebelumnya sempat
mengalami peningkatan tajam hingga sebesar 26 persen tahun 1999 karena krisis
ekonomi.
Gambar 3. menunjukkan komitmen pemerintah terhadap masalah
kemiskinan, dengan penurunan persentase penduduk miskin sejak tahun 2006
hingga mencapai 13,33 persen pada tahun 2010. Tetapi apabila diperhatikan di
tingkat provinsi, persentase penduduk miskin di provinsi-provinsi yang ada di
daerah Sumatera, Jawa dan Bali secara rata-rata lebih kecil dibandingkan dengan
angka persentase penduduk miskin di daerah lainnya (Tabel 2.).
Tabel 2. Persentase Penduduk Miskin di Indonesia menurut Provinsi Tahun 2008 dan 2009 serta Selisihnya
Provinsi Poverty Rate Provinsi Poverty Rate
2008 2009 Selisih 2008 2009 Selisih
NAD 23.6 21.8 -1.78 NTB 23.1 22.78 -0.35 Sumut 12.1 11.51 -0.61 NTT 25.7 23.31 -2.36 Sumbar 10.4 9.54 -0.84 Kalbar 10.8 9.3 -1.49 R i a u 10.2 9.48 -0.74 Kalteng 8.4 7.02 -1.38 J a m b i 9.2 8.77 -0.44 Kalsel 6.2 5.12 -1.09 Sumsel 17.4 16.28 -1.11 Kaltim 8.6 7.73 -0.84 Bengkulu 19.2 18.59 -0.57 Sulut 9.7 9.79 0.08
Lampung 20.9 20.22 -0.67 Sulteng 20.6 18.98 -1.65 Babel 7.9 7.46 -0.49 Sulsel 13.4 12.31 -1.11 Kepri 8.8 8.27 -0.51 Sultra 19.5 18.93 -0.57 DKI Jakarta 3.9 3.62 -0.24 Gorontalo 20.2 25.01 4.80
Jabar 12.6 11.96 -0.61 Sulbar 16.7 15.29 -1.37 Jateng 19.1 17.72 -1.33 Maluku 29.4 28.23 -1.19 DIY 18.1 17.23 -0.83 Malut 11.1 10.36 -0.73 Jatim 18.2 16.68 -1.52 Pabar 33.5 35.71 2.21
Banten 8.3 7.64 -0.62 Papua 35.3 37.53 2.24
B a l i 5.7 5.13 -0.60
Secara umum terjadi penurunan persentase penduduk miskin pada tahun
2009 dibandingkan tahun 2008, baik secara nasional maupun di tingkat provinsi.
Akan tetapi untuk beberapa Provinsi yang berada di bagian timur Indonesia, pada
tahun 2009 justru mengalami peningkatan persentase penduduk miskin, yaitu
Sulawesi Utara, Gorontalo, Papua dan Papua Barat (Tabel 2.). Hal ini
menunjukkan walaupun secara nasional terjadi penurunan persentase penduduk
miskin, akan tetapi di tingkat provinsi tidak semuanya mengalami hal yang sama.
Selain persentase penduduk miskin yang sangat beragam antar provinsi,
penurunan persentase yang terjadi secara nasional tidak terjadi di semua provinsi.
Sehingga, ‘apakah pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai pemerintah dengan
7
memberikan manfaat terhadap rakyat miskin’ merupakan hal yang menarik untuk
diteliti khususnya di tingkat provinsi.
1.2. Perumusan Masalah
Pembangunan ekonomi yang menempatkan manusia sebagai pusat
perhatian dan proses pembangunan, selayaknya memberikan manfaat bagi semua pihak, termasuk diantaranya kaum miskin atau yang disebut dengan pro-poor
growth (Departemen Sosial RI, 2005). Komitmen pemerintah untuk
mengentaskan kemiskinan terlihat dari berbagai program pengentasan kemiskinan
dalam RPJM 2005-2009 dan tersusun dalam SNPK. Bahkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014,
penekanan pada percepatan pembangunan wilayah (Sumatera, Jawa-Bali,
Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua) dengan tujuan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya
manusia, serta mengurangi ketimpangan (Bappenas, 2010). Pemerintah
memperhatikan kesejahteraan masyarakat tidak hanya di tingkat nasional saja,
akan tetapi hingga ke tingkat yang lebih rendah yaitu kepulauan.
Siregar dan Wahyuniarti (2007) dalam penelitiannya tentang Faktor-faktor
yang Memengaruhi Pengurangan Kemiskinan menyatakan bahwa
Program-Program Pengurangan Kemiskinan sebaiknya lebih fokus pada wilayah pertanian
di perdesaan Pulau Jawa dan Sumatera. Hal ini disebabkan persentase penduduk
miskin selama tahun 2000 sampai 2009 lebih dari 75 persennya berada di pulau
Jawa dan Sumatera. Selain itu, Wicaksana (2007) dalam penelitiannya yang
menganalisis ketimpangan kemiskinan antar Provinsi di Indonesia selama tahun
2000 sampai 2004 dengan menggunakan Indeks Entropi Theil, menyimpulkan
bahwa ketimpangan kemiskinan antar pulau tertinggi terjadi di Pulau Jawa. Hal ini
disebabkan konsentrasi jumlah penduduk miskin terbanyak di Pulau Jawa.
Berdasarkan kedua hasil penelitian tersebut terlihat walaupun pembangunan di Pulau
Jawa dan Sumatera relatif lebih cepat daripada lainnya, akan tetapi hingga RPJM
tahun 2005-2009 berakhir, masalah kemiskinan dan ketimpangan masih merupakan
permasalahan utama yang dihadapi dalam pembangunan, terutama di tingkat provinsi.
Suparno (2010) dalam penelitiannya tentang Studi Pro poor growthPolicy
ketidakmerataan terjadi di seluruh sektor dan status daerah selama periode
2002-2005, kemudian mengalami perbaikan selama periode 2005-2008 kecuali sektor
pertanian di perkotaan dan perdesaan. Tingkat kemiskinan di perdesaan lebih
tinggi dibanding perkotaan, dan mayoritas penduduk miskin bekerja di sektor
pertanian. Pada periode 2002-2005, pertumbuhan ekonomi berdasarkan sektor dan
status daerah (perdesaan dan perkotaan) belum bersifat pro poor growth. Periode
2005-2008, pertumbuhan ekonomi di perkotaan sudah pro poor growth sedangkan
di perdesaan belum bersifat pro poor growth. Hal ini mengindikasikan masih
terjadi bias perkotaan dalam pembangunan. Berdasarkan sektor menunjukkan
bahwa pertumbuhan sektor pertanian belum mengalami pro poor growth,
sedangkan di sektor industri sudah pro poor growth. Walaupun dalam RPJM
2005-2009, pro poor growth telah menjadi agenda penting dalam pengentasan
kemiskinan.
Kajian pro poor growth yang dilakukan oleh Suparno (2010), menghitung
manfaat pertumbuhan bagi penduduk miskin di tingkat nasional. Sedangkan
manfaat pertumbuhan bagi penduduk miskin di tingkat provinsi bisa sangat
beragam dan berbeda dengan yang terjadi secara nasional. Sehingga manfaat
pencapaian pertumbuhan ekonomi terhadap penduduk miskin di tingkat provinsi
melalui kajian pro poor growth merupakan hal yang menarik untuk diteliti,
terutama selama periode RPJM tahun 2005-2009 dengan program pembangunan
yang pro growth, pro job dan pro poor.
Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pro poor growth diantaranya
yaitu peningkatan produktifitas di sektor pertanian, berkurangnya ketimpangan
antar daerah, peningkatan kepemilikan aset dasar bagi rakyat miskin,
berkurangnya ketimpangan gender, berkurangnya ketimpangan bagi kaum
minoritas, komitmen politik untuk kebijakan pro-poor, dan suatu Negara yang
kuat (Klasen, 2007). Selain kajian pro poor growth di tingkat provinsi di
Indonesia, juga akan diteliti faktor-faktor yang memengaruhi pro poor growth.
Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang ingin dibahas
didalam penelitian ini dapat dituliskan sebagai berikut:
1. Bagaimana dinamika pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, dan
9
2. Bagaimana efek pertumbuhan dan efek distribusi terhadap perubahan
kemiskinan di tingkat provinsi di Indonesia?
3. Bagaimana derajat pro poor growth pertumbuhan ekonomi di tingkat
provinsi di Indonesia?
4. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap Pro poor growth di
tingkat provinsi di Indonesia?
1.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai
berikut:
1. Menganalisa dinamika pertumbuhan ekonomi, distibusi pendapatan dan
kemiskinan di tingkat provinsi di Indonesia.
2. Menganalisa efek pertumbuhan dan efek distribusi terhadap perubahan
kemiskinan di tingkat provinsi di Indonesia.
3. Menganalisa derajat Pro poor growth di tingkat provinsi di Indonesia.
4. Menganalisa faktor-faktor yang memengaruhi Pro poor growth di tingkat
provinsi di Indonesia.
1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Ukuran derajat pro poor growth di tingkat provinsi di Indonesia digunakan
untuk mengetahui seberapa besar pertumbuhan ekonomi dirasakan oleh
penduduk miskin. Berdasarkan ukuran ini dapat diketahui apakah
pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat bagi penduduk miskin.
2. Faktor-faktor yang memengaruhi pro poor growth dapat digunakan untuk
mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pro poor growth di
tingkat provinsi di Indonesia. Sekaligus sebagai salah satu pertimbangan
bagi pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, sehingga bisa diambil
kebijakan yang lebih tepat berdasarkan wilayah dalam pengentasan
1.5 Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini meliputi empat hal. Pertama, memberikan gambaran umum
tentang dinamika pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan dan kemiskinan di
tingkat provinsi di Indonesia. Kedua, mendekomposisi perubahan kemiskinan
terhadap efek pertumbuhan dan efek distribusi untuk mengetahui apakah
perubahan kemiskinan yang ada lebih dipengaruhi oleh pertumbuhan atau
distribusi pendapatan. Ketiga, menghitung derajat pro poor growth di tingkat
provinsi di Indonesia. Keempat, memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang
memengaruhi pro poor growth di tingkat provinsi di Indonesia.
Penelitian ini mencakup seluruh provinsi di Indonesia selama periode
RPJM 2005-2009. Data yang tidak tersedia tahun 2005 dan 2006 di provinsi baru
(Papua Barat dan Sulawesi Barat), didekati dengan data yang tersedia di provinsi
induk. Selain itu analisis di tingkat provinsi dilakukan tanpa memisahkan status
desa dan kota, serta tidak memisahkan secara sektoral.
Dekomposisi kemiskinan dan penghitungan derajat pro poor growth
dihitung untuk empat periode, yaitu 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 dan
2008-2009. Hal ini dilakukan untuk mengetahui derajat pro poor growth selama
pelaksanaan RPJM 2005-2009 yang mengagendakan pembangunan yang pro
growth, pro job dan pro poor, sebagai komitmen pemerintah dalam pengentasan
11
II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Pertumbuhan Ekonomi
Sebelum tahun 1970-an, pembangunan (development) secara tradisional
diartikan sebagai kapasitas dari sebuah perekonomian nasional -yang kondisi
ekonomi awalnya kurang lebih bersifat statis dalam kurun waktu yang cukup
lama- untuk menciptakan dan mempertahankan kenaikan pendapatan nasional
bruto atau GNI (Gross National Income). Indeks ekonomi lainnya yang juga
sering digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan adalah tingkat
pertumbuhan pendapatan perkapita (income per capita) atau GNI perkapita (Todaro dan Smith, 2006). Tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan unsur yang
paling diutamakan sedangkan masalah-masalah lain seperti kemiskinan,
diskriminasi, pengangguran, dan ketimpangan distribusi pendapatan, seringkali
dinomorduakan (Todaro dan Smith, 2006)
Pemikiran mengenai pertumbuhan ekonomi terus berkembang, dan secara
umum terdapat empat aliran pemikiran, yakni teori klasik, teori neo-Keynes, teori
neo-Klasik dan teori Modern (Tambunan, 2006). Teori klasik tentang
pertumbuhan antara lain Teori Pertumbuhan Adam Smith, Teori Pertumbuhan
David Ricardo, Teori Pertumbuhan Thomas Robert Malthus, dan Teori Marx.
Terdapat dua hal penting dari teori-teori klasik ini yang membedakan dengan
teori-teori yang muncul sesudahnya, yaitu faktor-faktor produksi utama adalah
tenaga kerja, tanah dan modal, serta peran teknologi, sedangkan ilmu pengetahuan
serta peningkatan kualitas dari tenaga kerja dan dari input-input produksi lainnya
terhadap pertumbuhan output dianggap konstan (teknologi dianggap sebagai suatu
koefisien yang tetap atau tidak berubah).
Teori pertumbuhan yang masuk kelompok pemikiran neo-Keynes adalah
model pertumbuhan Harrod-Domar. Model pertumbuhan Harrod-Domar
menekankan perlunya tabungan untuk kegiatan investasi yang akan mendorong
pertumbuhan ekonomi yang direpresentasikan oleh peningkatan pendapatan
nasional. Model ini merupakan gabungan dengan modifikasi pada model
pertumbuhan dari Domar dan model pertumbuhan dari Harrod, dimana model
model pertumbuhan Harrod lebih pada pertumbuhan Y atau GDP (Gross
Domestic Product) jangka panjang melalui peningkatan rasio modal-output
(Todaro and Smith, 2006).
Pemikiran dari teori neo-klasik didasarkan pada kritik atas
kelemahan-kelemahan sebagai penyempurnaan terhadap pandangan teori klasik. Beberapa
model neo-klasik diantaranya Model Pertumbuhan A. Lewis, Model Pertumbuhan
Paul A. Baran, Teori Ketergantungan Neokolonial, Teori Pertumbuhan WW.
Rostow, dan Teori Pertumbuhan Solow. Model Pertumbuhan A. Lewis dikenal
dengan sebutan suplai tenaga kerja yang tidak terbatas dengan meneliti
gejala-gejala di negara berkembang. Suplai tenaga kerja yang terlalu banyak di sektor
pertanian menyebabkan produktivitas tenaga kerja di sektor ini rendah, sehingga
perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri tidak sampai
menurunkan produksi pertanian (Nafziger, 2007).
Model pertumbuhan Paul A. Baran dikenal sebagai teori pertumbuhan dan
stagnasi ekonomi. Baran berpendapat akibat pengaruh Negara Maju, ekonomi
Negara Berkembang menjadi buruk. Pendapat ini muncul sebagai penolakan
terhadap pemikiran Marxis yang menyatakan bahwa Negara Sedang Berkembang
akan maju seperti di Eropa karena hubungannya dengan Negara Maju (Negara
Kapitalis), sehingga pemikiran ini sering disebut dengan tesis Neomarxis.
Teori Ketergantungan Neokolonial mempunyai dasar pemikiran yaitu
pembangunan ekonomi di Negara Sedang Berkembang sangat tergantung pada
Negara Maju, terutama investasi langsung (PMA) di sektor pertambangan dan
impor barang-barang industri. Sedangkan menurut Rostow, pembangunan
ekonomi di manapun merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus,
yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat maju. Proses pembangunan
yang dimaksud oleh Rostow yaitu masyarakat tradisional, pra kondisi untuk lepas
landas, lepas landas, menuju kedewasaan dan era konsumsi massal tinggi
(Nafziger, 2006).
Model Pertumbuhan Solow merupakan penyempurnaan dari Model
Pertumbuhan Harrod-Domar (Tambunan, 2009). Menurut teori ini pertumbuhan
ekonomi terjadi tidak saja dipengaruhi oleh peningkatan modal (melalui tabungan
13
tenaga kerja (pertumbuhan jumlah penduduk dan perbaikan pendidikan) dan
peningkatan teknologi, dengan asumsi:
1. Diminishing return to scale bila input tenaga kerja dan modal digunakan secara
parsial dan constant return to scale bila digunakan secara bersamasama.
2. Perekonomian berada pada keseimbangan jangka panjang (full employment).
(Todaro and Smith, 2006; Mankiw, 2007).
Model-model pertumbuhan yang telah dibahas tersebut, secara umum hanya
melihat pada salah satu sumber pertumbuhan saja, yaitu kontribusi dari
penambahan jumlah faktor-faktor produksi. Model ini kurang bisa menjelaskan
fenomena pertumbuhan ekonomi dewasa ini, dimana sumber pertumbuhan yang
terpenting adalah produktivitas yang menunjukkan adanya kemajuan teknologi,
dan bukan dari peningkatan jumlah faktor-faktor produksi yang digunakan. Oleh
karena itu, muncul pemikiran baru tentang pentingnya pengaruh kemajuan
teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi yang dikenal dengan model
pertumbuhan modern.
Model pertumbuhan modern tidak hanya memasukkan faktor-faktor
produksi seperti tenaga kerja dan modal saja sebagai faktor-faktor krusial dalam
pertumbuhan ekonomi, akan tetapi juga memasukkan kualitas sumber daya
manusia (SDM), kemajuan teknologi, kewirausahaan, bahan baku dan material.
Faktor-faktor krusial lainnya yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi
diantaranya ketersediaan dan kondisi infrastruktur, hukum serta peraturan,
stabilitas politik, kebijakan pemerintah, birokrasi dan terms of trade (ToT). Secara
umum, dalam model pertumbuhan modern, teknologi dan manusia tidak lagi
sebagai faktor eksogen saja, tapi merupakan faktor endogen sebagai faktor
produksi yang dinamis.
2.2. Kemiskinan
Kemiskinan seringkali didefinisikan sebagai ketidakcukupan pendapatan
dan harta untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pangan, sandang,
perumahan, pendidikan dan kesehatan, yang semuanya berada dalam lingkup
dimensi ekonomi. Todaro dan Smith (2006) menuliskan cakupan kemiskinan
absolut sebagai persoalan kemiskinan yang lebih penting. Cakupan kemiskinan
cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Penduduk ini hidup di bawah tingkat
pendapatan riil minimum tertentu atau di bawah garis kemiskinan. Garis
kemiskinan yang digunakan berbeda untuk tiap negara, tetapi yang umum
dijadikan standar adalah berdasarkan ketetapan World Bank yaitu pendapatan
perkapita sebesar US$ 1 atau US$2 per hari dalam US $ PPP (Purchasing Power
Parity), bukan nilai tukar resmi (exchange rate).
Menurut Bellinger (2007) konsep kemiskinan melibatkan multidimensi,
multidefinisi dan berbagai alternatif pengukuran. Secara umum, kemiskinan dapat
diukur dalam dua dimensi yaitu dimensi income atau kekayaan dan dimensi
non-faktor keuangan. Kemiskinan dalam dimensi income atau kekayaan tidak hanya
diukur dari rendahnya pendapatan yang diterima karena pendapatan rendah
biasanya bersifat sementara, tetapi juga diukur melalui kepemilikan harta
kekayaan seperti lahan bagi petani kecil dan melalui akses jasa pelayanan publik.
Sedangkan dari dimensi non-faktor keuangan ditandai dengan adanya
keputusasaan atau ketidakberdayaan yang juga dapat menimpa berbagai rumah
tangga berpenghasilan rendah.
Kemiskinan merupakan permasalahan umum yang terjadi dalam
pembangunan ekonomi, dengan berbagai ukuran kemiskinan yang digunakan
sebagai indikator tingkat kemiskinan. World Bank menetapkan kemiskinan
berdasarkan pendapatan per orang per hari, dimana penduduk miskin
didefinisikan sebagai penduduk yang mempunyai pendapatan kurang dari US$ 1
atau US$ 2 per hari. Sedangkan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
(BKKBN) menetapkan kemiskinan berdasarkan kriteria keluarga pra sejahtera
(pra KS) dan keluarga sejahtera I (KS I).
Penghitungan tingkat kemiskinan dihadapkan pada dua hal, yaitu
pengidentifikasian penduduk miskin dari total penduduk dan menghitung indeks
kemiskinan berdasarkan data yang tersedia (Sen, 1976). Head-count ratio H
sebagai ukuran kasar kemiskinan memenuhi dua aksiom yaitu aksiom
monotonicity dan aksiom transfer. Aksiom monotonicity yaitu suatu kondisi
dimana penurunan pendapatan seseorang yang berada di bawah garis kemiskinan
15
dimana transfer pendapatan dari seseorang yang berada di bawah garis
kemiskinan ke seseorang yang lebih kaya akan meningkatkan ukuran kemiskinan.
Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan sebagai
ketidakmampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasar. Penduduk miskin
adalah penduduk yang tidak memiliki kemampuan dari sisi ekonomi untuk
memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar.
Nilai garis kemiskinan yang digunakan mengacu pada kebutuhan minimum 2.100
kkal per kapita per hari ditambah dengan kebutuhan minimum non makanan yang
merupakan kebutuhan dasar seseorang yang meliputi kebutuhan dasar untuk
papan, sandang, sekolah, transportasi, serta kebutuhan rumahtangga dan individu
yang mendasar lainnya. Besarnya nilai pengeluaran (dalam rupiah) untuk
memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan non makanan tersebut disebut
garis kemiskinan (BPS, 2007).
Indikator kemiskinan yang dihitung oleh BPS selain jumlah dan persentase
penduduk miskin, juga digunakan ukuran indeks kedalaman kemiskinan (Poverty
Gap Index-P1) dan indeks keparahan kemiskinan (Distributionally Sensitive
Index-P2
∑
=
−
=
q i iz
y
z
n
P
11
α α) yang dirumuskan oleh Foster-Greer-Thorbecke (Foster, et. al., 1984)
sebagai berikut:
dimana: α = 0, 1, 2
z = garis kemiskinan
yi
bawah garis kemiskinan ( i=1, 2, 3, …, q), y
= rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di
i
q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan < q
n = jumlah penduduk
Jika α = 0 maka diperoleh Head Count Index (P0); α = 1 adalah Poverty Gap
Index (P1); dan α = 2 merupakan ukuran Distributionally Sensitive Index (P2).
Poverty Gap Index (P1) merupakan ukuran rata-rata ketimpangan pengeluaran
masing-masing penduduk miskin terhadap batas miskin. Semakin tinggi nilai
indeks ini semakin besar rata-rata ketimpangan pengeluaran penduduk miskin
tertentu dapat memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara
penduduk miskin, dan dapat juga digunakan untuk mengetahui intensitas
kemiskinan.
2.3 Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan
Distribusi pendapatan merupakan porsi pendapatan yang diterima oleh
setiap individu atau rumah tangga dalam suatu wilayah. Pendapatan yang diterima
setiap individu atau rumah tangga tersebut tergantung pada tingkat produktivitas
dan peranannya dalam perekonomian. Ukuran yang sering digunakan untuk
mengukur distribusi pendapatan adalah distribusi ukuran pendapatan, kurva
Lorenz, dan Gini ratio. Ketimpangan pendapatan terjadi apabila sebagian besar
penduduk memperoleh pendapatan yang rendah dan pendapatan yang besar hanya
dinikmati oleh sebagian kecil penduduk. Semakin besar perbedaan pendapatan
yang diterima masing-masing kelompok menunjukkan semakin besarnya
ketimpangan.
Adanya ketimpangan yang tinggi antara kelompok kaya dan miskin
menurut Todaro dan Smith (2006) akan menimbulkan setidaknya dua dampak
negatif yaitu:
1. Terjadinya inefisiensi ekonomi. Hal ini sebagian dikarenakan adanya
ketimpangan yang tinggi menyebabkan semakin banyak penduduk yang
kesulitan mengakses kredit terutama penduduk miskin, sedangkan penduduk
kaya cenderung lebih konsumtif untuk barang mewah atau investasi ke luar
negeri.
2. Melemahkan stabilitas dan solidaritas sosial.
Kuznets (1955) membuat hipotesis hubungan antara pertumbuhan
ekonomi dan ketidakmerataan pendapatan membentuk kurva U-terbalik (
inverted-U curve). Hipotesa Kuznets bersandar pada asumsi bahwa terdapat dua sektor
ekonomi dalam suatu negara, yaitu sektor pertanian tradisional di perdesaan
dengan pendapatan perkapita dan ketidakmerataan pendapatan yang rendah dan
sektor modern (sektor industri dan jasa) di perkotaan dengan pendapatan perkapita
17
[image:40.595.113.450.84.288.2]Sumber: Todaro dan Smith (2006)
Gambar 4. Kurva U Terbalik Kuznets (Inverted U Curve Hypothesis)
Kuznets menekankan adanya perubahan struktural dalam pembangunan
ekonomi, dimana dalam prosesnya sektor industri dan jasa cenderung berkembang
dan terjadi pergeseran dari sektor tradisional ke sektor modern. Selama masa
transisi tersebut, produktifitas dan upah tenaga kerja di sektor modern lebih tinggi
daripada sektor tradisional, sehingga pendapatan perkapita yang diterima juga
lebih tinggi, akibatnya ketidakmerataan pendapatan antara kedua sektor tersebut
meningkat. Sehingga pada awal pembangunan, pendapatan perkapita dan
kesenjangan pendapatan yang masih rendah, selanjutnya kesenjangan pendapatan
meningkat sejalan dengan meningkatnya pendapatan perkapita. Setelah
melampaui titik kulminasi akan terjadi perbaikan pada distribusi pendapatan.
2.4 Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi
utama atau suatu prasyarat keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan
peningkatan kesejahteraan (Tambunan, 2009). Pertumbuhan ekonomi dan
pengurangan kemiskinan dalam hal ini peningkatan kesejahteraannya, merupakan
hal yang saling berkaitan. Keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan
pengurangan kemiskinan menurut Todaro dan Smith (2006) dapat diidentifikasi
sebagai berikut. Pertama, pendapat yang menuliskan bahwa pertumbuhan yang
cepat akan berakibat buruk pada kaum miskin, karena mereka akan tergilas dan
menurut Warr (2000) pertumbuhan yang cepat akan bermanfaat bagi semua
pihak, termasuk penduduk miskin. Kedua, kalangan pembuat kebijakan yang
berpendapat bahwa pengeluaran publik yang digunakan untuk menanggulangi
kemiskinan akan mengurangi dana yang dapat digunakan untuk mempercepat
pertumbuhan. Ketiga, pendapat yang menyatakan bahwa kebijakan untuk
mengurangi kemiskinan tidak harus memperlambat laju pertumbuhan, dengan
alasan sebagai berikut:
1. Kemiskinan akan membuat kaum miskin tidak mempunyai akses sumber
modal, tidak mampu menyekolahkan anaknya, tidak punya peluang
berinvestasi dan mempunyai banyak anak sebagai investasi di masa tua.
Berbagai faktor ini akan menyebabkan pertumbuhan perkapita lebih kecil.
2. Data empiris menunjukkan kaum kaya di negara miskin tidak mau menabung
dan berinvestasi di negara mereka sendiri, walaupun sumber kekayaan mereka
berasal dari negara mereka sendiri.
3. Kaum miskin memiliki standar hidup seperti kesehatan, gizi dan pendidikan
yang rendah sehingga menurunkan tingkat produktivitas. Strategi yang
ditujukan untuk meningkatkan pendapatan dan standar hidup golongan miskin,
selain akan memperbaiki kesejahteraan mereka juga meningkatkan
produktivitas dan pendapatan keseluruhan.
4. Peningkatan pendapatan kaum miskin akan mendorong kenaikan permintaan
produk lokal, memperbesar kesempatan kerja lokal dan menumbuhkan
investasi lokal.
5. Penurunan kemiskinan secara masal akan menciptakan stabilitas sosial dan
memperluas partisipasi publik dalam proses pertumbuhan.
Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang cepat dan pengurangan
kemiskinan bukanlah hal yang saling bertentangan, tetapi harus dilaksanakan
secara simultan.
Siregar dan Wahyuniarti (2007) dalam penelitiannya tentang dampak
pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin
menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan dalam
mengurangi kemiskinan, namun magnitude dari pengaruh tersebut relatif tidak
19
dengan mengharapkan proses trickle down effect dari pencapaian pertumbuhan
ekonomi yang tinggi. Akan tetapi pertumbuhan ekonomi merupakan syarat
keharusan untuk mengurangi kemiskinan.
Dollar dan Kraay (2002) menyatakan bahwa secara rata-rata, pendapatan
kelompok termiskin dalam masyarakat akan meningkat secara proporsional
dengan peningkatan pendapatan rata-rata. Peningkatan pendapatan rata-rata
berarti peningkatan pendapatan dari kelompok termiskin, yang selanjutnya
mengubah kondisi perekonomian kelompok termiskin dan mengurangi
kemiskinan. World Bank (2006) dalam ikhtisarnya menuliskan empat butir
penting dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia yaitu (i) mengurangi
kemiskinan dari segi pendapatan melalui pertumbuhan, (ii) memperkuat
kemampuan sumber daya manusia, dan (iii) mengurangi tingkat kerentanan dan
risiko di antara rumah tangga miskin, dan juga (iv) memperkuat kerangka
kelembagaan untuk melakukannya dan membuat kebijakan publik lebih memihak
masyarakat miskin.
2.5Pro poor growth
Konsep Pro poor growth dijelaskan secara implisit oleh World Bank pada
tahun 1990 dalam laporannya dengan ‘broadbased growth’. Kemudian istilah pro
poor growth baru dijelaskan secara eksplisit dalam bahan kajian World Bank pada
tahun 1993. Sejak saat itu isu pro poor growth telah menarik perhatian secara luas
berbagai kalangan. Pro poor growth merupakan hubungan timbal-balik antara tiga
unsur: pertumbuhan, kemiskinan, dan ketidakmerataan. Tingkat kemiskinan tidak
hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi tetapi juga dipengaruhi oleh level
dan perubahan ketidakmerataan distribusi pendapatan.
Menurut World Bank (2008) terdapat empat metode pengukuran pro poor
growth meliputi:
1. Pro poor growth Index (PPGI) dikemukakan oleh Kakwani and Pernia pada
tahun 2000.
2. Poverty Bias of Growth (PBG) dikemukakan oleh Kakwani pada tahun 2000.
3. Poverty Growth Curve (PGC) dikemukakan oleh Son pada tahun 2003.
4. Poverty Equivalent Growth Rate (PEGR) dikemukakan oleh Kakwani, et. al.
Ravallion (2004) mendefinisikan pro poor growth sebagai peningkatan
PDB yang menurunkan kemiskinan. Menurut definisi ini, pertumbuhan yang
diikuti dengan penurunan kemiskinan termasuk pro poor growth, meskipun tidak
terjadi perbaikan distribusi pendapatan. Sedangkan badan-badan internasional
seperti PBB, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD),
UNDP, dan World Bank lebih sering menggunakan definisi pro poor growth
sebagai pertumbuhan ekonomi yang lebih menguntungkan penduduk miskin dan
memberikan kesempatan pada kelompok penduduk miskin untuk memperbaiki
situasi ekonomi seperti dikemukakan Kakwani, et al. (2004).
Kakwani dan Pernia (2000), dan Son (2003) menuliskan pro-poor growth
tidak hanya memperhitungkan pengurangan tingkat kemiskinan namun distribusi
pendapatan yang lebih merata. Pada prinsipnya pengurangan kemiskinan
bergantung pada dua faktor yaitu pertumbuhan dan distribusi pendapatan antara
penduduk miskin (kelas bawah) dan kaya (kelas atas). Grimm, et. al. (2007)
menuliskan tentang strategi ‘pro poor growth’ yaitu strategi pencapaian
pertumbuhan ekonomi yang mendorong peningkatan pendapatan dari masyarakat
miskin
Bourguignon (2004) menjelaskan hubungan pertumbuhan dan kemiskinan
dalam bentuk hubungan segitiga pertumbuhan, ketidakmerataan dan kemiskinan.
Pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan melakukan perubahan pada
distribusi pendapatan atau dapat juga dengan meningkatkan level pendapatan
(mendorong pertumbuhan). Kelompok dengan pendapatan rendah akan
mendapatkan tambahan pendapatan melalui redistribusi pendapatan, sehingga bisa
memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat terbebas dari kemiskinan. Sedangkan
dengan meningkatkan tingkat pendapatan, pertumbuhan ekonomi harus cukup tinggi
sehingga secara rata-rata pendapatan masyarakat naik. Kenaikan pendapatan ini akan
meningkatkan taraf hidup dan mengentaskan dari kemiskinan.
Gambar 5. merupakan penjelasan grafis dari efek pertumbuhan dan efek
distribusi terhadap distribusi pendapatan dan kemiskinan. Efek pertumbuhan
adalah efek perubahan secara proporsional pada seluruh level pendapatan
21
distribusi adalah efek dari perubahan dalam distribusi pendapatan relatif yang
independen terhadap rata-ratanya.
[image:44.595.117.495.132.346.2]
Sumber: Bourguignon (2004)
Gambar 5. Hubungan antara Kemiskinan, Tingkat Pendapatan Agregat dan Distribusi Pendapatan
Gambar 6. menunjukkan perubahan tingkat kemiskinan, dimana sumbu x
menunjukkan kepadatan distribusi pendapatan yaitu jumlah individu pada tiap
level pendapatan dalam skala logaritma. Sumbu y menunjukkan share penduduk
pada level pendapatan tertentu terhadap seluruh jumlah penduduk. Misalkan pada
distribusi awal jumlah penduduk miskin adalah area di bawah kurva sebelah kiri
garis kemiskinan dan diasumsikan pendapatan perkapita penduduk mengikuti
distribusi log Normal.
Peningkatan pada pendapatan seluruh lapisan masyarakat dengan distribusi
tetap, berarti distribusi pendapatan bergeser ke kanan dan bentuk kurva tetap,
sehingga penduduk yang masuk kategori miskin menjadi sebesar daerah yang
diarsir gelap dan daerah terang. Efek pertumbuhan menyebabkan jumlah
penduduk miskin akan berkurang sebesar daerah yang diarsir lebih terang,
sehingga jumlah orang miskin sekarang sebesar daerah yang diarsir gelap dan
daerah terang. Perubahan menjadi distribusi yang lebih merata dengan tingkat
pendapatan tetap, berarti distribusi pendapatan semakin menyempit, menyebabkan
penduduk yang masuk kategori miskin semakin sedikit (daerah terang). Efek Kemiskinan Absolut
dan Pengentasan Kemiskinan
Distribusi dan Perubahan Distribusi
Tingkat Pendapatan dan Pertumbuhan
distribusi menyebabkan jumlah penduduk miskin berkurang sebesar daerah yang
diarsir gelap, sehingga jumlah orang miskin sekarang sebesar daerah terang.
[image:45.595.79.483.129.442.2]Sumber: Bourguignon (2004)
Gambar 6. Perubahan Kemiskinan karena Efek Pertumbuhan dan Efek Distribusi
Peningkatan pendapatan dan perbaikan distribusi pendapatan masyarakat
secara bersama-sama akan menggeser distribusi pendapatan ke kanan dan
mempersempit ketimpangan antar individu. Hal ini akan mengurangi kemiskinan
sebesar daerah diarsir gelap ditambah dengan daerah diarsir lebih terang, sehingga
semakin efektif dalam mengentaskan kemiskinan. Pada kondisi ini maka jumlah
orang miskin akan sebesar daerah terang.
Hubungan pertumbuhan dan kemiskinan, Kakwani dan Son (2006)
berpendapat bahwa pertumbuhan akan mempengaruhi tingkat kemiskinan tidak
hanya melalui pertumbuhan itu sendiri, tetapi juga melalui cara pendistribusian
manfaat pertumbuhan diantara penduduk. Kombinasi antara pertumbuhan dan
redistribusi pendapatan dalam porsi yang tepat diperlukan untuk membuat
pertumbuhan dapat bermanfaat bagi penduduk miskin sehingga proses
23
2.6 Faktor-faktor yang memengaruhi Pro poor growth
Isu tentang pro poor growth yang semula didefinisikan sebagai
pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan pengurangan penduduk miskin oleh
World Bank, selanjutnya oleh para peneliti seperti Ravallion dan Chen (2001),
Son (2003), Kakwani dan Son (2006) mendefinisikan pro poor growth sebagai
suatu kondisi dimana pertumbuhan ekonomi akan memberikan manfaat yang lebih
ke penduduk miskin. Penduduk miskin mempunyai kesempatan untuk merubah
kondisi perekonomiannya, sehingga bisa keluar dari kondisi miskin. Isu pro poor
growth erat kaitannya dengan pengentasan kemiskinan, dan faktor yang
berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan akan memengaruhi juga pro poor
growth.
Produktifitas sektor pertanian
Bekerja di sektor pertanian akan memberikan peluang untuk menjadi
miskin, sehingga investasi di sektor pertanian merupakan prioritas utama dalam
pengentasan kemiskinan. Luas lahan yang dimiliki bukanlah sebagai faktor utama
yang harus dipenuhi, akan tetapi lebih ke kualitas lahan dan produktifitas sektor
pertanian (Geda, et al, 2005). Menurut Klasen (2007) produktifitas di sektor
tanaman pangan sebagai faktor penting yang berpengaruh terhadap pro poor
growth, khususnya negara yang sebagian besar penduduk miskin berada di
wilayah perdesaan. Meskipun investasi memegang peranan penting dalam
menggerakkan pro poor growth, namun demikian upaya peningkatan
produktifitas di sektor pertanian menjadi lebih penting sebagai instrumen dalam
menggerakkan pro poor growth.
Siregar dan Wahyuniarti (2007) dalam penelitiannya tentang Dampak
Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin
menunjukkan bahwa share sektor pertanian terhadap PDB berpengaruh terhadap
penurunan jumlah penduduk miskin. Suparno (2010) menyimpulkan bahwa
peningkatan PDRB sektoral khususnya pertanian merupakan faktor yang
Pengeluaran Pemerintah untuk Investasi Publik
Fan (2004) membuktikan bahwa pengeluaran pembangunan untuk
infrastruktur dan jasa di daerah pedesaan akan berpengaruh terhadap pertumbuhan
di sektor pertanian yang menjadi sektor terbesar terjadinya kemiskinan di Negara
berkembang. Selain itu pengeluaran pembangunan untuk teknologi dan modal
manusia juga merupakan faktor yang berpengaruh dalam pengentasan kemiskinan
di Negara Berkembang, khususnya negara-negara di Afrika. Pengeluaran
pembangunan baik untuk infrastruktur, jasa, teknologi dan modal manusia
terangkum sebagai pengeluaran investasi publik. Suparno (2010) juga menemukan
bahwa ternyata pengeluaran APBD sebagai proksi pengeluaran pemerintah untuk
sektor publik berpengaruh terhadap penurunan jumlah penduduk miskin.
Pengeluaran pemerintah dapat memberikan pengaruh langsung dan tidak
langsung terhadap kemiskinan (Fan, et al., 1999). Dampak langsung pengeluaran
pemerintah adalah manfaat yang diterima penduduk miskin dari berbagai program
peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pekerja, serta skema bantuan dengan
target penduduk miskin. Dampak tidak langsung berasal dari investasi pemerintah
dalam infrastruktur, riset, pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi penduduk,
yang secara simultan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di seluruh sektor
dan berdampak pada penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan peningkatan
pendapatan terutama penduduk miskin serta lebih terjangkaunya harga kebutuhan
pokok. Iradian (2005) juga menyatakan bahwa selain ketimpangan pendapatan,
pengeluaran pemerintah juga memiliki pengaruh terhadap penurunan kemiskinan.
Pendidikan bagi Kaum perempuan
Tingkat pendidikan kaum perempuan, khususnya bagi perempuan yang
berperan sebagai kepala rumah tangga memberikan pengaruh yang besar terhadap
upaya pengurangan kemiskinan (Geda, et al., 2005). Penelitian yang menunjukkan
hubungan negatif antara pendidikan kaum perempuan dengan fertilitas, dengan
pendidikan yang semakin tinggi maka fertilitas akan semakin rendah yang akan
berdampak pada ukuran rumah tangga, dimana ukuran rumah tangga merupakan
faktor penting yang berpengaruh terhadap kemiskinan. Hal ini terkait dengan
25
poor growth, dimana peningkatan pendidikan bagi kaum perempuan dan akses
untuk bekerja akan mengurangi ketimpangan gender tersebut (Klasen, 2007).
Mukherjee dan Benson (2003) meneliti tentang faktor-faktor yang
berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan di Malawi menemukan dua
variabel penting yang berpengaruh. Dua variabel penting tersebut adalah tingkat
pendidikan khususnya kaum perempuan, dan redistribusi tenaga kerja dari sektor
pertanian ke sektor perdagangan dan jasa, terbukti efektif dalam mengurangi
kemiskinan.
Tingkat Pendidikan bagi Kaum Laki-laki
Geda, et al., (2005) meneliti tentang faktor-faktor yang menentukan
kemiskinan di Kenya menyimpulkan tiga hal yang berpengaruh terhadap
kemiskinan, salah satunya yaitu tingkat pendidikan dari kepala rumah tangga.
Semakin rendah tingkat pendidikan kepala rumah tangga akan semakin besar
memberikan peluang yang lebih besar bagi rumah tangga menjadi miskin. Kepala
rumah tangga yang biasanya dipegang oleh kaum laki-laki, sehingga tingkat
pendidikan bagi laki-laki bepengaruh terhadap pengurangan kemiskinan.
Tingkat Pendidikan
Klasen (2007) menemukan bahwa peningkatan kepemilikan asset dasar
bagi penduduk miskin akan berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan. Asset
dasar yang dimaksud adalah modal manusia, dalam hal ini adalah pendidikan
penduduk miskin. Fan (2004) juga membuktikan bahwa modal manusia dalam
pendidikan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan
khususnya negara-negara di Afrika. Demikian pula halnya dengan Siregar dan
Wahyuniarti (2007) menemukan variabel yang signifikan dan relatif paling besar
pengaruhnya terhadap penurunan kemiskinan adalah pendidikan.
Ketimpangan Pendapatan
Pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal, investasi publik,
desentralisasi fiskal yang berpihak ke masyarakat miskin serta jaring pengaman
sosial yang fokus ke daerah tertinggal berperan terhadap pengurangan
terhadap pro poor growth (Klasen, 2007). Sehingga peningkatan ketimpangan
antar wilayah akan berpengaruh terhadap pro poor growth yang berarti pula
berpengaruh terhadap kemiskinan. Ketimpangan antar wilayah salah satunya bisa
didekati dengan ketimpangan pendapatan antar wilayah yang bisa dilihat dari
ukuran indeks gininya. Gelaw (2010) menyatakan bahwa kemiskinan akan tetap
tinggi jika pertumbuhan ekonomi dibarengi dengan ketimpangan pendapatan
Jumlah Penduduk
Jumlah penduduk mempunyai pengaruh terhadap jumlah penduduk
miskin. Semakin besar jumlah penduduk, maka kemungkinan jumlah penduduk
miskin juga akan semakin besar. Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor
yang berpengaruh terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin (siregar dan
Wahyuniarti, 2007). Indra (2008) juga memasukkan variabel populasi dalam
penelitiannya dengan asumsi bahwa peningkatan jumlah penduduk akan
menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin
Berdasarkan berbagai uraian yang telah dibahas, maka secara umum dapat
dituliskan beberapa faktor yang memengaruhi pro poor growth yang berarti pula
mempengaruhi poverty reduction, yaitu produktifitas sektor pertanian,
pengeluaran pemerintah untuk investasi publik, pendidikan bagi kaum perempuan,
pendidikan bagi kaum laki-laki, tingkat pendidikan, ketimpangan pendapatan dan
jumlah penduduk.
2.7 Tinjauan Empiris
Beberapa studi empiris yang menjelaskan hubungan pertumbuhan dan
pengurangan kemiskinan, khususnya pro poor growth, telah banyak dilakukan
oleh para ahli di berbagai negara maupun di Indonesia. Studi empiris yang pernah
27
No Peneliti Obyek/Tahun Metode/Hasil
(1) (2) (3) (4)
1 Kakwani, et al.
(2003)
Meneliti tentang keterkaitan
antara pertumbuhan ekonomi,
ketimpangan dan kemiskinan
di Korea dan Thailand tahun
1990-1999
Melalui ide pro poor growth, studi ini meneliti sejauh mana masyarakat
miskin memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi dengan
menggunakan Poverty Equivalent Growth Rate (PEGR). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Korea relatif lebih
memberikan manfaat ke masyarakat miskin daripada di Thailand.
2 Nunez dan
Espinosa (2005)
Mengukur pro poor growth
dengan PEGR dan
dekomposisi kemiskinan di
Kolombia periode 1996-2004
Pertumbuhan ekonomi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan,
keduanya mampunyai sifat yang hampir sama. Hanya pada tahun 2001 dan
2003 pertumbuhan bersifat pro poor growth sedangkan pada tahun lainnya
bersifat anti pro poor growth. Peningkatan kemiskinan di perkotaan pada
periode 1996-2004 sebesar 8,84 persen lebih banyak disebabkan oleh efek
pertumbuhan 5,17 persen dan efek distribusi 2,27 persen serta efek
pergeseran penduduk 1,41 per