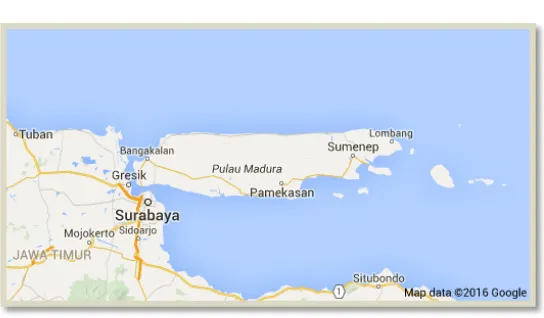ORANG KUAT DALAM DINAMIKA POLITIK LOKAL
STUDI KASUS: KEKUASAAN POLITIK FUAD AMIN DI
BANGKALAN
Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)
Oleh:
Ahmad Nurcholis
1111112000006
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
v
ABSTRAK Nama : Ahmad Nurcholis
Prodi : Ilmu Politik
Judul : Orang Kuat Dalam Dinamika Politik Lokal Studi Kasus: Kekuasaan Politik Fuad Amin Di Bangkalan
Penelitian ini menitikberatkan pada analisa monopoli kekuasaan politik sebagai impak keberadaan orang kuat lokal, bos lokal, dan oligark lokal. Monopoli kekuasaan politik ini setidaknya melahirkan berbagai bentuk penyimpangan, yang juga melahirkan bentuk pemerintahan model dinasti yang merupakan upaya elit untuk menempatkan beberapa kroni dan keluarganya di beberapa pos strategis pemerintahan (Leo Agustino). Model pemerintahan dengan kekuasaan yang absolut serta dinasti seperti ini kerapkali mengarah pada perampokan sistemik anggaran negara dan monopoli berbagai sumber ekonomi strategis. Dalam kasus Fuad Amin, penulis juga menemukan relevansi antara aspek orang kuat lokal dengan pondasi awal lahirnya kekuasaan politik yang berdampak pada konstruksi pemerintahan dinasti. Lahirnya dominasi serta kekuasaan politik Fuad Amin, pertama-tama diuntungkan dengan posisinya yang mewarisi modal kultural sebagai elit keturunan kiai terkemuka di satu sisi, serta kedekatannya dengan dunia blater di sisi lain. Selain itu, Fuad juga diuntungkan karena posisinya sebagai pengusaha/oligark lokal dengan kepemilikan harta yang melimpah. Tiga modal kekuatan awal ini tak pelak mempermudah dirinya untuk melenggang maju ke sektor politik formal. Keberhasilan ini juga ditopang oleh kultur masyarakat yang masih memegang teguh budaya patrimornial, sehingga ketergantungan masyarakat kepada kekuatan patron (Fuad Amin) masih sangat kental.
Metode penelitian yang penulis gunakan adalah dengan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dan telaah tambahan pada beberapa literatur yang penulis anggap penting. Hasilnya adalah bahwa kekuasaan politik Fuad Amin menjadi dominan karena tidak adanya lembaga hukum setempat yang independen, yang berani menindak segala penyimpangan yang dilakukan Fuad. Adanya laporan penyelewengan yang dilakukan oleh Fuad Amin, semisal kasus kekerasan terhadap para aktivis dan berbagai kasus korupsi, selalu mentah di meja polisi dan kejaksaan setempat. Kekuasaan politik Fuad semakin bertambah tatkala dirinya berhasil menjadi bupati Bangkalan pada tahun 2003 dan tahun 2008. Dengan mengenyam dua kekuatan, baik formal maupun informal, tampuk dominasi Fuad semakin tak terbendung. Fuad Amin bak raja yang bebas berbuat sekehendak hati dan tanpa kontrol yang tak terbatas. Gambaran ini tercermin dari kekuatan politiknya yang bukan sebatas ada di jejaring internal pemerintahan dan partai politik, tetapi menyebar ke setiap penjuru ormas, institusi pendidikan, dan kelompok-kelompok informal.
vi
KATA PENGANTAR
Proses penyusunan skripsi yang memakan waktu berbulan-bulan ini
penulis akui adalah berkat bantuan yang diberikan oleh banyak pihak. Baik
bantuan berupa saran maupun materil. Untuk itu, penulis patut mengucapkan rasa
terima kasihnya pertama-tama kepada:
1. Prof. Dr. Zulkifli, MA selaku Dekan Fisip UIN Jakarta.
2. Dr. Iding R. Hasan M.si selaku kepala jurusan Ilmu politik.
3. Dr. Chaider S. Bamualim M.A selaku dosen pembimbing.
4. Orang tua yang selalu memotivasi penulis untuk sesegera mungkin
menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Seluruh jajaran dosen ilmu politik FISIP UIN Jakarta.
6. Ela, Ima, Ali, Ikbal, Ilham, kawan-kawan angkatan, kawan-kawan
kampung, kawan pondok, kawan PMII, dan
kawan-kawan diskusi, yang namanya tidak bisa penulis sebut satu persatu.
Terima kasih banyak atas motivasinya, mengutip puisi Sutan Takdir:
“segala kulihat segala membayang, segala kupegang segala
mengenang,” kalian merupakan bagian sejarah kenangan yang tak
terlupakan.
7. Lembaga TII (Transparancy International Indonesia) yang karenanya
penulis mendapatkan beasiswa penelitian dan masukan berharga di
vii
8. Dan terakhir, rasa terima kasih ini khususnya penulis tujukan kepada
seluruh narasumber di Bangkalan. Yang demi keselamatan mereka
tidak bisa penulis sebutkan namanya dengan terang. Narasumber amat
terbuka memberikan informasinya atas data-data yang penulis perlukan
selama berlangsungnya wawancara. Seanjang menetap di Bangkalan,
banyak sekali pengalaman berharga yang penulis dapatkan.
Pengalaman itu kiranya akan selalu penulis ingat dan menjadi
pelajaran bagi perjuangan hidup ke depan. Semoga segala pengorbanan
demi mewujudkan Bangkalan menuju arah yang lebih baik tidak
berakhir sia-sia. Terima kasih untuk semuanya.
Depok, 26 Maret 2016
viii
DAFTAR GAMBAR
ix
DAFTAR BAGAN
Bagan IV.1 Bangunan Dinasti Politik Fuad Amin Periode 2003-2008 ... 100
Bagan IV.2 Bangunan Dinasti Politik Fuad Amin Periode 2008-2013 ... 101
Bagan IV.3 Garis Keturunan Syaikhona Kholil ... 146
x A. Geografi dan Demografi Pulau Madura ... 57
B. Tinjauan Singkat Kabupaten Bangkalan ... 64
C. Islamisasi dan Simbol Kiai dalam Perspektif Masyarakat Madura ... 67
D. Blater Sebagai Orang Kuat Lokal Madura ... 80
BAB IV DINAMIKA KEKUASAAN POLITIK FUAD AMIN DI BANGKALAN A. Terbentuknya Kekuasaan Politik Fuad Amin... 89
B. Fuad Amin dan Lanskap Orang Kuat Lokal di Bangkalan ... 107
xi
D. Friksi Bani Kholil ... 143
E. Kondisi Civil Society Selama Kepemimpinan Fuad Amin ... 148
F. Kemenangan Fuad Amin di Pilbup 2003 ... 175
G. Kemenangan Fuad Amin di Pilbup 2008 ... 190
H. Jaringan Kiai Fuad Amin... 209
I. Pencalonan Putranya, Makmun Ibnu Fuad ... 218
J. Penjegalan Imam Bukhori Kholil ... 223
K. Oligark Lokal... 243
L. Stagnasi Demokratisasi Parpol di Bangkalan ... 248
M. Intimidasi dan Strategi Ketergantungan Kepala Desa ... 259
N. Modus Korupsi Fuad Amin ... 270
O. Sumber Kekuasaan Fuad Amin ... 277
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan ... 283
B. Saran ... 288
DAFTAR PUSTAKA ... 290
1 BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
1998 merupakan tonggak awal proses perubahan sistem politik di Indonesia.
Jika di tahun sebelumnya Indonesia mengalami depolitisasi, maka di tahun
tersebut Indonesia mengalami masa transisi menuju reformasi. Reformasi, dalam
Kamus Merriam Webster didefinisikan sebagai “the act or process of
improving something or someone by removing or correcting faults,
problems, etc.” (Sebuah tindakan atau proses untuk meningkatkan
sesuatu/seseorang dengan menghapus atau memperbaiki kesalahan, masalah, dll).1
Secara kontekstual, perubahan dan perbaikan yang dituntutkan saat itu
adalah terkait dua isu penting, pertama menyangkut soal ekonomi, kedua
menyangkut soal politik. Dalam ekonomi, masyarakat mengharapkan adanya
perbaikan perekonomian; turunnya harga barang pokok, berkurangnya
pengangguran, dan adanya peningkatan kualitas standar hidup mereka. Sedangkan
dalam politik masyarakat mengharapkan Soeharto turun dari jabatannya sebagai
presiden.
Pada dasarnya, reformasi sedikitnya telah membawa angin segar bagi
kerangka kehidupan baru masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.
Harapan-harapan akan adanya Indonesia yang lebih baik dan lebih terbuka serta anggapan
bahwa reformasi merupakan simbol era pencerahan, setidaknya telah memberikan
2
sinyal optimisme dan dianggap akan mampu membawa banyak dampak
perubahan. Dua diantara beberapa perubahan yang paling fundamental dari
implikasi lahirnya reformasi ini adalah mulai terbukanya ruang ekspresi publik,
dan tuntutan daerah untuk andil bagian dalam pengelolaan wilayahnya sendiri.
Ikhwal terakhir ini, kita biasa menyebutnya dengan istilah desentralisasi, atau
pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah.
Desentralisasi, di era reformasi, tentu merupakan wacana dan terobosan
baru bagi sistem politik kita. Sekalipun undang-undang yang mengatur jalannya
pemerintahan daerah sebetulnya juga pernah mewarnai lanskap perjalanan sejarah
bangsa Indonesia sejak jaman penjajahan. Terhitung semenjak kolonialisme
sampai berakhirnya rezim orba, setidaknya ada 7 undang-undang yang mengatur
tentang pemerintahan daerah di dalamnya: Decentralisatiewet 1903, Wet op de
Bestuurshervorning (stb 1922/216), Osamuseirei No. 27 tahun 1942, UU No.
1/1945, UU No. 22/1948, UU No. 1/1957, UU No. 18/1965, UU No. 5/1974.2
Namun, undang-undang tentang pemerintahan daerah yang terbit pada era
reformasi, lewat implementasi desentralisasi dan otonomi daerah, memiliki esensi
yang berbeda dari era-era sebelumnya tersebut. Apalagi bila dibandingkan dengan
undang-undang pemerintah daerah pada era Orde Baru (1966-1998), yang
dicitrakan sebagai rezim diktatorial yang sentralistis yang keberadaannya justru
mengkooptasi ruang kebebasan bagi masyarakat untuk turut serta mengelola
negara.3
2 Wasisto Raharjo Jati, “Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia: Dilema
Sentralisasi atau Desentralisasi,” Jurnal Konstitusi, Volume 9 Nomor 4, (Desember 2012).
3
Kehadiran desentralisasi pasca meletusnya gelombang aksi dan demonstrasi,
merupakan fakta penting yang mesti tidak ditunda lagi saat itu. Setidaknya ia telah
menjadi salah satu kebutuhan mendesak yang amat urgen. Hal ini mengingat
banyaknya daerah yang mengancam untuk keluar dari barisan NKRI jika hak-hak
politiknya tidak terpenuhi. Sebab, selama berpuluh-puluh tahun, daerah
termarjinalkan. Mereka hanya menjadi penonton bagi kekayaannya sendiri yang
dirampas, dikeruk, dan dieksploitasi oleh pusat. Artinya, pola sentralistik adalah
paradigma satu-satunya yang membingkai hubungan pusat-daerah yang
diaplikasikan secara otoritatif oleh pemerintahan era Soeharto waktu itu.
Di tengah gejolak tuntutan itu, akhirnya UUD No. 22 tahun 1999 mengenai
pemerintahan daerah dirumuskan dan disetujui oleh eksekutif dan legislatif di
bawah kendali pemerintahan Habibie. Hal ini sedikitnya mampu meredam
instabilitas disintegrasi bangsa kala itu. Di antara beberapa daerah yang menuntut
memisahkan diri waktu itu antara lain: Aceh, Papua, Timor Timur dan Riau –
sekadar menyebutkan.4
Di samping melahirkan konsep desentralisasi – sebagai media antisipasi
gejolak yang terjadi di daerah, reformasi juga telah mencetuskan apa yang kita
kenal dengan kebijakan pemekaran daerah (redistricting)5 dan juga melahirkan
sistem turunannya berupa pilkada langsung. Sekalipun kemunculan sistem pilkada
langsung ini datang agak belakangan.
4 Ibid, h. 7.
5 Istilah redistricting digunakan oleh Leo Agustino untuk membedakan pemahaman terhadap
4
Menurut Leo Agustino, kebijakan redistricting merupakan sebuah upaya
dan usaha dari pemerintah untuk menciptakan tranformasi pelayanan publik yang
lebih komperehensif di masyarakat, agar keberadaan negara benar-benar dirasakan
dan sampai menyentuh masyarakat lapisan bawah – yakni sampai kepada
masyarakat di pelosok daerah terpencil sekalipun. Intinya adalah agar distribusi
kesejahteraan merata. Tidak hanya sebatas dirasakan oleh masyarakat kota.6
Sedangkan adanya mekanisme pilkada langsung merupakan sebuah manifestasi
yang menggambarkan terwujudnya masyarakat merdeka. Masyarakat yang bebas
menentukan siapa saja pemimpin yang pantas bagi mereka.7 Upaya ini dilakukan
dan ada sebagai wahana pengikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan
urusan-urusan negara, pembalikan logika orde baru yang bertubi-tubi mengalienasi
masyarakat dari negara.
Secara diametral, tambah Leo, ada dua faktor; dampak positif dan negatif
yang saling berhadap-hadapan sewaktu munculnya konsep otonomi daerah
(desentraliasasi) di satu sisi dan redistricting (pemekaran jabatan ke daerah) di sisi
lain.8 Dan penulis yakin, bahwa konsep turunannya, seperti lahirnya pilkada
langsung - yang juga tidak disertai pendidikan politik yang memadai - juga
menambah daftar kompleksitas serta kesemrawutan di dalam kehidupan politik
kita era reformasi ini. Selain faktor positif yang telah disebutkan di awal tulisan,
seperti hadirnya kebebasan, keadilan yang merata, dan efisiensi pelayanan publik,
konsep sistem politik baru pasca reformasi seperti ini juga setidaknya menyimpan
6 Leo Agustino, Sisi Gelap Otonomi Daerah: Sisi Gelap Desentralisasi di Indonesia
Berbanding Era Sentralisasi (Widya Padjadjaran, 2011), h. 31. 7 Ibid, h. 31.
5
banyak cacat, ambivalen secara bersamaan.9 Maraknya praktik KKN dan
tumbuhnya pemerintahan model dinasti merupakan contoh kecil dari berbagai
dampak negatif yang dihasilkan sistem desentralisasi. Ekses negatif yang paling
menonjol dari proses transisi ini adalah meruaknya praktek oligarki yang
menggurita ke tingkatan lokal. Reformasi nyatanya telah melahirkan “Soeharto”
baru dalam alam yang berbeda. Hal ini terlihat paradoks, karena di satu sisi
reformasi menumbuhkan harapan, tapi di sisi lain ternyata reformasi adalah
bagian penerusan warisan praktek oligarki yang tak kunjung selesai. Tetapi harus
digarisbawahi, bahwa kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, menurut
Syarif Hidayat, tidak melulu merupakan faktor utama maraknya penyelewengan
kekuasaan di tingkat lokal, perubahan paradigma relasi state-society di jaman orba
dan reformasi, juga turut berperan sebagai unsur penyumbang berkembangnya
kekuatan-kekuatan dominan yang menghambat laju perkembangan sosial,
ekonomi, politik, di masyarakat lokal.10
“...bahwa secara substansial, tidak semua permasalahan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi di daerah saat ini merupakan implikasi langsung dari implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Tetapi lebih sebagai akibat dari adanya pergeseran pola interaksi antara state dan society pada periode pemerintahan pasca Soeharto”11
Hal ini juga sepadan dengan komentar Rahadi T Wiratama dalam
catatannya selaku editor dalam buku Vedi R Hadiz, Dinamika Kekuasaan:
Ekonomi Politik Indonesia Pasca Soeharto, menurutnya, Vedi R Hadiz telah
berhasil memberikan gambaran umum bahwa demokrasi pasca Soeharto
9 Ibid, h. 51.
10 Syarif Hidayat, “Shadow State...? Bisnis dan Politik di Provinsi Banten,” dalam Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken, ed., Politik Lokal di Indonesia (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia dan KITLV, 2014), h. 302.
6
merupakan era di mana para oligark (kolega, kerabat pewaris orba) beradaptasi
dengan mekanisme prosedural formal baru – dengan memanfaatkan instrumen
politik yang tersedia, seperti partai politik, pemilu, parlemen, dan desentralisasi.12
Jadi, tumbangnya Soeharto bukan berarti menghilangkan tradisi oligarki yang
kadung mewabah di masa itu, melainkan meneruskan jenjang serta melahirkan
sistem oligarki dengan jenis yang baru.
Menggeliatnya sepak terjang para oligark yang bermain di wilayah lokal
pasca reformasi secara rasional memang terkesan wajar, karena hal itu menjadi
kesempatan langka bagi mereka (orang kuat lokal) untuk dapat menancapkan
cakarnya lebih dalam ke pusat arus kuasa lokal. Yang tidak mungkin mereka
lakukan saat Soeharto masih eksis berkuasa. Lantaran di zamannya, Soeharto
tidak memberikan celah sedikitpun bagi keberadaan para penentang dan
pesaingnya untuk berkembang. Di mana ia selalu berupaya mencengkeram
eksistensi mereka di berbagai sudut dimensi kehidupan ekonomi-politik. Maka tak
heran bila dalam hal ini Winters kemudian menyebut Soeharto sebagai oligarki
sultanistik.13 Kategoristik yang Winters sematkan kepada jenis kepemimpinan
Soeharto ini tidak terhindar dari eksistensi Soeharto yang menjadi satu-satunya
kekuatan tunggal dari pada oligark yang dominan.
12 Vedi R. Hadiz, Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Pasca-Soeharto, (Jakarta: LP3ES, 2005), h. xxii.
7
Dalam diskursus politik lokal, para oligark aras lokal ini sering diketemukan
dalam bentuknya sebagai “orang kuat lokal” (local strongmen)14 atau para “bos
lokal” (local bosses).15 Bertambah kuatnya eksistensi orang kuat lokal (local
strongmen, istilah Migdal) - karena pusat tak lagi mengontrol keberadaan mereka,
atau mengguritanya para bosisme (bossism, format baru local strongmen versi
Sidel) merupakan reduksi atas nilai-nilai demokrasi di sektor bawah tersebut. Dan
tak jarang, bahkan kebanyakan, antara “local strongmen, bangsawan, serta
birokrat/politisi lokal”16 pasca Soeharto, melakukan persekongkolan untuk
menghisap proyek-proyek negara yang dulu banyak dikerjakan oleh pusat.
Kendatipun untuk beberapa kasus, mereka pun acapkali terlibat sengit dalam
persaingan.17 Hanya saja, persaingan atau kerjasama yang mereka lakukan, tetap
dan tidak terlepas dari kepentingannya untuk mengumpulkan
sebanyak-banyaknya harta kekayaan bagi kemakmuran mereka sendiri, dari pada untuk
kepentingan rakyat.
Dengan bahasa yang lebih sederhana, desentralisasi, redistricting dan
pilkada langsung merupakan wahana peralihan paradigma dari stationary bandits
ke roving bandits.18 Penjelasan tentang stationary bandits dan roving bandits
14 Melvin Perjuangan Hutabarat. “Fenomena „Orang Kuat Lokal‟ Di Indonesia Era
Desentralisasi Studi Kasus Tentang Dinamika Kekuasaan Zulkifli Nurdin Di Jambi,” (Tesis S2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2012), h. 17.
15 Ibid, h. 20.
16 Klasifikasi kekuatan politik di tingkat lokal menurut Leo Agustino dibagi ke dalam tiga arus
utama: pertama adalah para birokrat yang berasal dari bangsawan, kedua birokrat yang berasal dari masyarakat awam, ketiga adalah para orang kuat lokal (Leo Agustino, Sisi Gelap Otonomi Daerah, 2011, h. 64).
17 Leo Agustino, Sisi Gelap Otonomi Daerah, h. 61-67.
18 Pembacaan penulis terhadap stationary bandits dan roving bandits merujuk pada bab yang
8
seperti diungkapkan oleh McGuire dan Olson yang penulis kutip dari Leo
Agustino adalah sebagai berikut::
“Stationary Bandits are rulers without a long lasting base..., they also want to maximize their own incomes. Sedangkan Roving Bandits are rulers without a realm of their own who use their armies to maximize their own incomes. In doing so, roving bandits are perpetually moving around, leaving a place after is plundered. In this respect they are very similar to nomads. The form of organization that result from this behavior is called anarchy
(McGuire & Olson 1996:63).”19
“Bandit Menetap adalah penguasa tanpa basis yang tahan lama ..., mereka ingin memaksimalkan pendapatan mereka sendiri. Sedangkan Bandit Pengembara adalah penguasa tanpa ranah yang menggunakan tentara untuk memaksimalkan pendapatan mereka. Dalam praktiknya, Bandit Pengembara- terus menerus bergerak, meninggalkan tempat setelah menjarahnya. Dalam hal ini mereka sangat mirip dengan kaum nomaden. Bentuk organisasi yang dihasilkan dari perilaku ini disebut anarki (McGuire & Olson 1996:63).” (Terjemahan dari penulis)
Dari sudut pandang historis, keberadaan orang kuat lokal atau local strongmen20
dan bosisme atau bossism21 di jaman orde baru dapat dikategorikan ke dalam dua
posisi yang berbeda. Jika bukan kepanjangan tangan orde baru, mereka adalah
kaum oposisi yang kontra terhadap orde baru. Selepas orba runtuh, dan reformasi
diaplikasikan dalam bentuk mekanisme otonomi daerah serta pilkada langsung,
kedua kelompok ini akhirnya berebut ambisi; saling berkompetisi untuk
bagaimana menguasai daerah yang tidak lagi dikontrol oleh pusat. Peralihan dari
sentralisme ke polisentrisme faktanya telah dijadikan ladang perebutan kekuasaan
oleh mereka. Kembalinya kaum oposisi yang selama zaman orba dibungkam dan
ditindas ke gelanggang politik lokal, memberikan dimensi ketegangan baru
orang kuat lokal, bawahan stionary bandits yang menancapkan pengaruhnya sebagai raja lokal ketika stationary bandits runtuh (Leo Agustino, Sisi Gelap Otonomi Daerah, 2011, h. 33).
19 Leo Agustino, Sisi Gelap Otonomi Daerah, h. 33.
20 Melvin Perjuangan Hutabarat. “Fenomena „Orang Kuat Lokal‟ Di Indonesia Era
Desentralisasi Studi Kasus Tentang Dinamika Kekuasaan Zulkifli Nurdin Di Jambi,” (Tesis S2
9
dengan kelompok yang dulu menyokong orba di ranah politik lokal. Bahkan
kelompok-kelompok tersebut, baik yang pro maupun yang kontra terhadap orba,
menggunakan berbagai cara untuk menghantarkannya menjadi raja lokal
kedaerahan.22 Seluruh potensi sumber daya kekuasaan dipraktikkan, termasuk
suap dan kekerasan (koersif).
Fenomena bos ekonomi (bossism) dan orang kuat lokal (local strongmen)
dalam mobilitas sosial, ekonomi, dan politik di struktur lokal memberikan
sinyalemen kepada kita bahwa tidak selamanya reformasi selalu membawa
dampak yang baik. Bukti di lapangan menunjukan, tradisi orde baru yang sarat
dengan korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) pun marak terjadi di daerah pasca
reformasi diimplementasikan. Para bosism dan local strongmen, pasca mereka
mencapai tampuk kekuasaan, dengan kewenangan yang mereka miliki, juga
melakukan hal yang serupa; represif, koruptif, kolutif, dan nepotistik. Sama seperti
yang dulu pernah dipraktikkan ketika Soeharto berkuasa. Adanya desentralisasi,
seolah-olah hanya mempolarisasikan praktek tersebut. Impaknya, kini KKN tidak
lagi terpusat, melainkan menyebar ke segala penjuru daerah. Bahkan mendagri di
kabinet Presiden SBY, Gamawan Fauji, mengatakan bahwa lebih 115 dari 524
kepala daerah menjalani proses hukum dan kebanyakan terjerat kasus korupsi.23
Kasus-kasus tersebut sampai sekarang masih banyak yang ditangani oleh KPK
dan selebihnya sudah mendekam dalam penjara.
22 Mohammad Agus Yusoff dan Leo Agustino, “Daripada Orde Baru Ke Orde Reformasi:
Politik Lokal di Indonesia Pasca Orde Baru,” Jebat: Malaysian Journal of History, Politics & Strategic Studies, Vol. 39 (July 2012): h. 86.
10
Kinerja para kepala daerah, dalam pusara perubahan menjadi semacam
parasit di tengah asa yang baru pulih. Pengkorupsian aset dan sumber daya daerah
secara besar-besaran, jika bukan rampok, apalagi bahasa yang pantas untuk
mereka? Canggihnya, mereka melakukan berbagai penyimpangan itu melalui
mekanisme lain yang lebih ekslusif, yaitu melalui pembentukan sistem kerja
pemerintahan „dinasti politik‟, - sebuah konsep dan metode “KKN” yang
dilakukan secara sistemik dan tertutup. Lahirnya pemerintahan dinasti seperti itu
tidak terhindar dari kokohnya dominasi sang elit.
Larangan politik dinasti memang tidak tertuang dalam peraturan
perundang-undangan, sebab masing-masing warga negara memiliki hak yang setara dan
egaliter, untuk atau tidak berpolitik; untuk mencalonkan atau dicalonkan.
Kebebasan egaliter ini nyatanya telah dijamin dalam konstitusi kita. Di sinilah
dinasti politik menjadi semacam problem dilematis bangsa. Karena di satu sisi,
model pemerintahan dinasti lahir sebagai pengejewantahan hak politik bagi warga
negara. Tapi di sisi lain, model pemerintahan dinasti politik - dengan kewenangan
yang besar, dan dominasi yang tersebar - rentan menciptakan dan terjadinya
penyelewengan. Seperti apa yang diungkapkan oleh Lord Acton: “power tends to
corrupt and absolute power corrupts absolutelly.”24
Secara definitif, pengertian dinasti politik seperti yang penulis sadur dari
Leo Agustino adalah suatu “kerajaan politik di mana elit menempatkan
keluarganya, saudaranya, dan kerabatnya di beberapa pos penting pemerintahan
11
baik lokal ataupun nasional.”25 Singkatnya, dengan dinasti politik, elit membentuk
strategi semacam jaringan kerajaan yang terstruktur dan sistematis, supaya
penyelewengan berbagai anggaran pemerintahan dapat diakal-akali secara efektif
dan terselubung. Pada prosesnya, dibutuhkan konsep matang untuk membangun
sebuah dinasti. Praktek kedinastian bukanlah usaha instan. Usaha ini memerlukan
strategi canggih dan konsep jitu. Penempatan satu persatu keluarga dan para
kerabat di berbagai pos jabatan penting bukanlah perkara mudah. Agar tidak
menuai protes dan kecaman, tak mungkin dilakukan tanpa melewati
penghegemonian dan dominasi di segala dimensi: baik sosial, ekonomi maupun
politik. Praksisnya, keterbentukannya dipersiapkan matang-matang agar permanen
dan kontinuistik.
Salah satu dinasti politik yang saat ini mendapatkan sorotan khusus di
antaranya adalah dinasti Fuad Amin di Bangkalan. Fuad adalah mantan Bupati
Bangkalan yang selama dua periode berturut-turut memenangkan kontestasi
pilkada. Setelah dua periode memimpin Bangkalan, di tahun berikutnya ia
mencalonkan diri sebagai anggota DPRD, dan terpilih. Kemudian Fuad Amin
didaulat untuk menjadi ketua DPRD Bangkalan. Anaknya, di periode yang sama,
berhasil pula menjadi Bupati Bangkalan, meneruskan estafet kepemimpinannya.
Dalam satu periode tersebut, anak dan ayah sama-sama menguasai dua sektor
paling krusial, yakni eksekutif dan legislatif.
Bangkalan merupakan wilayah administratif (kabupaten) yang masuk ke
dalam bagian Provinsi Jawa Timur. Bangkalan bukanlah wilayah redistricting
12
sebagaimana Banten dan beberapa daerah baru lainnya yang lahir pasca orde baru.
Dan sama halnya dengan beberapa daerah lainnya di Indonesia, sewaktu otonomi
daerah digulirkan, seluruh kekuatan sosial di Bangkalan berebut untuk saling adu
kuasa. Sejalan dengan apa yang Huntington katakan bahwa proses transisi yang
tanpa diikuti pranata politik yang mapan hanya akan menyebabkan perebutan
kekuasaan yang tidak sehat di antara kelompok-kelompok sosial masyarakat.26
Kondisi seperti ini lazim di negeri yang baru pertama mengalami demokratisasi,
sehingga mobilisasi lebih mungkin terjadi ketimbang partisipasi.
Asumsi awal terbentuknya dinasti politik di bawah kepemimpinan Fuad
Amin bisa dilihat dari beragam faktor, pertama dimungkinkan karena alam
reformasi tidak diimbangi oleh pranata hukum yang siap, baik dari segi yuridis
maupun manusianya. Artinya suprastruktur dan infrastruktur hukum belum teguh,
tegak, dan mapan. Kedua, civil society masih lemah, tidak terintegrasi dalam satu
kekuatan dominan. Ketiga, karena Fuad Amin merupakan salah satu cicit Kyai
Kholil Bangkalan yang merupakan ulama besar NU kharismatik yang banyak
dijadikan rujukan ilmu kegamaan. Di tengah masyarakat religius, penghormatan
khidmat kepada para kyai dan keturunannya merupakan sebuah tradisi lahiriah
yang wajib, ditambah, agama merupakan faktor pemersatu identitas masyarakat
Madura.27 Penghormatan masyarakat Bangkalan terhadap Fuad Amin salah
satunya bersumber dari faktor tersebut. Keempat, karena posisi Fuad sebagai
blater (baca: jawara), yang memudahkan dirinya menghegemoni
26 J.W. Schoorl, Modernisasi: Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-negara Sedang
Berkembang (Jakarta: PT. Gramedia, 1981), h. 186.
27 Mutmainnah, “Kiai dan Dinamika Politik Lokal di Kabupaten Bangkalan dan Sumenep,
13
kekuatan sosial di Bangkalan. Menurut Abdur Rozaki, sebagaimana penulis kutip
langsung dari wawancaranya dengan majalah detik, ia mengatakan:
“Kelihaian bermain di dua basis masyarakat, blater dan pesantren, menurut Abdur, melanggengkan kekuasaan Fuad. Mayoritas kepala desa (klebun) di Bangkalan yang menjadi tangan kanan Fuad adalah blater itu. Supaya loyal, para klebun itu disuruh membuat perusahaan lalu diberi proyek.”28
Bukti yang menggambarkan amat berpengaruhnya sepak terjang Fuad Amin di
Bangkalan adalah terlihat dalam sebuah pemberitaan yang dirilis oleh majalah
detik, bahwa menurut majalah tersebut, Fuad Amin digelari “Kanjeng atau Tuhan
Kedua” oleh sebagian masyarakatnya.29
Praktek kedinastian atau kekerabatan yang terjadi di Bangkalan, penulis rasa
sudah menembus batas etis dan moral. Dengan memanfaatkan wibawa dan nama
besar “Kyai Kholil Bangkalan” sebagai legitimasi atas kontrolnya pada
masyarakat, tentu ada sebuah pembodohan masif pada masyarakat yang mesti
segera dicerkaskan, agar masyarakat mulai rasional menanggapi dimensi
keagamaan dan politik praktis secara berbeda. Supaya eksistensi politik dinasti
bukan lagi dianggap sebagai hal mafhum dan wajar oleh sebagian masyarakat
awam, melainkan pengejewantahan oligarki baru era reformasi. Sebab itulah
dinasti politik di Bangkalan sebagai impak dari adanya dominasi yang kuat sangat
penting untuk diteliti, untuk melihat faktor-faktor penunjang keajegan dan
kekokohannya dalam masyarakat yang demokratis.
28 “Dinasti Tuhan Kedua di Bangkalan,” Majalah Detik, edisi 161 (29 Desember 2014 - 4 Januari 2015).
14 B. Pertanyaan Penelitian
Dalam merumuskan masalah pada penelitian ini, penulis mencoba
membatasinya dengan dua pertanyaan, yakni:
1. Bagaimana proses terbentuknya kekuasaan politik Fuad Amin di
Bangkalan?
2. Bagaimana dinamika kekuasaan politik Fuad Amin?
3. Bagaimana kondisi civil society selama kepemimpinan Fuad Amin?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan pokok masalah tersebut diatas, penelitian ini bertujuan:
1. Untuk mengetahui dan menganalisa pola terbentuknya kekuasaan politik
Fuad Amin di Bangkalan.
2. Untuk mengetahui dinamika politik Fuad Amin di Bangkalan.
3. Untuk mendalami kondisi civil society selama kepemimpinan Fuad Amin
di Bangkalan.
D. Manfaat Penelitian
Sebagai sebuah penelitian yang berorientasi atas asas manfaat, peneliti
membagi manfaat penelitian kedalam tiga aspek manfaat.
1. Manfaat Akademis
Secara akademis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur tambahan,
referensi tambahan dan informasi bagi para peneliti yang tertarik pada isu-isu
politik lokal – sebagai bentuk ijtihad bagi kemajuan ilmu politik. Selain itu, hasil
penelitian pun dapat dijadikan bahan rekomendasi bagi masyarakat setempat
15
berlebihan adalah buruk bagi masa depan demokrasi. Orientasi akademis lain dari
penelitian ini setidaknya memberikan gambaran bagaimana terciptanya Good
Governance di lingkungan pemerintahan lokal.
2. Manfaat Praktis
Hakikatnya, penelitian ini dilakukan atas dasar kegelisahan pribadi dalam
melihat fenomena mandegnya pembangunan di daerah-daerah yang memiliki pola
pemerintahan dominasi tunggal. Karena penulis sendiri merasakan betapa civil
society tidak berkembang sama sekali di daerah-daerah tersebut. Sekalipun ada itu
pun hanya suara-suara kecil saja. Karena kegelisahan tersebut akhirnya penulis
harapkan penelitian ini bukan hanya dijadikan sebagai hasil penelitian secara
tertulis, tetapi lebih dari itu dapat dijadikan solusi sekaligus aksiologi - mampu
diimplementasikan dalam kehidupan nyata.
E. Tinjauan Pustaka
Term dominasi dan munculnya dinasti politik di berbagai daerah pasca
reformasi khususnya, menjadi wacana serta diskursus menarik dalam kajian
politik kontemporer masa kini. Permasalahan utama kedinastian yang merebak
dan melanda beberapa segmentasi kehidupan politik di tanah air ditengarai telah
memunculkan rasa ketidakadilan dari segelintir elit yang turun temurun
mempertahankan status quo mereka. Apalagi kinerja elit yang duduk di jabatan
publik tidak mampu bekerja dengan maksimal, bahkan kinerja mereka terkesan
asal-asalan. Maindset yang tertanam dalam diri para birokrat kita bukan untuk
melayani, melainkan mencari keuntungan sebesar-besarnya dari posisi yang
16
mengurus rakyatnya sendiri. Tak ayal akhirnya rakyat kecewa dengan praktek
dominasi dan dinasti seperti ini.
Pemerintahan dengan model dinasti politik yang terjadi di alam demokrasi
memang tidak terlepas dan bersumber dari keterpilihan masing-masing individu
dalam setiap pemilihan, baik pileg, pilbup, pilgub, maupun pilpres. Pendeknya
dinasti politik adalah hak, dan demokrasi membuka ruang sebebas-bebasnya
kepada rakyat, kepada siapapun, untuk memilih atau tidak memilih, untuk
mencalonkan atau tidak mencalonkan, sesuai preferensi masing-masing. Hanya
saja, reformasi yang baru berlangsung, tidak secepat kilat memberikan pendidikan
politik kepada masyarakat, sehingga mobilisasi massa lebih menonjol ketimbang
partisipasi murni. Praktik patronase politik menjadi wacana substantif dalam
mobilisasi tersebut. Padahal syarat berkembangnya pembangunan politik
sebagaimana yang dikemukakan oleh Lucian Pye, bertalian erat dengan masalah
mobilisasi dan partisipasi seperti ini.30 Partisipasi bersumber dari kesadaran
masyarakat atas politik, sedangkan mobilisasi muncul lantaran masyarakat belum
mengerti arti penting politik dalam marwah kehidupan mereka sehari-hari.
Terbentuknya dinasti politik merupakan faktor dari latar belakang dan problem
seperti itu.
Karenanya, tema yang menyangkut dinasti politik banyak diminati. Di
antara mereka adalah Leo Agustino dan Mohammad Agus Yusof (2012):
Daripada Orde Baru Ke Orde Reformasi: Politik Lokal Di Indonesia Pasca Orde
Baru. Di dalam artikel yang diterbitkan oleh Malaysian Journal of History,
30 Lucian Pye, Pembangunan Politik dan Perubahan Politik (Jakarta: PT. Gramedia, 1985), h.
17
Politics & Strategic Studies, Leo dan Yusof menitikberatkan penelitian mereka
pada politik lokal di Indonesia setelah 1998 dan sebelum tahun tersebut. Dari
penelitiannya didapatkan bahwa gelombang demokratisasi tidak selamanya
berakhir dengan hasil yang sempurna. Negara-negara seperti India, Brazil,
Filipina, Thailand, Nigeria dan Peru mengalami nasib yang kurang baik,
berkebalikan dari esensi demokrasi yang diharapkan pada umumnya. Fakta lain
pasca demokratisasi dikumandangkan malah memicu terbentuknya sistem
otokratik semi pada politik lokal di negara-negara tersebut. Kemunculan para
orang kuat lokal serta bos ekonomi di kancah politik lokal merupakan bukti
betapa demokratisasi pun nyatanya dapat lahir dengan wajah lain.31
Esensi demokratisasi sebenarnya adalah untuk membebaskan masyarakat
dari belenggu otoritarian, sebuah transformasi nilai dari masyarakat tertutup
kepada masyarakat yang lebih terbuka, sehingga masyarakat mendapatkan hak
politiknya secara proporsional, terbentuknya civil society yang mapan, dan adanya
check and balance yang konstruktif. Tapi di tengah proses pendemokratisasi-an
tersebut, nyatanya demokratisasi juga telah ditunggangi oleh para free rider yang
kurang lebih memanfaatkan momen untuk adu kuasa baru. Setelah bertahun-tahun
dibungkam hak politiknya oleh rezim otoriter, hasrat untuk menjadi raja kecil di
daerah mewabahi segenap elemen masyarakat di spektrum lokal. Begitupun
dengan demokratisasi di Indonesia, yang tak luput dari keberadaan para pembajak
demokrasi tersebut. Saat demokratisasi berlangsung, banyak di antara mereka,
khususnya para pemain politik lokal yang juga memanfaatkan momen reformasi
31 Mohammad Agus Yusoff dan Leo Agustino, “Daripada Orde Baru Ke Orde Reformasi:
18
sebagai wadah arena persaingan untuk berkuasa. Mereka umumnya para elit lokal
yang dulu saat zaman orba adalah para penyokong, maupun kalangan yang
beroposisi terhadap Soeharto.
Padahal gambaran politik lokal sebelum orde reformasi lahir, berada dalam
posisi yang sangat monoton, sebab daerah tidak memiliki wewenang untuk
mengurus daerahnya secara mandiri. Daerah seolah-olah hanyalah wayang, dan
pusat adalah sebenar-benarnya dalang. Seluruh kebijakan serta wewenang daerah
dikendalikan oleh pusat sepenuhnya. Begitu kuatnya pusat, daerah seakan-akan
sekadar dijadikan sebagai lumbung kekayaan pusat semata; yang dikeruk
kekayaannya namun tidak diperhatikan keberadaannya.32 Tetapi setelah reformasi
1998 meletus, daerah seperti mendapatkan angin segar untuk bangkit. Hiruk pikuk
kehidupan politik yang pelik di masa orde baru seolah-olah sirna dengan
datangnya zaman reformasi. Harapan baru demi terwujudnya demokrasi yang
utuh-penuh, hinggap pada segenap masyarakat di daerah. Karena jika selama
masa orde baru mereka tidak bisa mendapatkan hak politiknya, maka di era
reformasi harapan akan mendapatkan hak politiknya datang kembali.
Tetapi, hasil penelitian Leo dan Yusof mendapatkan fakta lain. Politik lokal
mengalami “bulan madunya” (istilah Leo dan Yusof) sebagai daerah yang
didamba hanya beberapa tahun saja. Setelahnya, lanskap politik lokal di daerah
kembali ke wajah bopeng seperti zaman orba sedia kala. Kehidupan atau dinamika
politik yang berlangsung beberapa masa selanjutnya hampir serupa dengan zaman
19
Soeharto.33 Tumpuan permasalahan dari ketidakberubahan politik lokal pasca
reformasi menurut mereka ada pada eksistensi “orang kuat lokal”. Orang kuat
lokal ini terbagi menjadi dua. Pertama adalah penyokong orba, dimana ketika
Soeharto masih berkuasa, Soeharto tempatkan orang-orangnya di daerah. Tugas
mereka di daerah adalah untuk menjaga stabilitas daerah dari berbagai macam
bentuk protes dan aksi. Orang-orang peliharaan ini merupakan orang kuat yang
disegani – jika bukan karena yang ditakuti. Dan yang kedua adalah orang-orang
yang kontra terhadap Soeharto. Dua kelompok inilah yang nantinya kebanyakan
saling berebut kuasa di arena politik lokal sewaktu pilkada langsung
diimplementasikan. Dan saat reformasi memberikan nuansa baru dengan harapan
adanya kemajuan daerah yang lebih konstruktif, lagi-lagi yang hadir malah
reduksi dari nilai tersebut. Daerah malah lahir dengan raja-raja kecil di dalamnya.
Mereka mulai membangun model dinasti politik yang hampir mirip dengan apa
yang telah dilakukan oleh Soeharto dulu. Transisi orba ke reformasi nyatanya
tidak serta merta membawa dampak perubahan ke daerah-daerah, malah zaman
reformasi seolah-olah merupakan pembabakan baru neo-Soehartois. Karena
sebagian penduduk masyarakat yang tergambarkan sebagai “orang kuat” di
kedaerahan masih banyak yang mengutamakan ego nepotistik dibandingkan
semangat kebersamaan untuk pembangunan.34
Selain tulisan Leo Agustino dan Mohammad Agus Yusof (2012) soal:
Daripada Orde Baru Ke Orde Reformasi: Politik Lokal Di Indonesia Pasca Orde
Baru. Ada juga hasil analisa Wasisto Raharjo Djati yang penulis jadikan rujukan
20
tinjauan pustaka. Tulisan tersebut diterbitkan oleh jurnal sosiologi masyarakat,
Pusat Kajian Sosiologi (Labsosio FISIP-UI), dengan judul Revivalisme Kekuatan
Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal. Dalam tulisan
tersebut, Wasisto melihat pembentukan dinasti politik dari sudut pandang berbeda
pada umumnya. Jika kebanyakan ilmuwan melihat Dinasti Politik sebagai akibat
adanya campur tangan “elit yang membajak demokrasi,” Wasisto lebih
melihatnya dari proses internal familisme. Bahwa adanya elit kuat lokal hanyalah
merupakan bagian dari faktor eksternal pembentukan dinasti politik saja, tetapi di
sisi lain ada juga faktor internal yang melatarbelakanginya yakni bagaimana
keluarga saling memberikan pengaruh terhadap preferensi pembentukan “dinasti
politik”.
Dalam penelitiannya, disebutkan ada 3 unsur utama mengapa akhirnya
Dinasti Politik lahir. Pertama, karena kegagalan partai lokal melakukan
regenerasi politik. Kedua, biaya demokrasi partisipasi yang tinggi. Ketiga, adanya
kekuatan antar elit yang tidak seimbang.35 Dari ketiga unsur tersebut, Wasisto
melihat bahwa perumusan terbentuknya dinasti politik tidak hanya dapat
dilakukan melalui pendekatan Neopatrimornialisme sebagaimana Haris (2007)
dan Zuhro (2010), serta pendekatan Klan Politik sebagaimana Kreuzer (2005) dan
Cesar (2013), dan pendekatan Poltik Predator sebagaimana Asako (2010) dan Mc
Coy (1994) yang bertumpu pada tesis Migdal (1988) dan Sidel (2005), tetapi lebih
dari itu juga dapat dilihat dari perspektif familisme.36
35 Wasisto Raharjo Djati, “Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti
Politik di Aras Lokal,” Jurnal Sosiologi Masyarakat, Vol 18 No. 2 (Juli 2013: 203-231): h. 203.
21
Perspektif familisme sebagaimana yang dikutip langsung dari penelitian
Wasisto memberikan gambaran semacam ini:
“Pertama, analisis dinasti politik tidak boleh terpaku pada hubungan patronase keluarga secara umum, tetapi lebih terspesialisasikan menurut preferensi politik keluarga yang terbagi dalam tiga hal, yakni familisme, quasifamilisme, dan ego familisme. Kedua, pembentukan dinasti politik dipahami dalam dua nalar besar yakni by design yang mengarah achieved status atau by design yang mengarah pada by accident. Kedua nalar itu penting untuk membantu kita agar tidak terjebak pada pemikiran elit. Ketiga, sumber dinasti politik tidak hanya relasi keluarga intim atau demokrasi pasutri yang selama ini selalu menjadi diskursus dominan, namun terdapat empat aspek, seperti tribalisme, feodalisme, jaringan maupun populisme.”37
Dari pembacaan penulis terhadap analisis penelitian Wasisto, setidaknya dia
hendak mengemukakan bahwa pembentukan dinasti politik tidak hanya dapat
dilihat dari perspektif elit yang sudah menjadi semacam kaca mata umum bagi
para ilmuwan politik. Padahal melalui pendekatan familisme kita akan
mengetahui bagaimana proses pembentukan dinasti politik itu terjadi. Familisme
sendiri tidak terdeterminasi pada dorongan keluarga untuk membentuk atau tidak
membentuk kekuasaan secara dinasti, tetapi juga dilihatnya berdasarkan pada
dukungan dan dorongan dari masyarakat.38
Dengan penelitian yang sudah ada, seperti Leo Agustino dan Mohammad
Agus Yusof serta Wasisto Raharjo Djati, yang telah mengupas tuntas apa saja
faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya dinasti politik serta karakteristik
lingkungan sosio politiknya. Sekalipun penelitian di atas tidak terkait dengan tema
besar dominasi dan dinasti politik di Bangkalan, setidaknya penulis sudah
mendapatkan gambaran umum tentang bagaimana perkembangan dinamika
dinasti politik dari tahun ke tahun, baik itu sebelum era reformasi maupun
22
setelahnya. Ditambah referensi dari kedua tulisan tersebut setidaknya telah
memberikan masukan berarti bagi penggunaan teori serta pendekatan metodologi
sebagai “pisau analisis” pada tema yang akan penulis angkat. Karena penulis
sendiri sadari, bahwa topik dinasti politik di Bangkalan masih baru, sehingga
memerlukan literatur pendukung dari penelitian sejenis.
F. Metodelogi Penelitian
Metode yang akan digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian
kualitatif. Penelitian kualitatif sendiri merupakan sebuah metodelogi penelitian
dengan ketajaman dan kedalaman peneliti atas konteks dan fenomena objek
penelitian. Bahwa objek penelitian memiliki makna yang mesti dipahami secara
mendalam, karena sifatnya interpretatif, maka peneliti mesti memahami dan
mendalami makna dari beragam pemahaman yang berbeda-beda tersebut.39
Penelitian yang akan dilakukan merupakan kajian secara mendalam mengenai
impak lahirnya dominasi Fuad Amin pada pembentukan dinasti politik. Mengapa
dinasti politik muncul, dan bagaimana ia muncul, merupakan dua pertanyaan
utama yang harus peneliti jawab. Selain itu, peneliti pun hendak mengkaji ulang
apakah betul bahwa praktek intimidatif di lingkungan pemerintahan lokal masih
berlangsung sehingga mobilisasi massa sangat mungkin dilakukan. Atau apakah
legitimasi masyarakat pada pemerintahan dinasti bukan bersumber dari praktik
intimidatif yang sebetulnya sudah terlalu kuno dipraktikkan, melainkan berasal
dari budaya irasionalitas yang masih mengungkungi kesadaran masyarakat. Untuk
itu, peneliti mesti menganalisa pola struktural masyarakat, baik itu dari
23
peninggalan-peninggalan sejarah berupa karya tekstual, dokumen resmi, maupun
interaksi langsung dengan para ahli sejarah dan masyarakat Bangkalan.
G. Teknik Pengumpulan Data 1. Wawancara
Wawancara dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai
prosesi tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan
atau pendapatnya mengenai suatu hal.40Karenanya, tekhnik wawancara ini sangat
berguna untuk megelaborasi data serta pemantapan konteks mengenai wacana
yang akan didiskusikan. Oleh karenanya, proses wawancara atas kasus yang
hendak digarap akan dipusatkan terhadap beberapa nara sumber yang diantaranya
adalah para keluarga Bani Kholil, Madura Corruption Watch (MCW), masyarakat
dan pihak-pihak terkait.
2. Studi/Telaah Dokumentasi
Yang peneliti maksud dengan studi/telaah dokumentasi adalah pencarian
literatur yang berkaitan erat dengan topik penelitian. Studi/telaah dokumentasi
tersebut dapat berupa: artikel, jurnal, buku, catatan sejarah, koran, majalah, blog,
dll.41
H. Sistematika Penulisan
Untuk mendapatkan hasil penelitian yang komperehensif dan saling
berkorelasi antara bab yang satu dengan bab lainnya, maka penulis merunut topik
penelitian masing-masing ke dalam 5 bab. Bab pertama menerangkan latar
belakang penelitian, mengapa topik dominasi dan dinasti politik pada ranah
24
politik lokal dianggap muhim sehingga dipilih menjadi tema yang akan diteliti.
Bab kedua menjelaskan teori yang secara khusus digunakan sebagai pisau analisis
membedah tema yang diteliti, yang dalam hal ini penulis akan memaparkan apa
itu local strongmen dan apa itu bosisme dan apa itu oligarki, dan bagaimana
ketiga teori ini kompatibel untuk menerangkan munculnya dominasi dan dinasti
politik. Bab ketiga merupakan deskripsi wilayah yang hendak diteliti. Dalam bab
ini penulis menggambarkan bagaimana Bangkalan secara kultural, politik,
ekonomi dan agama. Selanjutnya adalah bab keempat, pada bagian ini penulis
menganalisa fenomena munculnya dominasi dan dinasti politik Fuad Amin di
Bangkalan melalui kaca mata teori yang sudah disediakan tadi. Apakah teori-teori
tersebut masih relevan untuk menjelaskan kedua fenomena itu atau tidak. Dan
kelima adalah penarikan kesimpulan dari hasil penelitian. Kesimpulan ini
membicarakan uraian singkat dari penyebab munculnya dominasi dan dinasti di
25 BAB II
KERANGKA TEORI
A. Teori Local Strongmen/Orang Kuat Lokal
Perubahan sosial politik yang terjadi dan merubah warna masyarakat dunia
pada saat ini, dinilai sebagai dampak pergerakan negara-negara di dunia dan
masyarakat di masa lalu. Atau dalam terminologi Marx, dikenal dengan diskursus
materialisme histroris1. Di mana globalisasi, kolonialisasi, dan industrialisasi
melahirkan pengaruhnya yang begitu primer. Huntington menjelaskan, bahwa
perubahan yang terjadi atas negara dan masyarakat di dunia hingga memunculkan
dualisme potret antara negara kuat dan negara lemah bukanlah disebabkan karena
macam-macam jenis pemerintahan yang dianut, tetapi lebih pada efektifitas
kinerja sebuah pemerintahan itu berjalan.2
Negara, dalam masa tertentu, pernah menjadi simbol tunggal dalam
dinamika kehidupan masyarakat karena kapabilitas dan koersinya yang begitu
besar. Segala garis kebijakan tersentralisasi pada wujud negara sebagai
satu-satunya pemilik kekuatan otonom. Negara menjadi pusat kuasa yang tak
terbendung. Pengalaman ini dapat kita lihat semasa perang dunia I, II, perang
dingin, di masa kolonialisme global, dan sewaktu gelombang industrialisasi
mendera dunia modern. Sedangkan pasca itu, semua kritik, peran sentral dan
1 Materialisme Historis merupakan sebuah konsep dari filsafat Karl Marx yang berarti seluruh
peradaban manusia berasal dari kontinuum sejarah yang tak putus-putus. Pip Jone, Pengantar
Teori-Teori Sosial (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), h. 78.
26
pengaruh negara lamat-lamat ditinggalkan oleh para pengkaji/ilmuwan
sosial-politik.3
Pasca kolonialisasi berakhir, kita pun disuguhkan dengan
fenomena-fenomena baru daripada dasawarsa sebelumnya, yakni munculnya beberapa
negara lemah, yang gagal menancapkan pengaruhnya di masyarakat, kesulitan
melakukan kontrol terhadap warganya, dan bersusah payah memaksakan aturan
konstitusi di wilayah teritorial mereka. Negara tidak dapat melakukan berbagai
inisiasi kebijakan di dalam perkembangan kehidupan sosial masyarakat
sebagaimana umumnya. Pada kasus ini, Joel S. Migdal mencoba menjelaskannya
dengan membawa kita pada pemahaman bahwa negara adalah bagian yang
terintegrasi dengan masyarakat. Sifat yang dimiliki negara tidak terlepas dari basis
sifat masyarakat di dalamnya.4 Migdal mendefinisikan negara sebagai organisasi
besar yang hidup berdampingan dengan organisasi-organisasi lainnya di luar
dirinya.5 Secara lengkapnya Joel S. Migdal mengatakan:
“The state is a sprawling organization within society that coexists with many other formal and informal social organizations, from families to tribes to large industrial enterprises. What distinguishes the state, at least in the modern era, is that state officials seek predominance over those myriad other organizations. That is, they aim for the state to make the binding rules
guiding people‟s behavior or, at the very least, to authorize particular other organizations to make those rules in certain realms. By “rules” I mean the
laws, regulations, decrees, and the like that state officials indicate they are willing to enforce through the coercive means at their disposal. Rules include everything from living up to contractual commitments to driving on the right side of the road to paying alimony on time. They involve the entire
3 Ibid, h. 58.
4 GSDRC (Governance and Social Development Resource Center) , “Document
Library, Summary: Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State
Capabilities in the Third World – Summary,” artikel ini diakses pada tanggal 24 Agustus 2015 dari
27
array of property rights and any of the other countless definitions of the
boundaries delineating acceptable behavior for people.”6
“Negara adalah organisasi yang luas di dalam masyarakat yang berdampingan dengan banyak organisasi sosial formal dan informal lainnya, dari keluarga, suku, perusahaan industri besar. Yang membedakan negara, di era modern setidaknya, adalah bahwa pejabat negara mencari dominasi atas segudang organisasi lainnya. Artinya, tujuan mereka untuk negara adalah untuk membuat aturan yang mengikat yang membimbing perilaku masyarakat atau, setidaknya, untuk mengotorisasi/menguasai organisasi lain khususnya untuk membuat aturan-aturan pada aspek tertentu. Dengan "aturan" saya mengartikannya hukum, peraturan, keputusan, dan seperti pejabat negara yang menunjukan kesediaan mereka untuk menegakkan melalui pemaksaan yang mereka tetapkan. Aturan mencakup segala sesuatu dari hidup, komitmen kontrak, mengemudi di sisi kanan jalan, membayar tunjangan tepat waktu. Mereka melibatkan seluruh peranti hak milik dan salah satu definisi yang tak terhitung lainnya dari batas-batas yang menggambarkan perilaku yang dapat diterima oleh orang-orang.” (Terjemahan dari penulis)
Eksistensi organisasi-organisasi di luar negara pada akhirnya menimbulkan
berbagai persoalan yang dapat mengurangi kapabilitas negara sebagai
satu-satunya alat pengontrol yang sah. Etnisitas, klan, bahkan kelompok-kelompok
macam sekte agama adalah macam-macam kekuatan yang bisa saja mengganggu
bahkan menghalang-halangi jalannya berbagai aturan serta rambu-rambu
pembangunan yang telah ditetapkan oleh negara. Hal seperti ini banyak kita
temukan pada kasus dan pengalaman negara-negara di dunia ketiga.
Di negara-negara yang baru merdeka, modernisasi aturan hukum bisa jadi
masih sering bertolak belakang dengan aturan-aturan tradisional yang secara
kultur masih kuat tertanam dalam kehidupan masyarakat. Hal ini diperparah lagi
dengan kompetisi antar kelompok kepentingan di antara mereka – untuk
mengambil alih kekuasaan yang diwariskan pasca bangsa penjajah hengkang.7
Maka akan terlihat maklum bila kondisi negara di dunia ketiga terbilang lemah.
28
Sebab infrastruktur negara, baik yang berupa sumber daya manusia maupun
fundamentalisme hukum, masih berada dalam tahap perkembangan. Sehingga
kontrol sosial sangat sulit diimplementasikan. Beda halnya pada kasus
negara-negara di eropa misalnya, di mana tentara, sistem peradilan hukum, dan
mekanisme penarikan pajak terorganisir secara baik, dan telah menjadi instrumen
pokok dalam wacana strategi dominasi kontrol negara terhadap masyarakat.8
Sedang pada kasus negara-negara baru di dunia ketiga, ikhwal itu belum tercipta
secara sempurna.
Beragam teori yang ada, seperti teori modernisasi, teori marxis, dan teori
ketergantungan, menurut Migdal, tidak mampu menjelaskan apa-apa terhadap
ketidakmampuan negara itu dalam mencapai legitimasi kontrol sosial mereka di
masyarakat. Teori modernisasi terlalu mengenyampingkan konflik yang lahir
dalam tubuh negara, teori marxis seringkali menjurus dan terlalu fokus pada
konflik antar kelas, dan teori ketergantungan, banyak mengabaikan peran
masyarakat. Ketiganya memiliki kelemahan saat dihadapkan pada pertanyaan:
mengapa negara A kuat sedang negara B lemah.9
Untuk itu, Migdal menyodorkan apa yang ia namakan dengan pendekatan
state in society, “yang menggambarkan masyarakat sebagai arena jejaring
organisasi-organisasi sosial daripada sebagai pendikotomian struktur.”10
“The model I am suggesting, what I call state-in-society, depicts society as a mélange of social organizations rather than a dichotomous structure.
8 GSDRC (Governance and Social Development Resource Center), “Document
Library, Summary: Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State
Capabilities in the Third World –Summary,” artikel ini diakses pada tanggal 24 Agustus 2015 dari
http://www.gsdrc.org/go/display&type=Document&id=3554 9 Joel S. Migdal, State in Society, h. 65.
29
Various formations, including the idea of the state as well as many others (which may or may not include parts of the state) singly or in tandem offer individuals strategies of personal survival and, for some, strategies of upward mobility. Individual choice among strategies is based on the material incentives and coercion organizations can bring to bear and on the
organizations‟ use of symbols and values concerning how social life should be ordered. These symbols and values either reinforce the forms of social control in the society or propose new forms of social life. Indeed, this struggle is ongoing in every society. Societies are not static formations but are constantly becoming as a result of these struggles over social control.”11
“Model yang saya sarankan, apa yang saya sebut state-in-society, yang menggambarkan masyarakat sebagai campuran berbagai macam organisasi sosial daripada sekedar struktur dikotomis. Berbagai formasi, termasuk gagasan negara serta banyak lagi yang lainnya (yang mungkin atau yang tidak mungkin termasuk bagian dari negara) secara tunggal atau tandem menawarkan individu-individu strategi bertahan hidup bagi pribadi dan, untuk beberapa, strategi mobilitas ke atas. Pilihan individu di antara beberapa strategi didasarkan pada insentif material dan lembaga paksaan yang dapat membawa, menanggung dan atas penggunaan simbol dan nilai organisasi tentang bagaimana kehidupan sosial harus diwujudkan. Simbol dan nilai-nilai ini baik yang memperkuat bentuk kontrol sosial dalam masyarakat atau yang mengusulkan bentuk-bentuk baru dari kehidupan sosial. Memang, perjuangan ini sedang berlangsung di setiap masyarakat. Masyarakat bukan merupakan bentuk statis tetapi terus menerus mecari bentuk dari hasil lewat perjuangan kontrol sosial ini.” (Terjemahan dari penulis)
“To be sure, in some instances, the idea-state may make and enforce many rules in the society or may choose to delegate some of that authority to other mechanisms, such as the church or market. There are other societies, however, where social organizations actively vie with one another in offering strategies and in proposing different rules of the game. Here, the mélange of social organizations is marked by an environment of conflict, an active struggle for social control of the population. The state is part of the environment of conflict in which its own parts struggle with one another. The battles may be with families over the rules of education and socialization; they may be with ethnic groups over territoriality; they may be with religious
organizations over daily habits.”12
“Yang pasti, dalam beberapa kasus, gagasan-negara dapat membuat dan menegakkan banyak aturan dalam masyarakat atau mungkin memilih mendelegasikan beberapa kewenangan ke mekanisme yang lain, seperti gereja atau pasar. Masih ada masyarakat lainnya, yang bagaimanapun, di mana organisasi-organisasi sosial secara aktif bersaing satu sama lain dalam menawarkan strategi dan mengusulkan aturan main yang berbeda. Di sini, campuran dari berbagai macam organisasi sosial ditandai oleh lingkungan
30
konflik, perjuangan aktif bagi kontrol sosial penduduk. Negara adalah bagian dari lingkungan konflik di mana negara merupakan bagian tersendiri yang juga berjuang dengan yang lainnya. Pertempuran mungkin saja terjadi dengan keluarga mengenai aturan pendidikan dan sosialisasi; mungkin dengan kelompok etnis mengenai kewilayahan; mungkin dengan organisasi keagamaan mengenai kebiasaan sehari-hari.” (Terjemahan dari penulis)
Dari paparan Migdal itu, kita dapat mengambil sebuah kesimpulan penting, selain
gambaran soal negara sebagai wahana konflik berbagai kepentingan organisasi
sosial yang saling berebut mendapatkan pencapaian mereka terhadap kontrol sosial
di masyarakat, namun juga soal kemunculan negara lemah (weak state) sebagai
impak kekalahan negara oleh kekuatan-kekuatan informal di luar institusi resmi.
Setidaknya, konsep Migdal mengenai negara lemah telah merejuvinasi kembali
asumsi-asumsi Weber yang terlalu idealistik dalam mendefinisikan negara sebagai
satu-satunya asosiasi politik dengan berbagai kekayaan haknya untuk memonopoli
kekerasan yang terjadi di lingkungan masyarakat.13
“Migdal percaya bahwa negara bukanlah satu-satunya organisasi yang hidup berdampingan dengan masyarakat. Di luar negara, bahkan lebih banyak lagi dari macam-macam organisasi yang ada, yang juga mencoba untuk memberikan dan menanamkan dominasi serta pengaruhnya seperti yang dilakukan oleh negara. Cara mereka melakukan itu semua, selain dengan memberikan insentif berupa bantuan dan keamanan, juga dengan memberikan sanksi sosial kepada siapa saja yang tidak mematuhinya. Sanksi sosial ini dapat berupa adanya tindakan kekerasan dan pengucilan. Dengan banyaknya organisasi yang menjamur di luar negara, maka masyarakat dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit untuk memilih satu di antara mereka, mana saja yang benar-benar memanifestasikan diri sebagai kelompok yang mampu menstimulus konstruksi „strategi bertahan hidup‟ bagi mereka. Masyarakat, dalam hal ini, bukan berarti hidup dalam kebebasan tanpa adanya aturan yang mengikat dan mengatur mereka, tapi faktanya mereka tetap hidup dalam aturan aturan, tetapi dalam alokasi yang tidak terpusat. Karena berbagai sistem aturan dan peradilan mengatur mereka dalam waktu dan secara bersamaan. Berhasil tidaknya sebuah organisasi untuk melakukan kontrol sosial terhadap anggotanya tidak saja
13Daniel Lambach, “State in Society: Joel Migdal and the limit of state authority.” Paper for
31
terlihat saat mereka mematuhi segala aspek dan aturan yang berlaku di dalam organisasi tersebut, tetapi saat mereka juga meyakini dan sadar bahwa nilai legitimasi yang mereka berikan adalah baik dan benar.”14
Harus digarisbawahi, bahwa kontrol sosial, dominasi, dan hegemoni merupakan
alat politik paling ampuh yang mesti dimiliki negara dalam rangka mengatur,
mengarahkan, memaksakan dan membatasi segala tindakan yang dilakukan oleh
masyarakat. Tanpa memegang kendali dominasi dan kontrol atas masyarakat,
negara akan menjadi lemah, dan masyarakat akan berpaling untuk mengikuti
aturan dan arahan yang berasal dari organisasi informal di luar negara. Sehingga
perebutan kontrol sosial di masyarakat mutlak menjadi penting sebab upaya
mobilisasi masyarakat hanya akan terjadi apabila tiga komponen ini terpenuhi:
partisipasi, kepatuhan, dan legitimasi.15 Kontrol sosial sendiri singkatnya diartikan
sebagai:
“The state‟s capacity to mobilise society rests on social control, defined as
the ability to make the operative rules of the game for people in society. The major struggles in many societies are over who has the right and ability to make the rules that guide people‟s social behaviour (the state or other
organisations).”16
“Kapasitas negara untuk memobilisasi masyarakat bertumpu pada kontrol sosial, yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk membuat aturan operasi dari aturan main untuk orang-orang dalam masyarakat. Perjuangan utama di banyak masyarakat adalah lebih kepada siapa yang benar dan mampu membuat aturan yang membimbing perilaku masyarakat sosial (negara atau organisasi lain).” (Terjemahan dari penulis)
14 Hasil terjemahan penulis dalam bagian tertentu pada artikel yang ditulis oleh Daniel Lambach, “State in Society: Joel Migdal and the limit of state authority.” Paper for presentation at the conference “Political Concepts Beyond the Nation State: Cosmopolitanism, territoriality, democracy”, Danish Political Theory Network Conference, University of Copenhagen, Department of Political Science Copenhagen, 27-30 October 2004.
15 GSDRC (Governance and Social Development Resource Center), “Document
Library, Summary: Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State
Capabilities in the Third World –Summary,” artikel ini diakses pada tanggal 24 Agustus 2015 dari
http://www.gsdrc.org/go/display&type=Document&id=3554
16 GSDRC (Governance and Social Development Resource Center), “Document
Library, Summary: Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State
Capabilities in the Third World –Summary,” artikel ini diakses pada tanggal 24 Agustus 2015 dari