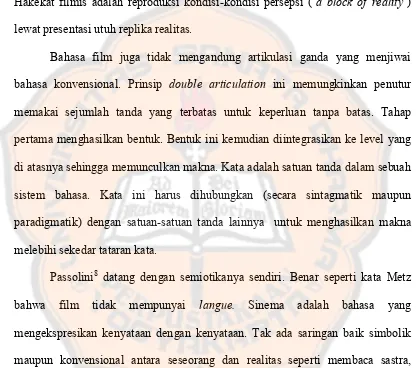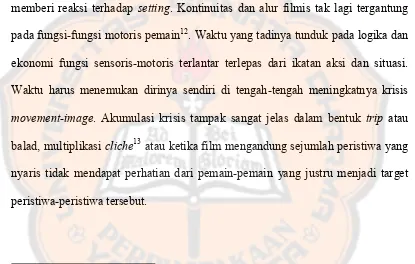ANAK-ANAK TIRI IBU PERTIWI:
RUANG WAKTU GARINIAN DAN MOLEKULARITAS PENGALAMAN DALAM PUISI TAK TERKUBURKAN
Tesis
Untuk Memenuhi Persyaratan Mendapat Gelar Magister Humaniora (M.Hum.) di Program Magister Ilmu Religi dan Budaya, Universitas Sanata Dharma
Yogayakarta
RUDY RONALD SIANTURI
Nomor Mahasiswa : 026322010
Magister Ilmu Religi dan Budaya
Universitas Sanata Dharma
i
ANAK-ANAK TIRI IBU PERTIWI:
RUANG WAKTU GARINIAN DAN MOLEKULARITAS PENGALAMAN
DALAM PUISI TAK TERKUBURKAN
Tesis
Untuk Memenuhi Persyaratan Mendapat Gelar Magister Humaniora (M.Hum.)
di Program Magister Ilmu Religi dan Budaya, Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
RUDY RONALD SIANTURI
Nomor Mahasiswa : 026322010
Magister Ilmu Religi dan Budaya
Universitas Sanata Dharma
ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Ujian Tesis
ANAK-ANAK TIRI IBU PERTIWI:
RUANG WAKTU GARINIAN DAN MOLEKULARITAS PENGALAMAN
DALAM PUISI TAK TERKUBURKAN
Oleh:
RUDY RONALD SIANTURI
NIM: 026322010
Dr. St. Sunardi
………
Pembimbing Utama
7 Oktober 2006
Dr. Antonius Sudiarja
………
iii
LEMBAR PENGESAHAN
Tesis
ANAK-ANAK TIRI IBU PERTIWI:
RUANG WAKTU GARINIAN DAN MOLEKULARITAS PENGALAMAN
DALAM PUISI TAK TERKUBURKAN
Oleh:
RUDY RONALD SIANTURI
NIM: 026322010
Telah dipetahankan di depan dewan penguji pada tanggal 14 Oktober
2006 dan dinyatakan memenuhi syarat
Tim Penguji
Ketua merangkap Moderator:
Dr. G. Budi Subanar, S.J. ………..
Anggota
: 1. Dr. St. Sunardi
………
.
2. Prof. Dr. A. Sudiarja
, S.J. ………..
3. Dr. Alb. Budi Susanto, S.J. ……….
Yogyakarta, 4 Oktober 2011
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Sanata Dharma
iv
Pernyataan
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tulisan ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk meraih gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan orang lain kecuali yang diacu secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Yogyakarta, 14 Oktober 2006
v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:
Nama : RUDY RONALD SIANTURI
Nomor Mahasiswa : 026322010
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul:
ANAK-ANAK TIRI IBU PERTIWI:
RUANG WAKTU GARINIAN DAN MOLEKULARITAS PENGALAMAN DALAM PUISI TAK TERKUBURKAN
Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalty kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.
Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.
Dibuat di Yogyakarta
Pada tanggal : 1 September 2008 Yang menyatakan,
vi
A DAWN
I woke up quite early at dawn. Through the window, I realized that the rain was still pouring down. Silently, I got off not to make any sound while out there a dog was barking ceaselessly. It was chilling out there.
Drinking some water, I felt so much better. The dog was still barking when someone’s cock flapping its wings so loudly. Where he hid it, I wondered. I have never seen any down there.
A memory came back. Several years ago, I loved reading John Steinbeck’s novels. My
friend introduced him to me. I t is always like this. Wailing dogs, cocks and hens fighting over corns, the farmers starting their day with whistle while horses kicking in the barn. Simple things, a simple life matrix that led him to Nobel Prize in literature.
I got out of our unit to listen to another kind of sound. It was like somebody was singing in the alley. The wind blowing was entrapped in the corridor creating mysterious sounds like Indian songs at night. Even Pavarotti would not be able to produce such a beautiful harmony.
I went up to the top of the building to have some exercise. In the swimming pool, falling leaves were being pushed gently by the ripples. The water was crystal, the breeze was refreshing. It was like a triangular love: the breeze, the leaves, and the water.
I stayed there for an hour watching the sun emerging slowly from the east. I enjoyed it until the first birds came out from nowhere.
Coming back, I looked at my wife sleeping peacefully. Her chest signaled the beat, the beats of life, a scene so simple so alive: a dawn.
vii
Ucapan Terima Kasih
Penelitian ini tidak akan selesai tanpa dukungan, dorongan dan doa-restu
banyak pihak. Dalam kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikannya
sebagai berikut:
1. Sujud syukur bagi Tuhan yang berkenan bergulat dalam arena tarung
batin bersama penulis yang sedang mencari dirinya secara terus-menerus.
Ada begitu banyak pengalaman intelektual, emosional terlebih spiritual
yang penulis petik selama ini. Penelitian ini menjadi latihan rohani
bersama sang Guru yang menjelaskan begitu banyak hal yang saling
terkait secara indah.
2. Terima kasih untuk Bapak Dr. St. Sunardi yang berperan sangat besar
dalam proses formasi intelektual penulis. Selama proses pembimbingan,
penulis sungguh merasakan dedikasi yang mendalam terhadap profesi dan
panggilan hidupnya sebagai pendidik dan scholar sekaligus. Bukan cuma ilmu yang penulis dapatkan namun ilmu kehidupan yang memancar dalam
kesehariannya, dalam kesederhanaannya dan dalam kedalaman ilmunya
yang mencengangkan. Terima kasih pula untuk Rm. Dr. Agustinus
Sudiarja S.J dan Rm. Dr. Budi Susanto S.J yang berkenan menjadi
pembaca ke-2 dan ke-3. Beliau berdua adalah dosen-dosen penulis yang
punya peran besar langsung atau tidak langsung dalam proses formasi
intelektual penulis.
3. Khususnya untuk Rm. Dr. G. Budi Subanar S.J dan Rm. Dr. T. Baskara
S.J yang sangat membantu penulis ketika penulis masih berada di Manila.
Terima kasih untuk keramahtamaan dan pengertiannya yang sangat luar
biasa bagi siapa saja. Kiranya Tuhan memberkati perjalanan panggilan
Romo berdua.
4. Untuk Rm. Dr. T. Baskara S.J, Rm. G. Budi Subanar S.J, Rm. Dr. Harry
Susanto S.J, Rm. Dr. Harriatmoko S.J, Rm. Dr. Budi Susanto S.J, Rm. Dr.
viii
Budiawan, Dr. Fransisko, Prof. Dr. Mahasin dan semua dosen lainnya),
terima kasih untuk setiap sentuhan dan pengaruh intelektual selama
penulis belajar di IRB. Penulis beruntung boleh mempunyai orang-orang
yang santai namun sangat mendalam ilmu dan daya analisanya dan tak
pernah ragu membagikannya dalam diskusi, dalam canda dan dalam setiap
perjumpaan.
5. Untuk teman-teman IRB yang secara luar biasa mewarnai secara
mendalam kehidupan penulis dengan canda-candanya yang luar biasa.
Terima kasih kalian telah banyak bertanya, mempertanyakan dan
menjawab banyak soal pada serta dengan penulis yang sangat merangsang
rasa ingin tahu penulis secara terus-menerus. Takkan kulupakan
wajah-wajah kalian dan kuyakin kalian pun demikian. Untuk Fitri, Rudy Ambon,
Pak Viktor, Mas Ali, Muklis, Singgih, Meli, Kemal, Wahid, Siska,
Samuel, Melati, Iyus, Tina dan semuanya saja ‘you are the best!’.
6. Tentu saja, tak lupa teman-teman KBI yang beberapa di antaranya
menunjukkan perhatian tulus terhadap penelitian penulis. Kiranya Tuhan
saja yang membalaskan jasa kalian.
7. Untuk teman-teman sesama peneliti Nusakambangan (Mas Ali, Iyus
Brekele dan Sri), terima kasih untuk kesempatan bersama dalam
susah-senang. Sungguh indah pengalaman bersama kalian semua. Sungguh
beruntung penulis mendapat kesempatan mencicipi bagaimana rasanya
menjadi peneliti yang melakukan penelitian di lapangan.
8. Terima kasih untuk Mbak Hengki yang selalu siap-sedia membantu
penulis menyelesaikan berbagai urusan dengan seyum manisnya dan
sikapnya yang sangat ramah. Kiranya Chelsea menjadi anak yang
membawa berkat bagi kedua orangtuanya.
9. Untuk para sahabat baru di Manila (Prof. Cirilo, Prof. Marjoire, Prof.
Antony, Prof. May-an, Prof. David, Prof. Nerissa), terima kasih untuk
setiap undangan diskusinya, untuk seyum sejuta kasihnya dan untuk setiap
rasa ketertarikannya pada penelitian penulis. Untuk Ate Tres, terima kasih
ix
menemukan buku-buku yang tidak sempat penulis bawa ke Manila.
Sungguh, semua itu sangat memotivasi penulis dalam proses penyelesaian
penulisan tesis ini.
10.Untuk teman-teman di geng Yahoo!360, terima kasih untuk cerita-cerita
dan sharing kalian. Sungguh semua itu mengisi hari-hari penulis secara bermakna. Untuk Susan, Debbie, Turtle, Evi, Avi, Tris, Kellianah, Peach,
Agent Q., I miss you all!
11.Terima kasih juga untuk Bayu adikku yang dengan ketulusan dan
kecerdasannya membantu penulis untuk optimis dan belajar selalu
bersedekah. Kiranya puasa kamu diterima Tuhan.
12.Untuk Herlin Untailawal, teman SMP penulis, dan Tila, terima kasih untuk
doa-doanya dan pelajaran rohaninya yang sangat mendalam.
13.Abang Lisa, Abang Sisco, Mama Kris, Mama Pemri, Mama Vita dan yang
terkasih adikku Rian, terima kasih setulusnya karena kalian selalu percaya
dengan saudaramu ini. Kalian adalah malaikat-malaikatku yang dikirim
Tuhan untuk mengingatkan dan membantu dengan setiap sms dan telepon
kalian. Mama Kris, terima kasih untuk begitu banyak bantuannya. Lae
Pemri dan Mama Pemri, terima kasih untuk pendampingan kalian yang
sungguh membuka pikiranku.
14.Untuk kalian keponakan-keponakanku, terima kasih untuk canda dan
setiap pertanyaan yang sangat mengusik kalbu dan otakku. Aku akan
selalu merindukan kalian dan dalam doa-doaku, wajah-wajah kalian selalu
muncul secara spontan.
15.Untuk para ipar di Manila dan di mana-mana, penulis haturkan terima
kasih mendalam untuk cinta kalian yang tak terukur dengan apapun.
Manang Nica, Sister Flora dan Sister Gloria, George, David, Larry dan
Eddy, terima kasih untuk setiap traktiran makannya, untuk setiap
ketertarikan pada proses penulisan tesis ini dan untuk setiap dorongan
tanpa batas yang telah kalian berikan. Penulis juga tidak akan melupakan
mertua penulis, Tatay, yang dalam sakitnya terus bercanda dan menyapa
x
Sisco,Inangbao Anik, terima kasih untuk setiap doa-restunya. Khusus
untuk Lae Vita dan Mama Vita, terima kasih untuk bulan-bulan indah
bersama penulis di Pangkal Pinang.
16.Terima kasih untuk Mama dan Bapa yang sudah bersabar dan selalu
percaya akan bahwa anaknya sanggup menyelesaikan satu lagi fase
perjalanannya. Mama dan Bapa selalu duduk bersama penulis meskipun
tanpa kata menemani hari-hari penuh pergulatan di depan layar komputer.
Tidak ada kata yang sanggup mengekspresikan keindahan setiap gelas
kopi yang Mama sediakan, untuk candanya setiap kali kesulitan
menghadang dan untuk setiap pertanyaan dari Mama dan Bapa mengenai
penelitian ini yang membantu menstimulasi pikiran penulis.
17. Terima kasih setulusnya untuk istri penulis yang rela ‘berpisah’ demi penyelesaian tesis ini, untuk setiap diskusi dan rangsangan intelektual
yang mengembangkan minat akademik dan daya analitik penulis secara
luar biasa. Sebagai seorang penyair dan penulis professional, sang Istri
banyak membantu penulis mendalami elemen-elemen puitis dalam Puisi Tak Terkuburkan. Tak lupa pula, terima kasih untuk setiap canda dan tawa yang boleh kami lalui di tengah-tengah setiap tantangan kehidupan
bersama.
18.Yang terakhir, terima kasih setulusnya untuk Yoshua, keponakan penulis,
yang selalu menyambut penulis dengan cerita dan pelukan kasihnya yang
membuat penulis selalu merasa dicintai dengan tulus.
Penulis telah belajar mencurahkan energi minat untuk mampu
menyelesaikan keseluruhan proses pendidikan formal ini. Tentu saja, studi ini
masih jauh dari sempurna dan untuk setiap kekurangannya menjadi
xi
Daftar Isi
Judul i
Halaman Persetujuan Pembimbing ii
Halaman Pengesahan iii
Pernyataan iv
Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah v
Halaman Persembahan vi
Ucapan Terima Kasih vii
Daftar Isi xi
Abstrak xiv
Abstract xv
Bab I Pendahuluan
A. Latar Belakang yang Melahirkan Sebuah Topik ... 1
1. Mengapa Sinema dan Filsafat? ... 2
2. Mengapa Film Puisi Tak Terkuburkan? ... 5
B. Status Questionis ... 10
C. Tujuan Penelitian ... 11
D. Metodologi ... 11
E. Relevansi Penelitian ... 12
F. Skema Penulisan ... 12
Bab II Film Sebagai Diskursus: Dari Saussure Menuju Semiotika Bahasa Film Hingga Deleuzian Time-Image 15 A. Produksi Makna Saussurian ... 18
B. Semiotika Film: Saussurian atau anti Saussurian ... 21
C. Gilles Deleuze: Dari Action-Image ke Time-Image ... 28
C.1 Durasi Bergsonian ... 28
C.2 Akumulasi Krisis dan Patahnya Proses Identifikasi ... 33
xii
C.2.3 Munculnya Pikiran dan Time-Image ... 37
C.3 Gerakan Ganda Cipta dan Hapus ... 40
C.3.2 Sinema adalah Pengetahuan, Aktor adalah Medium ... 41
C.4 Beberapa Kategori Deleuzian Lainnya ... 43
Bab III Menguak Bahasa Film Garin Nugroho 47 A. Kontradiksi, Fragmen Visualisasi dan Dialog Internal ... 51
1. Trauma: Fiksasi Ruang-Waktu dan Pergolakan Perseptual ... 51
2. Perbedaan Reaksi Para Tahanan Perempuan dan Laki-Laki... 56
3. Pengalaman akan Waktu: Garinian Time-Image? ... 62
B. Garinian Images: Pergeseran dari Movement-Image ke Time-Image... 66
1. Sudut Pandang Kamera dan Kontinuitas Temporal ... 66
2. Dialog Internal dan Konseptualisasi Ruang-Waktu Garinian ... 69
C. Musik dan Syair ... 72
Bab IV Membongkar Garinian Time-Image: Menuju Estetika Baru dan Originalitas Pikiran 73 A. Ruang Garinian ... 75
1. Ruang dan Kematian: Sebuah Distorsi ... 76
2. Diskontinuitas dan Ekstensivikasi Ruang: Intensivikasi Emosional ... 80
B. Waktu Garinian ... 84
1. Reduksi dan Paradoks Waktu Penjara... 85
2. Ruang-Waktu Garinian: Kontras, Pembalikan dan Partisipasi Penonton ... 89
C. Suara, Bunyi dan Musik: Monotonitas Dinamis, Simultanitas dan Doppler Effect ... 95
D. Garinian Time-Image ... 100
1. Proses Menjadi: Konfrontasi dan Filmic Caesura ... 100
2. Filmic Alliteration ... 110
xiii
4. Dialog Internal, Trial and Error serta Visualisasi ... 120 5. Munculnya Pikiran: Material Capture, Machinic Assemblage
dan Rhizome ... 132
Bab V Estetika Baru dan Proses Menjadi Indonesia: Sebuah Tawaran
Garinian 143
A. Estetika Baru: Molekularitas dan Sensasi ... 147 B. Menjadi Indonesia Model Garinian ... 155 C. Menuju Praxis Filsafat Kontemporer Indonesia ... 163
Daftar Pustaka 170
Sinopsis 172
xiv
Abstrak
Anak-Anak Tiri Ibu Pertiwi: Ruang-Waktu Garinian dan Molekularitas
Pengalaman dalam Puisi Tak Terkuburkan
Film Puisi Tak Terkuburkan merupakan upaya Garin Nugroho menelusup jauh ke dalam tragedi kemanusiaan dan trauma 1965. Film ini akan dianalisa secara Deleuzian.
Penelitian ini hendak menjawab empat pertanyaan yaitu: (1) Simbolisme apa yang ada dalam film tersebut?; (2) Bagaimanakah pengalaman waktu sinematik kita?; (3) Kesadaran seperti apa yang sedang ditawarkan?; dan (4) Bagaimanakah film berfungsi dalam proses menjadi Indonesia baru?
Studi ini bergerak melalui dinamika cipta-hapus dengan melibatkan penonton dalam konteks (zone of indeterminancy). Cipta-hapus ini adalah relasi-relasi antar real-imaginer, fisikal-mental, obyektif-subyektif, deskriptif-naratif, aktual-virtual yang saling merefleksikan dan menubruk hingga pada titik tertentu tak terbedakan lagi (point of indiscernibility). Konfrontasi ini memprovokasi pikiran yang terus bercabang seiring multiplikasi transformatif affective images. Inilah jaringan sirkular antar image yang sepenuhnya optikal-suara serta antar time-image dan thought-image. Praktisnya, proses analisa akan simultan dengan pengalaman sinematik (experiential) dalam bentuk retelling.
Hasil studi menunjukkan berbagai capaian Garin khususnya filmic ceasura, filmic alliteration, Doppler effect, medan vibrasi berkombinasi dengan dialog internal serta aneka ‘mutasi’ indrawi, gestural, pola dan dimensi interaksi. Selain menciptakan tanda-tanda, Garin juga mengembangkan filsafat waktunya lewat konfrontasi antar yang mekanis, represif dan affective images dengan vibrasi pada level personal maupun kolektif. Ia bahkan mendestabilisasikan distingsi waktu dan ruang (yaitu pertukaran bentuk dan isi secara intens-frontal dalam benak pemain maupun penonton) seraya menciptakan dimensi ruang-waktu Garinian.
xv
Abstract
The Outcasts of the Motherland: Garinian Time-Space and the Molecularity of Experience in The Poem Unburied.
The Poem Unburied represents Garin Nugroho’s filmic effort to retell the 1965 tragedy. The study adapts Deleuze's approach to film analysis.
This research explores four questions: (1) What symbolism exists in the film?; (2) What kind of cinematic experience of time is being offered?; (3) What kind of consciousness is being constructed?; and (4) How does film function in the process of becoming a new Indonesia?
This study makes use of the double movement of creation and erasure. It accommodates the audience’s cinematic experience in terms of . The creation-erasure is the relations between real-imaginer, physical-mental, objective-subjective, actual-virtual which reflect and collide with each other to the point of indiscernibility. This collision provokes thought to keep splitting proportionally to the transcendent plurality of affective images. This process gives rise to the fibrous web of connections among the images which are fully optical and audio and among time-image and thought-image. Shortly, the analysis process parallels the audience’s cinematic experience in the form of retelling.
The research shows Garin’s various achievements as evidenced in the way he used devices such as filmic caesura, filmic alliteration, Doppler effect and the vibration field in combination with the many types of sensory mutation, gestures, patterns and interactions. While creating new signs, Garin also develops his own philosophy of time through the confrontational encounters between the mechanical, repressive and affective images with the vibration is on the personal and collective level. He even destabilizes time-space distinction (making it intense and frontal exchanges between form and volume in the minds of characters and audience) creating the so-called Garinian time-space
Garin offers new aesthetics by continuously producing sensation that can be experienced in the minutest level. In terms of becoming Indonesia, he offers the notion of history as the multi-dimensional growth and multiplication resulting from the dynamic confrontation with the forces of life. History is a discontinuity calling for sensory participation in a fluid manner. The past (former present) can fully be comprehended experientially, not through an intellectual-ideological analysis. Being more sensitive to the body (locus of history) as the interconnectivities of affect-percept, he enables thought to think outside the
‘official’ thinking making it well-guarded from the dangers of ideological-visual uniformity and monolithic politicized subjectivity.
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang yang Melahirkan Sebuah Topik
Hidup tanpa lingkaran refleksi dan praktik, bagaimana mungkin bisa
merespon, mengantisipasi dan mentransformasi sarat dimensi pengalaman dan
interaksi antar pengalaman secara maksimal? Pertanyaan ini bisa direspon dari
tiga bidang yang berbeda yaitu sains, estetika dan filsafat. Di sisi lain, pengalaman
mengajarkan kita bahwa operasionalitas sebuah sudut pandang seringkali
membutuhkan sumbangan-sumbangan dari wilayah disiplin lainnya secara
langsung maupun tidak langsung. Tentu saja, tetap dimungkinkan aplikasi satu
sudut pandang secara ketat untuk mengupas tuntas sebuah permasalahan yang
sudah didefinisikan secara sistematis. Akan tetapi, pada titik tertentu biasanya
mono-analisis seperti itu mengalami kejenuhan dan membuka jalan bagi
operasionalitas disiplin-disiplin lainnya. Inilah yang kita kenal sebagai lintas
disiplin yang memungkinkan sesuatu ditelaah menurut dimensi-dimensi sains,
estetis maupun filosofisnya seperti yang kerap kita temukan dalam ranah cultural
studies.
Studi ini merupakan upaya menggabungkan ketika bidang di atas dengan
tekanan kuat pada dimensi estetis dan filosofis. Salah satu produk kultural yang
paling kuat merepresentasikan ketiganya adalah film. Dengan asumsi bahwa film
secara ketat ataupun longgar mengekspresikan estetika dan filsafat sang
pembuatnya, olah film sangat potensial untuk membawa kita pada temuan-temuan
baru dalam berbagai bidang termasuk filsafat itu sendiri.
Filsafat patut mendapat perhatian khusus tanpa meremehkan estetika dan
sains tentunya. Seringkali diasosiasikan dengan tradisi Yunani yang kemudian
menjadi tradisi pemikiran dunia Kristen Barat, filsafat di Indonesia tampaknya
gejala umum yang bisa menjelaskan situasi ini adalah fakta penerapan berpikir
secara filosofis atau lintas disipliner yang cenderung apatis, terlalu linier, kurang
reflektif namun mekanistis atau sekedar melekatkan teori seperti misalnya dalam
proses kritik sastra di kalangan mahasiswa umumnya.
Lemahnya tradisi filsafat di Indonesia paling tidak menyangkut dua hal.
Pengajaran filsafat di universitas-universitas swasta selalu berada di bawah
bayang-bayang teologi tertentu. Sementara itu, di universitas-universitas negeri,
filsafat selalu menjadi subordinasi Pancasila. Tanpa institusi-institusi yang
independen, bagaimana mungkin mengharapkan dialog sistematis yang kontinu
dan menyentuh setiap level pergulatan baik secara internal maupun lintas ilmu.
Filsafat tidak berpikir dan melibati apa yang sedang dihadapi masyarakatnya.
Sebaliknya, filsafat boleh dikatakan mengalami stagnasi dan juga begitu
ilmu-ilmu sosial lainnya. Oleh karena itu, filsafat harus menemukan dirinya kembali
dan mereorientasikan daya-daya hidupnya dalam rangka memberdayakan dirinya
dan/atau ilmu-ilmu humaniora lainnya dengan membuat berbagai pilihan dan
aliansi strategis.
1. Mengapa Sinema dan Filsafat?
Pada titik kritis inilah filsafat berhadap-hadapan dengan sinema baik pada
level teori maupun proses. Sebagai salah satu produk budaya yang paling
berpengaruh, sinema adalah harmoni adonan teknologi dan estetika yang terolah
kreatif dengan organisasi naratif tertentu seturut pilihan dan pesan tematik tertentu
(kandungan sosial sinema).
Di sisi lain, di dalam dirinya sendiri, sinema adalah industri kecerdasan
sekaligus perjalanan budaya material manusia yang hakikatnya diarahkan pada
eksplorasi dan eksploitasi ruang-ruang pengalaman manusia baik dengan dirinya,
sesamanya, dunia realitas dan berbagai sarana ataupun produk kulturalnya. Inilah
pusat pergulatan estetik individual (sutradara, misalnya) maupun kolektif
(penonton, misalnya), lingkaran produksi-distribusi-konsumsi yang mengandaikan
konsumsi.1 Secara semiotik, pengalaman sinematik adalah resultansi pengalaman
dengan gerak (movement) dan waktu (time). Harmoni sinematografis justru
tercipta lewat tumpang-tindih presentasi dan pengalaman signifikasi dalam
konteks hubungan-hubungan ruang-waktu2.
Dewasa ini, level dan corak pengalaman sinematik sekali lagi mengalami
transformasi revolusioner, menapaki tataran citraan-waktu spontan (direct
time-image). Sebelumnya, meskipun objek dan setting sudah memiliki realitasnya
sendiri, realitas itu sifatnya fungsional melulu tergantung tuntutan situasi. Ruang
(space) identik dengan sebuah setting yang mengandaikan serangkaian tindakan
untuk membukanya atau untuk mengantisipasi maupun memodifikasi ruang
tersebut. Gerak atau tindakan itu secara logis menghasilkan gagasan dan
pengalaman akan waktu. Waktu tergantung pada sang protagonis yang
mengkonsumsi3 setting dan aneka objek untuk mengekspresikan makna sekaligus
tindakannya (action-image based cinema).
Kini objek dan setting mewujud dalam realitas material otonom yang
menghasilkan signifikasi dalam dirinya sendiri. Secara esensial, penonton maupun
para pemain menciptakan berbagai setting dan objek dengan tatapan (gaze)
mereka. Mereka melihat dan mendengar objek-objek dan orang-orang di dalam
film itu seraya menunggu pematangan momen untuk aksi atau hasrat (passion)
terlahir secara langsung-spontan serta berkesinambungan (a pre-existing daily
life). Logika linear dan kontinuitas berbasis gerakan (movement-based continuity)
menjadi masa lalu. Kaitan-kaitan (rational cuts) yang mengandaikan gerak sang
1
Menurut hemat penulis, terlepas dari suguhan estetis yang terkandung dalam setiap proses produksi sinematik, setiap proses konsumsi (secara aktif, pasif, skeptis, dan seterusnya) pasti menghasilkan struktur pengalaman tertentu. Hal ini dimungkinkan karena sinema tanpa henti melibatkan pencerapan sensoris dan intelektual serta berbagai lapisan struktur pengalaman individual maupun kolektif (efek audiovisual versus derajad keterbukaan seseorang atau audiens terhadap tawaran sinematik tertentu), melibatkan memori (yang sifatnya sensoris, afektif, intelektual, sosial, religius, kultural, ideologis) maupun filter sosiokultural.
2
Bagian ini yang menyangkut direct time-image adalah buah pemikiran Gilles Deleuze seperti yang ia paparkan secara menyeluruh dalam bukunya Cinema 2, The Time-Image, Hugh Tomlinson dan Robert Galeta (trans), (London: The Athlone Press, 2000).
3
pemain (shot to sequence) dibekukan hanya menyisakan melulu optikal dan suara
yang dicerap indra sebelum sebuah tindakan mengambil ekspresinya. Waktu hadir
secara spontan, dialami secara simultan dengan sebuah situasi sinematik4. Waktu
sepenuhnya independen, tak tergantung lagi pada gerakan.
Seorang filsuf mengalami bagaimana sinema sedang menstrukturasi dan
merestrukturasi masyarakat secara keseluruhan. Struktur budaya dan identitas
sosial selalu dalam proses menjadi (in the process of becoming). Hadir situasi
baru. Hadir tantangan baru untuk melakukan refleksi filosofis-sistematis dan
respon-tindakan nyata (praksis). Inilah yang kiranya dilakukan Gilles Delauze,
salah satu teoritisi film sekaligus filsuf terkemuka. Ia percaya bahwa seorang
filsuf seyogyanya bekerja seiring perkembangan sinema. Filsuf adalah penyelam
dalam dunia tanda-tanda sinematik. Aktivitas ini adalah upaya untuk
mengklasifikasikan berbagai citra dan tanda namun kemudian diurutkan kembali
untuk tujuan-tujuan baru. Daya tarik sinema yang terpenting adalah
kemampuannya mentransformasikan konstruksi-konstruksi konseptual menjadi
dimensi-dimensi baru. Konseptualisasi itu sendiri selayaknya mengintegrasikan
percept dan affect (yang tidak boleh dikacaukan dengan istilah persepsi dan
perasaan atau feeling). Ketiganya membentuk kompleks kekuatan yang tak
terpisahkan yang bergerak dari seni ke filsafat dan dari filsafat ke seni. Jelas sekali
praksis dimaksud bukanlah untuk mengaplikasikan konsep-konsep filosofis dalam
sinema melainkan bekerja dengan konsep-konsep yang ditimbulkan dalam dan
oleh sinema. Pada gilirannya dialog intens terjadi antar keduanya dan antara
filsafat dan bidang-bidang ilmu lain secara umum.
4
Situasi sinematik adalah upaya penulis untuk menterjemahkan dan mendeskripsikan setiap potong audiovisual (shot) yang di dalamnya sudah mengandung keseluruhan elemen dan dimensi
2. Mengapa Film Puisi Tak Terkuburkan?
Puisi Tak Terkuburkan merupakan upaya Garin Nugroho menelusup jauh
ke dalam trauma dan tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah Indonesia di
tahun 19655. Berawal dan berpuncak pada terbunuhnya tujuh jenderal Angkatan
Darat di sebuah tempat yang disebut Lubang Buaya, kisah setelahnya adalah
mobilisasi tanpa batas, angkara murka, balas-dendam, aniaya, orgi penggorokan
masal di berbagai titik eksekusi di tanah Jawa khususnya dan di Indonesia
umumnya. Indonesia tak pernah lagi sama sejak kemenangan mutlak ABRI
khususnya Angkatan Darat terhadap musuh-musuh Pancasila (yang praktisnya
diterjemahkan sebagai Partai Komunis Indonesia beserta organisasi-organisasi
5
Keith Foulcher mencatat bagaimana ingatan sejarah (remembered history) menjadi bagian perkembangan sastra dan pergulatan para penulis Indonesia. Ia mencatat bahwa di sepanjang 1970-an, kebanyakan produk sastra bungkam terhadap peristiwa 1965 maupun dampaknya bagi kehidupan bangsa ini pada level individual, komunitas maupun sebagai bangsa. Ia mencatat bahwa paska 1965, ada sejumlah cerita pendek yang terbit namun tujuannya untuk menggalang pengertian (understanding) ataupun membersihkan nama. Sejarah mulai muncul kembali dalam khazanah kesusastraan Indonesia di tahun 1979 tidak lewat sastra seni (art literature) namun justru dalam genre sastra pop sebagai konsekuensi praktis dari pertumbuhan kelas elit menengah perkotaan yang diwakili kelompok muda yang tidak mengalami peristiwa itu secara langsung berbeda dari generasi penulis cerita pendek di atas. Akhirnya sejarah kembali secara serius digarap dengan kemunculan Yudhistira Ardi Noegraha dalam Mencoba Tidak Menyerah (Jakarta: Gramedia, 1979) yang merepresentasikan kombinasi sastra dan dokumen sosial. Dalam
perkembangan selanjutnya, kita melihat kebangkitan sastra seni lewat para penulis „kiri‟ yang
dipenjara karenan afiliasinya dengan peristiwa 1965. Begitulah, Pramoedya Ananta Toer menggelegar dengan Bumi Manusia di tahun 1980 selain banyak penulis cemerlang lainnya. Hingga akhirnya muncul Ajip Rosidi dengan Anak Tanah Air, Secercah Kisah (Jakarta: Gramedia, 1985) yang dengan Rendra merepresentasikan kelompok penulis muda Indonesia yang
menekankan „regional identities and regional cultural roots as a basis for the development in the
national literary tradition‟. Mereka mengklaim sebutan Angkatan Terbaru. Novelnya ini sangat
berbeda dari konvensi sastra angkatan sebelumnya seperti misalnya Nyali (Putu Wijaya). Anak Tanah Air, Secercah Kisahkarena merepresentasikan „a realist historical novel, in part a historical
documentary, full of autobiographical elements and peopled by actual historical figures, either
under their own names or thinly disguised behind pseudonyms‟. Buku dan posisi Ajip Rosidi yang independen tidak memihak kiri (Lekra) atau kalangan nasionalis ini menyulut polemik sebagaimana yang terekam dalam beberapa edisi Horison, April hingga Agustus 1987. Arief
Budiman waktu itu sempat menulis editorial bertajuk „Do we have the courage to look at our past
history?‟. Untuk lengkapnya, silahkan baca Keith Foulcher, 1991. “Making History: Recent Indonesian Literature and the Events of 1965,” dalam Robert Cribb (ed), The Indonesian Killings 1965 – 1966. Studies from Java and Bali (Australia: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, 1991), hlm. 101–119.
onderbow-nya sekaligus anggota-anggota dan para simpatisan langsung atau tidak langsung). Kemenangan Pancasila terhadap “G 30S PKI” menjadi titik nol sejarah republik ini, titik awal penulisan kemajuan bangsa, justifikasi ideologi
pembangunan, justifikasi etis kamp-kamp konsentrasi untuk mencerca, menjerat
dan mengisolasi berbagai anasir komunis dan antek-anteknya. Penjara-penjara
penuh sesak, Nusakambangan dan Pulau Buru identik dengan kaum buangan.
Terperangkap dalam puting-beliung tebasan clurit dan sayatan sembilu ini
adalah seorang seniman didong (musik tradisional rakyat Aceh) Ibrahim Kadir.
Tertuding anggota PKI, ia dilucuti dari desanya di Takengon, Aceh tengah, dan „hanya‟ dipenjara selama 11 (ditangkap 12 Oktober 1965) dan sebelum dibebaskan (22 oktober 1965) karena terbukti sekedar korban dari kekacauan dan
eforia kekerasan saat itu. Lewat panca indera sang seniman (yang dimainkan
Ibrahim Kadir sendiri), saksi hidup lusinan tahanan digiring ke ladang
pembantaian, Garin memainkan tutur sinematiknya. Didong sang seniman
menjadi musik sekaligus ritme dan tuturan sinematik di sana-sini sebelum layar
menutup 90 menit kemudian.
Dengan begitu, film produksi 1999 ini sangat menarik dan sangat
menantang untuk dipertemukan dengan proses sinesemiotik Deleuzian justru
karena kontroversi sejarah, mekanisme penjara yang hendak membungkam
kemanusiaan dan sentralitas didong terhadap dialog dan gerak. Pertama, penjara
adalah asumsi masyarakat demokratik. Penjara adalah konsekuensi logis
prinsip-prinsip retributif, korektif dan remedial. Pemenjaraan adalah kondisi ideal ketika
keadilan ditegakkan. Lebih dalam lagi ke diskursus penjara, kita akan menemukan
ada begitu banyak elemen dalam konstruk penjara dan pemenjaraan. Penjara
menunjukkan kesadaran sejarah yang meluas akan kesucian hak-hak asasi
manusia dan nilai-nilai universal dari demokrasi itu sendiri seperti kesetaraan,
kebebasan, kebebasan mengemukakan pendapat, individualitas, hak kepemilikan,
dan seterusnya.
Pada titik ini, kita berhadapan dengan paradoks penjara. Ketika penjara
isolasi eksklusif berkat sistem tertutup dan prinsip panoptikumnya6, penjara juga
sekaligus miniatur dari masyarakat yang melahirkannya (sebuah relasi diferensial)
dan sebuah masyarakat dalam dirinya sendiri (jadi sebuah sistem signifikasi yang
independen). Pertukaran serta komunikasi antar tanda pada setiap level di antara „subyek-subyek penjara‟ selalu menghadirkan keunikan dan kekuatan potensial kreatif penciptaan dalam rangka memaknai proses-proses kodifikasi dan
konvensionalisasi. Artinya, prinsip demokrasi justru mengalami banyak
pertanyaan dalam dinamisme kehidupan penjara. Demokrasi ternyata bukanlah
sebuah entitas yang given dan stabil tapi entitas labil yang terus-menerus
berbenturan dengan motivasi subversif, pemberontakan terhadap segala upaya
represi sistematis proses simbolik kontra ideologi resmi.
Garin mengkonfrontasikan institusi penjara dan olah rasa sang seniman
yang mendendang saat lidah kelu kehilangan kata tercekam realitas yang
melampaui kapasitas panca indra. Garin mengambil posisi sebagai pencipta
tanda-tanda yang memproduksi cara-cara baru dalam mengkonsumsi dan
memproduksi jaringan tanda, kontras-anarkhis dengan kebiasaan ingatan dan
sirkuit pencerap (perceptual circuits) bangsa ini.
Kedua, pengalaman sinematik direct time-image menisbihkan dikotomi
film-audiens. Penjara dan segala sesuatu dan setiap orang di dalamnya independen
menciptakan simbol-simbol dan sistem pertukaran tandanya masing-masing
(intertekstualitas dan intersubyektivitas). Berbagai hal menjelmakan dirinya
secara spontan! Aspek menjadi (becoming)7 ini bukan barang asing dalam
6
Jeremy Benthan (1748 – 1832), seorang hakim Inggris dan filsuf utilitarian adalah yang pertama memformulasikan prinsip pengawasan minor dengan efek maksimum. Penjara ditandai dengan menara pengawas yang memungkinkan penjaga melihat setiap terhukum sejelas siang hari sementara para napi tak pernah bisa memastikan apakah mereka sedang diamati atau tidak. Ini menghasilkan perasaan sedang diawasi secara terus-menerus. Disiplin ditegakkan lewat prisnip conditioning operant ketika para tahanan mengawasi tindak-tanduk mereka secara sukarela. Utilitarianisme ini secara khusus ditandai dengan evaluasi moral dan etis dalam kaitannya dengan kekuatan moral dan etika memproduksi kesenangan (pleasure) yaitu yang satu-satunya baik (the only good) atau penderitaan (pain) yaitu yang satu-satunya jahat (the only evil). Lihat Clarence L. Barnhart (ed), The American College Encyclopedia Dictionary (Chicago: Spencer Press, Inc., 1958), hlm. 114.
7
Konsep becoming yang dimaksud adalah seperti yang digambarkan Deleuze, “Cinema always
karya Garin Nugroho. Seperti dikatakan I. Bambang Sugiharto8, film-film Garin
berkat kombinasi fakta dan fiksi memungkinkan kita mereinterpretasi realitas
aktual dari kebaharuan perspektif (angle) potensialitasnya. Film-film ini
mendekonstruksi kategori-kategori dasar yang biasanya kita dayagunakan untuk
mencerap realitas dan pada saat yang sama menggeser posisi subyek dan
meletakkan subyek pada titik potong lalu-lintas berbagai impuls dan impresi yang
sangat liar namun begitu nyata untuk diacuhkan. Kepadatan realitas cerai-berai
tersebar membentuk jaringan (network) polifonik dan simultan, sebuah
intertekstualitas yang tak terduga namun begitu menyerap (absorbing). Garin
berhasil mendestabilisasikan kesadaran subyek seraya menyingkap lapisan fiksi
dari semua bentuk rasionalisasi sekaligus membuka sumbat lorong-lorong impuls
yang paling primordial. Bagi Sugiharto, tuturan Garin ini sangat strategis guna
mengungkap realitas tersembunyi bangsa ini khususnya menyangkut kombinasi
ganjil pra-moderen (bahkan Jaman Batu), horizon moderen and post moderen,
ketakberakaran dari paradigma-pardigma ini di Indonesia, hilangnya sejarah,
hilangnya heroisme, keruntuhan nilai-nilai normatif dan kegamangan dalam
konstelasi emosi. Garin berupaya mengungkap semua ini bukan ala Holywood
(bukan lewat identifikasi emosional dengan karakter juga bukan berkat kekuatan
bahasa atau kata-kata). Penonton disentuh lewat eksposisi sejumlah image, bahasa
tubuh dan adegan-adegan poetik. Film bukan untuk menghujat seorang pemain
dalam film tapi justru mengkritisi fiktisisasi kehidupan sehari-hari. Dengan cara ini, diri mengalami semacam „bersih jiwa‟ yang memungkinkan peningkatan kapasitas mencerap realitas original.
Garin merefleksikan pengaruh dan perkembangan bahasa sinematik paska
Perang Dunia II9 khususnya yang berkembang di Italia (neoRealisme) dan
movements, then you get other patterns, becomings rather than stories.” Lihat Gilles Deleuze.1990. Negotiation. 1972-1990, Martin Joughin (trans), (New York: Colombia University Press, 1990),hlm. 59.
8I. Bambang Sugiharto, “Garin Nugroho‟s Films and Social Transformation,”.dalam Philip
Cheah, Taufik Rahzen, Ong Hari Wahyu, Tonny Trimasanto (eds), And The Moon Dances: The Films of Garin (Yogyakarta: Bentang Pustaka. bekerjasama dengan SET Film Workshop and BingO, 2004), hlm. 187-189.
9
Perancis (New Wave)10. Tehnik ini mengintegrasikan tumpang-tindih radikal,
menonjolkan kontras, paradoks dan disharmoni, plot yang tak linear (plot bisa saja
dikorbankan tanpa menyebabkan gangguan berarti), ambigu moralitas dan
khususnya dengan mengeksplorasi karakter-karakter „sakit‟. Dalam karya-karya
Garin semua elemen di atas tampak dengan jelas yang mengingatkan kita pada
Taviani, intertekstualitas, Goddard atau bahkan gambar-gambar satiris surrealis
Bunuel misalnya. Akan tetapi, Garin tetap asli Indonesia11 yang menggulati
realitas negerinya dengan cara-cara laiknya tipikal Indonesia dan khususnya dari
perspektif sensibilitas Jawa. Narasi berfungsi tidak lebih sebagai bingkai. Garin
lebih menekankan pada citraan (image) daripada integritas konstruk film secara
keseluruhan. Film-filmnya selalu penuh dengan pregnant moments (Roland
Barthes). Setiap adegan dijiwai kedalaman eksistensial tertentu sehingga kita
dipaksa untuk berhenti berkali-kali untuk setiap adegan12. Dalam bahasa Deleuze,
protagonis dan penonton saling tumpang-tindih, yang nyata dan imaginer saling
menghapus sekaligus mencipta. Inilah kategori filmis baru yang menempatkan
gelisah dengan perkembangan film di tanah air yang cenderung menekankan tujuan-tujuan komersial, terhalang pisau sensor serta cenderung merefleksikan keinginan produser, silahkan baca Salim Said, Profil Dunia Film Indonesia, (Jakarta: Grafiti Pers, 1982).
Persoalan-persoalan yang disorot secara mendalam oleh Salim Said di atas juga menjadi keprihatinan seorang H. Usmar Ismail. Dalam kumpulan tulisannya, ia mengekspresikan sikapnya yang anti kiri dan posisinya soal komersialisasi film (yang dipengaruhi nilai-nilai Barat-Holywood). Ia juga mempertanyakan relevansi lembaga sensor, bagaimana posisi film sebagai alat politik serta berbagai persoalan perkembangan film di tanah air serta bagaimana soal-soal kebangsaan (lewat tema-tema perjuangan, gerilya ataupun pembangunan) menjadi pergulatan dunia sineas di masanya. Tak lupa juga ia menyinggung-nyinggung bagaimana latar belakang produser maupun sutradara turut mempengaruhi pilihan produk sinematik, dan seterusnya. Untuk lengkapnya, silahkan baca H. Usmar Ismail, Usmar Ismail Mengupas Film (Jakarta: Sinar Harapan, 1983).
Dalam kaitannya dengan eksistensi lembaga sensor yang secara historis merupakan produk kolonial itu dan respon seorang seniman, pandangan WS Rendra di bawah ini patut direnungkan.
Katanya, “Di dalam masyarakat kita, standard akal sehat kolektif masih rendah akibat tekanan
politik dari zaman raja-raja, zaman penjajahan, dan zaman sekarang. Rakyat dibiasakan dicecoki instruksi dan indoktrinasi, jadi kurang didorong untuk mengembangkan pikiran yang kreatif oleh kaum agama, kaum birokrat, atau pun oleh para politisi. Yah, maklumlah, kita masih berada dalam tingkat perkembangan. Oleh karena itu, sangat berbahaya bagi para seniman untuk berkompromi dengan selera penonton. Sebab, hal itu akan menurunkan mutu seninya, kecuali kalau ia sudah
mantap secara jujur akan menjadi penghibur saja”. Lihat WS Rendra, “Dunia Film di Mata Seorang Dramawan” dalam Harris Jauhari (ed), Layar Perak, 90 Tahun Bioskop di Indonesia
(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 150. 10
Dua gerakan ini akan kita dalami dalam bagian-bagian berikutnya. 11
Tekanan dengan italiks ini berasal dari penulis. 12
subyek di mana-mana, ambiguitas antara pergerakan tanpa henti (continuous
flowing) dan keterperangkapan yang membekukan (pemain tidak lagi “mengetahui” bagaimana berreaksi terhadap situasi-situasi yang jauh melebihi kapasitas respon manusiawi entah karena terlalu buruk, terlalu cantik, terlalu
mengejutkan, dan seterusnya). Momen ini melahirkan yang nyata justru karena
wadah imaginernya!
B. Status Questionis
Ada empat pertanyaan yang hendak dijawab dalam penelitian ini yaitu :
1. Simbolisme apa yang ada dalam film tersebut?
2. Bagaimanakah pengalaman waktu sinematik kita?
3. Kesadaran seperti apa yang sedang ditawarkan?
4. Bagaimanakah film berfungsi dalam proses menjadi „Indonesia baru‟?
Dalam pertanyaan pertama, kita secara obyektif hendak mencari dan
memetakan simbol-simbol apa yang menghadirkan waktu dalam film dimaksud.
Setelah itu adalah proses penafsiran atau pembacaan simbol-simbol itu dalam
kaitannya dengan pembentukan diri (self) yaitu pengalaman menemukan diri
(semacam sosiologi simbolisme). Dalam pertanyaan ketiga kita hendak menggali
dan merumuskan rangkaian pengalaman waktu sehubungan dengan pertanyaan
kedua tadi. Setelah ini semua mendapat jawaban-jawabannya, kita hendak
mendalami pertautan antara yang imaginer dan yang nyata itu khususnya secara
Deleuzian13 dalam konteks dan dalam perspektif menjadi Indonesia modern.
13“Film criticism faces two dangers: it shouldn‟t just describe films but nor should it apply to them
concepts taken from outside film. The job of criticism is to form concepts that aren‟t of course “given” in films but nonetheless relate specifically to cinema, and to some specific genre of film, to some specific film or other. Concepts specific to cinema, but which can only be formed philosophically. They are not technical notions (like tracking, continuity, false continuity, depth or flatness of field, and so on), because technique only makes sense in relation to ends which it
presupposes but doesn‟t explain. It is these ends that constitute the concepts of cinema. Cinema
sets out to produce self-movement in image, autotemporalization even: that‟s the key thing, and
C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan simbolisme dalam film
Garin Nugroho dengan menginventarisasi simbol-simbol, melacak latar belakang
(kaitan antara bahasa estetik dan biografi sinematik sutradara, gaya atau personal
style, posisi sutradara sebagai ateur dalam teks-teks sosial yang dominan)
memetakan pola-pola, dan menghasilkan semacam taksonomi tanda-tanda berikut
hubungan-hubungan antar tanda.
Kemudian, penelitian bisa mulai mempertanyakan bentuk dan proses
kesadaran seperti apa yang sadar atau tidak sadar coba dipresentasikan dan
dimaknai seorang Garin Nugroho. Kita akan melihat bagaimana tanda-tanda dan
hubungan-hubungan antar tanda dipadurangkaikan secara tehnis-estetis. Lebih
dalam lagi, kita akan mencermati dinamisme bagaimana, mengapa serta seberapa
jauh kesemuanya itu mampu memproduksi muatan kesadaran tertentu. Hal ini
tentu akan sangat terkait dengan muatan konsep waktu yang diproduksi,
dikonsumsi dan didistribusikan dalam film dimaksud secara simultan.
Pada tingkat selanjutnya, penelitian ini juga bertujuan meletakkan dan
menggulati Puisi Tak Terkuburkan dalam konteks dan perspektif menjadi
Indonesia moderen. Pada puncaknya, semua upaya di atas akan menjadi umpan
balik secara Deleuzian. Kata lain, penelitian ini berharap bisa mempresentasikan
temuan sejumlah tanda sinematik yang bisa diaplikasikan dalam dunia filsafat.
D. Metodologi
Pengalaman penelitian lapangan beserta pengolahan data-datanya, riset
dokumen serta riset kepustakaan akan saling mendukung menciptakan basis untuk
proses interpretasi yang berkelanjutan. Secara semiotik, setiap elemen akan
dianalisa dari dalam hingga elemen-elemen tersebut mencapai titik jenuh
membuncah sebagai sebuah sistem signifikasi kultural.
Ada dua level proses analisis yang interdependen. Secara khusus penulis
pola-pola berulang serta konsistensi gaya tutur sinematik sang sutradara. Dalam hal ini,
penulis akan banyak menggunakan teori-teori narasi film, sinematografi,
semiotika film khususnya sejak dari Metz, sosiohistoris film dan biografi karya
sinematik sang sutradara (Garin Nugroho). Kemudian level analisa akan
mengalami transformasi ke tataran paradigmatik yaitu secara Deleuzian (direct
time-image).
E. Relevansi Penelitian
Film adalah salah satu mitra baru dalam mereposisikan filsafat ke dalam
tempat yang semestinya, sebuah alat kultural untuk mengkontemplasikan dan
mendasarkan tindakan atau praktik sosial. Melalui film, kita bisa belajar dan
menganalisa sangat banyak dan mendalam bagaimana kita disignifikasi dengan
penanda-penanda apa, dengan citraan-citraan seperti apa dan berdasarkan
penilaian dan evaluasi siapa. Kita juga bisa belajar bagaimana memproduksi genre
film sendiri secara independen sekaligus simultan melakukan proses dialog intens
multi konteks dan perspektif dengan berbagai pihak. Pengalaman ini pada
gilirannya akan menciptakan arus balik kreatif yaitu menemukan kembali filsafat
dan menciptakan tanda-tanda baru.
F. Skema Penulisan
Penelitian ini akan bergerak lewat lima bagian besar. Bab I sifatnya
memproblematisasikan latar belakang dan mengkoordinasikan jalannya penelitian
dan proses penulisan. Kita berkutat dengan sejumlah gagasan pokok yang menjadi
dasar argumentasi selanjutnya.
Bab II berfungsi sebagai kerangka teoritis untuk memberi bingkai dan
batu pijakan analisa. Ini dimulai dengan mengupayakan ringkasan sekaligus
pemetaan baik secara diakronis maupun anakronis berbagai teori film sejak
Christian Metz hingga Gilles Deleuze. Penggalian ini sangat fundamental untuk
pencarian para pemikir, sineas dan kritikus. Selain itu, „arkeologi sinesemiotik‟ ini
akan memperlihatkan dinamisme dialektika sinesemiotik dengan berbagai disiplin
lainnya, bagaimana setiap proses tersebut sebenarnya mengandung bibit teori
narasi atau konsep tertentu yang kemudian dieksperimentasikan dalam eksplorasi
images baru yang menghasilkan persepsi ruang-waktu yang khas.
Secara khusus, penulis akan menunjukkan proses berpikir dan
representasi Deleuze dan bagaimana sikapnya terhadap kecenderungan teoritisasi
para pemikir lainnya serta kekhususan teorinya dibandingkan teori-teori film
lainnya. Kita harus bolak-balik memasuki pola-pola khas Deleuze dalam proses
mengaitkan filsafat dan seni, filsafat dan film dan bagaimana semua ini
menghasilkan struktur perseptual dan pengalaman baru dan time-images. Telusur
ini akan pungkas dengan sejumlah formula dan kesimpulan yang mengarahkan
kita pada kelaikan dan germinitasnya untuk diterapkan dalam gaya bertutur Garin
Nugroho.
Bab III melihat dan mendekati film sebagai artefak dalam sejarah
perfilman di Indonesia. Puisi Tak Terkuburkan akan menjadi sentral dalam bagian
ini. Kita akan melihat bagaimana seorang Garin khususnya lewat film ini
memposisikan dirinya secara khas. Kita berasumsi bahwa Garin berjuang dan
belajar keluar dari penjara ideologisasi simbol-simbol sekaligus menghidupkan
kembali simbolisme-simbolisme privat dan publik yang sudah direkonstruksi
regim Soeharto yang menginjeksikan instrumen-instrumen imagery
reproducation14-nya. Mengapa Puisi Tak Terkuburkan istimewa? Mengapa Garin
berbeda dengan sineas-sineas lainnya? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan
ini, kita akan berupaya merekonstruksi film ini menurut elemen-elemen
penyusunnya yang nantinya sekaligus menjadi dasar bagi argumentasi berikutnya.
Pokok-pokok Bab IV kemudian mengikuti perkembangan proses analisa
sejak dari awal. Bagian ini merupakan upaya mendialogkan Garin dalam Puisi
Tak Terkuburkan dengan corak berpikir Deleuzian. Kita akan melihat bagaimana
tanda-tanda dan hubungan-hubungan antar tanda dipadurangkaikan secara
tehnis-estetis yang kemudian memproduksi imagi-imagi tertentu. Imagi-imagi ini pada
14
gilirannya menghasilkan proses kesadaran tertentu. Ini semua sangat berkaitan
dengan konsep waktu yang diproduksi, dikonsumsi dan didistribusikan dalam film
dimaksud secara simultan. Dua level sintesa yang akan kita gulati adalah sintesa
diskursif dan sintesa artistik dari paham time-image yang ditunaskembangkan
Deleuze berhadapan dengan proses sinematik seorang Garin khususnya dalam
Puisi Tak Terkuburkan.
Analisa dengan demikian berada di level paradigmatik dengan fokus pada
pengalaman waktu yang ditawarkan Garin Nugroho khususnya lewat Puisi Tak
Terkuburkan. Pada bagian ini, penulis berharap akan berhasil memeras beberapa
tehnik, konsep dan gambar baru yang ditawarkan Garin. Semoga juga kita berhasil
menunjukkan kebaruan dalam proses mengkonsumsi karya audiovisual. Hal ini
sangat penting karena kita akan mengkomparasikan sinesemiotik Garin Nugroho
dan Gilles Deleuze khususnya pada bagian time-image. Dalam rangka bertemu,
bertaut dengan sinaps-sinaps filmik baru ini, kita akan bertanya bagaimana
dialektika Garin dan Deleuze bisa menghasilkan pola-pola sirkuit dan tanda-tanda
baru dalam dunia sinema Indonesia khususnya dan sinematografi umumnya!
Bab V adalah sintesa ringkas antara seni perfilman dan filsafat. Sintesa
ini meliputi dua level yaitu level filosofis dan level artistik. Bagaimana
tanda-tanda dan hubungan-hubungan antar tanda-tanda bisa diterapkan dalam dunia filsafat
(umpan balik Deleuzian). Penulis akan berupaya memeras beberapa konsep yang
dihasilkan dari dalam film sendiri namun dapat dikembangbiakkan dalam kultur
filosofis. Proyek ini memuncak pada problematisasi bagaimana pertautan antara
yang nyata dan imaginer dalam Puisi Tak Terkuburkan dalam konteks/perspektif
Indonesia. Kita akan mencoba menemukan mata rantai kerja keras
estetik-filosofis-ideologis seorang Garin dan upaya-upaya simboliknya merespon
situasi-situasi yang sedang berubah dengan dasyat nir batas dan mengantisipasi impian
15
Bab II
Film Sebagai Diskursus:
Dari Saussure Menuju Semiotika Bahasa Film Hingga
Deleuzian Time-Image
Sebagai bagian integral budaya komsumtif dewasa ini, film justru
menawarkan kausalitas terbalik. Barangkali dalam bayangan banyak orang, film
yang sangat tergantung pada teknologi itu seharusnya muncul sebagai produk
kreatif berbagai temuan di bidang mekanik, optik maupun kimiawi. Sayangnya,
tidak demikian realitasnya seperti yang ditulis Andre Bazin dalam The Myth of
Total Cinema?1.
Muybridge seorang pecinta kuda di tahun 1877 dan 1880 berhasil
mewujudkan hasratnya menangkap image derap seekor kuda dengan
mereduksinya menjadi serangkaian gerakan pada lempeng-lempeng kaca. Hal ini
hanyalah salah satu dari tiga komponen film yaitu simultanitas, emulsi2 kering dan
wadah yang fleksibel (flexible base). Ketika kimia menemukan wadah yang lebih
baik (gelatin-bromida dari perak), namun sebelum kemunculan gulungan seluloid
1 Andre Bazin, ―The Myth of Total Cinema,‖ dalam Gerald Mast, Marshall Cohen dan Leon
Braudy (eds), Film Theory and Criticism. Introductory Readings (New York: Oxford University Press, 1992), hlm. 34-37.
2 Ira Konigsberg menjelaskan demikian, ―The layer of light
-sensitive silver salts, suspended in gelatin, which is coated on the base of film. In color film, there are normally three separate emulsion layers, each also containing a chemical coupler sensitive to a different primary color. The latent image is formed in black-and-white film when the emulsion is exposed to light and made visible when the silver salts are transformed to black metal during developing. In color film the couplers are responsible for forming the colored image, which remains after the develop silver
di pasar, Marey mendesain kameranya dengan menggunakan berbagai lempeng
kaca. Akan tetapi, ketika akhirnya seluloid mulai dipasarkan, Lumiere pun
berupaya menggunakan kertas film. Sementara itu, kita mencatat benih film
sebenarnya sudah disemai sejak abad ke-17 dengan phenakistiscope3 atau
zootrope.
Di sisi lain, ada sejumlah upaya ilmiah utamanya Plateau yang melakukan
riset mendalam mensintesa gerakan-gerakan sederhana. Penemuan ini membuka
jalan bagi berbagai penemuan lainnya. Optik juga memainkan peranan dengan
menemukan betapa image bisa tertahan lama pada retina. Dan ilmu kimia secara
independen berupaya menemukan cara melakukan fiksasi image.
Bagi Bazin, ini semua mengherankan mengingat semua yang dibutuhkan
untuk menghasilkan gambar yang hidup namun harus menunggu hingga
perkembangan-perkembangan industrial maupun ekonomi abad 19.
Perkembangan-perkembangan ini mengisyaratkan adanya penemuan-penemuan
terpisah tak terkoordinir. Para penggagas film bisa dikatakan menjadi nabi yang
memproyeksikan sebuah jaman seperti yang kita alami saat ini. Dalam imaginasi
mereka, sinema dipandang sebagai representasi total dan sempurna dari realitas,
sebuah rekonstruksi dari kesempurnaan ilusi dunia luar dalam suara, warna dan
relief.
3
Sejarahwan P. Potoniee bahkan mengatakan bahwa bukannya fotografi
namun penemuan stereoskopi yang masuk ke pasar di tahun 1852 sesaat sebelum
upaya-upaya awal fotografi animasi yang membuka mata para ahli. Melihat obyek
mereka diam tak bergerak dalam ruang membuat mereka berpikir bahwa apa yang
mereka butuhkan adalah gerakan. Gerakan inilah yang menjadi kunci animasi foto
mereka menjadi kopi alamiah kehidupan. Gagasan ini kemudian menjadi tuntunan
penelitian dan eksperimentasi berikutnya.
Kita berhadapan dengan paradoks di sini. Sentralitas image secara historis
maupun teknis pada dasarnya kebetulan. Setiap penemuan yang ditambahkan pada
perkembangan sinema dengan sendirinya bergerak kian lama kian dekat ke
originalitas ide akan gambar yang hidup. Atau dengan kata lain, film belum juga
ditemukan! Hal ini kembali akan terlihat nyata dalam perjalanan film sebagai
diskursus dan praktik estetik. Kita akan melihat bagaimana kawin silang antar
disiplin dan berbagai peristiwa monumental melahirkan sejumlah gagasan yang
membawa kita makin lama makin dekat dengan realitas sinematik. Pertumbuhan
ini kemudian melahirkan banyak percabangan baru yang membuka berbagai
alternatif dalam menformulasikan realitas sinematik seperti yang diimpikan para
A. Produksi Makna Saussurian
Bianglala semiotika film tak akan serumit sekarang seandainya Saussure4
tak pernah mendekritkan diktum semiotikanya. Mainan favorit para filolog yaitu
berpuas-puas menjejaki sebuah kata atau suara secara evolutif (bagaimana sebuah
kata atau suara muncul dan tumbuh selama berabad-abad hingga menemukan
kestabilan bentuknya saat ini) terjungkir tanpa ampun. Para empu bahasa,
demikian fatwa Saussure, bertugas menjelaskan bagaimana kata atau suara
tertentu justru memproduksi makna. Faktanya makna atau signifikasi itu mandiri
di luar sistem dunia benda alias berhubungan secara semena-mena tanpa kepastian
dan dasar identifikasi. Sebaliknya, makna ada dan hanya berada dalam sebuah
sistem yang memungkinan ujaran (utterance) diproduksi, dikomunikasikan dan
dimengerti. Sistem ini adalah langue (grammar), sedangkan yang terujar dalam
sistem tersebut adalah parole. Kedua hal ini saling terkait dan memberi batas
ujaran yang mungkin (kapasitas komputasi sistem memungkinkan produksi bunyi
dan makna sekaligus) maupun yang ‗terlarang‘ (tak memungkinkan dalam
mekanisme sistem ataupun yang mungkin namun kosong makna).
Sebagai totalitas sistemik, bahasa berfungsi berkat jaring-jaring tanda
signifier (bunyi aktual atau jika tersurat, tampilan atau materi kasat mata dari
sebuah bunyi atau kata) dan signified (konsep atau makna). Hubungan signifier
dan signified ini arbiter dan nir relasi pasti lurus. Di sisi lain, seakan-akan kata dan
maknanya saling melibati mewujud dalam ketunggalan sebuah tanda. Paradoks ini
4
menyingkap fundamen tak sadar kolektif yaitu konvensi atau kodevikasi sosial
yang berfungsi sebagai kanon sistem. Tanda dengan demikian adalah fenomena
kolektif, sebuah entitas mental.
Lebih jauh lagi, Saussure meruntuhkan mitos nilai positif sebuah signifier.
Sebuah signifier bernilai hanya dalam hubungannya dengan setiap signifier
lainnya dalam sistem yang bersangkutan. Ujaran diproduksi hanya setelah
melewati filter seleksi yang menghilangkan potensi setiap signifier yang tak
terpilih. Bukan apa yang ada (present) tapi apa yang tak ada (absent) yang
menentukan! Makna mencuat justru karena ada perbedaan (difference) antar
signifier. Bayi dan babi misalnya dua komponen dalam sistem diferensial bahasa
Indonesia yang memungkinkan makna muncul dari hubungan arbiter dua signifier
y dan b.
Relasi negatif atau absensi ini tampak dalam dua aras primer. Pertama
adalah sintagmatik (aras kombinasi) yaitu relasi-relasi gramatikal di antara tanda
yang hadir dalam rantai pemaknaan (signifiying chain) konkret dan aktual seperti
dalam kalimat. Aras kedua adalah paradigmatik (aras seleksi atau subtitusi) yang
merangkum berbagai relasi di antara semua kemungkinan yang mungkin
(karenanya implisit atau absent) untuk setiap elemen dari sebuah rantai
pemaknaan5.
5
Saussure tak pelak lagi menangguk pengikut dan kejayaan di berbagai
lingkungan akademik. Gagasannya sangat original dan secara bersamaan juga
menjadi pergulatan intelektual Pierce di Amerika Serikat. Yang terakhir ini
mewakili aliran stukturalisme buah rahim mazhab Formalisme Rusia. Meskipun
keduanya mengandung sejumlah perbedaan namun keduanya memulai era baru
dalam dunia linguistik dan bahkan lintas disipliner. Muncul kegairahan baru
dalam menata pengertian dan cara mempersepsi realitas linguistik dan
realitas-realitas di luar linguistik. Sejak saat itu seakan segala sesuatu merepresentasikan
corak produksi makna dan proses pemaknaan tertentu. Tugas menemukan
‗bahasa‘ dari suatu tatanan dan memformulasikan hukum-hukum (langue) yang
mengatur proses-proses spontan ini menjadi sangat populer di kalangan komunitas
akademik di berbagai tempat.
dalam sebuah sistem (bahasa). Makna adalah akibat dari relasi total yang ada dengan unsur-unsur lain secara total; (2) Prinsip kesatuan. Sebuah tanda merupakan kesatuan yang tak dapat dipisahkan antara bidang penanda yang bersifat konkrit atau material (suara, tulisan, gambar, objek) dan bidang petanda (konsep, ide, gagasan, makna). Meskipun petanda yang abstrak dan nonmaterial bukan bagian instrinsik dari sebuah penanda, akan tetapi oleh Saussure ia dianggap hadir (present) bersama-sama penandanya yang konkrit dan kehadirannya adalah absolut; (3) Prinsip konvensional. Relasi struktural antara sebuah penanda dan petanda sangat tergantung pada apa yang disebut konvensi yaitu kesepakatan sosial tentang bahasa (tanda dan maknanya) di antara komunitas bahasa; (4) Prinsip sinkronik. Keterpakuan pada relasi struktural menempatkan semiotika struktural sebagai sebuah kecenderungan kajian sinkronik, yaitu kajian tanda sebagai sebuah sistem yang tetap di dalam konteks waktu yang dianggap konstan, stabil, dan tak berubah. Dengan demikian, ia mengabaikan dinamika, perubahan, serta transformasi bahasa: (5) Prinsip representasi. semiotika struktural dapat dilihat sebagai sebuah bentuk representasi, dalam pengertian sebuah tanda merepresentasikan suatu realitas, yang menjadi rujukan atau referensinya. Ketiadaan realitas berakibat logis pada ketiadaan tanda; (6) Prinsip kontiunitas. Ada kecenderungan pada semiotika struktural untuk melihat relasi antara sistem tanda dan penggunaannya secara sosial sebagai sebuah continuum, yaitu sebuah relasi waktu yang berkelanjutan dalam bahasa, yang di dalamnya berbagai tindak penggunaan bahasa selalu secara berkelanjutan mengacu pada sebuah sistem atau struktur yang tidak pernah berubah, sehingga di
dalamnya tidak dimungkinkan adanya perubahan radikal pada tanda, kode, dan makna‖. Lihat
B. Semiotika Film : Saussurian atau anti Saussurian?
Saussure pasti sudah ‗gila‘ ketika mendesakkan praktek prinsip-prinsip
semiotika dalam segala bidang. Semiotikanya mulai menuai keraguan dalam
lingkungan terpelajar. Patutkah sebuah temuan menjadi bahasa paripurna setiap
jenis proses tanda? Apakah semua sistem tanda pasti mengandaikan
hubungan-hubungan arbiter antar siginifier sebagai unit-unit dasar yang kasat mata? Paling
meresahkan adalah pernyataan bahwa signifikasi tak lebih dari efek diferensiasi.
Artinya, makna Saussurian adalah sebuah sistem yang sudah sempurna atau
selesai dalam dirinya sendiri alias sebuah sistem tertutup. Teks yang diproduksi
dalam sistem tertentu diperlakukan relatif sebagai totalitas yang koheren,
dipahami tidak dalam dirinya sendiri (bukan entitas yang secara organis pungkas
dan meliputi dirinya sendiri) melainkan hanya dalam hubungannya dengan sistem
induk.
Tidak heran apabila semiotika Saussurian ini menuai kecaman dan lawan.
Akan tetapi, realitas ini sekaligus merepresentasikan dinamisme dalam proses
perkembangan ilmu-ilmu sosial yang pada hakikatnya adalah proses melahirkan
kreativitas dan produktivitas baru. ‗Pertanyaan Saussurian‘ mengalami
transformasi drastis. Bukan lagi apa langue dari parole melainkan apakah langue
dari parole per definisi sudah cukup?
Semiotika film mulai tamasya dengan pertanyaan serupa. Dapatkah film
didefinisikan dalam perspektif langue dan parole? Menonton film-film klasikal
tetapi fakta visual dan visualisasi dalam film sungguh mengusik. Begitu sering
gambar visual seolah identik dengan objek dunia nyata. Film juga menggunakan
fotografi dan rekaman suara yang mustahil hanya representasi realitas (seperti
model imitasi langsung Bazinian). Sebaliknya, itu adalah presentasi dari realitas.
Singkatnya, fundamen signifikasi sinematik tampaknya tidak mengandaikan
struktur diferensi relasional.
Pertanyaan yang membuka gerbang kebuntuan ini adalah ‗apakah film itu
sebuah bahasa?‘6. Christian Metz termasuk yang mula-mula menjawab dengan
sistem semiotikanya sendiri. Metz menarik batas langue dan parole secara
berbeda yang ‗mengusir‘ sebagian kemungkinan aplikasi konsep-konsep
Saussurean. Bahasa selalu melibatkan intersubyektivitas dan historitas sosio
budaya tertentu. Bahasa muskil tanpa speaking public. Manakala bahasa adalah
sistem tanda yang dimaksudkan untuk interkomunikasi seturut garis Saussurean,
film sukar memenuhi kaidah ini. Komunikasi satu arah justru merupakan kekuatan
film. Film adalah film terlepas dari bahasa induknya, tak ada kemungkinan
mendeduksi bahasa film dari sumber yang melingkupinya. Yang bisa dilakukan
adalah menciptakan bahasa tersendiri (bahasa film). Metz menyoalnya sebagai
semacam bahasa (a kind of language) yang dibuat sepihak oleh pembuat