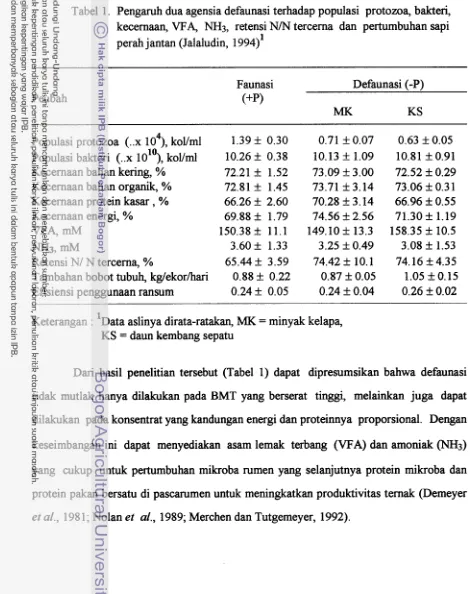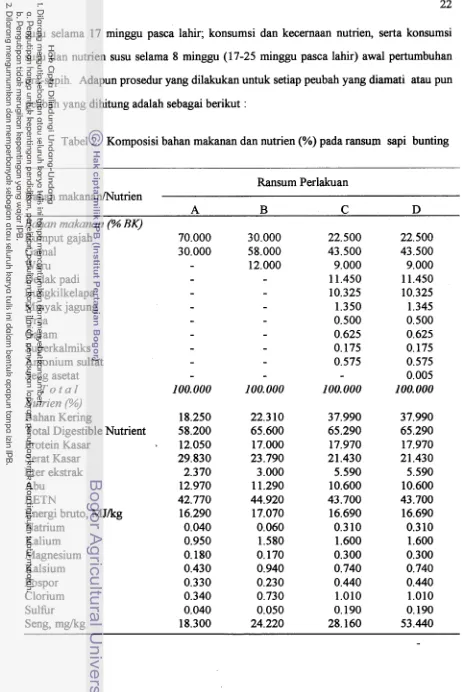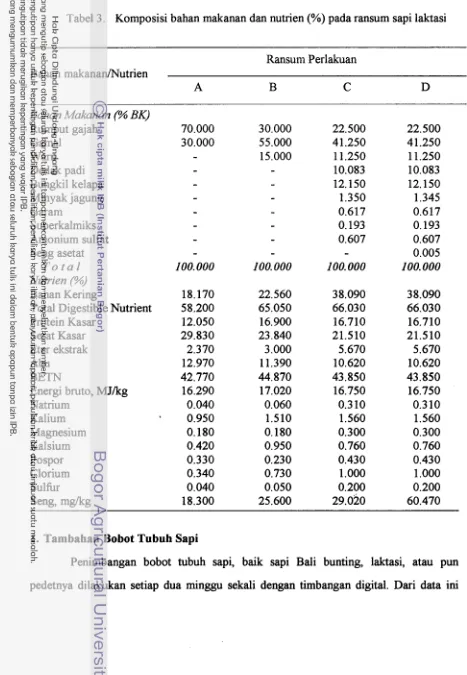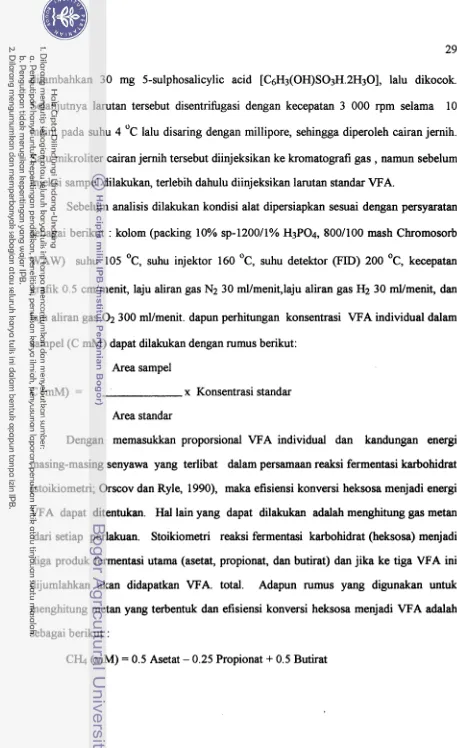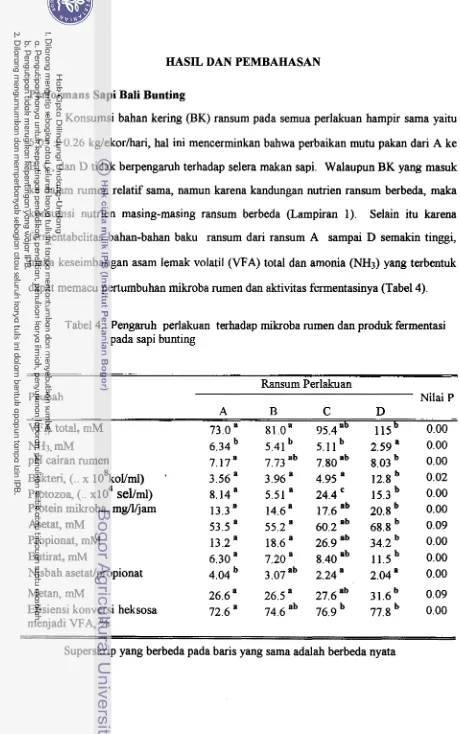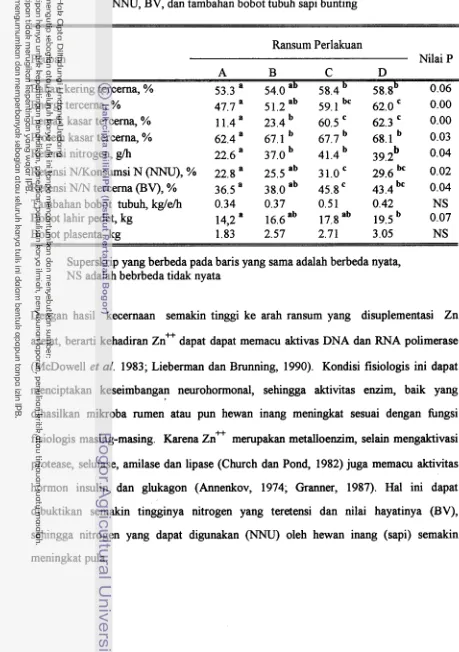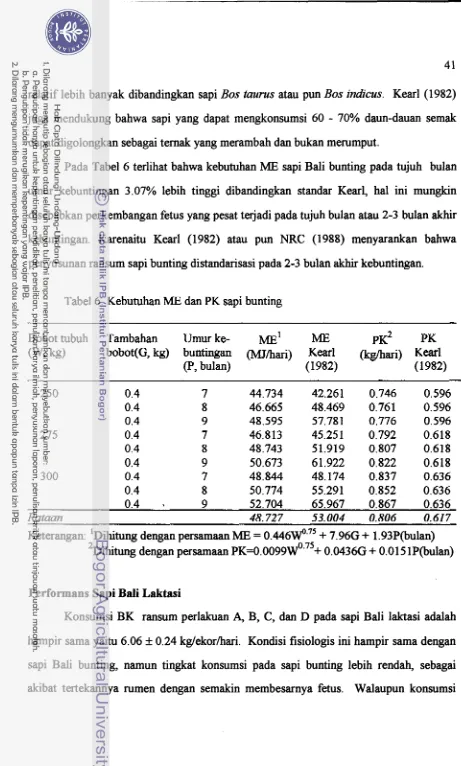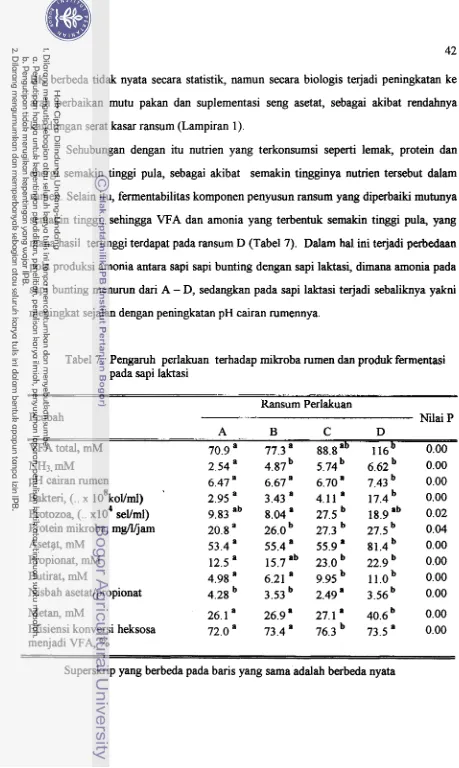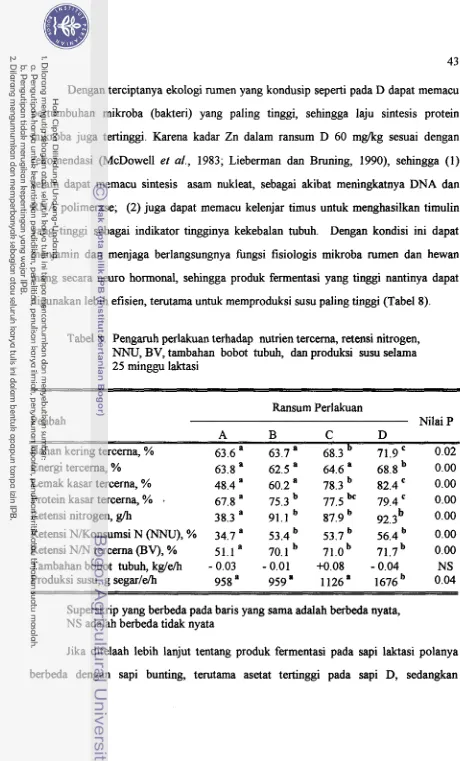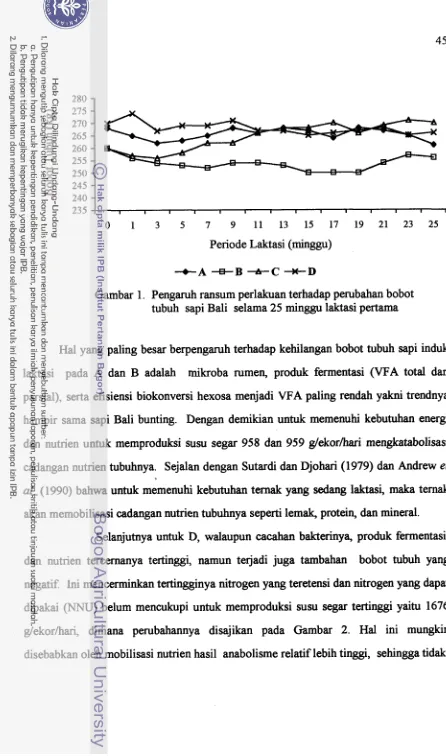PENINGKATAN PERFORMANS SAP1
BALI
MELALUI PERBAIKAN
MUTU
PAKAN
DAN
SUPLEMENTASI SENG
ASETAT
DISERTASI
I .Oleh
SENTANA PUTRA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
PERFORMANCE IMPROVEMENT OF BALI CATTLE THROUGH TEE USE OF QUALITY FEEDS AND
SUPPLEMENTATION
ZINC
ACETATESentana Putra
Under the supervision of Toha Sutardi as Chairman of Dissertation Committee, Djokowoerjo Sastradipradja, Tuty L. Yusuf, Jajat Jachja, and
Ketut Lana as member of committee.
ABSTRACT
Bali cattle (Bibos banteng) is indegenous animal that well recognized for superior reproduktive performance, high dressing out percentage, and high meatlbone ration. The animals however, is getting smaller and smaller in size due to continuous
offtake of quality bulls and poor nutrition. The experiment tried to improve
performance of the cattle through the use of leguminous tree foliage, concentrate feeds, and supplementation of zinc acetate. Experimental results were analyzed for the efficacy of the improvement followed by regression studies to elucidate metabolizable
energy (ME) and crude protein (CP) requirements of animals. The experiment was a
randomized complete block feeding trial in pregnant cows, 261
f
16.5 kg liveweight,where the treatments were A = 70% elephant grass (EG)
+
30% Gliricidia sepium (GS),B = 30% EG
+
58% GS+
12% Hibiscus tilliacius (HT), containing devaunating agent,C = 74% B + 25% concentrate feeds, and D = C
+
50 mg Zn-acetate/kg of dietary drymatter. The feeding regime was more or less maintained sine2 6.2
+
1.4 months ofpregnancy throughout 25 weeks of lactation.
The use of HT (treatment B) slightly decreased the total viable rumen protozoa from 8.14
x
1o4
to 5.5 1x
1o4
celldml, that was accompanied by a small increase in thetotal cultivable rumen bacteria from 3.56 x lo8 to 3.96
x
lo8 coloniedml. The changesreduced rumen
NH3
from 6.34 t o 5.41 mM (P<0.01), but increased digestibility (Pc0.0 1) of fat (1 1.4 vs 23.4%), crude protein (62.4 vs 67. I%), and N retention (22.6 vs 37.0 g/d). inclusion of concentrate feeds (treatment C) stimulated the growth of protozoa to 2.44 x 10' cellslml, while the total counts of bacteria remained unchanged (4.95 x lo8 colonieslml). The treatment improved fermentability of the whole diet that was apparent fiom the increase in the total volatile fatty acids (VFA) from 81.0 to 95.7mM and the increase in the rate of tungstic acid precipitible N (TAPN) formation from
14.6 to 20.8 mg/l in a hour. The changes lead to improvement in energy utilization that was noted fiom the drop of the acetatdpropionate ratio of the VFA fiom 3.07 to 2.01 and the increase in the efficiency of convertion of hexose energy into VFA from 74.6 to 77.8 % (P<0.01). Addition of Zn-acetate (treatment D) promoted growth of rurnen
9
bacteria to 1.28 x 10 colonies/ml and decrease the rumen protozoa to 1.53 x lo5 cellslml, so that fermentation, degestibility, and N utilization parameters were improved
pregnancy (0.465 vs 0.355kg/d) and gave birth to heavier calves (18.7 vs 15.4 kg).
Animals on treatment D yielded more milk than rest (2.73 vs 1.62 4%FCM/d).
Regression analysis revealed that the pregnant cows required 0.466
MJ
ME and9.91 g CP for maintenance, 7.96 MJ ME and 44 g CP for one kg liveweight gain, and
1.93 MJ ME and 15.1 g CP for one month advancement of pregnancy stage. The
lactating cows required 0.728 MJ ME and 1.9 g CP for maintenance, 4.393 MJ ME and
1.03 kg CP for one kg liveweight gain, and 3.272 MJ ME and 271 g CP for production
of one kg 4'YbFCM. Within ihe first 25 weeks of age, the requirements of the calves could be represented by following equations: ME (MJId) = -0.639
+
0.073W+
13.5746+
8.056D with R2 = 0.84 and Sb = 0.56, and CP (g/d) = -5.20+
0.661W+
3.686+
198.056
+
145.5D with R2 = 0.92 and S b = 26.6. In the equations, W stands for liveweight (kg), G for liveweight gain (kg/d) and D for dry matter consumption of diet.RINGKASAN
SENTANA PUTRA. Peningkatan Performans Sapi Bali melalui Perbaikan
Mutu Pakan dan Suplementasi Seng Asetat (dibimbing oleh TOHA SUTARDl sebagai
ketua, DJOKOWOERJO SASTRADIPRADJA, TUTY L. YUSUF, JAJAT JACHJA,
dan KETUT LANA sebagai anggota).
Sapi Bali (Bibos banteng) adalah sumber plasma nutfah asli yang bukan dimiliki
oleh masyarakat Bali saja, melainkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Sapi ini memiliki
beberapa keunggulan bila dibandingkan dengan sapi-sapi Bos indicus atau Bos taurus,
di antaranya daya reproduksi dan nilai karkasnya tinggi. Dengan terjadinya seleksi
negatif yakni pengurasan pejantan produktif dan berkualitas secara terus menerus,
belum intensifhya pelaksanaan progam inseminasi buatan, serta pakannya bermutu jelek
mendorong pedet yang terlahir semakin bertarnbah kecil.
Salah satu dari faktor tersebut dicoba diperbaiki terutama aspek nutrisi (mutu
pakan) yang dapat meningkatkan ekpresi gen seperti mutu energi, protein dan mineral.
Fenomena yang menonjol pada rendahnya performans sapi Bali adalah bobot lahir
rendah dengan mortalitas tinggi dan rendahnya pertumbuhan pedet pra-sapih sebagai
akibat produksi susu yang terbatas, sehingga semakin lama ukuran tubuh sapi Bali
semakin kecil. Walaupun 'demikian, sapi Bali masih nampak bulat dan berdaging,
karena itu perbaikan mutu pakan perlu dimulai dari sapi bunting, agar anak yang
dilahirkan kerangkanya lebih besar, sehingga dapat dijadikan sebagai sumber hayati
Indonesia (bibit) untuk masa depan.
Pemberian mutu pakan jelek sangat terkait erat dengan sistem pemeliharaan
secara tradisional, dimana hijauan pakan yang diberikannya hanya bertumpu pada
rumput lokal, selain berserat kasar tinggi dan protein kasarnya rendah juga defisien Zn
mikroba rumen dan aktivitasnya dalam merombak pakan, sehingga nutrien yang
tercerna rendah. Selanjutnya dengan kecernaan yang rendah sudah pasti pasokan
nutfien ke hewan inang (sapi) juga rendah, dan bila kondisi ini berlangsung lama, maka
tidak jarang menghambat pertumbuhan dan produktivitas sapi Bali.
Sangat menghawatirkan pemberian pakan berkualitas jelek secara nasional dan
terus-menerus pada sapi Bali bunting, karena akan berpengaruh negatif terhadap produk
metabolisme rumen, rendahnya kondisi tubuh sapi calon induk, bobot lahir pedet, dan
pertumbuhannya. Dengan demikian nantinya dapat berpengaruh terhadap rendahnya
performans sapi Bali secara keseluruhan, baik yang ada di pulai Bali atau pun di
kantong-kantong produksi seperti di Kawasan Timur Indonesia lainnya. Penggunaan
leguminosa semak/pohon, konsentrat dan suplementasi seng asetat dapat dilakukan
sebagai langkah perbaikan mutu pakan, agar tercipta ekologi rumen yang kondusip dan
pasokan nutrien produk metabolisme rumen ke hewan inang semakin tinggi. Dengan
langkah ini besar harapan dapat memenuhi kebutuhan fisiologis sapi Bali, sehingga
performansnnya dapat ditingkatkan, baik sapi Bali sedang bunting, laktasi atau pun
pertumbuhan pedetnya.
Percobaan dilakukan pada 12 ekor sapi Bali bunting pertama dengan umur
kebuntingan 5-6 bulan dan rataan bobot tubuhnya 261 k- 17 kg. Percobaan in vivo
dilakukan di Desa Buruan, Gianyar, Bali, sedangkan pengamatan laboratorium
menyangkut mikroba rumen clan produks fermentasinya dilakukan di Laboratorium
Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas Peternakan Universitas Udayana (UNUD) d m Laboratorium Analitik UNUD Bukit Jimbaran.
Bahan baku ransum yang digunakan berasal dari bahan-bahan lokal seperti (1)
hijauan meliputi : rumput gajah , gamal, dan daun waru; (2) konsentrat meliputi : dedak
padi, bungkil kelapa, minyak jagung, urea; garam, superkalmiks, amonium sulfat, dan
seng asetat. Bahan-bahan ini disusun sesuai ransum perlakuan masing-masing sapi Bali
bunting dan laktasi dengan kandungan TDN = 58 - 66%, protein kasar = 12 - 18%, dan
Zn = 18 - 60 mglkg. Adapun perbedaan ransum bunting dan laktasi hanya menekankan
pad? nisbah protein mudah didegradasi dengan protein 1010s degradasi (protein "by
pass") yakni masing-masing 2: 1 dan 1 : 1.
Rancangan kelompok lengkap teracak digunakan dalam percobaan ini dengan
empat ransum percobaan dan tiga blok sebagai ulangan, dimana tiap unit percobaan
terdapat satu ekor sapi dan pembelokannya berdasarkan perbedaan bobot tubuh.
Adapun ke empat ransum perlakuan tersebut adalah A = 70% rumput gajah
+
30%garnal (Ransum Hijauan Konvensional); B = 30% ruimput gajah
+
58% gamal+
12%waru (Ransum Hijauan dengan leguminosa semaklpohon); C = 75% B
+
25%konsentrat; dan D = ransum C disuplementasi 50 mglkg Zn asetat.
Peubah yang diamati konsumsi nutrien, VFA, NH3, pH, bakteri, protozoa,
produk fermentasi, kecernaan nutrien retensi nitrogen, dan tambahanlperubahan bobot
tubuh, baik pada sapi Bali bunting atau pun laktasi. Untuk pertumbuhan pedet
meliputi: konsumsi susu dan nutrien susu serta tambahan bobot tubuh selama 17
minggu pasca lahir, sedangkan delapan minggu pertumbuhan pra-sapih (17-25 minggu
pasca lahir) meliputi konsumsi susu, nutrien sum, konsumsi ransum, nutrien ransum,
dan tambahan bobot tubuh serta kecernaan nutrien.
Peningkatan performans sapi Bali bunting sejalan dengan perbaikan mutu pakan
dan suplementasi seng asetat. Konsumsi bahan kering (BK) pada sapi Bali bunting
hampir sama, narnun dengan fermentabilitasnya yang tinggi dapat meningkatkan asam
lemak volatil (VFA) dari Ransum Hijauan Konvensional (A); Ransum Hijauan dengan
leguminosa semWpohon (B); Ransum Berkonsentrat (C); dan Ransum Berkonsentrat
yang disuplementasi seng asetat (D) dengan hasil tertinggi terdapat pada ransum D.
Walaupun produksi amonia (NH3) semakin menurun dari A - D, namun populasi
gambaran bahwa rendahnya amonia pada ransum D mungkin telah digunakan untuk
pertumbuhan bakteri yang maksimal.
. Kehadiran Zn-asetat dapat memacu pertumbuhan bakteri rumen, terutarna Bfido
bacterium, dimana bakteri ini mempunyai kemampuan memproduksi asam laktat yang
selanjutnya menjadi asam propionat. Hal ini dapat dibuktikan bahwa produk fermentasi
meningkat (asetat, propionat, dan butirat), walaupun produksi metannya pada ransum D
juga tertinggi, namun dengan propionat yang tertinggi ternyata menghasilkan efisiensi
konversi energi heksosa menjadi energi VFA tertinggi.
Proses selanjutnya pada sapi Bali bunting adalah dengan produk fermentasi
mmen yang semakin tinggi dapat meningkatkan pencernaan fermentatif atau pun
hidrolitik, sehingga kecernaan nutrien pada ransum A, B, C, dan D semakin meningkat.
Hasil kecernaan ini memberi konstribusi terhadap peningkatan nitrogen yang teretensi,
nitrogen yang dapat digunakan (NNU), serta nilai hayati protein pakan dan protein mikroba (BV), sehingga selain dapat meningkatkan tambahan bobot tubuh induk dan
bobot plasenta juga terhadap bobot lahir pedet. Kendati tambahan bobot tubuh dan
bobot plasenta berbeda tidak nyata, namun dengan bobot plasenta yang semakin
meningkat berarti dapat mentransfer nutrien lebih banyak ke fetus, sehingga nyata dapat
meningkatkan bobot lahir pedet. Hal ini memberi gambaran bahwa antara bobot
plasenta berkorelasi positif dengan bobot lahir pedet (Ft2 = 0.80; Nilai P = 0.0001).
Adapun kebutuhan energi termetabolis (ME, MJJhari) dan protein kasar (PK, kg/hari)
adalah 0.466 MJ ME dan 9.9 g PK untuk setiap kg bobot metabolis (hidup pokok); 7.76
MJ ME dan 44 g PK untuk setiap kg tambahan bobot tubuh; dan 1.93 MJ ME dan 15.1
g PK untuk setiap bulan pertambahan umur kebuntingan.
Performans sapi Bali laktasi juga meningkat searah dengan perbaikan mutu
pakan dan suplementasi Zn-asetat. Konsumsi BK ransum A, B, C, dan D hampir sama,
ini menunjukkan bahwa ransum perlakuan tidak berpengamh terhadap selera makan
sapi. Konsumsi BK ini lebih tinggi dari pada sapi Bali bunting, sebagai akibat
membesarnya fetus selama umur kebuntingan, karena itu dapat membatasi kapasitas
rurqen, sehingga akhirnya menurunkan konsumsi.
Fenomena yang sama juga terjadi pada sapi Bali laktasi seperti sapi bunting,
dimana dengan perbaikan mutu pakan ini selaim memperbaiki fermentabilitas ransum
juga dapat menciptakan ekologi rumen yang kondusip. Dalam ha1 ini diperoleh VFA
dan amonia semakin tinggi, sehingga dapat memacu pertumbuhan bakteri dengan hasil
tertinggi terdapat pada ransum berkonsentrat yang hisuplementasi Zn-asetat (D).
Walaupun kehadiran waru tidak efektif sebagai agensia defaunasi terutarna pada ransum
berkonsentrat (C) dan D, namun dengan kehadiran Zn dan sulhr yang lebih tinggi
selain dapat mengaktivasi kerja enzim-enzim pencernaan juga dapat merubah pola
fermentasi tidak seperti sapi Bali bunting, terutama pada D. Selanjutnya dengan
perubahan pola fermentasi pada sapi Bali laktasi menghasilkan asam asetat tertinggi
dengan propionat relatif lebih rendah dibanding sapi C. Hal ini membawa konskwensi
meningkatnya produksi gas metan, kendati demikian dengan VFA total dan amonianya
tertinggi dapat meningkatkan efesiensi konversi energi heksosa menjadi VFA. Hal ini
dapat memacu pencernaan pasca rumen, sehingga nutrien yang tercerna juga meningkat.
Jadi dengan meningkatnya kecernaan nutrien dapat meningkatkan retensi nitrogen,
NNU, dan BV, yang pada akhirnya rmeningkatkan produksi susu . Kebutuhan ME
(MJIhari) dan PK (kglhari) sapi Bali laktasi adalah 0.728 MJ ME dan 1.9 g PK untuk
hidup pokok; 4.393
MJ
ME dan 1.03 kg PK untuk setiap 1 kg tambahan bobot tubuh;dan 3.272 MJ ME dan 0.271 kg PK untuk produksi susu 1 kg 4%
FCM.
Walaupun kandungan nutrien susu tidak berbeda nyata antar ransum, namun
dengan produksi susu semakin tinggi ke arah sapi yang disuplementasi Zn-asetat, maka
pertumbuhan pedet selama 17 minggu pasca lahir meningkat sejalan dengan
seperti laktosa, lemak, protein dan energi susu berpengaruh 77% terhadap tambahan
bobot tubuh pedet, namun di antara nutrien tersebut laktosa peranannya tertinggi yakni
72%
( R ~
= 0.72; Nilai P = 0.0006). Selanjutnya pertumbuhan pedet selama delapan minggu pra-sapih (17-25 minggu pasca lahir) masih sangat ditentukan oleh konsumsinutrien susu daripada konsumsi ransum, dimana sumbangan efektifnya masing-masing
42% vs 21%
m2
= 0.61; Nilai P = 0.0005). Kebutuhan ME (MJhari) dan PK (g~hari)pedet pada pertumbuhan pra-sapih dapat dihitung dengan persamaan masing-masing
ME = -0.6389
+
0.0728W+
13.574G+
8.0559F dan PK = -5.1966 + 0.6607W+
198.0546+
145.5D (dimana W = bobot tubuh, G = tarnbahan bobot tubuh, dan D = bahan kering ransum yang dikonsumsi).. . .
PENINGKATAN PERFORMANS SAP1 BALI MELALUI PERBAIKAN MUTU PAKAN DAN
SUPLEMENTASI SENG ASETAT
Oleh
SENTANA PUTRA
Disertasi sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh gelar Doktor pada Program Pascasarjana
Institut Pertanian Bogor
PROGRAM PASCASARJANA lNSTlTUT PERTANlAN BOGOR
Judul Disertasi : Peningkatan Performans Sapi Bali melalui Perbaikan Mutu Pakan dan Suplementasi Seng Asetat
Nama Mahasiswa : SENTANA PUTRA
Nomor Pokok : 94521fPTK
Menyetuj ui 1. Komisi Pembimbing
Prof. Dr. Toha Sutardi, M.Sc.
- .
Ketua
-
(Prof. Dr. D. Sastradipradja) (Dr. Drh.Tuty L. Yusuf, MS.)
(Dr. Ir. Jajat Jachja, F.A., M.Agr,) Anggota
2. Ketua Program Studi Ilmu Ternak
-At!).---
(Prof. Dr. Adi Sudono, M.Sc.)
(Prof. Dr. Ketut Lana) Anggota
RIWAYAT HIDUP
Penulis dilahirkan di Desa Antiga, Manggis, Karangasem, Bali pada tanggal 17
April 1957, merupakan anak ke tiga dari empat bersaudara, dengan ibu bernama Ni N.
Seriya dan ayah N. Rentjana (almarhum). Pendidikan Sekolah dasar diselesaikan di
SD Negeri 1 Antiga pada tahun 1970; Pendidikan Sekolah Menengah Pertarna
diselesaikan di SMP Negeri Ulakan, Manggis, Karangasem pada tahun 1973; dan
Pendidikan Sekolah Menengah Atas diselesaikan di SMA Negeri 1 Singaraja, Bali pada
tahun 1976.
Pada tahun 1977 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran
Hewan dan Petemakan (FKHP) Universitas Udayana (UNUD) Denpasar, Bali dan lulus
sebagai Sarjana Peternakan pada awal tahun 1984. Selanjutnya penulis pada tahun
1990 melanjutkan pendidikan S2 yakni Magister Sains (MS) dalam bidang Ilmu Temak
pada Program Pascasarjana lnstitut Pertanian Bogor (WB) dan selesai pada tahun 1992.
Pada tahun 1994 penulis melanjutkan pendidikan S3 (Doktor) pada Program Pascasrjana
IPB dengan biaya dari Tim Manajemen Program Doktor
(TMPD)
Direktorat JenderalPendidikan Tinggi. Sejak tahun 1984 penulis mulai magang di laboratorium Nutrisi
dan Makanan Ternak dan tahun 1986 diangkat menjadi staf pengajar pada Jurusan
Nutrisi dan Makanan ~ e m a k , Fakultas Petemakan UNUD Denpasar, Bali.
Pada tahun 1984 penulis menikah dengan Dra. Ida Ayu Putu Sari dan sampai
saat ini penulis telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama Jananuraga
UCAPAN TERIMA KASIH
Puji syukur penulis haturkan kehadapan Ida Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang
Maha Kuasa atas asung kertha waranugrahaNya, sehingga penelitian dan penulisan
disertasi yang berjudul Peningkatan Performans Sapi Bali melalui Perbaikan Mutu
Pakan dan Suplementasi Seng Asetat dapat diselesaikan.
Melalui kesempatan ini perkenankan penulis menyampaikan terima kasih yang
tulus kepada Prof. Dr. Toha Sutardi, M.Sc. sebagai ketua komisi pembimbing, Prof. Dr.
Djokowoerjo Sastradipradja, Dr. Drh. Tuty L. Yusuf, MS., Dr. Ir. Jajajt Jachja, F.A.,
M.Agr., dan Prof Dr. Ketut Lana sebagai anggota komisi pembimbing, atas
pengarahan, bimbingan, dan motivasinya selama penulis melakukan penelitian dan
penyelesaian penulisan disertasi.
Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Rektor Institut pertanian Bogor
(IPB) dan Direktur Program Pascasarjana IPB atas kesempatan yang diberikan untuk
mengikuti studi Program Doktor. Kepada Rektor Universitas Udayana (UNUD) dan
Dekan Fakultas Peternakan (Fapet) UN UD disampaikan terima kasih atas ijin melanjutkan studi Doktor dan bantuan dana penelitian
.
Ucapan terima kasih jugapenulis sampaikan kepada Tim Manajemen Program Doktor (TMPD) Dirjen Dikti yang
membiayai penulis selama studi di Program Pascasarjana IPB.
Kepada Kepala Dinas Peternakan Tingkat I Propinsi Bali, Pinpinan P3Bali, dan
Bupati Kepala Daerah Tingkat I1 Kabupaten Badung, disampaikan terima kasih, atas segala bentuk batuan yang diberikan selama penelitian berlangsung. Bantuan tersebut
sangat menunjang keberhasilan penulis menyelesaikan penelitian dan penulisan
disertasi. Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kepala
laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak, Fapet UNUD dan staf serta kepala
selama penulis menganalisis beberapa peubah disertasi, sehingga disertasi ini dapat
diselesaikan.
, Kepada istri Dra. Ida Ayu Putu Sari dan ananda Jananuraga Maharddhika yang
tercinta disampaikan terima kasih dan penghargaan atas pengertian, kasih sayang dan
kesetiannya mendampingi penulis selama penelitian berlangsung dan selama proses
penyelesaian penulisan disertasi. Terima kasih dan penghargaan yang tulus juga
disampaikan kehadapan ayah (almarhum), ibu, kakak dan adik serta ayah (almarhum)
dan ibu mertua, k&k dan adik ipar yang tercinta atas bantuan materiil, sepirituil, dan
doa restunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini dengan baik. Terima
kasih juga penulis sampaikan kepada Ir. Ida Ayu Made Sukarini, M.Agr. atas kerja
samanya yang baik dalam penelitian ini. Demikian juga teman-teman serta semua pihak
yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu atas bantuan, baik dalam bentuk tenaga
atau pun dorongan moril, sehingga penelitian dan penulisan disertasi ini dapat
diselesaikan dengan baik.
Bogor, Februari 1999
DAFTAR IS1
Halaman
. . .
DAFTARTABEL xvi
. . .
DAFTARGAMB
PLR
xvii. . .
DAFTARLAMPIRAN xviii
PENDAHULUAN . . . 1 LatarBelakang . . . 1 TujuanPenelitian . . . 4
KegunaanPenelitian . . . 5
TINAJAUAN PUSTAKA . . . 6 Asal Usul Sapi Bali dan Performansnya . . . 6
Pengaruh Keragaman Hijauan Makanan Ternak terhadap
. . .
Performans Ternak 8
. . .
Pengaruh Konsentrat terhadap Performans Ternak 11
. . .
Pengaruh Defaunasi terhadap Perfonnans Ternak 12
Pengaruh Reduksi Emisi Metan terhadap Performans Ternak . . . 15
Pengaruh Suplementasi Sulfur dan Seng terhadap Performans Ternak . . . . 15
MATERI DAN METODE . . . 19
. . .
Lokasi dan Lama Percobaan 19
. . .
Sapi Percobaan 19
. . .
Ransum Percobaan 19
. . .
Rancangan Percobaan 21
PeubahyangDiamati . . . 21
. . .
AnalisisData 33
. . .
HASILDANPEMBAHASAN
Performans Sapi Bali Bunting . . .
Pendugaan Kebutuhan Energi Termetabolis dan Protein Kasar
. . .
Sapi Bali bunting
Performans Sapi Bali Laktasi . . .
Pendugaan Kebutuhan Energi Termetabolis dan Protein Kasar
. . .
Sapi Bali Laktasi
Performans Perturnbuan Pedet Sapi Bali . . .
Pendugaan Kebutuhan Energi Termetabolis dan Protein Kasar
34 34 40 41 48 49
5 5
KESlMPULAN DAN SARAN . . . 58
Kesimpulan . . . 59
Saran . . . 59
DWTARPUSTAKA . . . 60
DAFTAR TABEL
Nomor Judul tabel Halaman
1 Pengaruh dua agensia defaunasi terhadap populasi protozoa, bakteri, kecernaan nutrien,
VFA,
NH3, retensi N, dan pertumbuhan sapi perahj a m (Jalaludin, 1994) . . . 14 r
. . .
2. Komposisi bahan makanan dan nutrien
(YO)
pada ransum sapi bunting 223. Komposisi
bahan
makanan dan nutrien (%) pada ransum sapi laktasi . . . 23#engaMh-n terhadap mikroba lumen dan produk fermentasi
. . .
pada sapi W i n g 3 3
Pengarub ~rJ&ua.n terhadap nutrien tercerna, retensi nitrogen, NNU,
BV, dan$m&&zm-bobot tubuh sapi bunting . . . 38 -
KebutJlan .- apqgiME dan PK sapi bunting . . . F
4 1
Pe@.perk&im erhadap mikroba rumen dan prod& fermentasi
. . .
pada-sapi hktai 42
'Pengaruh perlakuan terhadap nutrien tercerna, retensi nitrogen, NNU, BV, tambahan bobot tubuh, dan produksi susu sapi selama 25
minggu laktasi . . . 43
Kebutuhan ME dan PK sapi laktasi . . . . . 48
10. Pengaruh perlakuan terhdap tarnbahan bobot tubuh pedet, konsumsi susu, dan nutrien susu selama 17 minggu pasca
lahir (periode menyusu) . . . 5 0
T'f,.
Pengaruh
perlakuan terhadap konsumsi nutrien susu, nutrien ransum,dan
tarnbahan bobot tubuh pedet, selama delapan minggu awalpertumbuhan pra-sapih . . . 53
22. Kecernaan nutrien (%) pada susu dan ransum yang diberikan
. . .
. . pedet sapi selama delapan minggu awal pertumbuhan pra-sapih 54
. .
. . .
13. Kebutuhan ME dan PK pedet sapi Bali selama 16 minggu menyusu 56
DAFTAR GAMBAR
Nomor Judul gambar Halaman
1. Pengaruh ransum perlakuan terhadap perubahan bobot tubuh
sapi Bali selama 25minggu laktasi pertama . . . 45
2. Pengaruh ransum perlakuan terhadap produksi susu sapi Bali
Selama 25 minggu laktasi pertama . . .
3. Pengaruh ransum perlakuan terhadap perkembangan bobot
bobot tubuh pedet sapi Bali selama 25 minggu pertumbuhan
pra-sapih . . . 5 1
DAFTAR LAMPIRAN
Nomor Judul lampiran Halaman
. . .
1
.
Konsumsi nutrien berdasarkan bahan kering pada sapi Bali bunting 692
.
Konsumsi nutrien berdasarkan bahan kering pada sapi Bali laktasi . . . 693 . Bobot tubuh sapi Bali pada saat konsepsi (melalui IB). tambahan bobot tubuh kosong (tampa plasenta dan pedet) serta bobot partus
dan plasenta pada masing-masing ransum perlakuan . . . 70
. . .
4 . Analisis sidik ragam VFA total (rnM) cairan rumen sapi bunting 70
5 . Analisis sidik ragam NH3 (mM) cairan rumen sapi bunting . . . 71
6
.
Analisis sidik ragam pH cairan rumen sapi bunting . . . 717 . Analisis sidik ragam cacahan bakteri (koVml) cairan rumen
. . .
sapi bunting 71
8
.
Analisis sidik ragam cacahan protozoa (seVml) cairan rumensapi bunting . . . 72
. . .
9 . Analisis sidik ragam protein mikroba (mg/l/jarn) sapi bunting 72
10
.
Analisis sidik ragarn asam asetat (mM) cairan rumen sapi bunting . . . 72....
1 1 . Analisis sidik ragarnasarnpr~pionat ( m . ) cairan sapi bunting . . . 7 3
12
.
Analisis sidik ragam asam butirat (mM) cairan rumen sapi bunting . . . 7313
.
Analisis sidik ragam nisbah asam asetat dengan asam propionat cairan. . .
rumen sapi bunting 73
14
.
Analisis sidik ragam produksi metan (mM) sapi 7415 . Analisis sidik ragam efisiensi konversi energi heksosa menjadi
. . .
VFA sapi bunting 74
16 .. Analisis sidik ragam bahan kering tercerna (%) ransum sapi bunting . . . 74
1 7
.
Analisis sidik ragam energi tercerna (%) ransum sapi bunting . . . 7518 . Analisis sidik ragam lemak kasar tercerna (%) ransum sapi bunting . . . 75
19 . Analisis sidik ragam protein kasar tercerna (%) ransum sapi bunting . . . 75
20
.
Analisis sidik ragam retensi nitrogen (glhari) sapi bunting . . . 762 1 . Analisis sidik ragam retensi nitrogen/konsumsi nitrogen (NPU. %)
. . .
sapibunting 76
22 . Analisis sidik ragam retensi nitrogenlnitrogen tercerna (BV. %)
. . .
sapi bunting 76
23
.
Analisis sidik ragam tarnbahan bobot tubuh (kg/ekor/hari)sapibunting . . . 77
24
.
Analisis sidik ragam bobot lahir pedet (kg). . .
7725
.
Analisis sidik ragam bobot plasenta (kg) . . . 7726
.
Peubah-peubah yang digunakan untuk menduga kebutuhan energitermetabolisme (ME. MJIhari) dan protein kasar
(PK.
kglhari)sapibunting
. . .
78. . .
27
.
Analisis sidik ragam VFA total(mM)
cairan rumen sapi laktasi 8028
.
Analisis sidik ragam NH3(mM)
cairan rumen sapi laktasi . . . 80. . .
29 . Analisis sidik ragam pH cairan rumen sapi laktasi 80
3 0 . Analisis sidik ragam cacahan bakteri (koVml) cairan rumen
. . .
sapi laktasi
3 1 .
.
Analisis sidik ragam cacahan protozoa (seVml) cairan rumen. . . sapi laktasi
3 2
.
Analisis sidik ragam protein rnikroba (mgwjarn) sapi laktasi . . .33
.
Analisis sidik ragam asam asetat(mM)
cairan rumen sapi laktasi . . .3 4
.
Analisis sidik ragam asam propionat (mM) cairan rumen sapi laktasi. .
35
.
Analisis sidik ragam asam butirat (rnM) cairan rumen sapi laktasi. . .
36
.
Analisis sidik ragam nisbah asam asetat dengan asam propionatcairan rumen sapi bunting . . .
. . .
37 . Analisis sidik ragam produksi metan (mM) sapi laktasi
3 8 . Analisis sidik ragam efisiensi konversi energi heksosa menjadi
VFAsapilaktasi . . .
39
.
Analisis sidik ragam bahan kering tercerna (%) ransum sapi laktasi. . .
40
.
Analisis sidik ragam energi tercerna (%) ransum sapi laktasi. . .
41 . Analisis sidik ragam lemak kasar tercerna (YO) ransum sapi laktasi
. . .
42
.
Analisis sidik ragam protein kasar tercerna (%) ransum sapi laktasi . . .4 3 . Analisis sidik ragam retensi nitrogen (glhari) sapi laktasi . . .
44 . Analisis sidik ragam retensi nitrogenflconsumsi nitrogen (NPU. %)
. . . sapi laktasi
45
.
Analisis sidik ragam retensi nitrogednitrogen tercerna (BV. %)46. Analisis sidik ragam tambahan bobot tubuh (kg/ekor/hari)
sapilaktasi . . . 86
47.
.
Analisis sidik ragam produksi susu segar (kglekorlhari) selama24 minggu laktasi . . . 86
48. Peubah-peubah yang digunakan untuk menduga kebutuhan energi
termetabolisme (ME, MJ/hari) dan protein kasar (PK, kglhari)
sapilaktasi . . . 87
49. Analisis sidik ragam konsumsi susu (kg BWekorhari) pada pedet
selama 17 minggu pasca lahir . . . 87
50. Analisis sidik ragam konsumsi laktosa susu (kglekorhari) pada
pedet selama 17 minggu pasca lahir . . . 88
5 1. Analisis sidik ragam konsumsi lemak susu (kg BWekorlhari) pada
pedet selama 17 minggu pasca lahir
. . .
8852. Analisis sidik ragam konsumsi protein susu (kg/ekor/hari) pada
pedet selama 17 minggu pasca lahir . . . 88
53. Analisis sidik ragam konsumsi energi susu (kglekorhari) pada
pedet selama 17 minggu pasca lahir . . . 89
54. Analisis sidik ragam bobot tubuh pedet (kg) seminggu pasca lahir
. . .
8955. Analisis sidik ragam bobot tubuh pedet (kg) pada 17 minggu
. . .
pascalahir 89
56. Analisis sidik ragam tambahan bobot tubuh pedet (kglekorhari)
selama 17 minggu pasca lahir . . . 90
57. Analisis sidik ragam konsumsi susu (kg BWekorhari) pada pedet
. . .
58. Analisis sidik ragam konsumsi laktosa susu (kgekorhari) pada pedet
selama 8 minggu pertumbuhan pra-sapih (1 7-25 minggu pasca lahir) . . . 90
59.
.
Analisis sidik ragam konsumsi lemak susu (kglekorlhari) pada pedetselama 8 minggu pertumbuhan pra-sapih (17-25 minggu pasca lahir) . . . 91 60. Analisis sidik ragam konsumsi protein susu (kg/ekor/hari) pada pedet
selama 8 minggu pertumbuhan pra-sapih (17-25 minggu pasca lahir) . . . 91
6 1. Analisis sidik ragam konsumsi energi susu (kgekorhari) pada pedet
selama 8 minggu pertumbuhan pra-sapih (1 7-25 minggu pasca lahir) . . . 9 1
62. Analisis sidik ragam konsumsi ransum (kg BWekor/hari) pada pedet
selama 8 minggu pertumbuhan pra-sapih (17-25 minggu pasca lahir) . . . 92
63. Analisis sidik ragam konsumsi bahan organik (kglekorki) pada pedet selama 8 minggu pertumbuhan pra-sapih (17-25 minggu
pasca lahir) . . . 92
64. Analisis sidik ragam konsumsi lemak kasar (kglekorhari) pada pedet selama 8 minggu pertumbuhan pra-sapih (17-25 minggu
pasca lahir) . . . 92
65. Analisis sidik ragam konsumsi protein kasar (kglekorhari) pada pedet selama 8 minggu pertumbuhan pra-sapih (17-25 minggu
pasca lahir) . . . 93
66. Analisis sidik ragam konsumsi energi bruto (kgfekorlhari) pada pedet selama 8 rninggu pertumbuhan pra-sapih (1 7-25 minggu
pasca lahir) . . . .,. . . . 93
67. Analisis sidik ragam bobot tubuh pedet (kg) pada 25 minggu
pascalahir . . . 93
68. Analisis sidik ragam tarnbahan bobot tubuh pedet (kgekorhari)
. . .
69. Analisis sidik ragam kecernaan bahan kering susu dan ransum (%)
pedet selama 8 minggu pertumbuhan pra-sapih (1 7-25 minggu
. . .
pasca lahir 94
70. Analisis sidik ragam kecernaan lemak kasar susu dan ransum (%) pedet selarna 8 minggu pertumbuhan pra-sapih (1 7-25 minggu
. . .
pascalahir 94
71. Analisis sidik ragam kecernaan protein kasar susu dan ransum (%)
pedet selama 8 minggu pertumbuhan pra-sapih (17-25 minggu
. . .
pasca lahir 95
72. Analisis sidik ragam kecernaan energi susu dan ransum (%)
pedet selama 8 minggu pertumbuhan pra-sapih (1 7-25 minggu
. . .
pascalahir 95
73. Peubah-peubah yang digunakan untuk menduga kebutuhan energi
termetabolisme (ME, MJthari) dan protein kasar (PK, kgthari)
69. Analisis sidik ragam kecernaan bahan kering susu dan ransum (%) pedet selama 8 minggu pertumbuhan pra-sapih (17-25 minggu
. . .
pascalahir 94
70. Analisis sidik ragam kecernaan lemak kasar susu dan ransum (%)
pedet selama 8 minggu pertumbuhan pra-sapih (1 7-25 minggu
. . .
pasca lahir 94
71. Analisis sidik ragam kecernaan protein kasar susu dan ransum (%) pedet selama 8 minggu pertumbuhan pra-sapih (1 7-25 minggu
. . .
pasca lahir 95
72. Analisis sidik ragam kecernaan energi susu dan ransum (%)
pedet selarna 8 minggu pertumbuhan pra-sapih (1 7-25 minggu
. . .
pascalahir 95
73. Peubah-peubah yang digunakan untuk menduga kebutuhan energi
termetabolisme (ME, MJfhari) dan protein kasar (PK, kg~hari)
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Sapi Bali bukan milik masyarakat Bali saja, melainkan milik seluruh rakyat
Indonesia sebagai sumber plasma nutfah asli Indonesia. Apabila dibandingkan dengan
sapi-sapi Bos taurus atau pun Bos indicus, sapi Bali memiliki beberapa keunggulan di
antaranya daya reproduksi dan nilai karkasnya tinggi. Menurut Soehadji (1991) daya
reproduksi sapi Bali seperti angka kebuntingan dan tingkat kelahiran cukup tinggi
masing-masing 90 dan 83%, sedangkan rataan nilai karkasnya mencapai 58%. Akhir-
akhir ini sifat-sifat keunggulan tersebut mulai dipertanyakan keberadaannya, mengingat
ukuran bobot sapi semakin kecil, bobot lahirnya rendah dengan mortalitas yang cukup
tinggi dan pertumbuhan pra-sapih yang rendah sebagai akibat rendahnya produksi susu.
Permasalahan tersebut di atas memunculkan isu nasional bahwa sapi Bali yang
ada saat ini telah mengalami dekadensi genetik, sebagai akibat adanya seleksi negatif
yakni pengurasan pejantan produktif yang berkualitas secara terur-menerus untuk
diantarpulaukan atau pun diekspor. Faktor lain yang ikut berpengaruh terhadap
fenomena tersebut adalah belum intensifnya program inseminasi buatan ( I . ) dan kurang terkontrolnya perkawinan dengan pejantan lokal, serta belum diperhatikannya
keberadaan sapi calon induk
Secara keseluruhan terjadinya permasalahan tersebut tidak dapat dilepaskan dari
penerapan sistem tradisional. Karena sistem pemberian pakan yang hanya bertumpu
pada rurnput lapangan belum mampu memenuhi kebutuhan fisiologis sapi Bali akan
nutrien (terutama protein dan mineral mikro), baik untuk hidup pokok atau pun untuk
produksi. Dengan demikian, jika kondisi fisiologis ini berlangsung dalam kurun waktu
yang lama, selain dapat menurunkan performans sapi Bali juga ekspresi gennya.
nasional di masa mendatang dengan genetik potensial yang lebih tinggi, maka
hendaknya perbaikan mutu pakan dimulai dari sejak bunting pertama.
Konsekuensi logis dari pemeliharaan sapi Bali secara tradisional adalah belum
terpenuhi kebutuhannya akan nutrien terutama energi atau pun protein. Sejalan dengan
prediksi Sutardi (1991) bahwa kebutuhan sapi Bali akan protein relatif lebih tinggi
dibanding dengan sapi jenis lain. Selain itu, jika ditinjau dari asal usulnya sapi Bali
berasal dari sapi liar (Bibos banteng) yang dalam hidupnya lebih banyak memanfaatkan
daun semaldpohon sebagai sumber pakannya. Fenomena ini sejalan dengan pernyataan
Kearl (1982) bahwa ternak yang dapat memanfaatkan 60-70% daun-daunan, maka
ternak tersebut dapat digolongkan sebagai perambah (browser). Oleh karena itu, dalam
upaya meningkatkan performans sapi Bali hendaknya berbasis pada daun-daunan lokal
yaitu leguminosa semak dan pohon sejalan dengan konsep sistem tiga strata (Nitis ef a/.,
1986). Selanjutnya Nitis (ef al., 1996) menjelaskan bahwa sapi Bali yang diberi hijauan
sistem tiga strata yakni 30% rumput (stratum 1); 45% daun semak (Stratum 2); 20%
daun pohon (stratum 3); dan 5% limbah palawija tambahan bobot tubuh pedetnya 26%
lebih tinggi daripada sapi non strata.
Pemberian hijauan leguminosa semak dan pohon, selain kandungan energinya
tinggi juga menyediakan sumber protein yang cukup, baik yang mudah didegrasi atau
I
pun 1010s degradasi dalam rumen. Daun gamal (Gliricidia sepium) dan waru (Hibiscus
tilliacius) salah satu leguminosa semak dan pohon yang dapat befingsi sebagai
sumber protein mudah didegrasi (DIP) dan 1010s degradasi
(UP)
(Sutardi, 1995).Kedua leguminosa ini perlu diatur pernberiannya agar nisbah DIPIUIP mendekati 2: 1
untuk sapi sedang bunting atau pun tumbuh (Sutardi et al., 1983) dan 1: 1 untuk sapi
laktasi (NRC, 1988). Fungsi lain yang tak kalah pentingnya dari daun waru adalah
diduga mengandung saponin seperti daun kembang sepatu (Hibiscus rosasinensis),
meningkatkan bakteri rumen, sehingga meningkatkan metabolisme rumen. Langkah ini
merupakan salah satu cara untuk perbaikan mutu pakan yang nantinya dapat diharapkan
terciptanya ekologi rumen yang kondusip dalam memacu pertumbuhan bakteri dan
aktivitas fermentasinya, shingga produk metabolisme rumen dapat dimanfaatkan hewan
inang dengan efisien.
Suplementasi konsentrat ditunjang dengan meningkatknya produksi limbah
industri pertanian seperti dedak padi dan bungkil kelapa, karena selain ketersediaannya
cukup juga dapat diharapkan sebagai sumber karbohidrat mudah terlarut dan protein
1010s degradasi. Dengan perbaikan mutu pakan ini besar harapan terbentuknya asam
lemak volatil (VFA) yang lebih banyak terutama propionat, sehingga selain sebagai
sumber energi bagi mikroba rumen juga dapat digunakan sebagai prekursor glikogen
bagi sapi induk; sebagai sumber glukosa untuk pertumbuhan fetus; dan prekursor
produksi susu. Dengan 30% suplementasi konsentrat pada sapi Bali yang pakan
dasarnya rumput menurut Nitis dan Lana (1983) tarnbahan bobot tubuhnya 76.8-297%
lebih tinggi daripada rumput saja, dengan urutan terbaik bungkil kelapa, gaplek, dan
dedak padi. Karena kehadiran konsentrat ini memperbesar peluang terbentuknya VFA
(asam propionat) lebih banyak, dengan produksi metan yang semakin sedikit (Blaxter,
1969; Orskov dan Ryle, 1990), sehingga efisiensi penggunaan energinya lebih tinggi.
Perbaikan mutu pakan untuk menekan emisi metan pada suplementasi
konsentrat tersebut juga dilengkapi dengan minyak jagung sebagai sumber aarn lemak
tidak jenuh. Kehadiran mnyak jagung ini dapat berfbngsi sebagai aseptor elektron,
dimana saat yang bersamaan H2 hasil metabolisme karbohidrat sebagai donor elektron
bereaksi membentuk asam lemak jenuh (Maczulak et al., 1981; Tillman et al., 1986).
Langkah ini menurut Abdullah et al. (1991) salah satu biomanipulasi proses nutrisi
untuk menghambat aktivitas bakteri metanogenik (Methanobacterium ruminantium),
Efisiensi biokonversi ransum yang berkonsentrat dalam rumen sangat ditentukan
oleh pertumbuhan dan aktivitas mikroba rumen, maka salah satu mineral perlu
dipqrtimbangan kehadirannya yakni sulfur (S). Karena, selain dapat memacu sintesis
mikroba rumen, juga dapat mensintesis beberapa vitamin seperti biotin dan tiamin serta
koenzim (Komsarczuk dan Durand, 1991). Kehadiarn
S
ini menurut Hunter dan Vercoe(1984) perlu disesuaikan dengan keberadaan nitrogen ransum, agar nisbahnya
mendekati 1 : 10, sehingga dapat meningkatkan kecernaan nutrien ransum. Selanjutnya
Jalaludin (1994) menyarankan menggunakan amonium sulfat, selain sebagai sumber
non nitrorgen protein (NPN) juga sebagai sumber S anorganik pada ransum
berkonsentrat, sehingga dapat meningkatkan tambahan bobot sapi FH 1.0 kglekorlhari.
Biofermentasi ransum dalam rumen dan metabolisme berikutnya di satu
sisi lebih banyak ditentukan oleh aktivitas enzim, baik dari mikroba rumen ataupun dari
sel-sel hewan inang (ternak), namun di sisi lain seng (Zn) sebagai aktivatornya yang
terdapat pada bahan makanan ternak di Indonesia kadanya relatif rendah (Little, 1986).
Sehubungan dengan itu suplementasi Zn menurut Underwood (1977) dan McDowell et
al. (1 983) sangat penting dilakukan, karena jika defisien dapat berpengaruh negatif
terhadap keseluruhan proses reproduksi pada ternak betina dari estrus, kelahiran, dan
laktasi. Kehadiran mineral Zn ini adalah sebagai metaloenzim, dimana fbngsi yang
paling menonjol adalah mengaktivasi DNA, RNA polimerase dan sintesis asam nukleat
(Lieberman dan Bruning, 1990), sehingga secara keseluruhan fbngsi fisiologis dan
keseimbangan hormonal ternak sangat tergantung dari kehadiran Zn tersebut.
Mengingat beberapa nutrien seperti laktat, asetat, dan urea sangat dibutuhkan untuk
pertumbuhan fetus (Miller et al., 1976), maka Zn yang disuplementasikan sebaiknya
dalam bentuk garam Zn-asetat.
Bertitik tolak dari permasalahan tersebut di atas, maka dengan perbaikan mutu
sapi Bali bunting akan energi dan protein, sehingga dapat meningkatkan ekologi rumen
dan produk metabolismenya, yang nantinya dapat meningkatkan bobot lahir pedet; (2)
dapat memenuhi kebutuhan sapi Bali laktasi akan energi dan protein, sehingga dapat
meningkatkan ekologi rumen dan produk metabolismenya, serta nantinya susu yang
dihasilkan meningkat pula; (3) dapat memenuhi kebutuhan pedet akan energi dan
protein, sehingga pertumbuhan pra-sapihnya juga meningkat.
Tujuan Penelitian
Bertumpu pada beberapa pemikiran tersebut di atas, rangkaian penelitian ini
bertujuan : (1) untuk meningkatkan performans sapi Bali bunting, sehingga nantinya
didapatkan peningkatan bobot lahir pedet; (2) untuk meningkatkan performans sapi Bali
laktasi, sehingga akhirnya didapatkan produksi susu yang meningkat pula; (3) untuk
meningkatkan performans pertumbuhan pedet pra-sapih; dan (4) untuk mengetahui
kebutuhan energi dan protein, baik untuk sapi bunting, laktasi, atau pun pertumbuhan
pra-sapih pedet.
Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian yang diperoleh , selain untuk pengembangan ilmu pengetahu-
an khususnya terhadap @asanah ilmu nutrisi sapi Bali, terutama menyangkut aspek
kebutuhannya akan nutrien yakni energi dan protein. Aspek lain perlu dikembangkan
dalam penelitian lain adalah aspek pemuliaan ternak, reproduksi, dan nutrisi yang
dilakukan secara terintegrasi dan berkesinambungan. Kegunaan lain yang tak kalah
pentingnya adalah sebagai bahan kebijakan bagi pemerintah melalui Direktorat
Jenderal Peternakan dalam upaya pengembangan sapi Bali di seluruh Indonsesia, baik
untuk pembibitan atau pun penghasil daging yang bermutu, khususunya Kawasan
TINJAUAN PUSTAKA
Asal Usul Sapi Bali dan Performansnya
Sapi Bali yang berkembang sampai saat ini adalah keturunan langsung dari
banteng liar (Bibos banteng) yang secara sporadis masih terdapat di Jawa Barat, Jawa
Timur, dan Kalimantan (Payne, 1970; Payne dan Rollinson, 1973). Hal ini didasarkan
pada tanda-tanda yang dimiliki sapi Bali adalah sama dengan banteng liar.
Selanjutnya setelah dilakukan penelitian terhadap golongan darah dan protein pada
populasi sapi Bali ditemukan keragaman genetik yang tinggi, karena darahnya
mengandung keturunan sapi Bos zndicus atau pun Bos taurus (Namikawa et al., 1980;
Namikawa et al., 1982; Martojo et al., 1988).
Menurut Fisher (dalam Devendra et al., 1973) kariotipe sapi Bali identik dengan
kariotipe banteng dan sapi Eropah (Bos taurus) yang terdiri dari 2n = 60 kromosom
yakni 29 pasang kromosom accrocenfric dan 2 kromosom submetacentric. Walaupun
kariotipe ke dua jenis sapi tersebut sama, namun sapi Bali bukan keturunan Bos taurus,
karena sapi jantan F1 hasil silangannya steril. Sementara hasil penelitian Namikawa dan
Widodo (1973) sapi Bali yang ada di Indonesia darahnya mempunyai kelompok
Hb,
dan kandungan Hb penotipe golongan X-nya tinggi. Ini berarti teori yang menyatakan
bahwa sapi Bali yang berkembang sampai saat ini adalah benar berasal dari banteng
liar.
Beberapa hasil penelitian tentang bobot lahir sapi Bali telah dilaporkan oleh
beberapa peneliti di antaranya, Payne (1970) menyatakan bahwa bobot lahir sapi Bali
adalah berkisar 13
-
18 kg. Dalam hasil penelitian Sumbung et al. (1978) dilaporkanbahwa rataan bobot lahir sapi Bali adalah 12.6 f 2.60 kg. Selanjutnya Darmadja (1980)
melaporkan bahwa rataan bobot lahir sapi Bali adalah 15.6 kg dengan toleransi
moyang sapi Bali) kisaran bobot lahirnya hampir sama seperti yang dilaporkan Payne
(1970) yaitu 13.5
-
18.0 kg. Dari hasil penelitian tersebut dapat dipresumsikan bahwakeragaman bobot lahir sapi Bali dominan disebabkan oleh perbedaan kondisi nutrien
induk selama kebuntingan. Sejalan dengan Gregory (1961) bahwa keragaman bobot
lahir sapi Bali, 60% dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan 40% faktor genetik.
Selanjutnya Cantet et aZ. (1988) menyatakan bahwa keragaman bobot lahir sapi Bali 36
-
65% dipengaruhi oleh urutan tahun kelahiran, umur induk, dan jenis kelamin.
Dari pernyataan dua peneliti tersebut di atas, lebih konkrit dapat dilihat pada
hasil penelitian Djagra et al. (1979) bahwa keragaman bobot lahir dan bobot sapih sapi
Bali dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya umur induk, jenis kelamin, dan
iklim. Lebih jauh dijelaskan bahwa bobot lahir tertinggi (17.8
+
1.8 kg) terdapat padakelahiran anak yang ke enam, sehingga bobot sapihnya juga tertnggi (80.5
+
17.1 kg).Hasil penelitian ini sejalan dengan laporan Holland et al. (1977) bahwa anak sapi dari
induk berumur dua, tiga, dan empat tahun berturut-turut 15,8, dan 6 persen lebih ringan
daripada anak dari induk berumur 5-8 tahun. Hal yang sama juga dilaporkan dari
beberapa peneliti bahwa umur induk berpengaruh nyata terhadap bobot lahir anaknya
(Brinks et a]., 1973; Winks et al., 1978; dan Nelson et al., 1982).
Pengaruh musim, baik musim hujan atau pun musim kemarau tidak menunjuk-
kan perbedaan yang nyata terhadap bobot lahir (Djagra et al., 1979; Abas, 1980; Liwa,
1983). Hal ini bukan disebabkan oleh lamanya musim hujan atau kemarau, akan tetapi
karena refleksinya terhadap pasokan nutrien yang hampir sama selama kebuntingan,
sehingga nutrien yang terabsorpsi ke fetus lewat plasenta induknya belum mampu
memberikan pertumbuhan yang berbeda. Lain halnya dengan bobot sapih, bahwa pada
musim hujan bobotnya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan musim kemarau yaitu
Berbicara hubungan musim dengan produksi HMT dan produktivitas ternak,
jelas produksi HMT pada musim hujan, baik kuantitas atau pun kualitasnya lebih baik
daripada musim kemarau (Nitis et al., 1986), sehingga kondisi ini dapat memacu
induknya untuk berproduksi susu lebih banyak dan lebih bermutu. Hasil penelitian ini
sejalan dengan apa yang dianjurkan oleh Gunardi (1975) agar anak-anak sapi diatur
kelahirannya yakni terjadi pada awal musim hujan saat rumput dan HMT yang lainnya
produksinya tinggi untuk menyediakan nutrien yang cukup dan berrnutu dalam
meningkatkan produksi susu induknya. Fenomena ini akan memberikan sumbangan
yang sangat berarti dalam upaya meningkatkan bobot sapih seperti apa yang
diharapkan banyak orang.
Pengaruh Keragaman Hijauan Makanan Ternak terhadap Performans Ternak
Penggunaan sumber pakan yang berasal dari hijauan saja (100%) masih dapat
meningkatkan produktivitas ternak, jika proporsinya diatur sedemikian rupa, sehingga
keseimbangan nutrien untuk kebutuhan fisiologis ternak terpenuhi. Dalam ha1 ini
hijauan makanan ternak (HMT) yang digunakan, secara makro hendaknya minimal
terdiri dari HMT sebagai sumber energi dan sumber protein yang sudah barang tentu di
dalamnya diharapkan telah mengandung beberapa mineral dan vitamin yang
dibutuhkan oleh ternak.
Nitis et al. (1994) melaporkan bahwa sapi Bali betina yang diberi HMT dari
tiga sumber yaitu rumput/leguminosa, leguminosa sernak, dan daun-daunan pohon
(sistem tiga strata = STS) pertumbuhamya lebih tinggi 80.57% pada musim hujan
dan 142.72% pada musim kemarau dibandingkan dengan non tiga strata (NTS). Lebih
jauh dijelaskan bahwa pemberian HMT STS juga berpengaruh positif terhadap
reproduksi sapi Bali betina yaitu interval siklus estrus dan siklus estrus tenang
yang diberi HMT STS dan NTS selama umur kebuntingan adalah berbeda tidak nyata
yaitu masing-masing 0.27 dan 0.23 kglekorlhari (Nitis et al., 1995). Dalam ha1 ini,
walaupun konsumsi ransum sapi yang diberi HMT STS nyata lebih tinggi daripada sapi
yang diberi HMT NTS, namun belum mampu memberi kontribusi yang nyata terhadap
tambahan bob0 tubuh. Karena kebutuhan nutrien pada sapi bunting beragam dan tinggi
sesuai prioritas kebutuhannya secara individual, baik untuk pertumbuhan induk,
perkembangan plasenta, pertumbuhan fetus dan kelenjar ambing.
Hal lain yang cukup menggembirakan pada
H M T
STS adalah adanyaketerpaduan antara HMT sumber protein yang degradasinya tinggi (gamal = Gliricidia
sepzum), HMT sumber protein "by pass" (lamtoro = Leucaena leucocephala), dan
H M T
sebagai agensia defaunasi (wam = Hibiscus tillicius). Langkah ini sejalandengan rekomendasi Sutardi et al. (1 983) bahwa campuran gamal dengan lamtoro
dapat menyediakan protein degradasinya tinggi dan protein "by pass", sehingga selain
dapat meningkatkan pertumbuhan mikroba rumen juga prestasi produksi ternak.
Sapi Bali yang diberi HMT
STS
bobot lahir pedetnya adalah 16.50 kg, sedangkansapi yang diberi HMT NTS bobot lahir pedetnya 15.80 kg; keduanya berbeda tidak nyata
(Nitis et al., 1996). Lebih lanjut dijelaskan bahwa tambahan bobot tubuh pedet STS dan
NTS yang menyusu langsung pada induknya selama 18 minggu d m 36 rninggu pasca
lahir masing-masing adalah 0.439 vs 0.270 kglekorlhari dan 0.437 vs 0.346 kg/ekor/hari.
Dengan tingginya pertumbuhan ini berdampak terhadap penurunan bobot induknya
yakni masing
-
masing 0.175 vs 0.147 kgtekorfhari dan 0.055 vs 0.037 kg/ekor/hari.Hal ini memberi gambaran bahwa penurunan bobot tubuh tersebut selama laktasi sebagai
akibat produksi susu sapi yang diberi HMT
STS
relatif lebih tinggi daripada sapi yangdiberi HMT NTS, dimana kondisi fisiologis ini terrefleksi pada tingginya pertumbuhan
pra-sapih pedet. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Subhagiana (1998) bahwa
yang diberi HMT STS dan NTS selama umur kebuntingan adalah berbeda tidak nyata
yaitu masing-masing 0.27 dan 0.23 kglekorlhari (Nitis et al., 1995). Dalam ha1 ini,
walaupun konsumsi ransum sapi yang diberi HMT STS nyata lebih tinggi daripada sapi
yang diberi HMT NTS, namun belum mampu memberi kontribusi yang nyata terhadap
tarnbahan bob0 tubuh. Karena kebutuhan nutrien pada sapi bunting beragam dan tinggi
sesuai prioritas kebutuhannya secara individual, baik untuk pertumbuhan induk,
perkembangan plasenta, pertumbuhan fetus dan kelenjar ambing.
Hal lain yang cukup menggembirakan pada HMT STS adalah adanya
keterpaduan antara HMT sumber protein yang degradasinya tinggi (gamal = Gliricidia
sepium), HMT sumber protein "by pass" (lamtoro = Leucaena leucocephala), dan
HMT sebagai agensia defaunasi (waru = Hibiscus tillicius). Langkah ini sejalan
dengan rekomendasi Sutardi et al. (1983) bahwa campuran gamal dengan lamtoro
dapat menyediakan protein degradasinya tinggi dan protein "by pass", sehingga selain
dapat meningkatkan pertumbuhan mikroba rumen juga prestasi produksi ternak.
Sapi Bali yang diberi HMT STS bobot lahir pedetnya adalah 16.50 kg, sedangkan
sapi yang diberi HMT NTS bobot lahir pedetnya 15.80 kg; keduanya berbeda tidak nyata
(Nitis et al., 1996). Lebih lanjut dijelaskan bahwa tarnbahan bobot tubuh pedet STS dan
NTS yang menyusu langsung pada induknya selama 18 minggu dan 36 minggu pasca
lahir masing-masing adalah 0.439 vs 0.270 kglekorkari dan 0.437 vs 0.346 kglekorlhari.
Dengan tingginya pertumbuhan ini berdampak terhadap penurunan bobot induknya
yakni masing
-
masing 0.175 vs 0.147 kgtekorlhari dan 0.055 vs 0.037 kglekorlhari.Hal ini memberi gambaran bahwa penurunan bobot tubuh tersebut selama laktasi sebagai
akibat produksi susu sapi yang diberi HMT STS relatif lebih tinggi daripada sapi yang
diberi HMT NTS, dimana kondisi fisiologis ini terrefleksi pada tingginya pertumbuhan
pra-sapih pedet. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Subhagiana (1998) bahwa
10
tubuhnya selama laktasi relatif lebih tinggi daripada kambing tingkat produksi susu
rendah.
.
Penggunaan nutrien pada sapi sedang laktasi diprioritaskan untuk produksi susu,yang mana jika aktivitas metabolisme kelenjar ambing semakin tinggi, berarti sebagiai
cerminan pasokan nutrien yang cukup (Mepham, 1976; Collier, 1985). Sehubungan
dengan itu kebutuhan nutrien sapi laktasi meningkat sejalan dengan peningkatan produksi
susu. Holmes dan Wilson (1984) menyatakan bahwa pada awal laktasi produksi susu
meningkat dengan cepat dan mencapai puncak laktasi pada minggu ke tiga sampai ke
delapan setelah melahirkan. Pada sisi yang lain, secara fisiologis selera rnakan dan
tingkat konsumsi bahan kering (BK) sampai 18%, terutama selama tiga minggu pertama
setelah melahirkan (Garmsworthy, 1988). Dengan demikian, untuk memenuhi kebutuhan
ternak akan nutrien sebagai prekursor sum, maka ternak akan memobilisasi cadangan
nutrien tubuhnya seperti lemak, protein, dan mineral (Sutardi dan Djohari, 1976; Andrew
et a]., 1990). Berangkat dari kondisi fisiologis ini cukup rasional terjadinya mobilisasi
cadangan nutrien tubuh ternak berdampak pada penyusutan bobot tubuhnya.
Glukosa merupakan metabolit utama yang digunakan oleh kelenjar ambing untuk
sintesis susu, yang mana ha1 ini nampak jelas bahwa laju serapannya hampir dua kali
lebih besar dari keluarannya pada laktosa susu (Annison et al., 1974). Selanjutnya
glukosa yang diambil dari kelenjar ambing oleh sel-sel alveoli menurut Waghorn dan
Baldwin (1984) sekitar 88% digunakan untuk sintesis gula susu (laktosa), sedangkan 12%
sisanya dipakai untuk oksidasi, pembentukan alfa gliserol fbsfat dan sintesis komponen
susu lainnya. Pada kondisi mobilisasi nutrien yang baik, maka kebutuhan glukosa dalam
sintesis laktosa susu dapat dipenuhi glukoneogenesis, terutama dari propionat dan asam
amino.
Jadi dengan peningkatan glukoneogenesis akan diikuti peningkatan penyerapan
dari jaringan adipose (Vernon, 1988). Sehubungan itu jika mobilisasi nutrien tubuh
berlangsung terlalu lama, maka ternak sulit memperbaiki kondisi tubuhnya selama
laktasi. Karena itu perbaikan mutu pakan hendaknya mulai dilakukan pada saat ternak
bunting, selain dapat menumbuhkan dan meperbanyak sel-sel sekretori (alveoli) kelenjar
ambing juga dapat memasok prekursor susu yang lebih banyak saat ternak laktasi.
Pengaruh Konsentrat terhadap Performans Ternak
Penggunaan biji-bijian (konsentrat) dalam ransum memegang peranan penting
dalam upaya meningkatkan produksi asarn propionat pada biokonversi pakan dalam
rumen. Secara alami dengan peningkatan produksi asam propionat tersebut cenderung
menurunkan produksi energi yang terbuang dalam bentuk metan (Blaxter, 1969; Tillman
et al., 1986; Orskov dan Ryle, 1990). Lebih lanjut dijelaskan bahwa dengan semakin
tingginya asam propionat, maka prekursor pembentuk glikogen semakin banyak,
sehingga dapat meningkatkan laju pertumbuhan ternak. Suplementasi konsentrat pada
tingkat 30% saja pada pakan dasar rumputljerami padi atau HMT yang lainnya sudah
dapat meni