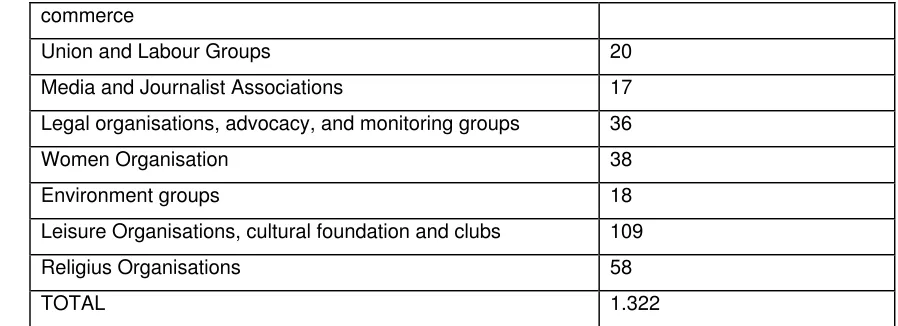POLITIK HAK ASASI MANUSIA DAN TRANSISI DI
INDONESIA
Sebuah Tinjauan Kritis
Politik Hak Asasi Manusia dan Transisi di Indonesia: Sebuah Refleksi Kritis
© 2008 ELSAM
Editor Bahasa: Erasmus Cahyadi
Editor Isi: Eddie Sius Riyadi
Cetakan Pertama: Agustus 2008
Semua penerbitan ELSAM didedikasikan kepada para korban pelanggaran hak asasi manusia, selain sebagai bagian dari usaha pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.
Penerbitan ini dimungkinkan atas kerja sama antara ELSAM dan ICTJ Jakarta
Penerbit:
ELSAM – Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
Kata Sambutan Agung Putri
Saudari-saudara, warga republik yang kami hormati.
Dalam rangka mendirgahayukan momen peringatan hari berdirinya Lembaga Studi dan
Advokasi Masyarakat (ELSAM) yang ke-15, di antara pelbagai kegiatan seremonial yang
konvensional maupun progresif, ELSAM menerbitkan dua buku. Buku yang pertama,
yang ditulis oleh Robertus Robet, mengangkat sebuah subjek khusus dan besar yang
fenomenal dalam lebih dari dua dekade di pelbagai belahan dunia dan satu dekade di
Indonesia, yaitu “keadilan transisional” (transitional justice). Sebenarnya, ELSAM telah
banyak mempublikasikan subjek ini sebelumnya dalam seri buku bertajuk “seri
transitional justice” yang kurang lebih terdiri dari 8 judul, jurnal DIGNITAS (dua edisi),
buletin ASASI, dan pelbagai briefing paper dan position paper. Yang membedakan buku
yang ditulis Robertus Robet dibanding beberapa terbitan kami sebelumnya adalah bukan
sekadar soal perspektif yang digunakan, tetapi terutama soal penempatan posisi ELSAM
di dalamnya.
Dari segi perspektif, Robet melihat persoalan transisi politik bukan sebagai suatu
keniscayaan demokratisasi melainkan sebuah kontingensi. Kontingensi ini tampak bukan
sekadar dalam pertarungan Realpolitik melainkan juga dalam kontestasi gagasan
normatif. Karena itu, politik hak asasi manusia juga bersifat kontingen. Dalam
kontingensi seperti itulah ELSAM mau tidak mau dengan segala daya dan
kemampuannya berupaya memainkan perannya. Peran itu terasa sulit dilakoni di samping
karena realitas Realpolitik baik di tingkat birokrasi dan mesin politiknya maupun di
tingkat civil society yang tidak terkonsolidasi dengan baik, juga karena pertarungan
gagasan itu – tidak seperti di Afrika Selatan dan Amerika Latin – kurang didukung oleh
Buku kedua, yang ditulis oleh Abdul Manan, sebenarnya dapat dilihat sebagai sebuah
biografi ELSAM. Secara umum, buku ini tidak berkisah tentang pergulatan “batin”
ELSAM tetapi lebih menyorot pada beberapa gagasan-gagasan, program-program dan
agenda besar yang diusung ELSAM, yang secara signifikan berkontribusi pada
perkembangan demokrasi, penegakan keadilan, dan pengakuan terhadap hak asasi
manusia di Indonesia. Terlepas dari berbagai tantangan dan hambatan yang dijumpai
Elsam dalam pergulatannya mempromosikan HAM, buku ini mengangkat beberapa
pengalaman faktual tentang keberhasilan ELSAM dalam advokasi kasus-kasus
pelanggaran HAM di Indonesia, advokasi kebijakan, dan penyelenggaraan pendidikan
publik berupa pelatihan dan kursus hak asasi manusia bagi para human rights defenders.
Tidak kurang dari itu, buku kedua ini juga menyoroti soal peran ELSAM dalam
menginisiasi, mendukung, meneruskan, dan merawat beberapa gagasan besar dan penting
seperti gerakan studi hukum kritis dan kaitannya dengan gagasan “negara hukum
demokratis” (rule of law), hak atas penentuan nasib sendiri (right to self-determination)
dan hak-hak masyarakat adat, keadilan transisional (termasuk di dalamnya adalah soal
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi).
Apa maksud dari penerbitan kedua buku tersebut? Lebih dahulu lagi, apa maksud kita
merayakan hari jadi ELSAM? Bukanlah karena kelatahan kita melakukan ini, melainkan
karena kita mau sejenak memetik momen kontemplatif dan reflektif di tengah banalitas
aksi keseharian kita. Peringatan hari lahir adalah momen kultural untuk merenungi
kebermaknaan diri dan merebut kembali otentisitas yang sempat menguap bersama
keringat aksi kita. Sejarah perdaban berkisah – bahkan sampai pada zaman audiovisual
sekarang ini – bahwa tidak ada hal lain yang lebih membawa kita ke kontemplasi tentang
makna kehadiran kita di dunia ini ketimbang berenang dalam arus kata-kata. Biarkan kata
itu menghampiri kita, dan sejenak berhentilah kita berkata-kata. Biarkan kita diam,
jangan ada kata terucap. Biarkan kata-kata itu yang berkata.
Demikianlah. ELSAM bersama teman-temannya mau merayakan hari lahir itu dalam
keheningan, lalu kemudian mendengarkan untaian kata dari kedua buku tersebut. Seorang
kata-kata dari sebuah buku menghampirinya bahkan menyerbunya, lalu tiba giliran dia untuk
menilai, merenung, mengkritik, merekomendasikan, meniati, dll. Pembaca yang sejati
adalah seorang yang selalu memposisikan dirinya sebagai “sang pemula” dalam
menghadapi sesuatu. Ketertarikannya adalah sensasi ketertarikan sang pemula.
Ketertarikan sang pemula adalah ketertarikan tanpa beban, tanpa pretensi, tanpa praduga,
tanpa penghakiman.
Saudari-saudara sesama warga republik mungkin sudah memiliki prapengetahuan tentang
ELSAM, termasuk gagasan-gagasannya, program dan agendanya, kekurangan dan
kelebihannya. Tetapi, bersikap sebagai “sang pemula” akan membawa Anda pada sebuah
realitas lain yang mungkin tidak akan pernah Anda dapatkan kalau Anda sudah selalu
memiliki prapengetahuan dan praduga. Sikap sang pemula adalah sikap yang kita
butuhkan sekarang ini untuk membangun sebuah konsolidasi masyarakat sipil untuk
kembali menegakkan dan merebut kembalinya politik. Sikap sang pemula adalah sikap
sang demokrat sejati, sang republikan berkeutamaan, seorang negarawan yang handal dan
setiawan.
Akhir kalam, semoga kehadiran kedua buku yang diterbitkan dalam rangka peringatan
hari lahir ELSAM yang ke-15 ini menggugah kita untuk sejak saat ini saling “hadir”
sebagai “sang pemula” yang otentik, penuh ketertarikan, penuh pesona, dan penuh
ketakterdugaan. Republik ini sudah muak dengan banalitas. Republik ini merindu
agen-agen progresif, penuh pesona, dan kreatif. Semoga.
Jakarta, 14 Agustus 2008
Dra. Agung Putri, M.A.
Kata Sambutan Asmara Nababan
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, biasa disingkat ELSAM, kami dirikan 15
tahun yang lalu dalam semangat untuk turut memperjuangkan dan mencapai visi
terciptanya masyarakat dan negara Indonesia yang demokratis, berkeadilan, dan
menghormati hak asasi manusia. Visi tersebut masih sangat relevan hingga sekarang,
karena meskipun rejim otoriter telah diganti dengan rejim demokrasi namun berbagai
ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia masih terus berlangsung, bahkan
pelanggaran berat hak asasi manusia masa lampau tidak atau belum dapat diselesaikan.
Untuk memperjuangkan dan mencapai visi tersebut, kami telah merumuskan misi sebagai
sebuah organisasi non-pemerintah (ornop) yang memperjuangkan hak asasi manusia, baik
hak sipil, politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya secara tak terpisahkan. Misi
ini dilakukan melalui serangkaian program dan tindakan yang saling berkaitan dan
berkesinambungan, muali dari riset, pelatihan, pengembangan jaringan, hingga advokasi
kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dialami masyarakat dan, tentu saja, kebijakan
publik yang berdampak terhadap hak asasi manusia, dalam 15 tahun terakhir ini.
Dalam rangka perayaan ulang tahun ELSAM yang ke-15, sekaligus bersamaan dengan
peringatan 10 tahun reformasi, juga 100 tahun kebangkitan nasional dan 63 tahun
kemerdekaan Indonesia, serta 60 tahun Deklarasi Universal HAM, kami menerbitkan
buku yang merekam ideal yang kami perjuangkan serta bagaimana pengalaman ELSAM
dalam memperjuangkannya. Tentu maksud dari buku ini tidak untuk gagah-gagahan,
namun jauh melampaui itu semua, yang utama kami maksudkan tetap sebagai salah satu
usaha berkontribusi bagi gerakan hak asasi manusia di Indonesia. Melalui buku ini, kami
bermaksud berbagi wawasan dan pengalaman ELSAM dalam memperjuangkan hak asasi
memaparkan berbagai masalah-masalah, peluang, tantangan, serta hambatan yang
dihadapi dalam kurun 15 tahun dalam memajukan dan melindungi hak asasi manusia.
Dengan rasa gembira kami menyambut penulisan dan penerbitan buku ini, yang telah
merespon dan menjawab maksud kami untuk berbagi wawasan dan pengalaman tersebut.
Apa yang ingin kami bagikan ini ditulis dan diterbitkan dalam dua buku yang berbeda
namun saling berhubungan. Kedua buku ini ditulis oleh penulis yang berkomitmen dan
dari luar ELSAM, untuk mendukung objektivitas, namun dengan tetap memanfaatkan
dokumen-dokumen resmi ELSAM serta mewawancarai sejumlah pihak, khususnya dari
lingkungan para pendiri, pengurus, dan aktivis ELSAM, selain memanfaatkan informasi
dari media massa serta pemerhati ELSAM.
Buku pertama, berjudul “Politik Hak Asasi Manusia dan Transisi di Indonesia” ditulis
oleh Sdr. Robertus Robet, aktivis muda yang energik sekaligus sekretaris jendral
Perhimpunan Pendidik Demokrasi (P2D). Buku ini merekam ideal yang diperjuangkan
ELSAM dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat,
khususnya yang terjadi di masa lalu, secara berkeadilan dalam konteks masa transisi
politik pasca-Soeharto. Buku kedua, berjudul “Demi Keadilan: Catatan 15 Tahun Elsam
Memperjuangkan HAM” ditulis oleh Sdr. Abdul Manan, wartawan muda penuh
komitmen sekaligus sekretaris jendral Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Buku ini
merekam pengalaman ELSAM sebagai sebuah ornop yang memperjuangkan hak asasi
manusia di Indonesia dengan berbagai problem dan tantangan yang dihadapi, dari masa
pendiriannya hingga kini, sejak dominannya wacana pembangunan di bawah rejim
otoriter hingga reformasi dan transisi demokrasi.
Kami berterima kasih kepada Sdr. Robertus Robet dan Sdr. Abdul Manan yang telah
menjawab dan merealisasikan maksud kami dengan meluangkan waktu – dalam berbagai
kesibukannya – serta perhatian dan komitmennya bagi penulisan kedua buku yang sangat
berharga ini. Juga haturan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah
Akhir kata, kami berharap kedua buku ini dapat berguna bagi para pembaca dan
mencapai maksud kami untuk berbagi wawasan dan pengalaman dalam upaya kita
bersama untuk memperjuangkan hak asasi manusia demi mencapai Indonesia yang lebih
beradab, demokratis, dan berkeadilan.
Selamat membaca.
Jakarta, 17 Agustus 2008
Asmara Nababan
Daftar Isi:
Kata Sambutan
Daftar Isi
Pendahuluan: Politik Hak Asasi Manusia dan Emansipasi
Bab 1: Relasi antara Negara dan LSM dan Fragmentasi Keagenan
Pengantar
Asal Usul dan Mistifikasi
Diskursus Normatif
Fragmentasi dan Pergeseran Keagenan Politik
Penutup: Apa yang Tersisa?
Bab 2: Kritik Atas Logika Transisi di Indonesia
Pengantar
Pembakuan Transisi yang Mematikan Politik
Demokrasi sebagai Perjumpaan yang Partikular dan Universal
Kondisi-Kondisi Diskursif Hak Asasi Manusia di Indonesia
Batas-Batas Ekuivalen Politik
Kesimpulan
Bab 3: Ketegangan dan Dinamika dalam Diskursus Politik Transisi
Pengantar
Akar Kekejaman: Munculnya Negara Otoritarian
Konfigurasi Politik Wacana KKR
Menolak KKR: Mengharapkan Ada Eichmann di Jakarta?
Penutup
Pendahuluan
Sejarah Kekerasan Orde Baru
Pertarungan Memperebutkan Masa Silam di Era Pasca-Orde Baru
Masa Depan Indonesia ada di Masa Lalu
Pendahuluan:
Politik Hak Asasi Manusia dan Emansipasi
Ada paradoks dalam perkembangan hak asasi manusia belakangan ini. Paradoks itu
tampak dari dua kecenderungan yang sepertinya saling menihilkan. Di satu sisi, orang
mengakui kemajuan-kemajuan dalam legalisasi norma-norma serta instrumen hak asasi
dengan berbagai ratifikasi konvenan hak-hak sipil dan politik serta kovenan hak-hak
ekonomi, sosial dan budaya. Juga diakui makin berkembangnya diskursus mengenai hak
asasi itu sendiri yang diikuti dengan intensitas yang makin tinggi untuk membasiskan
segala urusan di bawah payung hak. Selain itu, pada saat yang sama seiring dengan
menguatnya isu hak, praktik politik juga secara perlahan mulai lebih berorientasi pada
demokrasi dan cara-cara damai, sebagaimana terlihat dalam isu “reformasi” berbagai alat
represi Negara serta efisiensi birokrasi. Namun demikian, di sisi yang lain, pada saat yang
sama makin banyak juga orang yang resah dengan meluasnya berbagai bentuk konflik
dalam masyarakat, intoleransi, dominasi dan pernyataan kebencian di ruang publik serta
ketidakpuasaan sejumlah korban atas penyelesaian kejahatan kemanusiaan di masa lalu.
Ketidakpuasaan ini juga bisa ditambah dengan kenyataan bahwa di saat kita menikmati
kebebasan sipil dan demokrasi, pada saat yang sama kerja-kerja lembaga HAM semacam
Komnas-HAM, misalnya, dianggap lebih buruk ketimbang kerja lembaga yang sama di
masa politik otoritarian. Demokrasi tidak hanya menginstalasikan berbagai kemajuan,
pada saat yang sama – di atas kemajuan itu – ia juga mentransparansikan berbagai
persoalan dalam perjuangan dan pelembagaan hak asasi. Demokrasi telah merelatifkan
Dulu, di masa otoritarianisme, hak asasi – dalam hal ini terutama hak kebebasan politik –
merupakan isu paling subtansial. Dengan itu, di bawah legitimasi melawan
otoritarianisme, kita mempunyai kebiasaan untuk mempersatukan hak asasi dan
demokrasi menjadi satu kesatuan. Itu terjadi karena memang secara konkret keduanya
absen dalam kepolitikan otoritarianisme, sehingga mempersatukan keduanya dalam satu
nafas tuntutan perjuangan sebagai imajinasi politik menjadi relevan untuk menggantikan
otoritarianisme.
Setelah rejim otoritarian runtuh, demokrasi menjadi arena di mana segala norma, nilai
dan ideologi diinstalasikan di atasnya. Akibatnya, di jaman demokrasi ini, hak asasi
secara normatif telah dipisahkan dengan demokrasi dan direlatifkan setidaknya dengan
isu hak-hak yang lain kalau bukan oleh ideologi-ideologi politik yang relatif “baru”.
Pemisahan ini kemudian juga diikuti dengan pemisahan aktor-aktor pengusungnya; dulu
lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan lembaga advokasi serta gerakan mahasiswa
dianggap sebagai satu-satunya tiang penyangga civil society, tetapi sekarang orang
berbicara mengenai partai dan komisi-komisi sebagai tiang utama perjuangan
kepentingan. Ini diikuti dengan makin banyaknya orang-orang yang dulunya aktivis hak
asasi manusia beralih profesi dan “naik kelas” menjadi aktivis partai dan anggota di
komisi-komisi.
Keadaan ini memperlihatkan satu kecenderungan asimetris yakni bahwa, di satu sisi,
sebagai imajinasi emansipasi yang berjasa mendobrak politik otoritarian, hak asasi terus
dianggap sebagai nilai perjuangan substantif, sementara pada arah yang lain, seiring
dengan penjamakan kekuasaan dalam demokrasi, berbagai bentuk pengelolaan dan
peralatan pengorganisasiannya justru semakin terfragmentasi. Dengan kata lain, dewasa
ini terjadi diskrepansi yang mendalam antara imajinasi esensial hak asasi dengan cara
memperjuangkannya. Diskrepansi inilah yang menghasilkan suatu keadaan yang
membingungkan dalam hak asasi kita dewasa ini: semakin banyak ayat-ayat HAM
diakomodasi, semakin kuat pula ketidakpuasaan orang terhadap kondisi perlindungan dan
Dalam situasi paradoksal ini, banyak pejuang hak asasi bersikap gamang sehingga sering
kali mereka mengambil sikap yang sama dengan berbagai kelompok yang sejak dulu
memang telah bersikap sinis terhadap demokrasi. Kekecewaan para korban dan penggiat
advokasi terhadap keadaan seperti itu membawa mereka kepada semacam tuduhan
fatalistik bahwa demokrasi dan kebebasan bukan lain hanya sejenis “alat” saja dari
kepentingan borjuasi asing. Ditambah dengan keadaan di mana Negara relatif lemah,
sementara lembaga judikatif dan legislatif dipenuhi oleh korupsi, sinisme terhadap
demokrasi dengan gampang diarahkan menjadi kebencian terhadap demokrasi. Di sini
para aktivis HAM dengan gampang berpotensi menjadi satu deret dengan para
pendukung Soeharto dan kaum fundamentalis. Orang terperangkap dalam suatu keadaan
"memaki-maki demokrasi” sambil melupakan bahwa ruang yang dipakai untuk memaki
itu adalah buah dari demokrasi. Dengan kata lain, dalam praktik dan pengalaman saat ini
di Indonesia kita menemukan adanya kebingungan yang mengarah kepada destruksi
akibat pemisahan antara hak asasi dengan demokrasi.
Di titik ini – untuk menghindari kekecewaan dan destruksi yang lebih parah – kita perlu
membangun kesadaran yang baru, tidak hanya mengenai makna yang terpisah-pisah dan
khusus antara demokrasi dan hak asasi, tetapi juga tentang praktik dan konsepsi yang
menjembatani keduanya yakni: politik. Persoalan ini dapat dirumuskan dalam satu
formulasi sebagai: bagaimana politik hak asasi dijalankan dalam tatanan demokrasi?
Hak asasi manusia, sebagaimana kita mengerti dari perjuangannya sepanjang sejarah –
baik perjuangan dalam arti praktik advokasi “non-legal” sehari-hari dalam wujud
perlawanan para korban maupun dalam arti legaliasasi dan diplomasinya – pada dasarnya
bukan lain adalah imajinasi universalitas yang tanpa batas mengenai keadilan dan
martabat manusia. Ia bisa dirumuskan dalam hukum, pasal dan ayat-ayat, namun ia tidak
akan pernah selesai dan terpuaskan dalam “fullness” melalui ayat-ayat, konvensi dan
diplomasi itu. Ia akan terus berkembang seiring dengan tuntutan dan perilaku dari jaman
ke jaman. Sementara demokrasi bukan lain adalah fasilitas yang memberikan
kemungkinan bagi segala nilai dan imajinasi untuk mengungkapkan dirinya: baik
hak asasi dan demokrasi itu sendiri. Dengan demikian, di dalam demokrasi, hak asasi
memang memiliki segi-segi substansial, namun di sisi yang lain ia juga tetap merupakan
“contested political imaginary” yang bersifat “cair” dan tetap harus berhadapan dengan
musuh-musuhnya sendiri.
Di titik ini, untuk “mengamankan” hak asasi, kita membutuhkan pandangan dan konsepsi
yang lebih fundamental tentang hak asasi dan politik. Selama ini dalam paraktik dan
kebiasaan lama, kita selalu memandang hak asasi manusia hanya sebatas sebagai hukum
semata-mata. Kita biasanya melupakan basis dan pengandaian utama hak asasi manusia
yakni politik itu sendiri.
Pentingnya politik dalam hak asasi manusia dapat dilihat dalam logika fungsional hak
asasi manusia itu sendiri. Hak asasi dapat berfungsi sebagai hak asasi hanya apabila ia
memenuhi prasyarat yakni bahwa pertama secara normatif ia bersifat fundamental dan
universal; kedua, ia berada dalam jaminan suatu institusi politik umum; ketiga, ia menjadi
bagian dari sistem hukum institusi kenegaraan itu. Artinya, hak asasi selalu bertautan
dengan idealisasi, negara dan proses kewargaan di dalamnya. Singkatnya, hak asasi
manusia selain berdiri sebagai norma universal, ia juga mesti selalu dipikirkan dengan
mengandaikan adanya kapabilitas Negara dan kepolitikan umum yang dinamis dan
mendukungnya, serta politik dan hukum kewargaan yang progresif baik dalam rupa
partisipasi warga maupun dalam rupa akomodasi dalam konstitusi. Tanpa ketiga unsur
ini, jelas hak asasi akan mandeg. Hak asasi tanpa politik dan citizenship tidak akan
pernah berfungsi menjadi hak asasi.
Hak-hak kaum minoritas misalnya, sebelum ia dikenal melalui normativitasnya saat ini,
pada mulanya ia berakar dalam perjuangan emansipasi kelompok-kelompok kulit
berwarna di berbagai belahan dunia dalam menghadapi praktik-praktik imperialisme,
perbudakan serta rasisme dan kebijakan yang diskriminatif. Begitu juga hak-hak kaum
buruh yang berakar dalam perjuangan persamaan dan kesejahteraan serta pergolakan
revolusioner terutama di Eropa menjelang dan dalam masa Revolusi Industri. Hak-hak
negara juga memiliki akar yang panjang dalam sejarah perjuangan dan revolusi di
negara-negara terutama Perancis. Sementara hak-hak sipil dan politik yang lebih terperinci
mengenai jaminan bebas dari ancaman siksaan, penghancuran kebudayaan, memiliki akar
yang kuat dalam trauma Holocoust selama Perang Dunia II.
Akar kejadian dari kemunculan hak-hak itu memang kini menjadi sejarah, namun
demikian meski secara tekstual ia telah dirumuskan sebagai hak, persoalan-persoalan
dalam pemenuhan dan perjuangan untuk mencapainya masih terus terjadi di berbagai
belahan lain di muka bumi, bahkan di Negara-negara maju di mana hak-hak itu sendiri
pernah secara gemilang dilahirkan. Di Amerika Serikat, misalnya, meski ia merupakan
tempat di mana beragam hak-hak kebebasan dijunjung tinggi dan dirumuskan, tidak
berarti sekarang rakyatnya tidak memerlukan lagi perjuangan hak asasi. Meluasnya peran
dan kontrol Negara dalam kehidupan sipil belakangan ini menunjukkan bahwa Negara itu
pun masih mempunyai masalah dan rakyatnya tetap perlu memperjuangkan
pendirian-pendirian yang fundamental atas kebebasannya. Dengan kata lain, sekali lagi, kita mesti
menyadari bahwa hak asasi bisa menjadi hak asasi manusia hanya dengan mengandaikan
suatu perjuangan politik.
Begitupun dalam kasus “reformasi” dan demokrasi di Indonesia, hak asasi tidak akan
berhenti atau “penuh” hanya karena rejim Soeharto sudah dijatuhkan, ia juga tidak akan
menjadi lebih mudah setelah demokrasi mekar. Ini tentu saja berakar dari kenyataan
bahwa hak asasi itu sendiri memang adalah imajinasi yang tiada habis-habisnya, yang
sama tak terbatasnya dengan harapan dan cita-cita manusia mengenai good life dan good
society. Selain itu adalah fakta bahwa di dalam demokrasi itu juga dimungkinkan
tumbuhnya kekuatan-kekuatan politik yang beraneka ragam, menghasilkan lawan-lawan
dan tantangan baru bagi hak asasi sendiri. Di titik ini, menjadi penting untuk menghindari
segala godaan untuk puas pada kehadiran bebagai bentuk pembakuan hak asasi ke dalam
hukum dan terikat pada modus-modus institusionalisasinya yang lama.
Di sini menjadi beralasan bagi buku ini untuk memulai sebuah upaya membuka
dengan mengungkapkan bagaimana aktor utama hak asasi dan demokrasi terbentuk
secara diskursif dalam suatu kepolitikan yang dinamis. Dengan menjelaskan bagaimana
“LSM” yang selama ini mengklaim dirinya pelopor juga ternyata terus berubah dan
dikenai relasi serta kontradiksi dari jaman ke jaman, maka diharapkan para aktivis LSM
sekarang bisa memahami dirinya sebagai produk dari suatu sejarah dan peristiwa politik.
“Citra diri” yang dimiliki yaitu sebagai pejuang juga terus berubah dan bergerak ke
berbagai arah sebagaimana tampak dalam pergeseran fungsi-fungsi keaktoran dan
keagenan sekarang. Menyadari dan berkehendak untuk mengubah dunia di luar sana
harus juga diikuti kesadaran bahwa “aku” sendiri terus berubah. Paparan ini tidak
dimaksudkan untuk mendorong suatu perelatifan yang mengarah pada oportunisme
politik bagi LSM-LSM, melainkan untuk memberikan dasar pertimbangan baru bagi
kemungkinan pembentukan, rekonstruksi bagi model-model pengorganisasain baru yang
lebih memadai.
Upaya ini dilanjutkan dalam bab dua buku ini yang memberikan semacam refleksi
teoretis melalui kritik terhadap paradigma transisi yang konvensional. Bab mengenai
“kritik terhadap logika transisi” bermaksud untuk menunjukkan kekeliruan dalam
paradigma perubahan di Indonesia yang terlalu mengandalkan model dan trajektori yang
baku. Pembakuan dalam skenario-skenario perubahan yang “objektif” ini mengakibatkan
keterbatasan imajinasi dalam perubahan sekaligus mematikan aspirasi perubahan yang
luas dan tak terbatas ke dalam skema-skema hukum dan institusi formal belaka. Buku ini
juga melihat adanya kemungkinan bahwa perubahan yang diskematisasi dalam
penggalan-penggalan tahap yang sudah jadi itu secara “ideologis” berimplikasi bagi
pemandulan gerakan sosial yang semula menjadi motor perubahan dan menjadikannya
lebih sebagai perjuangan dalam koordinat prosedur dan institusional. Dari situ, melalui
kritiknya, bagian ini bermaksud mengajukan suatu cara pandang yang membebaskan hak
asasi dari keterbatasan perjuangan legal-objektifnya dan mengembalikan hak asasi
sebagai perjuangan emansipasi.
Upaya untuk mengembalikan hak asasi sebagai proyek emansipasi yang bersifat politis
bab tiga disajikan semacam peta umum mengenai persoalan serta posisi-posisi keagenan
dalam politik transisi di Indonesia terutama yang berkaitan dengan politik perebutan
“ingatan” di Indonesia. Dengan memahami “ingatan dan sejarah” sebagai wilayah yang
diperebutkan oleh berbagai kelompok dalam demokrasi, maka jelas ditunjukkan bahwa
“ingatan” itu sendiri adalah sebuah arena politik ketimbang sekadar arena hukum.
Akibatnya, di sini hukum itu sendiri harus dipahami bukan lain hanya sekadar
kepanjangan tangan kekuasaan politis semata yang saling berkontestasi untuk mengusai
“kesadaran/ketaksadaran” publik akan sejarah kemanusiaan itu sendiri.
Kenyataan ini yang kemudian secara lebih konkret ditunjukkan dalam ironi perselisihan
dalam tubuh para aktor sendiri dalam mendefinisikan makna kebenaran dalam politik
ingatan, antara yang berpaku terus pada trajektori legal transisionis dalam model
pengadilan di satu sisi dan model non-pengadilan (KKR) di sisi yang lain. Kegagalan
dalam cara pandang transisionis terbukti secara telak terutama dalam kebangkrutan
skenario legalis, di mana pengadilan-pengadilan hak asasi yang diadakan untuk
mengadili beberapa kejahatan hak asasi di masa lalu ternyata memang hanya berhenti
pada “mengadili” untuk kemudian malah membebaskan dan meloloskan sejumlah
terdakwa. Kebangkrutan ini makin diperdalam dengan kepercayaan buta kepada
mekanisme hukum sebagai satu-satunya mekanisme untuk menyelesaikan perkara yang
sesungguhnya perkara politik dalam kasus dibatalkannya UU KKR dalam judicial review
yang ironisnya diajukan oleh sejumlah korban dan LSM. Kegagalan ini tidak hanya
membuktikan semacam “kenaifan” politik dan absennya pemahaman akan “yang politik”
dalam persoalan hak asasi manusia, tetapi juga menunjukkan bahwa pembakuan
transisionis memang tidak dapat dipakai apabila hak asasi tetap mau diusung sebagai
agenda politik emansipasi.
Namun demikian, buku ini juga tidak mau berhenti pada kritik yang mengesankan
fatalisme. Buku ini mau menekankan pada supremasi yang politis dalam
memperjuangkan hak asasi serta kemungkinan-kemungkinan yang akan dibukanya di
masa depan. Oleh karena itu, pada bagian penutup, buku ini mengajak kita untuk melihat
bermaksud membuka lagi kesadaran bahwa sejauh hak asasi dimengerti sebagai politik
emansipasi maka seluruh kegagalan legal yang terjadi sebelumnya bukanlah sebuah titik
final yang mengakhiri segala upaya.
Kini di jaman di mana advokasi hak asasi bisa lebih gampang mendekat ke para politisi
dan para aktivis bisa “relatif mudah” masuk ke komisi-komisi maka semestinya politik
hak asasi tetap berpeluang dan bisa dilakukan secara lebih matang. Yang terpenting di
sini – sebagaimana dikemukakan dalam bab penutup – pada akhirnya memang adalah
fidelity, keyakinan dan kesetiaan dalam harapan mengenai suatu misteri bahwa
Bab 1
Relasi antara Negara dan LSM dan Fragmentasi Keagenan
Pengantar
Satu dasawarsa lalu, banyak pihak mendeklarasikan jaman ini sebagai jaman hak asasi
manusia. Deklarasi ini bermula datang dan seiring dengan optimisme orang akan matriks
kepastian sejarah yang sama yang digaungkan oleh pemikir politik kontemporer
mengenai kepastian akan demokrasi dengan “civil society” sebagai soko-gurunya. Dari
sini, muncul kombinasi yang diagungkan: nilai-nilai universalitas hak asasi di satu sisi
dengan keagenan politik civil society di sisi yang lain. Dalam politik Indonesia Orde Baru
masa itu, kedua kekuatan ini bertumpu pada satu tubuh kepolitikan yang juga sempat
dianggap primadona pada jamannya yakni Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM.
Dari sini boleh dikatakan muncul triadic politik alternatif yang menjadi formula bagi
perjuangan demokrasi Indonesia era Orde Baru: hak asasi-civil socity dan LSM.
Kini, setelah rejim Orde Baru jatuh dan demokrasi dicapai serta diinstalasikan sebagai
pranata dalam tubuh Negara, primadona itu kini nyaris kehilangan gincu, bedak dan daya
tariknya. Dulu dalam suasana otoritarian kekerasan dibuat oleh Negara dan keadilan tidak
mendapatkan tempat, hak asasi dipinggirkan dan diharamkan dari hukum nasional dan
konstitusi, sementara partisipasi dan kesadaran politik ditekan sama sekali. Kini dalam
era demokrasi yang strukturnya dibangun oleh topangan LSM, donor dan mantan
penguasa, semua yang semula ditolak oleh Negara Orde Baru kini diambil alih sebagai
Untuk hak asasi manusia Negara menyediakan komisi nasional hak asasi manusia, untuk
korupsi Negara menyediakan KPK, untuk kecelakaan dan penyelewengan hukum Negara
menyediakan bermacam-macam komisi, untuk keadilan, partisipasi, kritik, dinamisasi
dan perubahan politik Negara mendorong beranak-pinaknya partai politik dan
organisasi-organisasi masyarakat. Singkatnya, apa yang semula merupakan fasilitas politis yang
dimiliki secara ekslusif oleh LSM kini beralih menjadi milik Negara. Bukan hanya itu,
peralihan dalam instasalsi ideal kepolitikan ini juga kemudian diikuti dengan pergeseran
sekutu terpentingnya: lembaga donor menjadi lebih tertarik untuk mendanai kegiatan
lembaga-lembaga atau komisi-komisi pemerintah ketimbang LSM.
Dari sini komponen triadik hak asasi-civil socity-LSM pada akhirnya dilepaskan satu
demi satu. Hak asasi kini sudah jadi hak yang konstitusional, sementara civil society –
setelah menguatnya era partai-partai – adalah konsep usang yang memang nyaris tidak
diperlukan lagi. Akibatnya, yang jadi pertanyaan kemudiana adalah apa yang tersisa
untuk LSM? Untuk menjawab pertanyaan ini, penting bagi kita untuk menelusuri secara
singkat perjalanan LSM.
Asal Usul dan Mistifikasi
Pada tahun 1985, dilakukan sebuah survei mengenai pemetaan masalah “LPSM-LPSM”
[Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat] Indonesia. Survei itu tergolong sangat
serius karena disokong oleh lebih dari 10 LSM terbesar di Indonesia pada era itu plus
dukungan dari Asia Foundation; dipimpin oleh Adi Sasono selaku Ketua Steering
Committee, sementara risetnya sendiri dipimpin oleh Fachry Ali. Semangat ber-LSM
jaman itu dengan segera bisa ditangkap dengan memperhatikan sebuah paragraf dari
laporan survei tersebut yang menegaskan posisi unik sebagai berikut:
politiknya, yang tentu saja sedikit berbeda dengan Muhammadiyah yang sudah sejak berdirinya, tetap konsisten dengan pengembangan masyarakat.1
Adalah antusiasme yang luar biasa berlebihan ketika survei ini dengan cara simplistis
membentangkan cara pikir transhistoris dalam meletakkan relasi dan peran LSM. Dengan
menyebut peran pada masa kolonial, pendirian dalam survei memasang sejumlah
kekaburan mengenai pertama bahwa seolah-olah LPSM (dengan istilah dan definisi yang
seteknis-teknisnya) telah ada dan dikenal di masa kolonial. Kedua, bahwa apa yang
disebut sebagai LPSM itu berciri aktivitas dalam rangka “pengembangan harga diri
masyarakat banyak sebagai suatu bangsa”. Dan ketiga, bahwa SI dan SDI boleh dilihat
sebagai LPSM yang kemudian mengembangkan sayap politiknya. Penggambaran ini jelas
mengaburkan antara gerakan kemerdekaan menentang kolonialisme, baik yang
menggunakan politik identitas (seperti SI) maupun bukan (pra-negara modern lokal)
dengan konsern di dalam politik kewargaan dalam berhadapan dengan kuasa negara
modern dan pasar. Hal kedua yang juga dikaburkan di sini adalah aspek historitas dan
latar belakang sosial pembentukan LSM itu.
Sama sekali berbeda dengan seting kolonial, di mana isu dominan yang muncul adalah
tanah air dan kemerdekaan sebagai komunitas bangsa. Dalam seting awalnya di masa
Orde Baru, peran dan kedudukan dari apa yang dikenal sekarang sebagai LSM senantiasa
dikaitkan atau bahkan diletakkan sebagai bagian dari konsep lain yang lebih kompleks
dan canggih yakni konsep civil society. Kerangka ini telah menghasilkan pendasaran
yang sangat kuat bagi pembentukan karakter politik maupun definisi konseptual
lembaga-lembaga ini yakni sangat berbasis kelas menengah, memiliki ideologi yang beragam
dalam arti renggang, luwes dan memasang jarak dengan institusi dan aparat negara.
Untuk bisa menjelaskan pembentukan asal-usul semacam ini kita mesti melihat dua
kecenderungan; yang pertama adalah pembentukan diskursus LSM sebagai entitas yang
tumbuh dalam dan mempengaruhi proses politik dan perubahan sosial di Indonesia yang
1
khas, dan kedua adalah kekuatan politik normatif sebagaimana yang disampaikan oleh
organisasi dan pendirian sejumlah aktivis pembela hak asasi manusia di era awal Orde
Baru, dan ketiga adalah kita mesti kembali ke ide kritik ekonomi politik pembangunan di
masa tahun 70-an awal di mana masa ini ditunjuk oleh banyak kalangan sebagai masa
awal munculnya LSM, yang kemudian mewarisi karakter dan pendirian kepada yang ada
sekarang.
Semula banyak kalangan lebih suka menggunakan ornop (organiasai non-pemerintah)
untuk menamai kelompok-kelompok dalam masyarakat yang melakukan
aktivitas-aktivitas sosial-politik penyadaran masyarakat dan kritik terhadap pemerintah. Istilah ini
disukai karena beberapa alasan: pertama, karena ia mencerminkan otonomi dan
demarkasi dengan kekuasaan, dan kedua karena ia mengesankan kritik dan alternatif
langsung dari kebijakan pemerintah. Namun justru karena potensi watak demikianlah,
maka pemerintah kemudian tidak menyukai istilah ini. Akibatnya para aktivis ornop
sendiri pada waktu itu, untuk menghindari pertentangan dengan pemerintah, memutuskan
untuk tidak meneruskan pemakaian istilah ini.
Di masa kini pemerintah lebih akrab menyebut lembaga-lembaga ini dengan LSM
(Lembaga Swadaya Masyarakat). Penggunaan istilah LSM ini sebenarnya kurang tepat
karena ia dipakai secara sangat overlapped, hendak menyebut siapa saja yang berada di
luar pemerintah baik itu serikat buruh, kelompok-kelompok paguyuban tani, kelompok
studi, yayasan-yayasan yang mengurus HAM di kota-kota ataupun kelompok-kelompok
paguyuban kedaerahan dan profesi yang kurang resmi serta lembaga-lembaga bantuan
hukum. Semuanya dicampur-adukkan di dalam satu istilah.
Ismid Hadad mencoba memberikan pembedaan yaitu dengan memisahkan antara apa
yang disebutnya dengan kelompok primer (kelompok-kelompok tani,
paguyuban-paguyuban di komunitas dan serikat-serikat rakyat) dan kelompok sekunder (kelompok
yang membantu pendirian dan pengembangan kelompok primer). Kelompok primer
inilah yang lebih tepat disebut sebagai LSM sementara kelompok sekunder yang
Dari pembagian ini, secara sosiologis terdapat satu hal penting yakni soal otentisitas.
Implisit di dalam pembagian ini, Hadad menegaskan bahwa LSM memiliki keterkaitan
yang organik dengan kepentingan-kepentingan masyarakat yang sesungguhnya. Jadi di
sini tidak ada aspek representasi; LSM adalah presentasi langung dari kepentingan
rakyat banyak. Dengan demikian jelaslah bahwa organisasi-organisasi yang bertebaran di
perkotaan yang dihuni oleh para sarjana lulusan universitas meskipun bergembar-gembor
dengan kegiatan tani dan buruh tidak dapat disebut sebagai LSM karena tidak ada petani
dan buruh sungguhan di situ, atau dengan kata lain tidak ada otentisitas aktor, yang ada
adalah si sarjana yang pandai membuat proposal dan program. LPSM memang adalah
kategori yang secara fungsional paling pas buat kalangan kedua ini.
Namun demikian, tidak semua orang segera sepakat dan menerima pengistilahan ini.
Mungkin karena istilah LPSM ini apabila kita blejeti secara jujur maka sebenarnya
dengan gampang kita bisa memahami bahwa istilah LPSM itu adalah sebuah penghalusan
dari istilah calo atau broker, yang tentu saja sangat tidak nyaman bagi para aktivis LSM
itu sendiri.
Namun demikian, bahasa politik dan hukum Orde Baru sendiri pada waktu itu telah
terlanjur mendefiniskan kelompok-kelompok ini dengan istilah tunggal yakni LSM.
Terutama di masa-masa akhirnya, Orde Baru kerap menyebut siapa saja yang mengkritik
pandangan dan kebijakannya dengan sebutan LSM.2 Jadi dengan begitu istilah LSM
bukan lagi sekadar sebutan yang dipakai untuk organisas-organisasi di luar pemerintah
melainkan lebih merupakan tuduhan dari pemerintah kepada kelompok-kelompok yang
menentang dirinya. Dari sini barulah muncul semacam identitas balik, di mana pada
akhirnya para aktivis itu kemudian juga menerima dan mulai mendefinsikan diri mereka
sebagai LSM secara lebih kuat.
2
Dengan demikian terjadi pergeseran aspek otentisitas dalam makna swadaya
sebagaimana disebut oleh Hadad pada bagian muka. Kalau sebelumnya LSM itu
sebenarnya digunakan untuk menyebut aktivitas kelompok-kelompok masyarakat bawah
maka kini para sarjana kota yang ketiban pulung menyandang istilah ini. Pemerintah
lebih tertarik untuk bertengkar dengan para sarjana dan aktivis kota ketimbang petani,
dan para aktivis kota ini juga merasa nyaman disebut sebagai “masyarakat swadaya”,
sehingga keduanya rupanya menjalin kesepakatan diam-diam untuk menggunakan istilah
LSM ini tidak lagi kepada petani dan buruh tetapi kepada yayasan-yayasan yang
beroperasi di ibu kota provinsi yang bekerja dengan press conference, riset dan studi.
Dari sinilah sebenarnya terjadi proses substitusi dari apa-apa yang seharusnya dilakukan
dan menjadi wilayah grass root menjadi apa-apa yang diatasnamakan oleh kelompok
menengah di atasnya di ibu kota provinsi. Substitusi kepentingan ini berlaku secara
sangat kuat. Dari sini pula klaim-klaim politik LSM itu kemudian dibasiskan dan
diperkuat.
Diskursus Normatif
Tidak dapat dipungkiri bahwa setelah pemberangusan kehidupan politik secara umum
pasca-1965, negara Orde Baru yang tampil sebagai pemenangnya nyaris mendominasi
seluruh aspek kehidupan sosial dan politik pada waktu itu. Keadaan ini sedikitnya
disokong pula oleh semacam sikap reseptif dari politisi maupun intelektual yang anti
terhadap rejim Soekarno yang hidup di jaman itu. Kritik dan independensi yang mereka
gaungkan untuk menghadapi dan menjatuhkan Soekarno yang dituduh sebagai diktator
pada waktu itu, rupanya tidak dapat secara serta merta dan lancar digunakan untuk
menilai praktik politik rejim baru sesudahnya. Dengan demikian tidak dapat dipungkiri
bahwa satu-satunya politik yang berlaku pada saat itu adalah “politik” sebagaimana yang
dimiliki dan dikendalikan oleh rejim Soeharto.
Sisa terakhir dari politik yang masih dimiliki oleh kalangan non-state pada waktu itu
tuntutan yang juga sangat normatif, dalam beberapa hal bahkan metafisis (dalam kasus
Yap Thiam Hien misalnya yang pendirian-pendirian kemanusiaannya sedemikian rupa
bercampur dan didasari oleh pandangan-pandangan religiositasnya) yakni isu hukum dan
hak asasi manusia. Di dalam isu inilah kelompok-kelompok yang nanti disebut sebagai
civil society atau non-state actor ini hadir dan melaksanakan sejumlah aktivitas untuk
melakukan kritik dan kontrol (meski sangat minim) terhadap praktik pelaksanaaan kuasa
Orde Baru pada waktu.
Di wilayah normatif inilah tampil dua orang yang sangat bersemangat dan berpengaruh
yakni: Yap Thiam Hien dan HJC. Princen. Kedua orang ini adalah pelopor pemberani
yang membuka jalan untuk tampilnya politik hak asasi manusia yang subtil dan sangat
ideal di masa itu. Pada tahun 1966 seperti mendahului dan memancang fondasi, Princen
mendirikan kantor Lembaga Pembela Hak-Hak Asasi Manusia yang sangat berperan
dalam mengawasi praktik-praktik penahanan dan pemenjaraan para pendukung Soekarno
oleh Orde Baru. Di sinilah Princen menjadi salah satu yang pertama dalam memberikan
dasar-dasar praksis untuk menjaga apa yang dikenal orang sebagai “hak-hak dan
kebebasan sipil”.
Sementara di masa di mana Orde Baru masih menikmati suasana paginya, Yap Thiam
Hien dengan lantang telah berteriak:
… melihat seakan-akan “Orde Lama” semuanya des duivels dan “Orde Baru” segalanya der engelen bukan saja penglihatan yang kabur, melainkan juga secara implisit, tanpa disadari, mengakui diri sendiri sebagai anak setan (Yap, 1966).3
Dari segi politik, Yap adalah bagian dari salah satu pemenang pada waktu itu, karena ia
pun anti-PKI dan anti-Soekarno. Namun berbeda dengan pendukung Orde Baru lainnya,
sikap Yap menentang Soekarno dan PKI rupanya lebih dimotivasi oleh rasionalitas dan
ideal tertentu ketimbang kepentingan politik dan perebutan kuasa semata. Ini terbukti dari
kejahatan yang dilakukan oleh Orde Baru, sehingga kemudian sama seperti Princen, pada
akhirnya ia pun harus berhadapan dan mengalami represi oleh rejim yang ikut ia dirikan.
Merelatifkan watak dan eksistensi dari Orde Baru dan Orde Lama menjelaskan hal
terpenting dari suatu pendirian politik yang go beyond interest, nyaris resi. Dengan
mengatakan “Orde Lama bukanlah iblis dan Orde Baru bukan pula malaikat” telah
ditegaskan pentingnya suatu arena di luar politik yang lebih inti dan fundamental yaitu
faktor kesadaran manusia dan kebebasan serta otonomi individu dalam memandang dan
menjinakkan politik itu sendiri. Sikap ini yang mestinya dipakai untuk mengatasi sistem
kuasa apa pun.
Di sini jarak atau demarkasi otomatis menjadi penting: “tidak Orde Lama tidak pula Orde
Baru”. Dari sikap semacam inilah diwariskan gagasan yang mulai memilah-milah mana
kuasa mana ideal; mana negara dan mana bukan negara; mana pejuang moral dan mana
yang politik; mana yang discourse of ethics dan mana yang discourse of power.4 Inilah
salah satu etik atau semacam stand point yang hingga kini masih dipakai oleh LSM di
Indonesia untuk menunjukkan “kemurnian” pendiriannya. Sehingga dengan demikian,
kritik dan gugagatan mereka terhadap negara selain didasarkan atas perbedaan dan
aspirasi prinsip dalam memandang kehidupan politik yang demokratis juga didasarkan
atas semacam “pandangan hidup” bahwa “ber-LSM” berarti harus menjaga jarak dan
hidup terpisah dari tujuan dan ruang lingkup kuasa negara.
Inilah salah satu tradisi dan gagasan penting yang dipakai oleh banyak LSM sepanjang
Orde Baru untuk menilai diri mereka satu sama lain. Di titik ini, posisi ini nyaris
menggambarkan figur intelektual yang dibayangkan oleh Benda, yang mengganggap
rasionalitas dan kemanusiaan harus diletakkan di atas apa yang disebutnya political
passion, karena menurutnya politik, bagaimanapun, selalu melibatkan uang dan
3
Dipetik dari Pledoi Pembela Kedua dalam kasus Dr. Subandrio. Dikutip dari Yap Thiam Hin (1998), Negara, HAM dan Demokrasi (ed. Daniel Hutagalung), Jakarta: YLBHI, hlm. 216.
4
kekuatan.5 Dua hal yang by nature sangat bertentangan dengan pendirian LSM yang mau
mengambil jarak dengan kekuasaan apa pun.
Dengan dasar pendirian yang sangat normatif dan moralis semacam ini maka tidak
mengherankan juga apabila konsep civil society yang kemudian berkembang dalam tema
advokasi LSM di Indonesia menjadi konsepsi yang sangat homogen. Dipakai untuk
menjelaskan semua pihak yang berada di luar negara dan tetap menjaga batas itu dapat
disebut sebagai civil society. Di sini gambaran mengenai pertarungan dan perubahan
politik beserta aktor-aktornya memang menjadi sangat sederhana; terbatas pada
dialektika dan relasi state dan society dalam pengertian dan definisi yang paling luas.
Akibatnya gagasan dan pandangan yang partikularistik dalam artian perhatian kepada
entitas-entitas yang lebih kecil seperti entitas gender, kelas dan kultur memang tidak
dilihat secara khusus.
Akibatnya jelas, secara politik konsepsi ini sangat menekankan peran kaum profesional,
golongan menengah dan intelektual kota sebagai motor utama penggerak. Di sini menjadi
sangat masuk akal bahwa kemudian dari segi aktor LSM-LSM itu banyak sekali dipimpin
dan digerakkan oleh para sarjana hukum dan para lulusan universitas mantan aktivis
gerakan mahasiswa. Sementara dari segi ide(ologi) gerakan LSM yang muncul kemudian
sangat berpusat pada ide-ide liberal mengenai kebebasan dan peran negara yang minim
dalam politik.
Jumlah CSO’s di Indonesia (tahun 2000)
Category Number of Organisations
Think tanks and research organisations 41
Student and youth Association/Alumni groups 36
Humanitarian and walfare groups 305
Business/Professional asss., cahmbers of trade and 555
“Discourse and Democratic Practise” dalam K. White (ed.), The Cambridge Companion to Habermas, Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 233-255.
5
commerce
Union and Labour Groups 20
Media and Journalist Associations 17
Legal organisations, advocacy, and monitoring groups 36
Women Organisation 38
Environment groups 18
Leisure Organisations, cultural foundation and clubs 109
Religius Organisations 58
TOTAL 1.322
Sumber: UNSFIR berdasarkan MASINDO (2000) Association and NGO’s Guide 2000.6
Tabel di atas meski tidak secara langsung menunjuk LSM, namun fakta dan gambaran
umum yang ditampilkannya mempertegas pandangan sebelumnya yang menyebutkan
bahwa gerakan LSM sangat berwatak kelas menengah. Dari 1.322 organisasi yang ada
hanya 20 organisasi yang merupakan organisasi buruh. Dari jumlah itu tidak ada
organisasi petani dan kaum grass root yang lainnya. Absennya peran dan keberadaan
kelompok-kelompok grass root itu memperjelas beberapa kemungkinan yakni pertama
bahwa paling tidak hingga tahun 2000, yakni 2 tahun setelah jatuhnya rejim Soeharto,
memang tidak terbentuk suatu persekutuan politik yang memadai di kalangan grass root;
dan yang kedua, kalaupun ada maka persekutuan-persekutuan itu memang harus dicari
dan ditemukan dalam cerita dan selubung yang lebih besar yakni selubung politik kelas
menengahnya. Dengan kata lain yang terjadi adalah proses substitusionalisme yang
dimainkan oleh organisasi-organisasi yang lebih menonjol, besar dan vokal terhadap
organisasi grass root yang ada.
Dari Normativitas Hukum ke Normativitas Pembangunan
Jadi tidak dapat dipungkiri, setuju ataupun tidak, salah satu faktor pembentuk karakter
LSM selama Orde Baru yang utama adalah semacam idealisme untuk melakukan
evaluasi normatif terhadap negara. Karenanya di titik ini hukum dan diskursus HAM
Posisi semacam itu tentu saja dapat dengan mudah dipahami. Sebagai rejim yang baru
terbentuk, Orde Baru membawa persoalan hukum dan kemanusiaan yang kompleks dan
mengerikan: pembantaian jutaan orang, pemberangusan partai-partai dan organisasi
politik, penahanan dalam kamp-kamp tahanan dan penghilangan orang. Dengan demikian
“adalah normal” apabila perhatian orang harus berkisar pada wilayah penataan dan
perbaikan wajah politik dari rejim yang baru terbentuk itu. Dengan kata lain,
mengencangnya dan tampilnya isu HAM dan hukum (hak-hak sipil dan politik) yang
segera memang mengikuti atau boleh dikatakan paralel dengan rejimentasi politik yang
terbentuk pada masa itu.
Barulah setelah masa-masa “pembangunan” ekonomi dan sosial berjalan dan rejim politik
yang terbentuk makin memiliki kekuatan nyata untuk melakukan kontrol dan penindasan
terhadap pembangkang, maka isu HAM dan tuntutan terhadap keadilan menurun dengan
sendirinya. Isu HAM tenggelam dan makin dipinggirkan dalam wacana politik Orde Baru
pada akhir 60-an itu, sementara isu “negara hukum” yang biasanya memang hanya
berfungsi sebagai suplemen dari isu HAM tampil dalam bentuk yang sangat low profile;
karitatif, prosedural, nyaris sama sekali tidak memiliki daya kritik yang memadai
terhadap praktik kekuasaan yang terpusat.
Maka seiring dengan mengencangnya pembangunan kapitalisme Orde Baru yang
tercermin dalam menguatnya peran negara sebagai akibat pertumbuhan ekonomi dan
industri, tuntutan-tuntutan politik yang normatif sekalipun makin mundur ke belakang.
Pada titik ini, negara yang makin kuat mulai menjalankan strategi baru dalam berelasi
dengan masyarakat. Implikasi dari pembesaran kekuasan negara itu sangat terlihat dari
cara bagaimana orang pada jaman ini menilai diri dan perananan LSM serta relasinya
dengan negara.
6
Dikutip kembali dari Iwan Gardono Sujatmiko (2001), “Wacana Sivil Society di Indonesia”,
Ada dua perkembangan penting. Yang pertama, munculnya psikologi subordinat dalam
mendefinisikan peran LSM. Ismid Hadad salah satu yang menjadi tokoh LSM pada
waktu itu menuliskan dan ia mempercayai bahwa untuk menjawab “tantangan Repelita V
yakni bagaimana secara efektif memperbaiki nasib 55 juta rakyat yang masih berada di
bawah garis kemiskinan” selayaknya pemerintah bekerja sama dengan LSM yang
memiliki kemampuan untuk menjangkau golongan miskin.7 Pada titik ini Hadad
kemudian menganjurkan agar LSM sendiri pun mendefinisikan dirinya dalam tingkat
harmonisasi tertentu dengan pemerintah. Konsisten dengan harmonisasi itu, ia pun
meletakkan fungsi LSM dalam tiga kategori yang sangat moderat yakni pertama fungsi
yang komplementer yakni menjalankan proyek-proyek yang tidak dapat digarap oleh
pemerintah; kedua fungsi subsider yakni melakukan peran tambahan untuk melengkapi
proyek pemerintah; dan ketiga fungsi perantara yaitu memediasi komunikasi antara
lembaga birokrasi dengan grass root. Jadi dengan demikian fungsi LSM di sini
benar-benar ditempatkan selaku kepanjangan tangan pemerintah.
Dalam situasi dan modus hubungan yang sangat subordinatif bercampur dengan kerelaan
banyak orang kemudian mengusulkan untuk mengganti istilah ornop yang sering dipakai
waktu itu sebagai terjemahan bebas dari istilah Inggris non-governmental organisation
(NGO) karena istilah “non-pemerintah” di situ dianggap terkesan oposan, terkesan
organisasi tandingan dan pengganti pemerintah. Inferioritas ini rupanya juga seiring dan
seirama dengan keinginan pemerintah sendiri mengingat hal yang sama juga ditekankan
oleh Emil Salim yang waktu masih menjabat sebagai Menteri Negara Kependudukan dan
Lingkungan Hidup. Emil Salim menegaskan bahwa istilah ornop itu lebih berakar pada
tradisi Eropa yang berkesan “against the establishment” sementara di Indonesia peran
NGO “by nature tidak berakar dan tidak berorientasi pada sikap anti-pemerintah.”8
Karakter semacam ini juga disepakati oleh tokoh seperti Dawam Rahardjo ketika ia
memaparkan peran tokoh Dr. Sutomo. Dawam menyebut Dr. Sutomo sebagai pelopor
LSM di Indonesia. Menurut Dawam, berbeda dengan tokoh-tokoh pergerakan lainnya
7
Ismid Hadad (1983), “Menampilkan Potret Pembangunan Berwajah Swadaya Masyarakat”,
yang secara tegas berkonfrontasi dengan penjajah, Sutomo malah memilih
aktivitas-aktivitas yang “non-radikal” dan “non-politik” seperti meningkatkan pendidikan dan
kesadaran rakyat dan memperbaiki kondisi sosial ekonomi”.9
Sikap dan pilihan reseptif yang berkembang pada masa itu kemudian memang
mendorong kepada suatu penyakit umum yang diderita oleh kebanyakan orang Indonesia
ketika itu yakni phobia politik. Tidak hanya orang Indonesia, Geoffrey B Hainsworth
yang menempatkan LSM sebagai pihak terhormat dan mentereng yakni sebagai kekuatan
ketiga antara pasar dan negara pun menderita phobia dan menganjurkan untuk phobia
yang sama:10
Kecurigaan terhadap LPSM oleh pejabat-pejabat tertentu mungkin
merupakan hambatan yang lebih sulit disingkirkan guna meluruskan
pelaksanaan operasi di tempat-tempat tertentu dan sehubungan dengan
jenis-jenis fungsi tertentu LPSM harus jauh-jauh menghindari masalah
“politik” dan ia harus berhati-hati mengenai “pemolitikan” kepentingan
kelompok yang dikaitkan dengan mereka.11
Adalah sulit untuk dimengerti bagaimana mungkin orang yang sama yang mengatakan
LSM sebagai “gerakan ketiga” dari pasar dan negara, yang di tingkat jargon hanya
tipis-tipis saja perbedaaanya dengan slogan-slogan untuk gerakan politik seperti Manifesto
Komunis, menganjurkan sebuah praksis yang sangat bertolak belakang dan ironis
“menghindar masalah politik”. Bagaimana mungkin institusi ketiga setelah pasar dan
negara bisa menolak terhindar dari politik? Bukankah dari nama dan posisinya sendiri
pun sudah nama dan posisi yang sangat politis?
8
Lihat wawancara Emil Salim dalam Prisma, No 4, April 1983, hlm. 66.
9
M. Dawam Raharjo (1988), “Dokter Soetomo: Pelopor LSM?”, Prisma No 7, Tahun 1988, hlm. 11-24.
10
Geoffrey. B Hainsworth (1983), “Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat dan Perataan Pembangunan”, Prisma No 4, April 1983, hlm. 38-53.
11
Jadi jelas sebenarnya di sini, ada semacam kekaburan antara sikap intelektual tentang apa
dan bagaimana peran LSM seharusnya dengan perhitungan akan berbahayanya
kekuasaan negara pada waktu itu yang sangat otoriter.
Namun demikian isu “pemolitikan” dan anjuran untuk “jauh-jauh menghindari masalah
politik” itu tidak semuanya didengar dan diikuti oleh semua orang di jaman itu. Di tahun
yang sama, bertentangan dengan Hainsworth dan Hadad, Abdul Hakim yang waktu itu
menjabat sebagai Manajer Eksekutif LBH Indonesia berpendirian berbeda, dan nyaris
seperti mendeklarasikan sebuah partai politik ia menulis:
Golongan militer dan birokrat merupakan kelompok-kelompok sosial yang
terorganisir secara rapi dan mempunyai visi dan ideologi yang relatif
homogen, yaitu ide persatuan nasional. Ideologi persatuan nasional ini
memberikan legitimasi penting bagi naiknya golongan militer dan birokrat
ke panggung kekuasaan politik … Dalam pada itu, kelompok-kelompok
sosial di luar sektor negara umumnya merupakan kelompok sosial yang
kurang terorganisir secara rapi dan secara ideologis tercerai berai.12
Di sini jelas dalam pendirian Hakim, bahwa politik dan perjuangan politik tidak mungkin
disingkirkan dalam aktivitas LSM, bahkan politik menjadi state of nature LSM dalam
pendiriannya, karena ketimpangan dalam akses terhadap kekuasaan antara golongan
penguasa (militer dan birokrat) dengan golongan diluar negara.
Kesenjangan akses tehadap kekuasan inilah yang menurut Hakim melahirkan problem
dasar keadilan. Untuk itu ia kemudian mengusulkan suatu isu yang sama sekali berbeda
dengan diskursus LSM di jaman itu yakni apa yang disebutnya dengan Pembangunan
Hukum yang responsif-progresif yakni “cara untuk mendorong dan mempercepat proses
emansipasi sosial masyarakat di lapis bawah”.13 Dengan demikian di luar usulan dan
ajakan agar LSM bertindak reseptif, menjadi kepanjangan tangan program pembangunan
12
Lihat dalam Abdul Hakim G. Nusantara (1983), “Mencari Strategi Pembangunan Hukum”,
negara, Hakim justru datang dengan istilah baru yang berbeda dengan wacana dominan
per-LSM-an pada waktu itu.
Melengkapi pendiriannya yang sangat politis dalam melihat peran LSM, ia kemudian
menegaskan keperluan-keperluan baru untuk mencapai emansipasi itu yakni dengan:
pertama, menciptakan kondisi yang memungkinkan kelompok bawah dapat
mengorganisasikan perjuangannya; kedua, memperbesar akses masyarakat bawah ke
lembaga-lembaga peradilan; ketiga, ornop harus meningkatkan peranannya untuk
“menyadarkan hak-hak masyarakat” dan “merencanakan program litigasi baru yang
diarahkan untuk merangsang munculnya “jurisprudensi baru yang responsif-progresif;
keempat, bersama pemerintah membantu masyarakat bawah untuk membangun
organisasi yang mandiri sebagai alat perjuangan kepentingan; kelima, diberlakukannya
peradilan tata usaha negara; keenam, meneliti seluruh keputusan-keputusan peradilan.
Pendirian-pendirian ini menegaskan sisa-sisa kekuatan kritik yang masih ada dari
normative politics yang muncul di era awal Orde Baru. Hanya berbeda dengan Yap dan
Princen yang benar-benar berpatok pada gagasan moralis mengenai hukum dan HAM,
bagi Hakim, hukum dan HAM itu memang mengalami sejumlah perubahan yang
menjadikan ideal normatif itu menjadi lebih radikal dan struktural. Namun jelas,
kehadiran ini membuktikan fakta lain yakni bahwa subordinasi di bawah pembangunan
kapitalisme Orde Baru tidak pula sepenuhnya menguasai LSM di Indonesia di awal 80-an
itu.
Ruang dalam kerenggangan kuasa Orde Baru itu sendiri kemudian makin menemukan
tempatnya yang lebih kondusif sebagai akibat krisis minyak yang terjadi di pertengahan
tahun 1980-an yang memaksa negara untuk mulai membuka sumber-sumber dan
investasi ekonomi lain. Sehingga dengan itu keterikatan dengan faktor internasional
memang menjadi lebih intens sehingga struktur dan relasi ketergantungan Indonesia
dengan lembaga-lembaga keuangan dunia pun semakin terbentuk secara matang. Di titik
inilah faktor baru masuk dalam relasi LSM dan negara yakni faktor internasional atau
13
faktor international community yang pada gilirannya nanti akan sangat menentukan dan
memberikan dimensi baru dalam ketegangan hubungan antara LSM dengan rejim Orde
Baru.
Pada titik ini, dengan perubahan pada aras ekonomi politik nasional dan internasional
tersebut, memang muncul kebutuhan dan tuntutan baru dalam melihat masalah dan
subjek advokasi. Di sini anjuran-anjuran untuk “menjauhi politik” bisa juga dimaksudkan
sebagai upaya untuk mengajak LSM agar lebih terfokus pada isu-isu kerakyatan yakni
keadilan sosial dan kemiskinan. Sehingga dalam beberapa hal “menjauhi politik” dalam
anjuran ini, bisa pula dilihat sebagai anjuran untuk tidak terlibat dalam “politik elite” atau
politik di wilayah infrastruktur negara. Pada titik ini, arus utama yang memang muncul
seiring dengan derasnya wacana pembangunan yang juga dikencangkan oleh pemerintah
adalah wacana mengenai “empowerment” dan gerakan pendidikan penyadaran serta
pendampingan masyarakat, terutama dalam kerangka melihat relasi-relasi yang
memproduksi ketimpangan dalam masyarakat. Kecendrungan ini secara tepat kemudian
dirumuskan oleh Hanmann sebagai berikut:
Kebutuhan reorientasi pembangunan dari yang bersifat top-down ke arah grass root membutuhkan peran LSM. Di sini meskipun tetap meletakkan peran LSM di dalam kerangka paradigma pembangunan, Hannam menyebutkan bahwa efek politik dari peran ini dengan sendirinya pun akan tampak bahwa “kalau kelompok swadaya terbentuk maka kaum miskin akan lebih terorganisir, lebih sadar akan perubahan dan tatanan sosial.14
Sebagai kelanjutannya, pada momen ini LSM mendapatkan sandaran ideologisnya yang
kedua setelah “normative politics” sebelumnya. Di luar wacana negara hukum dan
HAM, isu mengenai kemiskinan dan perubahan struktural mulai masuk ke dalam wacana
dominan perjuangan LSM di Indonesia.
14
Dari sinilah subject matter LSM itu mulai bergeser atau paling kurang menemukan
dimensi terbarunya yakni dimensi ekonomi-politik. Seiring dengan itu, kecendrungan ini
sendiri bertepatan dengan keadaan-keadaan baru di dalam gerakan sosial lainnya di
Indonesia seperti gerakan mahasiwa yang mulai membawa isu-isu kerakyatan dengan
modus komite-komite aksi pembelaan rakyat terutama petani pada masa itu, ditambah
dinamika baru intelektual di kampus-kampus yang terorganisir di dalam
kelompok-kelompok studi dengan ide-ide dan perspektif yang lebih radikal. Pada titik ini
benih-benih untuk tumbuhnya kekuatan politik baru muncul, kombinasi dari keterorganisiran
dan pencarian aktor-aktor perubahan baru serta ideologi perubahan.
Potensi inilah yang dilihat oleh pengamat semacam Liddle dan Eldridge. Eldridge, secara
optimistik tiba pada kesimpulan dan harapan yang sama dengan Arief Budiman bahwa –
dalam kalimat Arief – “LSM telah menjadi saluran yang absah bagi partisipasi sosial dan
politik yang sebelumnya telah dibendung oleh pemerintah.”15 Dengan kata lain LSM
pada erea 80-an itu telah berhasil bergerak go beyond normative politics yang dominan di
era awal Orde Baru dan menghadirkan tantangan tersendiri terutama pada praktik
pembangunan kapitalisme Orde Baru.
Tantangan ini, tentu tidak dibiarkan begitu saja oleh negara. Pada tahun 1985 keluar
Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan yang mengenakan kontrol ketat terutama
dalam hal asal-usul pendanaan bagi LSM. Sementara pada tahun 1990 keluar lagi
Instruksi Mendagri No. 8 tahun 1990 (inmendagri) tentang Pembinaan LSM. Inmendagri
tersebut meminta dilakukannya inventarisasi dan pembinaan terhadap semua LSM di
bawah Departemen dalam Negeri serta diberlakukannya kontrol dengan melarang LSM
terlibat politik harus memelihara ideologi persatuan dan melaporkan dirinya ke
pemerintah.
15
Arief Budiman sebagaiman dikutip dalam Philip Eldridge (1989), “LSM dan Negara”, Prisma
Perkembangan dan perubahan ini dengan sendirinya menghadirkan warna dan karakter
baru dalam relasi LSM dan Negara di Indonesia secara umum, Eldridge merangkum
ketegangan itu di dalam tabel sebagai berikut:
Matriks: Model LSM
Setengah bergantung Dukungan Timbal
balik
Dalam sudut pandang empiris, kategori yang dikembangkan Eldridge di atas tampak
cukup mencerminkan pemetaan posisi dan aspirasi LSM di Indonesia terutama dalam
relasinya dengan negara. Namun demikian, penggambaran semacam ini boleh dibilang
sangat ditentukan oleh cara pandang Eldridge yang melihat posisi dan relasi itu dalam
kacamata dan sudut pandang LSM sebagai aktor utama. Pendekatannya sangat
institusional-behavioralistik. Akibatnya, dengan pendekatan semacam ini, Eldridge
kurang bisa menjelaskan sebab-sebab dan latar belakang mengapa relasi semacam itu
tercipta. Terbentuknya relasi yang panetratif, non-akomodatitf atau non-penetratif atau
akomodatif di dalam LSM yang berbeda-beda dalam banyak hal tidak ditentukan
banyak ditentukan oleh model mobilisasi dan penerapan kuasa politik rejim Orde Baru
serta watak ideologis dari LSM yang dimaksud.
Dengan demikian, Eldridge di sini kurang memperhatikan aspek-aspek terpenting dalam
politik korporatis negara Orde Baru pada waktu itu serta model-model akomodasinya
terhadap lingkungan di luar struktur negara. Akibatnya, ia cenderung untuk
menghomogenkan watak dan dinamika LSM yang berbeda-beda itu ke dalam sebuah
relasi umum yang non-politis dan non-ideologis. Dilupakan fakta bahwa cara LSM yang
berbeda dalam merespon kebijakan negara juga sangat menentukan terhadap bagaimana
negara merespon tantangan LSM-LSM itu sendiri; artinya harus ditegaskan fakta mana
saja kolaborator dan mana saja penantang otoritarianisme.
Namun demikian, keterbatasan analisis Eldridge ini tentu saja dapat dipahami mengingat
setting analisis tahun 80-an di mana gejolak dan protes kelompok-kelomppok sosial yang
menantang kebijakan negara sendiri pun masih sangat minim. Secara kasar memang bisa
dimengerti bahwa watak LSM secara umum pada era itu memang masih dipengaruhi oleh
diskursus pembangunan dan perpanjangan tangan negara.
Dominasi diskursus pembangunan Orde Baru ini bergeser dan mengalami tantangan yang
signifikan dan memasuki tahap yang kurang dibayangkan oleh analisis Eldridge, baru
terjadi pada akhir 80-an dan awal 90-an. Pada saat itu, aktor pendobrakan terhadap
diskursus pembangunan Orde Baru bertambah makin luas dengan melibatkan
kelompok-kelompok masarakat baru seperti buruh yang menyatu dengan gerakan mahasiswa serta
keterlibatan komunitas internasional yang makin intens dalam isu hak asasi manusia di
Indonesia.16
16
Salah satu batu penjuru yang memperlihatkan secara gamblang pendobrakan itu adalah
dengan munculnya kasus Kedung Ombo di tahun 1989. Perlawanan masyarakat terhadap
kasus ini memperlihatkan tiga hal penting: yaitu pertama adalah bahwa perlawanan itu
secara radikal membalik paradigma kemitraan LSM dengan pemerintah yang pada
awalnya dikesankan sebagai hubungan suka sama suka; kedua, kasus itu juga
menjungkirbalikan paradigma pembangunan Orde Baru yang sangat bergantung pada
fasilitasi dan saran-saran Bank Dunia dan IMF dan; ketiga, kasus ini menjadi pengantar
bagi kemunculan relasi dan pertemuan antara LSM dengan aktor lama perubahan politik
di Indonesia, yaitu gerakan mahasiwa. Dari kasus ini, pengalaman dan kekuatan baru
tumbuh dalam diri LSM di Indonesia. Kritik mereka terhadap lembaga-lembaga
pembangunan dunia yang intens dan keras dalam kasus itu mengantarkan mereka ke
dalam pertautan yang lebih intens dengan lembaga-lembaga internasional, sementara di
dalam negeri persekutuan yang mereka jalin dengan komite aksi dan
kelompok-kelompoik mahasiswa memberikan tenaga baru bagi mereka dalam merespon
kebijakan-kebijkan sosial politik Orde Baru pada waktu itu.
Dari Jaman Pembangunan ke Jaman Hak
Pada tahun 1993, tahun di mana Komnas HAM didirikan, beberapa peristiwa dan debat
penting mengenai LSM sedang hangat-hangatnya berlangsung di media masa.
Ketua Komisi X DPR Markus Wauran, anggota FPP DPR Jusuf Syakir, dan Wakil Ketua Komisi II DPR Soetardjo Soerjogoeritno secara terpisah di sini kemarin menegaskan keberadaan LSM yang berorientasi pada kepentingan donatur jelas melanggar ketentuan Instruksi Mendagri 8/1990. Karena itu mereka minta Mendagri segera turun tangan.17
Lebih jauh lagi artikel yang sama menyampaikan pernyataan sebagai berikut:
17
… tidak ada pihak yang melarang LSM menerima bantuan luar negeri tapi yang diharapkan [adalah] mereka tidak bekerja demi kepentingan pemberi dana, bukan menelanjangi negeri sendiri.18
Dana dan donor asing merupakan isu paling sensitif sekaligus paling sering diangkat
dalam setiap konflik dan ketegangan antara negara versus LSM di Indonesia, bahkan
hingga 10 tahun terakhir setelah tahun 1993 itu. Dari isu ini tampak satu hal yang pasti
yakni bahwa ketidakmampuan LSM dalam mengelola dan menggalang dana untuk
dirinya sendiri merupakan the weakest link yang paling diminati untuk dipakai oleh
pemerintah untuk menghantam karakter LSM. Di kalangan pemerintah, terdapat dua
pandangan simultan yakni pertama bahwa hidup LSM bergantung pada donor asing dan
sekaligus – karena itu – pemerintah asing bisa memperalat LSM-LSM tersebut untuk
menancapkan kepentingannya di Indonesia. Menghantam donor asing – yang pada
konteks itu merupakan satu-satunya sumber hidup LSM – jelas merupakan semacam
senjata pamungkas untuk menekan dan mematikan LSM. Yang jadi pertanyaanya di sini
adalah mengapa dan bagaimana mungkin soal donor asing ini dikaitkan dengan LSM?
Pertautan politik antara LSM dan pihak asing sebenarnya telah disinyalir dan dihadapi
oleh rejim Soeharto dan pada waktu itu diantisipasi dengan menerbitkan UU No. 8/ 1985
yang mengharuskan laporan dan kontrol ketat terhadap penggunaan dana asing oleh
LSM. Namun demikian, kekhawatiran dan “kejengkalan” rejim terhadap LSM dan donor
asing dalam konteks itu memang bisa dirujuk dari figur yang memperlihatkan himpitan
kepentingan antara isu-isu yang dibawa oleh LSM yang paralel dengan tuntutan sejumlah
pemerintah asing.
Sebagaimana diketahui, peran dan intervensi lembaga-lembaga pembangunan asing
sebenarnya telah diterima dan bahkan demikian marak di era 80-an. Ini tampak dari
demikian kuatnya wacana pembangunan dan peran bank dunia, IGGI dan yang lainnya
dalam panorama pembangunan ekonomi Orde Baru. Namun demikian pada era tersebut,
bantuan dan hubungan dengan lembaga asing itu masih berjalan dalam satu skenario
18