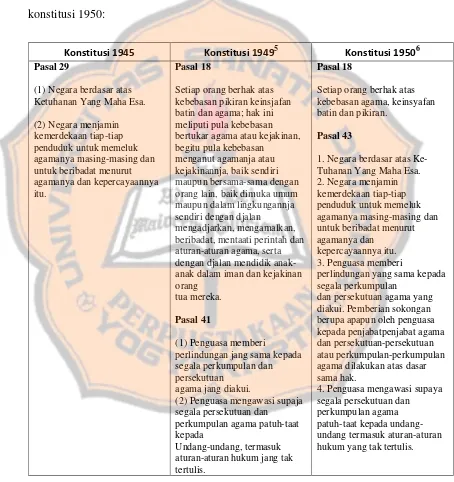SABULUNGAN DALAM TEGANGAN IDENTITAS BUDAYA:
KAJIAN ATAS RELIGI ORANG MENTAWAI
DI SIBERUT SELATAN
TESIS
Diajukan untuk mememenuhi persyaratan mendapat gelar Magister Humaniora (M.Hum)
di Program Magister Ilmu Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma
Disusun oleh:
KORNELIUS GLOSSANTO 156322006
PROGRAM MAGISTER ILMU RELIGI DAN BUDAYA UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA
ii
SABULUNGAN DALAM TEGANGAN IDENTITAS BUDAYA:
KAJIAN ATAS RELIGI ORANG MENTAWAI
DI SIBERUT SELATAN
TESIS
Diajukan untuk mememenuhi persyaratan mendapat gelar Magister Humaniora (M.Hum)
di Program Magister Ilmu Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma
Disusun oleh:
KORNELIUS GLOSSANTO 156322006
PROGRAM MAGISTER ILMU RELIGI DAN BUDAYA UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA
iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
TESIS
SABULUNGAN DALAM TEGANGAN IDENTITAS BUDAYA: KAJIAN ATAS
RELIGI ORANG MENTAWAI DI SIBERUT SELATAN
Oleh
Kornelius Glossanto
NIM: 156322006
Telah disetujui oleh:
Yustinus Tri Subagya, M.A., Ph.D. Pembimbing
iv
HALAMAN PENGESAHAN
TESIS
SABULUNGAN DALAM TEGANGAN IDENTITAS BUDAYA: KAJIAN ATAS RELIGI ORANG MENTAWAI DI SIBERUT SELATAN
Oleh
KORNELIUS GLOSSANTO NIM: 156322006
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis pada tanggal 8 Januari 2019
dan telah dinyatakan memenuhi syarat.
Tim Penguji
Ketua : Dr. Y. Devi Ardhiani, M. Hum. ...
Sekretaris/Moderator : Dr. G. Budi Subanar, SJ. ...
Anggota : Dr. St. Sunardi ...
Dr. Y. Devi Ardhiani, M. Hum. ...
Yustinus Tri Subagya, M.A., Ph.D. ...
Yogyakarta, 18 Januari 2019
Direktur Program Pascasarjana
v
PERNYATAAN KEASLIAN
Yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama : Kornelius Glossanto NIM : 156322006
Program : Magister Ilmu Religi dan Budaya Universitas : Sanata Dharma
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis:
Judul : Sabulungan dalam Tegangan Identitas Budaya: Kajian atas Religi Orang Mentawai di Siberut Selatan
Pembimbing : Yustinus Tri Subagya, M.A., Ph.D. Tanggal diuji : 8 Januari 2019
Adalah benar-benar hasil karya saya.
Di dalam tesis/ karya tulis/ makalah ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan atau gagasan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang saya aku seolah-oleh sebagai tulisan saya sendiri tanpa memberi pengakuan kepada penulis aslinya.
Apabila kemudian terbukti bahhwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Program Magister Ilmu Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, termasuk pencabutan gelar Magister Humaniora (M. Hum.) yang telah saya peroleh.
Yogyakarta, 8 Januari 2019
Yang memberikan pernyataan
vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS
Nama : Kornelius Glossanto NIM : 156322006
Program : Magister Ilmu Religi dan Budaya
Demi keperluan pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta karya ilmiah yang berujudil:
SABULUNGAN DALAM TEGANGAN IDENTITAS BUDAYA: KAJIAN ATAS RELIGI ORANG MENTAWAI DI SIBERUT SELATAN
Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolahnya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lainya demi kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya atau memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.
Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.
Dibuat di : Yogyakarta Pada tanggal : 8 Januari 2019 Yang menyatakan
vii
HALAMAN PERSEMBAHAN
Sura’ Sabeu kukua ka
Ulaumanua Sipulubeunan,
Tulisan ini saya persembahkan kepada:
Sa’sara’inakku ka sangamberi polak Mentawai,
Keluarga dan para sahabat,
Universitas Sanata Dharma,
Serikat Misionaris Xaverian
dan
Kepada mereka yang selalu berhasrat untuk mengenal yang lain dan
viii ABSTRAK
Berbicara mengenai budaya orang Mentawai tidak bisa dilepaskan dari telaah mengenai sabulungan. Kepercayaan lokal Mentawai yang mengakui keberadaan dan pengaruh roh-roh alam tersebut seringkali dilukiskan sebagai landasan keselarasan manusia dan lingkungannya. Pada tahun 1954 peristiwa Rapat Tiga Agama menjadi
sarana legitimasi tindakan pelarangan sabulungan. Hal tersebut dilatarbelakangi upaya
negara ‘mendisiplinkan’ agama di Indonesia sebagai bentuk pengakuan atas Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dominasi yang diwarnai tindak diskriminasi dan kekerasan. itu memunculkan konflik ideologi antara negara dan orang Mentawai di Siberut. Tesis ini berisikan ulasan mengenai bagaimana dominasi negara atas sebuah kepercayaan lokal di Siberut memicu timbulnya perlawanan terselubung dari orang Mentawai yang berusaha menjaga identitas budaya mereka. Model perlawanan tersebut menurut kajian James C. Scott merupakan ‘senjata orang-orang yang kalah’ menghadapi kelas yang mendominasi kehidupan mereka. Ritual-ritual tradisi sabulungan ditampilkan kembali sebagai ekspresi budaya sambil menghidupi keberagamaan sesuai anjuran dan tuntutan pemerintah. Upaya revitalisasi budaya melalui semangat inkulturatif yang ditawarkan Gereja Katolik dan penyadaran nilai-nilai budaya melalui pendidikan berjalan namun bukan tanpa halangan. Makin lunturnya penghayatan akan sabulungan dan nilai budaya di dalamnya serta perubahan gaya hidup modern menunjukkan gegar budaya dan ambivalensi yang dialami orang Mentawai di Siberut dewasa ini.
ix ABSTRACT
Talking about the culture of the Mentawai people cannot be separated from the study of Sabulungan. Mentawai local beliefs that recognize the existence and influence of these natural spirits are often described as the basis of harmony between humans and their environment. In 1954 the event of the Three Religion Meeting became a means of legitimizing the prohibition of sabulungan. This was motivated by the state's efforts to 'discipline' religion in Indonesia as a form of recognition of the One Precept of Godhead. Domination is characterized by acts of discrimination and violence. It gave rise to ideological conflicts between the state and the Mentawai people on Siberut. This thesis contains a review of how the state's dominance of a local belief in Siberut triggered the emergence of covert resistance from the Mentawai people who tried to maintain their cultural identity. The resistance model according to James C. Scott's study is "the weapons of the weak" facing a class that dominates their lives. The rituals of the Sabulungan tradition are reappeared as cultural expressions while living religion according to the recommendations and demands of the government. Efforts to revitalize culture through the inculturative spirit offered by the Catholic Church and awareness of cultural values through education but not without obstacles. The fading away of appreciation of sabulungan and cultural values in it and changes in modern lifestyles show cultural shock and ambivalence experienced by Mentawai people in Siberut today.
x
KATA PENGANTAR
Tulisan ini semata-mata bukan merupakan karya ilmiah yang disusun atas
tuntutan studi dan keperluan akademis. Seluruh rangkaian penyusunan tesis ini ibarat
sebuah perjalanan; perjalanan untuk keluar dari diri sendiri dan membuka hati bagi yang
lain. Pengalaman satu setengah tahun hidup bersama konfrater Xaverian di pastoran
Siberut berdampingan dengan para suster ALI dan KSFL dan saudara-saudara di
Mentawai, terutama di Siberut Selatan telah berhasil menggerakkan saya untuk mencintai
dunia baru tersebut. Melihat kembali ke belakang, betapa saya sangat berterima kasih
kepada: Ferdinanda Maria Saurei, Juliasman Satoko, Marinus Satoleuru, dan Albertina
Sakukuret, yang telah membukakan mata dan hati saya akan keunikan bumi sikerei.
Terima kasih keluarga baruku di Siberut, terutama pula kepada anak-anak di asrama St.
Yosef dan St. Theresia Lisieux yang dengan cara kalian telah membuka mulut saya dan
mengajari saya berceloteh dengan bahasa Mentawai.
Selama kesempatan-kesempatan kunjungan selanjtutnya saya juga banyak
dibantu oleh Marinus Satoleuru dan Petrus Marjuni untuk berjumpa dengan para
narasumber. Terima kasih juga atas kesediaan berbagi kisah-kisah kalian: Marinus Saurei,
Elyzius Sakeletuk, Bruno Tatebburuk, Teu Lomoi Samalinggai, Hieronimus Keppa
Salakoppak, Mateus Samalinggai, Yohanes Laidoak Sanambaliu, pasangan Agustinus
Salemurat dan Marianna Saruruk, Pakirek Salakkirat, Marinus Salolosit, Anton
xi
Saurei, Mateus Sakukuret, Thomas Tatebburuk, Yohanes Salakopak, dan Selester
Sagurujuw. Kisah pengalaman kalian merupakan pemberian tak ternilai bagi saya yang
masih mulai menulis kisahnya sendiri. Sura’ sabeu ku kua ka sarainaku: Siprianus Sokkot
Sagoroujou dan Eujenius Salemurat yang telah banyak membantu menterjemahkan
banyak hal yang masih baru bagi saya dan terutama semangat yang tak lelah dikobarkan
sehingga akhirnya kisah ini bisa dirasakan lebih dekat dan berhasil dituntaskan. Masura’
bagatta ku kua ka tubumui.
Terima kasih pula kepada Yustinus Tri Subagya, dosen dan pembimbing
saya, yang telah dengan sabar meluangkan waktu dan perhatiannya mendampingi saya
yang masih sangat awam dalam penysusunan karya ini. Terima kasih pula kepada para
dosen dan teman-teman di IRB Sanata Dharma atas segala bentuk perhatian dan
sumbangan pengetahuan, pengalaman, dan kisah-kisahnya. Sebagai lulusan ilmu teologi
yang berkutat dengan konsep-konsep mengangkasa, pengalaman belajar bersama kalian
telah berhasil menghempaskan saya kembali untuk tidak lupa berpijak pada bumi
manusia ini dengan segala kompleksitasnya.
Akhirnya kepada ayahanda tercinta Fransiskus Xaverius Tarwoto dan Mas
Lukas Sadhana, banyak terima kasih atas dukungan dan doanya yang tak kunjung putus,
bahkan makin bertambah di saat rasa putus asa sudah menyelimuti perjalanan pendidikan
ini. Kepada seluruh keluarga dan saudara-saudaraku yang selalu menyemangati dan
mendukung dari kejauhan, banyak terima kasih untuk cintanya. Akhirnya kepada Serikat
Xaverian yang telah mempercayakan misi pembelajaran ini kepada saya, yang mengantar
saya mengarungi gugusan pulau-pulau di Mentawai hingga pelosok Nusantara, saya
xii DAFTAR ISI
JUDUL ... i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ... iii
HALAMAN PENGESAHAN ... iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ... v
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI ... vi
HALAMAN PERSEMBAHAN... vii
ABSTRAK ... viii
ABSTRACT ... ix
KATA PENGANTAR ... x
DAFTAR ISI ... xii
BAB I : PENDAHULUAN... 1
A. Latar Belakang ... 1
B. Tema Penelitian ... 3
C. Rumusan Masalah... 3
D. Tujuan Penelitian ... 4
E. Manfaat Penelitian ... 4
F. Kajian Pustaka ... 5
G. Kerangka Teori ... 18
xiii
I. Sistematika Penulisan ... 29
BAB II : KEPULAUAN MENTAWAI, ORANG SIBERUT, DAN SABULUNGAN ... 30
A. Gambaran Umum Kepulauan Mentawai ... 31
1. Lokasi Geografis ... 31
2. Kependudukan ... 34
B. Gagasan Mengenai Komunitas Orang Mentawai ... 36
1. Mitos Asal-Usul Orang Mentawai ... 39
2. Perjumpaan Orang Mentawai dengan Petualang, Aparat Kolonial, dan Misionaris ... 41
C. Sabulungan dan Negara ... 46
D. Upaya Pembatasan Sabulungan ... 50
E. Memudarnya Sabulungan dari Kehidupan Orang Mentawai ... 56
BAB III : SABULUNGAN, PANDANGAN HIDUP DAN RITUS KEHIDUPAN ORANG MENTAWAI ... 61
A. Sabulungan dan Sikebukat ... 63
B. Sabulungan dan Pandangan Hidup Simatoi ... 65
1. Kehidupan yang Diidamkan: Hidup Panjang dan Kematian yang Baik ... 66
2. Ritual dalam Siklus Kehidupan Manusia dan Relasi dengan Alam ... 69
xiv
A. Dominasi Negara dan ‘Pemaksaan’ Agama Resmi ... 79
B. Siasat Sikebukat dan Pemerhati Sabulungan ... 85
C. Ekspresi Sabulungan ... 91
D. Identitas Budaya: Ambivalensi Orang Mentawai ... 96
BAB V : PENUTUP ... 102
A. Kesimpulan... 102
B. Tanggapan ... 104
Lampiran ... 105
1 BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Sebagai anggota sebuah kongregasi religius misioner dalam Gereja Katolik, selama
masa pendidikan periode tahun 2012-2014, saya mendapat kesempatan untuk berkarya di
sebuah paroki di Siberut. Siberut merupakan satu dari empat pulau utama – dan juga pulau
terbesar – di wilayah Kepulauan Mentawai. Pada tahun 1999 wilayah kepulauan ini
berdiri secara otonom – memisahkan diri dari Kabupaten Padang Pariaman – sebagai
sebuah kabupaten (Kab. Kepulauan Mentawai) dengan ibu kota Tuapeijat dan menjadi
salah satu dari 12 kabupaten di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Mayoritas penduduk di
kepulauan ini dikenal sebagai suku Mentawai dan hidup berdampingan dengan para
pendatang yang berasal dari suku Minangkabau, Nias, Batak, Jawa dan Flores.
Dalam sejarah Gereja Katolik, kegiatan misi di wilayah kepulauan Mentawai
dimulai pada tahun 1954 oleh para misionaris dari Serikat Xaverian. Dan hingga saat ini,
agama-agama samawi telah dikenal di hampir seluruh wilayah kepulauan itu. Suku
Mentawai memiliki kepercayaan tradisional yang dikenal dengan istilah sabulungan.
Sabulungan berasal dari dua kata sa = bentuk plural dari sebuah kesatuan dan bulu =
2
sabulungan mengandung unsur keyakinan akan roh-roh yang dihormati dengan berbagai
ritual persembahan (Juniator, 2012: 69).
Selama bertugas di Siberut, penulis mengamati sebagian orang masih mempercayai
bahwa sakit tertentu bisa jadi disebabkan oleh perjumpaan antar roh (simagre). Oleh
karena itu alih-alih pergi berobat ke puskesmas, mereka memilih memanggil sikerei
(tabib tradisional) untuk mengobati orang yang mengalami sakit tertentu. Padahal di kota
kecamatan di Muara Siberut, telah berdiri Puskemas dan Poliklinik yang dikelola oleh
para suster ALI (Assistenti Laiche Internazionali)1. Peristiwa ini menarik bagi penulis,
mengingat mayoritas masyarakat Siberut telah menganut agama Katolik (83,49%) dan
Protestan (14,39%).2 Masih dilibatkannya sikerei dalam pengobatan tidak terlepas dari
tradisi sabulungan yang mempercayai bahwa munculnya penyakit berasal dari pengaruh
kekuatan supranatural.
Banyak dari orang Mentawai di Siberut yang kendati telah menganut salah satu
agama resmi yang ada di sana, seperti Katolik, Protestan maupun Islam, dalam keseharian
tetap memegang pantangan-pantangan atau menjalankan ritual-ritual yang
dilatarbelakangi oleh tradisi sabulungan.3 Namun tidak sedikit juga orang Mentawai yang
sudah tidak mengenal lagi sabulungan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan identitas
budaya mereka. Sejarah masa lalu di mana sabulungan dilarang oleh pemerintah,
perubahan gaya hidup, dan pembangunan daerah, menjadikan generasi muda orang
Mentawai mulai tercabut dari akar religiositasnya sendiri. Fenomena inilah yang menarik
bagi saya untuk dikaji lebih dalam. Bagaimana masyarakat Mentawai di P. Siberut
1 ALI atau juga dikenal Institut Sekulir “Mater Amabilis” berdiri pada 11 Oktober 1952 di Milan, Italia.
Permohonan Prefek Apostolik Padang, Mgr. Pasquale de Martino, atas tenaga biarawati yang berkarya di bidang medis menjadi latar belakang pembentukan institut tersebut.
3
bersiasat untuk menjaga nilai-nilai religi budaya yang terkandung dalam sabulungan
berhadapan dengan dominasi negara, pewarta agama serta masuknya budaya modern.
1.2. TEMA PENELITIAN
Sabulungan merupakan kepercayaan tradisional orang Mentawai. Orang Mentawai
pada awalnya tidak memiliki istilah tertentu untuk menyebut sistem kepercayaan mereka
atau ‘agama’. Pasca kemerdekaan Indonesia melalui Rapat Tiga Agama4, tahun 1954
keberadaan sabulungan dilarang. Namun selama perjalanan waktu, pengaruh larangan
tersebut mulai memudar dan membuat orang Mentawai saat ini memiliki pandangan dan
sikap yang berbeda atas kepercayaan lokal tersebut. Sebagian dari mereka masih
memandang sabulungan sebagai sumber identitas budaya Mentawai dan mencoba
mempertahankannya. Sebagian lagi berada dalam situasi ambivalen antara hendak
melupakan dan meninggalkan tradisi tersebut atau menghidupinya dengan cara baru.
1.3. RUMUSAN MASALAH
1. Mengapa negara melalui aparatusnya berusaha menghapuskan sabulungan?
Kapan dan dengan cara bagaimana usaha penghapusan itu berlangsung?
2. Bagaimana pandangan orang Mentawai saat ini tentang sabulungan dan
ritus-ritusnya dalam kehidupan sehari-hari?
3. Bagaimana siasat orang Mentawai mempertahankan sabulungan dan di mana
posisi sabulungan dalam pandangan orang Mentawai saat ini?
4 Coronesse mencatat perwakilan Rapat Tiga Agama ini merujuk pada Islam, Protestan, dan Arat
4 1.4. TUJUAN PENELITIAN
Melalui rumusan persoalan di atas penulis mencoba menggali data di lapangan dan
sejumlah literatur mengenai dominasi negara, pengaruh agama-agama samawi,
perubahan pola hidup terhadap religi orang Mentawai yang terkandung dalam
kepercayaan sabulungan. Hal itu bertujuan untuk mengungkap beberapa poin di bawah
ini:
1. Untuk mengetahui alasan, waktu pelaksanaan dan cara-cara yang dilakukan
negara dalam usaha menghapuskan sabulungan.
2. Untuk menganalisa bagaimana sabulungan dan ritus-situsnya dipandang dalam
kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Mentawai dewasa ini.
3. Untuk melihat siasat orang Mentawai mempertahankan sabulungan dan di mana
posisi sabulungan dalam pandangan orang Mentawai saat ini.
1.5. MANFAAT PENELITIAN
Penelitian ini berguna untuk melihat bagaimana dominasi negara terhadap
kepercayaan lokal – seperti yang tampak dalam pelarangan sabulungan – terjadi di
lapangan. Selain itu dari hasil penelitian ini bisa juga dilihat bagaimana orang Mentawai
di Siberut Selatan mempertahankan dan menghidupi religiositas mereka di tengah
pengaruh pembangunan, kehadiran agama-agama samawi, serta perubahan pola
kehidupan. Informasi ini akan sangat berguna untuk melihat sejarah perubahan identitas
budaya dan religi orang Mentawai serta mengungkap faktor-faktor apa saja yang turut
5 1.6. KAJIAN PUSTAKA
Dalam bagian ini akan diuraikan dua pokok pemikiran mengenai konsep agama dan
relasi kepercayaan lokal dengan agama-agama resmi pemerintah. Pertama akan kita lihat
bagaimana konsep agama dikonstruksi di Indonesia. Selanjutnya pada bagian kedua akan
diulas secara singkat bagaimana kepercayaan-kepercayaan lokal berhadapan dengan
agama-agama ‘resmi’ di Indonesia dan sejarah perkembangannya hingga saat ini.
1.Konsep Agama di Indonesia
Richard King dalam bagian kedua bukunya Agama, Orientalisme dan
Poskolonialisme (2001) menjelaskan bagaimana sejarah terjadinya pergeseran makna
‘agama’. Ia merujuk pada konsep Cicero di masa pra-Kristen yang mengatakan akar kata
‘agama’ (religion) adalah bahasa Latin religio. Kata religio memiliki kaitan dengan kata
religere yang berarti ‘melacak kembali’ atau ‘membaca ulang’. Cicero dengan alur
pemikiran tersebut ingin memperlihatkan bahwa konsep ‘agama’ pada dasarnya berkaitan
erat dengan usaha menghadirkan kembali adat dan ritual dari nenek moyang atau leluhur
sebuah kelompok (King 2001: 68). Dalam pandangan ini ‘agama’ mengacu pada konsep
yang lebih luas dan memungkinkan dinamika kehidupan yang pluralistik. Karena jelas
dengan adanya beragam tradisi dan budaya di dunia, dimungkinkan juga muncul beragam
‘agama’. Dari konsep ini semua bentuk kepercayaan dan tradisi budaya lokal suku-suku
di Indonesia – seperti Kaharingan, Merapu, Parmalim, Sabulungan –bisa dikategorikan
sebagai agama. Namun rupanya sejarah memperlihatkan alur yang beragam.
Pada abad ke-3 ditemukan karya seorang penulis Kristen, Lactantius, yang menolak
konsep ‘agama’ Cicero. Lactantius berpendapat bahwa kata religio berasal dari kata Latin
6
Lactantius memperlihatkan bahwa religio merupakan hubungan atau ikatan antara Yang
Ilahi dan manusia. Ia juga kemudian mempertentangkan antara kelompok yang
menyembah dewa-dewa dan mereka yang percaya kepada Tuhan sebagai entitas yang
tunggal, sebagai sumber kebenaran. Hal ini mengakibatkan berakhirnya kehidupan yang
pluralistik karena pergeseran makna ‘agama’ dari pemikiran Cicero kepada pandangan
Lactantius menyebabkan pula ketidaksetaraan antara kelompok-kelompok yang ada.
Dalam hal ini Kekristenan menempatkan diri sebagai pemegang kebenaran karena konsep
monoteisnya dan memandang kelompok-kelompok penyembah dewa-dewa dan tradisi
nenek moyang sebagai orang yang terbelakang atau kaum pagan yang masih percaya pada
takhayul. King menyimpulkan bahwa perubahan makna semantik sebagaimana
dijelaskan Lactantius menyebabkan perubahan seluruh konsep mengenai ‘agama’.
Sehingga diskusi-diskusi mengenai istilah ‘agama’ atau religio pada masa modern hingga
saat ini cenderung mengacu pada pemikiran Lactantius, di mana ‘agama’ dikonstruksikan
dalam paradigma Kekristenan yang secara eksklusif menitikberatkan konsep-konsep
keyakinan teistik – baik dalam wujud mono- , poli-, heno-, atau pan- teistik. Selain itu
muncul pula konsep dualisme antara dimensi Ilahi dan dimensi manusiawi serta konsep
dunia yang suci atau transenden di mana manusia mengikatkan diri (religare) kepadanya.
Dengan demikian menurut King, konsep ‘agama’ merupakan konstruksi sosio-kultural
yang khas dengan genealoginya sendiri yang khas juga (King, 2001: 71-76).
Berbeda dari Lactantius dan Cicero, Clifford Geertz memiliki definisi tersendiri
mengenai agama. Ia pertama-tama melihat agama sebagai sebuah sistem simbol.
Demikian definisi Geertz atas agama (Geertz, 1992: 5):
7
konsep-konsep mengenai suatu tatatan umum eksistensi dan (4) membungkus konsep-konsep ini dengan semacam pancaran faktualitas, sehingga (5) suasana hati dan motivasi-motivasi itu
tampak khas dan realistis.”
Pernyataan Geertz tentang agama yang demikian ini jelas memberikan ‘konsep agama’
ruang lingkup yang sangat luas. Baik agama-agama besar dunia seperti Hinduisme,
Kekristenan, Yahudi maupun Islam hingga kepercayaan-kepercayaan tradisional sebuah
suku tertentu termasuk dalam definisi tentang agama itu.
Menurut Geertz dalam kacamata antropologi sebuah agama menjadi penting karena
berfungsi sebagai sumber konsep atau gagasan yang umum dan jelas – mengenai dunia
kehidupan, mengenai pribadi manusia, dan juga bagaimana relasi antara keduanya itu –
bagi pribadi-pribadi tertentu maupun juga bagi sebuah kelompok masyarakat (Geertz,
1992: 46). Fungsi yang demikian dapat dengan mudah ditemui juga dalam sistem
kepercayaan lokal yang ada di Indonesia. Masing-masing kepercayaan tersebut dengan
jelas dan sistematis memperlihatkan bagaimana pola relasi antara manusia dan alam
kehidupannya. Dengan demikian jika menggunakan sudut pandang antropologis seperti
diuraikan oleh Geertz, sistem kepercayaan lokal yang begitu banyak di Indonesia juga
bisa dikategorikan sebagai agama.
Kata ‘agama’ dalam bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai:
“sistem, prinsip kepercayaan kepada Tuhan (dewa dsb) dengan ajaran kebaktian dan
kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu.” (KBBI edisi ke-2, cetakan
ke-4, 1995). Namun jika dilihat dalam sejarah, kata ‘agama’ yang kita kenal saat ini telah
mengalami rangkaian proses pemaknaan yang panjang. Dalam sejarah bangsa Indonesia
8
ini untuk berdagang. Kehadiran para penjelajah samudera dan pedagang ini lah yang
memperkenalkan bentuk baru religiositas. Pada masa itu pengaruh Hinduisme dan
Budhisme mulai tersebar sehingga memunculkan kerajaan-kerajaan Hindu dan Budha.
Kemunculan kerajaan-kerajaan tersebut memberikan gambaran bagaimana ‘agama’ telah
menjadi sumber legitimasi politis dan status sosial. Pada masa itu menjadi ber-‘agama’
pertama-tama berarti menjadi modern, berkuasa, dan sejahtera (Ropi, 2017: 44).
Di Indonesia kata ‘agama’ diterima begitu saja secara umum untuk
menterjemahkan kata ‘religion’. Padahal secara semantik kata ‘agama’ memiliki makna
yang lebih sempit dari kata ‘religi’ – yang juga diadopsi dalam bahasa Indonesia dari
bahasa Belanda ‘religie’. Kata ‘agama’ sendiri berasal dari bahasa Sansekerta yang
memiliki makna harafiah ‘abadi’ dan membawa gagasan mengenai pewahyuan
(revelation). Menurut Michael Picard (2011), hal ini yang menjadikan konsep mengenai
agama di Indonesia menjadi unik. Menurutnya kata ‘agama’ merupakan paduan unik:
sebuah kata Sansekerta yang mengandung pandangan Kekristenan mengenai apa yang
disebut sebagai agama dunia dengan pemahaman Islam tentang apa yang didefinisikan
sebagai agama yang tepat. Agama yang tepat dalam pandangan itu mengandung
unsur-unsur seperti: sebuah wahyu Ilahi yang direkam dalam kitab suci oleh para nabi utusan,
sistem peraturan bagi pemeluknya, upacara pujian bagi umat, dan pengakuan atau
keyakinan akan Tuhan yang Esa (Picard, 2011:3, 2017: 25). Unsur Tuhan, Nabi, dan
Kitab suci menjadi elemen utama sebuah agama (Ropi, 2017:119). Kategori-kategori
tersebut kemudian digunakan oleh Departemen Agama sebagai syarat sebuah ‘agama’ di
Indonesia. Rupanya syarat-syarat ini-lah yang kemudian diusulkan oleh Departemen
Agama pada tahun 1952 sebagai kategori resmi untuk melihat apakah sebuah
9
Sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia para tokoh kemerdekaan sepakat
bahwa agama merupakan elemen yang penting bagi negara (Ropi, 2017:57). Namun
dalam perkembangannya sejak kemerdekaan Indonesia pada 1945 terdapat sedikit
perubahan mengenai kedudukan agama dalam Undang-Undang Dasar. Tabel berikut
memperlihatkan bagaimana kedudukan agama dalam konstitusi 1945, konstitusi 1949 dan
konstitusi 1950:
Konstitusi 1945 Konstitusi 19495 Konstitusi 19506
Pasal 29
5 Konstitusi Republik Indonesia Serikat sebagaimana diputuskan dalam Keppres Nomor 48 Tahun 1950 6 Undang-Undang Republik Indonesia Serikat Nomor 7 Tahun 1950
10
Meskipun terdapat sejumlah perubahan yang terjadi dalam kebijakan negara atas agama
di Indonesia, dalam ketiga model konstitusi negara tidak tercantum agama apa saja yang
dimaksud. Dan walaupun tampak bahwa kebebasan beragama dan menganut kepercayaan
warga negara dijamin oleh pemerintah, dalam praktiknya wujud jaminan dan pengakuan
kebebasan beragama tersebut masih terus mengalami perubahan yang panjang. Baru
dalam TAPPRES NO.1/PNPS/Tahun 1965 pemerintah secara eksplisit menyatakan 6
agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khong Hu Cu – sebagai agama yang
dipeluk oleh orang Indonesia dan yang muncul dalam sejarah perkembangan
agama-agama di Nusantara.Pada masa Orde Baru berdasar Tap MPR No.4 Tahun 1978, secara
tertulis kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dipandang berbeda dengan agama.
Selanjutnya keberadaan aliran kepercayaan tradisional atau agama-agama lokal tidak lagi
berada dalam wewenang Departemen Agama melainkan dipercayakan kepada
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Jenderal Budaya kemudian
membentuk direktorat baru yakni Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa dan Tradisi (Picard, 2011:15). Kemunculan Tap MPR No.4 Tahun 1978
menjadi awal mula peraturan pemerintah yang mewajibkan pengisian kolom agama
dalam pembuatan KTP. Dampaknya banyak penganut agama lokal yang harus
menghadapi pilihan antara mengkonversi keyakinan mereka pada agama-agama yang
diakui oleh pemerintah, atau berjuang dan berafiliasi dengan salah satu agama resmi
tersebut.
Aliran-aliran kepercayaan tradisional yang telah ada di Nusantara jauh sebelum
kemerdekaan akibatnya harus menerima nasib diwacanakan sebagai sesuatu yang kuno,
asing, dan penghalang terbentuknya masyarakat yang merdeka dan modern. Padahal
11
diwariskan dan mewarnai kehidupan suku turun-temurun. Para penganut aliran
kepercayaan dalam rezim pemerintahan Orde Baru disamakan statusnya sebagai orang
yang ‘belum beragama’ dan kelompok ini juga belum diakui sebagai warga negara
seutuhnya. Mereka dipandang oleh pemerintah sebagai kelompok yang perlu
‘diberadabkan’ (Ropi, 2017:155). Untuk itu masyarakat dalam kelompok ini harus
menganut salah satu dari enam agama yang diakui oleh pemerintah sehingga agar bisa
memperoleh pengakuan dan pelayanan dari pemerintah sebagai warga negara dan bagian
dari kelompok masyarakat modern.
Sejarah pembentukan konsep agama di Indonesia dan penerapannya dalam
kebijakan negara telah memunculkan apa yang dikenal dengan politik rekognisi. Hal ini
mengacu pada upaya kelompok mayoritas yang berkuasa untuk menggunakan agama
sebagai alat legitimasi kekuasaan untuk mengontrol kelompok minoritas, yang dalam
kasus di atas merupakan para penghayat aliran kepercayaan.
2. Agama Lokal vs Agama ‘Resmi’
Sebelum tahun 1950an sistem kepercayaan tradisional orang Mentawai dikenal
dengan nama sabulungan. Baru setelah kemerdekaan di tahun 1950an itu, pemerintah dan
para misionaris menambahkan kata arat untuk menyebut sistem kepercayaan lokal
tersebut sebagai agama. Sebenarnya kata arat merupakan adaptasi dari kata dalam bahasa
Indonesia ‘adat’ (custom). Sebelum kata arat digunakan, orang Mentawai menggunakan
kata punenyang berarti ‘kegiatan’ (activity) baru dalam perjalanan waktu kata ini berubah
menjadi arat. Kata arat sendiri memiliki makna yang lebih luas. Ia bisa berarti
peraturan-peraturan, norma-norma, adat maupun kebiasaan-kebiasaan (Juniator, 2012: 68).
Kehadiran agama-agama dari luar dan peristiwa yang dikenal dengan Rapat Tiga
12
Rapat Tiga Agama sendiri muncul dengan latar belakang program pemerintah pasca
kemerdekaan yang bertujuan untuk menyatukan suku-suku dari seluruh nusantara dalam
kelompok sosial dan budaya utama yang bersifat nasional (Persoon 2004: 23; Mulhadi
2007: 20-21; Juniator 2012:72). Mulhadi menulis bahwa pelarangan sabulungan oleh
pemerintah pada 1954 bukan karena kepercayaan tersebut mengandung unsur ajaran
sesat atau juga bukan merupakan sempalan dari agama-agama resmi yang diakui negara.
Kepercayaan tradisional suku Mentawai itu dilarang karena ketakutan pemerintah yang
memandang sistem kepercayaan itu berpotensi mengancam kestabilan Negara Kesatuan
(Mulhadi, 2007:14). Kekhawatiran pemerintah ini kemudian dipertegas dengan
dikeluarkannya UU No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau
Penodaan Agama. Menurut Komisioner Komnas HAM, Imdadun Rahmat, UU tersebut
lahir dari keinginan pemerintah Soekarno dalam usaha membendung ateisme dan
beragam upaya merekayasa bentuk aliran-aliran baru yang kehadirannya bisa merusak
agama-agama yang telah ada7.
Dengan pelarangan atas sabulungan serta praktik-praktiknya, pemerintah daerah
Sumatera Barat bersama dengan aparat melarang segala bentuk praktik yang berkaitan
dengan kepercayaan lokal tersebut bahkan juga membakar dan memusnahkan
benda-benda yang berhubungan dengannya. Masyarakat suku Mentawai diminta untuk beralih
kepada agama-agama resmi yang kala itu diakui pemerintah Indonesia, yakni Islam,
Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha. Sabulungan diidentikkan dengan kepercayaan
masyarakat ‘primitif’ dan dengan demikian oleh pemerintah bisa dilenyapkan sehingga
13
budaya modern – masyarakat yang merdeka, diakuinya pemerintahan sentralistik, serta
penghayatan atas agama resmi – bisa diterima (Juniator 2012:73).
Program ‘pendisiplinan’ agama-agama tradisional di Indonesia itu berlangsung
selama periode 1950an – 1967 di masa pemerintahan Soekarno dan berlanjut hingga era
kepemimpinan Soeharto (1967-1998). Tappres No. 1 tahun 1965 yang menjadi landasan
pengaturan agama-agama di Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno bertujuan
mencegah terjadinya konflik dan kekerasan yang diakibatkan oleh pencemaran agama
yang beragam di Indonesia. Dengan begitu banyaknya etnis dan aliran kepercayaan,
pencemaran agama bisa memecah belah bangsa dan mempengaruhi stabilitas nasional.
Di masa Orde Baru, pemerintahan Soeharto menjadikan peraturan tersebut sebagai sarana
politis untuk melawan ideologi komunis dengan memanfaatkan sentimen anti PKI pasca
peristiwa 30 September. Keberadaan orang-orang yang tidak beragama yang diidentikkan
dengan komunisme menjadi ancaman bangsa. Komunisme bukan saja ditolak tetapi juga
dipertentangkan dengan jati diri bangsa dengan menggunakan landasan agama (Ropi,
2017: 132). Di kepulauan Mentawai sendiri proses itu terjadi pula. Pulau-pulau yang
berada di selatan, P. Pagai dan P. Sipora mengalami dampak yang paling kentara.
Sedangkan di P. Siberut sekelompok orang Mentawai memilih menetap di bagian hulu
sungai dan pedalaman untuk menghindari pengaruh pemerintah (Juniator 2012: 73-74;
Hammons 2016: 407). Untuk itulah hingga saat ini jejak-jejak tradisi sabulungan masih
bisa ditemukan di wilayah P. Siberut.
C.S. Hammons menuliskan bahwa pada periode tahun 1980-1990an, banyak
penduduk di desa-desa di Siberut menganut agama Kristen (Protestan atau Katolik).
Namun demikian di desa-desa hulu, yang terletak jauh dari garis pantai, mereka memilih
14
atau Islam sebagai ‘agama’ (religion) (Hammons 2016:407). Inilah yang disebut oleh
Coronesse sebagai sistem ‘bikultural’. Ia berpandangan bahwa tidak mungkin pertemuan
Tiga Agama tahun 1954 dan peristiwa pelarangan atas kepercayaan tradisional itu
sesudahnya bisa serta merta menjadikan masyarakat suku Mentawai beralih kepercayaan.
Sabulungan menurut Coronesse belum terkikis habis di hati orang Mentawai. Ia menulis:
Pada hakikatnya Arat Sabulungan belum terkikis habis di lubuk hati orang Mentawai, yang menjalankan upacara Arat dengan sembunyi-sembunyi. Hal mana dapat dibuktikan dalam laporan yang tercantum:
- Larangan Pemerintah tentang Arat pada lahirnya dipatuhi, namun secara diam-diam, kegiatan Arat Sabulungan dijalankan juga.
- Agama yang baru dipeluk sama sekali belum lagi merasuk ke hati dan tradisi tua yang telah membudaya sangat susah lenyap.
- Kepercayaan terhadap obat sikerei, lebih ampuh dan manjur ketimbang obat-obatan modern dan Puskesmas.
- Payah sekali mencari suatu metoda untuk meyakinkan pengikut-pengikut arat sabulungan. (Surat Keputusan Pimpinan Proyek Penerangan, Bimbingan Dakwah/Khutbah Agama Katolik tentang pengangkatan tenaga-tenaga team operasional penerangan agama Katolik daerah No.056/ Kep.19/1974-75.)
Oleh sebab itu corak keagamaan di Mentawai disebut Bikultural; bersama-sama (dengan) agama resmi, hidup dengan diam-diam agama asli yang digolongkan ke dalam aliran kebatinan (Coronesse, 1986:39).
Konsep mengenai bikulturalisme sendiri memiliki cakupan yang cukup luas.
Secara umum bikulturalisme mengacu pada gagasan mengenai rasa nyaman dan
kemahiran seseorang menghidupi budaya warisannya bersamaan dengan budaya di
negara atau wilayah di mana ia berada (SJ. Schwartz, 2010: 26). Dalam pandangan
tersebut seseorang yang fasih berbicara baik bahasa Jawa dan Batak umpamanya, atau
15
merupakan contoh bikulturalisme. Akan tetapi secara lebih dalam, sebagaimana ditulis
oleh Schwartz, bikulturalisme meliputi juga penyatuan nilai-nilai warisan budaya
tertentu dengan arus budaya lain menjadi sebuah perpaduan yang unik dan bersifat
personal. Dalam pandangan terebut situasi yang dialami orang Mentawai – menghidupi
sabulungan sebagai warisan budaya dan menganut agama Katolik dan Protestan
sebagaimana dituntut pemerintah – merupakan wujud bikulturalisme. Berbeda dengan
sinkretisme – di mana terjadi perbaduan dan perpaduan unsur-unsur agama dan
aliran-aliran kepercayaan sehingga muncul bentuk baru yang abstrak demi mencari keserasian
– dalam bikulturalisme tidak diperoleh bentuk baru budaya yang tunggal. Masing-masing
unsur budaya yang dihidupi secara bersamaan tetap berdiri mandiri. Hammons (2016:
404-405) mencatat pula bahwa saat ini banyak dijumpai masyarakat Suku Mentawai
yang tetap mempraktikkan kepercayaan lokal sabulungan dan juga memeluk salah satu
agama yang ada; Protestan, Katolik atau Islam. Hal itu merupakan sesuatu yang wajar.
Menjadi tidak wajar justru mereka yang tidak menganut agama resmi dan hanya
mempraktikkan agama lokal saja. Karena dalam pandangan mereka, tidak memeluk
agama resmi yang diakui negara berarti anti-negara.
Selain peristiwa pelarangan atas sabulungan di Mentawai, kepercayaan lokal
masyarakat suku Ngaju, Kaharingan, di Kalimantan Tengah juga mengalami hal yang
serupa. Nama Kaharingan berarti: membangkitkan hidup, membuat hidup (Baier 2007:
567, Baier 2014: 172). Kaharingan sendiri sebenarnya merupakan salah satu sistem
kepercayaan lokal yang ada di Kalimantan. Seperti juga Arat Sabulungan, para penganut
16
ataupun roh-roh lain yang berada di sekitar mereka. Mereka juga percaya bahwa segala
benda dan tumbuhan yang ada memiliki jiwa dan mampu merasa seperti halnya manusia.8
Jika sabulungan dilarang keberadaanya oleh pemerintah pada 1954, Kaharingan di
Kalimantan memiliki sejarah yang berbeda. Para penganut Kaharingan berusaha
memperjuangkan sistem kepercayaan mereka untuk bisa diterima sebagai agama resmi.
Sebagai salah satu cara agar Kaharingan sejalan dengan butir pertama Pancasila – di mana
negara menjunjung Ketuhanan Yang Maha Esa – pada tahun 1953 Kaharingan
menyatakan bahwa mereka mengakui pula Tuhan yang Esa yakni apa yang mereka sebut
Ranying Hatalla Langit. Ia adalah Yang Mahakuasa sumber kehidupan dan juga
penghancur. Teologi yang dianut oleh Kaharingan juga menyerupai Trimurti pada agama
Hindu (Baier 2007: 565-566).
Perjuangan para penganut Kaharingan memperoleh pengakuan sebagai pemeluk
agama resmi negara masih harus menempuh proses yang panjang. Di Indonesia sebuah
aliran kepercayaan dianggap sebagai ‘agama’ jika memiliki unusr-unsur mendasar
seperti: 1) mangandung kepercayaan akan Tuhan yang Esa, 2) memiliki kitab suci, 3)
tempat ibadat, serta 4) hari-hari raya keagamaan9. Untuk memenuhi kriteria tersebut
penganut Kaharingan mengadaptasi kembali mitos penciptaan suku Ngaju dan
menjadikannya sebagai kitab suci dengan sebutan ‘Panaturan Tamparan Taluh
Handiai’.10 Setelah masa tahun 1970-an mereka menyebut tempat ibadat agama
Kaharingan dengan istilah Balai Basarah. Dan barulah pada tahun 1980 pemerintah
secara resmi mengakui Kaharingan, bukan sebagai agama resmi yang berdiri otonom,
8Lih. Khalikin, A. 2016. Studi Agama Kaharingan pada Era Reformasi di Kalimantan
Tengah. Harmoni, 10(1), Hlm. 189-206.
9Bdk. Iskandar, N., Suud, A. K., & Si, S. 2017. Penguatan Peran Intelijen Kejaksaan dalam Pengawasan
Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM) demi Ketertiban dan Ketenteraman Umum. Jakarta: Miswar. Hlm. 27.
17
melainkan sebagai bagian dari agama Hindu. Oleh karena itu sistem kepercayaan ini
dikenal dengan sebutan agama Hindu Kaharingan (Baier 2007: 566-568).
Ada begitu banyak contoh kisah para penganut ‘agama lokal’ dan aliran
kepercayaan tradisional yang ada di Indonesia berhadapan dengan kebijakan pemerintah
pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Sebagian dari penganut agama-agama lokal
tersebut harus rela meninggalkan ajaran para leluhur dan beralih memeluk agama resmi
negara. Sebagian yang lain memilih untuk memperjuangkan keyakinan tradisional
mereka sehingga bisa diakui negara atau setidaknya menggabungkan diri pada salah satu
agama resmi negara sebagaimana dilakukan oleh pemeluk Kaharingan di Kalimantan.
Kini keberadaan aliran kepercayaan seperti mendapat angin segar. Pada 7
November 2017, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi atas
Undang-Undang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk). Permohonan uji materi
tersebut dilayangkan oleh beberapa perwakilan kelompok penganut kepercayaan di
Indonesia. Mereka datang dari Komunitas Merapu di P. Sumba, penganut kepercayaan
Parmalim di Sumatera Utara, penganut kepercayaan Ugamo Bangsa Batak di Sumatera
Utara, serta perwakilan dari penganut kepercayaan Sapto Darmo di Jawa. Bagian yang
diuji dalam sidang MK itu adalah pasal 61 ayat (1) dan (2) serta pasal 64 ayat (1) dan (5)
dari UU No.23 tahun 2006 juncto UU No.24 tahun 2013. Hasilnya, ketua MK Arif
Hidayat menyatakan bahwa kata 'agama' dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 bertentangan dengan UUD 1945
18
termasuk aliran kepercayaan.11 Melalui putusan itu kini para penganut agama lokal atau
aliran kepercayaan bisa mencantumkan status kepercayaan mereka pada kolom Kartu
Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal ini merupakan babak baru dalam
sejarah perjuangan pengakuan atas agama dan kepercayaan lokal yang ada di Indonesia.
G. KERANGKA TEORI
Dalam tesis ini penulis mencoba melihat fenomena peminggiran dan perlawanan
yang dialami orang Mentawai di Siberut dalam kehidupan sehari-hari dengan pendekatan
James Scott (1985). Scott memaparkan hasil penelitian lapangannya selama 2 tahun
(1978-1980) terhadap kaum petani di sebuah desa kecil yang dinamainya Sedaka (bukan
nama sebenarnya) di wilayah Kedah, barat laut Malaysia. Fokus perhatiannya tertuju pada
perjuangan ideologis kaum petani yang menghasilkan perlawanan terhadap kelompok
yang mengeksploitasi mereka dengan latar belakang revolusi hijau yang terjadi pada masa
itu. Dari model pendekatan Scott, penulis mencoba mengambil salah satu poin pemikiran
penting untuk menganalisis hasil penelitian dalam tesis ini. Buah pemikiran Scott yang
penulis gunakan adalah konsepnya mengenai ‘perlawanan dalam wujud keseharian’
(everyday forms of resistance).
1. Perlawanan dalam Wujud Keseharian
Scott (1985: xvi) melihat bahwa kemunculan kaum petani sebagai tokoh utama
sejarah tidak begitu dominan. Mereka sering hanya dikenal sebagai kelompok anonim
yang dikaitkan dengan statistik pajak, pergerakan tenaga kerja, kaum pemilik tanah, dan
hal-hal lain yang berhubungan dengan produksi hasil pertanian. Kondisi dan situasi yang
11
19
dialami kaum petani tidak memungkinkan mereka melakukan pemberontakan terhadap
kelompok yang mendulang keuntungan dan mengeksploitasi diri mereka. Konflik yang
muncul di Sedaka antara petani miskin dan para pemilik tanah yang kaya dilatarbelakangi
oleh perubahan hubungan produksi. Revolusi hijau yang terjadi memicu perubahan pola
pertanian. Panen yang dilipatgandakan dalam dua kali musim tanam serta mekanisasi
pertanian yang didukung pemerintah hanya menambah keuntungan di kalangan para
pemilik tanah. Hal ini memicu terjadinya ketidakseimbangan sosial antara para tuan tanah
dan petani.
Kesenjangan yang terjadi tampak dalam perilaku para tuan tanah seperti misalnya:
mengubah kebijakan sewa tanah, penggantian buruh tani manusia dengan mesin, dan
menyewakan tanah garapan yang luas dalam jangka waktu yang panjang. Selain itu di
dalam relasi kehidupan sosial antara tuan tanah dan petani muncul perubahan perilaku
yang merugikan kaum petani miskin. Para tuan tanah mengurangi atau tidak lagi
memberikan pesta panen, memberi zakat dan sedekah sebagaimana dilakukan seturut
tradisi Islam, serta pengakuan-pengakuan sosial yang dulunya mewarnai kehidupan sosial
di wilayah Sedaka (Scott, 1985: 305). Hal ini bagi para petani kecil merupakan hal yang
merugikan. Konsekuensinya para petani miskin berusaha memperjuangkan kepentingan
mereka agar praktik-praktik sosial masa lalu diperoleh kembali. Diskriminasi oleh para
tuan tanah terhadap kelas petani akibat perubahan proses produksi pertanian itu memicu
munculnya perlawanan.
Bagi Scott kaum minoritas seperti para petani di Sedaka tidak dimungkinkan
mengadakan perlawanan frontal, terbuka, dan kolektif karena situasi struktur kelas sosial
yang kompleks dan rumit di antara para pemilik tanah dan petani. Selain itu ketika para
20
maka pilihan lainnya adalah melakukan protes sambil ‘melarikan diri’ atau menghindar
(Scott 1985: 244). Scott dalam pengamatan lapangannya di Malaysia menitikberatkan
perhatiannya pada bentuk perlawanan kelompok petani yang dilakukan secara sederhana
yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini yang oleh Scott disebutnya sebagai
‘perlawanan dalam wujud keseharian’ kaum petani.
Berbeda dengan model perlawanan yang terang-terangan, terorganisir dan
terencana rapi, bentuk perlawanan ini muncul dalam hal-hal yang seolah remeh temeh
belaka. Sikap bermalas-malasan, kepatuhan palsu, gosip, pencurian kecil-kecilan, hingga
melakukan sabotase, merupakan bentuk-bentuk senjata perlawanan kaum petani (Scott
1985: 29). Di permukaan orang akan melihat bagaimana kaum petani seolah ‘tunduk’
pada kebijakan pemerintah dan para pemilik tanah. Namun investigasi Scott
menunjukkan bahwa di bawah permukaan yang tampak itu para petani tetap mengadakan
perlawanan dan mengkritik pihak yang menguasai mereka. Scott mencermati pola-pola
perlawanan yang terjadi di kalangan kaum petani di Sedaka menghasilkan semacam
pembedaan antara dua wujud perlawanan. Di satu sisi adalah ‘perlawanan yang
sesungguhnya’ yang memiliki ciri: (1) Organik, sistematik, dan kooperatif. (2) Memiliki
prinsip tertentu dan tidak mementingkan diri sendiri. (3) Bisa berdampak pada munculnya
gerakan revolusioner. (4) Memiliki ide atau tujuan meniadakan kelas dominan. Di sisi
lain merupakan ‘perlawanan kecil-kecilan’ yang justru berciri hal yang sebaliknya: (1)
Tidak teratur dan tidak sistematis. (2) Oportunis dan mengutamakan kepentingan diri
sendiri. (3) Tidak sampai berujung pada gerakan revolusioner. (4) Sama sekali tidak
tersirat upaya atau gagasan menggulingkan kelas dominan.
Kedua model perlawanan tersebut menurut Scott penting untuk melihat gerakan
21
perlawanan yang tampak kecil-kecilan bisa menjadikan analisis terhadap gerakan
perlawanan kaum petani itu menjadi kurang lengkap. Keputusan Scott untuk menggali
konflik kelas di Sedaka dari sudut pandang kelompok minoritas menjadi penting untuk
menggali apa yang terjadi di bawah permukaan situasi sosial yang terjadi.
Penelitian Scott di Sedaka memberikan sumbangan gagasan mengenai pembedaan
antara public transcript dan hidden transcript. Apa yang tampak di permukaan, seperti
relasi kuasa antara petani dan dominasi para pemilik lahan, dipandang sebagai ‘public
transcripts’. Sementara perlawanan dan protes para petani yang dilakukan di bawah
permukaan itulah yang disebut ‘hidden transcript’. Bentuk resistensi yang dilakukan para
petani bisa muncul dalam kegiatan gosip, pencurian dan sabotase kecil-kecilan, mogok
kerja atau bermalas-malasan. Menurut Scott perlawanan yang sifatnya frontal dan
dilakukan dalam skala besar tidak mungkin terjadi dan hanya akan berakhir sia-sia
melawan kaum pemilik tanah yang kaya dan didukung oleh pemerintah. Kelas petani
menurut Scott seringkali berada dalam posisi yang ironis dalam konflik antar kelas.
Segala bentuk revolusi dan perlawanan terbuka akan dengan mudah ditindak dengan
tegas oleh pemerintah dan kelas yang mendominasi. Bahkan ketika para petani memberi
dukungan mereka kepada salah satu kelompok partai, tidak memberikan jaminan
kepastian bahwa nasib mereka kelak akan diperjuangkan. Bayang-bayang akan
pembunuhan massal, penindasan, serta kehancuran moral yang disebabkan oleh
pemberontakan menjadikan kaum petani cenderung menghindari konfrontasi secara
terbuka (Scott, 1985:29-30).
2. Resistensi Orang Siberut dalam Praktik Sabulungan
Ada beberapa pokok pemikiran Scott dalam penelitiannya yang penulis gunakan
22
pemikiran tersebut adalah: hegemoni dalam konflik ideologi, model perlawanan simbolik
dan gagasan mengenai narasi terselubung (hidden transcript).
a. Hegemoni dalam Konflik Ideologi
Jika dalam penelitian James Scott kaum petani berhadapan dengan dominasi para
pemilik tanah dengan latar belakang revolusi hijau, orang Mentawai di Siberut dalam
penelitian ini berada di posisi serupa berhadapan dengan dominasi negara dan para
pewarta agama pasca kemerdekaan Indonesia. Barker (2014:119) secara singkat
menjelaskan hegemoni sebagai upaya memproduksi seperangkat makna, gagasan,
ide-ide, dan juga ideologi, oleh golongan yang berkuasa dan kemudian secara otoriter
golongan tersebut berupaya menjaga dan mempertahankannya. Menurut Gramsci,
ideologi sendiri bisa dipandang sebagai ide-ide, gugus makna, dan praktik yang fungsinya
mendukung kekuasaan kelas sosial tertentu (Barker, 2014:138). Dalam konteks konflik
di Sedaka, wujud hegemoni tersebut tampak dalam pertarungan ideologi yang terjadi
antara tuan tanah dan kaum petani. Para pemilik tanah yang kaya – karena kedudukan
sosialnya – dan diperkuat oleh dukungan pemerintah memiliki kuasa untuk memaksakan
gagasan dan ide-ide mereka tentang bagaimana sebaiknya perilaku para petani. Namun
tidak demikian dengan kelas petani. Mereka selalu berada di posisi subordinat yang tidak
menguntungkan untuk memaksakan ide-ide mereka terhadap orang kaya (Scott, 1985:
315).
Situasi yang serupa terjadi di Siberut pasca kemerdekaan Republik Indonesia.
Negara muncul sebagai pihak yang mendominasi gagasan dan ide-ide mengenai warga
negara modern. Dominasi ideologi tersebut muncul dalam kebijakan pemerintah di P.
23
diwacanakan secara dangkal melalui penghayatan atas ‘agama resmi’12 – di mana
tampak bahwa kepercayaa-kepercayaan tradisional seperti sabulungan tidak termasuk
dalam kategori tersebut – hidup dalam desa-desa yang dibentuk pemerintah, dan
mengenyam pendidikan. Dan sebagaimana para petani kecil di Sedaka, penghayat
sabulungan di Siberut berada dalam posisi yang tidak memungkinkan memaksakan
gagasan mereka sendiri terhadap negara sebagai kelas yang berkuasa. Konflik ideologi
yang terjadi di Siberut inilah yang kemudian menyebabkan diskriminasi kelompok
tertentu sehingga memicu munculnya perlawanan. Dalam hal ini perlawanan dipahami
bukan semata-mata sebagai perilaku ofensif yang berusaha membalikkan tatanan kelas
sosial melainkan juga sebagai upaya protes serta negosiasi yang terjadi di dalam relasi
kekuasaan itu sendiri. Resistensi orang Mentawai di Siberut bukan terwujud dalam
perilaku menentang program pemerintah dan menolak segala bentuk peraturan yang
diberikan, tetapi justru terjadi melalui negosiasi dengan segala perubahan tersebut.
b. Model Perlawanan Simbolik.
Suatu tindakan atau aksi seseorang atau sekelompok orang lahir dari kehendak yang
dipengaruhi oleh kesadaran mereka. Scott berpendapat bahwa aksi perlawanan dan
pemikiran (mengenai) perlawanan selalu berhubungan secara dialogis. Kesadaran untuk
melakukan aksi tersebut tidak selalu muncul dalam bentuk yang sama. Ada kalanya garis
aksi yang muncul bisa berupa hal yang mustahil dan unik (Scott, 1985: 38). Menganalisis
kesadaran intensional yang ada di balik tindakan resistensi suatu kelompok menjadi
penting untuk memahami bentuk protes dalam wujud keseharian.
24
Bentuk perlawanan simbolik kelas tertentu tidak bisa dilepaskan dari gagasan
mengenai ‘mistifikasi’ atau ‘kesadaran palsu’ yang muncul dari hegemoni simbolis pula.
Dalam hal ini Scott mengutip pemikiran Gramsci mengenai tindakan kelompok dominan
yang berkuasa mengendalikan sektor-sektor idiologis dari masyarakat seperti agama,
pendidikan, dan media massa. Mereka dengan demikian berusaha membangun
gagasan-gagasan yang indah, ideal, dan tampak asli. Apa yang dilakukan negara di daerah-daerah
seperti di Siberut merupakan wujud hegemoni simbolis tersebut. Gagasan yang dibangun
adalah bahwa warga negara yang baik adalah mereka yang menerima sila Ketuhanan
Yang Maha Esa dan hal itu dinyatakan dengan dianutnya agama tertentu. Gagasan lain
yang dibangun adalah bahwa masyarakat yang merdeka dan modern meninggalkan segala
bentuk tradisi animisme. Gagasan mengenai cara hidup bermasyarakat yang berpusat
pada wilayah administratif sebagaimana diakui pemerintah juga merupakan
konsep-konsep yang diwacanakan oleh pemerintah. Bagi Gramsci, sebagaimana ditulis Scott,
mereka yang merupakan kelas yang didominasi lebih diperbudak dalam tataran pemikiran
daripada dalam tataran praktik dan perilaku (Scott, 1985: 39).
Hegemoni simbolik negara di atas dengan demikian berhadapan dengan ideologi
orang Mentawai di mana relasi keduanya tidak pernah sejajar. Bentuk-bentuk ritual,
tradisi, simbol-simbol budaya, serta norma-norma tradisional yang telah dihidupi orang
Mentawai sekian lama telah membentuk semacam ideologi yang tidak bisa begitu saja
dihilangkan. Bahwa kemudian orang-orang Mentawai di Siberut berduyun-duyun
menganut agama sebagaimana diharapkan pemerintah dengan demikian tidak
semata-mata memperlihatkan tidak adanya perlawanan. Ritual-ritual sabulungan yang masih
dihidupi sekelompok orang Mentawai di Siberut bisa jadi merupakan wujud
25
kelompok yang dikuasai begitu saja oleh tatanan sosial yang diupayakan oleh para
penguasa.
c. Narasi Terselubung
Konflik yang terjadi di antara kelas tuan tanah dan petani miskin di Sedaka
berlangsung seperti di atas ‘pentas’. Relasi antara para petani dan tuan-tuan tanah yang
kaya tampak berjalan normal. Para petani menghormati kedudukan para pemilik lahan
dan mengiyakan apa yang mereka harapkan dari kaum mereka. Demikian pula para
pemilik lahan juga menjalankan peran sosial mereka dengan memberikan zakat dan
sumbangan kepara orang-orang miskin pada hari-hari besar keagamaan. Namun situasi di
bawah pentas justru berbeda. Perlawanan yang berlangsung justru terjadi ‘di bawah
permukaan’. Sifat bermalas-malasan, kepatuhan palsu, gosip di kedai-kedai kopi, dan
sabotase peralatan produksi pertanian, terus berlangsung. Gerakan di bawah pentas ini
merupakan bentuk narasi yang terselubung (hidden transcript) yang oleh Scott dibedakan
dengan situasi kehidupan umum yang tampak di permukaan (public transcript) (Scott,
1990:4).
Pemikiran Scott mengenai hidden transcript yang diterapkannya dalam penelitian
terhadap petani di Sedaka diuraikan secara detail dalam bukunya Hidden Transcripts:
Domination and And The Arts of Resistance (1990). Segala bentuk tingkah laku,
perbincangan, praktik-praktik yang dilakukan kelompok subordinat di ‘luar pentas’
tersebut sama sekali bertentangan dan mampu mengubah apa yang tampak di ‘atas
pentas’. Istilah hidden transcript ini digunakan Scott untuk memperlihatkan bahwa apa
yang terjadi di ‘luar pentas’ benar-benar berada di luar pengamatan para pemegang
kekuasaan atau kelas yang mendominasi (Scott, 1990:4). Maka untuk melihat bagaimana
26
antara hidden transcript dan public transcript (Scott, 1990: 5). Ada 3 karakteristik hidden
transcript menurut Scott (1990: 14) yang penting untuk diperhatikan. Pertama, narasi
terselubung (hidden transcript) secara khusus diperuntukkan bagi kelas sosial tertentu
dan terhadap seperangkat tindakan tertentu. Dengan demikian narasi kelas sosial tersebut
diuraikan dalam ‘publik terbatas’ dan oleh karena itu ‘tersembunyi’ bagi golongan kelas
tertentu. Dalam kisah petani di Sedaka, apa yang dilakukan para petani tersembunyi bagi
kelompok tuan tanah dan pemerintah. Sedangkan dalam kasus di Siberut, praktik
sabulungan tersembunyi bagi pemerintah dan para pewarta agama. Kedua, narasi
terselubung tidak hanya berwujud wacana, cerita-cerita, tetapi juga mencakup
serangkaian praktik dan tindakan. Tindakan para petani di Sedaka bekerja sambil
bermalas-malasan, pencurian, menghindari pajak, merupakan hal yang tak terlepas dari
konsep narasi terselubung. Hal yang mirip terjadi pula dikalangan orang Mentawai di
Siberut, yang menghindari istilah sabulungan dan lebih memilih menggunakan kata
‘budaya’ serta menjalankan pula kewajiban hidup beragama sebagaimana dianjurkan
agama masing-masing. Karakteristik ketiga dari narasi terselubung adalah situasi yang
memperlihatkan bahwa perbatasan antara public transcript dan hidden transcript tidak
selalu jelas. Perbatasan tersebut selalu menjadi bagian dari wilayah perjuangan
terus-menerus antara kelompok yang mendominasid an kelompok subordinat.
Pemikiran Scott ini juga yang akan digunakan untuk melihat fenomena yang terjadi
di Siberut. Bagaimana orang Mentawai dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat
umum mengikuti arahan pemerintah untuk menganut agama resmi dan meninggalkan
tradisi sabulungan? Namun situasi yang terjadi di bawah pentas memperlihatkan hal yang
27
untuk melihat fenomena yang terjadi di kalangan orang Mentawai di Siberut yang masih
menjaga tradisi sabulungan dalam kehidupan mereka saat ini.
H. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam (in-depth interview) dan
studi pustaka untuk mengumpulkan data. Pemilihan informan dilakukan dengan metode
purposive sampling. Wawancara dilakukan kepada sejumlah tokoh masyarakat dan tetua
adat yang ada di wilayah Kecamatan Siberut Selatan. Lokasi ini dipilih karena di sana
masih bisa dijumpai masyarakat tradisional Mentawai. Wilayah tersebut juga sering
menjadi tujuan kunjungan wisatawan mancanegara ataupun domestik yang ingin
mengenal dan melihat dari dekat kehidupan tradisional suku Mentawai.
Penelitiaan lapangan dilakukan secara khusus oleh penulis dalam 2 periode. Yang
pertama pada bulan Januari 2017 selama 2 minggu dan yang kedua dilaksanakan pada
bulan Desember 2017 sampai awal Januari 2018 selama 4 minggu. Pada kunjungan
pertama, penulis mengadakan perbincangan dengan beberapa kenalan di Siberut
mengenai tema tesis ini. Dari pertukaran pikiran tersebut, penulis dibantu beberapa
kenalan mencoba mencari tokoh-tokoh masyarakat yang dipandang memiliki pemahaman
atas tema yang akan penulis angkat dalam tulisan ini. Waktu kunjungan yang cukup
singkat, dan kesulitan menjumpai para informan di kediaman mereka mejadi salah satu
kendala yang penulis hadapi di lapangan. Kebanyakan dari mereka sedang tidak berada
di rumah kediamannya ketika penulis mengunjungi mereka. Sebagian sedang berada di
ladang atau sedang pergi ke tempat lain. Terbatasnya waktu dan kesulitan untuk membuat
janji bertemu dengan tokoh yang bersangkutan menjadikan penulis tidak banyak
28
Pada kunjungan yang kedua, dari pertengahan bulan Desember 2017 hingga awal
Januari 2018, penulis lebih banyak mengadakan wawancara dengan beberapa informan
yang telah ditentukan. Penulis banyak dibantu oleh seorang guru setempat, Marinus
Satoleuru, yang ayahnya juga seorang sikerei. Selain itu penulis juga dibantu oleh
sekretaris paroki gereja setempat, Bapak Petrus Marjuni, orang Jawa yang sejak masa
mudanya mengabdi di Siberut. Bersama Marinus dan Bapak Petrus Marjuni, penulis
mengunjungi sejumlah tokoh, mulai dari orang yang dituakan dalam suku, pejabat
pemerintahan, dan orang-orang yang bergerak di bidang pendidikan dan pariwisata.
Semua informan adalah orang Mentawai. Bersama Marinus dan Bapak Marjuni juga
penulis banyak bertukar pikiran mengenai tema tesis ini dan menentukan siapa-siapa yang
sekiranya cukup memahami situasi budaya setempat dan sejarahnya di masa lalu. Marinus
juga banyak membantu penulis dalam berkomunikasi dengan penduduk setempat dengan
bahasa Mentawai. Para narasumber yang dipilih merupakan tetua dalam sebuah suku
yang mengalami sendiri peristiwa tahun 1954, para katekis atau guru agama Katolik orang
Mentawai yang memahami juga budaya setempat, serta tokoh-tokoh yang sempat
menjabat sebagai kepala dusun atau desa.
Kesulitan menjumpai para informan di waktu yang ditentukan masih menjadi
kendala. Sebagian besar wawancara dilakukan pada sore hingga malam hari. Saat itu para
informan sudah berada di rumah setelah seharian bekerja. Penulis juga berkesempatan
mewawancarai Bupati Kep. Mentawai, Bapak Yudas Sabaggalet yang kebetulan pada
saat itu datang untuk merayakan Natal di Muara Siberut. Kesempatan ini tidak
dijadwalkan sebelumnya oleh penulis. Data dari wawancara dan pembacaan sejumlah
29
menggunakan bahan-bahan sekunder dari literatur dan arsip untuk memperkaya analisa
tesis ini.
I. SISTEMATIKA PENULISAN
Tesis ini dibagi menjadi lima bagian. Bagian pertama berisi latar belakang dan
tujuan penulisan, pertanyaan penelitian, kajian pustaka, landasan teoritis, dan metode
penelitian. Pada bagian kedua akan diulas mengenai gambaran umum kepulauan
Mentawai saat ini, gagasan mengenai orang Mentawai dalam mitos tradisonal dan dari
sejumlah penelitian. Bagaimana perjumpaan orang Mentawai dengan budaya dari luar,
sistem kepercayaan mereka dan relasinya dengan negara juga merupakan poin-poin yang
akan disajikan dalam bab yang kedua. Bab yang ketiga akan berisikan pembahasan
mengenai sabulungan di mata mereka yang dituakan dalam suku dan masyarakat
(sikebukat) serta bagaimana ritual sabulungan masih menjadi bagian dari kehidupan
sehari-hari orang Mentawai di Siberut. Pada bab yang keempat penulis mencoba
menyajikan persoalan dominasi negara terhadap sabulungan serta bagaimana siasat
perlawanan orang Mentawai. Akhirnya pada bagian yang terakhir penulis akan
30 BAB II
KEPULAUAN MENTAWAI, ORANG SIBERUT DAN SABULUNGAN
Bab kedua ini akan menjelaskan tiga pokok bahasan. Bagian pertama akan berisi
gambaran umum situasi Kepulauan Mentawai. Hal itu meliputi keadaan geografis, situasi
penduduk, hingga perkembangan apa saja yang sedang terjadi di wilayah tersebut hingga
saat ini. Pokok bahasan kedua memuat uraian mengenai gagasan komunitas orang
Mentawai. Bagian ini akan berisi beberapa tulisan yang disusun oleh para peneliti
Mentawai. Pembahasan mengenai bagaimana asal-usul orang Mentawai – sebagaimana
termuat dalam hasil penelitian terdahulu dan mitos tradisional mereka – secara singkat
juga akan dimuat pada bagian kedua ini. Penjelasan mengenai kepercayaan tradisional
orang Mentawai dan bagaimana negara melalui aparatusnya berusaha menghapuskannya
akan menjadi poin pembahasan bagian yang ketiga. Pada bagian terakhir itu pula penulis
akan memberikan gambaran mengenai situasi memudarnya sabulungan dalam kehidupan
31 A. Gambaran Umum Kepulauan Mentawai
1. Lokasi Geografis
Secara geografis kepulauan Mentawai terletak di sebelah barat Pulau Sumatera –
dipisahkan oleh Selat Mentawai – dan merupakan 1 dari 12 kabupaten di Provinsi
Sumatera Barat. Wilayah kepulauan dengan luas 6.011,35 km2 dan garis pantai sepanjang
1.402,66 km13 ini terdiri empat pulau utama, yakni P. Siberut, P. Sipora, P. Pagai Utara
dan P. Pagai Selatan. Selain keempat pulau utama tersebut terdapat ratusan pulau-pulau
kecil yang tersebar di wilayah Mentawai. Namun data BPS tahun 2017 baru mencatat 99