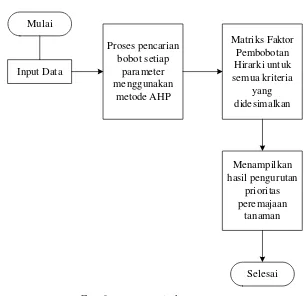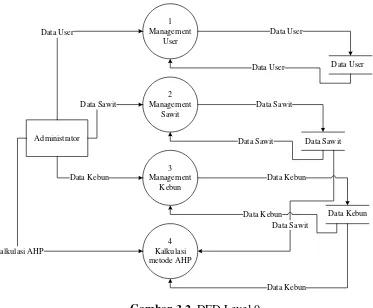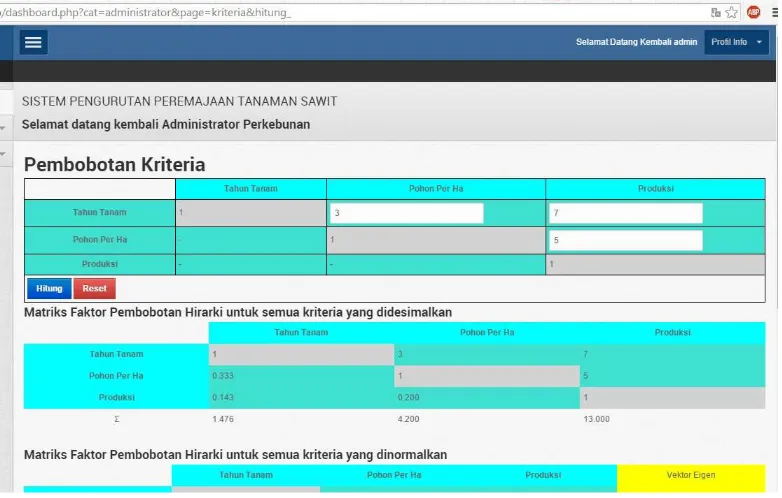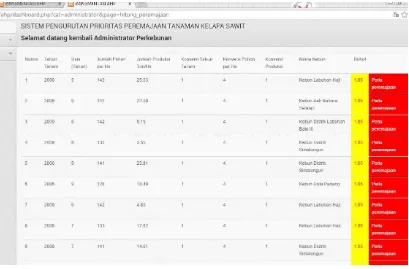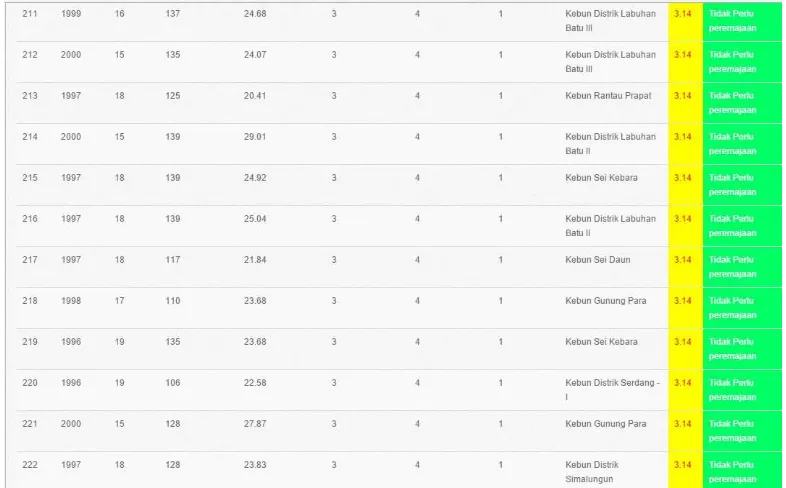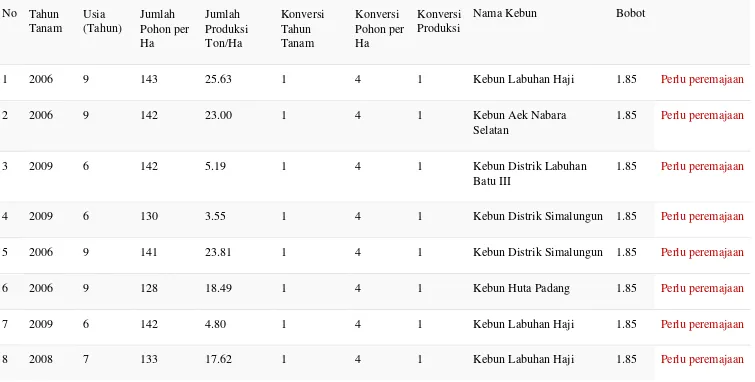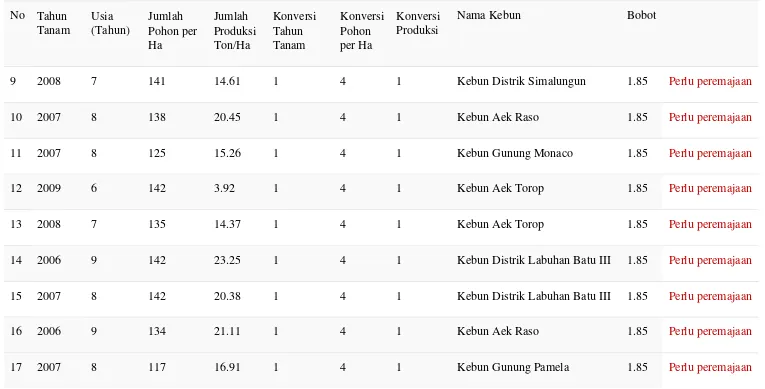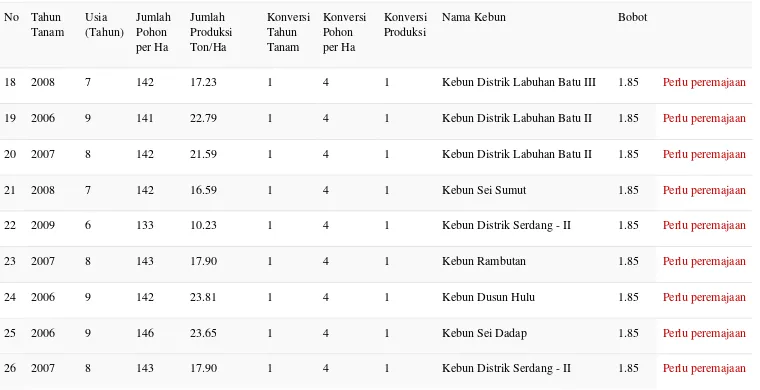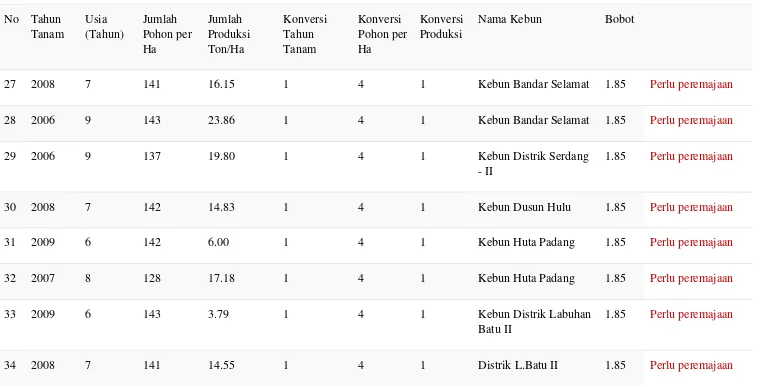PENGURUTAN PRIORITAS PEREMAJAAN TANAMAN
DENGAN MENGGUNAKAN METODE ANALYTICAL
HIERARKHI PROCESS
SKRIPSI
TRI SETIAWAN
091402095
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
SKRIPSI
Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat memperoleh ijazah Sarjana Teknologi Informasi
TRI SETIAWAN 091402095
PROGRAM STUDI S1 TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
PERSETUJUAN
Judul : PENGURUTAN PRIORITAS PEREMAJAAN
TANAMAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE ANALYTICAL HIERARKHI PROCESS
Kategori : SKRIPSI
Nama : TRI SETIAWAN
Nomor Induk Mahasiswa : 091402095
Program Studi : SARJANA (S1) TEKNOLOGI INFORMASI
Departemen : TEKNOLOGI INFORMASI
Fakultas : ILMU KOMPUTER DAN TEKNOLOGI
INFORMASI (FASILKOM-TI) UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Diluluskan di
Medan, 22 Januari 2015
Komisi Pembimbing:
Pembimbing 2 Pembimbing 1
Sarah Purnamawati,ST.,M.Sc Dr. Syahril Efendi, S.Si.,M.IT NIP 19830226 201012 2 003 NIP 19671110 199602 1 001
Diketahui/Disetujui oleh
Program Studi S1 Teknologi Informasi Ketua,
PENGURUTAN PRIORITAS PEREMAJAAN TANAMAN DENGAN
MENGGUNAKAN METODE ANALYTICAL HIERARKHI PROCESS
SKRIPSI
Saya mengakui bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, kecuali beberapa
kutipan dan ringkasan yang masing-masing telah disebutkan sumbernya.
Medan, 22 Januari 2015
UCAPAN TERIMA KASIH
Alhamdulillah segala puji dan syukur saya sampaikan kehadirat Allah SWT beserta Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memberikan rahmat, hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memperoleh gelar Sarjana Program Studi S-1 Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara.
Dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada:
1. Ayah penulis, Ir. H Sundiandi M.Sc., ibu penulis, Dra. Hj Erlina Zarniaty, kakak penulis Dr. Dian Prastuty dan Dr. Ade Andriani yang telah memberikan doa dan dukungan moral kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini beserta keluarga besar yang telah turut mendoakan penulis.
2. Bapak Dr. Syahril Efendi, S.Si.,M.IT., M.Kom dan Ibu Sarah Purnamawati,ST.,M.Sc selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu, pikiran, saran, dan kritiknya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dedy Arisandi, ST.,M.Kom dan Ibu Erna Budhiarti Nababan, M.IT yang telah bersedia menjadi dosen penguji dan memberikan saran dan kritik yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ketua dan Sekretaris Program Studi S1 Teknologi Informasi, Bapak M. Anggia Muchtar, S.T., MM.IT. dan Bapak Mohammad Fadly Syahputra, B.Sc., M.Sc.IT.
5. Seluruh dosen yang mengajar serta Ibu Delima dan Bang Faisal, sebagai staf Tata Usaha Program Studi Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara. 6. Sahabat-sahabat yang selalu mendukung dan memberi semangat kepada
penulis, Bryan Wahyudi, Muhammad Santana, Dhimas Eko Prasetyo, Akhmad Sofyan Dalimunthe, Ahmad Yazid, Boho Surianto Naibaho S.TI dan semua teman angkatan 2009.
7. Seluruh rekan kuliah sejawat yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
ABSTRAK
Proses pendukung keputusan pada dasarnya adalah memilih suatu alternatif untuk
menyelesaikan suatu permasalahan. Beberapa permasalahan yang sering muncul
bersifat kompleks dengan aspek atau kriteria yang diambil cukup banyak. Pada
dasarnya, setiap persoalan dapat diselesaikan dengan melihat persoalan tersebut
selayaknya suatu kerangka yang terorganisir, yang memungkinkan adanya
ketergantungan antar komponen dan ketergantungan antar elemen dalam suatu
komponen. Kerangka pemikiran tersebut memungkinkan pengambil keputusan untuk
mengambil keputusan yang efektif atas persoalan tersebut dengan jalan
menyederhanakan, sehingga mempercepat proses pengambilan keputusan yang
dilakukan. Adapun salah satu contoh pengambilan keputusan yaitu pengurutan
prioritas peremajaan tanaman. Faktor – faktor yang menjadi acuan penting yaitu :
Jumlah produksi, umur tanaman, dan jumlah pohon per hektar. Salah satu metode
yang cocok untuk menyelesaikannya ialah dengan Analytical Hierarkhi Process
(AHP). karena metode ini salah satu metode yang dapat melakukan penilaian kriteria
yang detail dengan suatu kerangka berfikir yang komprehensif pertimbangan proses
hirarki yang kemudian dilakukan penghitungan bobot untuk masing-masing kriteria
dalam menentukan proiritas peremajaan tanaman. Hasil pengurutan peremajaan
tanaman di dapat dari penjumlahan dari hasil perkalian tiap – tiap hasil perkalian
matriks dengan ketiga kriteria. Kriteria yang digunakan disini adalah nilai rata – rata
tiap – tiap kriteria dari data sawit tiga tahun terakhir. Output yang ditampilkan tersebut
berupa tabel ranking yang berisikan tahun tanam, usia pada tahun 2014, Jumlah pohon
per Ha, Jumlah produksi Ton per Ha, kemudian data konversi kriteria – kriteria
tersebut, letak kebun areal tanamannya dan hasil akhir bobot.
THE PRIORITY SORTING OF REPLANTING USING ANALYTICAL HIERARKHI PROCESS METHODS
ABSTRACT
The process of supporting decision is basically choosing an alternative for solving a
problem. Some problems that often appeared are complex with the most taken aspect
or criteria. Basically, each of problems can be solved by viewing that problems as an
organized-framework, possibly any dependence among the elements of component.
The framework is dedicated to take the decision simply, in order to fasten the process
of taking the decision that has been done. One of the sampels in taking the decision is
the priority sorting of replanting. The factors that have been important indicator are
the quantity of production, the age of the plant, and the amount of the trees per
hectare. One of the appropriate methods is Analytical Hierarkhi Process (AHP). This
method can perform the rating of criteria detailly with comprehensive framework. The
consideration of hierarchy process is done by counting the quality of each criteria in
deciding the priority of replanting. Results sorting plant rejuvenation obtained from
the sum of the results of multiplying each - each matrix multiplication results with all
three criteria. The criteria used here is value - average each - each criterion of oil three
years of data. The output is displayed in the form of a table containing the planting
rank, age in 2014, the number of trees per ha, Total production Tons per Ha, then the
data conversion criteria - these criteria, the location of the garden area and the final
weight of the plants.
Halaman
ABSTRAK iv
ABSTRACT v
DAFTAR ISI vi
DAFTAR TABEL ix
DAFTAR GAMBAR xi
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 2
1.3. Tujuan Penelitian 2
1.4. Batasan Masalah 3
1.5. Manfaat Penelitian 3
1.6. Sistematika Penulisan 3
BAB 2 LANDASAN TEORI 5
2.1. Peremajaan Kelapa Sawit 5
2.2. PT Perkebunan Nusantara III 5
2.3. Sistem Pendukung Keputusan 6
2.4. Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) 6
2.4.1. Komparasi Berpasang 7
2.4.2. Prosedur AHP 8
vii
2.5. Penelitian Terdahulu 12
BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 13
3.1. Data yang Digunakan 13
3.2. Arsitektur Umum 15
3.3. Diagram Aliran Data 15
3.3.1. DFD Level 0 15
3.3.2. DFD Level 1 16
3.4. Analisis Sistem 18
3.5. Perancangan Tampilan Antarmuka 26
3.5.1. Rancangan tampilan halaman log in 26
3.5.2. Rancangan tampilan halaman menu sistem 26
BAB 4 IMPLIMENTASI DAN PENGUJIAN 28
4.1. Implementasi Sistem 28
4.1.1. Spesifikasi hardware dan software yang digunakan 28
4.2. Implementasi perancangan antarmuka 29
4.2.1. Tampilan Awal 29
4.2.2. Tampilan Halaman Utama 30
4.2.3. Tampilan Menu Sistem dengan Pilihan User Management 30
4.2.4. Halaman Data Kebun 31
4.2.5. Halaman Data Sawit 31
4.2.6. Halaman Penghitungan 32
4.2.7. Halaman Output 34
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 81
5.1. Kesimpulan 81
5.2. Saran 81
ix
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1 Nilai Skala Komparasi Berpasangan 8
Tabel 2.2 Nilai RI 9
Tabel 2.3 Skala Penilaian Berpasangan 9
Tabel 2.4 Penilaian Berpasangan Lengkap 9
Tabel 2.5 Jumlah Kolom 10
Tabel 2.6 Normalisasi 10
Tabel 2.7 Tabel Rata - Rata 10
Tabel 2.8 Penelitian Terdahulu 12
Tabel 3.1 Tabel Kebun Sei Meranti 13
Tabel 3.2 Tabel Kebun Sei Daun 14
Tabel 3.3 Tabel Kebun Tor Gamba 14
Tabel 3.4 Tabel Kebun Rambutan 14
Tabel 3.5 Skala Penilaian Berpasangan 19
Tabel 3.6 Penilaian Berpasangan Lengkap 19
Tabel 3.7 Jumlah Kolom 20
Tabel 3.8 Normalisasi 20
Tabel 3.9 Rata - Rata 22
Tabel 3.10 Nilai RI 24
Tabel 3.11 Data Konversi Kriteria 25
Tabel 4.2 Output Pengurutan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit 36
xi
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 3.1 Arsitektur Umum 15
Gambar 3.2 DFD Level 0 16
Gambar 3.3 DFD Level 1 (Management User) 16
Gambar 3.4 DFD Level 1 (Management Sawit) 17
Gambar 3.5 DFD Level 1 (Management Kebun) 17
Gambar 3.6 DFD Level 1 (Kalkulasi AHP) 18
Gambar 3.7 Pohon Hierarki 18
Gambar 3.8 Flowchart Tahap Normalisasi 21
Gambar 3.9 Flowchart Vektor Bobot 23
Gambar 3.10 Flowchart Pengujian 24
Gambar 3.11 Flowchart Hasil Pengujian 25
Gambar 3.12 Halaman Login 26
Gambar 3.13 Halaman Menu Sistem Peremajaan Tanaman 27
Gambar 4.1 Tampilan Awal 29
Gambar 4.2 Halaman Utama 30
Gambar 4.3 Halaman User Management 30
Gambar 4.4 Halaman Data Kebun 31
Gambar 4.5 Halaman Data Sawit 31
Gambar 4.6 Pembobotan Kriteria 32
Gambar 4.7 Hasil Tidak Konsisten 32
Gambar 4.9 Hasil Konsisten 33
Gambar 4.10 Halaman Output yang perlu diremajakan 34
ABSTRAK
Proses pendukung keputusan pada dasarnya adalah memilih suatu alternatif untuk
menyelesaikan suatu permasalahan. Beberapa permasalahan yang sering muncul
bersifat kompleks dengan aspek atau kriteria yang diambil cukup banyak. Pada
dasarnya, setiap persoalan dapat diselesaikan dengan melihat persoalan tersebut
selayaknya suatu kerangka yang terorganisir, yang memungkinkan adanya
ketergantungan antar komponen dan ketergantungan antar elemen dalam suatu
komponen. Kerangka pemikiran tersebut memungkinkan pengambil keputusan untuk
mengambil keputusan yang efektif atas persoalan tersebut dengan jalan
menyederhanakan, sehingga mempercepat proses pengambilan keputusan yang
dilakukan. Adapun salah satu contoh pengambilan keputusan yaitu pengurutan
prioritas peremajaan tanaman. Faktor – faktor yang menjadi acuan penting yaitu :
Jumlah produksi, umur tanaman, dan jumlah pohon per hektar. Salah satu metode
yang cocok untuk menyelesaikannya ialah dengan Analytical Hierarkhi Process
(AHP). karena metode ini salah satu metode yang dapat melakukan penilaian kriteria
yang detail dengan suatu kerangka berfikir yang komprehensif pertimbangan proses
hirarki yang kemudian dilakukan penghitungan bobot untuk masing-masing kriteria
dalam menentukan proiritas peremajaan tanaman. Hasil pengurutan peremajaan
tanaman di dapat dari penjumlahan dari hasil perkalian tiap – tiap hasil perkalian
matriks dengan ketiga kriteria. Kriteria yang digunakan disini adalah nilai rata – rata
tiap – tiap kriteria dari data sawit tiga tahun terakhir. Output yang ditampilkan tersebut
berupa tabel ranking yang berisikan tahun tanam, usia pada tahun 2014, Jumlah pohon
per Ha, Jumlah produksi Ton per Ha, kemudian data konversi kriteria – kriteria
tersebut, letak kebun areal tanamannya dan hasil akhir bobot.
THE PRIORITY SORTING OF REPLANTING USING ANALYTICAL HIERARKHI PROCESS METHODS
ABSTRACT
The process of supporting decision is basically choosing an alternative for solving a
problem. Some problems that often appeared are complex with the most taken aspect
or criteria. Basically, each of problems can be solved by viewing that problems as an
organized-framework, possibly any dependence among the elements of component.
The framework is dedicated to take the decision simply, in order to fasten the process
of taking the decision that has been done. One of the sampels in taking the decision is
the priority sorting of replanting. The factors that have been important indicator are
the quantity of production, the age of the plant, and the amount of the trees per
hectare. One of the appropriate methods is Analytical Hierarkhi Process (AHP). This
method can perform the rating of criteria detailly with comprehensive framework. The
consideration of hierarchy process is done by counting the quality of each criteria in
deciding the priority of replanting. Results sorting plant rejuvenation obtained from
the sum of the results of multiplying each - each matrix multiplication results with all
three criteria. The criteria used here is value - average each - each criterion of oil three
years of data. The output is displayed in the form of a table containing the planting
rank, age in 2014, the number of trees per ha, Total production Tons per Ha, then the
data conversion criteria - these criteria, the location of the garden area and the final
weight of the plants.
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang
Peremajaan Tanaman adalah penggantian tanaman perkebunan, karena sudah rusak /
tidak menghasilkan dengan tanaman perkebunan yang sama dan dapat dilakukan
secara selektif maupun menyeluruh. Tanaman Rusak (TR) / Tanaman Tidak
Menghasilkan (TTM) adalah tanaman yang sudah tua, rusak dan tidak memberikan
hasil yang memadai lagi, walaupun ada hasilnya tetapi secara ekonomi sudah tidak
produktif lagi (produksi kurang dari 15% dari produksi normal).
Sampai saat ini beberapa perusahaan perkebunan di Indonesia melakukan
peremajaan perkebunan dengan melakukan penyeleksian data – data setiap kebun. Di
PTPN 3, ada beberapa faktor yang menentukan bahwa tanaman tersebut harus
diremajakan. Faktor – faktor yang menjadi acuan penting yaitu : Tren produksi 3
tahun terakhir, umur tanaman, dan jumlah pohon per hektar. Pengelompokan tanaman
dibagi berdasarkan tahun tanam suatu kebun. Maka setiap kebun berbeda arealnya
walau di tanam dengan tahun yang sama. Ini akan memudahkan perbandingan jika
penurunan produksi tanaman disuatu kebun berbeda jauh dengan produksi tanaman
dikebun lainnya (dengan catatan tahun tanam sama), maka produksi yang menurun
drastis tersebut akan dilakukan peremajaan tanaman.
Setiap areal tanaman cepat atau lambat akan melakukan proses peremajaan.
Untuk itu perusahaan setiap tahunnya mendata dan menghitung jumlah produksi
tanaman dan memprediksi daerah mana saja yang akan diremajakan. Agar
tanaman, diperlukan pengurutan tingkat prioritas kelompok tanaman yang akan
diremajakan. Jika mengetahui urutan kelompok tanaman mana yang akan
diprioritaskan dengan waktu secepat mungkin, maka lebih mudah suatu perusahaan
melakukan persiapan anggaran dana untuk mewujudkan peremajaan kelompok –
kelompok tanaman tersebut.
Dalam konteks perkebunan komersial, yang menjadi tujuan perusahaan yaitu
keuntungan yang optimal. Keuntungan optimal perusahaan perkebunan sangat
ditentukan oleh sumber pendapatan perusahaan. Secara pasti, hal itu merupakan fungsi
produksi dari tanaman yang ditanam dikebun. Atas pertimbangan hal tersebut, salah
satu tindakan manajemen yang perlu dilakukan ialah peremajaan tanaman. Salah satu
alasan tidak mampu melakukan peremajaan dikarenakan kurang tepat dalam
memprediksi anggaran dana. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem yang lebih cepat
dan tepat memprediksi areal mana saja yang didahulukan untuk diremajakan.
Salah satu metode yang tepat adalah Analytical Hierarkhi Process (AHP)
karena metode ini salah satu metode yang dapat melakukan penilaian criteria
majemuk dan detail dengan suatu kerangka berfikir yang komprehensif pertimbangan
proses hirarki yang kemudian dilakukan perhitungan bobot untuk masing-masing
criteria dalam menentukan proiritas pengajuan sertifikasi sesuai dengan kuota.
1.2. Rumusan Masalah
Bagaimana mengetahui urutan areal tanaman yang didahulukan berdasarkan prioritas
kebutuhan peremajaan.
1.3. Tujuan Penelitian
Adapun penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui urutan giliran setiap
areal tanaman yang akan dilakukan proses peremajaan dengan menggunakan metode
3
1.4. Batasan Masalah
Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah:
1. Input berupa list areal tanaman dan parameter yang mempengaruhi prioritas
kebutuhan peremajaan tanaman yaitu : Tren Produksi, Umur Tanaman,
Jumlah Pohon/ha
2. Output berupa ranking areal - areal tanaman kelapa sawit seluruh kebun
PTPN3 berdasarkan prioritas kebutuhan peremajaan tanaman.
3. Sumber berdasarkan data dari PTPN3.
1.5. Manfaat Penelitian
Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:
a. Membantu pengguna dalam menentukan urutan giliran peremajaan tanaman
setiap areal tanaman terutama kelapa sawit.
b. Memperdalam ilmu peneliti tentang metode Analytical Hierarkhi Process.
1.6. Sistematika Penulisan
Tugas akhir ini disusun dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
BAB 1 PENDAHULUAN
Pada bab pendahuluan berisi tentang hal-hal yang mendasari dilakukannya penelitian
serta mengidentifikasi masalah penelitian. Bagian-bagian yang terdapat dalam bab
pendahuluan ini terdiri atas latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan
masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA
Pada bab tinjauan pustaka berisi landasan teori, kerangka pikir dan hipotesis yang
BAB 3 METODOLOGI
Pada bab metodologi berisi metodologi penelitian yang dilakukan dalam menerapkan
metode Analytical Hierarkhi Process dalam penghitungan bobot menggunakan
parameter yang mendukung peremajaan tanaman.
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada bab hasil dan pembahasan berisi penjelasan hasil dari pengujian penghitungan
bobot menggunakan metode Analytical Hierarkhi Process yang akan menampilkan
hasil pengurutan prioritas peremajaan tanaman.
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN
Pada bab kesimpulan dan saran berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran
BAB 2
LANDASAN TEORI
2.1. Peremajaan Kelapa Sawit
Terdapat beberapa pertimbangan dalam menentukan saat petani pekebun harus melakukan peremajaan. Pertimbangan dalam melakukan peremajaan antara lain adalah umur tanaman sudah tua (umumnya 19 - 25 tahun). Secara fisiologis tanaman tua seperti ini memiliki produktivitas yang semakin menurun, sehingga dipandang tidak lagi memberikan keuntungan secara ekonomis malah bisa merugi. Umumnya batas umur ekonomis yang digunakan sebagai patokan teknis untuk tanaman kelapa sawit rata-rata 25 tahun, namun tidak jarang umur ekonomis hanya mencapai 19 tahun.
Pada umur tanaman tua ini produktivitas tanaman rendah (umumnya < 12 ton/ha/th tidak ekonomis atau rata-rata 1 ton/ha/bl). Tanaman yang berproduksi rendah sebagai akibat dari umur tanaman sudah tua atau tumbuhnya kurang besar dan dianggap kurang menguntungkan. Kesulitan pelaksanaan panen juga dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan saat petani pekebun harus melakukan peremajaan kebunnya. Tanaman yang sudah tua umumnya memiliki pohon tinggi yang dapat menyulitkan saat pemanenan, sehingga efektivitas dan efisiensi panen menjadi rendah karena ongkos produksi menjadi mahal. Kebun yang sudah tua kerapatan tanamanumumnya rendah, sehinggatanaman dengan kerapatan yang rendah tidak ekonomis untuk dikelola sehingga perlu diremajakan.
2.2. PT Perkebunan Nusantara III
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) adalah Badan Usaha Milik
Perusahaan ini berkantor pusat di Medan, Sumatera Utara dan resmi didirikan
dari hasil restrukturisasi BUMN pada tahun 1996. Direktur Utama perusahaan
adalah Bagas Angkasa sedangkan Komisaris Utama adalah Achmad Mangga Barani.
PTPN III dibentuk berdasarkan PP No.8 Tahun 1996, Tanggal 14 Pebruari 1996
dalam rangka restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibidang
perkebunan. PTPN III merupakan penggabungan kebun-kebun diwilayah Sumetera
Utara dari eks PTP III, PTP IV dan PTP V.
2.3. Sistem Pendukung Keputusan (SPK)
SPK merupakan sistem informasi berbasis komputer yang intraktif, fleksibel,
dan dapat beradaptasi, yang secara khusus dikembangkan untuk mendukung
penyelesaian permasalahan yang tidak terstruktur untuk meningkatkan pembuatan
keputusan (Turban 1995).
2.4. Metode Analytical Hierarchy Process (AHP)
Metode AHP merupakan salah satu model untuk pengambilan keputusan yang
dapat membantu kerangka berfikir manusia. Pada dasarnya AHP adalah metode yang
memecah suatu masalah yang kompleks dan tidak terstruktur ke dalam
kelompok-kelompok, mengatur kelompok-kelompok tersebut ke dalam suatu susunan hirarki,
memasukkan nilai numeris sebagai pengganti persepsi manusia dalam melakukan
perbandingan relatif, dan akhirnya dengan suatu sintesis ditentukan elemen mana yang
mempunyai prioritas tertinggi (Permadi, 1992). Metode AHP memakai persepsi
manusia yang dianggap expert sebagai input utama, yaitu orang yang mengerti benar
permasalahan yang diajukan, merasakan akibat suatu masalah, atau punya
kepentingan terhadap masalah tersebut. Saaty (1991) menyatakan bahwa pada
dasarnya metode Proses Hirarki Analitik (PHA) adalah memfokuskan suatu situasi
yang kompleks tak terstruktur, ke dalam bagian-bagian komponennya, menata bagian
atau variabel itu ke dalam suatu susunan hirarki, memberi nilai numerik pada
pertimbangan subjektif tentang relatif pentingnya setiap variabel, dan mensintesis
berbagai pertimbangan itu untuk menetapkan variabel mana yang memiliki prioritas
7
dengan itu, dalam memecahkan persoalan dengan AHP (decomposition)¸ prinsip
penilaian komparatif (comparative judgment), prinsip sintesa prioritas (synthesis of
priority) dan prinsip konsistensi logis (logical consistency).
1. Decomposition, yaitu pemecahan yang utuh menjadi unsur-unsurnya. Jika ingin
mendapatkan hasil yang lebih akurat, pemecahan juga dilakukan terhadap
unsur-unsurnya sampai tak mungkin dilakukan pemecahan lebih lanjut,
sehingga didapatkan beberapa tingkatan (hirarki) dari persoalan tadi.
2. Comparative Judgment. Prinsip ini berarti membuat penilaian tentang
kepentingan relative dua elemen pada suatu tingkat tertentu dalam kaitannya
dengan tingkat di atasnya. Penilaian itu merupakan inti dari AHP, karena akan
berpengaruh terhadap prioritas elemen-elemen. Hasil dari penilaian disajikan
dalam bentuk matriks yang dinamakan maktriks pairwise comparison.
3. Synthesis of Priority. Pada setiap matriks “pairwise comparison” terdapat local
priority. Oleh karena “pairwise comparison” terdapat pada setiap tingkat, maka
untuk mendapatkan global priority harus dilakukan sintesa di antara local
priority tersebut. Pengurutan elemen-elemen tersebut menurut kepentingan
relatif melalui prosedur sintesa yang dinamakan priority setting.
4. Logical consistency. Konsistensi dalam hal ini mempunyai dua makna. Pertama
bahwa objek-objek yang serupa dapat dikelompokkan sesuai dengan
keseragaman dari relevansinya. Kedua bahwa tingkat hubungan antara
objek-objek didasarkan pada kriteria tertentu misalnya sama penting, sedikit lebih
penting, jelas lebih penting, mutlak lebih penting.
2.4.1. Komparasi Berpasang
Tahap terpenting dalam AHP adalah penilaian dengan teknik komparasi berpasangan
terhadap aktor-aktor pada suatu tingkat hirarki. Penilaian dilakukan dengan
memberikan bobot numeric dan membandingkan antara satu elemen dengan elemen
lainnya. Tahap selanjutnya adalah melakukan sintesa terhadap hasil penilaian untuk
menentukan elemen mana yang memiliki prioritas tertinggi dari terendah. Skala
komparasi yang digunakan adalah 1 sampai 9 adalah yang terbaik. Hal ini telah
dibuktikan oleh Saaty dengan berdasarkan pertimbangan tingginya akurasi yang
ditunjukkan dengan nilai Root Means Square (RMS) dan Median Absolute Deviation
(MAD) pada berbagai problema. Nilai skala komparasi yang dimaksudkan disajikan
Tabel 2.1. Nilai Skala Komparasi Berpasangan, (Saaty, 1991)
Tingkat Kepentingan Definisi
1 Sama penting
3 Sedikit lebih penting
5 Jelas lebih penting
7 Sangat jelas lebih penting
9 Pasti/mutlak lebih penting
1/(1-9) Kebaikan nilai tingkat kepentingan dari skala 1 - 9
2.4.2. Prosedur AHP
Pada dasarnya, prosedur atau langkah-langkah dalam metode AHP yaitu
mendefenisikan masalah, sintesis, mengukur konsistensi, menghitung Consistency
Index (CI), menghitung rasio, dan memeriksa konsistensi hierarki.
Cara menghitung Indek Konsistensi (CI) dapat dilihat dengan persamaan (2.1):
CI = (λ maks-n)/n (2.1)
di mana n = banayak kriteria
Cara menghitung Rasio Konsistensi (CR) dapat dilihat dengan persamaan (2.2)
CR = CI/RC (2.2)
Di mana CR = Consistency Ratio
CI = Consistency Index
IR = Indeks Random Consistency
Untuk memeriksa Konsistensi Hierarki dapat dilihat dengan table 2.2 . Jika
nilainya lebih dari 10%, maka penilaian data judgment harus diperbaiki. Namun jika
rasio konsistensi (CI/IR) kurang atau sama dengan 0.1, maka hasil perhitungan
9
Tabel 2.2. Nilai RI
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RI 0 0 5.8 0.9 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49
2.4.3. Contoh Penerapan AHP
Penerapan AHP pada contoh kasus sederhana. Suatu kasus yang harus
diputuskan mempunyai 3 kriteria yaitu Kriteria A, B dan C.
Langkah 1:
Buat matrik berpasangan dan berikan tingkat kepentingannya. Tidak perlu seluruh
angka diisi. Cukup diagonal ke atas saja. Lihat tabel 2.3:
Tabel 2.3. Skala Penilaian Berpasangan
Kriteria A Kriteria B Kriteria C
Kriteria A 1 3 1
Kriteria B 1 5
Kriteria C 1
Angka 1 pada diagonal matrik di atas merupakan perbandingan kriteria yang sama.
Angka 3 pada Kriteria B menyatakan bahwa Kriteria lebih penting sedikit daripada
Kriteria A demikian seterusnya. Untuk mengisi angka pada kotak yang kosong
dilakukan dengan cara dibagi yaitu mengisi elemen Kriteria A vs Kriteria B. Maka
cukup mengambil nilai Kriteria A vs Kriteria A (yaitu 1), kemudian dibagi dengan
nilai Kriteria B vs Kriteria A (yaitu 3) menghasilkan 0.333 lihat tabel 2.4. :
Tabel 2.4. Penilaian Berpasangan Lengkap
Kriteria A Kriteria B Kriteria C
Kriteria A 1 3 1
Kriteria B 0.3333333 1 5
Langkah 2 :
Lakukan normalisasi. Caranya dengan membagi setiap elemen dengan jumlah
masing-masing kolom.
Tabel 2.5. Jumlah Kolom
Kriteria A Kriteria B Kriteria C
Kriteria A 1 3 1
Kriteria B 0.3333333 1 5
Kriteria C 1 0.2 1
Jumlah 2.3333333 4.2 7
Tabel 2.6. Normalisasi
Kriteria A Kriteria B Kriteria C
Kriteria A 0.4285714 0.7142857 0.1428571
Kriteria B 0.1428571 0.2380952 0.7142857
Kriteria C 0.4285714 0.047619 0.1428571
angka normal seperti di tabel 2.5. didapat dari kriteria dibagi jumlah. Contohnya 1
dibagi 2.3333 .. hasilnya 0.42857 (Lihat tabel 2.6.).
Langkah 3:
Cari rata-rata setiap kriteria. Caranya, jumlahkan tiap baris kemudian dibagi dengan
jumlah kriteria yang ada. Untuk kasus ini jumlah kriterianya 3 (A, B, C).
Tabel 2.7. Rata- rata
Kriteria A Kriteria B Kriteria C Rata - rata
Kriteria A 0.4285714 0.7142857 0.1428571 0.428571429
Kriteria B 0.1428571 0.2380952 0.7142857 0.365079365
11
Maka Vektor Bobot yaitu : W1= 0.428571429
W2= 0.365079365 W3= 0.206349206
Langkah 4:
Kalikan bobot dengan matrik berpasangan tadi. Mana yang paling besar, itulah yang paling penting
1 3 1 0.42857143 1.730159
0.3333333 1 5 0.36507937 = 1.539683
1 0.2 1 0.20634921 0.707937
Kalau di atas, maka tentunya urutannya adalah Kriteria A, Kriteria B dan Kriteria C
Setelah ini masuk ke langkah pengujian
Langkah 1:
Kalikan bobot tadi dengan matrik berpasangan yang pertama.
Langkah 2:
cari nilai t dengan cara bagilah hasil pada langkah 1 tadi dengan masing-masing
bobotnya, kemudian jumlahkan semuanya. Setelah itu bagilah dengan jumlah kriteria
yaitu 3. Lihat rumus dan angka di bawah ini :
Sehingga t = 3.895
Langkah 3:
Hitung Consistency Index (CI) dengan cara mengurangkan t di atas dengan jumlah
kriteria. Hasilnya dibagi lagi dengan jumlah kriteria.
CI = (t-n)/n —> (3.985-4)/4 = -0.0375
Langkah 4:
Hitung Consistency Ratio (CR) dengan cara CI/RI. RI didapatkan dari tabel. Lihat
tabel 2.2.
Karena contoh kasus ini menggunakan hanya 3 kriteria artinya RI yang dipakai 3 yaitu
5.8.
Sehingga CR= -0.0375/5.8 = -0.000647 5:
Langkah 5
Cek hasilnya, jika CR kurang dari 0.1 maka hasilnya bisa disebut konsisten. Jika tidak
konsisten, matrik berpasangannya harus diulang untuk dibuat.
2.5. Penelitian Terdahulu
Bagian ini menjelaskan beberapa penelitian terdahulu terkait dengan prioritas
peremajaan tanaman. Tabel penelitian terdahulu ditunjukkan pada tabel 2.3
Tabel 2.8. Penelitian Terdahulu
Penulis Judul Penelitian Metode Kekurangan
Sutrisno Badri
(2012)
Aplikasi model untuk
mengembangkan Klaster
agroindustri kelapa sawit
AHP Kriteria yang menjadi
faktor pendukung
lebih subjektif
Anton Setiawan
Honggowibowo
(2010)
Implementasi metode
analytical hierarchy
process untuk
pengambilan keputusan
pemilihan foto
berdasarkan tujuan
perolehan foto
AHP Menggunakan grafik
untuk menunjukkan
output. Tidak
dijabarkan urutannya
BAB 3
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM
Bab ini membahas beberapa hal diantaranya seperti data yang digunakan, tahapan
pengenalan yang dilakukan, penerapan metode yang digunakan dan analisis
perancangan sistem dalam mengimplementasikan metode Analytical Hierarkhi
Process. Pembahasan bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang spesifikasi dan
kebutuhan dalam pengerjaan dan pengembangan aplikasi.
3.1. Data yang Digunakan
Data penelitian yang digunakan berasal dari PTPN 3 bagian tanaman yaitu berupa
tahun tanam untuk memperoleh umur tanaman, jumlah pohon per Ha, dan jumlah
produksi. Jadi totalnya ada 342 kelompok tanaman kelapa sawit yang berasal dari 30
kebun tanaman kelapa sawit PTPN 3. Contoh data yang digunakan diantaranya adalah
:
3.1. Tabel Kebun Sei Meranti
3.2. Tabel Kebun Sei Daun
3.4. Tabel Kebun Rambutan
15
3.2. Arsitektur Umum
Pada desain ini ditunjukkan bagaimana setiap proses berlangsung dan membentuk
sebuah aplikasi yang terbentuk dengan sistematis. Rancangan arsitektur dapat dilihat
pada Gambar 3.1.
Mulai
Input Data
Proses pencarian bobot setiap
parameter menggunakan
metode AHP
Matriks Faktor Pembobotan Hirarki untuk semua kriteria
yang didesimalkan
Menampilkan hasil pengurutan
prioritas peremajaan
tanaman
Selesai Gambar 3.1. Arsitektur Umum
3.3. Diagram Aliran Data
Penjelasan dalam pengaturan database besertaalur dan transformasi data dalam sistem
akan dijelaskan dengan diagram aliran data atau DFD.
3.3.1. DFD Level 0
DFD level 0 mencakup gambaran secara umum alur input dan output seperti yang
Administrator
Gambaran secara umum alur input dan output pada DFD level 1 yang akan dibagi jadi
4 bagian. Pada gambar 3.3. aliran data user yang dimaksud adalah username dan
password.
Data User Data User
Data User Data User
17
Berikutnya adalah DFD Management Sawit yang berisikan data parameter yang
diperlukan sistem untuk menentukan prioritas peremajaan tanaman.
Administrator Data Sawit
Data Sawit Data Sawit
Data Sawit
Data Sawit Data Sawit
Data Sawit
Data Sawit
Gambar 3.4. DFD Level 1 (Management Sawit)
Bagian ketiga adalah management kebun yang juga digambarkan secara umum seperti
yang ditunjukkan pada gambar 3.5. :
Administrator Data Kebun
Data Kebun Data Kebun
Data Kebun
Data Kebun Data Kebun
Data Kebun
Data Kebun
Pada bagian terakhir mencakup penghitungan metode AHP yang juga menggunakan
data sawit dan data kebun. Kalkulasi metode AHP ditunjukkan pada gambar 3.6. :
Administrator
1 Kalkulasi Meode AHP
2 Menampilkan Hasil Kalkulasi
Data Sawit
Nilai Bobot
Hasil Kalkulasi
Hasil Kalkulasi
Data Sawit
Data Kebun Data Kebun
Gambar 3.6. DFD Level 1 (Kalkulasi AHP)
3.4. Analisis Sistem
Analisis diperlukan sebagai dasar perancangan sistem. Pada penelitian ini,
terdapat enam tahap yang merupakan prosedur menggunakan metode AHP. Berikut
adalah hierarki yang ditunjukkan pada gambar 3.7. :
Peremajaan Tanaman Sawit
Tahun
Tanam Pohon per
Ha
Produksi
Areal
Tanaman 1 Tanaman 2Areal Tanaman 3Areal
Areal Tanaman n
19
Tahapan Pertama adalah mendefenisikan masalah dan menentukan solusi yang
diinginkan, lalu menyusun hierarki dari permasalahan yang dihadapi. Dalam hal ini
yaitu peremajaan tanaman kelapa sawit yang menghasilkan berdasarkan tahun tanam.
Tahap Kedua yaitu menentukan nilai bobot dari parameter – parameter dari data
perkebunan pada tahun 2011, 2012 dan 2013. Angkanya ditentukan berdasarkan
seberapa penting parameter tersebut dalam peremajaan tanaman. Buat matriks
berpasangan dan berikan tingkat kepentingannya. Tidak perlu seluruh angka diisi.
Cukup diagonal ke atas saja. Lihat tabel 3.5. :
Tabel 3.5. Skala Penilaian Berpasangan
Tahun Tanam (Umur)
Pohon per Ha Produksi
Tahun Tanam (Umur)
1 3 7
Pohon per Ha 1 5
Produksi 1
Angka 1 pada diagonal matriks di atas merupakan perbandingan kriteria yang sama.
Angka 3 pada Kriteria Pohon per Ha menyatakan bahwa Kriteria lebih penting sedikit
daripada Kriteria Tahun Tanam (Umur) demikian seterusnya. Untuk mengisi angka
pada kotak yang kosong dilakukan dengan cara dibagi yaitu mengisi elemen Kriteria
Tahun Tanam (Umur) vs Kriteria Pohon per Ha. Maka cukup mengambil nilai Kriteria
Tahun Tanam (Umur) vs Kriteria Tahun Tanam (Umur) yaitu 1, kemudian dibagi
dengan nilai Pohon per Ha vs Tahun Tanam (Umur) yaitu 3 menghasilkan 0.333 lihat
tabel 3.6. :
Tabel 3.6. Penilaian Berpasangan Lengkap
Tahun Tanam (Umur)
Pohon per Ha Produksi
Tahun Tanam (umur)
Tabel 3.6. Penilaian Berpasangan Lengkap (Lanjutan)
Tahun Tanam (Umur)
Pohon per Ha Produksi
Pohon per Ha 0,3333333 1 5
Produksi 0,143 0,2 1
Tahap Ketiga yaitu lakukan normalisasi. Caranya dengan membagi setiap kriteria
dengan jumlah masing-masing kolom.
Tabel 3.7. Jumlah Kolom
Tahun Tanam (Umur)
Pohon per Ha Produksi
Tahun Tanam (Umur)
1 3 7
Pohon per Ha 0,333 1 5
Produksi 0,143 0,2 1
Jumlah 1,476 4,2 13
Tabel 3.8. Normalisasi
Tahun Tanam (Umur)
Pohon per Ha Produksi
Tahun Tanam (Umur)
0,677 0,714 0,538
Pohon per Ha 0,226 0,238 0,385
21
Pada tabel 3.7. dilakukan penjumlahan kolom. Contohnya pada kolom Kirteria Tahun
Tanam (Umur)
1 + 0,333 + 0,143 = 1,476.
angka normal seperti di tabel 3.8. didapat dari kriteria dibagi jumlah. Contohnya
1 / 1,476 = 0.677
Mulai
Inv_krieria1 =1/kriteria1 Inv_krieria2 =1/kriteria2 Inv_krieria3 =1/kriteria3
Jumlahkolom1 = 1 + inv_kriteria1 + inv_kriteria2 Jumlahkolom2 = kriteria1 + 1 + inv_kriteria3
Jumlahkolom3 = kriteria2 + kriteria3 +1
Normalisasi_kriteria1_1 = 1 / jumlahkolom1 Normalisasi_kriteria1_2 = inv_kriteria1 / jumlahkolom1 Normalisasi_kriteria1_3 = inv_kriteria2 / jumlahkolom1
Selesai Kriteria1, Kriteria2, Kriteria3
Normalisasi_kriteria2_1 = kriteria1 / jumlahkolom2 Normalisasi_kriteria2_2 = 1 / jumlahkolom2 Normalisasi_kriteria2_3 = inv_kriteria3 / jumlahkolom2
Normalisasi_kriteria3_1 = kriteria2 / jumlahkolom3 Normalisasi_kriteria3_2 = kriteria3 / jumlahkolom3
Normalisasi_kriteria3_3 = 1 / jumlahkolom3
Gambar 3.8. Flowchart Tahap Normalisasi
Tahap keempat yaitu Cari rata-rata setiap kriteria. Caranya, jumlahkan tiap baris
kemudian dibagi dengan jumlah kriteria yang ada. Untuk kasus ini jumlah kriterianya
Tabel 3.9. Rata- Rata
Tahun Tanam (Umur)
Pohon per Ha
Produksi Rata - rata
Tahun Tanam (Umur)
0,677 0,714 0,538 0,643
Pohon per Ha 0,226 0,238 0,385 0,283
Produksi 0,097 0,048 0,077 0,074
Maka Vektor Bobot yaitu : W1= 0,643
W2= 0,283 W3= 0,074
Kalikan bobot dengan matriks berpasangan tadi. Mana yang paling besar, itulah yang
paling penting
1 3 7 0,643 2,008
0.333 1 5 0,283 = 0,866
0,143 0.2 1 0,074 0,222
Kalau di atas, maka tentunya urutannya adalah Kriteria tahun tanam (umur) , Kriteria
pohon per Ha dan Kriteria Produksi.
Hasil perkalian matriks juga berperan langsung dalam hasil pengurutan peremajaan
tanaman. Hasil tersebut akan dikalikan ke setiap kriteria – kriteria yang diperlukan
dalam peremajaan tanaman sehingga menghasilkan hasil penghitungan akhir bobot
23
Mulai
Jlhbaris1 = normalisasi_kriteria1_1 + normalisasi_kriteria2_1 + normalisasi_kriteria3_1 Jlhbaris2 = normalisasi_kriteria1_2 + normalisasi_kriteria2_2 + normalisasi_kriteria3_2 Jlhbaris3 = normalisasi_kriteria1_3 + normalisasi_kriteria2_3 + normalisasi_kriteria3_3
Kriteria1, kriteria2, kriteria3
rataan1 = jlhbaris1 /n rataan2 = jlhbaris2 /n rataan3 = jlhbaris3 /n
Selesai
vecktorbobotkriteria1 = (matriks[0][0] * rataan1) + (matriks[0][1] * rataan2) + (matriks[0][2] * ratan3)
vektorbobotkriteria2 = (matriks[1][0] * ratan1) + (matriks[1][1] * ratan2) + (matriks[1][2] * ratan3)
vectorbobotkriteria3 = (matriks[2][0] * ratan1) + (matriks[2][1] * ratan2) + (matriks[2][2] * ratan3)
Gambar 3.9. Flowchart Vektor Bobot
Tahap kelima yaitu pengujian. Kalikan bobot tadi dengan matriks berpasangan yang
pertama. Cari nilai t dengan cara bagilah hasil pada langkah 1 tadi dengan
masing-masing bobotnya, kemudian jumlahkan semuanya. Setelah itu bagilah dengan jumlah
Sehingga t = 3,097
Hitung Consistency Index (CI) dengan cara mengurangkan t di atas dengan jumlah
kriteria. Hasilnya dibagi lagi dengan jumlah kriteria.
CI = (t-n)/n-1 —> (3.097-3)/3-1 = 0,048
Hitung Consistency Ratio (CR) dengan cara CI/RI. RI didapatkan dari tabel. Lihat
tabel 3.10. :
Tabel 3.10. Nilai RI
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RI 0 0 5.8 0.9 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49
Karena contoh kasus ini menggunakan hanya 3 kriteria artinya RI yang dipakai 3 yaitu
5.8.
Sehingga CR= 0.0375/5.8 = 0.083
Cek hasilnya, jika CR kurang dari 0.1 maka hasilnya bisa disebut konsisten. Jika tidak
konsisten, matriks berpasangannya harus diulang untuk dibuat.
start
T = 1 /3 (vektorbobotkriteria1 / rataan1)+(vektorbobotkriteria2 /rataan2)+
(vektorbobotkriteria3 /rataan3)
Ci = (t-n)/n-1
CR= 0.0375/5.8
CR < 0.1
konsisten ya
Tidak konsisten tidak
end
25
Tahap Keenam yaitu mencari hasil pengurutan peremajaan tanaman kelapa sawit
berdasarkan tahun tanam dengan cara menjumlahkan hasil perkalian dari tiap –tiap
hasil perkalian matriks dengan data konversi kriteria – kriteria tersebut. Data konversi
di dapat dai pengelompokkan kriteria – kriteria ke dalam satuan dari angka 1 sampai
dengan 5 seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.11. :
Tabel 3.11. Data Konversi Kriteria
Kriteria Data Awal Data Konversi
Tahun Tanam <1990 1990 – 1995
Produksi <5000
5000-15000
Bobot = (vectorbobotkriteria1 *koversiusia[a]*-1) + vectorbobotkriteria2 + konversipohon_per_ha[a] +
vectorbobotkriteria3 + konversiproduksi[a]
3.5. Perancangan Tampilan Antarmuka
Antarmuka pengguna (user interface) merupakan media yang menghubungkan
manusia dengan komputer. Perancangan antarmuka bertujuan untuk memberikan
gambaran umum tampilan dari aplikasi yang akan dibuat. Pada tampilan antarmuka
aplikasi akan ditampilkan panel citra dan panel tombol.
3.5.1 Rancangan tampilan halaman log in
Untuk masuk ke dalam sistem peremajaan sawit, admin harus mengisi
username dan password. Username terletak diurutan pertama di tengah atas dan
berfungsi sebagai identitas admin yang akan mengakses system peremajaan sawit.
Sedangkan password terletak di bawah username dan berfungsi sebagai kata kunci
dari identitas admin tersebut sehingga tidak dapat diakses orang lain yang tidak
berkepentingan.
Perancangan Sistem Peremajaan Tanaman Sawit
Username :
Password :
Masuk
Gambar 3.12. Halaman Login
3.5.2 Rancangan tampilan halaman menu sistem
Di Kolom kiri terdapat tombol menu yang diperlukan untuk
pengimplementasikan pengurutan data. Tombol “sistem” berfungsi untuk meng-input
data management, data kebun dan data parameter yang akan ditampilkan dikolom
sebelah kanan. Untuk mengisi data di sistem digunakan tombol “daftar” dan jika ingin
27
berfungsi untuk meng-input bobot yang digunakan berdasarkan kriteria – kriteria
tersebut. Setelah memasukkan nilai bobot gunakan tombol “hitung” untuk mencari
nilai konsistensinya atau “reset” untuk menghapus. Jika nilai tersebut keluar muncul
tombol “hitung peremajaan” dengan syarat hasil hitungan tersebut konsisten da nada
tombol “riset” jika ingin mengganti nilai bobot
MENU
Penghitungan Sistem
BAB 4
IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai implementasi dari Analytical Hierarkhi
Process sesuai perancangan yang telah dijelaskan pada bab 3 serta melakukan
pengujian dari sistem yang telah dibuat.
4.1. Implementasi Sistem
Sesuai dengan hasil analisis dan perancangan yang telah dibuat, Analytical Hierarkhi
Process akan diimplementasikan ke dalam sebuah sistem dengan menggunakan
bahasa pemrograman PHP.
4.1.1 Spesifikasi hardware dan software yang digunakan
Spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk
membangun sistem adalah sebagai berikut:
1. Processor Intel® Core™ 2 Duo CPU @ 2.20GHz
2. Kapasitas hard disk 320 GB
3. Memory RAM yang digunakan 4 GB
4. Sistem operasi yang digunakan adalah Microsoft Windows 8.1 Pro 32-bit
5. XAMPP Version 1.8.3
29
Pengerjaan Program dengan menggunakan Bahasa PHP membutuhkan method
untuk membantu penghitungan AHP dengan baik, maka digunakan method tambahan
yang digunakan untuk membantu proses penghitungan hingga pengujian. Beberapa
method yang digunakan dalam proses penghitungan AHP dapat dilihat pada tabel 4.1.
Tabel 4.1 Method yang digunakan dalam program
Fungsi Keterangan
include() Untuk memanggil halaman yang ada di
file lain.
$_SESSION() Deklarasi nama di dalam sesi.
mysql_connect() Untuk menyambung ke database.
focus() Menjalankan fungsi yang ada di
dalamnya ketik dalam keadaan terpilih.
while() Menjalankan perintah ketika kondisi
belum terpenuhi.
4.2. Implementasi perancangan antarmuka
4.2.1. Tampilan Awal
Tampilan awal sistem dimulai dengan log in dan password untuk bisa masuk
ke sistem tersebut.
4.2.2. Tampilan Halaman Utama
Halaman utama menampilkan menu sistem untuk memilih data apa yang ingin
di masukkan dan ada pilihan menu penghitungan dapat digunakan setelah
selesai memasukkan semua data yang diperlukan.
Gambar 4.2. Halaman Utama
4.2.3. Tampilan Menu Sistem dengan Pilihan User Management
Halaman menu sistem dengan pilihan user management merupakan tempat
mendaftar akun admin sistem peremajaan tanaman dengan mengisi username
password. Juga bias meng-edit atau menghapus akun yang sudah ada.
31
4.2.4. Halaman Data Kebun
Halaman data kebun berfungsi mendaftar kebun – kebun kelapa sawit yang
ada di perusahaan dan bisa meng-edit atau menghapus data kebun yang sudah
ada.
Gambar 4.4. Halaman Data Kebun
4.2.5. Halaman Data Sawit
Halaman data sawit merupakan tempat mengisi data kriteria – kriteria seperti
umur tanaman, jumlah produksi/ha, dan jumlah pohon/ha. Seperti halaman
sistem sebelumnya, halaman ini juga dilengkapi dengan edit data serta
menghapus data.
4.2.6. Halaman Penghitungan
Halaman penghitungan berfungsi untuk penghitungan bobot dari kriteria –
kriteria yang merupakan parameter dalam menentukan pengurutan prioritas
peremajaan tanaman. Langkah awal adalah meng-input angka bobot pada
masing - masing kriteria seperti pada gambar 4.6. :
Gambar 4.6. Pembobotan Kriteria
Setelah meng-input angka pembobotan pada kriteria, selanjutnya klik pada
tombol hitung. Setelah sistem selesai melakukan penghitungan dengan metode
AHP, maka didapatlah hasil preferensi responden. Jika CR (Consistency Ratio)
kurang dari 0.1 maka hasilnya bisa disebut konsisten. Jika tidak konsisten,
matrik berpasangannya harus diulang untuk dibuat. Pada gambar 4.7. Hasil CR
adalah 0,281 yaitu lebih besar dari 0,1. Maka preferensi respondennya tidak
konsisten.
33
Jika Tidak Konsisten, admin harus mengganti angka bobot pada tabel kriteria
yang pertama (paling atas). Jika angka pembobotan tersebut cocok maka
hasilnya akan konsisten.
Gambar 4.8. Pembobotan Kriteria dengan Angka yang Cocok
4.2.7. Halaman Output
Setelah mendapat hasil preferensi responden yang konsisten, klik tombol
“Hitung Nilai Peremajaan” untuk melihat hasil output. Pada halaman Output
akan muncul hasil pengurutan peremajaan tanaman kelapa sawit berdasarkan
kriteria – kriteria yang menjadi parameter. Nilai pentingnya peremajaan diukur
dengan total perkalian vector eigen dengan data konversi. Pada hasil akhir
bobot dapat dilihat, jika nilainya lebih kecil dari 3 maka data tersebut perlu
diremajakan sedangkan nilai yang lebih besar dari 3 belum perlu untuk
diremajakan.
35
Gambar 4.11. Halaman Output belum perlu diremajakan
4.3. Hasil Pengujian
Hasil pengurutan peremajaan tanaman di dapat dari penjumlahan dari hasil
perkalian tiap – tiap hasil perkalian matriks dengan ketiga kriteria. Kriteria yang
digunakan disini adalah nilai rata – rata tiap – tiap kriteria dari data sawit tiga tahun
terakhir. Output yang ditampilkan tersebut berupa tabel ranking yang berisikan tahun
tanam, usia pada tahun 2014, Jumlah pohon per Ha, Jumlah produksi Ton per Ha,
kemudian data konversi kriteria – kriteria tersebut, letak kebun areal tanamannya dan
hasil akhir bobot. Berikut adalah hasil pengujian dari pengurutan prioritas peremajaan
Tabel 4.2. Output Pengurutan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit
No Tahun Tanam
Usia (Tahun)
Jumlah Pohon per Ha
Jumlah Produksi Ton/Ha
Konversi Tahun Tanam
Konversi Pohon per Ha
Konversi Produksi
Nama Kebun Bobot
1 2006 9 143 25.63 1 4 1 Kebun Labuhan Haji 1.85 Perlu peremajaan
2 2006 9 142 23.00 1 4 1 Kebun Aek Nabara
Selatan
1.85 Perlu peremajaan
3 2009 6 142 5.19 1 4 1 Kebun Distrik Labuhan
Batu III
1.85 Perlu peremajaan
4 2009 6 130 3.55 1 4 1 Kebun Distrik Simalungun 1.85 Perlu peremajaan
5 2006 9 141 23.81 1 4 1 Kebun Distrik Simalungun 1.85 Perlu peremajaan
6 2006 9 128 18.49 1 4 1 Kebun Huta Padang 1.85 Perlu peremajaan
7 2009 6 142 4.80 1 4 1 Kebun Labuhan Haji 1.85 Perlu peremajaan
37
Tabel 4.2. Output Pengurutan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit (Lanjutan)
No Tahun Tanam
Usia (Tahun)
Jumlah Pohon per Ha
Jumlah Produksi Ton/Ha
Konversi Tahun Tanam
Konversi Pohon per Ha
Konversi Produksi
Nama Kebun Bobot
9 2008 7 141 14.61 1 4 1 Kebun Distrik Simalungun 1.85 Perlu peremajaan
10 2007 8 138 20.45 1 4 1 Kebun Aek Raso 1.85 Perlu peremajaan
11 2007 8 125 15.26 1 4 1 Kebun Gunung Monaco 1.85 Perlu peremajaan
12 2009 6 142 3.92 1 4 1 Kebun Aek Torop 1.85 Perlu peremajaan
13 2008 7 135 14.37 1 4 1 Kebun Aek Torop 1.85 Perlu peremajaan
14 2006 9 142 23.25 1 4 1 Kebun Distrik Labuhan Batu III 1.85 Perlu peremajaan
15 2007 8 142 20.38 1 4 1 Kebun Distrik Labuhan Batu III 1.85 Perlu peremajaan
16 2006 9 134 21.11 1 4 1 Kebun Aek Raso 1.85 Perlu peremajaan
Tabel 4.2. Output Pengurutan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit (Lanjutan)
No Tahun Tanam
Usia (Tahun)
Jumlah Pohon per Ha
Jumlah Produksi Ton/Ha
Konversi Tahun Tanam
Konversi Pohon per Ha
Konversi Produksi
Nama Kebun Bobot
18 2008 7 142 17.23 1 4 1 Kebun Distrik Labuhan Batu III 1.85 Perlu peremajaan
19 2006 9 141 22.79 1 4 1 Kebun Distrik Labuhan Batu II 1.85 Perlu peremajaan
20 2007 8 142 21.59 1 4 1 Kebun Distrik Labuhan Batu II 1.85 Perlu peremajaan
21 2008 7 142 16.59 1 4 1 Kebun Sei Sumut 1.85 Perlu peremajaan
22 2009 6 133 10.23 1 4 1 Kebun Distrik Serdang - II 1.85 Perlu peremajaan
23 2007 8 143 17.90 1 4 1 Kebun Rambutan 1.85 Perlu peremajaan
24 2006 9 142 23.81 1 4 1 Kebun Dusun Hulu 1.85 Perlu peremajaan
25 2006 9 146 23.65 1 4 1 Kebun Sei Dadap 1.85 Perlu peremajaan
39
Tabel 4.2. Output Pengurutan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit (Lanjutan)
No Tahun
1.85 Perlu peremajaan
30 2008 7 142 14.83 1 4 1 Kebun Dusun Hulu 1.85 Perlu peremajaan
31 2009 6 142 6.00 1 4 1 Kebun Huta Padang 1.85 Perlu peremajaan
32 2007 8 128 17.18 1 4 1 Kebun Huta Padang 1.85 Perlu peremajaan
33 2009 6 143 3.79 1 4 1 Kebun Distrik Labuhan
Batu II
1.85 Perlu peremajaan
Tabel 4.2. Output Pengurutan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit (Lanjutan)
No Tahun Tanam
Usia (Tahun)
Jumlah Pohon per Ha
Jumlah Produksi Ton/Ha
Konversi Tahun Tanam
Konversi Pohon per Ha
Konversi Produksi
Nama Kebun Bobot
35 2008 7 141 16.32 1 4 1 Kebun Huta Padang 1.85 Perlu peremajaan
36 2009 6 132 3.55 1 4 1 Kebun Bangun 1.85 Perlu peremajaan
37 2007 8 142 23.84 1 4 1 Kebun Rantau Prapat 1.85 Perlu peremajaan
38 2008 7 136 23.04 1 4 1 Kebun Rantau Prapat 1.85 Perlu peremajaan
39 2009 6 142 4.32 1 4 1 Kebun Rantau Prapat 1.85 Perlu peremajaan
40 2007 8 141 21.79 1 4 1 Kebun Aek Torop 1.85 Perlu peremajaan
41 2006 9 142 22.71 1 4 1 Kebun Aek Torop 1.85 Perlu peremajaan
42 2009 6 143 4.60 1 4 1 Kebun Tor Gamba 1.85 Perlu peremajaan
43 2007 8 142 19.66 1 4 1 Kebun Tor Gamba 1.85 Perlu peremajaan
41
Tabel 4.2. Output Pengurutan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit (Lanjutan)
No Tahun Tanam
Usia (Tahun)
Jumlah Pohon per Ha
Jumlah Produksi Ton/Ha
Konversi Tahun Tanam
Konversi Pohon per Ha
Konversi Produksi
Nama Kebun Bobot
45 2009 6 138 2.52 1 4 1 Kebun Sarang Giting 1.85 Perlu peremajaan
46 2006 9 141 23.58 1 4 1 Kebun Bukit Tujuh 1.85 Perlu peremajaan
47 2007 8 118 16.55 1 4 1 Kebun Distrik Serdang - I 1.85 Perlu peremajaan
48 2008 7 132 15.21 1 4 1 Kebun Distrik Serdang - I 1.85 Perlu peremajaan
49 2009 6 131 2.04 1 4 1 Kebun Distrik Serdang - I 1.85 Perlu peremajaan
50 2006 9 132 24.46 1 4 1 Kebun Ambalutu 1.85 Perlu peremajaan
51 2006 9 138 19.57 1 4 1 Kebun Rambutan 1.85 Perlu peremajaan
52 2008 7 133 15.27 1 4 1 Kebun Sei Meranti 1.85 Perlu peremajaan
Tabel 4.2. Output Pengurutan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit (Lanjutan)
No Tahun Tanam
Usia (Tahun)
Jumlah Pohon per Ha
Jumlah Produksi Ton/Ha
Konversi Tahun Tanam
Konversi Pohon per Ha
Konversi Produksi
Nama Kebun Bobot
54 2006 9 143 23.55 1 4 1 Kebun Sei Meranti 1.85 Perlu peremajaan
55 2009 6 143 4.44 1 4 1 Kebun Sei Meranti 1.85 Perlu peremajaan
56 2006 9 143 23.74 1 4 1 Kebun Sei Daun 1.85 Perlu peremajaan
57 2009 6 143 3.31 1 4 1 Kebun Sei Daun 1.85 Perlu peremajaan
58 2008 7 143 14.47 1 4 1 Kebun Sei Daun 1.85 Perlu peremajaan
59 2007 8 143 20.01 1 4 1 Kebun Sei Daun 1.85 Perlu peremajaan
60 2007 8 140 21.32 1 4 1 Kebun Bandar Selamat 1.85 Perlu peremajaan
61 2008 7 141 14.50 1 4 1 Kebun Ambalutu 1.85 Perlu peremajaan
62 2008 7 132 15.21 1 4 1 Kebun Silau Dunia 1.85 Perlu peremajaan
43
Tabel 4.2. Output Pengurutan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit (Lanjutan)
No Tahun
1.85 Perlu peremajaan
66 2008 7 143 17.21 1 4 1 Kebun Aek Nabara
Selatan
1.85 Perlu peremajaan
67 2007 8 142 20.37 1 4 1 Kebun ANS 1.85 Perlu peremajaan
68 2007 8 142 20.64 1 4 1 Kebun Sei Kebara 1.85 Perlu peremajaan
69 2006 9 141 23.41 1 4 1 Kebun Sei Kebara 1.85 Perlu peremajaan
70 2006 9 143 23.31 1 4 1 Kebun Distrik
Labuhan Batu I
1.85 Perlu peremajaan
Tabel 4.2. Output Pengurutan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit (Lanjutan)
No Tahun Tanam
Usia (Tahun)
Jumlah Pohon per Ha
Jumlah Produksi Ton/Ha
Konversi Tahun Tanam
Konversi Pohon per Ha
Konversi Produksi
Nama Kebun Bobot
72 2007 8 143 19.57 1 4 1 Kebun Distrik Labuhan
Batu I
1.85 Perlu peremajaan
73 2009 6 143 4.34 1 4 1 Distrik L Batu I 1.85 Perlu peremajaan
74 2008 7 142 14.60 1 4 1 Kebun Sei Baruhur 1.85 Perlu peremajaan
75 2006 9 136 22.21 1 4 1 Kebun Pulau Mandi 1.85 Perlu peremajaan
76 2007 8 143 23.50 1 4 1 Kebun Sei Baruhur 1.85 Perlu peremajaan
77 2006 9 143 23.78 1 4 1 Sei Baruhur 1.85 Perlu peremajaan
78 2008 7 140 14.74 1 4 1 Distrik LBatu I 1.85 Perlu peremajaan
45
Tabel 4.2. Output Pengurutan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit (Lanjutan)
No Tahun
2.21 Perlu peremajaan
85 2001 14 92 18.96 2 3 1 Dusun Hulu 2.21 Perlu peremajaan
86 2005 10 131 18.81 2 4 1 Kebun Rambutan 2.49 Perlu peremajaan
87 2003 12 140 23.60 2 4 1 Kebun Distrik
Labuhan Batu III
2.49 Perlu peremajaan
Tabel 4.2. Output Pengurutan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit (Lanjutan)
No Tahun Tanam
Usia (Tahun)
Jumlah Pohon per Ha
Jumlah Produksi Ton/Ha
Konversi Tahun Tanam
Konversi Pohon per Ha
Konversi Produksi
Nama Kebun Bobot
89 2005 10 140 24.18 2 4 1 Distrik L Batu III 2.49 Perlu peremajaan
90 2002 13 114 23.46 2 4 1 Distrik L Batu III 2.49 Perlu peremajaan
91 2001 14 138 24.10 2 4 1 Distrik L Batu III 2.49 Perlu peremajaan
92 2002 13 120 23.38 2 4 1 Kebun Tanah Raja 2.49 Perlu peremajaan
93 2004 11 125 22.46 2 4 1 Kebun Ambalutu 2.49 Perlu peremajaan
94 2003 12 105 20.27 2 4 1 Kebun Ambalutu 2.49 Perlu peremajaan
95 2004 11 131 21.79 2 4 1 Kebun Rambutan 2.49 Perlu peremajaan
96 2005 10 129 19.98 2 4 1 Kebun Ambalutu 2.49 Perlu peremajaan
97 2004 11 147 24.33 2 4 1 Kebun Sei Dadap 2.49 Perlu peremajaan
47
Tabel 4.2. Output Pengurutan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit (Lanjutan)
No Tahun Tanam
Usia (Tahun)
Jumlah Pohon per Ha
Jumlah Produksi Ton/Ha
Konversi Tahun Tanam
Konversi Pohon per Ha
Konversi Produksi
Nama Kebun Bobot
99 2004 11 136 28.55 2 4 1 Kebun Sei Meranti 2.49 Perlu peremajaan
100 2003 12 129 21.18 2 4 1 Kebun Pulau Mandi 2.49 Perlu peremajaan
101 2003 12 121 23.22 2 4 1 Kebun Sei Dadap 2.49 Perlu peremajaan
102 2002 13 123 24.25 2 4 1 Kebun Sei Dadap 2.49 Perlu peremajaan
103 2002 13 115 22.27 2 4 1 Kebun Pulau Mandi 2.49 Perlu peremajaan
104 2001 14 123 23.61 2 4 1 Kebun Sei Dadap 2.49 Perlu peremajaan
105 2004 11 138 23.25 2 4 1 Kebun Pulau Mandi 2.49 Perlu peremajaan
106 2005 10 138 20.64 2 4 1 Kebun Pulau Mandi 2.49 Perlu peremajaan
Tabel 4.2. Output Pengurutan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit (Lanjutan)
2.49 Perlu peremajaan
109 2001 14 117 23.51 2 4 1 Kebun Gunung
Monaco
2.49 Perlu peremajaan
110 2002 13 135 27.35 2 4 1 Kebun Gunung
Monaco
2.49 Perlu peremajaan
111 2002 13 125 19.96 2 4 1 Gunung Pamela 2.49 Perlu peremajaan
112 2001 14 126 24.24 2 4 1 Gunung Pamela 2.49 Perlu peremajaan
113 2003 12 127 21.49 2 4 1 Kebun Distrik
Simalungun
2.49 Perlu peremajaan
114 2004 11 127 22.45 2 4 1 Kebun Distrik
Simalungun
2.49 Perlu peremajaan
49
Tabel 4.2. Output Pengurutan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit (Lanjutan)
No Tahun
2.49 Perlu peremajaan
117 2001 14 121 21.02 2 4 1 Kebun Silau Dunia 2.49 Perlu peremajaan
118 2003 12 132 23.14 2 4 1 Kebun Distrik
Serdang - I
2.49 Perlu peremajaan
119 2004 11 122 22.28 2 4 1 Kebun Tanah Raja 2.49 Perlu peremajaan
120 2003 12 122 23.99 2 4 1 Kebun Tanah Raja 2.49 Perlu peremajaan
121 2002 13 125 22.87 2 4 1 Distrik Serdang - I 2.49 Perlu peremajaan
122 2001 14 122 23.10 2 4 1 Kebun Distrik
Serdang - I
2.49 Perlu peremajaan
Tabel 4.2. Output Pengurutan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit (Lanjutan)
No Tahun Tanam
Usia (Tahun)
Jumlah Pohon per Ha
Jumlah Produksi Ton/Ha
Konversi Tahun Tanam
Konversi Pohon per Ha
Konversi Produksi
Nama Kebun Bobot
124 2003 12 127 20.52 2 4 1 Kebun Silau Dunia 2.49 Perlu peremajaan
125 2003 12 141 24.03 2 4 1 Kebun Gunung Para 2.49 Perlu peremajaan
126 2002 13 121 21.52 2 4 1 Kebun Distrik
Simalungun
2.49 Perlu peremajaan
127 2005 10 142 21.94 2 4 1 Kebun Bangun 2.49 Perlu peremajaan
128 2004 11 123 21.32 2 4 1 Kebun Huta Padang 2.49 Perlu peremajaan
129 2005 10 130 20.13 2 4 1 Kebun Huta Padang 2.49 Perlu peremajaan
130 2001 14 137 26.36 2 4 1 Bandar Selamat 2.49 Perlu peremajaan
131 2003 12 128 23.61 2 4 1 Kebun Huta Padang 2.49 Perlu peremajaan
51
Tabel 4.2. Output Pengurutan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit (Lanjutan)
No Tahun Tanam
Usia (Tahun)
Jumlah Pohon per Ha
Jumlah Produksi Ton/Ha
Konversi Tahun Tanam
Konversi Pohon per Ha
Konversi Produksi
Nama Kebun Bobot
133 2004 11 128 17.71 2 4 1 Kebun Sei Silau 2.49 Perlu peremajaan
134 2005 10 132 14.75 2 4 1 Kebun Sei Silau 2.49 Perlu peremajaan
135 2001 14 106 21.75 2 4 1 Kebun Huta Padang 2.49 Perlu peremajaan
136 2002 13 136 27.56 2 4 1 Bandar Selamat 2.49 Perlu peremajaan
137 2003 12 137 24.93 2 4 1 Bandar Selamat 2.49 Perlu peremajaan
138 2001 14 103 17.04 2 4 1 Kebun Bangun 2.49 Perlu peremajaan
139 2002 13 139 23.50 2 4 1 Kebun Bangun 2.49 Perlu peremajaan
140 2003 12 138 22.34 2 4 1 Kebun Bangun 2.49 Perlu peremajaan
141 2004 11 128 22.45 2 4 1 Dusun Hulu 2.49 Perlu peremajaan
Tabel 4.2. Output Pengurutan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit (Lanjutan)
2.49 Perlu peremajaan
144 2005 10 134 22.38 2 4 1 Kebun Tanah Raja 2.49 Perlu peremajaan
2.49 Perlu peremajaan
149 2004 11 104 16.13 2 4 1 Kebun Hapesong 2.49 Perlu peremajaan
150 2004 11 143 25.55 2 4 1 Kebun ANS 2.49 Perlu peremajaan
53
Tabel 4.2. Output Pengurutan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit (Lanjutan)
No Tahun
2.49 Perlu peremajaan
153 2001 14 140 21.80 2 4 1 Kebun Aek Nabar
Utara
2.49 Perlu peremajaan
154 2002 13 141 22.68 2 4 1 Kebun Aek Nabar
Utara
2.49 Perlu peremajaan
155 2005 10 140 25.55 2 4 1 Kebun Aek
Nabara Selatan
2.49 Perlu peremajaan
156 2004 11 142 26.88 2 4 1 Kebun Sei
Baruhur
2.49 Perlu peremajaan
157 2003 12 137 25.66 2 4 1 Labuhan Haji 2.49 Perlu peremajaan
158 2004 11 139 26.62 2 4 1 Labuhan Haji 2.49 Perlu peremajaan
Tabel 4.2. Output Pengurutan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit (Lanjutan)
2.49 Perlu peremajaan
161 2003 12 122 23.45 2 4 1 Kebun Distrik
Labuhan Batu I
2.49 Perlu peremajaan
162 2005 10 141 24.96 2 4 1 Kebun Distrik
Labuhan Batu I
2.49 Perlu peremajaan
163 2004 11 136 28.55 2 4 1 Distrik L Batu I 2.49 Perlu peremajaan
164 2001 14 132 23.63 2 4 1 Kebun Batang
Toru
2.49 Perlu peremajaan
165 2002 13 133 25.64 2 4 1 Kebun Batang
Toru
2.49 Perlu peremajaan
166 2005 10 123 17.32 2 4 1 Kebun Aek Raso 2.49 Perlu peremajaan
55
Tabel 4.2. Output Pengurutan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit (Lanjutan)
No Tahun
Labuhan Batu II
2.49 Perlu peremajaan
169 2002 13 133 25.64 2 4 1 Kebun Distrik
Tapanuli Selatan
2.49 Perlu peremajaan
Tabel 4.2. Output Pengurutan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit (Lanjutan)
No Tahun Tanam
Usia (Tahun)
Jumlah Pohon per Ha
Jumlah Produksi Ton/Ha
Konversi Tahun Tanam
Konversi Pohon per Ha
Konversi Produksi
Nama Kebun Bobot
177 2004 11 140 23.23 2 4 1 Kebun Sei Sumut 2.49 Perlu peremajaan
178 2003 12 139 23.90 2 4 1 Kebun Sei Sumut 2.49 Perlu peremajaan
179 2001 14 139 24.50 2 4 1 Kebun Sei Sumut 2.49 Perlu peremajaan
180 2002 13 134 23.41 2 4 1 Kebun Sei Sumut 2.49 Perlu peremajaan
181 2005 10 141 26.17 2 4 1 Kebun Bukit Tujuh 2.49 Perlu peremajaan
182 2005 10 141 20.50 2 4 1 Kebun ANU 2.49 Perlu peremajaan
183 2002 13 108 19.73 2 4 1 Distrik Serdang - II 2.49 Perlu peremajaan
184 2003 12 124 23.44 2 4 1 Distrik Serdang - II 2.49 Perlu peremajaan
185 2004 11 129 21.87 2 4 1 Distrik Serdang - II 2.49 Perlu peremajaan
57
Tabel 4.2. Output Pengurutan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit (Lanjutan)
No Tahun
2.49 Perlu peremajaan
188 2002 13 138 22.86 2 4 1 Kebun Membang
Muda
2.49 Perlu peremajaan
189 2003 12 122 23.45 2 4 1 Kebun Tor Gamba 2.49 Perlu peremajaan
190 2003 12 138 29.04 2 4 1 Kebun Merbau
Selatan
2.49 Perlu peremajaan
191 2004 11 137 26.15 2 4 1 Kebun Membang
Muda
2.49 Perlu peremajaan
192 2003 12 145 24.35 2 4 1 Kebun Membang
Muda
2.49 Perlu peremajaan
193 2001 14 126 20.15 2 4 1 Rantau Prapat 2.49 Perlu peremajaan