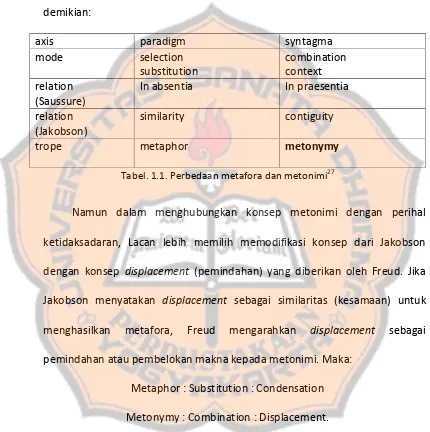ABSTRAK
Gaya hidup hijau diperkenalkan sebagai gaya hidup alternatif untuk menyelesaikan persoalan lingkungan hidup. Wacana lingkungan hidup arus utama menyatakan bahwa kehadiran manusia dengan segala tindakan konsumsinya menyebabkan krisis lingkungan hidup yang meliputi kenaikan suhu secara global, kelangkaan energi dan air tawar,deforestasi, perubahan iklim yang kemudian mempengaruhi kelangkaan pangan, kerusakaan ekosistem dan kepunahan spesies tertentu, yang kemudian saling tumpang tindih dengan persoalan kemiskinan serta persoalan sosial lainnya. Karena itu gaya hidup hijau dipandang sebagai harapan akan keterlibatan setiap orang untuk memperbaiki segala kerusakan alam dan kerusakan sosial.
Tesis ini berusaha untuk membaca bagaimana gaya hidup hijau dipraktikkan di Indonesia, khususnya di Provinsi DI. Yogyakarta, dan melihat apa yang dihasilkan oleh praktik budaya demikian. Penelitian dilakukan dengan metode etnografi baru yang mencoba menarasikan pengalaman hidup subjek hijau dengan lebih dekat. Sementara teori yang dipakai adalah teori psikoanalisa Lacanian, khususnya teori fetis yang dielaborasikan dengan teori metonimi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya hidup hijau membuat subjek menjadi fetis terhadap objek hijau, melebih-lebihkan kemampuan objek-objek yang dianggap hijau dan membuat subjek harus bergerak secara metonimi dari objek yang satu ke objek yang lain. Gaya hidup hijau ternyata belum berhasil menjadi alternatif jalan hidup untuk membawa subjek keluar dari lingkaran masyarakat konsumsi. Gaya hidup hijau justru menjadi alat subjek mempertahankanpleasure atau kesenangan berkonsumsi, dan menghindari penderitaan kastrasi dari Hukum Sang Ayah.
ABSTRACT
The Green Living concept was introduced as an alternative way of living that may put an end to environmental issues. The main discourse states that human beings with their act of consuming is causing this environmental crisis, i.e. a rise in the global climate, clean water and energy scarcity, deforestation, climate change which causes food deficiency, damaged ecosystem, and the extinction of certain species, which then overlaps with other social problems like poverty. Green Living is said to be the best solution to overcome social and natural damages.
This thesis is to observe how green living is implemented in Indonesia, particularly in the Special District of Yogyakarta, and to see what outcome it could bring. This research is conducted using the new ethnographical method which tries to narrate the live experiences of the green subjects in a much closer point of view. Thus, the theory used in this research is the Lacanian Psychoanalysis theory, especially the theory of fetishism, which is then elaborated into the metonymic theory.
The result of this research suggest that green living makes subject to have a certain fetish towards green objects, exaggerate the potentiality of presumed green objects, and make subjects move metonymically from one object to another. Green living has not yet succeeded in becoming an alternate way of life for the subjects to escape the trap of consumerism. This way of living turns out to be a tool to maintain the pleasure of consumption, and to avoid the castration suffering from the Name of the Father.
FETISISASI GAYA HIDUP HIJAU DALAM MASYARAKAT KAPITALIS
TESIS
Untuk Memenuhi Persyaratan Mendapat Gelar Magister Humaniora (M.Hum.) di
Program Magister Ilmu Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
Oleh:
Nur Ani Br Tanggang NIM: 126322002
PROGRAM MAGISTER ILMU RELIGI DAN BUDAYA UNIVERSITAS SANATA DHARMA
HALAMAN JUDUL
FETISISASI GAYA HIDUP HIJAU DALAM MASYARAKAT KAPITALIS
TESISUntuk Memenuhi Persyaratan Mendapat Gelar Magister Humaniora (M.Hum.) di Program Magister Ilmu Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
Oleh:
Nur Ani Br Tanggang NIM: 126322002
PROGRAM MAGISTER ILMU RELIGI DAN BUDAYA UNIVERSITAS SANATA DHARMA
KATA PENGANTAR
Tesis ini dimulai dari pertanyaan tentang keseharian, sesuatu yang sederhana saya kira. Namun akhir dari tesis ini sejujurnya jauh lebih berat dari yang saya perkirakan. Meski begitu bukan berarti saya sudah mendapatkan kepuasan karena sudah menemukan jawaban atas pertanyaan itu. Masih ada keresahan karena ada pertanyaan demi pertanyaan yang muncul dan belum bisa dijawab, bahkan ada berbagai keraguan yang selalu mengejar. Ditambah lagi rasa tidak puas karena seharusnya tesis ini bisa dibuat dengan lebih baik lagi. Satu hal yang pasti, tesis ini menjadi cukup personal bagi saya. Saya bergerak seiring dirinya. Dari yang dulu saya kira saya tahu sesuatu hingga kini saat saya tahu terlalu banyak hal yang saya tidak tahu. Tesis ini memang tidak dikerjakan dengan cara
yang cukup akademis. Terlalu semau-gue. Karena itu ia dipenuhi kelemahan di
sana-sini. Namun ia sungguh membantu saya untuk menjadi pijakan melanjutkan pencarian atas kegelisahan yang belum terhenti.
Karena itu saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua orang yang mengiringi saya berjalan menyelesaikan tesis ini. Terimakasih kepada Bapak St Sunardi yang telah (saya paksa) menjadi dosen pembimbing yang sangat membantu saya menemukan arah dan posisi tesis ini. Terimakasih kepada Romo Dr. Gregorius Subanar S.J., yang begitu sabar mendorong dan memberikan motivasi, Prof. Dr. A. Supratiknya, Romo Dr. Benny Hari Juliawan S.J., Romo Dr. Baskara T. Wardhaya S.J., Romo Dr. A. Bagus Laksana S.J., dan Dr Katrin Bandel. Terimakasih juga kepada Mbak Desy yang telah bersedia direpotkan dan sangat membantu mengingatkan banyak hal, terutama mendorong untuk cepat lulus, juga buat Pak Mul.
kepada semua teman-teman IRB angkatan 2012 (Tian, Dwi, Bang Ucup, Saman, Udung, Mas Felix, Mbak Lany, Mas Rudy, Mas Totok, Miko, Bung Rendra, Pak Willy, Ajeng, serta Bung Krisna). Demikian juga teman-teman lintas angkatan (Mbak Vita, Mbak Luc, Vina, Felo), terutama Mas Zuhdi dan Uda Inyiak yang telah memberi masukan, khususnya tentang teori Lacan.Terima kasih juga untuk teman-teman di Perkantas, yang khawatir namun percaya kepada saya selama menempuh kuliah.
Dan yang terutama saya berterimakasih kepada Bapak dan Mamak yang selalu mendukung dan mendoakan, meski kerap kali pilihan-pilihanku merepotkan kehidupan sosial kalian. Begitu juga dengan adik-adik, empat adik ipar dan lima ponakan yang hadir ketika saya masih sibuk berkutat dengan buku.
ABSTRAK
Gaya hidup hijau diperkenalkan sebagai gaya hidup alternatif untuk menyelesaikan persoalan lingkungan hidup. Wacana lingkungan hidup arus utama menyatakan bahwa kehadiran manusia dengan segala tindakan konsumsinya menyebabkan krisis lingkungan hidup yang meliputi kenaikan suhu
secara global, kelangkaan energi dan air tawar,deforestasi, perubahan iklim yang
kemudian mempengaruhi kelangkaan pangan, kerusakaan ekosistem dan kepunahan spesies tertentu, yang kemudian saling tumpang tindih dengan persoalan kemiskinan serta persoalan sosial lainnya. Karena itu gaya hidup hijau dipandang sebagai harapan akan keterlibatan setiap orang untuk memperbaiki segala kerusakan alam dan kerusakan sosial.
Tesis ini berusaha untuk membaca bagaimana gaya hidup hijau dipraktikkan di Indonesia, khususnya di Provinsi DI. Yogyakarta, dan melihat apa yang dihasilkan oleh praktik budaya demikian. Penelitian dilakukan dengan metode etnografi baru yang mencoba menarasikan pengalaman hidup subjek hijau dengan lebih dekat. Sementara teori yang dipakai adalah teori psikoanalisa Lacanian, khususnya teori fetis yang dielaborasikan dengan teori metonimi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya hidup hijau membuat subjek menjadi fetis terhadap objek hijau, melebih-lebihkan kemampuan objek-objek yang dianggap hijau dan membuat subjek harus bergerak secara metonimi dari objek yang satu ke objek yang lain. Gaya hidup hijau ternyata belum berhasil menjadi alternatif jalan hidup untuk membawa subjek keluar dari lingkaran masyarakat
konsumsi. Gaya hidup hijau justru menjadi alat subjek mempertahankanpleasure
atau kesenangan berkonsumsi, dan menghindari penderitaan kastrasi dari Hukum Sang Ayah.
ABSTRACT
The Green Living concept was introduced as an alternative way of living that may put an end to environmental issues. The main discourse states that human beings with their act of consuming is causing this environmental crisis, i.e. a rise in the global climate, clean water and energy scarcity, deforestation, climate change which causes food deficiency, damaged ecosystem, and the extinction of certain species, which then overlaps with other social problems like poverty. Green Living is said to be the best solution to overcome social and natural damages.
This thesis is to observe how green living is implemented in Indonesia, particularly in the Special District of Yogyakarta, and to see what outcome it could bring. This research is conducted using the new ethnographical method which tries to narrate the live experiences of the green subjects in a much closer point of view. Thus, the theory used in this research is the Lacanian Psychoanalysis theory, especially the theory of fetishism, which is then elaborated into the metonymic theory.
The result of this research suggest that green living makes subject to have a certain fetish towards green objects, exaggerate the potentiality of presumed green objects, and make subjects move metonymically from one object to another. Green living has not yet succeeded in becoming an alternate way of life for the subjects to escape the trap of consumerism. This way of living turns out to be a tool to maintain the pleasure of consumption, and to avoid the castration suffering from the Name of the Father.
DAFTAR ISI
Halaman Judul... i
Persetujuan... ii
Pengesahan... iii
Pernyataan Keaslian... iv
Pernyataan Publikasi Karya Ilmiah Untuk Kepentingan Akademis... v
Kata Pengantar... vi
BAB II: ANTROPOSENTRISME DALAM WACANA LINGKUNGAN HIDUP... 42
A. Manusia Sebagai Persoalan... 46
1.Terlalu Banyak Manusia ... 46
2. Terlalu Banyak Konsumsi ... 53
B. Hijau Sebagai Jalan Selamat ... 63
1. Gaya Hidup Hijau ... 63
BAB III: Menata Hidup, Mengatur Konsumsi... 79
A. Individualisasi ... 80
1. Mulai Dari Diri Sendiri ... 81
2. Kesadaran Diri ... 86
B. Menjadi Konsumen Hijau ... 90
1. Homestead ... 91
C. Liyan Yang Tak Hijau ... 149
1. Keluhan Kepada Liyan ... 149
2. Adakah Hal Baru ... 161
a. Warga Berdaya ... 162
b. Warga “Hijau” ... 168
BAB IV: Fetisisasi Gaya Hidup Hijau... 175
A. Dilema Politik Konsumsi ... 176
1. Berkonsumsi Sebagai Berpolitik ... 177
2. Gaya Hidup Yang Mahal ... 179
B. Hijau Sebagai Fetis ... 185
2. Fetis Sebagai Bahasa Metonimi ... 189
3. Fetis Sebagai Bahasa Hasrat ... 203
BAB V: PENUTUP... 210
DAFTAR PUSTAKA... 214
DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1.1. : Kampanye Hemat Air ... 4
Gambar 1.2. : Sumbu Aphasia ... 35
Gambar 1.3. : Formula Metonimi ... 36
Gambar 2.1. : Kampanye #BeliYangBaik ... 43
Gambar 2.2. : Kampanye Kementrian Lingkungan Hidup ... 49
Gambar 2.3. : Kampanye UNEP ... 58
Gambar 4.1 : Kayu bekas di rumah ramah lingkungan ... 189
Gambar 4.2 : Pakaian dan Tas dari bahan bekas ... 190
Gambar 4.3. : Rumah yang lokal ... 193
Gambar 4.4. : Makanan organik yang lokal dan sehat ... 195
Gambar 4.5. : Rumah yang sederhana dan hijau ... 197
BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Gerakan lingkungan hidup modern dimulai sejak Pasca Perang Dunia Kedua, di
berbagai negara, dan menurut situasi masing-masing secara teritorial. Jadi
meski ada kesamaan pada isu tertentu, seringkali ideologi dan karakter
gerakan berbeda-beda. Misalnya latar belakang serta model “gerakan
lingkungan” di Jerman dengan “gerakan lingkungan” di Jepang ataupun India,
masing-masing berdiri dengan perbedaan yang cukup besar.
Partai Hijau di Jerman membangun gerakannya berdasarkan ideologi kiri
yang mencari pelabuhan perjuangan setelah kehilangan partai komunis1.
Sementara “gerakan lingkungan” di Jepang dimulai dengan persoalan
kesehatan masyarakat lokal pada masa-masa negara ini mengalami
industrialisasi. Dan “gerakan lingkungan” di India justru membangunnya
melalui semangat primordial, yakni spiritualitas kepada Bumi sebagai Sang Ibu
pemberi kehidupan.2Perjuangan yang bersifat lokal atauCitizens’ Movements
atauCitizens’ Initiativeadalah ciri utamanya.3
1 Yannis Stavrakaskis (2000), “On the emergence of Green ideology: the dislocation factor in
Green politics”, dalam David Howarth, Aletta J. Norval dan Yannis Stavrakakis (Ed.), Discourse Theory and Political Analysis,Manchester: Manchester University Press.
Globalisasi menciptakan semacam “kebutuhan” untuk menyatukan
gerakan-gerakan ini. Apa yang berserak, berwarna, beragam dan terbuka
dipaksa masuk ke dalam sebuah kata yang universal sekaligus membatasi,
yaitu gerakan lingkungan hidup. Jadilah Hari Bumi atau Earth Day dimulai
sejak 22 April 1970 di Amerika Serikat sebagai titik penentu. Sejak kelahiran
Hari Bumi, gerakan lingkungan hidup didominasi oleh wacana lingkungan
hidup arus utama yang kira-kira berisi demikian: manusia adalah penyebab
masalah lingkungan hidup, ledakan penduduk membuat begitu banyak barang
konsumsi harus diproduksi dan menghasilkan berlimpahnya racun, sampah
hingga pemanasan global.
Hari Bumi yang pertama ini menjadi pertanda khusus bagaimana jika
sebuah pengetahuan tertentu memberikan interupsi atas sebuah kehidupan
yang semula “normal”. Ia datang memberikan pengetahuan yang traumatik,
dan menimbulkan kepanikan dan rasa takut yang minta segera diatasi. Dan
karena persoalan ini dikaitkan dengan masalah konsumsi maka ia pun
tumpang-tindih dengan isu kesehatan dan kritik alienasi konsumsi akibat
kapitalisme yang menghasilkan konsumsi massal. Meskipun kita tetap bisa
menemukan “produk samping” berupa gerakan anti kapitalisme yang
memakai penanda gerakan lingkungan sebagai senjata untuk mengkritik
kapitalisme sebagai penyebab krisis lingkungan secara global, yang umumnya
Yang menarik adalah wacana lingkungan hidup arus utama tidak hanya
membawa wacana tentang krisis, tapi juga membawa teknik atau tata-cara
praktis penyelesaiannya. Pengetahuan yang traumatik menyiapkan
penerimanya kepada pengetahuan yang berikutnya. Ia adalah shock therapy
yang mempersiapkan massa untuk masuk kepada sesuatu yang diterima
dengan harapan besar agar terhindar dari chaosyang digadang-gadang sudah
menanti.4
Jika penyebab masalah adalah manusia dan konsumsi maka tentu teknik
penyelesaian yang ditawarkan adalah hal yang sama pula. Solusinya adalah
bahwa setiap orang mampu mengatur pola konsumsinya. Mengubah
kebiasaan yang lama dan masuk kepada kebiasaan yang baru, yakni pola
konsumsi yang diatur menurut aturan yang dikenal sebagai gaya hidup hijau
(green life style). Sebagaimana nasib berbagai gerakan sosial yang ujug-ujug
didepolitisasi sebagai gaya hidup (life style), gerakan lingkungan hidup juga
bernasib serupa.
Seperti yang dinyatakan sebelumnya gaya hidup hijau selalu
diperkenalkan kemudian setelah krisis terlebih dahulu dibicarakan. Misalnya
ide gaya hidup hijau dalam pemakaian air tawar. Wacana dimulai dengan
krisis tentang jumlah air tawar yang digambarkan terlalu sedikit untuk
dibandingkan dengan jumlah orang yang memakainya. Wacana ini
menyatakan bahwa hanya tersedia 1% air tawar (dari seluruh air) di bumi
untuk sekitar 7 milyar penduduk bumi. Jadi masalahnya diletakkan pada
persoalan jumlah, yakni jumlah air dan jumlah manusia.
Pembayangannya adalah meski dalam pemakaian yang adil untuk setiap
orang, jumlah air tawar di bumi akan berada pada krisis dan segera akan
menciptakan perang perebutan air. Maka sebagai pencegahannya diajaklah
umat manusia untuk mengatur pemakaian air di berbagai kesempatan. Salah
satu solusinya adalah berhemat memakai air untuk kebutuhan domestik dan
kegiatan-kegiatan lainnya.
Gb. 1.1. Kampanye Hemat Air
Kampanye senada juga dilakukan pada wacana krisis energi listrik.
Masalahnya disebutkan pada jumlah energi yang terlalu terbatas untuk umat
manusia yang terlalu banyak. Teknik penyelesaiannya adalah penghematan
pemakaiannya bagi setiap orang. Untuk kasus sampah plastik, kembali
menerapkan sistem plastik berbayar agar masyarakat “jera” memakai kantung
plastik dengan boros.
Masalah pemanasan global yang terlampau jelas disebabkan oleh
industri berbasis kapitalisme juga menawarkan jalan keluar melalui komitmen
perubahan gaya hidup konsumen. Salah satunya sebagaimana yang
dinyatakan oleh seorang akademisi sekaligus pakar lingkungan hidup di
Indonesia berikut: 1) menghemat pemakaian arus listrik dan bahan bakar
minyak (BBM), 2) mematikan lampu listrik yang tidak penting, 3) mematikan
komputer ketika tidak bekerja, 4) mematikan alat pendingin ketika tidak
berada di dalam ruangan, 5) mematikan televisi saat tidak menonton, 6)
menghindari penggunaan liftatau eskalator pada bangunan berlantai dua, 7)
memaksimalkan penggunaan transportasi umum dan kendaraan yang
berbahan bakar gas atau biodiesel, 8) memakai kendaraan bebas polusi
seperti sepeda dan becak, 9) menghindari pembakaran sampah, 10)
menerapkan konsep 3R (reduce atau mengurangi, reuse atau menggunakan
kembali, danrecycle atau mendaur ulang) dalam sistem pengelolaan sampah,
11) mendesain bangunan dengan sirkulasi udara dan pencahayaan alami, 12)
mengontrol emisi operasional perusahaan, 13) membeli produk lokal untuk
mengurangi transportasi barang-barang impor, 14) jika terpaksa beli produk
impor yang mempunyai recycle logo, 15) mengganti tas belanja dari bahan
plastik ke bahan kain atau bahan organik lainnya, 16) menggunakan kertas
diikuti penanaman kembali dan membuka lahan dengan cara tidak membakar,
18) menghentikan penebangan hutan secara liar, 19) membudayakan gemar
menanam pohon, dan 20) menggunakan tanaman hidup sebagai pagar.5
Secara umum demikianlah sebagian langkah praktis gaya hidup hijau
yang dibawa dan disebarluaskan oleh para aktivis maupun pendukung
gerakan lingkungan hidup arus utama.Tentu saja tidak ada yang baru dalam
daftar gaya hidup hijau yang disampaikan–kecuali bahwa ternyata bagi media
nasional hal itu cukup dan layak menjadi isi pidato pengukuhan seorang guru
besar bidang lingkungan hidup.
Gaya hidup hijau bicara soal penataan konsumsi. Mulai dari pra hingga
pasca, semuanya diatur dan ditata. Konsumsi apa yang dihindari, barang apa
yang harus dikonsumsi, bagaimana cara mengkonsumsi, dan apa yang harus
dilakukan terhadap sampah pasca konsumsi. Tapi beberapa bentuk gaya
hidup hijau yang direkomendasikan itu bukanlah pola hidup yang asing di
Indonesia, misalnya memakai transportasi becak atau sepeda ataupun
konsumsi panganan lokal. Namun rasa bangga yang tersirat dari cara aktivis
hidup hijau mengabarkannya seolah-olah mengatakan kehidupan demikian
adalah pola hidup baru, asing, alternatif dan tentu saja, dianggap lebih baik.
5 Langkah gaya hidup hijau ini diberitakan oleh sebuah media nasional sebagai bagian dari isi
Hal utama yang menyebabkannya adalah karena ia datang dari
negara-negara sejahtera yang telah melewati penderitaan kerusakan lingkungan
hidup pada masa-masa industrialisasi. Menurut Ibrahim (2011: 313-314) gaya
hidup hijau di Eropa adalah bagian dari sub-politics atau inisiatif warga yang
ditandai dengan kemunculan gerakan hidup sederhana dan gerakan
tanggung-jawab sosial. Termasuk gerakan yang menciptakan dan
menawarkan pola-pola konsumsi alternatif. Maka apa yang kira-kira terjadi
jika gaya hidup hijau yang demikian coba diterapkan begitu saja di Indonesia
tanpa memperdulikan situasi sosial, ekonomi serta budayanya?
Di Indonesia gaya hidup hijau belum menjadi peraturan yang ditetapkan
negara untuk harus dipatuhi oleh masyarakatnya, maka bagaimana pelaku
gaya hidup hijau di Yogyakarta melakukan pola hidup ini? Lebih jauh lagi,
hasrat seperti apa yang mendorong mereka melakukannya? Sebagian besar
karya penelitian menyebutkan bahwa gaya hidup hijau yang dibawa oleh
komunitas dan individu hijau di Indonesia merupakan bagian dari gerakan
sosial baru untuk menciptakan masyarakat alternatif di tengah penciptaan
masyarakat konsumsi saat ini. Tapi benarkah demikian? Hal inilah yang akan
B. Rumusan Masalah
a. Bagaimanakah praktik gaya hidup hijau yang diterapkan oleh partisipan?
b. Dengan pola gaya hidup hijau-nya, subjek seperti apakah yang dihasilkan?
c. Sebagai bagian dari masyarakat konsumsi, bagaimana subjek penelitian ini
menunjukkan hasrat masyarakat Indonesia saat ini?
C. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka
penelitian ini bertujuan untuk:
1. Memberi gambaran dan analisa tentang praktik gaya hidup hijau yang
diterapkan oleh masyarakat konsumsi Indonesia.
2. Memberi analisa tentang pembentukan subjek yang dihasilkan lewat
praktik gaya hidup hijau yang dilakukan.
3. Menganalisa hasrat masyarakat konsumtif Indonesia yang mendorong
mereka melakukan praktik gaya hidup hijau.
D. Manfaat Penelitian
Hasil dari penelitian nantinya diharapkan dapat bermanfaat pada:
1. Ilmu pengetahuan humaniora khususnya Kajian Budaya. Penelitian ini
diharapkan dapat memperkaya eksplorasi terhadap budaya kontemporer
dengan menggunakan pendekatan penelitian dengan perspektif Kajian
2. Masyarakat dapat melihat bahwa gaya hidup hijau pada masyarakat
kontemporer lahir dan mewujud tidak semata-mata karena sebuah
persoalan lingkungan yang terberi dan mampu dijelaskan dengan
objektivitas. Dengan demikian membantu masyarakat untuk melihat secara
kritis dan menganalisanya demi kepentingan publik. Secara khusus
penelitian ini mencoba memberi suara lain di tengah dukungan kuat
terhadap gaya hidup hijau yang dinyatakan oleh para akademisi dan aktivis
lingkungan hidup di Indonesia pada umumnya.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi peneliti lain yang
ingin mengangkat topik serupa terutama untuk mengeksplorasi hal-hal
yang tidak mampu diakomodasi oleh penelitian ini.
E. Tinjauan Pustaka
Slavoj Žižek menulis sebuah artikel berjudul “Fat-Free Chocolate and
Absolutely No Smoking: Why Our Guilt About Consumption is All-Consuming”
yang membahas pandangannya tentang fenomena konsumsi makanan sehat
dan ramah lingkungan. Menurut Žižek, mengkonsumsi makanan organik,
mendiami rumah ramah lingkungan di pedesaan dan memiliki barang-barang
berlabel ekologi kini menjadi sebuah brand atau merk kultural yang amat
cocok dengan jenis kapitalisme baru, yaitu kapitalisme kultural (cultural
Kapitalisme kultural merupakan kapitalisme tahap ketiga yang
mengutamakan konsumsi pengalaman (the commodification of experiences)
atau otentisitas konsumsi. Dimana seseorang menjadi konsumen untuk
mendapatkan sebuah pengalaman yang bersifat langsung, supaya ketika
mengkonsumsinya didapatkan kenikmatan akan pengalaman hidup yang
bermakna.
Žižek menulis artikel ini dengan menggunakan perspektif Psikoanalisa
Lacanian dan ekonom Jeremy Rifkin yang memperkenalkan istilah cultural
capitalism. Dengan menggunakan dua pandangan ini, Žižek membagi jenis
masyarakat konsumsi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah konsumen
yang “jouisseur propre” atau masyarakat yang siap untuk mengkonsumsi
secara berlebihan demi mewujudkan kediriannya dalam kenikmatan
(enjoyment). Yang kedua adalah jenis masyarakat yang “enlightened
hedonist” atau kaum hedonis yang telah tercerahkan yang mampu
mengkalkulasi kenikmatan dalam berkonsumsi. Tujuannya adalah
memperpanjang kenikmatan konsumsi tanpa harus disusahkan dengan
bayang-bayang resiko berkonsumsi, yakni memburuknya kesehatan dan
kerusakan lingkungan hidup.
Žižek mengatakan bahwa kapitalisme kultural yang ditunjukkan oleh
berbagai pola berkonsumsi saat ini merupakan jalan buntu masyarakat
konsumsi. Ketika kesalahan konsumsi coba dipulihkan oleh tindakan
ujung-ujungnya dijawab dengan konsumsi lagi. Kritik terhadap kapitalisme dijawab
dengan kapitalisme berikutnya. Kapitalisme dikritik karena membuat
masyarakat mengalami alienasi dengan dirinya sendiri lewat konsumsi yang
bersifat massal. Kemudian kritik ini diatasi dengan menghadirkan pengalaman
otentik melalui kapitalisme kultural yang mengkomodifikasi pengalaman.
Žižek memberikan contoh konsumsi coffee karma yang ditawarkan
Starbucks. Dengan membeli kopi di Starbucks kita telah ikut dalam rencana
Fair Trade yang mensejahterakan para petani kopi dan ikut pula memelihara
lingkungan hidup. Karena itu dianggap wajar jika harganya menjadi mahal
karena setiap tegukan kopi kini menjadi pengalaman yang bermakna besar
bagi hidupnya dan bagi dunia. Artikel inilah yang mendasari penelitian ini,
dengan mencoba melihat cara berkonsumsi pengalaman ekologis masyarakat
Indonesia di Yogyakarta.
Soal konsumsi hijau sudah cukup banyak diteliti di Indonesia, khususnya
dalam sudut pandang penelitian kuantitatif ekonomi manajemen.
Penelitian-penelitian ini umumnya membahas tingkat kepuasan dan faktor-faktor yang
mempengaruhi konsumen membeli barang-barang berlabel hijau. Hampir
semua penelitian ini hanya berakhir pada perhitungan kuantitatif yang sangat
terbatas dalam menafsirkan situasi masyarakat kontemporer di Indonesia.
Selain itu pada umumnya penelitian-penelitian yang ada berfokus pada studi
kasus saja. Apakah meneliti satu pola hidup hijau saja, atau konsumsi satu
Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Budi Suharjo, Muchlis Achmady
dan Mohammad Reza Ahmady (2013) yang disampaikan dalamProceedings of
8th Asian Business Research Conference 1 - 2 April 2013, Bangkok, Thailand,
dengan judul “Indonesian Consumer’s Attitudes Towards Organic Products”.
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk melihat faktor-faktor
apa saja yang mempengaruhi masyarakat Indonesia membeli atau tidak
membeli bahan makanan organik. Penelitian ini dilakukan di Jakarta dan Jawa
Barat dan melibatkan 200 orang responden.
Hasilnya ternyata hanya 13% yang secara rutin mengkonsumsi makanan
organik meski secara keseluruhan para responden mengaku mengetahui
keunggulan serta manfaat makanan organik untuk kesehatan dan ekologi.
Para partisipan yang tidak mengkonsumsi makanan organik secara rutin
memiliki beberapa alasan. Alasan yang paling utama adalah harga bahan
pangan organik yang sangat mahal. Selain itu bahan pangan ini hanya dijual di
tempat-tempat khusus dan tidak ditemukan di pasar tradisional yang
didatangi oleh masyarakat Indonesia pada umumnya.
Hasil penelitian ini mirip dengan temuan Tri Widodo dan Rina Sari
Qurniawati (2015) yang merupakan akademisi dari STIE AMA Salatiga.
Penelitian ini berjudul “Pengaruh Kolektivisme, Perceived Consumer
Effectiveness, Dan Kepedulian Lingkungan Terhadap Perilaku Pembelian
Ramah Lingkungan”, dan diterbitkan dalam Jurnal “Among Makarti” Vol. 8 No
dan kualitatif berupa survey kepada 40 orang partisipan dan in-depth
interviewkepada 10 orang responden yang dianggap dapat mewakili.
Salah satu hasil penting yang didapat adalah tidak adanya korelasi yang
signifikan antara kepedulian kepada lingkungan dengan tindakan pembelian
produk-produk ramah lingkungan. Alasan penting yang disampaikan oleh
partisipan adalah karena barang-barang yang dilabeli ramah lingkungan pada
umumnya memiliki harga yang lebih mahal daripada barang-barang lain yang
tidak berlabel ramah lingkungan. Kedua penelitian diatas menunjukkan satu
hal yang sama, yaitu biaya mengkonsumsi barang ramah lingkungan yang
mahal. Karena itu penelitian saya mengajukan pertanyaan, hasrat seperti apa
yang mendorong mereka bersedia mengkonsumsi makanan dan barang
ramah lingkungan yang berharga lebih mahal.
Selanjutnya penelitian yang cukup penting didapat dari Dini Asmarani
(2016) yang meneliti tentang budaya mengkonsumsi pangan organik di kota
Yogyakarta. Tesis bidang Antropologi ini berjudul “Pangan Organik: Konsumsi
Simbolik Kaum Urban Di Yogyakarta”, menggunakan metode penelitian
kualitatif sosio antropologi berupa observasi dan interview. Penelitian ini
bertujuan untuk menggambarkan makna konsumsi pangan organik terhadap
model pangan yang ditekuninya.
Berangkat dari premis imaji pangan organik sebagai model pangan yang
lebih cerdas dan berwawasan lingkungan, penelitian ini kemudian
konsumsi makna simbolik. Mengkonsumsi pangan organik berarti
mengkonsumsi bahan pangan yang memilki imaji prestisius dan eksklusif,
mendongkrak prestise dan percaya diri, ada hasrat dan kesenangan diri yang
coba dibangun.
Kesimpulan ini didapat Asmarani melalui telaah konsumen pangan
organik dan para produsen pangan organik yang memiliki jaringan komunitas
yang cukup kuat di Yogyakarta. Para produsen ini rajin memberi iklan melalui
media sosial tentang segala kegunaan pangan organik sembari menunjukkan
hal-hal negatif dari pangan konvensional. Mereka juga rajin mengadakan
berbagai macam acara diskusi, seminar, lokakarya, sehingga pangan organik
mendapatkan tempat yang terkesan cerdas untuk dibicarakan terus-menerus.
Diskusi-diskusi ini ikut membantu konstruksi pangan organik sebagai makanan
sehat, higienis dan prestisius.
Penelitian ini amat membantu melihat sebuah budaya kontemporer
yang sedang berkembang di Yogyakarta, khususnya budaya tentang makan
dan gaya hidup hijau yang terangkum dalam pangan organik. Kelemahan dari
penelitian ini adalah tidak tegasnya sang peneliti menentukan posisi
penelitiannya. Secara umum penelitian ini menunjukkan bahwa
mengkonsumsi pangan organik tak lebih dari sekedar bentuk konsumsi
simbolik yang hanya memuaskan hasrat dan kesenangan.
Namun pada bagian lain sang peneliti juga mengafirmasi pernyataan
organik adalah bentuk perlawanan terhadap model pangan konvensional yang
merusak lingkungan, memiskinkan petani dan mengganggu kesehatan. Meski
pada bagian akhir kesimpulan, sang penulis kemudian menyatakan keraguan
akan manfaat pangan organik dengan menyatakan bahwa belum ada
penelitian yang memastikan makanan sebagai faktor utama penunjang
kesehatan manusia karena kesehatan itu bukan saja dipengaruhi oleh
makanan tapi juga oleh pikirannya.
Penelitian ini memiliki cukup banyak perbedaan dengan penelitian yang
saya lakukan. Asmarani hanya meneliti fenomena pangan organik, sementara
penelitian yang saya lakukan berbicara soal gaya hidup hijau. Dimana pangan
organik hanyalah salah satunya, jadi terdapat pola hidup yang beragam.
Selain itu metode serta sudut pandang yang saya pakai menghasilkan
kesimpulan yang berbeda.
Penelitian lain yang cukup penting berjudul “Organisasi Pemuda
Lingkungan Di Indonesia Pasca-Orde Baru” yang ditulis oleh Tim YOUSURE
atau Youth Studies Centre Fisipol UGM (2014). Sebagaimana judul yang
diberikan, buku ini berisi gambaran tentang organisasi dan komunitas hijau
apa saja yang muncul dan berkembang di Indonesia pasca Orde Baru.
Penelitian ini memetakan 31 organisasi dan komunitas yang tersebar di 4
kota, yakni Jakarta, Bogor, Bandung dan Yogyakarta, yaitu kota-kota yang
Universitas menjadi faktor penting karena anggota dari organisasi dan
komunitas ini pada umumnya adalah mahasiswa dan alumni yang telah
bekerja, namun masih memiliki hubungan dengan para mahasiswa di
organisasi atau komunitas itu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif
sosiologi. Dilakukan dengan cara wawancara, observasi kegiatan partisipan
serta pengumpulan data sekunder melalui pantauan liputan kegiatan
komunitas yang diunggah di media sosial (facebook dan twitter) dan media
online(blogdanwebsite).
Sebagai pisau analisa, penelitian ini menggunakan teori Gerakan Sosial
Baru. Gerakan lingkungan hidup memang menjadi bagian dari kelahiran
Gerakan Sosial Baru di Amerika Utara dan Eropa Barat yang menghasilkan
masyarakat pasca-industri dan pasca-material. Sayangnya data penelitian ini
tidak memberikan perbandingan dengan konteks sosial dan politik Indonesia
yang memiliki persoalan yang berbeda, termasuk persoalan lingkungan hidup
yang kompleks. Sehingga tak heran jika buku ini sangat optimis dalam
memandang kemunculan organisasi dan komunitas lingkungan hidup dengan
segala jajaran aktivismenya sebagai kemunculan masyarakat baru di
Indonesia.
Seandainya analisa penelitian dihubungkan dengan konteks sosial politik
Indonesia kontemporer yang lebih mendalam, mungkin saja akan ditemukan
antara masyarakat yang melahirkan gerakan sosial baru dengan konteks
masyarakat Indonesia saat ini.
Gerakan sosial baru di Eropa muncul dalam masyarakat pasca
industrialisasi, sedangkan Indonesia sekarang ini justru berada dalam proses
industrialisasi yang dilakukan oleh berbagai korporasi. Diantaranya justru
korporasi multinasional yang datang dari negara-negara Eropa itu. Karena itu
perlu kiranya konteks yang lebih lengkap dan tepat untuk memakai teori
gerakan sosial baru untuk mengkaji gerakan lingkungan hidup kontemporer di
Indonesia.
Sebelumnya Suharko (1997) telah melakukan penelitian sosiologi
berjudul “NGO Dan Gerakan Hijau (Studi tentang Ideologi dan Gerakan
Lingkungan di Yogyakarta)”, juga menggunakan teori Gerakan Sosial Baru.
Yang berbeda adalah penelitian Suharko berfokus pada analisa ideologi yang
dibawa oleh delapan NGO atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang bekerja di
Yogyakarta di tengah situasi politik Indonesia Orde Baru. Menurut Suharko
gerakan lingkungan yang ada di Indonesia pada masa Orde Baru sudah
memiliki keragaman jenis aktivisme. Dari aktivisme yang mengusung
persoalan kesehatan dan keragaman tanaman obat tradisional, hingga
kegiatan NGO yang mendampingi petani dan nelayan.
Namun dari keragaman kegiatan dan aksi tersebut, delapan NGO ini
justru ditemukan memiliki kesamaan ideologi. Yaitu ideologi
pada saat itu. Barisan NGO ini, menurut Suharko, hanya menjalankan apa
yang dijalankan penguasa, tidak ada niat untuk mengubah situasi yang ada.
Kegiatan-kegiatan mereka hanya menambal kekurangan-kekurangan ideologi
pembangunanisme yang dijalankan negara, bahkan cenderung akomodatif
dan bekerja-sama dengan negara.
Menurut saya akan sangat menarik jika seandainya ketajaman analisa
dan konteks penelitian yang sama juga dilakukan dalam penelitian tentang
organisasi dan komunitas Indonesia pasca-orde baru. Supaya kita bisa
mendapatkan gambaran yang lebih kaya tentang perubahan-perubahan yang
terjadi di Indonesia. Dalam hal ini perkembangan apa yang terdapat pada
wacana dan ideologi yang diusung gerakan lingkungan hidup dan mewarnai
perjalanan masyarakat Indonesia.
Namun penjabaran data tentang kemunculan, perkembangan dan
dinamika gerakan organisasi dan komunitas lingkungan pasca-orde baru yang
digambarkan merupakan kekuatan tersendiri. Setidaknya buku ini menjadi
salah satu penelitian penting yang merekam fenomena ideologi hijau
kontemporer Indonesia.
F. Kerangka Teoritis
Untuk kebutuhan analisis terhadap rumusan masalah dan data yang
dari Jacques Lacan. Yaitu teori Fetis yang dielaborasikan dengan teori
Metonimi untuk mengartikulasikan Hasrat subjek yang diteliti.
Hasrat
Hasrat, bagi Lacan, adalah esensi diri manusia. Lacan mengikuti Spinoza yang
menyatakan bahwa hasrat adalah inti dari eksistensi manusia6, dan karena itu
ia menjadi perhatian utama psikoanalisa. Hasrat (desire, désir) dibedakan
dengan demand dan need. Jika demand dan need dapat dipuaskan maka
sebaliknya yang terjadi pada hasrat.
Hasrat selalu bergerak, kepuasannya selalu ditunda. Jika ia berhasil
dipuaskan maka sesungguhnya ia berhenti menjadi hasrat. Karena itu hasrat
tidak memiliki objek, bahkan ia segera menghilang ketika ada objek yang
dicapai. Kepuasan adalah pembunuh hasrat.7 Dengan demikian hasrat selalu
berupa dorongan yang terus-menerus bergerak menginginkan. Karena itulah
Lacan menyebut hasrat sebagai metonimi.
Sebagai bagian dari ketidaksadaran maka hasrat terikat kepada penanda
atau signifier dan hukum Sang Ayah. Hasrat hanya dapat dikenali di dalam
penanda, bahkan ia dihadirkan melalui penanda. Karena itu hasrat subjek
adalah hasrat Other. Jika sebuah objek dihasrati oleh seseorang maka hal itu
6 Jacques Lacan (1958-1959), The Seminar Of Jacques Lacan, Book VI: Desire And Its
Interpretation, 4, dibaca dalam bentuk pdf.
terjadi bukan karena kualitas intrinsik tertentu pada objek itu, melainkan
karena objek dihasrati oleh yang lain.
Subjek mengambil hasrat Other dan menjadikannya sebagai hasratnya
sendiri agar ia menjadi subjek yang berhasrat seperti Other. Man’s desire is
the Other’s desire. Bahkan seringkali subjek berhasrat agar dihasratkan oleh
Other atau memenuhi hasrat Other. Man’s desire is to be desired by the
Other. Jadi di dalam hasrat ada hubungan dialektikal dengan hasrat subjek
lain. Subjek tidak hanya berhasrat kepada apa yang dihasrati Other, bahkan ia
berhasrat dengan cara yang sama. Struktur hasrat-nya persis seperti struktur
pada Other8. Hasrat adalah produk sosial dan bukan sekedarprivate affair.
Karena itu hasrat tidak dapat dipisahkan dengan fase simbolik. Dalam
fase inilah hasrat lahir bersamaan dengan momen ketika anak masuk ke
dalam fase simbolik dan menjadi subjek. Fase simbolik adalah fase dimana
hubungan imajiner antara ibu dengan anak diinterupsi oleh Hukum Sang Ayah
(Name of The Father). Tindakan ini menimbulkan perubahan identifikasi anak
dari yang imajiner (fase cermin) digantikan oleh identifikasi secara simbolik.
Ketika seorang anak baru lahir ia memiliki hubungan yang sangat khusus
dengan ibu. Ibu selalu hadir bagi dirinya (omnipotent), dan anak adalah objek
hasrat ibu. Namun kemudian hari berlalu, si anak mendapati ternyata ibu
tidak selalu bisa hadir untuk dirinya. Ia mulai berkenalan dengan lack mother.
Anak menyadari bahwa ia bukanlah satu-satunya objek hasrat ibu.
8Bruce Fink (1995),The Lacanian Subject, Between Language and Jouissance, United Kingdom:
Hubungan anak dengan ibu diintervensi oleh ayah yang menyatakan
bahwa ibu adalah miliknya dan bukan milik si anak. Hubungan anak dengan
ibu dipisahkan oleh ayah. Anak mengalami kastrasi simbolik, ia harus
menerima kenyataan bahwa ia bukanlah objek hasrat atau phalus imajiner
mOther. Bahwa Sang Ayah-lah yang memiliki phallus simbolik yang mampu
mengisilackmOther. Ia bukanlah sang objek ideal yang dibutuhkan ibu untuk
mengisi hasratnya. Identifikasi anak dengan phalus imajiner usai sudah.
Dalam proses kastrasi ini terjadi penggantian (substitusi) dimana
penanda Hukum Sang Ayah menduduki tempat penanda hasrat mOther. Ayah
simbolik memberi nama pada hasrat mOther. Penanda hasrat mOther
mengalami represi dan menjadi ketidaksadaran.
Hasilnya adalah tinanda (signified)atau ide tentang phalus sebagai objek
imajiner yang diasumsikan sebagai pemuas hasrat ibu berubah menjadi
impossible object. Yang hadir adalah phallic signifier yang tidak merujuk
kepada objek apapun. Ia menjadi penanda atas sebuah ketiadaan atau lack
atauabsenceatas yang sebelumnya tidak ia miliki9.
Hukum Sang Ayah kini menjadi master signifier yang memberikan
struktur dunia simbolik kepada anak yang telah menjadi subjek signifier.
Kastrasi adalah proses simbolik yang melaluinya anak masuk ke dunia
simbolik. Di dalamnya bertabur berbagai penanda atau signifier dan proses
pemaknaan (signification).
Di dunia simbolik inilah subjek dapat mengambil posisinya sebagai
subjek yang berhasrat dan berwicara, melaluinya subjek dapat menegaskan
identitasnya. Dunia imaji yang sebelumnya ia tinggali sudah tergantikan. Ia
kini menjadi subjek yang terbelah ($) yang telah kehilangan dirinya yang
“murni” atau the real namun sekaligus menemukan dirinya dalam bentuk
penanda. Subjek adalah efek penanda, dan penanda mewakili subjek kepada
penanda lainnya10.
Dalam dunia simbolik subjek dapat mengartikulasikan hasratnya. Yaitu
hasrat yang berasal dari Other yang bergerak, mengalir kepada subjek melalui
bahasa dan diskursus. Hasrat muncul melalui rangkaian antara penanda,
bahkan hasrat menjadi bahasa dan wicara sebagaimana fungsinya dalam
rangkaian penanda11. Karena itu tepatlah dikatakan bahwa hasrat
bergantung, dan tunduk kepada Hukum atau Other. Apa yang dilarang oleh
Hukum, itulah yang dicari oleh hasrat.12Tanpa Hukum hasrat tidak hadir.
Berbeda dengan Saussure yang menghubungkan signifier dengan
signified, penanda dengan tinanda, Lacan menghubungkan signifier dengan
signifier, penanda dengan penanda. Namun rangkaian penanda ini tidak
berjalan dengan konsisten. Selalu ada yang terpeleset kepada penanda
10Ibid, hlm. 207. 11Ibid, hlm. 205.
berikutnya. Rangkaian yang bersifat metonimik ini menyebabkan hasrat juga
selalu bergerak kepada hasrat berikutnya, tanpa akhir.
Hal ini sekaligus menandakan bahwa adalah hal yang mustahil bagi
penanda untuk dapat dengan sempurna mengekspresikan dan memuaskan
hasrat. Adalah hal yang mustahil bagi hasrat untuk mendapatkan kembali
objek hasrat yang semula, yakni phalus. Karena phalus akan hilang selamanya
dan karena subjek sesungguhnya tidak pernah memilikinya. Kemustahilan ini
adalah bukti bahwa simbolik juga mengalamilack.
Rangkaian metonimik pada penanda inilah yang membuat hasrat tidak
mampu memiliki objek. Satu-satunya objek yang terlibat dengan hasrat adalah
objek penyebab hasrat atau object-cause of desire. Lacan menyebutnya
sebagai objet petit a (autre) atau objet (a).
Cause → desire → metonymic slippage from one object to the next13
Objet (a) berfungsi untuk mendorong hasrat agar hadir, namun ia juga
menghalangi subjek dengan mengingat bahwa objet (a) adalah objek yang
hilang yang tidak dapat dicapai. Secara paradoks objet (a) memiliki fungsi
sebagai pendorong sekaligus sebagai penghalang hasrat.14 Objet (a) adalah
apa yang tersisa dari proses konstitusi objek, ia adalah secarik yang
menghindar dari proses simbolisasi. Objet (a) hadir untuk menjadi remainder
atau pengingat bahwa ada lack pada subjek, sekaligus mengisi kekosongan
dalam fase simbolik saat terciptalackpada rangkaian penandaan.
Hasrat, fase simbolik, bahasa dan penanda, serta Hukum Sang Ayah
memikili hubungan yang saling terkoneksi. Hukum Sang Ayah mengatur hasrat
dan tidak melarang hasrat. Ia menjadi prasyarat agar hasrat secara tidak
terbatas mengalir dari penanda yang satu kepada penanda lain. Hukum Sang
Ayah menopang struktur hasrat dengan struktur hukum simbolik.15
Fetisisme
Konsep tentang fetis pertama kali diajukan oleh Charles de Brosses pada
tahun 1760. Ia memakainya untuk menunjukkan praktik agama primitif yang
melibatkan pemujaan terhadap objek natural tertentu, seperti batu, hewan
ataupun pohon. Konsep fetisisme menjadi sangat lekat dengan Karl Marx
melalui istilah commodity fetishism (fetisisme komoditi). Marx memakainya
untuk menjelaskan situasi hubungan sosial dalam masyarakat kapitalisme
yang selalu diperantarai oleh objek komoditas.
Menurut Marx, uang adalah objek fetis yang memiliki nilai komoditas
pada dirinya. Ia menjadi standar nilai komoditas untuk dipertukarkan dengan
komoditas lainnya agar menghasilkan surplus nilai. Uang menjelma menjadi
alat mediasi atas setiap realitas material dan menjadi penyetara universal atas
nilai. Ia adalah sebuah kekuatan simbolik yang tereduksi dalam bentuk
hubungan langsung antara individu.16
Bagi Marx, relasi sosial pada masa pra-kapitalisme (feodal) berlangsung
dengan lebih jelas. Pada masa ini hubungan masyarakat dialami sebagai relasi
antar manusia yaitu –memakai istilah dari Hegel- sebagai tuan dan budak.
Sementara dalam masa kapitalisme, relasi antar manusia menjadi setara dan
bebas di hadapan hukum (pasar) karena manusia kini ditempatkan pada
hubungannya dengan sang objek fetis.
Jika sebelumnya “relasi antara tuan dan budak”-lah yang menjadi fetis,
kapitalisme kemudian memindahkannya (displacement) menjadi “relasi antara
objek” melalui sistem komoditas. Wilayah fetis berubah dari relasi antar
subjek (between men) menjadi relasi antar objek (between things). Dimana
relasi sosial tidak lagi transparan dalam bentuk relasi interpersonal tuan dan
hamba, melainkan relasi antar objek yang disamarkan dalam bentuk
hubungan kerja.17
Seperti Marx, Freud juga menempatkan konsep fetisisme sebagai
pemindahan ataudisplacement. Menurutnya fetis berarti ketertarikan seksual
subjek dipindahkan dari objek seksual yang “normal” kepada objek
penggantinya (substitusi). Dalam kedua kasus ini, proses pemindahan ini
mengarahkan fokus tertuju kepada elemen yang parsial dan “lebih rendah”
dan mengaburkan sekaligus membentuk ulang hubungan sosial.
Adalah Krafft-Ebing yang pertama kali menggunakan istilah fetis sebagai
bagian dari seksual perversi yang kenikmatannya bergantung kepada
kehadiran objek tertentu. Biasanya objek fetis ini berupa benda mati seperti
sepatu atau pakaian dalam.18 Freud sendiri menyatakan bahwa kasus fetis
kebanyakan terjadi pada laki-laki, yang mengalami kengerian akan kastrasi
yang dialami secara imajiner pada fase Oedipal.
Si anak melihat bahwa ibu (mother) dan perempuan lainnya tidak
memiliki penis. Baginya ada persoalan phalus yang seharusnya ada namun
justru hadir sebagai pengalaman kehilangan. Fakta ini menimbulkan
kekhawatiran yang sangat besar padanya, karena lack of penis adalah bukti
telah terjadi kastrasi. Dan kastrasi berarti kehilangan objek hasrat.
Kekhawatiran itu membayangi. Jika perempuan benar telah dikastrasi
maka tubuhnya sekarang juga berada dalam bahaya, terancam untuk
mengalami hal yang sama. Maka ia harus membangun mekanisme
pertahanan diri untuk menolak fakta ini, yakni membangun persepsinya
sendiri yang berseberangan dengan fakta. Ia harus menyangkalnya.
Si anak kemudian mengambil objek tertentu atau bagian tertentu dari
tubuh (misalnya serpihan bulu yang mirip dengan pubic hair) yang ditetapkan
untuk memiliki peran yang dimiliki oleh penis. Proses ini dibentuk oleh
tindakan kompromi si anak dengan pemindahan (displacement) objek
tertentu untuk mengisi lack of penis dengan tujuan untuk menghancurkan
18Dylan Evans (2006),An Introductory Dictionary of Lacanian Psychoanalysis, London: Routledge,
bukti-bukti yang memungkinkan terjadinya kastrasi. Dengan demikian rasa
takut atau khawatir mengalami kastrasi dapat dihindari.19
Freud membagi tiga subjek yang dihasilkan dari pengalaman subjek
dengan kastrasi, yaitu neurotik, psikosis dan perversi. Subjek neurotik adalah
subjek yang menerima kastrasi dan tunduk kepada hukum. Sementara dua
lainnya tidak menerima kastrasi dan mengambil mekanisme pertahanan
tertentu. Untuk subjek perversi pertahanan yang dilakukannya adalah dengan
melakukan penyangkalan atau disavowal akan realitas terjadinya kastrasi. Di
dalam perversi inilah tercipta –salah satunya- fetis.
Proses pertahanan diri pada fetis berlangsung dua tahap. Yang pertama
adalah disavowal atau penyangkalan akan realitas. Subjek menolak untuk
mengakui eksistensi aktual yang menghadirkan pengalaman traumatik: bahwa
ibu (mother) dan perempuan pada umumnya tidak memiliki penis. Tahap ini
kemudian dielaborasikan dengan formasi berikutnya yakni substitusi atau
menggantikan penis yang tiada dengan objek partikular. Jadi fetis melakukan
kompromi dengan mengambil objek realitas untuk mengambil peran objek
yang hilang.
Di sini Freud mengembangkan teori fetis dengan menunjukkan sebuah
paradoks yang terjadi pada subjek perversi. Ia menyatakan bahwa subjek fetis
mampu melakukan dua komponen intra fisik yang bersifat paradoks secara
yang sama ia juga menolak pengetahuan tersebut (disavowal). Freud
menyebut mekanisme ini sebagai splitting of the ego, sebagai aspek
metafisika pada subjek fetis.
Yang pertama adalah menerima realitas (avowal) “i know that..”.
Namun menerima realitas ketiadaan penis berarti kehilangan objek hasrat,
sebuah situasi yang sungguh berat. Karena itu objek fetis hadir untuk
memerankan diri sebagai adult memorial yang mengingatkan diri kepada
pengalaman kehilangan. Dengan demikian mekanisme kedua dapat
dilaksanakan, yaitu subjek mampu menarik ego dari realitas (disavowal), “but
even so”. Ia menyangkal realitas lack of penis, namun pada saat yang sama ia
menempatkan objek fetis. Padahal kehadiran objek fetis sebagai adult
memorial justru menjadi bukti yang tak terbantahkan bahwa sesungguhnya
telah terjadi kastrasi atau ketiadaan penis.
Lacan mengambil konsep Freud namun membedakan penis dengan
phalus dan menyatakan phalus sebagai penanda atas lack of Other. Posisi
Other (dapat ditempati oleh ibu atau perempuan, atau siapa saja yang
memiliki figur otoritas) adalah posisi yang diproyeksikan secara ekternal dari
tempat dimana subjek mencari jawaban atas sebuah pertanyaan tentang
hasratnya.
Pertanyaan itu berada dalam bentuk “Che vuoi?” atau “What do you
(the Other) want?” atau “Apa yang ia (Liyan) inginkan?”. Pertanyaan yang jika
bentuk: “What does he (the Other) want of me?” atau “Apa yang ia (Liyan)
inginkan dariku?”. Phalus adalah penanda atas ekonomi fisik yang mengalami
lack, dan dengan demikian ia berperan penting dalam menciptakan
subjektivitas.20
Menurut Lacan, fetis muncul sebagai hasil dari pertemuan (intersection)
atas dualack, yaitulacksubjek danlack Otheratau liyan. Setiap individu yang
berbahasa akan mengalami lack, dan karena Other adalah tempat dimana
bahasa berlabuh maka setiap yang berbahasa akan terus bergantung kepada
Other. Menurutnya sedari kecil setiap anak akan membangun lack antara
dirinya dengan sekitarnya bahkan dengan dirinya sendiri. Lack hadir karena
kegagalan anak untuk merasa cukup dengan dirinya. Kebergantungan subjek
terhadap liyan atau kepada pengasuhnya menjadi sumber atas rasa
kekhawatirannya, meski di saat itu sang anak berada aman di tangan sang
pengasuh.
Anak mengekspresikanlackini melalui kebutuhan (demand) untuk terus
kembali kepada objek, misalnya payudara ibu. Namun tidak ada objek yang
dapat setara dengan lack ini. Maka meskipun kebutuhan akan objek
terpenuhi, kebergantungan anak kepada Other terus berlangsung. Demikian
pulalackdan kekhawatirannya.
Payudara ibu adalah objet a, yang ketika anak disapih, objek ini “hilang”
anak mendapatkannya kembali. Situasi ini secara simbolik menjadi asal mula
lack anak (subjeck’s original lack) dan menjadi situasi yang tak akan pernah
bisa diatasinya. Ada pengalaman yang amat dalam akan objek yang hilang (the
loss of object). Lack pertama inilah yang berfungsi membuat subjek
bergantung kepada liyan (Other) secara terus menerus sekaligus gagal untuk
mendapatkan kepuasan.
Subject’s original lack = Lack of objet a = Continuing lack of satisfaction
Selain mendapati diri yang mengalami lack, sebagaimana disebutkan
diatas, subjek juga mendapati bahwa big otheratau m(O)ther juga mengalami
lack karena m(O)ther tidak memiliki phalus (maternal phallus). Padahal liyan
atau ibu atau m(o)ther adalah sumber kebutuhan sang anak yang ia rindukan.
Maka ketika anak berjumpa maternal phalus maka ia juga gagal mendapatkan
kepuasan dari sang liyan ataubig Other.
Mother’s lack = Subject’s original lack
Maka kita mendapatkan persamaan rangkaian identitas berupa:
Mother’s lack = Subject’s original lack = Continuing lack of satisfaction = Lack of
objet a
Persamaan ini menjadi:
Mother’s lack = Lack of objet a21
Jadi lack ofobjet a tercipta ketika ada dua lack yang terjadi (two lacks
overlap), yaitu lackpada subjek dan lackpada liyan atau m(o)ther. Ketiadaan
yang membuat subjek gagal mendapatkan kepuasan secara terus-menerus.
Inilah yang membuat subjek harus menyangkal. Penyangkalan dalam formula
fetisisme adalah “I know that Mother doesn’t have a penis (avowal atau
pengakuan), but nevertheless...i believe that she has (disavowal atau
penyangkalan)”.22
Subjek menyangkal kastrasi dengan menciptakan objek fetis yang
dimaksudkan untuk mengambil peran simbolik dari maternal lack. Fetis
adalah jenis khusus dari objet a agar subjek dapat dialihkan perhatiannya dari
kondisi yanglackkepada objek fetis ini agar subjek kembali bisa mendapatkan
kepuasan. Untuk mendukung hal ini maka hasrat subjek juga harus
dipindahkan kepada objek a, subjek harus “berhenti” mengejar hasratnya dan
mendedikasikan dirinya untuk mendukung fungsi objet a.
Pada kondisi inilah kemudian objet a menanggung kesamaan struktural
dengan “komoditas”. Ia bukan hanya sebuah objek yang kongkrit namun juga
membawa nilai yang samar, sebuah pokok yang salah dibawa oleh sang objek
dan menjadi penting dalam proses pertukaran. Objet a tidak semata-mata
hanya sebuah metafor. Ia menjadi pengganti atau substitusi untuk objek lain
demikian objet a menciptakan kesan yang salah seolah ada sesuatu yang
membuat ia kemudian bertindak sebagai pengganti.23
Dalam konsep fetis, Lacan membedakan antara objek yang dihasratkan
oleh subjek dengan objek lain yang disebut sebagai objet a. Objet a memiliki
dua fungsi. Pertama sebagai objek penyebab hasrat (object-cause of desire)
dan kedua sebagai object of the drive, yaitu objek yang darinya subjek
mendapatkan kenikmatan (pleasure). Fetis adalah contoh dari objet a.
Deminya represi diterobos agar subjek dapat lebih mengenali sumberrealdari
kenikmatannya sehingga subjek dapat memasuki mekanisme penyangkalan
(disavowal).
Hubungan antara objet a, subjek yang menghasrati, dan objek hasrat
dimisalkan melalui hubungan diantara pendamping (chaperone), pelamar
(suitor) dan kekasih (beloved). Sang pendamping hanyalah individu yang
mendukung si pelamar untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Namun
dengan memposisikan dirinya pada bagian itu ia menjadi bagian dari struktur
yang sedang berlangsung, dan menjadi penyebab hasrat. Ia menjadi objek
penyebab hasrat (object-cause of desire) dan menjadi sumber kenikmatan,
meski dirinya sendiri tidak dihasrati. Demikianlah sang pendamping
menempati fungsi objet a.
Si pendamping adalah subjek yang menyerah mengejar hasratnya
sendiri. Ia malah mendedikasikan dirinya untuk mendukung objet a dalam
fungsinya sebagai penghalang hasrat. Ia memang menyerah mengejar
hasratnya, namun ia tidak menghilangkan hasrat itu. Ia memindahkan
hasratnya dengan menempati posisi sebagai pendamping atau pendukung
saja agar si pelamar dapat terus menghasrati sang kekasih. Sang pendamping
adalah objet a, menempati peran sebagai objek fetis. Keterlibatan si pelamar
dengan objet a ternyata menstabilkan libidinal dan menghasilkan kenikmatan.
Sementara sang pelamar adalah subjek fetis yang tahu bahwa si
pendamping hanyalah seorang perempuan tua yang tidak memiliki kekuatan
apa-apa untuk menghentikannya mendapatkan apa yang dimauinya.
Pengetahuan ini disebut sebagai pengakuan (avowal) “i know that”. Namun
meski demikian “but even so”, dan dengan alasan yang seringkali tidak jelas, si
pelamar tetap mengenali betapa pentingnya peran sang pendamping.
Sehingga ia mencurahkan perhatiannya kepadanya. Tindakan ini adalah
penyangkalan (disavowal). Pengetahuan subjek dikhianati oleh pengetahuan
yang bersifat kontras yang disandikan ke dalam fantasi dan akhirnya
memberikan struktur atas tindakannya kemudian.
Fetis tidak membutuhkan tindakan represi. Tidak ada pengetahuan yang
harus direpresi agar ia bisa mendapatkan kepuasan melalui upaya pengejaran
hasratnya. Fetis mendapatkan kepuasannya melalui keterlibatannya dengan
objet a. Fetis seringkali disebut sebagai seksualitas yang menyimpang dalam
yang lain. Yang ia kejar adalah objek fetis yang berfungsi sebagai penghalang
atau yang menunda subjek dapat mencapai hasratnya.
Metonimi
Lacan mengaitkan psikoanalisa sebagai ilmu tentang ketidaksadaran dengan
bahasa melalui adagium yang paling terkenal sekaligus menjadi dasar, yaitu
ketidaksadaran terstruktur seperti bahasa. Dan salah satu efek bahasa yang
mempengaruhi ketidaksadaran itu adalah metafora dan metonimi. Menurut
Lacan, pada kedua bagian inilah kekuatan bahasa sebagai penanda (signifier)
dan tinanda (signified) mendapat maknanya secara penuh.24 Untuk teori ini
Lacan dipengaruhi oleh formalis asal Rusia yaitu Roman Jakobson dan
menggabungkannya dengan formula condensation dan displacement yang
diberikan oleh Sigmund Freud.
Roman Jakobson menyebut metafora dan metonimi sebagai gangguan
berbahasa atau aphasia. Gangguan motorik (kontiguitas) menunjukkan
reduksi pada stok verbal merupakan apashia yang pusat gangguannya berada
di metonimi, sementara pada metafora terdapat proses substitusi dan
seleksi.25 Menurutnya ada dua sumbu bahasa yaitu vertikal dan horizontal
yang ekuivalen dengan formula bahasa dari Saussure tentang seleksi dan
24 Ellie Ragland-Sullivan (1987), Jacques Lacan and The Philosophy of Psychoanalysis, USA:
University of illinois Press, hlm. 234
kombinasi bahasa serta dua relasi unit bahasa yakni in absentia dan in
praesentia.
Gb. 1. 2. Sumbu Aphasia
Lacan mengikuti Jakobson dengan menghubungkan metonimi pada
sumbu horizontal sehingga melibatkan kombinasi bahasa dan beroposisi
dengan sumbu vertikal yang melibatkan substitusi dan seleksi bahasa.
Metafora dihasilkan dari substitusi dari satu penanda dengan penanda lainnya
dalam rangkaian penanda. Sementara metonimi merupakan hasil dari
penanda yang dikombinasikan atau dihubungkan (contiguity) dalam rangkaian
penanda tunggal (hubungan horizontal). Karena itu metonimi berada pada
hubungan diakronik antara satu penanda dengan penanda lainnya dalam
rangkaian penandaan (signifying chain).26
Jika hubungan metafora dihasilkan melalui kekuatan represi, maka
hubungan metonimik dihasilkan dengan kekuatan kombinasi. Hubungan ini
berfungsi untuk menyatukan rangkaian unit penanda yang berbeda ke dalam
terjadi bukan karena similaritas antara penanda (sebagaimana yang terjadi
pada metafora), melainkan karena sifat difference,discrimination,contiguity,
dan displacement. Perbedaan antara metafora dan metonimi diringkas
demikian:
Tabel. 1.1. Perbedaan metafora dan metonimi27
Namun dalam menghubungkan konsep metonimi dengan perihal
ketidaksadaran, Lacan lebih memilih memodifikasi konsep dari Jakobson
dengan konsep displacement (pemindahan) yang diberikan oleh Freud. Jika
Jakobson menyatakan displacement sebagai similaritas (kesamaan) untuk
menghasilkan metafora, Freud mengarahkan displacement sebagai
pemindahan atau pembelokan makna kepada metonimi. Maka:
Metaphor : Substitution : Condensation
Metonymy : Combination : Displacement.
Lacan kemudian mengembangkannya dan membentuk formula metonimi:
f (S . . .S’) S ≡ S (--) s
Gb. 1. 3. Formula Metonimi28
27Russell Grigg (2008),Lacan, Language, and Philosophy, USA: State University of New York
Formula ini dibaca demikian: Bagian kiri persamaan, bagian luar tanda
kurung, Lacan menulis f S atau the signifying function sebagai signification
effect atau efek pemaknaan. Bagian dalam tanda kurung adalah S...S’, yaitu
hubungan antara satu penanda dengan penanda lain di dalam rangkaian
penandaan. Di sisi kanan persamaan adalah S (--) s, yaitu penanda dengan (--)
atau BAR dari algoritma Saussurean, BAR tidak disilang yang berarti tidak ada
signified baru yang dihasilkan dalam proses ini. Tanda ≡ dibaca sebagai ‘is
congruent with’ atau ‘adalah sebangun dengan’. Maka seluruh formula
dibaca: ‘fungsi pemaknaan dari hubungan antar penanda dengan penanda
lainnya adalah sebangun dengan mempertahankan bar’. Berarti metonimi
mempertahankan resistensi pemaknaan (signification) sehingga tidak
menghasilkan makna baru.29
Lacan menyatakan metonimi berfungsi untuk memindahkan
(displacement) ketidaksadaran dengan menggantikan kata (words) untuk
makna ketidaksadaran. Jadi ada mekanisme pertahanan yang menutup
ketidaksadaran, misalnya dengan represi atau penyangkalan. Metonimi
adalah struktur satu dimensi (one-dimensional structure) yang memindahkan
makna kepada Other (A). Metafora mampu menghasilkan dan
mempertahankan kestabilan makna, sementara metonimi selalu menunda
kemunculan makna.
Penundaan ini terjadi karena metonimi berada pada relasi diakronik
dimana satu penanda akan bergerak menuju penanda lain secara
terus-menerus. Sifat penundaan inilah yang membuat Lacan menyimpulkan bahwa
metonimi adalah hasrat (desire) yang selalu berupaya mendapatkan
satisfaction. Sama seperti metonimi, hasrat juga selalu bergerak menghasrati
yang lain. Ia selalu mengalami penundaan hasil karena jika terwujud maka ia
tidak lagi menjadi hasrat.
Karena itu menurut Lacan, metonimi adalah word-to-word connections
between signifier. Ia adalah hubungan antara kata dengan kata sebagai
penanda (signifier), termasuk pada hubungan semantiknya. Pada metonimi
hubungan semantik antara istilah laten dan manifestasi sudah mapan, namun
hubungan ini mengurangi efek makna karena keduanya tidak bersandar pada
proses penyatuan malahan saling bertabrakan.30Makna hanya dapat “keluar”
dari ketidaksadaran menuju kesadaran (consciousness) jika signifier utama
(points de capiton) berhasil menyatukan rangkaian seluruh hubungan menjadi
satu keutuhan.31
G. Metode penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan
pendekatan etnografi baru. Penelitian ini didesain untuk mendeskripsikan dan
menafsirkan pola tertentu dari nilai, perilaku, keyakinan dan bahasa dari
30Russel Grigg (2008), hlm. 161-163.
keseharian kelompok masyarakat yang melakukan gaya hidup hijau dalam
kesehariannya di kota Yogyakarta. Metode ini mencoba menangkap dan
menarasikan pendapat kelompok masyarakat itu tentang ide dan keyakinan
yang diekspresikan melalui tindakan yang dapat diamati, yakni bahasa,
tindakan serta interaksi mereka.
Metode penelitian ini mencoba sedekat mungkin dengan suara atau
pendapat mereka tentang gaya hidup hijau yang dijalankan, kemudian
menganalisanya dalam perspektif teori Psikoanalisa Lacanian. Adapun
kepentingan-kepentingan metodologis yang perlu dijabarkan pada bagian ini
adalah:
1. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Provinsi DI Yogyakarta dengan memilih
partisipan secara purposif.
2. Data dan Sumber Data
Data dalam penelitian ini adalah informasi tentang pengalaman hidup
dalam melakukan gaya hidup hijau di Provinsi DI Yogyakarta. Data diambil
dari subjek yang memiliki pengalaman tertentu dalam melakukan gaya
hidup hijau dalam kesehariannya. Dan beberapa dari mereka aktif
melakukan kampanye gaya hidup hijau, khususnya melalui komunitas yang