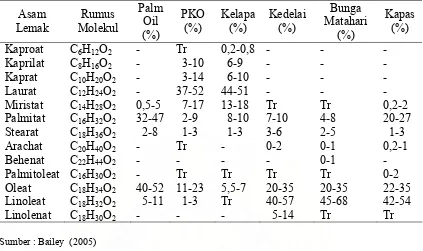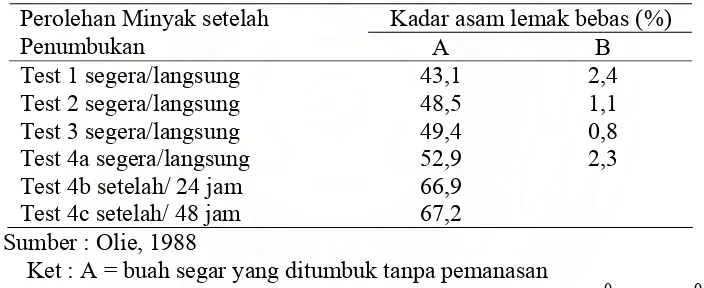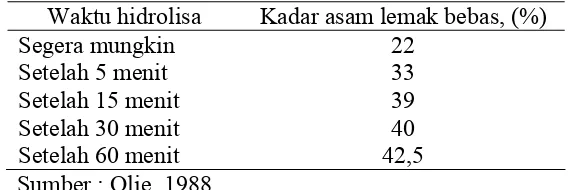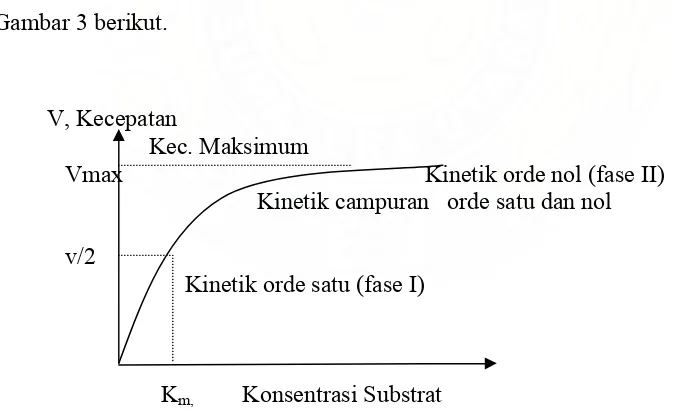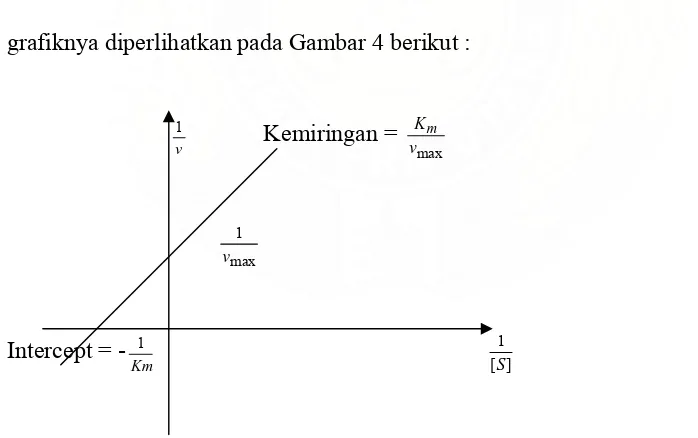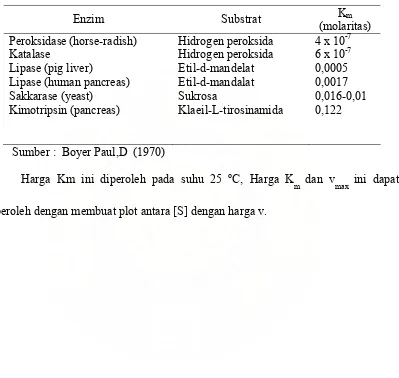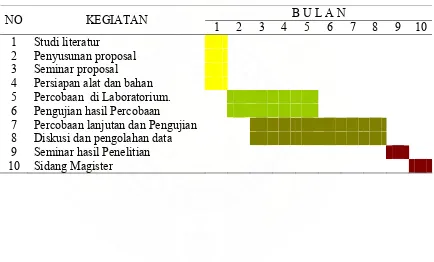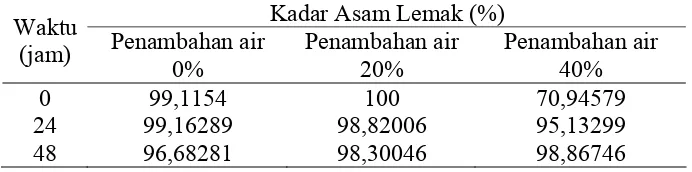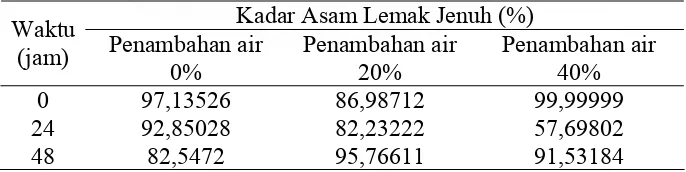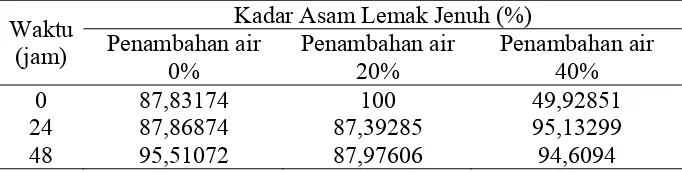PEMANFAATAN BUAH SAWIT SISA SORTIRAN
SEBAGAI SUMBER BAHAN BAKU ASAM LEMAK
TESIS
Oleh
JUSTAMAN ARIFIN KARO KARO
067022007/TK
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2009
Justaman Arifin Karo-Karo : Pemanfaatan Buah Sawit Sisa Sortiran Sebagai Sumber Bahan Baku Asam Lemak, 2009
PEMANFAATAN BUAH SAWIT SISA SORTIRAN
SEBAGAI SUMBER BAHAN BAKU ASAM LEMAK
TESIS
Untuk Memperoleh Gelar Magister Teknik
dalam Program Studi Magister Teknik Kimia
pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara
Oleh
JUSTAMAN ARIFIN KARO KARO
067022007/TK
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Judul Tesis : PEMANFAATAN BUAH SAWIT SISA SORTIRAN SEBAGAI SUMBER BAHAN BAKU ASAM LEMAK
Nama Mahasiswa : Justaman Arifin Karo Karo Nomor Pokok : 067022007
Program Studi : Teknik Kimia
Menyetujui Komisi Pembimbing
(Prof. Dr. Ir. Setiaty Pandia) (Rondang Tambun, ST, MT)
Ketua Anggota
Ketua Program Studi, Direktur,
(Prof. Dr. Ir. Setiaty Pandia)` (Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa B., MSc)
Telah diuji pada : Tanggal 10 Maret 2009
PANITIA PENGUJI TESIS
K e t u a : Prof. Dr. Ir. Setiaty Pandia A n g g o t a : 1. Rondang Tambun, ST, MT
2. Dr. Halimatuddahliana, ST, M.Sc 3. Dr. Rumondang Bulan,MS
ABSTRAK
Buah sawit sisa sortiran adalah buah sawit yang sudah melewati waktu panen TBS (tandan buah segar) dengan kadar asam lemaknya yang tinggi. Bila buah sawit sisa sortiran ini diolah dengan TBS akan menurunkan kualitas CPO (crude palm oil) yang dihasilkan. Penelitian ini menggunakan bahan baku buah sawit sisa sortiran untuk menghasilkan asam lemak. Penelitian ini memvariasikan 3 (tiga) faktor (perlakuan), ketiga faktor masing-masing dengan 3 (tiga) taraf. Faktor pertama adalah perlakuan buah sawit dengan 3 (tiga) taraf yaitu buah sawit tidak dilukai, buah sawit dilumatkan dan buah sawit dimemarkan. Faktor kedua adalah penambahan air terdiri dari 3 (tiga) taraf yaitu 0, 20 dan 40% dari buah sawit. Faktor ketiga adalah lama penyimpanan terdiri dari 3 (tiga) taraf yaitu 0, 24 dan 48 jam. Pada penelitian ini, perolehan kadar asam lemak yang dapat dicapai 100 %. Kondisi optimum ini diperoleh pada perlakuan buah sawit sisa sortiran yang dilumatkan dengan waktu tanpa penyimpanan atau 0 hari (langsung diproses) dan penambahan air 20 % dari buah sawit.
Kata Kunci: Buah sawit sisa sortiran, asam lemak, enzim lipase, enzimatik.
ABSTRACT
Residual palm sorted is a kind of seed palm which passed harvest term TBS (fresh stem of palm) with high content of fatty acid. If this residual palm sorted was processed together with TBS, it will decrease the quality of CPO (crude palm oil) This research use row material of residual palm sorted to produce fatty acid. This research use 3 (three) variable factors (treatment) which have 3 (three) levels. The first factor is treatment of seed palm with 3 (three) levels they are unbroken seed palm, blended seed palm, and hammered seed palm. The second factor is additional water at 3 (three) levels, they are 0, 20 and 40 % from seed palm. The third factor is saving time with 3 (three) levels, they are 0, 24 and 48 hours.. According to this research grade, fatty acid was obtained 100 %. This optimum condition was obtained by blended residual palm sorted without fermentation (0 day ) or direct process and additional water 20 %.
Key words : residual palm sorted, fatty acid, lipase enzyme, enzymatic.
KATA PENGANTAR
Pujian hanya berhak disampaikan kepadaNya, karena hanya Allah SWT yang
sanggup menyangga segala macam pujian yang ditujukan kepadaNya. Teriring pula
ucapan Alhamdulillahi rabbil’alamin atas segala karunianya sehingga penyusunan
tesis ini yang bertujuan untuk memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan
pendidikan Magister Teknik Kimia. Tulisan ini berjudul ”Pemanfaatan Buah sawit
sisa sortiran sebagai sumber bahan baku asam lemak”.
Dalam menyusun tesis ini, saya menerima banyak bantuan, bimbingan dan
fasilitas dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih
kepada :
1. Rektor Universitas Sumatera Utara, Prof. dr. Chairuddin P. Lubis, DTM&H,
SpA(K) atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk
mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister.
2. Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara yang dijabat oleh
Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa B., MSc atas kesempatan menjadi mahasiswa
Program Magister pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
3. Prof.Dr.Ir.Setiaty Pandia, Ketua Program Studi Magister Teknik Kimia,
Universitas Sumatera Utara sekaligus sebagai Ketua Komisi Pembimbing
4. Dr.Halimatuddahliana,ST,MSc selaku sekretaris Program studi Magister
Teknik Kimia Universitas Sumatera Utara
5. Rondang Tambun, ST, MT selaku anggota komisi Pembimbing
6. Baristand Industri Medan yang telah memfasilitasi penulis
7. Staf pengajar Magister Teknik Kimia, Universitas Sumatera Utara
8. Kedua orang tua penulis untuk setiap dukungannya
9. Istri dan kedua anak penulis dalam motivasi serta setiap dukungannya
10.Seluruh rekan Magister Teknik Kimia, Universitas Sumatera Utara
Sesudahnya saya memohon nasehat dan saran, karena tulisan ini
membutuhkan banyak perbaikan untuk perkembangannya. Mudah mudahan Allah
membukakan hati saya untuk mau menerima nasehat dan mampu melaksanakannya.
Medan, Pebruari 2009
Penulis
RIWAYAT HIDUP
Nama Lengkap : Justaman Arifin Karo Karo
Tempat/ Tanggal Lahir : Guru Kinayan, 11 Januari 1964
Agama : Islam
Riwayat Pendidikan : Tahun 1972 masuk SD Swasta Sapta Marga, Selayang,
Kec. Selesai Kab. Langkat Sumut, tamat tahun 1977
dan melanjutkan ke SMP Nasional Selayang Kec.
Selesai dan tahun 1978 pindah ke SMP Persiapan
Selesai dan Ujian akhir di SMP Negeri 2 Binjai, tamat
tahun 1981 dan kemudian tahun 1981 melanjutkan ke
SMA Negeri 2 Medan, tamat tahun 1984. Tahun 1984
masuk ke Fakultas Teknik Unsyiah (Universitas Syiah
Kuala) Banda Aceh Jurusan Teknik Kimia dan tamat
Sarjana Teknik Kimia (S1), Universitas Syiah Kuala,
Banda Aceh, tahun 1990 dengan menyelesaikan
Penelitian serta Tugas Akhir di ITS (Institut Teknologi
Sepuluh Nopember) Surabaya, tamat tahun 1990. Dan
kemudian tahun 1997 mengikuti pendidikan Waste
Water Treatment, di Universitas Bremen, Jerman,
tamat tahun 1998. Pada tahun 2006, penulis
memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan
Pascasarjana di Sekolah Pascasarjana Universitas
Sumatera Utara pada Program Studi Magister Teknik
Kimia.
Riwayat Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (sebagai Tenaga peneliti) pada
Balai Litbang Industri Banda Aceh, dari tahun 1991 s/d
tahun 2000 kemudian Pegawai Negeri Sipil (sebagai
Tenaga peneliti) di Baristand Industri Medan dari tahun
2000 s/d sekarang
Status keluarga : Kawin
Nama istri : Risma, SE
Jumlah Anak : 2 (dua) orang, Anak Nomor 1 (satu) bernama Lailatul
Fitri Br Karo, 04-03-1995, Kelas 2 (dua) SMPN 1
Medan, Anak Nomor 2 (dua), bernama M. Syawal
Karo Karo, 30-12-2000, Kelas 2 (dua) SDN 84 Helvetia
Medan
Nama Orang Tua
Ayah : S. Burhanuddin Karo Karo
Ibu : Hamidah Br Sembiring Gurukinayan
Jumlah saudara : 6 (enam) bersaudara dan penulis anak nomor 3 (tiga).
DAFTAR ISI
Halaman
ABSTRAK ... i
ABSTRACT ... ii
KATA PENGANTAR ... iii
RIWAYAT HIDUP ... v
DAFTAR ISI ... vii
DAFTAR TABEL ... ix
DAFTAR GAMBAR ... x
DAFTAR LAMPIRAN ... xi
I. PENDAHULUAN ... 1
1.1 Latar Belakang ... 1
1.2 Perumusan Masalah ... 4
1.3 Tujuan Penelitian ... 5
1.4 Manfaat Penelitian ... 5
1.5 Ruang Lingkup Penelitian ... 6
II . TINJAUAN PUSTAKA ... 8
2.1. Kelapa Sawit ... ... 8
2.2. Asam Lemak ... ... 9
2.3. Enzim ... ... 14
2.4. Perkembangan Asam Lemak pada Buah Kelapa Sawit... ... 16
2.5. Kinetika Reaksi ... ... 19
III. METODOLOGI PENELITIAN ... 24
3.1. Tempat dan Waktu ... 24
3.2. Bahan Penelitian ... 24
3.3. Alat-alat Penelitian ... 24
3.4. Rancangan Percobaan ... 25
3.5. Prosedur Percobaan ... 25
3.6. Pengolahan Data ... 28
3.7. Pengujian Hasil Percobaan ... 28
3.8. Jadwal Penelitian ... 29
IV. HASIL DAN PEMBAHASAAN ... 30
4.1. Hasil Penelitian ... 30
4.2. Pembahasan ... 34
V. KESIMPULAN DAN SARAN ... 52
5.1 Kesimpulan ... 52
5.2 Saran ... 52
DAFTAR PUSTAKA ... 54
DAFTAR TABEL
Nomor Judul Halaman
1 Persentase Kandungan Asam Lemak pada beberapa Minyak Nabati ... 10
2 Industri Asam Lemak di Indonesia ... 10
3 Kadar Asam lemak bebas pada minyak setelah penumbukan ... 17
4 Kadar Asam lemak bebas pada perikarp yang telah dilukai dan ditumbuk 18 5 Harga Km beberapa Enzim ... 23
6 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penelitian ... 29
7 Perolehan asam lemak untuk buah sawit sisa sortiran tidak dilukai ... 30
8 Perolehan asam lemak untuk buah sawit sisa sortiran dilumatkan ... 30
9 Perolehan asam lemak untuk buah sawit sisa sortiran dimemarkan ... 31
10 Perolehan asam lemak jenuh untuk buah sawit sisa sortiran tidak dilukai 31 11 Perolehan asam lemak jenuh untuk buah sawit sisa sortiran dilumatkan . 32 12 Perolehan asam lemak jenuh untuk buah sawit sisa sortiran dimemarkan 32
13 Perolehan asam lemak tidak jenuh untuk buah sawit tidak dilukai ... 33
14 Perolehan asam lemak tidak jenuh untuk buah sawit dilumatkan ... 33
15 Perolehan asam lemak tidak jenuh untuk buah sawit dimemarkan ... 33
16 Kadar air dan densitas asam lemak untuk waktu hidrolisa 0 (nol) hari dengan berbagai variabel penambahan air dan perlakuan terhadap buah sawit sisa sortiran ... 34
DAFTAR GAMBAR
Nomor Judul Halaman
1 Pembuatan Asam lemak dari Kelapa Sawit ... 14
2 Pengaruh konsentrasi Enzim terhadap kecepatan reaksi ... 20
3 Pengaruh konsentrasi substrat terhadap kecepatan reaksi ... 21
4 Grafik persamaan Lineweaver-Burk ... 22
5 Diagram Alir Percobaan... 27
6 Perolehan asam lemak untuk buah sawit sisa sortiran tidak dilukai ... 35
7 Perolehan asam lemak jenuh untuk buah sawit sisa sortiran tidak dilukai 36
8 Perolehan asam lemak tidak jenuh untuk buah sawit tidak dilukai ... 38
9 Perolehan asam lemak untuk buah sawit sisa sortiran dilumatkan ... 39
10 Perolehan asam lemak jenuh untuk buah sawit sisa sortiran dilumatkan . 41 11 Perolehan asam lemak tidak jenuh untuk buah sawit sortiran dilumatkan 42 12 Perolehan asam lemak untuk buah sawit sortiran dimemarkan ... 44
13 Perolehan asam lemak jenuh untuk buah sawit sortiran dimemarkan ... 45
14 Perolehan asam lemak tidak jenuh untuk buah sawit dimemarkan ... 46
DAFTAR LAMPIRAN
Nomor Judul Halaman
A. Data Pengamatan Perolehan Asam Lemak ... 57
B. Tahap-tahap Percobaan ... 59
C. Hasil Analisa Asam Lemak dengan metoda GC ... 61
D. Pohon Kelapa Sawit ... 88
E. Pohon Industri Turunan Minyak Sawit ... 89
I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kelapa sawit merupakan salah satu sumber minyak nabati yang sangat
potensial khususnya sebagai oleopangan dan oleokimia. Sebagai bahan oleopangan,
minyak kelapa sawit umumnya digunakan untuk minyak goreng, margarin, vanaspati
dan pengganti lemak cokelat (cocoa butter), sedangkan sebagai bahan nonpangan
(oleokimia) dapat berupa asam lemak, gliserin, sabun, deterjen, pelumas, plastisizer,
kosmetik dan alternatif bahan bakar diesel.
Dengan memperhatikan letak geografis, sumber daya lahan serta sumber daya
manusia, maka kelapa sawit dapat menjadi suatu komoditi andalan untuk agribisnis di
Indonesia. Pada umumnya di Indonesia, produk utama dari kelapa sawit ini adalah
untuk minyak goreng (makan), dan para produsen minyak sawit biasanya menjual
produknya dalam bentuk minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) atau
langsung menjualnya dalam bentuk tandan buah segar (TBS). Melihat hal ini, perlu
diberi perhatian terhadap peningkatan nilai tambah minyak sawit dengan merubahnya
menjadi oleopangan dan oleokimia. Pada akhir-akhir ini oleopangan dan oleokimia
dari bahan nabati lebih disenangi para konsumen dibandingkan dengan oleopangan
dan oleokimia yang berasal dari hewan atau bahan sintetik, karena sifatnya yang
mudah terurai di lingkungan oleh mikroorganisme dan harganya yang lebih murah.
Salah satu produk oleokimia yang dapat diperoleh dari minyak sawit adalah
pada tahun-tahun mendatang, karena asam lemak ini banyak dipakai pada berbagai
industri seperti industri ban, kosmetik, plastik, cat, farmasi, deterjen dan sabun. Oleh
karena itu, perlu dilakukan suatu langkah dalam pemenuhan asam lemak di Indonesia.
Selama ini penyebab utama kurangnya minat para pengusaha untuk memproduksi
asam lemak adalah karena proses pembuatnya yang dinilai tidak ekonomis, dan juga
karena minyak sawit pada saat ini sudah memiliki pangsa pasar yang baik sebagai
bahan minyak makan (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera
Utara, 2007).
Dari data lapangan PKS setelah dilakukan penyortiran TBS (tandan Buah
segar) diperoleh buah sawit sisa sortiran lebih kurang sebesar 7-10 % dari kapasitas
giling PKS (Pabrik Kelapa Sawit) yang besarnya 30 ton TBS perjam, sehingga buah
sawit sortiran yang dihasilkan sebanyak 2-3 ton per jam (PKS Padang Brahrang,
Selesai, PTPN II, 2005). Selama ini buah sawit sortiran yang digunakan di PKS
mempengaruhi kualitas CPO yang dihasilkan. Jadi CPO yang dihasilkan bermutu
rendah yang akhirnya mempengaruhi biaya proses dan nilai harga jual dari CPO di
pasaran Nasional dan Internasional sehingga merugikan pihak manajemen PKS dan
petani. Selain itu buah sawit sortiran juga banyak terdapat di lahan petani akibat dari
panen yang terlambat serta akibat dari pengangkutan yang terlambat.
Pihak manajemen PKS dalam usahanya menangani buah sawit sortiran ini
adalah mempercepat waktu tranportasi dari lapangan ke PKS dan penyortiran yang
selektif. Buah sawit sortiran ini terjadi akibat dari panen terlalu dini, panen terlalu
sehingga buah sawit sortiran tidak dapat dihindari terutama TBS yang berasal dari
perkebunan sawit rakyat. Selama ini buah sawit sortiran dijual kepihak lain dengan
harga murah sebesar 30-40 % dari harga TBS segar (PKS Padang Brahrang, Selesai,
PTPN II, 2005). Jika hal ini terus berlanjut yang akhirnya akan dapat merugikan
pihak petani maupun pihak PKS. Selain itu dewasa ini isu mengenai industri
oleokimia yang ramah lingkungan sangat populer akibat banyaknya produk turunan
dari buah sawit yang siap untuk menggeser produk petrokimia yang kurang ramah
lingkungan. Oleh karena itu perlu dicari bahan alternatif dan proses yang
menghasilkan oleokimia yang tidak merusak lingkungan, dengan kata lain yang
mudah terurai di lingkungan.
Selama ini asam lemak diperoleh dengan cara menghidrolisa minyak sawit
pada suhu tinggi yaitu 240-260 oC dan tekanan 45-50 bar ataupun secara enzimatik.
Ditinjau dari segi teknik dan ekonomi, kedua cara ini dinilai kurang efisien karena
memerlukan terlebih dahulu satu pabrik pengolahan untuk memproduksi CPO
sebagai bahan bakunya. Untuk mengatasi hal ini, maka dilakukan penelitian proses
pembuatan asam lemak alternatif yang lebih murah, yaitu memproduksi secara
langsung asam lemak dari buah kelapa sawit sisa sortiran, dengan cara mengaktifkan
enzim lipase yang terdapat pada buah sawit sisa sotiran.
Dari penelitian Tambun (2002), asam lemak dapat diperoleh melalui hidrolisa
buah sawit segar secara langsung dengan mengaktifkan enzim lipase, yang terdapat
pada buah kelapa sawit segar. Penelitian ini mengkaji alternatif proses yang akan
kelapa sawit secara enzimatik, yaitu dengan cara mengaktifkan enzim lipase yang
terdapat pada buah kelapa sawit segar. Hasil yang diperoleh pada penelitian tersebut
adalah dengan tingkat konversi hidrolisa sampai 54,446 % dalam waktu 24 jam. Hasil
ini dicapai pada suhu kamar 28 oC, tekanan 1 atm dan penambahan air 40% dari
massa mesokarp.
Melihat kondisi ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk
memanfaatkan buah sawit sisa sortiran sebagai bahan baku asam lemak. Penelitian
ini dilakukan mencakup teknologi proses pembuatan asam lemak dengan cara
mengaktifkan enzim lipase yang terkandung pada buah sawit. Adapun manfaatnya
adalah sebagai informasi dan untuk dapat diterapkan dan diaplikasikan dalam skala
industri sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dari buah sawit sisa sortiran,
tumbuhnya industri pembuatan asam lemak, dan dapat menambah nilai ekonomis dari
buah sawit sisa sortiran serta bahan alternatif untuk menghasilkan produk asam lemak
yang memenuhi syarat SNI (Standar Nasional Indonesia).
1.2 Perumusan Masalah
Selama ini produksi asam lemak dari kelapa sawit diperoleh dengan cara
hidrolisa minyak sawit dengan menggunakan air pada suhu sekitar 240 oC – 260 oC
dan tekanan 45 - 50 bar. Cara lain yang digunakan adalah dengan menghidrolisa
minyak sawit secara enzimatik, yaitu dengan menggunakan enzim lipase. Ditinjau
dari segi ekonomi dan teknik, kedua cara ini dinilai kurang efesien karena untuk
pembuatan asam lemak ini diperlukan terlebih dahulu satu pabrik pengolahan buah
Dari uraian latar belakang di atas dan untuk mengatasi hal ini, maka perlu
dikaji suatu alternatif proses pembuatan asam lemak yang lebih murah, maka dapat
dirumuskan permasalahan penelitian ini yaitu, seberapa besar kemungkinan buah
sawit sisa sortiran dapat dimanfaatkan sebagai alternatif sumber bahan baku asam
lemak dengan proses hidrolisa langsung menggunakan enzim lipase yang ada pada
buah sawit itu sendiri.
1.3 Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan :
1. Untuk mengetahui kondisi terbaik pada rentang penelitian (waktu
penyimpanan atau waktu hidrolisa, penambahan air dan perlakuan
buah pada proses hidrolisa langsung dengan menggunakan bahan baku
buah sawit sisa sortiran untuk menghasilkan produk asam lemak.
2. Untuk mengetahui jumlah asam lemak yang dihasilkan dan jenis asam
lemak serta komposisinya pada kondisi operasi terbaik.
1.4 Manfaat Penelitian
1. Adapun manfaat penelitian ini sebagai informasi tentang teknologi
alternatif proses dalam mengolah buah sawit sisa sortiran untuk
menghasilkan produk asam lemak.
2. Sebagai informasi bagi dunia industri yang menggunakan bahan baku
1.5Ruang Lingkup Penelitian 1.5.1 Skala yang Digunakan
Percobaan dan pengujian dilakukan dalam skala laboratorium sesuai dengan
parameter-parameter yang telah ditetapkan dan variabel percobaan yang dilakukan
seperti di bawah ini. Sampel (buah sawit) yang digunakan diambil dari petani sawit di
lapangan. Sampel untuk percobaan adalah buah sawit brondolan yaitu buah sawit
yang telah masak dan sudah jatuh ditanah dan mulai membusuk.
1.5.2 Variabel Percobaan dan Parameter Uji Variabel yang diamati terdiri dari :
a. Variabel tetap
Temperatur : 28 oC (temperatur kamar)
Tekanan : 1 atm
b. Variabel tidak tetap (berubah)
Penambahan air : 0 %, 20%, dan 40 % berat buah sawit sisa sortiran
Perlakuan buah : buah sawit tanpa pelukaan, buah sawit dilumatkan
dan buah sawit dimemarkan
Waktu reaksi : 0 hari, 1 hari dan 2 hari
1.5.3 Metoda yang Digunakan
Penelitian ini menggunakan metode hidrolisa secara langsung buah kelapa
sawit sortiran dengan memanfaatkan dan mengaktifkan enzim lipase. Enzim lipase
tersebut sebagai biokatalisator yang terdapat pada buah kelapa sawit, merupakan
suatu alternatif proses yang dilakukan untuk memperoleh asam lemak. Enzim lipase
yang terdapat pada buah kelapa sawit diaktifkan dalam menghidrolisa trigleserida
menjadi asam lemak dan gliserol. Produk asam lemak yang diperoleh dianalisa
dengan instrumen Gas Chromatografi (GC). Standar produk asam lemak yang
digunakan adalah Standar Nasional Indonesia untuk analisa asam lemak bebas, kadar
II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Kelapa Sawit
Tanaman kelapa sawit (Elaeis guinnensis Jacq) adalah salah satu dari
beberapa tanaman golongan palm yang dapat menghasilkan minyak dan asam lemak.
Kelapa sawit dikenal terdiri dari empat macam tipe atau varietas yaitu type
Macrocarya, Dura, Tenera dan Pisifera. Masing-masing tipe dibedakan berdasarkan
tebal tempurung. Warna daging buah adalah putih kuning diwaktu masih muda dan
berwarna jingga setelah buah menjadi matang. Daerah penanaman kelapa sawit di
Indonesia adalah daerah Jawa Barat, Lampung, Riau, Sumatera Barat, Sumatera
Utara, Aceh dan tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Negara penghasil kelapa
sawit selain Indonesia adalah Malaysia, Nigeria dan Amerika Tengah. Saat ini
Indonesia penghasil buah sawit nomor satu di dunia kemudian diikuti Malaysia (Pusat
Penelitian Kelapa Sawit Medan, 2007).
Bahan untuk mendapatkan minyak dan asam lemak adalah buah sawit. Buah
yang baik berasal dari tandan buah yang sudah matang sempurna. Di stasiun
penggilingan buah dilakukan sortasi tandan buah yaitu untuk memisahkan tandan
buah berdasarkan fraksi. Tandan buah yang telah dipanen sebaiknya tidak mengalami
masa penyimpanan. Dengan kata lain bahwa tandan buah setelah dipanen segera
diolah. Lama penyimpanan sebaiknya tidak lebih dari dua hari, sebab penyimpanan
yang lebih lama akan merusak minyak. Dalam hal ini tandan buah segar akan makin
banyak mengandung asam lemak.
2.2 Asam Lemak
Asam lemak disebut juga asam alkanoat atau asam karboksilat. Secara umum
rumus molekulnya adalah CnH2nO2 dan rumus umumnya adalah R-COOH dan rumus
bangunnya adalah mempunyai gugus fungsi R-C-OH. Klasifikasi asam lemak terdiri
dari 2 bagian : yaitu asam lemak jenuh (saturated) dan asam lemak tak jenuh
(unsaturated). Asam lemak jenuh adalah asam lemak yang atom karbonnya memiliki
ikatan jenuh (ikatan tunggal) dan asam lemak tak jenuh yaitu asam lemak yang atom
karbonnya memiliki ikatan rangkap.
Asam lemak diperoleh dari tumbuh-tumbuhan dan hewan seperti kelapa sawit,
kelapa, jagung, kedelai, biji jarak dan biji bunga matahari. Sedangkan asam lemak
sintetik dapat diperoleh dari industri petrochemical. Dalam penggunaannya, asam
lemak memegang peranan penting pada industri kimia oleo, seperti pada indsutri ban,
sabun, detergent, alkohol lemak, polimer, amina, kosmetik dan farmasi.
Kandungan asam lemak pada beberapa sumber minyak nabati dapat dilihat
Tabel 1 Persentase Kandungan Asam lemak pada beberapa minyak nabati
Di Indonesia sudah ada beberapa industri asam lemak yang didirikan, yang
terbesar di pulau Sumatera khususnya di Sumatera Utara dan selainnya di pulau
Jawa. Data mengenai nama perusahaan, lokasi dan kapasitas produksi dari industri
asam lemak di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:
Tabel 2 Industri Asam lemak di Indonesia
No Nama Perusahaan Lokasi Kapasitas Produksi
(Tahun 2007) 1 PT. Aribhawana Utama
Asam lemak dapat juga dibuat dari buah kelapa sawit tanpa terlebih dahulu
mengolahnya menjadi minyak kelapa sawit, dengan proses hidrolisa langsung buah
sawit sortiran dengan bantuan enzim lipase sebagai biokatalisator yang terdapat pada
buah kelapa sawit. Hidrolisa dengan mengaktifkan enzim lipase yang terdapat pada
buah kelapa sawit jika ditinjau dari segi ekonomi dan teknik sangat baik sekali,
karena sesuai tujuannya yaitu untuk menghasilkan asam lemak dan gliserol, maka
proses ini tidak perlu lagi melakukan pengolahan terlebih dahulu terhadap TBS
(tandan buah segar) menjadi minyak CPO (Crude Palm Oil).
Hidrolisa minyak dengan H2O merupakan metode yang umum dipakai untuk
menghasilkan asam lemak. Reaksi ini akan menghasilkan gliserol sebagai produk
samping. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut :
CH2RCOO CH2OH
CHRCOO + 3 H2O ←⎯→ CHOH + 3 RCOOH
CH2RCOO CH2OH
Trigliserida Air Gliserol Asam lemak
Reaksi ini dilakukan pada suhu 240 oC – 260 oC dan tekanan 45 – 50 bar.
Pada proses ini derajat pemisahan mampu mencapai 99%. Hal yang membuat proses
ini kurang efesien adalah karena proses ini memerlukan energi yang cukup besar dan
komponen-komponen minor yang ada di dalamnya seperti -karoten mengalami
kerusakan.
Hidrolisa minyak secara enzimatik dilakukan dengan cara immobilized enzim
dibandingkan dengan proses hidrolisa minyak dengan H2O pada suhu dan tekanan
tinggi. Pada proses ini, kekurangannya adalah pemakaian enzim lipase yang sangat
mahal. Reaksi yang terjadi pada proses hidrolisa secara enzimatik adalah sebagai
berikut :
CH2RCOO CH2OH
lipase
CHRCOO + 3 H2O ←⎯→ CHOH + 3 RCOOH
CH2RCOO CH2OH
Trigliserida Air Gliserol Asam lemak
Reaksi ini dilakukan pada kondisi optimum aktifitas enzim lipase yaitu pada
suhu 35 oC dan pH 4,7-5. Derajat pemisahan pada proses ini mampu mencapai 90%.
Hidrolisa secara langsung buah kelapa sawit sortiran dengan mengaktifkan
enzim lipase sebagai biokatalisator yang terdapat pada buah kelapa sawit merupakan
suatu alternatif proses yang dapat dilakukan untuk memperoleh asam lemak. Enzim
lipase yang terdapat pada buah sawit akan membantu air dalam menghidrolisa
trigleserida menjadi asam lemak dan gliserol.
Jika proses ketiga dibandingkan dengan proses pertama dan kedua, memiliki
kelebihan dan kekurangan, antara lain :
1. Hidrolisa minyak sawit dengan air pada suhu dan tekanan tinggi mampu
menghasilkan pemisahan asam lemak dengan gliserol sampai 99%, tetapi
proses ini menggunakan minyak yang telah diolah dari tandan, disamping itu
juga dapat merusak komponen-komponen minor yang dapat terdapat dalam
2. Pada Proses hidrolisa minyak secara enzimatik, kebutuhan energi relatif kecil,
kekurangan dari proses ini adalah harga enzim lipase yang sangat mahal.
Pemakaian enzim lipase secara berulang-ulang dapat dilakukan, tetapi hal ini
memerlukan tambahan proses untuk mendapatkan enzim lipase yang
mempunyai kemampuan yang sama seperti semula. Di samping itu, karena
sifat enzim yang sangat sensitif terhadap temperatur dan pH, maka
kemungkinan kerusakan pada enzim lipase secara tiba-tiba tentu saja dapat
terjadi, sementara pemenuhan enzim lipase ini relatif sulit dilakukan karena
faktor biaya dan supplier enzim lipase yang terbatas di pasaran.
3. Hidrolisa dengan mengaktifkan enzim lipase yang terdapat pada buah kelapa
sawit jika ditinjau dari segi ekonomi dan teknik sangat baik sekali, karena
sesuai dengan tujuannya yaitu untuk menghasilkan asam lemak dan gliserol,
maka proses ini tidak perlu lagi melakukan pengolahan terlebih dahulu
terhadap tandan buah segar menjadi minyak. Tetapi, sampai saat ini penelitian
di bidang pemanfaatan buah sawit ini belum banyak yang dipublikasikan.
Diagram proses tentang pembuatan asam lemak dari bahan baku buah kelapa
Buah
Gambar 1 Pembuatan asam lemak dari kelapa sawit
2.3 Enzim
Suatu sel tumbuhan mengandung lebih kurang 5-50x108 molekul enzim.
Enzim-enzim ini masing-masing bergaris tengah antara 20-100 A0, berat molekunya
10.000 sampai beberapa juta Dalton, dan tersusun dari asam-asam amino sebanyak
100 sampai 10.000 buah.
Enzim atau disebut juga fermen merupakan suatu golongan biologis yang
sangat penting dari protein. Enzim disebut biokatalisator karena semua perombakan
zat makanan dalam organisme hanya dapat terjadi jika didalamnya terdapat enzim.
Zat-zat yang diuraikan oleh enzim digolongkan sebagai substrat. Fungsi enzim pada
umumnya dapat merombak sesuatu zat dalam bentuk yang lebih kecil untuk
kemudian diuraikan menjadi zat-zat yang siap diresorpsi.
Jika suatu enzim mengalami perubahan dalam bentuknya, misalnya denaturasi
(perusakan), maka struktur kimianya sebagai protein atau proteida akan mengalami
masih terdapat lengkap. Bagian enzim sebagai pembawa protein disebut apo-enzim
dan yang bersifat katalitik disebut ko-enzim.
Dalam ko-enzim terdapat daya kerja yang spesifik, karena itu enzim disebut
juga biokatalisator yang spesifik atau katalisator biospesifik. Suatu ko-enzim dapat
mengkatalisi suatu substrat secara berulang kali. Oleh sebab itu enzim terdiri atas
pembawa protein (koloidal) dan gugus prostetis atau ko-enzim, maka reaksi kimianya
dapat ditulis sebagai berikut :
apo-enzim + ko-enzim holo-enzim
Ko-enzim sebagai golongan yang aktif secara kimiawi bersifat katalitik dan
dapat dirubah. Di sini sifat katalitiknya berlainan, seperti yang kita ketahui bahwa
status katalisator tidak mengalami perubahan dalam reaksinya, tetapi pada
biokatalisator terjadi perubahan, tetapi setelah itu terdapat reaksi yang sekunder
dengan enzim kedua, sehingga keadaan semula dipulihkan kembali. Pembawa protein
bertanggung jawab terhadap berlangsungnya daya komponen ko-enzim, yaitu pusat
semua aktifitas dan ko-enzim tersebut merupakan organ pelaksana terjadinya
perubahan-perubahan (reaksi) dalam metabolisma. Molekul-molekul yang mengalami
perubahan ini adalah substrat. Protein (pembawa) menentukan molekul-molekul yang
mana dapat bereaksi dengan ko-enzim sebagai partner reaksinya.
Enzim dapat diklasifikasikan atas beberapa bagian, antara lain:
1. Esterase : pankreatik lipase, liver esterase, rikinos lipase, kloropillase,
phospatases, azolesterase.
2. Proteinase dan Peptidase : pepsin, tripsin, erepsin, rennin, papain,
3. Amidase : urease, arginase, purine amidase.
4. Karbohidrase : sukrase, emulsin, amilase
5. Oksidase : dehidrogenase, katalase, peroksidase, tirosinase, lakkase,
indophenol oksidase, urikase, lukiferase (Wirahadikusumah M, 1985).
Enzim yang sangat berpengaruh dalam pembentukan asam lemak dan gliserol
ádalah enzim lipase. Enzim lipase banyak terdapat pada bijian-bijian yang
mengandung minyak, seperti kacang kedelai, biji jarak, kelapa sawit, kelapa, biji
bunga matahari, biji jagung dan juga terdapat dalam daging hewan dan dalam
beberapa jenis bakteri. Dalam buah kelapa sawit, selain enzim lipase terdapat juga
enzim oksidase, yaitu enzim peroksidase. Enzim lipase yang tedapat pada kelapa
sawit ini adalah ricinus lipase yang cara kerjanya sangat mirip dengan pankreatik
lipase. Enzim lipase ini bertindak sebagai biokatalisator yang menghidrolisa
trigliserida menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Enzim peroksidase berperan
dalam proses pembentukan peroksida yang kemudian dioksidasi lagi dan pecah
menjadi gugusan aldehid dan keton. Senyawa keton ini juga dioksidasi lagi akan
pecah menjadi asam.
2.4 Perkembangan Asam Lemak Pada Buah Kelapa Sawit
Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan asam lemak pada minyak
kelapa sawit telah diteliti, dan penemuan yang mendasari penelitian-penelitian
1. Penemuan Fickenday (1910), yang menyatakan bahwa hidrolisa minyak
secara enzimatik dipengaruhi oleh lipoid yang terdapat di dalam minyak.
2. Penemuan Loncin (1952), yang menyatakan bahwa hidrolisa autokatalitik
secara spontan dapat terjadi pada minyak tumbuh-tumbuhan .
Pada minyak kelapa sawit, asam lemak bebas dapat terbentuk karena adanya
aksi mikroba atau karena hidrolisa autokatalitik oleh enzim lipase yang terdapat pada
buah sawit. Hasil penelitian Fickenday (1910) yang menyatakan adanya pengaruh
lipoid pada buah sawit ditunjukkan pada Tabel 3 berikut :
Tabel 3 Kadar asam lemak bebas pada minyak setelah penumbukan
Kadar asam lemak bebas (%) Perolehan Minyak setelah Test 4b setelah/ 24 jam Test 4c setelah/ 48 jam
43,1
Ket : A = buah segar yang ditumbuk tanpa pemanasan
B = buah ditumbuk setelah dipanaskan pada suhu, 90 0C – 100 0C
Menurut Olie (1988), hal yang harus diingat bahwa pada pelaksanaan
penelitian ini, perikarp buah sawit ditumbuk dan dikupas dan selanjutnya dipisahkan
dari inti, tanpa adanya pemanasan terlebih dahulu untuk mengeluarkan minyak.
Pengaruh waktu proses hidrolisa minyak sawit terhadap perolehan kadar asam lemak
bebas pada perikarp yang telah dilukai dan ditumbuk diperlihatkan pada Tabel 4
Tabel 4 Kadar asam lemak bebas pada perikarp yang telah dilukai dan ditumbuk
Waktu hidrolisa Kadar asam lemak bebas, (%) Segera mungkin
Ada 2 pendapat yang menyatakan pengaruh mikroorganisme pada buah
sawit :
1. Fickenday (1910), menyatakan bahwa keasaman akan meningkat dengan
cepat pada perikarp buah yang dilukai, jika buah ini diletakkan pada
tempat terbuka dan mengandung jamur.
2. Wilbaux (1980) menyatakan bahwa jamur dari tipe Oospora
(kemungkinan Geotrichium candidum) terbukti mampu meningkatkan
kandungan asam lemak bebas pada buah sawit segar dari 0,1 % menjadi
6,4 % dalam waktu 60 jam
Jika hasil penelitian ini dihubungkan dengan penelitian Loncin (1952), maka
dapat disimpulkan bahwa hidrolisa karena adanya aktifitas mikroba dapat terjadi
secara berdampingan dengan hidrolisa secara autokatalitik. Hal ini kemungkinan
dapat terjadi terutama jika kondisi optimum dari mikroba dan enzim lipase dapat
dipertahankan, seperti :
a. temperatur harus dibawah 50 0C.
Indikasi dari aktifitas enzim lipase ini dapat diketahui dengan mengukur
kenaikan bilangan asam. Enzim lipase ini sangat aktif, bahkan pada kondisi yang
baik, minyak sawit jarang diproduksi dengan kandungan asam lemak bebas dibawah
2% atau 3%, dan pada kondisi optimum, kandungan asam lemak pada minyak bisa
mencapai 60% atau lebih. Enzim lipase akan mengalami kerusakan pada suhu 60 0C,
dan aktifitas enzim ini lambat pada buah yang baru dipanen, tetapi aktifitasnya akan
lebih cepat meningkat apabila buah mengalami luka. Buah yang baru dipanen dan
dilepas dari tandannya pada umumnya telah mengalami luka, tetapi hal ini tidak
cukup untuk memberi peluang berkembangnya aktifitas enzim lipase secara optimum.
Salah satu perlakuan secara mekanik yaitu melukai buah sawit sisa sortiran.
2.5 Kinetika Reaksi
Pada reaksi hidrolisa ini, reaksi dapat terjadi secara irreversible karena pada
percobaan ini kontak antara substrat dan enzim selalu dapat terjadi karena adanya
bantuan perlakuan pengadukan. Hal ini dapat terjadi karena sampel pada percobaan
ini adalah campuran antara serat dengan minyak, sehingga proses pengadukan dapat
dilakukan. Disamping itu kadar air pada buah ataupun air yang ditambahkan akan
membantu proses pengadukan sehingga kontak antara substrat dengan enzim dapat
terjadi dengan baik. Reaksi balik pada percobaan ini dapat dianggap tidak terjadi
karena kadar air pada produk yang dihasilkan sangat besar, dimana kandungan air
yang sangat besar ini bergabung dengan alkohol (sweet water atau gliserol) sehingga
baik. Hal inilah yang mendasari bahwa pada penentuan kinetika reaksi, konsentrasi
air sebagai salah satu reaktan dapat dianggap mengikuti reaksi orde nol (air dianggap
selalu tersedia dalam jumlah berlebih). Sebagai hasilnya, persamaan laju reaksi akan
mengikuti orde satu, walaupun pada kenyataannya reaksinya adalah bimolekular. Jadi
pada reaksi ini laju reaksi tergantung pada konsentrasi substrat, bukan pada
konsentrasi air.
Pada penentuan kinetika secara enzimatis ini, konsentasi substrat dan
konsentrasi produk yang diperoleh sudah dapat melukiskan mekanisme kinetika
reaksi yang terjadi, dan mekanisme ini dapat diselesaikan sesuai dengan persamaan
Michaelis-Menten.
Pada reaksi ini, kecepatan reaksi bergantung pada konsentrasi enzim yang berperan
sebagai katalisator. Pada Gambar 2 terlihat hubungan antara konsentrasi enzim
dengan kecepatan reaksi apabila konsentrasi substrat berlebihan. Di sini dapat dilihat
bahwa banyaknya substrat ditransformasikan sesuai dengan tingginya konsentrasi
Tetapi jika konsentrasi enzim yang digunakan tetap, sedangkan konsentrasi
substrat dinaikkan maka hubungan yang didapat adalah seperti pada Gambar 2.3.
Di sini dapat dilihat bahwa pada penambahan pertama kecepatan reaksi naik dengan
cepat, tetapi jika penambahan substrat dilanjutkan maka tambahan kecepatan mulai
menurun sampai pada suatu ketika tidak ada tambahan kecepatan lagi.
Michaelis menyatakan bahwa rekasi yang dikatalisis oleh enzim pada
berbagai konsentrasi substrat mengalami 2 fase, yaitu jika konsentrasi substrat masih
rendah, daerah yang aktif pada enzim tidak semuanya terikat dengan susbtrat (fase I),
dan jika jumlah molekul substrat meningkat maka daerah yang aktif terikat
seluruhnya oleh substrat, dan pada saat ini enzim sudah bekerja dengan kapasitas
penuh. Pengaruh konsentrasi substrat terhadap kecepatan reaksi diperlihatkan pada
Gambar 3 berikut.
V, Kecepatan
Kec. Maksimum
Vmax Kinetik orde nol (fase II) Kinetik campuran orde satu dan nol
v/2
Kinetik orde satu (fase I)
Km, Konsentrasi Substrat
Gambar 3 Pengaruh Konsentrasi Substrat terhadap Kecepatan Reaksi
Dibandingkan dengan reaksi enzimatik yang lain yaitu dengan cara
Harga Km yang besar ini menunjukkan bahwa minyak sawit dan enzim lipase tidak
berikatan secara kuat. Penyebab dari pada hal ini adalah karena adanya inhibisi oleh
produk yang terbentuk, sehingga aktifitas enzim lipase untuk mengkatalisa minyak
menjadi asam lemak menjadi menurun/terganggu.
Untuk menguji harga Km yang diperoleh, dapat dilakukan dengan
menggunakan persamaan Lineweaver-Burk.
Kalau dilihat kembali persamaan : v =
m
Persamaan tersebut identik dengan persamaan garis lurus : y = ax + b, dimana
grafiknya diperlihatkan pada Gambar 4 berikut :
Gambar 4 Grafik Persamaan Lineweaver-Burk
Hasil yang diperoleh dari persamaan Lineweaver-Burk ini akan sama dengan
Sebagai perbandingan, harga-harga Km pada reaksi enzimatik lainnya dapat dilihat
seperti pada Tabel 5 berikut ini :
Tabel 5 Harga Km Beberapa Enzim
Harga Km ini diperoleh pada suhu 25 oC, Harga K
m dan vmax ini dapat
III. METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Tempat dan Waktu
Penelitian ini dilakukan di laboratorium Baristand (Balai Riset dan
Standardisasi) Industri Medan dan bekerja sama dengan PPKS (Pusat Penelitian
Kelapa Sawit) Medan, dengan waktu penelitian selama 4 (empat) bulan mulai dari
Maret 2008 sampai Juni 2008. Pengambilan sampel buah sawit sortiran dari PKS
(Pabrik Kelapa Sawit) Mancang Kec. Selesai, Kabupaten Langkat dan petani sawit di
daerah Desa Selayang Kec. Selesai, Kabupaten Langkat Sumatera Utara.
3.2 Bahan Penelitian
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Buah
sawit sisa sortiran, bahan kimia untuk pengujian produk asam lemak seperti gas
Nitrogen, gas Hidrogen dan etanol.
3.3 Alat-alat Penelitian
Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1
(satu) unit perontok, 1 (satu) unit penggiling atau pencercah, 1 (satu) unit pengepres,
1 (satu) unit penyaring, 1 (satu) unit oven, serta peralatan gelas dan peralatan uji
laboratorium seperti beaker gelas, tabung reaksi dan instrument GC (Gas
Chromatografy).
3.4 Rancangan Percobaan
Metode yang digunakan untuk mendesain percobaan dalam menentukan
kondisi optimum proses hidrolisa langsung buah sawit sisa sortiran menjadi asam
lemak dengan menggunakan tiga faktor sebagai variabel bebas yaitu :
1. Pelukaan buah
2. Penambahan air
3. Waktu reaksi
Percobaan dilakukan untuk memperoleh data perolehan asam lemak, asam
lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Percobaan ini dilakukan dengan
menghidrolisa langsung buah sawit sisa sortiran dengan mengaktifkan enzim lipase
yang ada pada buah sawit sisa sortiran itu sendiri, dengan tujuan untuk memperoleh
asam lemak yang optimum. Pada perolehan asam lemak yang optimum, ditetapkan
menjadi kondisi optimum untuk memperoleh asam lemak optimum dari buah sawit
sisa sortiran, kondisi ini diperoleh kombinasi dari ketiga perlakuan yang yang
diamati.
3.5 Prosedur Percobaan
Penelitian ini dilaksanakan melalui pengambilan sampel di petani sawit dan di
PKS. Sampel atau buah sawit yang digunakan dalam percobaan ini adalah buah sawit
yang brondolan. Kemudian percobaan laboratorium dilaksanakan sesuai dengan
rancangan percobaan dengan rancangan 3 (tiga) faktorial, faktor percobaan yaitu
waktu reaksi terdiri dari 3 (tiga) taraf dan pelukaan buah dengan 3 (tiga) taraf, serta
Adapun prosedur percobaan mengikuti tahapan sebagai berikut:
1. Persiapan bahan baku, peralatan percobaan dan bahan-bahan
pendukung lain
2. Pembersihan buah sawit sisa sortiran dari kotoran dan ditimbang
sebanyak 5400 gram untuk setiap bagian percobaan
3. Buah sawit sisa sortiran dibagi kedalam 3 (tiga) bagian dan setiap
bagian 1800 gram, ketiga bagian sampel tersebut ada dilukai, tanpa
dilukai dan dilumatkan
4. Setiap sampel atau tiap bagian dari buah sawit sisa sortiran pada no. 3
(tiga) dibagi ke dalam 3 (tiga) bagian lagi, selanjutnya diberi
penambahan air 0%, 20% dan 40% dari buah sawit yang ditimbang
5. Kemudian sampel pada no. 4 (empat) disimpan pada temperatur suhu
kamar dan tekanan 1 atm selama 0 hari, 1 hari dan 2 hari
6. Pemisahan produk hasil reaksi dengan cara campuran sampel no. 5
(lima) dipress untuk mendapatkan cairannya dari bagian perikarp
7. Cairan yang didapat disaring menggunakan kain saring untuk
mendapatkan cairan yang jernih dan bersih dari kotoran yang ada.
8. Cairan yang dihasilkan diovenkan pada suhu 105 oC, untuk
menguapkan air yang ada pada sampel
9. Cairan yang sudah diovenkan dikemas didalam wadah yang tertutup
kemudian dilakukan pengujian produk hasil reaksi (cairan) dengan
Adapun diagram alir prosedur percobaan yang dilakukan ada pada gambar 5 Dilukai, tanpa pelukaan dan
dilumatkan
3.6 Pengolahan Data
Metode statistik dengan menggunakan Program Excell digunakan untuk
mengetahui pengaruh konsentrasi penambahan air, perlakuan buah dan waktu reaksi
hidrolisa pada reaksi hidrolisa langsung buah sawit sisa sortiran menjadi asam lemak
untuk memperoleh kondisi optimum. Pengaruh ketiga variabel tersebut akan dianalisa
menggunakan metode statistik untuk memperoleh kondisi optimum (Montgomary,
2005; Sudjana, 1995).
Data dari percobaan diolah secara statistik untuk melihat jumlah perolehan
asam lemak yang dihasilkan. Pengolahan data digunakan untuk mengetahui perolehan
asam lemak yang terjadi pada reaksi hidrolisa langsung terhadap buah sawit sisa
sortiran. Serta melihat hubungan antara setiap faktor perlakuan dan interaksi antara
faktor perlakuan (waktu reaksi dan perlakuan buah serta penambahan air).
Diharapkan dari analisa data diperoleh suatu hubungan yang memberikan perolehan
asam lemak yang optimum untuk nilai besaran waktu reaksi hidrolisa dan perlakuan
buah serta penambahan air (Montgomary, 2005; Sudjana, 1995).
3.7 Pengujian Hasil Percobaan
Setelah selesai percobaan, produk yang dihasilkan dianalisa kadar asam
lemaknya dengan instrumen analisa metoda Gas Chromatografi (GC), kadar air dan
densitasnya sesuai dengan standar parameter uji SNI yang diberlakukan untuk semua
3.8 Jadwal Penelitian
Penelitian dengan judul Pemanfaatan buah sawit sisa sortiran sebagai sumber
bahan baku asam lemak dengan metode RAL (Rancangan Acak Lengkap)
dijadwalkan seperti Tabel 6. Waktu penelitian yang digunakan selama (10) sepuluh
bulan dengan perincian sebagai berikut :
Tabel 6 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penelitian
B U L A N NO KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Studi literatur
2 Penyusunan proposal 3 Seminar proposal 4 Persiapan alat dan bahan 5 Percobaan di Laboratorium. 6 Pengujian hasil Percobaan
7 Percobaan lanjutan dan Pengujian 8 Diskusi dan pengolahan data 9 Seminar hasil Penelitian
10 Sidang Magister
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Penelitian
4.1.1 Perolehan asam lemak untuk berbagai variabel waktu, penambahan air dan perlakuan terhadap buah sawit sisa sortiran
Data percobaan perolehan kadar asam lemak untuk buah sawit sisa sortiran
tidak dilukai dengan berbagai variasi waktu dan penambahan air dari analisa metoda
GC dapat dilihat pada Tabel 7 berikut :
Tabel 7 Perolehan asam lemak untuk buah sawit sisa sortiran tidak dilukai
Kadar Asam Lemak (%)
24 96,61002 99,99999 69,90902
48 100 100 95,54297
Data percobaan perolehan asam lemak untuk buah sawit sisa sortiran
dilumatkan dengan berbagai variasi waktu dan penambahan air dari anlisa metoda
GC dapat dilihat pada Tabel 8 berikut:
Tabel 8 Perolehan asam lemak untuk buah sawit sisa sortiran dilumatkan
Kadar Asam Lemak (%)
24 99,16289 98,82006 95,13299
48 96,68281 98,30046 98,86746
Data percobaan perolehan asam lemak untuk buah sawit sisa sortiran
dimemarkan dengan berbagai variasi waktu dan penambahan air dari analisa metoda
GC dapat dilihat pada Tabel 9 berikut:
Tabel 9 Perolehan asam lemak untuk buah sawit sisa sortiran dimemarkan
Kadar Asam Lemak (%)
0 91,19302 99,99999 61,28502
24 67,79276 93,74042 99,64079
48 94,06062 100 100
4.1.2 Perolehan asam lemak jenuh untuk berbagai variabel waktu, penambahan air dan perlakuan terhadap buah sawit sisa sortiran
Data percobaan perolehan asam lemak jenuh untuk buah sawit sisa sortiran
tidak dilukai dengan berbagai variasi waktu dan penambahan air dari analisa metoda
GC dapat dilihat pada Tabel 10 berikut:
Tabel 10 Perolehan asam lemak jenuh untuk buah sawit sisa sortiran tidak dilukai
Kadar Asam Lemak Jenuh (%) Waktu
0 97,13526 86,98712 99,99999
24 92,85028 82,23222 57,69802
48 82,5472 95,76611 91,53184
Data percobaan perolehan asam lemak jenuh untuk buah sawit sisa sortiran
dilumatkan dengan berbagai variasi waktu dan penambahan air dari analisa metoda
Tabel 11 Perolehan asam lemak jenuh untuk buah sawit sisa sortiran dilumatkan
Kadar Asam Lemak Jenuh (%) Waktu
24 87,86874 87,39285 95,13299
48 95,51072 87,97606 94,6094
Data percobaan perolehan asam lemak jenuh untuk buah sawit sisa sortiran
dimemarkan dengan berbagai variasi waktu dan penambahan air dari analisa metoda
GC dapat dilihat pada Tabel 12 berikut:
Tabel 12 Perolehan asam lemak jenuh untuk buah sawit sisa sortiran dimemarkan
Kadar Asam Lemak Jenuh (%) Waktu
24 64,83282 90,13954 99,64079
48 89,94129 96,33947 100
4.1.3 Perolehan asam lemak tidak jenuh untuk berbagai variabel waktu, penambahan air dan perlakuan terhadap buah sawit sisa sortiran
Data percobaan perolehan asam lemak tidak jenuh untuk buah sawit sisa
sortiran tidak dilukai dengan berbagai variasi waktu dan penambahan air dari analisa
Tabel 13 Perolehan asam lemak tidak jenuh untuk buah sawit tidak dilukai
Kadar Asam Lemak Tidak Jenuh (%) Waktu
Data percobaan perolehan asam lemak tidak jenuh untuk buah sawit sisa
sortiran dilumatkan dengan berbagai variasi waktu dan penambahan air dari analisa
metoda GC dapat dilihat pada Tabel 14 berikut:
Tabel 14 Perolehan asam lemak tidak jenuh untuk buah sawit dilumatkan
Kadar Asam Lemak Tidak Jenuh (%) Waktu
Data percobaan perolehan asam lemak tidak jenuh untuk buah sawit sisa
sortiran dimemarkan dengan berbagai variasi waktu dan penambahan air dari analisa
metoda GC dapat dilihat pada Tabel 15 berikut:
Tabel 15 Perolehan asam lemak tidak jenuh untuk buah sawit dimemarkan
4.1.4 Hasil pengujian kadar air dan densitas asam lemak hasil percobaan Asam lemak hasil percobaan kemudian dianalisa kadar air dan densitasnya.
Hasil analisa kadar air dan densitas asam lemak yang diperoleh dapat dilihat pada
Tabel 16 berikut
Tabel 16 Kadar air dan densitas asam lemak untuk waktu hidrolisa 0 (nol) hari dengan berbagai variabel penambahan air dan perlakuan terhadap buah sawit sisa sortiran
Parameter
Buah tidak dilukai dan penambahan air 0% Buah tidak dilukai dan penambahan air 20% Buah tidak dilukai dan penambahan air 40%
Buah dilumatkan dan penambahan air 0% Buah dilumatkan dan penambahan air 20% Buah dilumatkan dan penambahan air 40%
Buah dimemarkan dan penambahan air 0% Buah dimemarkan dan penambahan air 20% Buah dimemarkan dan penambahan air 40%
0,2317
4.2.1 Percobaan Buah sawit sisa sortiran yang tidak dilukai
Perolehan kadar asam lemak bebas, kadar asam lemak jenuh dan kadar asam
tidak jenuh dari hasil penelitian yang telah dilakukan untuk berbagai variabel waktu
dan penambahan air untuk buah sawit sisa sortiran yang tidak dilukai dapat dilihat
4.2.1.1. Perolehan asam lemak, untuk buah sawit sisa sortiran tidak dilukai Perolehan kadar asam lemak bebas dari hasil penelitian (Tabel 7) yang telah
dilakukan untuk berbagai variabel waktu dan penambahan air terhadap buah sawit
sisa sortiran yang tidak dilukai dapat dilihat pada Gambar 6 berikut :
60
Gambar 6 Perolehan asam lemak untuk buah sawit sisa sortiran tidak dilukai
Dari Gambar 6 menunjukkan bahwa perolehan asam lemak meningkat sesuai
dengan bertambahnya waktu dan terjadi pada kondisi penambahan air 20%, tetapi
perolehan asam lemak dari yang besar kemudian mula-mula menurun dan kemudian
meningkat dengan bertambahnya waktu dan kondisi ini terjadi pada penambahan air
0% dan 40%. Hal ini disebabkan karena reaksi hidrolisa oleh enzim lipase yang
terjadi berlangsung secara reversibel selain itu bahan baku yang digunakan sudah
terfermentasi secara alami di lapangan. Menurut Fickenday (1910), menyatakan
buah ini diletakkan pada tempat terbuka dan mengandung jamur. Wilbaux (1980),
menyatakan bahwa jamur dari tipe Oospora (kemungkinan Geotrichium candidum)
terbukti mampu meningkatkan kandungan asam lemak bebas pada buah sawit segar
dari 0,1 % menjadi 6,4 % dalam waktu 60 jam. Penyebab dari pada hal ini adalah
karena adanya inhibisi oleh produk yang terbentuk, sehingga aktifitas enzim lipase
untuk mengkatalisa minyak menjadi asam lemak menjadi menurun/terganggu.
4.2.1.2 Perolehan asam lemak jenuh, untuk buah sawit sisa sortiran tidak dilukai Perolehan kadar asam lemak jenuh dari hasil penelitian (Tabel 10) yang telah
dilakukan untuk berbagai variabel waktu dan penambahan air terhadap buah sawit
sisa sortiran yang tidak dilukai dapat dilihat pada Gambar 7 berikut :
Gambar 7 Perolehan asam lemak jenuh untuk buah sawit sisa sortiran tidak dilukai
Dari Gambar 7 menunjukkan bahwa perolehan asam lemak jenuh menurun
tetapi perolehan asam lemak jenuh dari yang besar kemudian mula-mula menurun
dan kemudian meningkat dengan bertambahnya waktu dan kondisi ini terjadi pada
penambahan air 20% dan 40%. Hal ini disebabkan karena reaksi hidrolisa dengan
enzim lipase terjadi secara reversibel selain itu bahan baku yang digunakan sudah
terfermentasi secara alami di lapangan. Menurut Fickenday (1910), menyatakan
bahwa keasaman akan meningkat dengan cepat pada perikarp buah yang dilukai, jika
buah ini diletakkan pada tempat terbuka dan mengandung jamur. Wilbaux (1980),
menyatakan bahwa jamur dari tipe Oospora (kemungkinan Geotrichium candidum)
terbukti mampu meningkatkan kandungan asam lemak bebas pada buah sawit segar
dari 0,1 % menjadi 6,4 % dalam waktu 60 jam. Penyebab dari pada hal ini adalah
karena adanya inhibisi oleh produk yang terbentuk, sehingga aktifitas enzim lipase
untuk mengkatalisa minyak menjadi asam lemak menjadi menurun/terganggu.
4.2.1.3 Perolehan asam lemak tidak jenuh, untuk buah sawit sisa sortiran tidak dilukai
Perolehan kadar asam lemak tidak jenuh dari hasil penelitian (Tabel 13) yang
telah dilakukan untuk berbagai variabel waktu dan penambahan air terhadap buah
Gambar 8 Perolehan asam lemak tidak jenuh untuk buah sawit tidak dilukai
Dari Gambar 8 menunjukkan bahwa perolehan asam lemak tidak jenuh
meningkat sesuai dengan bertambahnya waktu dan terjadi pada kondisi penambahan
air 0%, tetapi perolehan asam lemak tidak jenuh dari yang kecil kemudian mula-mula
meningkat dan kemudian menurun dengan bertambahnya waktu dan kondisi ini
terjadi pada penambahan air 20% dan 40%. Hal ini disebabkan karena reaksi hidrolisa
yang terjadi pleh enzim lipase secara reversibel selain itu bahan baku yang digunakan
sudah terfermentasi secara alami di lapangan. Penyebab dari pada hal ini adalah
karena adanya inhibisi oleh produk yang terbentuk, menurut Fickenday (1910),
menyatakan bahwa keasaman akan meningkat dengan cepat pada perikarp buah yang
dilukai, jika buah ini diletakkan pada tempat terbuka dan mengandung jamur.
Wilbaux (1980) menyatakan bahwa jamur dari tipe Oospora (kemungkinan
Geotrichium candidum) terbukti mampu meningkatkan kandungan asam lemak bebas
aktifitas enzim lipase untuk mengkatalisa minyak menjadi asam lemak menjadi
menurun/terganggu.
4.2.2 Percobaan Buah sawit sisa sortiran yang dilumatkan
Perolehan kadar asam lemak, kadar asam lemak jenuh dan kadar asam lemak
tidak jenuh dari hasil penelitian yang telah dilakukan untuk berbagai variabel waktu
dan penambahan air terhadap buah sawit sisa sortiran yang dilumatkan dapat dilihat
pada Gambar 9, 10 dan 11 berikut :
4.2.2.1 Perolehan asam lemak bebas, untuk buah sawit sisa sortiran dilumatkan
Perolehan kadar asam lemak bebas dari hasil penelitian (Tabel 8) yang telah
dilakukan untuk berbagai variabel waktu dan penambahan air terhadap buah sawit
sisa sortiran yang dilumatkan dapat dilihat pada Gambar 9 berikut :
Dari Gambar 9 menunjukkan bahwa perolehan asam lemak meningkat sesuai
dengan bertambahnya waktu dan terjadi pada kondisi penambahan air 40%, tetapi
perolehan asam lemak dari yang besar kemudian mula-mula menurun dan kemudian
meningkat dengan bertambahnya waktu dan kondisi ini terjadi pada penambahan air
0% dan 20%. Hal ini disebabkan karena reaksi hidrolisa oleh enzim lipase terjadi
secara reversibel selain itu bahan baku yang digunakan sudah terfermentasi secara
alami di lapangan. Penyebab dari pada hal ini adalah karena adanya inhibisi oleh
produk yang terbentuk, menurut Fickenday (1910), menyatakan bahwa keasaman
akan meningkat dengan cepat pada perikarp buah yang dilukai, jika buah ini
diletakkan pada tempat terbuka dan mengandung jamur. Wilbaux (1980), menyatakan
bahwa jamur dari tipe Oospora (kemungkinan Geotrichium candidum) terbukti
mampu meningkatkan kandungan asam lemak bebas pada buah sawit segar dari 0,1
% menjadi 6,4 % dalam waktu 60 jam, sehingga aktifitas enzim lipase untuk
mengkatalisa minyak menjadi asam lemak menjadi menurun/terganggu.
4.2.2.2 Perolehan asam lemak jenuh, untuk buah sawit sisa sortiran dilumatkan
Perolehan kadar asam lemak jenuh dari hasil penelitian (Tabel 11) yang telah
dilakukan untuk berbagai variabel waktu dan penambahan air terhadap buah sawit
Gambar 10 Perolehan asam lemak jenuh untuk buah sawit sisa sortiran dilumatkan
Dari Gambar 10 menunjukkan bahwa perolehan asam lemak jenuh meningkat sesuai
dengan bertambahnya waktu dan terjadi pada kondisi penambahan air 0%, tetapi
perolehan asam lemak jenuh dari yang besar kemudian mula-mula menurun dan
kemudian meningkat dengan bertambahnya waktu dan kondisi ini terjadi pada
penambahan air 20%. Sedangkan untuk penambahan air 40% dari perolehan asam
lemak jenuh yang kecil kemudian meningkat dan selanjutnya agak menurun, hal ini
disebabkan karena reaksi hidrolisa oleh enzim lipase terjadi secara reversibel selain
itu bahan baku yang digunakan sudah terfermentasi secara alami di lapangan.
Penyebab dari pada hal ini adalah karena adanya inhibisi oleh produk yang terbentuk,
menurut Fickenday (1910), menyatakan bahwa keasaman akan meningkat dengan
cepat pada perikarp buah yang dilukai, jika buah ini diletakkan pada tempat terbuka
dan mengandung jamur. Wilbaux (1980) menyatakan bahwa jamur dari tipe Oospora
(kemungkinan Geotrichium candidum) terbukti mampu meningkatkan kandungan
jam, sehingga aktifitas enzim lipase untuk mengkatalisa minyak menjadi asam lemak
menjadi menurun/terganggu.
4.2.2.3 Perolehan asam lemak tidak jenuh, untuk buah sawit sisa sortiran dilumatkan
Perolehan kadar asam lemak tidak jenuh dari hasil penelitian (Tabel 14) yang
telah dilakukan untuk berbagai variabel waktu dan penambahan air terhadap buah
sawit sisa sortiran yang dilumatkan dapat dilihat pada Gambar 11 berikut
:
Gambar 11 Perolehan asam lemak tidak jenuh untuk buah sawit sortiran dilumatkan
Dari Gambar 11 menunjukkan bahwa perolehan asam lemak tidak jenuh dari
besar kemudian menurun dratis kemudian meningkat kembali sesuai dengan
bertambahnya waktu dan terjadi pada kondisi penambahan air 40%, tetapi perolehan
asam lemak tidak jenuh dari yang kecil kemudian mula-mula meningkat dan
penambahan air 20% dan 0%. Hal ini disebabkan karena reaksi hidrolisa oleh enzim
lipase terjadi secara reversibel selain itu bahan baku yang digunakan sudah
terfermentasi secara alami di lapangan. Penyebab dari pada hal ini adalah karena
adanya inhibisi oleh produk yang terbentuk, menurut Fickenday (1910), menyatakan
bahwa keasaman akan meningkat dengan cepat pada perikarp buah yang dilukai, jika
buah ini diletakkan pada tempat terbuka dan mengandung jamur. Wilbaux (1980),
menyatakan bahwa jamur dari tipe Oospora (kemungkinan Geotrichium candidum)
terbukti mampu meningkatkan kandungan asam lemak bebas pada buah sawit segar
dari 0,1 % menjadi 6,4 % dalam waktu 60 jam, sehingga aktifitas enzim lipase untuk
mengkatalisa minyak menjadi asam lemak menjadi menurun/terganggu.
4.2.3 Percobaan Buah sawit sisa sortiran yang dimemarkan
Perolehan kadar asam lemak, kadar asam lemak jenuh dan kadar asam lemak
tidak jenuh dari hasil penelitian yang telah dilakukan untuk berbagai variabel waktu
dan penambahan air untuk buah sawit sisa sortiran yang dimemarkan dapat dilihat
pada gambar 12, 13 dan 14 berikut :
4.2.3.1 Perolehan asam lemak, untuk buah sawit sisa sortiran dimemarkan Perolehan kadar asam lemak bebas dari hasil penelitian (Tabel 9) yang telah
dilakukan untuk berbagai variabel waktu dan penambahan air terhadap buah sawit
Gambar 12 Perolehan asam lemak untuk buah sawit sortiran dimemarkan
Dari Gambar 12 menunjukkan bahwa perolehan asam lemak meningkat sesuai
dengan bertambahnya waktu dan terjadi pada kondisi penambahan air 40%, tetapi
perolehan asam lemak dari yang besar kemudian mula-mula menurun dan kemudian
meningkat dengan bertambahnya waktu dan kondisi ini terjadi pada penambahan air
0% dan 20%. Hal ini disebabkan karena reaksi hidrolisa yang terjadi oleh enzim
lipase secara reversibel selain itu bahan baku yang digunakan sudah terfermentasi
secara alami di lapangan. Menurut Fickenday (1910), menyatakan bahwa keasaman
akan meningkat dengan cepat pada perikarp buah yang dilukai, jika buah ini
diletakkan pada tempat terbuka dan mengandung jamur. Wilbaux (1980), menyatakan
bahwa jamur dari tipe Oospora (kemungkinan Geotrichium candidum) terbukti
mampu meningkatkan kandungan asam lemak bebas pada buah sawit segar dari 0,1
adanya inhibisi oleh produk yang terbentuk, sehingga aktifitas enzim lipase untuk
mengkatalisa minyak menjadi asam lemak menjadi menurun/terganggu.
4.2.3.2 Perolehan asam lemak jenuh untuk buah sawit sisa sortiran dimemarkan Perolehan kadar asam lemak jenuh dari hasil penelitian (Tabel 12) yang telah
dilakukan untuk berbagai variabel waktu dan penambahan air terhadap buah sawit
sisa sortiran yang dimemarkan dapat dilihat pada Gambar 13 berikut :
Gambar 13 Perolehan asam lemak jenuh untuk buah sawit
sortiran dimemarkan
Dari Gambar 13 menunjukkan bahwa perolehan asam lemak jenuh meningkat
sesuai dengan bertambahnya waktu dan terjadi pada kondisi penambahan air 40%,
tetapi perolehan asam lemak jenuh dari yang besar kemudian mula-mula menurun
dan kemudian meningkat dengan bertambahnya waktu dan kondisi ini terjadi pada
penambahan air 0% dan 20%. Hal ini disebabkan karena reaksi hidrolisa yang terjadi
terfermentasi secara alami di lapangan. Penyebab dari pada hal ini adalah karena
adanya inhibisi oleh produk yang terbentuk, menurut Fickenday (1910), menyatakan
bahwa keasaman akan meningkat dengan cepat pada perikarp buah yang dilukai, jika
buah ini diletakkan pada tempat terbuka dan mengandung jamur. Wilbaux (1980),
menyatakan bahwa jamur dari tipe Oospora (kemungkinan Geotrichium candidum)
terbukti mampu meningkatkan kandungan asam lemak bebas pada buah sawit segar
dari 0,1 % menjadi 6,4 % dalam waktu 60 jam, sehingga aktifitas enzim lipase untuk
mengkatalisa minyak menjadi asam lemak menjadi menurun/terganggu.
4.2.3.3 Perolehan asam lemak tidak jenuh, untuk buah sawit sisa sortiran dimemarkan
Perolehan kadar asam lemak tidak jenuh dari hasil penelitian (Tabel 15) yang
telah dilakukan untuk berbagai variabel waktu dan penambahan air terhadap buah
sawit sisa sortiran yang dimemarkan dapat dilihat pada Gambar 14 berikut :
Gambar 14 Perolehan asam lemak tidak jenuh untuk buah sawit
Dari Gambar 14 menunjukkan bahwa perolehan asam lemak tidak jenuh tidak
ada perubahan sesuai dengan bertambahnya waktu dan terjadi pada kondisi
penambahan air 20%, tetapi perolehan asam lemak tidak jenuh dari yang besar
kemudian mula-mula menurun dan kemudian meningkat dengan bertambahnya waktu
dan kondisi ini terjadi pada penambahan air 0% dan 20%. Hal ini disebabkan karena
reaksi hidrolisa yang terjadi oleh enzim lipase secara reversibel selain itu bahan baku
yang digunakan sudah terfermentasi secara alami di lapangan. Penyebab dari pada hal
ini adalah karena adanya inhibisi oleh produk yang terbentuk, menurut Fickenday
(1910), menyatakan bahwa keasaman akan meningkat dengan cepat pada perikarp
buah yang dilukai, jika buah ini diletakkan pada tempat terbuka dan mengandung
jamur. Wilbaux (1980), menyatakan bahwa jamur dari tipe Oospora (kemungkinan
Geotrichium candidum) terbukti mampu meningkatkan kandungan asam lemak bebas
pada buah sawit segar dari 0,1 % menjadi 6,4 % dalam waktu 60 jam, sehingga
aktifitas enzim lipase untuk mengkatalisa minyak menjadi asam lemak menjadi
menurun/terganggu.
4.2.4 Pengaruh Variabel Percobaan Terhadap Perolehan Asam Lemak
Pada percobaan ini dilakukan beberapa variabel proses yang sangat
berpengaruh terhadap perolehan asam lemak. Variabel proses dibagi menjadi 2 (dua)
bagian yaitu variabel tetap dan variabel tidak tetap, untuk pengaruh suhu dan
kematangan buah sebagai variabel tetap, sedangkan kadar tingkat pelukaan buah,
4.2.4.1 Pengaruh Berbagai Tingkat Pelukaan Buah
Dari Penelitian ini hasil yang terbaik dicapai pada perlakuan buah yang
dilumatkan. Dengan proses seperti ini terbukti bahwa kadar asam lemak yang
diperoleh lebih tinggi dibandingkan jika buah tidak dilumatkan sampai halus (hanya
dimemarkan/dilukai).
Dari Penelitian Tambun (2002), perlakuan terhadap tingkat pelukaan buah
sawit sisa sortiran dan pengadukan sangat berpengaruh terhadap proses hidrolisa
langsung karena akan membantu terjadinya kontak antara enzim dan minyak
(substrat). Hal ini karena posisi enzim lipase pada buah sawit belum diketahui secara
pasti, sehingga untuk mengatasi hal ini maka buah harus dilumat sampai halus,
kemudian minyak dan seratnya dicampur kembali. Pengaturan kecepatan pengadukan
pada reaksi ini perlu dilakukan, karena pada proses ini pengadukan berpengaruh
kepada waktu kontak antara air, substrat dan enzim. Disamping itu, karena yang
diaduk adalah campuran serat dan minyak, maka pemilihan rancangan pengaduk
sangat perlu untuk diperhatikan.
4.2.4.2 Pengaruh Penambahan Air
Dari gambar diatas terlihat bahwa persentase asam lemak yang paling tinggi
diperoleh pada percobaan buah sawit sisa sortiran dilumatkan dengan suhu 28 oC dan
penambahan 20 % air. Tingkat hidrolisa yang diperoleh pada kondisi ini adalah 100