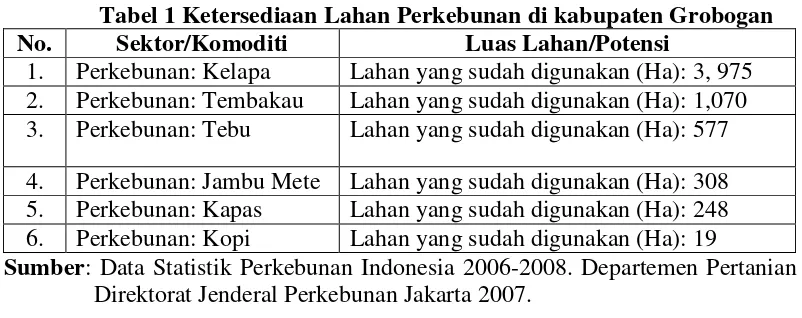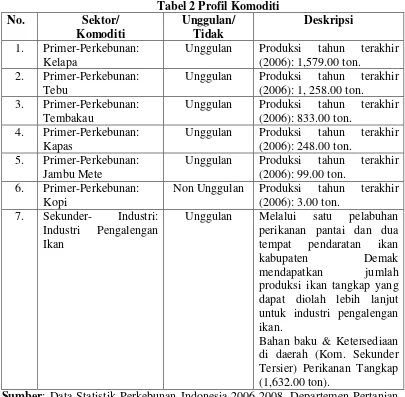Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Sastra
Program Studi Ilmu Sejarah
SKRIPSI
Disusun Oleh:
Makaria Asfina Ratu
044314002
PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH
JURUSAN SEJARAH FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
i
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sastra
Program Studi Ilmu Sejarah
SKRIPSI
Oleh:
Makaria Asfina Ratu 044314002
PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH JURUSAN SEJARAH FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA
ii
TERHADAP KEHIDUPAN PETANI DI KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 1870-1875”, yang ditulis oleh Makaria Asfina Ratu/044314002.
TELAH DISETUJUI OLEH:
Pembimbing
iii
Skripsi ini kupersembahkan untuk;
Mendiang ayahku, Fransiscus Ambo.
Ibuku, Agustina Indrayani Inya.
Adikku, Samuel Kalimanjaya.
Dan...
iv
In order to succeed, we must first believe that we can.
v
OLEH:
MAKARIA ASFINA RATU 044314002
“Dipertahankan di depan Panitia Penguji Skripsi Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma pada
tanggal 17 Desember 2009”
Susunan Panitia Penguji
Ketua : Prof. P.J. Suwarno, S.H _____________
Anggota : 1. Drs. Hb. Hery Santosa, M.Hum _____________
2. Drs. Ign. Sandiwan Suharso _____________
3. Drs. Silverio R.L. Aji Sampurno, M.Hum _____________
Yogyakarta, 17 Desember 2009 Fakultas Sastra
Universitas Sanata Dharma Dekan,
vi
kesarjanaan di perguruan tinggi. Skripsi ini tidak memuat karya orang lain atau
suatu lembaga atau bagian dari karya orang lain atau suatu lembaga, kecuali
bagian-bagian tertentu yang dijadikan sumber.
Yogyakarta,
Makaria Asfina Ratu
vii
Skripsi berjudul “Dampak PelaksanaanAgrarische Wet 1870 terhadap Kehidupan Petani di Kabupaten Grobogan tahun 1870-1875” disusun berdasarkan tiga permasalahan pokok. Pertama, bagaimana keadaan Kabupaten Grobogan sebelum pelaksanaan Agrarische Wet 1870; kedua, bagaimana pelaksanaan Agrarische Wet 1870 di Kabupaten Grobogan; dan ketiga, apa dampak dari pelaksanaan tersebut. Skripsi ini menggunakan teori fungsionalisme dari Robert K. Merton yang menyatakan bahwa kemiskinan itu bersifat fungsionalis. Kemiskinan perlu dipertahankan untuk melestarikan sebuah sistem yang ada dalam suatu lingkungan tertentu.
Keadaan geografis dari Kabupaten Grobogan merupakan faktor penting penyebab pesatnya perkembangan usaha-usaha perkebunan, baik pada masa
Cultuurstelselmaupun masa liberal. Kemudian pelaksanaanAgrarische Wet 1870
semakin mempertegas ‘politik pintu terbuka’ dan era perdagangan bebas di Hindia-Belanda. Perkembangan usaha-usaha perkebunan berdampak pada kehidupan petani di Kabupaten Grobogan. Dengan kondisi kehidupan yang subsisten, petani kemudian menjadi buruh di perkebunan-perkebunan swasta.
Pada kenyataannya, idealisme liberal tidak tercapai. Petani yang seharusnya juga diuntungkan tidak merasakan keuntungan dari pelaksanaan
‘politik pintu terbuka’ dan era perdagangan bebas pada masa itu. Kegagalan
viii
The thesis entitled “Dampak Pelaksanaan Agrarische Wet 1870
terhadap Kehidupan Petani d Kabupaten Grobogan Tahun 1870-1875” (The Impact of the Realization ofThe Agrarische Wet 1870to the Peasants’ Life in the Grobogan Regency in 1870-1875) was formatted with three principal problems:first, how the condition of the Grobogan regency before the realization ofThe Agrarische Wet 1870is; second, how the realization ofThe Agrarische Wet 1870in the Grobogan residence is; and third, what its impacts to the peasants life are. This thesis uses the functionalism theory by Robert K. Merton who said that poverty has a functional characteristic, i.e., poverty is needed to support a system of a particular society.
The geographical condition of the Grobogan regency was the main factor that caused the rapid development of the private plantation enterprises, either in the Cultuurstelsel period or in the liberal period. Then, the realization of The Agrarische Wet 1870 affirmed the ‘open door policy’ and free trade era in East-Indies. The development of the private plantation enterprises had impacts to the peasants’ life. In the subsistence life, the peasants became the labors for the private plantations.
ix
Nama : Makaria Asfina Ratu
Nomor Mahasiswa : 044314002
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan
Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul:
“DAMPAK PELAKSANAANAGRARISCHE WET 1870TERHADAP
KEHIDUPAN PETANI DI KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 1870-1875’
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan
kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan,
mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan
data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau
media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya
maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya
sebagai penulis.
Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.
Dibuat di Yogyakarta
Pada tanggal 17 Desember 2009
Yang menyatakan
x
pada masa kolonial, khususnya masa liberal. Ketika membahas mengenai
perkembangan perkebunan pada abad ke-19, maka sosok petani atau yang juga
sering disebut sebagai buruh tani mempunyai keterikatan yang sangat erat.
Ditinjau dari sudut pandang filsafat sejarah, konteks tersebut menunjukkan sebuah
gerak spiral. Gerak sejarah spiral merupakan gabungan antara gerak sejarah siklis
dan gerak sejarah linear. Karena di dalamnya terdapat unsur kesinambungan,
maka gerak tersebut tidak hanya melulu siklis tetapi pada masanya muncul juga
gerak linear.
Pada masa kerajaan (feodal) raja merupakan tuan tanah, pemerintah
kolonial sebagai golongan kapitalis dan petani sebagai buruh. Kemudian pada
masa kolonial (Cultuurstelsel) melalui berbagai perjanjian dengan raja-raja
pemerintah kolonial menjadi tuan tanah sekaligus golongan kapitalis dan petani
sebagai buruh. Lalu pada masa liberal pemerintah kolonial sebagai tuan tanah dan
para pemilik modal swasta sebagai golongan kapitalis, sedangkan petani tetap
sebagai buruh. Perubahan kekuasaan dari raja ke pemerintah kolonial sebagai tuan
tanah dan perubahan kekuasaan dari pemerintah kolonial ke para pemilik modal
swasta sebagai golongan kapitalis mengidentifikasikan sebuah gerak linear dalam
pola siklis yang ada.
Ucapan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat
xi
Juningsih, M. Hum; Prof. Dr. P. J. Suwarno, S. H; (alm.) Drs. G. Moedjanto, M.
A. Terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah berbagi pengetahuan dan
pengalaman serta menjadi motivator untuk dapat menemukan atau memberikan
yang terbaik untuk masa depan.
Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada mas Tri yang banyak
membantu di Sekretariat Jurusan Ilmu Sejarah Universitas Sanata Dharma.
Terima kasih juga kepada teman-teman seangkatan yang mengagumkan; Nana,
Anon, Agus/P’De, Darwin, Kaka dan Buy. Kepada sahabat-sahabatku tercinta;
Mami-Andar, Nenek Desy, Tante-Ve dan Wisni. Terima kasih atas dukungan
yang terus-menerus kalian berikan. Terima kasih banyak kepada almarhum bapak,
ibuku, adikku semata wayang dan si kecil; Izzi.
Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
xii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAAN KARYA ……….. vi
ABSTRAK ………. vii
ABSTRACT ……….. viii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ………. ix
KATA PENGANTAR ……… x
DAFTAR ISI ……….. xii
BAB I PENDAHULUAN……… 1
A. Latar Belakang ...………... 1
B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah ……… 5
C. Perumusan Masalah ………... 6
D. Tujuan Penelitian ………... 7
E. Manfaat Penelitian ………... 7
F. Kajian Pustaka ………... 8
G. Landasan Teori ………... 11
H. Metode Penelitian ………... 17
I. Sistematika Penulisan ………... 18
BAB II SEKILAS TENTANG KABUPATEN GROBOGAN………... 21
A. Gambaran Umum dan Sejarah Kabupaten Grobogan……… 21
xiii
di Hindia-Belanda ………... 37
B. PelaksanaanAgrarische Wet 1870 di Kabupaten Grobogan ...……….. 46
BAB IV DAMPAK PELAKSANAANAGRARISCHE WET 1870 TERHADAP KEHIDUPAN PETANI DI KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 1870-1875...………... 52
A. Dampak di Bidang Ekonomi ………... 55
B. Dampak di Bidang Sosial ……….. 59
BAB V PENUTUP………... 66
1
A. Latar Belakang Masalah
Masyarakat Indonesia adalah masyarakat agraris yang berbasis ekonomi
pertanian, dimana petani merupakan tulang punggung kelangsungan hidup dari
masyarakat agraris tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh sejarahnya yang meskipun
mengalami pergantian jaman, pertanian tetap eksis dan menjadi soko guru
kehidupan.1 Kehidupan agraris di Indonesia telah berlangsung sejak jaman
kerajaan hingga sekarang. Seperti di Jawa, kehidupan yang berbasis agraris telah
dimulai dari kerajaan Jawa Kuna hingga sekarang. Tetapi pada masa kolonial ada
beberapa perubahan yang terjadi dalam kehidupan agraris tersebut. Petani yang
merupakan tonggak dari kehidupan agraris tersebutlah yang lebih merasakan
dampak dari perubahan yang terjadi pada masa itu.
Sejak tahun 1830-an, kehidupan petani menjadi sangat memprihatinkan,
terutama dengan diterapkannyaCultuurstelsel.Ciri utama dariCultuurstelselyang
diperkenalkan oleh van den Bosch adalah keharusan bagi rakyat di Jawa untuk
membayar pajak dalam bentuk barang, yaitu hasil-hasil pertanian mereka dan
bukan dalam bentuk uang seperti yang mereka lakukan selama sistem pajak tanah
1 Suhartono W. Pranoto,
masih berlaku.2 Melalui Cultuurstelsel ini, pemerintah Hindia-Belanda berharap
dapat mengatasi permasalahan ekonomi negeri induk yang pada masa itu sedang
mengalami keterpurukan.
Selama masa Cultuurstelsel, seperlima tanah pertanian ditanami tanaman
komersial yang jenisnya ditentukan oleh pemerintah. Upaya van den Bosch tidak
sia-sia karena ekspor gula dari Jawa menguasai pasar dunia. Kerajaan Belanda
menikmati keuntungan besar dari hasilCultuurstelseltersebut, kas negara kembali
stabil bahkan dapat disebut sebagai sebuah surplus. Namun, di sisi lain kehidupan
para petani semakin menurun karena lahan-lahan produktif (subur) dan beririgasi
yang dulunya digunakan sebagai lahan pertanian diubah menjadi lahan
perkebunan oleh pemerintah.
Dalam perkembangannya Cultuurstelsel mendapat berbagai kritikan,
terutama dari kaum liberal dan humanis. Kaum liberal berpendapat bahwa
pemerintah seharusnya tidak ikut campur dalam urusan ekonomi, pihak swastalah
yang lebih tepat mengurusi bidang tersebut sedang pemerintah fungsinya adalah
menjadi pelindung warga negara, penyedia prasarana, penegak hukum, dan
pengatur keamanan dan ketertiban. Sedang kritikan kaum humanis lebih pada
masalah kesejahteraan hidup petani yang semakin memprihatinkan. Kritikan
kaum humanis berangkat dari adanya kasus kelaparan yang menimpa petani di
Jawa pada akhir tahun 1840-an. Kritikan kaum humanis tersebutlah yang
2
kemudian memperkuat kritikan kaum liberal terhadap pemerintah. Perjuangan
keduanya berbuah penghapusanCultuurstelselsecara resmi pada tahun 1870.
Dengan dihapusnya Cultuurstelsel, kemudian dimulailah suatu haluan
politik baru oleh pemerintah Hindia-Belanda, yaitu Sistem Liberal. Adanya
perubahan dalam sistem pemerintahan tersebut, menyebabkan perubahan dalam
berbagai aspek kehidupan di Hindia-Belanda. Sistem Liberal berarti bahwa
Hindia-Belanda terbuka terhadap modal-modal swasta yang ingin berinvestasi di
Hindia-Belanda. Kesempatan seperti ini mengakibatkan perkembangan
perkebunan-perkebunan besar pada masa liberal, khususnya di pulau Jawa dan
Sumatera. Selain itu, dapat dikatakan pula bahwa pada tahun 1870, Belanda
memasuki periode kapitalisme modern3 yang ditandai dengan pelaksanaan
“politik pintu terbuka”.
Berdasarkan latar belakang tersebut, topik Dampak Pelaksanaan
Agrarische Wet 1870 terhadap Kehidupan Petani di Kabupaten Grobogan tahun
1870-1875 menjadi menarik untuk dikaji. Ada dua alasan penting yang mendasari
topik ini menjadi patut untuk dikaji lebih dalam, yaitu; pertama, Agrarische Wet
tahun 1870 merupakan undang-undang agraria yang dikeluarkan pada masa
liberal dengan idealisme akan kebebasan dan kesejahteraan umum, akan tetapi
dalam pelaksanaan hingga pada akhirnya rakyat (khususnya petani) tetap tidak
merasakan apa yang disebutkan sebagai kesejahteraan umum yang menjadi
cita-cita perjuangan kaum liberal. Petani tetap menajdi korban eksploitasi agraria.
3
Kedua, dengan alasan pertama tadi terbukti bahwa Agrarische Wet tahun 1870
tidak memberikan sebuah pencerahan bagi petani masa itu. Akan tetapi,
undang-undang agraria kita hingga saat ini masih berdiri dengan membawa jiwa
Agrarische Wet tahun 1870 di dalamnya. Oleh karena itu, menarik untuk dikaji
secara lebih mendalam karena kemudian muncul sebuah hipotesis bahwa apakah
keterbelakangan petani yang terjadi di negara kita hingga saat ini ada kaitannya
dengan jiwaAgrarische Wet 1870yang tetap lestari dalam undang-undang agraria
negara kita.
Dipilihnya kurun waktu dari tahun 1870 sampai dengan 1875 adalah
karena pada periode ini, khususnya di pulau Jawa dan Sumatera terjadi
perkembangan usaha-usaha perkebunan milik swasta sebagai salah satu dampak
dari pelaksanaan dari Agrarische Wet 1870. Pada masa pemerintahan
Hindia-Belanda, wilayah Jawa Tengah merupakan salah satu wilayah
perkebunan-perkebunan besar Belanda di pulau Jawa. Kabupaten Grobogan merupakan salah
satu daerah di Jawa Tengah yang juga menjadi pusat perkembangan usaha-usaha
perkebunan swasta. Selain itu, kehidupan petani di Grobogan terlihat bertolak
belakang dengan pesatnya perkembangan perkebunan yang terjadi. Di satu sisi
usaha perkebunan berkembang dengan pesat dari tahun 1870 sampai dengan tahun
1875, akan tetapi di sisi lainnya kehidupan petani tidak mengalami pekembangan
B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah
Agar pembahasan dari permasalahan dalam penulisan ini tidak menjadi
kabur, maka ada beberapa hal yang perlu diidentifikasikan. Pertama,
kritikan-kritikan terhadap pelaksanaan Cultuurstelsel (1830-1870) merupakan sebuah
proses perubahan politik di Hindia-Belanda. Kasus kelaparan dan wabah penyakit
yang menimpa petani di Jawa pada akhir tahun 1840-an menjadi pukulan keras
yang akhirnya membuat kaum humanis menuntut penghapusan Cultuurstelsel
(1860). Bersamaan dengan hal tersebut, kaum liberal memenangkan politiknya di
parlemen Belanda pada tahun 1870 sehingga Cultuurstelsel dihapuskan secara
resmi dan dimulailah politik kolonial baru, yaitu politik liberal.
Kedua, politik liberal pada dasarnya berarti komersialisasi
Hindia-Belanda, dengan pelaksanaan ‘politik pintu terbuka’ maka penanaman modal
swasta membanjiri Hindia-Belanda. Untuk mengontrol atau mengatur hal tersebut,
dewan menteri de Waal mengeluarkan sebuah undang-undang yang dikenal
dengan Agrarische Wet tahun 1870. Undang-undang ini secara garis besar
memuat ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak atas tanah dan ketentuan
penggunaannya. Pelaksanaan poltik liberal di Hindia-Belanda menyebabkan
pesatnya perkembangan usaha-usaha swasta, khususnya di pulau Jawa dan
Sumatera. Ketiga, pada kenyataannya Agrarische Wet tidak juga berhasil
meningkatkan kesejahteraan hidup petani yang semakin lama semakin
menunjukkan kemerosotan di tengah pesatnya perkembangan usaha swasta.
Dalam metode sejarah dikenal dua batasan, yaitu batasan temporal atau
waktu yang digunakan adalah periode tahun 1870 sampai dengan tahun 1875.
Tahun 1870 merupakan awal mula masuknya modal swasta, selain pengusaha
Belanda, ke Hindia-Belanda yang kemudian menyebabkan berkembangnya
perkebunan-perkebunan di Hindia-Belanda swasta. Sedang tahun 1875
menunjukkan peningkatan dari perkembangan perkebunan-perkebunan besar di
Jawa dan Sumatera yang juga disertai dengan berdirinya industri-indudtri
perkebunan dalam skala besar. Sedangkan batasan spasial atau tempat yang
digunakan dalam penulisan ini adalah Kabupaten Grobogan yang terletak di Jawa
Tengah.
C. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan pada
bagian sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan
dikaji adalah sebagai berikut:
a. Bagaimana keadaan Kabupaten Grobogan sebelum pelaksanaan
Agrarische Wet1870?
b. Bagaimana pelaksanaanAgrarische Wet1870 di Kabupaten Grobogan?
c. Apa dampak Agrarische Wet terhadap kehidupan petani di Kabupaten
Grobogan tahun 1870-1875?
D. Tujuan Penulisan
Tujuan dari penulisan ini secara garis besar terbagi dua, antara lain sebagai
a. Akademis
Tulisan ini bertujuan untuk menambah wawasan khususnya menyangkut
masalah agraria di Indonesia, khususnya sejarah perkebunan dan petani
di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah periode 1870-1875.
b. Praktis
Tulisan ini bertujuan untuk merekonstruksi seperti apa sistem
perkebunan Belanda yang diterapkan di Jawa. Dengan rekonstruksi
tersebut, maka tulisan ini juga akan merekonstruksi seperti apa
dampaknya terhadap perkembangan perkebunan dan kehidupan petani.
E. Manfaat Penulisan
a. Teoretis
Tulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sebuah wacana
pembelajaran tentang pengalaman di masa lalu, sehingga masyarakat
luas dapat merencanakan masa depan yang jauh lebih baik lagi.
b. Praktis
Tulisan ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi
pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian serupa.
F. Kajian Pustaka
Sebagai suatu ilmu yang mempelajari masa lalu umat manusia maka studi
sejarah menggunakan rekaman peristiwa masa lalu sebagai sumber sejarah yang
cetak lainnya yang akan digunakan dalam penulisan ini. Dikarenakan keterbatasan
dalam menemukan dan menggunakan sumber primer, maka
sumber-sumber yang akan digunakan dalam penulisan ini merupakan sumber-sumber sekunder,
yaitu sumber yang berasal dari tangan kedua. Artinya, sumber-sumber tertulis
yang digunakan bukan merupakan tulisan orang yang terlibat secara langsung
dalam peristiwa tersebut.
Beberapa buku yang digunakan dalam penulisan ini antara lain adalah
buku yang ditulis oleh Furnivall yang berjudul Netherlands India. Dalam buku
ini, Furnivall memberikan deskripsi mengenai Hindia-Belanda, ia memberikan
uraian yang cukup lengkap mulai dari latar belakang atau masa transisi menuju
liberalisasi, dinamika sistem tersebut, dan dampak atau hasil dari penerapan
sistem tersebut di Hindia-Belanda. Tetapi, uraian-uraian tersebut terasa kurang
mendalam. Dijelaskan dalam bukunya mengenai bagaimana penerapan sistem
liberal di Hindia-Belanda dalam bidang perkebunan secara umum. Dalam
penulisan ini juga digunakan buku yang ditulis oleh Suhartono W. Pranoto dengan
judul Serpihan Budaya Feodal (Yogyakarta, 2001). Buku ini merupakan
kumpulan dari makalah atau artikel-artikel milik penulis. Beberapa tulisan yang
terangkum dalam buku ini memaparkan potret kehidupan petani, baik pada masa
kerajaan, kolonial, maupun masa kini. Memang Surakarta merupakan salah satu
daerah istimewa pada periode 1830-1875 dan kehidupan petani di daerah ini sama
memprihatinkan dengan yang terjadi di daerah perkebunan dan industri swasta
yang sedang berkembang di Hindia-Belanda. Berangkat dari tulisan tersebut
Semarang sebagai salah satu pusat perkebunan tebu dan industri gula terbesar di
Jawa, maka harusnya ini juga menjadi suatu perihal yang patut dikaji. Selain
tulisan Furnivall dan Suhartono W. Pranoto tersebut, juga digunakan buku
Sejarah Nasional Indonesia Jilid IV (Jakarta, 1984) yang disusun oleh Marwati
Djoened Poesponegoro dan kawan-kawan. Dalam buku ini, editor menguraikan
bagaimana sejarah Indonesia khususnya abad ke-18 dan ke-19. Buku ini sedikit
banyak memberikan uraian mengenai perkembangan ekonomi Indonesia pada
abad ke-19, pada bagian tersebut terdapat uraian mengenai sistem sewa tanah,
sistem tanam paksa, dan sistem liberal. Tetapi karena buku ini hanya memaparkan
pembahasan-pembahasan tersebut secara garis besar saja, maka pemaparannya
cenderung kurang mendalam.
Selain ketiga buku yang isinya telah dijelaskan secara singkat di atas,
penulisan ini juga menggunakan buku-buku lainnya dengan isi yang berkaitan
dengan topik penulisan ini. Adapun buku-buku tersebut antara lain adalah buku
yang ditulis oleh Clifford Geertz dengan judul Agricultural Involution: The
Process of Ecological Change in Indonesia (Barkeley, 1963); Soediono M. P.
Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, sebagai penyunting buku berjudul Dua
Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa
ke Masa (Jakarta, 1984); The History of Java (London, 1817) tulisan Thomas
Stamford Raffles; dan beberapa buku lainnya.
Potret kehidupan petani Indonesia merupakan sebuah kajian yang menarik
dari masa ke masa. Banyak penulis maupun peneliti mengkaji topik-topik yang
berjudul Karesidenan Pekalongan Kurun Cultuurstelsel: Masyarakat Pribumi
Menyongsong Pabrik Gula4, memberikan suatu analisis mengenai berbagai
macam dampak dari berdirinya pabrik-pabrik gula di Jawa, khususnya di
Pekalongan. Salah satu dampak yang disebutkan Edi Cahyono dalam tulisannya
adalah bahwa berdirinya pabrik gula telah menyebabkan masyarakat Jawa yang
awalnya bermata pencaharian sebagai petani beralih menjadi buruh pabrik. Dalam
penulisan ini ditemukan adanya kesamaan dengan tulisan Edi Cahyono, seperti
peralihan mata pencaharian tersebut. Setelah dikeluarkannyaAgrarische Wetpada
tahun 1870, perkebunan-perkebunan swasta berkembang dengan sangat pesat di
pulau Jawa dan Sumatera. Di Jawa, dalam kasus ini, petani juga kemudian beralih
menjadi buruh perkebunan.
Berbeda dengan kasus dalam tulisan Edi Cahyono, tulisan ini mencoba
memberikan suatu penjelasan yang bersifat klarifikasi. Selama ini masih saja ada
orang yang beranggapan bahwa ketika petani dihadapkan dengan suatu
pertumbuhan industri, maka dengan serta merta petani kemudian beralih profesi
menjadi buruh. Pendapat demikian tidaklah salah, hanya saja orang terkadang
melupakan bahwa terkadang beberapa petani tidak begitu saja meninggalkan
profesinya sebagai petani dan menjadi buruh sepenuhnya. Dengan latar
belakangan ekonomi petani pada tahun 1800-an dan terutama setelah
Cultuurstelsel, bahkan setelah dikeluarkannya Agrarische Wet 1870, petani tetap
4
mempunyai kehidupan yang subsisten.5 Dengan kehidupan ekonomi yang
subsisten petani harus bekerja lebih keras untuk dapat memenuhi kebutuhan
hidupnya, sehingga membutuhkan penghasilan tambahan. Petani tidak
meninggalkan lahan pertanian untuk bekerja di lahan perkebunan , tetapi bukan
berarti mereka tidak bekerja di lahan perkebunan. Dengan latar belakang ekonomi
tersebut bekerja di lahan pekebunan memang menjanjikan, tetapi untuk memenuhi
kebutuhan pangan petani tetap mengolah lahan pertanian. Tulisan ini akan
memberikan klarifikasi bahwa ada tiga unsusr penting yang jelas berbeda, yaitu
petani, buruh tani, dan petani yang juga buruh tani.
Dengan adanya seleksi dan kritik sumber yang dilakukan secara
bersamaan dalam langkah tersebut, maka tulisan ini mencoba menyajikan suatu
karya dengan tujuan melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada
tulisan-tulisan atau penelitian-penelitian sebelumnya.
G. Landasan Teori
Dalam penulisan ini ada beberapa konsep yang digunakan sebagai dasar
landasan teori. Konsep-konsep tersebut antara lain adalah petani, pertanian,
perkebunan,Cultuurstelsel, Kerja Wajib, dan Sistem Liberal. Petani adalah orang
yang mata pencahariannya bercocok tanam (mengolah tanah).6 Dalam penulisan
ini juga harus dibedakan secara jelas konsep antara pertanian dan perkebunan.
5
Dalam konteks penulisan ini, kehidupan subsisten yang dialami petani dimengerti sebagai ketidakmampuan secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
6
Lahan pertanian ditanami dengan tanaman-tanaman pangan, seperti padi, jagung,
dan lain-lain (bukan tanaman komersial). Sedangkan lahan perkebunan ditanami
dengan tanaman-tanaman komoditi pasar, seperti kopi, tebu, tembakau, dan
lain-lain yang termasuk kategori tanaman komersial.
Pada dasarnya Cultuurstelsel atau sistem tanam berarti pemulihan sistem
eksploitasi berupa penyerahan-penyerahan wajib yang pernah dipraktekkan VOC
dahulu. Sistem tanam mewajibkan petani untuk menanam tanaman-tanaman
komersial yang jenisnya ditentukan oleh pemerintah untuk diekspor ke pasaran
dunia. Van den Bosch, gubernur Hindia-Belanda yang menerapkan sistem
tersebut, yakin bahwa cara ini sangat efektif untuk memperoleh tanaman ekspor
yang dibutuhkan sebagai komoditi perdagangan di pasar dunia.
Istilah Kerja Wajib dalam penulisan ini berarti himpunan berbagai jenis
kerja yang wajib dilakukan oleh rakyat untuk kepentingan pemerintah, pejabat,
atau kepentingan umum.
Pada dasarnya kerja wajib pada abad ke-19 terdiri atas empat kategori,
yaitu:
a. Kerja umum (heerendiensten), terdiri dari berbagai jenis kerja di sektor
pekerjaan umum, pelayanan umum, dan penjagaan keamanan;
b. Kerja wajib pancen (pancendiensten), khusus untuk melayani rumah
tangga pejabat. Kerja ini sebenarnya termasuk kategori kerja wajib
c. Kerja wajib tanam (cultuurdiensten), meliputi sektor pertanian, terdiri
dari berbagai jenis kerja di bidang penanaman, pengolahan dan
pengangkutan tanaman wajib dari pemerintah;
d. Kerja wajib desa (desadiensten, gemeendiensten), meliputi jenis kerja
untuk kepentingan kepala desa dan bermacam-macam pekerjaan yang
berkaitan dengan kepentingan warga desa dan lingkungan desa pada
umumnya.7
Sebagai suatu sistem pajak, kerja wajib merupakan ekstraksi tenaga kerja
petani, baik untuk kepentingan raja, pemerintah kolonial maupun untuk
kepentingan masyarakat pada umumnya. Kerja wajib dan penyerahan wajib
merupakan ujung tombak dari pelaksanaan Cultuurstelsel yang mau tidak mau
berpengaruh buruk terhadap kehidupan petani dan ekonomi desa.
Dalam penulisan ini yang dimaksud dengan Sistem Liberal adalah suatu
kebijakan pemerintah kolonial dimana modal swasta diberi peluang sepenuhnya
untuk mengusahakan kegiatan di Hindia-Belanda.8Sistem ekonomi yang baru ini
menyebabkan pertumbuhan perkebunan semakin meluas. Sistem Liberal juga
berarti lembaran baru bagi petani untuk mendapatkan uang dengan cara yang baru
pula, yaitu dengan menjual tenaga atau menyewakan tanah pada pihak-pihak
swasta yang menanamkan modalnya di sektor perkebunan. Perkebunan menjadi
7
A. M. Djuliati Suryo, Eksploitasi Kolonial Abad XIX, Kerja Wajib di Karesidenan Kedu 1800-1890, (Yogyakarta, 2000), hal. 24-25.
8
pusat kekuasaan dan petani sangat tergantung pada kekuasaan tersebut. Dominasi
kekuasaan sepenuhnya ada pada perkebunan dan petani menjadi klien yang loyal.9
Raffles pada masa kekuasaannya di Hindia-Belanda menerapkan suatu
kebijakan agraria, yaitu dalam masalah tanah dengan melakukan registrasi
kadestral yang dapat dikatakan mengacu pada teori David Ricardo tentang pajak
tanah (the rent of land).10 Pola penguasaan tanah pada masa Raffles mencoba
menghilangkan peranan golongan feodal lama (penguasa lokal; raja) dan
menggantinya dengan kekuasaan pemerintah jajahan yang tetap berciri feodal.
Tanah adalah milik pemerintah. Maka, di desa semua tanah tersebut adalah milik
desa. Sehingga pemerintah desa membayar pajak yang besarnya telah ditetapkan
oleh pemerintah. Pada wilayah-wilayah dimana kekuasaan lokal tidak efektif
Raffles langsung mengundang pemodal asing untuk mengikuti lelang sehingga
sang pemenang dapat langsung menguasai tanah, penduduk, dan hasil panen.
Kemudian pada masa van den Bosch, gubernur jenderal yang kemudian
memerintah di Hindia-Belanda menggantikan Raffles, memanfaatkan kebijakan
yang telah diterapkan tersebut. Jika tidak ada pencatatan luas tanah, maka akan
sulit bagi van den Bosch untuk menerapkan Cultuurstelsel di Jawa. Dengan
adanya kebijakan Raffles tersebut, maka ia dapat dengan mudah memaksa petani
untuk meluangkan 1/5 dari luas tanahnya untuk ditanami tanaman tertentu, seperti
kopi, tebu, tembakau, dan lain sebagainya. Dapat dikatakan bahwa kebijakan
9
A. M. Djuliati Suroyo.Op. cit., hal,114.
10
tersebut mengacu pada teori dari Thomas Robert Malthus tentang sewa tanah dan
masalah penduduk. Dalam pandangan Malthus, penduduk dalam jumlah dan
tingkatan hidupnya langsung berkaitan dengan tersedianya sumber kehidupan
manusia (sumber daya produksi)11. Pulau Jawa merupakan wilayah di
Hindia-Belanda dengan jumlah penduduk terbesar pada masa itu, yang berarti tersedianya
tenaga kerja dalam julah besar yang dapat mensukseskan Cultuurstelsel yang
dicetuskan oleh van den Bosch.
Menurut Robert K. Merton kemiskinan itu bersifat fungsional, untuk itu
kemiskinan perlu dipertahankan untuk melestarikan sebuah sistem yang ada
dalam suatu lingkungan tertentu. Kemiskinan dapat disebut sebagai subsidi bagi
berbagai kegiatan ekonomi yang menguntungkan orang-orang kaya atau golongan
atas. Kemiskinan menjamin tersedianya tenaga kerja yang dapat dibayar murah
untuk pekerjaan-pekerjaan berat (kasar). Kemiskinan yang dialami oleh petani di
Grobogan selama masa-masa perkembangan perkebunan dalam jumlah besar di
daerah tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu sifat fungsional dari keadaan
tersebut untuk melestarikan sistem eksploitasi oleh kolonial maupun pemilik
modal. Jadi, dapatlah disimpulkan bahwa sifat fungsional dari kemiskinan
tersebut hanya menguntungkan golongan atas, yang dalam konteks ini ialah
pemerintah kolonial maupun pihak swasta. Sedangkan golongan bawah, yaitu
petani tidak diuntungkan dengan kemiskinan yang terus dipertahankan oleh
golongan atas.
11
Agrarische Wet 1870 pada Sistem Liberal dapat dikatakan berdasar pada
pemikiran yang serupa dengan pemikiran Raffles dan van den Bosch tersebut.
BaikAgrarische Wetmaupun Sistem Liberal itu sendiri pada dasarnya merupakan
ajang komersialisasi Hindia-Belanda dengan membuka peluang bagi para pemilik
modal swasta. Agrarische Wet 1870 semakin mempertegas hal tersebut. Dengan
Agrarische Wet 1870 pemilik modal dapat menguasai tanah, penduduk (tenaga
kerja), dan hasil panen. Kemiskinan yang terjadi juga merupakan suatu keadaan
yang perlu dilestarikan agar pemerintah kolonial maupun pemilik modal dapat
terus melakukan eksploitasi terhadap tanah maupun penduduknya.
Berbagai kebijakan dan sistem yang diterapkan pemerintah kolonial dalam
bidang agraria sepanjang tahun 1870 tentu saja mempunyai banyak dampak. Ada
banyak perubahan yang terjadi dalam kurun waktu tersebut terutama di
daerah-daerah perkebunan seperti di Grobogan. Beberapa perubahan yang sangat
menonjol adalah perubahan di bidang ekonomi dan sosial. Dampak di bidang
ekonomi dapat dilihat dengan jelas yaitu timbulnya kemiskinan di kalangan
petani, sedang untuk dampak sosial, salah satunya adalah muncul golongan baru
dalam masyarakat, yaitu golongan buruh. Untuk itu, dalam penulisan ini akan
digunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan ekonomi dan pendekatan
sosial.
Pendekatan ekonomi digunakan untuk mendeskripsikan kesejahteraan
hidup petani. Selain itu, pendekatan ini juga akan sangat membantu dalam
menelaah latar belakang dikeluarkannya Agrarische Wet 1870 pada masa liberal
tentang kehidupan petani, baik peran dan kedudukannya dalam masyarakat di
Jawa pada umumnya dan di Kabupaten Grobogan pada khususnya. Pendekatan
sosial juga digunakan untuk melihat dan menganilisis perubahan-perubahan sosial
dalam kehidupan petani di Kabupaten Grobogan pada khususnya sebagai akibat
dari perkembangan perkebunan pada tahun 1870.
H. Metode Penelitian
Sebagai sebuah studi sejarah, penelitian ini tentu menggunakan metode
sejarah. Metode sejarah dalam konteks penulisan ini adalah proses menguji dan
menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lalu.12 Tulisan ini
merupakan sebuah kajian pustaka, sehingga metode yang akan dilakukan dalam
penulisan ini adalah mengumpulkan sumber-sumber tertulis baik primer maupun
sekunder. Akan tetapi, karena keterbatasan dalam menemukan dan menggunakan
sumber primer, maka penulisan ini akan lebih banyak menggunakan sumber
tertulis yang bersifat sekunder dan juga tersier. Sumber-sumber tertulis ini tidak
hanya terbatas pada jenis buku dan media cetak lainnya, tetapi juga termasuk
beberapa sumber yang diambil dari situs-situs internet.
Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari
tiga tahapan, yaitu pertama, pengumpulan data; kedua, analisis data; dan ketiga
penulisan. Tahap pertama, pengumpulan data. Proses ini dilakukan di
perpustakaan-perpustakaan maupun dengan cara browsing melalui internet.
12
Dalam proses ini terdapat sistem seleksi untuk mendapatkan data-data yang sesuai
dengan topik yang akan dikaji.
Kedua, analisis data. Pada bagian ini data-data yang telah terkumpul pada
tahapan sebelumnya diolah melalui proses interpretasi. Data-data yang telah
diseleksi pada saat pengumpulan data dihadapkan dengan teori dan pendekatan
yang digunakan dalam penulisan ini, sehingga tercipta suatu analisis data.
Ketiga, penulisan atau historiografi. Tahap ketiga ini merupakan langkah
terakhir dari metode yang digunakan dalam penulisan ini. Setelah melalui ketiga
tahapan sebelumnya, maka terakhir adalah menyajikan data-data yang telah
diinterpretasikan tersebut dalam bentuk tulisan, yaitu skripsi.
I. Sistematika Penulisan
Sesuai dengan garis besar permasalahan yang telah dipaparkan pada
bagian perumusan masalah di awal, maka studi sejarah sekitar dampak dari
pelaksanaan Agrarische Wet 1870 terhadap kehidupan petani di Kabupaten
Grobogan dari tahun 1870 sampai dengan tahun 1875 disusun menurut
sistematika penulisan yang terpadu dalam urutan waktu tertentu.
Studi ini di awali dengan uraian deskriptif-naratif mengenai kehidupan
agraris di Hindia-Belanda pada abad ke-19, khususnya di Jawa. Bagian ini akan
memaparkan bagaimana kondisi Hindia-Belanda di bawah pemerintahan Raffles–
sebagai pengantar–juga di bawah van den Bosch (1830-1870).
Kebijakan-kebijakan agraria apa saja yang telah diterapkan selama masa itu. Sedikit
pelaksanaannya yang kemudian menimbulkan berbagai kritikan hingga kemudian
dihapuskannya Sistem Tanam tersebut.
Pada bab II dipaparkan tentang kondisi Kabupaten Grobogan sebelum
pelaksanaanAgrarische Wet 1870. Uraian tersebut akan disusun secara kronologis
dimulai dari periodeCultuurstelselsampai dengan periode Sistem Liberal.
Bab III pelaksanaanAgrarische Wet 1870. Uraian analisis ini akan diawali
dengan uraian mengenai pelaksanaan Sistem Liberal sebagai suatu haluan politik
baru di Hindia-Belanda yang kemudian melahirkan kebijakan-kebijakan baru,
seperti Agrarische Wet 1870. Setelah itu dilanjutkan dengan uraian mengenai
pelaksanaannya.
Bab IV sebagai inti dari ketiga bab analisis dalam penulisan ini
memaparkan mengenai dampak dari pelaksanaan Agrarische Wet 1870 terhadap
kehidupan petani di Kabupaten Grobogan tahun 1870-1875. Dapat dikatakan
bahwa Agrarische Wet 1870 memberi dampak langsung terhadap liberalisasi
perkebunan dan dampak tidak langsung terhadap kehidupan petani. Agrarische
Wet yang dikeluarkan tahun 1870 merupakan undang-undang yang dikeluarkan
untuk mengatur penanaman modal swasta yang masuk ke Hindia-Belanda.
Sebagian besar dari modal-modal swasta tersebut menanamkan modalnya di
bidang perkebunan, sehingga perkembangan pesat perkebunan di Hindia-Belanda
tidak terelakkan lagi. Keadaan ini yang kemudian memberikan dampak terhadap
Bab V merupakan bab penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari analisis
terhadap rumusan permasalahan yang telah dipaparkan penjelasannya pada
21
A. Gambaran Umum dan Sejarah Kabupaten Grobogan
Kabupaten Grobogan merupakan salah satu kabupaten yang terletak di
Jawa Tengah dengan ibu kotanya Purwodadi. Kabupaten ini berbatasan dengan
Kabupaten Blora di sebelah timur; Kabupaten Ngawi (Jawa Timur), Kabupaten
Sragen, dan Kabupaten Boyolali di sebelah selatan; Kabupaten Semarang di
sebelah barat; serta Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Pati di
sebelah utara. Secara goegrafis, Kabupaten Grobogan merupakan lembah yang
diapit oleh dua pegunungan, yaitu Pengunungan Kendeng di bagian selatan dan
Pegunungan Kapur Utara di bagian utara. Bagian tengah wilayahnya berupa
dataran rendah.
Kabupaten Grobogan merupakan kabupaten terluas kedua di Jawa Tengah
setelah Kabupaten Cilacap. Kabupaten Grobogan terbagi ke dalam 19 buah
kecamatan yang terdiri dari 273 desa dan 7 kelurahan. Pusat pemerintahan
kabupaten Grobogan berada di kecamatan Purwodadi.
Pada jaman kerajaan, kabupaten Grobogan merupakan daerah
mancanagari1dari Kerajaan Mataram. Pada waktu itu, Susuhunan Amangkurat IV
mengangkat seorang abdinya, yaitu Ng. Wongsodipo, untuk menjadi Bupati di
1 Mancanagari merupakan wilayah kerajaan yang diperoleh dengan cara
Grobogan dengan nama RT Martopuro. Wilayah RT. Martopuro pada saat itu
meliputi wilayah Sela, Teras Karas, Wirosari, Santenan, Grobogan, dan beberapa
weilayah di Sukowati bagian utara Begawan Sala.2
RT Martapuro sendiri menetap di Kartasura. Lalu, ketika terjadi
kekacauan di Kartasura maka pengawasan terhadap wilayah Grobogan ia
serahkan kepada RT Suryonagoro yang tidak lain adalah menantunya sendiri. Di
bawah pemerintahan RT Suryonagoro Grobogan menjadi ibu kota kabupaten. RT
Suryonagoro juga menciptakan struktur pemerintahan pangreh praja, ia
menciptakan jabatan-jabatan pemerintahan dari jabatan bupati sampai dengan
jabatan bekel di desa-desa. Tetapi, pada tahun 1864 ibu kota kabupaten berpindah
ke Purwodadi.
Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, Grobogan merupakan bagian
dari Karesidenan Semarang. Baru pada tahun 1905 dengan dikeluarkannya
Decentralisatie Besluit oleh pemerintah Hindia-Belanda, Grobogan diberi hak
otonomi dan dapat membentuk Dewan Daerah sehingga pada tahun 1908,
Grobogan akhirnya mendapatkan otonomi penuh dari pemerintah Hindia-Belanda.
Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, daerah-daerah di Indonesia
dibagi ke dalam daerah propinsi dan daerah propinsi ini dibagi lagi menjadi
bagian-bagian yang lebih kecil. Kemudian ketetapan tersebut diperjelas dengan
dikeluarkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1948 tentang pemerintahan daerah.
Pasal 1 dari undang-undang ini menyatakan bahwa daerah Negara Republik
2
Indonesia tersusun dalam tiga tingkatan, yaitu tingkat propinsi, tingkat kabupaten
dan tingkat desa.
Pembentukan daerah-daerah tingkat dua di propinsi Jawa Tengah baru
dilakukan 2 tahun setelah undang-undang tentang pembagian daerah Negara
Republik Indonesia tadi dikeluarkan. Tepatnya, pada tahun 1950 dengan
dikeluarkannya Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 dibentuklah daerah-daerah
tingkat dua di propinsi Jawa Tengah. Jadi, secara hukum pembentukan Kabupaten
Grobogan sebagai daerah tingkat dua dalam proponsi Jawa Tengah didasari oleh
undang-undang tersebut.
B. Penduduk Kabupaten Grobogan
Pada tahun 2007, penduduk di kabupaten Grobogan tercatat berjumlah
1.385.817 jiwa. Dari jumlah ini sebagian besar penduduknya bermata pencaharian
sebagai petani. Oleh karena faktor inilah pada masa Cultuurstelsel maupun masa
Liberal, kabupaten Grobogan menjadi daerah pilihan pemerintah kolonial dan
pihak swasta untuk mendirikan usaha-usaha perkebunannya.
Pulau Jawa merupakan pulau dengan jumlah penduduk terbesar di
Hindia-Belanda pada masa Cultuurstelsel. Hal ini berarti bahwa daerah-daerah di pulau
Jawa memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk keberhasilan usaha-usaha
perkebunan pemerintah, yaitu ketersediaan sumber daya manusia yang dibutuhkan
untuk dijadikan tenaga kerja perkebunan. Hal ini juga menjadi lebih efektif lagi
karena penduduk di pulau Jawa memang merupakan masyarakat agraris, dimana
Dalam pelaksanaannya, Cultuurstelsel membawa penderitaan bagi
penduduk di Hindia-Belanda. Di kabupaten Grobogan, yang merupakan salah satu
pusat perkebunan pemerintah pada saat itu, para petani sangat menderita oleh
eksploitasi pemerintah kolonial melalui perkerjaan-pekerjaan wajib untuk
perkebunan pemerintah. Penderitaan petani di Grobogan pada periode
Cultuurstelsel mencapai puncaknya pada akhir tahun 1840-an dengan terjadinya
bencana kelaparan dan wabah penyakit yang menimpa para petani. Sebagai akibat
dari bencana kelaparan dan wabah penyakit tersebut ialah penurunan jumlah
penduduk yang sangat drastis. Semula penduduk di kabupaten Grobogan
berjumlah 89.500 jiwa, lalu setelah dilaksanakannya Cultuurstelsel dan dengan
adanya bencana kelaparan dan wabah penyakit pada akhir tahun 1840-an jumlah
tersebut berkurang menjadi 9.000 jiwa.
Dinilai memiliki andil dalam penderitaan petani, oleh kaum humanis
Belanda, Cultuurstelsel dituntut penghapusannya. Penghapusan Cultuurstelsel
secara resmi akhirnya terlaksana pada tahun 1870 yang ditandai dengan
kemenangan kaum liberal di parlemen Belanda yang juga menandakan
dimulainya haluan politik baru di Hindia-Belanda, yaitu Sistem Liberal.
Pada masa Liberal, kabupaten Grobogan masih menjadi salah satu daerah
di Jawa yang menjadi pilihan para pemilik modal swasta untuk mendirikan
usaha-usaha perkebunan mereka. Perubahan fase industri perkebunan yang terjadi pada
periode ini tidak membawa banyak perubahan positif dalam kehidupan petani di
kabupaten Grobogan. Pada periode Liberal, petani tetap menjadi korban
swasta sama terikatnya dengan saat petani bekerja di perkebunan pemerintah pada
periode Cultuurstelsel. Meskipun dengan bekerja di perkebunan-perkebunan
swasta berarti petani bebas dari kerja rodi, tetapi sistem kontrak di perkebunan
swasta bagai ikatan kerja rodi yang diterapkan pemerintah kolonial. Pihak swasta
memberikan sanksi tertentu, dari sanksi-sanksi ringan hingga berat, bagi buruh
tani yang mencoba melarikan diri dari perkebunan selama masa kontraknya masih
berlaku.
Pihak swasta pun tidak memberikan tunjangan-tunjangan kesejahteraan
bagi para buruhnya. Hal ini disebabkan oleh adanya pajak-pajak yang harus
dibayarkan oleh pihak swasta kepada pemerintah Hindia-Belanda. Sehingga
petani tetap tidak bisa memperbaiki taraf hidupnya ke tingkat yang lebih baik.
Tetapi, petani di kabupaten Grobogan dapat bertahan bahkan hingga
sekarang. Dapat dibuktikan dengan masih adanya sektor pertanian dan
perkebunan di daerah ini. Hingga sekarang pun sebagian besar penduduknya
bekerja di sektor pertanian. Perkembangan pertanian dan perkebunan di kabupaten
Grobogan juga disebabkan karena ketersediaan sumber daya manusianya.
C. Sektor Perkebunan di Kabupaten Grobogan
Sekitar seperempat bagian dari wilayah kabupaten Grobogan merupakan
lahan perkebunan. Beberapa faktor, seperti faktor geografis dan juga sumber daya
manusianya merupakan faktor utama yang mendukung keberlangsungan sektor
memungkinkan penduduk setempat untuk membudidayakan tanaman-tanaman
pertanian maupun perkebunan.
Bagian tengah wilayah kabupaten Grobogan merupakan pusat pemukiman
penduduk dan lahan pertanian juga perkebunan. Dua pegunungan yang mengapit
wilayah kabupaten Grobogan merupakan kawasan huutan jati, mahoni dan hutan
campuran yang berfungsi sebagai hutan resapan air hujan. Lembah yang
membujur dari timur ke barat merupakan lahan pertanian yang produktif. Daerah
lembah ini sebagian bahkan telah didukung dengan adanya saluran irigasi, jalan
raya dan jalur kereta api.
Adapun ketersediaan lahan perkebunan di kabupaten Grobogan adalah
sebagaiman tercantum dalam tabel berikut;
Tabel 1 Ketersediaan Lahan Perkebunan di kabupaten Grobogan No. Sektor/Komoditi Luas Lahan/Potensi
1. Perkebunan: Kelapa Lahan yang sudah digunakan (Ha): 3, 975 2. Perkebunan: Tembakau Lahan yang sudah digunakan (Ha): 1,070 3. Perkebunan: Tebu Lahan yang sudah digunakan (Ha): 577
4. Perkebunan: Jambu Mete Lahan yang sudah digunakan (Ha): 308 5. Perkebunan: Kapas Lahan yang sudah digunakan (Ha): 248 6. Perkebunan: Kopi Lahan yang sudah digunakan (Ha): 19
Sumber: Data Statistik Perkebunan Indonesia 2006-2008. Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan Jakarta 2007.
Seperti tercantum dalam tabel di atas, perkebunan-perkebunan seperti
perkebunan tembakau, perkebunan tebu dan perkebunan kopi masih tetap
berlangsung di daerah Grobogan seperti halnya pada periode Cultuurstelsel
(1830-1870) sampai dengan periode Liberal (1870-1875). Meskipun lahan
perkebunannya tidak begitu luas, tetapi hasilnya masih merupakan komoditi
Perkebunan kelapa menempati posisi pertama dengan lahan yang sangat luas,
hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Grobogan membudidayakan kelapa.
Sebagian besar hasilnya diolah menjadi santan atau bahkan ada yang diolah
menjadi minyak kelapa. Sedangkan untuk perkebunan lainnya hanya terdapat di
beberapa kecamatan saja dengan lahan yang tidak begitu luas bahkan sempit,
seperti lahan untuk perkebunan kopi yang hanya seluas 19 Ha.
Untuk lebih rinci, hasil-hasil perkebunan tersebut dapat dilihat dalam tabel
berikut;
Non Unggulan Produksi tahun terakhir (2006): 3.00 ton.
Pada periode ini, penduduk di Kabupaten Grobogan lebih mempunyai
variasi dalam membudidayakan jenis-jenis tanaman di lahan-lahan perkebunan
yang tersedia. Hal ini karena sudah tidak adanya ketentuan-ketentuan yang
mengatur jenis tanaman apa saja yang boleh ditanam oleh petani, seperti yang
terjadi pada masaCultuurstelsel maupun masa liberal. Pada masaCultuurstelsel,
petani terikat oleh ketentuan-ketentuan pemerintah Hindia-Belanda dalam
pengolahan lahan pertanian mereka dan jenis-jenis tanaman perkebunan yang
harus dibudidayakan. Sedangkan pada masa liberal, pihak swasta menggantikan
posisi pemerintah Hindia-Belanda. Tuntutan pasar yang menentukan jenis-jenis
tanaman perkebunan pada masa itu. Kemudian pada periode ini (2006-2008) juga
jenis-jenis tanaman perkebunannya mengikuti tuntutan pasar, tetapi berbeda
dengan pada masa liberal. Petani bekerja dengan lebih bebas dalam mencapai
hasil yang telah ditargetkan dan perhitungan untung-rugi pun tidak begitu
dominan dalam prinsip usaha perkebunan pada masa ini.
Pada periode ini (2006-2008) terdapat penambahan jenis perkebunan,
seperti perkebunan kelapa, perkebunan jambu mete dan perkebunan kapas yang
juga merupakan perkebunan primer. Bahkan perkebunan kelapa menjadi
perkebunan dengan hasil paling banyak diantara perkebunan-perkebunan lainnya.
Selain perkebunan-perkebunan primer tersebut masih terdapat beberapa jenis
perkebunan lainnya seperti perkebunan jarak pagar.
Perkembangan perkebunan pada masa ini tentu tak bisa terlepas begitu
saja dengan perkebunan-perkebunan sebelumnya. Terbukti dengan masih
tembakau dan perkebunan kopi yang juga merupakan perkebunan-perkebunan
penting pada masaCultuurstelselmaupun masa liberal.
Pada masaCultuurstelsel, kabupaten Grobogan juga merupakan salah satu
pusat perkebunan milik pemerintah kolonial. Pada masa ini, rakyat diharuskan
menyerahkan 1/5 bagian dari lahan pertaniannya untuk ditanami dengan tanaman
komersial yang jenisnya ditentukan oleh pemerintah. Pemerintah mewajibkan
rakyat untuk menanam tanaman-tanaman seperti tebu, tembakau dan kopi yang
selanjutnya hasilnya diserahkan kepada pemerintah Hindia-Belanda. Belanda
memperoleh pendapatan yang sangat besar dari pelaksanaanCultuurstelsel.
Akan tetapi, beban rakyat semakin besar dengan adanya berbagai jenis
kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah Hindia-Belanda. Selain
harus menanam tanaman ekspor, mereka masih harus menjalani kerja rodi
membangun sarana-prasarana umum, juga masih harus membayar pajak terhadap
pemerintah. Penderitaan petani akibat eksploitasi selama periode Cultuurstelsel
akhirnya memuncak pada akhir tahun 1840-an dengan terjadinya bencana
kelaparan dan wabah penyakit. Bencana tersebut menyebabkan berkurangnya
jumlah penduduk di beberapa wilayah di Jawa. Sebagai contoh adalah wilayah
Demak dan Grobogan yang mengalami penurunan jumlah penduduk yang sangat
drastis. Di Grobogan, penduduknya semula berjumlah sekitar 89.500 jiwa, pada
akhir tahun 1840-an berkurang menjadi sekitar 9.000 jiwa.
Banyaknya angka pengurangan tersebut (sekitar 80.500 jiwa) disebabkan
karena ketidakmampuan rakyat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka
lebih banyak menghabiskan waktu untuk menanam tanaman-tanaman wajib dari
pemerintah daripada menanam tanaman-tanaman pangan, seperti padi ataupun
jagung. Sedangkan bekerja wajib pada pemerintah tidaklah mendapatkan upah
bahkan petani masih mempunyai kewajiban untuk membayar pajak.
Dengan adanya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan
Cultuurstelsel, banyak kritikan yang muncul dari negeri Belanda yang menuntut
penghapusan Cultuurstelsel terutama kritikan dari kaum liberal dan kaum
humanis. Kaum liberal berpendapat bahwa pemerintah seharusnya tidak ikut
campur dalam urusan ekonomi, pihak swastalah yang lebih tepat mengurusi
bidang tersebut sedang pemerintah fungsinya adalah menjadi pelindung warga
negara, penyedia prasarana, penegak hukum, dan pengatur keamanan dan
ketertiban. Sedang kaum humanis mengkritik masalah kemiskinan petani.
Kritikan kaum humanis ini berangkat dari adanya kasus kelaparan yang menimpa
petani di Jawa pada akhir tahun 1840-an.
Kasus kelaparan dan wabah penyakit yang menimpa petani di Jawa,
termasuk di Grobogan disebabkan oleh ketidaksiapan petani dalam menghadapi
bencana kelaparan. Adapun beberapa alasan mengapa petani di kabupaten
Grobogan pada saat itu tidak siap menghadapi bencana kelaparan dan wabah
penyakit yang menyerang pada akhir tahun 1840-an ialah karena; pertama,
ketentuan Cultuurstelsel yang mewajibkan rakyat untuk menyediakan 1/5 bagian
dari lahan pertaniannya untuk ditanami tanaman komersial membuat
berkurangnya lahan pertanian yang digunakan untuk menanam tanaman pangan,
Bahkan tidak menutup kemungkinan untuk tidak adanya lagi lahan untuk tanaman
pangan, karena petani akhirnya memilih untuk menanami seluruh lahan
pertaniannya dengan tanaman perkebunan. Pemikiran ini didasari oleh tingginya
harga hasil-hasil perkebunan dan juga tingkat keberhasilan lahan bertanaman
campuran. Tanaman pangan seperti padi pada akhirnya hanya ditanam sekedar
untuk pemenuhan kebutuhan pokok atau untuk kebutuhan sehari-hari saja karena
tanaman pangan seperti padi tidak termasuk dalam tanaman ekspor, sedangkan
tanaman perkebunan memang ditujukan sebagai komditi ekspor yang tentu saja
dapat dijamin memiliki harga yang jauh lebih tinggai, terutama untuk tanaman
tebu. Permintaan terhadap ekspor gula tebu sangat tinggi pada masa ini,
konsumen di Eropa sangat menyukai ekspor gula tebu dari Hindia-Belanda.
Artinya, ketika tanaman pangan ditanam bercampuran dengan tanaman
perkebunan maka ada kemungkinan bahwa hanya tanaman perkebunan saja yang
tumbuh dengan subur.
Kedua, perawatan tanaman perkebunan menyita banyak waktu sehingga
petani tidak lagi mempunyai waktu untuk mengurusi lahan pertaniannya. Berbeda
dengan tanaman pertanian, contohnya padi, yang tidak memerlukan perawatan
khusus hingga tiba saatnya dipanen. Sedangkan untuk tanaman perkebunan,
contohnya tembakau, memerlukan perawatan dan pemeliharaan yang kompleks.
Hal inilah yang kemudian menyebabkan banyak petani yang memilih untuk
menanami seluruh lahan pertaniannya dengan tanaman perkebunan. Ketiga,
sebagai akibat dari terabainya tanaman pangan, terutama padi, membuat harga
seperti padi masih merupakan konsumsi pokok masyarakat di Hindia-Belanda.
Sementara itu, daya beli petani sangat rendah. Kelangkaan padi dan rendahnya
daya beli petani mengakibatkan ketidaksiapan ketika bencana kelaparan melanda.
Kurangnya pemenuhan terhadap kebutuhan pokok ini tentu saja kemudian juga
mengakibatkan petani lebih mudah terserang berbagai penyakit. Oleh karena itu,
ketika terjadi bencana kelaparan dan wabah penyakit malaria yang melanda Jawa
pada masa Cultuurstelsel, petani tidak dapat mengatasinya. Hal inilah yang
kemudian mengakibatkan terjadinya penurunan jumlah penduduk di kabupaten
Grobogan secara drastis, yaitu dari penduduk yang semula berjumlah 89.500 jiwa
setelah terjadinya bencana kelaparan dan wabah penyakit berkurang menjadi
hanya 9.000 jiwa saja. Angka pengurangan yang sangat besar ini menunjukkan
bagaimana buruknya kesejahteraan hidup petani di kabupaten Grobogan pada
masaCultuurstelsel.
Masalah kesejahteraan hidup petani di Hindia-Belanda yang tetap
memprihatinkan akhirnya mengundang berbagai kritikan di Belanda. Kritikan
yang paling menonjol ialah dari kaum humanis yang beranjak dari kasus
kelaparan dan wabah penyakit yang melanda petani di Jawa, khususnya di
Grobogan dan Demak pada akhir tahun 1840-an. Kritikan-kritikan dari kaum
humanis harus disampaikan dalam rapat parlemen agar tujuan untuk
menghapuskan Cultuurstelsel dapat tercapai. Dengan demikian, kaum liberal
merupakan tokoh yang dapat menyuarakan kritikan tersebut di parlemen. Kaum
liberal yang juga sudah lama menentang kaum konservatif akhirnya
di Hindia-Belanda, yaitu Sistem Liberal. Dimulainya Sistem Liberal berarti juga
penghapusan Cultuurstelsel secara resmi pada tahun 1870. Sistem Liberal dapat
diartikan sebagai pengambilalihan kuasa ekonomi dari tangan pemerintah oleh
kaum liberal. Perekonomian bukan lagi dikuasai oleh pemerintah melainkan oleh
pihak swasta atau pemilik modal. Liberalisme berarti terbukanya peluang bagi
modal swasta untuk mengusahakan kegiatan di Hindia-Belanda. Hal ini juga dapat
disebut sebagai komersialisasi Hindia-Belanda, terlebih lagi dengan
dikeluarkannyaAgrarische Wet pada tahun 1870. Jadi, pada tahun 1870 ini dapat
dikatakan bahwa pemerintah Hinda-Belanda menerapkan “politik pintu terbuka”.
Menurut Ramadhan, gagasan ekonomi liberal didasarkan pada sebuah
pandangan bahwa setiap individu harus diberi akses seluas mungkin untuk
melakukan kegiatan-kegiatan ekonominya, tanpa ada campur tangan dari negara.
Atas dasar tersebut, maka campur tangan negara tidak diperlukan lagi.3Meskipun
di Hindia-Belanda sudah mulai berjalan politik “pintu terbuka”, tetapi para
pemilik modal masih enggan menanamkan modalnya terutama pada sektor
perkebunan. Hal ini disebabkan karena pada waktu itu belum ada perangkat
hukum yang menjamin keberhasilan usaha perkebunan dalam skala besar.
Tidak berbeda jauh dengan masa Cultuurstelsel, pada masa Liberal
kabupaten Grobogan pun menjadi salah satu wilayah yang menjadi pilihan para
pemilik modal swasta untuk mendirikan usaha-usaha perkebunan mereka. Faktor
geografis dan ketersediaan tenaga kerja tetap memegang peranan penting sebagai
3
faktor yang menyebabkan kabupaten Grobogan menjadi daerah perkembangan
usaha-usaha perkebunan pihak swasta.
Dengan latar belakang demikian, maka tidak mengherankan ketika melihat
keberadaan sektor perkebunan di kabupaten Grobogan yang masih berlangsung
35
Jauh sebelum perkebunan milik swasta berkembang pesat pada abad
ke-19, usaha ekspor sebenarnya sudah dimulai sejak lama. Perdagangan antar dunia
sudah dimulai sejak abad ke-16, ketika bangsa-bangsa Eropa mulai berlayar ke
Asia Tenggara. Komoditi-komoditi perdagangan pasar dunia tersedia dalam
jumlah yang banyak di Asia Tenggara, sehingga semakin lama bangsa-bangsa
Eropa semakin banyak berdatangan ke Asia. Mulai dari Spanyol, Portugis,
Inggris, sampai Belanda berlomba-lomba menguasai nusantara (sebutan Indonesia
jaman dulu). Pada akhirnya Belanda berhasil menguasai nusantara pada tahun
1602 melalui VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie). VOC dikenal dengan
monopolinya terhadap perdagangan rempah-rempah di nusantara. Pada akhir abad
ke-18, VOC mengalami kebangkrutan. Kekuasaan terhadap nusantara beralih ke
tangan pemerintah negeri induk.
Beberapa komoditi seperti lada, pala, cengkeh, dan kayu manis yang
sebelumnya hanya dikumpulkan dari tanaman liar mulai dibudidayakan oleh
penduduk di berbagai daerah di Hindia-Belanda. Gejala ini menunjukkan bahwa
usaha perkebunan sudah dimulai. Negara sejak awal telah menjadi penguasa
utama yang memonopoli usaha perkebunan, baik sebagai pemilik maupun sebagai
pedagang hasil perkebunan. Proses produksi dan pemasaran ditentukan oleh
institusi tradisional, sementara itu rakyat hanya berfungsi sebagai penyedia tenaga
kerja dan tidak memiliki kekuatan tawar menawar untuk menentukan besar
kecilnya nilai dan hasil produksi.
Perkebunan di Hindia-Belanda, terutama di Jawa dan Sumatera, telah
tumbuh dan berkembang sejak masaCultuurstelsel(1830). Pada masa itu, van den
Bosch memutuskan untuk menerapkanCultuurstelseldan mengembangkan sektor
perkebunan semaksimal mungkin. Langkah van den Bosch tersebut adalah untuk
menyelamatkan perekonomian Hindia-Belanda dan juga negeri induk yang sedang
mengalami krisis dan ancaman kebangkrutan. Pada masa itu terjadi eksploitasi
dalam sektor perkebunan secara besar-besaran dan hal tersebut dikuasai
sepenuhnya oleh pemerintah.
Setelah kebijakan Culturstelsel yang diterapkan oleh van den Bosch
(1830), usaha perkebunan menjadi sumber keuangan yang penting untuk
pemerintah kolonial di Hindia-Belanda. Oleh karena itu, pemerintah sangat
memperhatikan bidang tersebut. Pemerintah Hindia-Belanda mempunyai kuasa
penuh untuk melakukan eksploitasi dalam bidang tersebut, baik eksploitasi
terhadap tanah, tenaga kerja, maupun hasilnya.
Memasuki abad ke-19, sebuah perubahan besar mulai terjadi dalam usaha
perkebunan di Indonesia. Berbeda dari kebijakan-kebijakan sebelumnya yang
bersifat terbatas, pemerintah Hindia Belanda yang menggantikan posisi VOC
berusaha memaksimalkan potensi lahan-lahan yang subur, lahan-lahan yang
belum diolah, dan tenaga kerja penduduk lokal untuk menghasilkan berbagai jenis
Dengan masuknya modal swasta ke Belanda, maka
Hindia-Belanda menjadi sebuah koloni yang sangat komersial bagi negeri Hindia-Belanda. Untuk
mengatur modal-modal swasta yang masuk ke Hindia-Belanda, dewan menteri de
Waal mengeluarkan Agrarische Wet (Undang-Undang Agraria). Banyaknya
modal swasta yang masuk ke Hindia-Belanda telah menyebabkan tumbuh dan
berkembangannya bidang perkebunan. Sejak dikeluarkannya Agrarische Wet,
perkebunan-perkebunan besar mulai berdiri di Hindia-Belanda, khususnya di
Jawa dan Sumatera. Berbeda dengan eraCultuurstelsel, eksploitasi dalam sektor
perkebunan dikuasai oleh pemilik modal atau pihak swasta.
A. Cultuurstelseldan Pelaksanaan Sistem Liberal di Hindia-Belanda
Keadaan ekonomi di Hindia-Belanda sejak awal abad ke-19 dapat
dikatakan sedang berada dalam masa kritis. Ada beberapa faktor yang menjadi
penyebab memburuknya keadaan ekonomi tersebut. Faktor pertama adalah
adanya Perang Jawa (1825-1830). Perang tersebut menyebabkan pemerintah
Hindia-Belanda harus mengeluarkan banyak uang untuk membiayai peperangan.
Pemerintah Hindia-Belanda berjuang sangat keras untuk menghentikan
peperangan, karena peperangan tersebut dianggap mengancam keberadaan
kolonial di Hindia-Belanda, khususnya di Jawa. Seharusnya masalah keuangan
tersebut dapat diatasi dengan pemasukan dari pajak yang telah diterapkan di Jawa,
akan tetapi pemasukan sektor ini belum optimal. Penarikan pajak belum berjalan
rakyat menyerahkan pajak dalam bentuk hasil bumi, tetapi pada masa kolonial
pajak dibebankan dalam bentuk uang.
Faktor kedua adalah hilangnya sumber kas negara. Kekuasaan Napoleon
Bonaparte atas wilayah Belanda sejak 1795–yang kemudian dibentuk menjadi
Kerajaan Belanda pada tahun 1806, sebelum akhirnya diinkorporasi ke dalam
Kekaisaran Perancis pada tahun 1810–telah menguntungkan Inggris untuk
menguasai beberapa koloni Belanda. Setelah Kongres Wina tahun 1815 Belanda
memperoleh kembali kemerdekaannya, tetapi Belgia yang masuk ke dalam
kedaulatannya memberontak pada tahun 1830. Pada akhirnya Belgia memisahkan
diri dari Belanda pada tahun 1839. Dengan pemisahan Belgia, Belanda kehilangan
industrinya. Belanda kehilangan tanah domein negara di Belgia yang disewakan
sebagai sumber keuangan. Tidak hanya kehilangan Belgia, Belanda juga
kehilangan Afrika Selatan dan Ceylon1. Keadaan tersebut tentu saja memperburuk
kondisi perekonomian Belanda.
Faktor ketiga adalah dominasi Inggris dalam bidang perdagangan. Belanda
kalah dalam persaingan perdagangan di pasar Eropa, terutama dalam bidang
ekspor. Inggris mempunyai modal yang jauh lebih besar dibandingkan dengan
Belanda, sehingga dapat dengan mudah menguasai pasar Eropa. Modal Belanda
banyak terserap untuk membiayai Perang Jawa dan untuk mengatasi masalah
ekonomi di negeri Belanda sendiri.
Dari ketiga faktor di atas, dua faktor terakhir terlihat seakan-akan tidak
berhubungan dengan Hindia-Belanda. Tidak demikian jika dilihat secara
1
keseluruhan. Artinya, krisis-krisis seperti disebutkan di atas merupakan ancaman
kebangkrutan bagi negeri induk, yaitu Belanda. Hindia-Belanda, sebagaimana
halnya Belgia, Afrika Selatan dan Ceylon, merupakan salah satu daerah koloni
Belanda. Bagi Belanda, sebagai negeri induk, koloni-koloni ini merupakan
sumber devisa yang menyumbangkan pendapatan untuk menunjang
perekonomian negeri induk. Maka, ketika salah satu daerah koloninya tidak lagi
menyediakan devisa bagi negeri induk, yang terjadi ialah ketidakseimbangan
ekonomi di negeri induk. Sehingga untuk menyeimbangkannya kembali maka
daerah koloni yang lainnya harus memberikan devisa yang lebih besar daripada
sebelumnya. Dalam hal ini, Hindia-Belanda merupakan salah satu daerah koloni
yang diharapkan dapat menyelamatkan negeri induk dari ancaman kebangkrutan.
Lalu, ketika hal tersebut berhasil, Belanda akan mempunyai modal yang cukup
untuk dapat menyaingi Inggris dalam perdagangan di pasar Eropa.
Oleh karena itu, Van den Bosch, gubernur jenderal Hindia-Belanda
berikutnya, harus memikirkan cara untuk menjadikan Hindia-Belanda sebagai
daerah koloni yang dapat menyelamatkan Belanda dari ancaman kebangkrutan.
Bertolak dari prinsip Baud, van den Bosch akhirnya mencetuskan Cultuurstelsel
(1830-1870). Dalam pandangan Bosch, perkebunan tidak akan berhasil jika petani
tidak dipaksa dengan ketentuan-ketentuan pemerintah. Oleh karena itu,
Cultuurstelsel yang diprakarsai oleh Bosch memuat tujuh ketentuan sebagai
1. Persetujuan-persetujuan akan dilakukan dengan penduduk agar mereka
menyediakan sebagian dari tanahnya untuk penanaman tanaman
dagangan yang dapat dijual di pasaran Eropa;
2. Bagian dari tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan ini
tidak boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki
penduduk desa;
3. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman dagangan tidak
boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi;
4. Bagian dari tanah yang disediakan untuk menanam tanaman dagangan
dibebaskan dari pembayaran pajak tanah;
5. Tanaman dagangan yang dihasilkan di tanah-tanah yang disediakan,
wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia-Belanda; jika nilai
hasil-hasil tanaman dagangan yang ditaksir itu melebihi pajak tanah yang
harus dibayar rakyat, maka selisih positifnya harus diserahkan kepada
rakyat;
6. Panen tanaman dagangan yang gagal harus dibebankan kepada
pemerintah, sedikit-dikitnya jika tidak disebabkan oleh kurang rajin
atau ketekunan dari pihak rakyat;
7. Penduduk desa mengerjakan tanah-tanah mereka di bawah
pengawasan kepala-kepala mereka, sedangkan pegawai-pegawai Eropa
panen, dan pengangkutan tanaman-tanaman berjalan dengan baik dan
tepat pada waktunya.2
Jalan raya Anyer-Panarukan yang dibangun Daendels turut memberikan
kegunaan besar pada masa Cultuurstelsel. Perkebunan-perkebunan di Jawa yang
mulai berkembang sejakCultuurstelselsebagian besar berada di sepanjang pesisir
utara Jawa. Selain karena kualitas tanah yang digunakan untuk perkebunan harus
merupakan tanah dengan tingkat kesuburan tinggi atau dapat dikatakan sebagai
tanah dengan kualitas terbaik, sebagian besar terdapat di sepanjang daerah
tersebut juga demi kemudahan dalam pengangkutan hasil-hasil perkebunan
tersebut menuju pelabuhan sepanjang pantai utara Jawa untuk kemudian diangkut
oleh kapal-kapal menuju Eropa.
Dengan demikian Jawa menjadi salah satu pusat perkembangan
perkebunan, selain Sumatera. Karesidenan Semarang, Jawa Tengah, merupakan
salah satu pusat perkebunan-perkebunan besar di Jawa, salah satu daerahnya
adalah Kabupaten Grobogan. Di daerah tersebut berkembang beberapa
perkebunan, seperti perkebunan kopi dan tebu. Keberhasilan Bosch dalam
menangani keterpurukan ekonomi negeri induk tidak dapat dipungkiri.
Cultuurstelsel yang diprakarsainya berhasil meningkatkan ekspor
tanaman-tanaman perkebunan dari Hindia-Belanda, sehingga sedikit demi sedikit
perekonomian negeri induk mulai membaik.
Culturstelsel dengan berbagai penyimpangan dalam pelaksanaannya
kemudian mengundang kritikan dari kaum humanis dan kaum liberal Belanda.
2
Akhirnya tahun 1870, Cultuurstelsel dihapuskan secara resmi yang ditandai
dengan kemenangan kaum liberal di parlemen Belanda. Meskipun untuk beberapa
jenis tanaman sudah mulai dihapuskan sejak tahun 1860 dan beberapa jenis
tanaman juga ada yang baru dihapuskan setelah tahun 1870. Penghapusan
Cultuurstelsel dan kemenangan kaum liberal di parlemen Belanda menandakan
sebuah haluan politik baru yang akan diterapkan di Hindia-Belanda, yaitu politik
liberal.
Pergelutan antara kaum konservatif dengan kaum liberal sebenarnya telah
berlangsung lama. Bahkan, beberapa gubernur-jenderal di Hindia-Belanda pernah
mencoba untuk menerapkan politik liberal pada masa-masa pemerintahan mereka.
Adapun para gubernur-jenderal tersebut antara lain ialah; Daendels (1808-1816)
dan Raffles (1811-1816). Kedua penguasa ini dikenal memperjuangkan hak
perseorangan, baik dalam hal kepemilikan tanah, penggunaan hasil tanam,
maupun dalam hal hukum dan keadilan. Berbagai upaya dilakukan Daendels
dalam mewujudkan idealismenya, tetapi tidak semua idenya dapat terwujud. Hal
ini karena desakan keadaan dimana pada waktu itu Belanda harus berusaha keras
mempertahankan Jawa dari ancaman Inggris. Namun, pada akhinya Jawa tetap
jatuh ke tangan Inggris.
Di bawah kekuasaan Raffles (1811-1816), berbagai upaya pembaharuan
yang juga berdasarkan pada idealisme liberal banyak dilakukan. Salah satunya
yang terkenal adalah sistem pemungutan sewa tanah. Sistem pemungutan sewa
tanah milik Raffles ini bertujuan memperbaiki sistem paksa peninggalan VOC