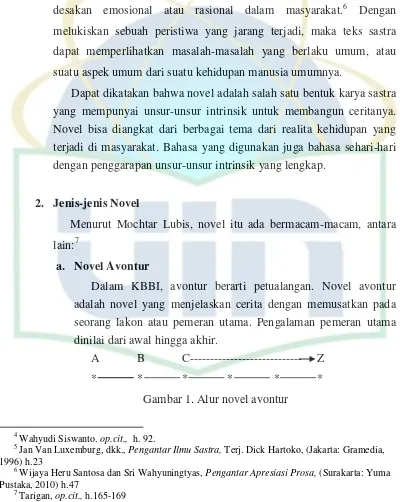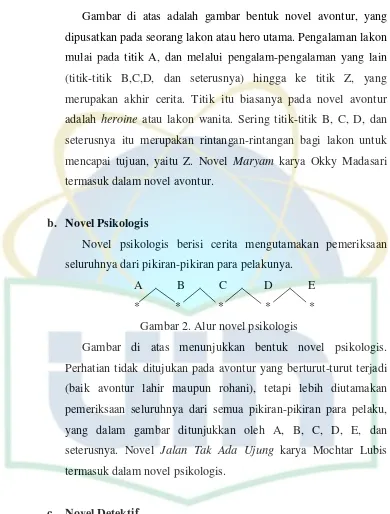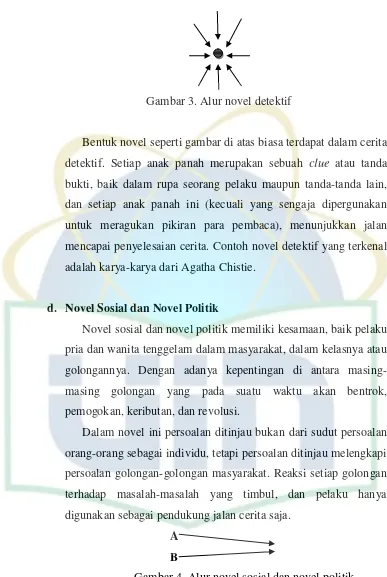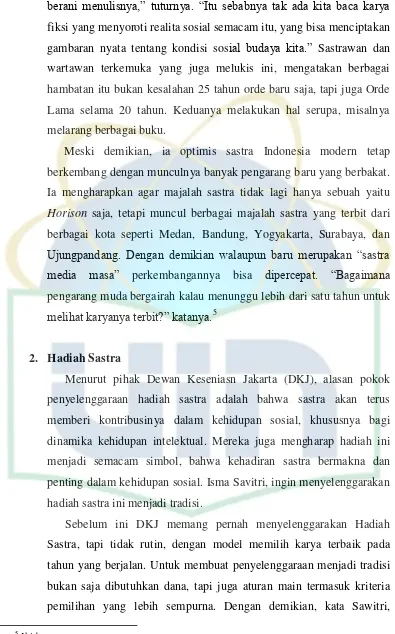SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
Skripsi
Diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.)
Oleh
Hardiyani Windari 1111013000084
JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
KARYA MOCHTAR, LTJBIS SERTA IMPLIKA,ST}IYA TERIIADAP PEMBEI,AJARAN APRESIASI SASTRA DI
SEKOLAII MENENGAE ATAS (SMA)
Skripsi
Diajukan kepada Fakultas Ilmu Tmbiyah dan Keguruan
untuk lvIerlen&hi Persyaratan Memperoleh Gelar Ssrlarn Peadidika$ (S,Pd.)
Oleh
Hardivani Wi*dari
I\rIM. 1111013000084
JURUS$I PENDIDIKAI\I BAIIASA DAI\I SASTRA INDOFTESIA
FAKULTAS ILMU TARBTYAH DAN KEGURUAN UIN SYARIT IIIDAYATI]LL"A,II
JAKARTA
2015 Mengetahui,
Dosen Pemlfmhing
A
/l
/
,.4/'l\
/
[c,
1111013000084, diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta dan telah dinyatakan lulus dalam ujian Munaqosah pada
tanggal 12 Oktober 2075, di hadapan dewan penguji. Oleh karena itu, penulis
berhak memperoleh gelar Sarjana S-1 (S.Pd.) dalam bidang Pendidikan Bahasa dan
Sastra Indonesia.
Jakarta, l2 Oktober 2015
Panitia Ujian Munaqosah
Ketua Panitia (Ketua Jurusan/Prodi)
Makyun Subuki. M.Hum. NIP. 19800305 200901 I 015
Sekretaris (Sekretaris Jurusan/Prodi)
Dona Aii Karunia Putra. M.A.
NIP. 19840409 20110l 1 015
Penguji I
Novi Diah Haryanti. M.Hum.
NIP. 19841t26 20t503 2 007
Penguji II
Rosida Erowati, M.Hum.
NIP. 19771030 200801 2 009
Tanggal Tanda Tangan
l%-"
l\:v^i
0,,#'
e*l
qol( lto23/,o
us
rflnout
'. t. "'...'..
Saya yang bertanda tan
Nama
Tempat/Tgl.Lahir NIM
Jurusan / Prodi
Judul Skripsi
gan di bawah ini, Hardiyani Windari
Tangerang/O4 September I 993
I l l r013000084
Pendidikan Bahasa dan Sasta Indonesia
Analisis Latar dalam Novel Jalan Tak Ada Ujung Karya Mochtar Lubis serta Implikasinya terhadap Pembelajaran
Apresiasi Sasta di SekolahMenengah Atas (SMA)
Dosen Pembimbing : Ahmad Bahtiar, M.Hum.
Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat benar-benar hasil karya sendiri
dan saya bertanggung jawab secara akademis atas apa yang saya tulis.
Pemyataan ini dibuat sebagai salah satu syarat menempuh Ujian Munaqasah.
Tak Ada Ujung Karya Mochtar Lubis Serta Implikasinya terhadap Pembelajaran
Apresiasi Sastra di Sekolah Menengah Atas”. Jurusan Pendidikan Bahasa dan
Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015. Pembimbing: Ahmad Bahtiar, M.Hum.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan latar yang tergambar
dalam novel Jalan Tak Ada Ujung karya Mochtar Lubis dengan melakukan
analisis objektif dan implikasinya terhadap pembelajaran sastra di sekolah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam analisis
novel Jalan Tak Ada Ujung adalah pendekatan objektif dengan tinjauan sosiologi
sastra. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar bukan saja mengenai tempat, waktu dan keadaan sosial di dalam novel. Tetapi latar juga berkaitan dengan karakter tokoh di dalam cerita, latar berkaitan dengan waktu peristiwa dan dalan
novel Jalan Tak Ada Ujung memiliki latar sosial tentang keadaan ekonomi dan
juga kondisi politik. Ditinjau dengan sosiologi sastra terdapat relevansi dengan peristiwa di luar karya sastra yang merupakan refleksi dari peristiwa yang terjadi
pada masa novel Jalan Tak Ada Ujung dibuat. Melalui penelitian ini peserta didik
akan mengetahui bahwa dalam memahami sebuah novel, latar dapat menciptakan setiap kemunculan peristiwa yang terdapat pada cerita dalam novel. Penelitian tentang analisis latar dapat diimplikasikan dalam pembelajaran apresiasi sastra di Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagai upaya memberikan pengetahuan lebih mendalam terhadap latar dalam materi analisis unsur intrinsik.
the road with no end by Mochtar Lubis as well as implications for Literary appreciation of Learning in Senior High School". The Department of Language and Indonesian Literature Education, Faculty of Tarbiya and Teacher Sciences. State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015. Mentor: Ahmad Bahtiar, M. Hum.
This study aims to describe the setting reflected in the novel A Road with
No End novel by Mochtar Lubis did an analysis of the objective and the implications for learning literature in school. The methods used in this research is descriptive, qualitative approach. While the approach used in the analysis of the
novel A Road with No End is an objective approach with literaty sociology study.
Based on the results of the research that has been done, it was found that the setting is not just about place, time and social circumstances in the novel. But also with regard to the character of the character in the story, the setting related to
time and events in the novel A Road with No End of social setting about economy
and also political conditions. Reviewed by sociology of literature there is relevance to the events outside of literary works that are a reflection of events
taking place during the novel A Road with No End is created. Through these
studies the learners will know in understanding a novel, the setting can create each occurrence of the events in the story in the novel. Research about analysis setting can be implied in a literary appreciation of learning in Senior High School in an effort to give more in-depth knowledge against the setting of the intrinsic elements of the analysis in the material.
Maha Kuasa akan segala sesuatu, pencipta segala yang dikehendaki-Nya dan
pemberi rahmat serta karunia, sehingga proses penulisan skripsi ini dapat
terselesaikan. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah Swt. limpahkan kepada
Nabi Muhammad saw., keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir
zaman.
Ide penulisan skripsi ini berawal dari mata kuliah “sejarah sastra” saat
membahas tentang novel Jalan Tak Ada Ujung yang digunakan penulis sebagai
tugas akhir semester, dari situlah penulis berusaha mendalami kembali dengan
menganalisis novel tersebut. Akhirnya dalam pencarian, penulis menemukan
bahasan tentang latar yang terdapat dalam novel. Proses penyusunan skripsi ini
menggunakan beberapa kajian. Kajian-kajian tersebut digunakan sebagai alat
untuk menganalisis novel Jalan Tak Ada Ujung dengan asumsi bahwa adanya
keterkaitan latar dengan unsur intrinsik lainnya dalam novel dan karya sastra tidak
lepas dari konteks sosialnya. Skripsi berjudul “Analisis Latar dalam Novel Jalan
Tak Ada Ujung Karya Mochtar Lubis serta Implikasinya terhadap Pembelajaran Apresiasi Sastra di Sekolah Menengah Atas” ini merupakan tugas akhir yang
harus dipenuhi untuk mencapai gelar Sarjana.
Dalam pengerjaan skripsi ini, penulis tidak dapat terlepas dari bantuan,
bimbingan dan dukungan pribadi-pribadi yang senantiasa mendampingi dan
membimbing dalam proses penyelesaian skripsi sebagai tugas akhir menempuh
Strata satu.
Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:
1. Prof. Dr. Ahmad Thib Raya, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan
3. Ahmad Bahtiar, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan
bimbingan dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
4. Dosen-dosen Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang dengan
senang hati membagi ilmu dan memberikan arahan kepada penulis selama
penyusunan skripsi.
5. Bapak Harno dan Ibu Sri Winda, orangtuaku tercinta, yang selalu menguatkan
hati dan pikiran ketika lemah dan lelah, yang tak hentinya memberikan kasih
sayang, perhatian, pengertian, motivasi, semangat, serta doa untuk setiap
langkah penulis dalam menuntut ilmu dan menyelesaikan skripsi. Terimakasih
yang tak terhingga untuk mereka.
6. Dhandi Laksono, Haris Tri Suseto dan Bayu Adji Ramadhan, adik-adikku
tersayang terima kasih atas waktu canda dan tawa ketika rasa penat
menghampiri.
7. Said Kurniawan, S.Kom., yang selalu memberikan perhatian, dukungan, doa
dan juga meluangkan waktunya untuk membantu penulis hingga
terselesaikannya skripsi ini.
8. Risma Nurpadilah dan Aprilia Dwi Permatasari, sahabat yang selalu
meluangkan waktu, teman berbagi keluh kesah terima kasih atas saran,
dukungan dan doa kalian.
9. Sahabat-sahabat tercinta dan seperjuangan Widiyowati Tria Rani Astuti, Rifqi
Faizah, Amanah Ari Rachmanita, Aminah Ratna Ningsih, Silviani Marlinda
dan Hadiyati Wulan Dani yang telah meluangkan waktu untuk saling
mendoakan dan saling membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Teman-teman mahasiswa Jurusan PBSI, khususnya kelas C angkatan 2011
kemudahan bagi kita semua. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi
penulis dan umumnya bagi pembaca, serta dapat memberikan sumbangsih bagi
khazanah ilmu pengetahuan.
Jakarta, 04 September 2015
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
ABSTRAK ... i
ABSTRACT.. ... ii
KATA PENGANTAR.. ... iii
DAFTAR ISI.. ... vi
DAFTAR GAMBAR... ... viii
DAFTAR LAMPIRAN ... ix
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ... 1
B. Identitas Masalah…. ... 5
C. Pembatasan Masalah ... 6
D. Perumusan Masalah ... 6
E. Tujuan Penulisan ... 6
F. Manfaat Penelitian ... 7
G. Metode Penelitian... 8
1. Sumber Data/Objek Penelitian. ... 9
2. Teknik Pengumpulan Data. ... 9
3. Teknik Analisis Data. ... 9
BAB II KAJIAN TEORI A. Novel ... 11
1. Pengertian Novel ... 11
2. Jenis-jenis Novel. ... 12
3. Unsur-unsur Intrinsik Novel… ... 16
4. Unsur Ekstrinsik Novel. ... 24
5. Sosiologi Sastra. ... 25
C. Pemikiran Mochtar Lubis ... 32
D. Pembicaraan Beberapa Karya Mochtar Lubis... 35
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN A. Sinopsis Novel Jalan Tak Ada Ujung. ... 38
B. Analisis Objektif Novel Jalan Tak Ada Ujung. ... 40
1. Tema.. ... 40
2. Alur... 41
3. Tokoh dan Penokohan ... 48
4. Latar ... 57
5. Sudut Pandang ... 71
6. Gaya Bahasa. ... 72
7. Amanat. ... 73
C. Analisis Latar dalam Novel Jalan Tak Ada Ujung ... 74
1. Hubungan dengan Tema... 74
2. Hubungan Penokohan ... 75
3. Hubungan Waktu Peristiwa ... 79
4. Hubungan dengan Kondisi Sosial Ekonomi... 81
5. Hubungan dengan Sosial Politik ... 83
D. Implikasi Terhadap Pembelajaran Apresiasi Sastra di Sekolah ... 85
BAB V PENUTUP A.Simpulan ... 89
B. Saran ... 90
Gambar 3 Alur Novel Detektif
Gambar 4 Alur Novel Sosial dan Novel Politik
Lampiran 2 Surat Bimbingan Skripsi
Lampiran 3 Surat Pernyataan Uji Referensi
Lampiran 4 Daftar Uji Referensi
A. Latar Belakang
Sastra harus dipandang dalam hubungan yang tak terpisahkan
dengan kehidupan masyarakat, latar belakang unsur sejarah dan sosial
yang mempengaruhi pengarang.1Karya sastra merupakan suatu cerminan
atau gambaran keadaan yang terjadi di masyarakat. Seorang pengarang
membuat karya sastra karena ia menangkap keadaan di masyarakat.
Masyarakat dan kehidupannya ini dijadikan suatu sumber data untuk
penulisan karya sastra. Realita yang ada dalam masyarakat diangkat dan
diceritakan dalam sebuah karya sastra.
Proses penciptaan (produksi karya sastra) serta penyebaran dan
penggandaannya sastra melibatkan berbagai macam pihak. Pencipta karya
sastra, yakni pengarang, berdasarkan kreativitas, imajinasi, dan kerjanya
menuliskan atau menciptakan suatu karya. Bagi banyak orang, karya sastra
menjadi sarana untuk menyampaikan pesan tentang kebenaran, tentang apa
yang baik dan buruk. Ada pesan yang sangat jelas disampaikan, ada pula
yang bersifat tersirat secara halus. Karya sastra juga dapat dipakai untuk
menggambarkan apa yang ditangkap sang pengarang tentang kehidupan di
sekitarnya. Sastra merupakan media komunikasi, yang melibatkan tiga
komponen, yakni pengarang sebagai pengirim pesan, karya sastra sebagai
pesan itu sendiri, dan penerima pesan yakni pembaca karya sastra maupun
pembaca yang tersirat dalam teks atau yang dibayangkan oleh
pengarangnya.
Unsur intrinsik sebuah novel adalah unsur-unsur yang secara
langsung turut serta membangun cerita. Unsur yang dimaksud, misalnya
peristiwa, cerita, plot, penokohan, tema, latar, sudut pandang penceritaan,
bahasa atau gaya bahasa, dan lain-lain.
1
Robert Escarpit, Sosiologi Sastra, terj. Ida Sundari Husen, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,
Latar menunjukkan pada tempat, yaitu lokasi di mana cerita itu
terjadi, waktu, kapan cerita itu terjadi dan lingkungan sosial-budaya,
keadaan kehidupan bermasyarakat tempat tokoh dan peristiwa terjadi.
Sebagaimana dikemukakan di atas, latar terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu
tempat, waktu dan lingkungan sosial-budaya. Latar yang berisi tentang
sejarah Indonesia terdapat dalam kumpulan cerita pendek karya Idrus yang
berjudul Dari Ave Maria Ke Jalan Lain Ke Roma. Dalam kumpulan cerita
pendek tersebut terdapat 2 latar waktu yang berbeda masa, yaitu masa
masa penjajahan Jepang dan setelah kemerdekaan.
Salah satu novel yang menarik latarnya adalah novel Jalan Tak
Ada Ujung karya Mochtar Lubis yang juga berisi tentang sejarah
Indonesia. Latar atau setting dalam novel tersebut menggambarkan
keadaan sosial masyarakat Indonesia pada tahun 1946-1947 yang
mencakup latar fisik yaitu latar tempat dan waktu yang berlatarkan
pascakemerdekaan, juga terdapat di dalamnya yaitu latar sosial saat
terjadinya revolusi. Mochtar Lubis menangkap apa yang terjadi pada masa
itu. Ketika itu Indonesia yang sudah merdeka karena kedatangan sekutu
yang membuat Jepang menyerah. Kedatangan sekutu disambut dengan
sikap netral oleh pihak Indonesia, karena diketahui bahwa tugas sekutu
hanyalah untuk membebaskan tawanan perang serta melucuti pasukan
Jepang. Akan tetapi, setelah diketahui bahwa dalam pasukan sekutu
terdapat serdadu Belanda dan aparat Netherland Indies Civil
Administration (NICA) yang terang-terangan bermaksud menegakkan
kembali pemerintah Hindia Belanda.2 Kedatangan sekutu yang diikuti
dengan Belanda atau NICA mempengaruhi kondisi sosial budaya,
ekonomi, politik, dan pendidikan di Indonesia. Pasukan Belanda
bersenjata tank, dibantu oleh pasukan udara yang kuat, langsung
menyusup ke dalam wilayah Republik Indonesia. Dalam dua minggu,
Belanda berhasil menguasai hampir semua kota besar dan kota-kota
penting di Jawa Barat dan Jawa Timur.3
2
Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia VI.
(Jakarta: Balai Pustaka, 2008) h.186
3
George McTurnan Kahin. Nasionalisme dan Revolusi Indonesia, terj. Tim Komunitas Bambu
Pada karya Mochtar Lubis yang berjudul Jalan Tak Ada Ujung,
penulis mengkaji analisis latar (setting) dalam novel tersebut dengan
menggunakan tinjauan sosiologi sastra. Dengan latar (setting) dalam novel
tersebut, Mochtar Lubis ingin menceritakan tentang apa yang terjadi di
Indonesia pada masa setelah proklamasi. Melalui karya sastra yang dibuat
dengan latar cerita tentang pascakemerdekaan bangsa Indonesia akan
memberikan pengetahuan lebih kepada pembaca, tentang fakta yang
disampaikan melalui karya sastra.
Terkait analisis novel Jalan Tak Ada Ujung karya Mochtar Lubis
yang pernah dilakukan sebelumnya, terdapat tesis dan skripsi yang
menjadikan novel JTAU karya Mochtar Lubis sebagai objek penelitian.
Dengan judul “Pandangan Kemanusiaan Mochtar Lubis”, “Tinjauan Psikologis Tokoh”, dan “Patriotisme dalam Novel JTAU”.4 Terdapat jurnal
yang menganalisis novel Jalan Tak Ada Ujung karya Mochtar Lubis.
Jurnal tersebut menganalisa pola struktur cerita dari Jalan Tak Ada Ujung
karya Mochtar Lubis. Dari sisi struktur ceritanya, plot dari JTAU dan
kesatuan maknanya dihasilkan dengan menghubungkan bagian peristiwa,
orang dan latar belakang secara dekat. Makna kehidupan diinterpretasikan
Guru Isa sebagai ketakutan yang amat sangat dapat mengembangkan
makna lebih lanjut dan selanjutnya menghadirkan makna kehidupan
merusak pikiran.5
Sastra mempunyai relevansi dengan masalah-masalah dunia nyata,
maka pengajaran sastra harus dipandang sebagai sesuatu yang penting yang patut menduduki tempat yang selayaknya. Pengajaran sastra jika
dilakukan dengan cara yang tepat, maka pengajaran sastra dapat juga
memberikan sumbangan terhadap keberhasilan dalam proses belajar dan
mengajar. 6 Hal ini juga berhubungan dengan konsep Horace tentang
dulce dan utile, yakni bahwa sastra itu indah dan bermanfaat. Maka dalam hal ini, sastra dapat berguna untuk mengajarkan sesuatu, yaitu melalui
pendidikan sastra khususnya di mata pelajaran Bahasa dan Sastra
Indonesia di sekolah.
4Tesis, Agus R. Sarjono, “Citra Rumah dalam Novel Jalan Tak Ada Ujung
Mochtar Lubis dan
Keluarga Gerilya Pramoedya Ananta Toer” Program Studi Ilmu Susastra, Universitas Indonesia,
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. 2002. Selanjutnya mengenai Judul Skripsi lainnya terdapat dalam BAB II pada penelitian relevan.
5
Charles Butar-butar, Analisis Struktur pada Novel Jalan Tak Ada Ujung karya Mochtar
Lubis, Indonesia Scientific Journal Database, 6, 2008, h.338
6
Masalah penting yang sering dihadapi guru dalam kegiatan
pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia adalah memilih atau
menentukan bahan pembelajaran yang tepat dalam rangka membantu
siswa mencapai kompetensi yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh
kenyataan bahwa dalam kurikulum atau silabus, bahan pembelajaran
hanya ditulis secara garis besar dalam materi pokok. Dalam kompetensi
tersebut, siswa diharapkan dapat mengembangkan potensinya sesuai
dengan kemampuan, kebutuhan dan minatnya.7 Tugas gurulah untuk
menjabarkan materi pokok tersebut sehingga menjadi bahan pembelajaran
yang lengkap.
Selama ini guru mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di
Sekolah Menengah Atas (SMA) cenderung menggunakan teknik atau
metode pembelajaran secara teoretik dan monoton sehingga menimbulkan
kebosanan dan ketidaktertarikan siswa untuk belajar mata pelajaran ini.
Padahal dari pembelajaran Apresiasi Sastra Indonesia ini guru diharapkan
bisa lebih mengeksplorasikan cara pengajarannya untuk lebih
mengenalkan siswa kepada sejarah tentang Indonesia yang di ceritakan
melalui karya sastra. Oleh karena itu, siswa dituntut berpikir kritis dan
menggunakan imajinasinya dalam usaha menganalisis karya sastra dan
mengapresiasi sastra.
Selain hanya teori, siswa juga harus memiliki pengalaman sastra,
misalnya dengan membaca karya sastra atau membuat karya sastra.
Sebagai contoh, untuk memperoleh teori tentang unsur-unsur dalam novel
atau karya sastra lain, seorang guru harus memperkenalkan novel tersebut
dengan cara mengkaji dan mengapresiasinya. Dalam sastra dimanfaatkan
antara realitas sejarah dengan rekaan. Fungsinya adalah mempertegas
kebenaran dan ketepatan isi cerita seluruhnya dalam rangka membawa
message (pesan) teksnya.8 Dengan mengajak siswa untuk mengapresiasi karya sastra dapat juga memberikan pengetahuan baru bahwa peristiwa
7
Depdiknas, Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, (Jakarta: Badan
Standar Nasional Pendidikan, 2006), h. 107.
8
yang terjadi dalam kehidupan nyata dapat pula tergambarkan melalui
karya sastra, dalam hal ini adalah novel.
Maka dari penjabaran tersebut, penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul penelitian “Analisis Latar dalam Novel Jalan Tak
Ada Ujung Karya Mochtar Lubis serta Implikasinya terhadap
Pembelajaran Apresiasi Sastra di Sekolah Menengah Atas”. Tinjauan
sosiologi sastra digunakan untuk mengkaitkan kondisi keadaan di luar
karya sastra dengan apa yang diceritakan dalam novel. Diharapkan dalam
pembelajaran Bahasa Indonesia dalam materi apresiasi sastra tidak hanya
memberikan pengetahuan tentang unsur-unsur yang terdapat dalam novel,
melainkan dapat juga mengkaitkan sejarah dengan cerita dalam novel
Jalan Tak Ada Ujung karya Mochtar Lubis.
B. Identifikasi Masalah
Sesuai dengan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada
latar yang tergambarkan dalam cerita pada novel Jalan Tak Ada Ujung
karya Mochtar Lubis yang menggambarkan Indonesia di tahun 1946-1947
atau tepatnya saat Indonesia pascakemerdekaan.
1. Belum adanya analisis novel Jalan Tak Ada Ujung karya Mochtar
Lubis terkait latar fisik maupun latar sosial Indonesia
pascakemerdekaan.
2. Belum adanya analisis karya sastra mengenai perjuangan
pergerakan nasional bangsa Indonesia yang tergambarkan dalam
latar (setting) yang terdapat dalam novel Jalan Tak Ada Ujung
karya Mochtar Lubis.
3. Kurangnya metode yang dilakukan guru dalam materi
pembelajaran apresiasi sastra dalam pelajaran Bahasa Indonesia di
Sekolah Menengah Atas (SMA).
4. Kurangnya bahan pembelajaran apresiasi sastra Indonesia di
C. Pembatasan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah,
pembatasan masalah pada penelitian ini adalah, penulis mengkaji dan
memaparkan “Analisis Latar dalam Novel Jalan Tak Ada Ujung Karya
Mochtar Lubis serta Implikasinya terhadap Pembelajaran Apresiasi Sastra di SMA”
D. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan
masalah seperti telah diuraikan di atas maka diperlukan suatu perumusan
masalah dalam penelitian ini, adapun perumusan masalahnya sebagai
berikut:
1. Bagaimana latar yang tergambarkan dalam novel Jalan Tak Ada
Ujung karya Mochtar Lubis?
2. Bagaimana implikasi novel Jalan Tak Ada Ujung karya Mochtar
Lubisterhadap pembelajaran Apresiasi Sastra Indonesia di SMA?
E. Tujuan Penulisan
Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan
penelitian ini sebagai berikut:
1. Mendeskripsikan latar yang tergambarkan dalam novel Jalan Tak
Ada Ujung karya Mochtar Lubis.
2. Mendeskripsikan implikasi novel Jalan Tak Ada Ujung karya
Mochtar Lubis terhadap pembelajaran Apresiasi Sastra di SMA.
F. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoretis
a. Memberikan pengetahuan dalam mengkaji salah satu unsur
pembangun cerita novel yakni latar yang terdapat dalam novel
b. Memberikan pengetahuan tentang keadaan sosial dan politik zaman
pascakemerdekaan.
c. Memberikan pengetahuan mengenai hasil kajian tentang latar
dalam novel Jalan Tak Ada Ujung karya Mochtar Lubis yang dapat
dimanfaatkan sebagai bahan pembelajaran apresiasi sastra di
Sekolah Menengah Atas (SMA).
2. Manfaat Praktis
a. Siswa SMA, dengan adanya pembelajaran karya sastra diharapkan
meningkatkan kemampuan siswa untuk menganalisis sebuah karya
sastra yang berhubungan dengan keadaan sosial di luar karya sastra
tersebut.
b. Diharapkan penelitian ini juga berguna bagi para peneliti lain yang
ingin melakukan penelitian dengan tema yang sejenis.
c. Dapat dimanfaatkan oleh guru sebagai alternatif bahan
pembelajaran apresiasi sastra di sekolah/madrasah, untuk
meningkatkan kemampuan apresiasi siswa dalam pembelajaran
sastra. Terutama dalam mengapresiasi sebuah karya yang diangkat
berdasarkan sejarah yang terjadi di Indonesia dan dapat menambah
pengetahuan bagi siswa.
d. Dapat menambah pengetahuan pembaca tentang kesusastraan
pascakemerdekaan.
G. Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau
lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian
pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. Sedangkan deskripsi yaitu berupa
kata-kata, gambar dan bukan angka-angka.9
Metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu prosedur yang menggunakan
data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari objek yang diamati.
Dalam hal ini objek yang diamati adalah novel Jalan Tak Ada Ujung karya
Mochtar Lubis dan implikasinya terhadap pembelajaran apresiasi sastra di
SMA.
Metode ini dimaksud untuk memberikan gambaran, analisis dan
penjabaran secara objektif agar dapat mengungkapkan hubungan antar
unsur-unsur cerita di dalam teks dan dapat menggambarkan sejarah
Indonesia yang terkandung di dalamnya. Metode ini digunakan untuk
menggambarkan hal-hal faktual yang terdapat dalam karya sastra sehingga
pembaca mendapatkan gambaran yang jelas mengenai sejarah Indonesia
yang terkandung dalam latar pada novel Jalan Tak Ada Ujung karya
Mochtar Lubis.
Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis novel ini adalah
pendekatan objektif lalu juga ditinjau berdasarkan sosiologi sastra yang
penelitiannya dipusatkan kepada keterkaitan dengan yang terjadi di luar
karya sastra. Lalu jenis penelitian yang akan peneliti pergunakan adalah
penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan adalah
serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data
pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.
Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan pendekatan
sosiologi sastra dengan menghubungkan cerita dalam novel Jalan Tak Ada
Ujung dengan keadaan sosial, yakni pergerakan perjuangan yang tergambar pada latar cerita dalam novel tersebut dan latar kejadian pada
cerita dalam novel, yaitu pada zaman pascakemerdekaan Indonesia
1946-1947.
9
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2009) h.
1. Sumber Data/Objek Penelitian
a. Data Primer
Data penelitian ini bersumber pada novel Jalan Tak Ada
Ujung karya Mochtar Lubis diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia dan merupakan cetakan kelima pada 2002.
b. Data Sekunder
Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh
secara tidak langsung atau lewat perantara, tetapi masih berdasar
pada kategori konsep yang akan dibahas. Sumber data sekunder
yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari karya tulis
ilmiah, buku-buku, dan juga artikel dari koran.
2. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling
utama dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah
untuk mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang
dilakukan oleh peneliti adalah dengan membaca teks sastra dalam
hal ini novel Jalan Tak Ada Ujung karya Mochtar Lubis kemudian
menyimak secara seksama untuk pada akhirnya peneliti melakukan
pencatatan. Langkah berikutnya penelitian kepustakaan berkenaan
dengan kajian latar (setting) dalam novel.
3. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data adalah suatu cara yang digunakan untuk
menguraikan keterangan-keterangan atau data-data yang diperoleh
agar data-data tersebut dapat dipahami bukan saja oleh peneliti,
tetapi juga oleh orang lain yang ingin mengetahui hasil penelitian
itu.
Setelah data terkumpul, lalu dianalisis berdasarkan pendekatan
sosiologi sastra untuk mengungkapkan pokok masalah yang diteliti
Metode penulisan yang dipakai adalah analisis teks dengan awal
penulisan dimulai mengenai pembahasan secara intrinsik tentang
cerita tersebut untuk melihat secara lebih jelas
permasalahan-permasalahan yang timbul dalam cerita serta
pendukung-pendukung isi penceritaan berupa penokohan, alur, latar, tema dan
gaya bahasa. Setelah itu, dilanjutkan dengan pembahasan mengenai
unsur intrinsik lebih mendalam tentang latar dari cerita tersebut
dengan keadaan yang relevan berdasarkan latar dalam cerita pada
A. Novel
Dalam pembicaraan karya sastra rekaan atau imajinasi kita dapat
membaginya menjadi tiga bagian, yakni fiksi, puisi, dan drama. Orang
sering menggolongkan hasil-hasil sastra menjadi prosa dan puisi.
Termasuk prosa di dalamnya adalah novel, cerita pendek, dan esai.
1. Pengertian Novel
Kata novel berasal dari kata Latin novellus yang diturunkan pula
dari kata novies yang berarti “baru”. Dikatakan baru karena bila
dibandingkan dengan jenis-jenis sastra lainnya seperti puisi, drama,
dan lain-lain, maka jenis novel ini muncul kemudian.1 Novel
merupakan suatu bentuk karya sastra. Novel atau prosa rekaan adalah
kisahan atau cerita yang diemban oleh pelaku-pelaku tertentu, dengan
peranan, latar serta tahapan dalam rangkaian cerita tertentu yang
bertolak dari hasil imajinasi (dan kenyataan) sehingga menjalin suatu
cerita.2 Novel adalah suatu cerita yang fiktif dalam panjang yang
tertentu, yang melukiskan para tokoh, gerak, serta adegan kehidupan,
yang representatif dalam suatu alur atau suatu keadaan yang agak
kacau atau kusut.3
Pada hakikatnya sastra menyajikan gambaran kehidupan, dan
kehidupan itu sendiri dan sebagian besar terdiri dari kenyataan sosial
dan fenomena sosial itu bersifat konkret yang terjadi di sekeliling kita
sehari-hari. Karya sastra adalah karya yang dimaksudkan oleh
pengarang sebagai karya sastra, berwujud karya sastra, dan diterima
1
Henry Guntur Tarigan, Prinsip-Prinsip Dasar Sastra, (Bandung: Angkasa, 2011) h.167
2
Aminuddin dalam Wahyudi Siswanto, Pengantar Teori Sastra, (Jakarta: PT. Grasindo, 2008)
h. 125-126
3
oleh masyarakat sebagai karya sastra.4 Novel tidak melukiskan
kenyataan, tetapi menampilkan segala macam hubungan dan kaitan
yang kita kenal kembali, berdasarkan pengalaman kita sendiri
mengenai kenyataan. Itulah sebabnya mengapa teks novel sangat
cocok untuk melukiskan segi-segi yang khas dalam kenyataan.5
Novel adalah produk masyarakat. Novel berada di masyarakat
karena novel dibentuk oleh anggota masyarakat berdasarkan
desakan-desakan emosional atau rasional dalam masyarakat.6 Dengan
melukiskan sebuah peristiwa yang jarang terjadi, maka teks sastra
dapat memperlihatkan masalah-masalah yang berlaku umum, atau
suatu aspek umum dari suatu kehidupan manusia umumnya.
Dapat dikatakan bahwa novel adalah salah satu bentuk karya sastra
yang mempunyai unsur-unsur intrinsik untuk membangun ceritanya. Novel bisa diangkat dari berbagai tema dari realita kehidupan yang
terjadi di masyarakat. Bahasa yang digunakan juga bahasa sehari-hari
dengan penggarapan unsur-unsur intrinsik yang lengkap.
2. Jenis-jenis Novel
Menurut Mochtar Lubis, novel itu ada bermacam-macam, antara
lain:7
a. Novel Avontur
Dalam KBBI, avontur berarti petualangan. Novel avontur
adalah novel yang menjelaskan cerita dengan memusatkan pada
seorang lakon atau pemeran utama. Pengalaman pemeran utama
dinilai dari awal hingga akhir.
A B C--- Z
[image:25.595.114.514.255.757.2]* * * * * *
Gambar 1. Alur novel avontur
4
Wahyudi Siswanto. op.cit., h. 92.
5
Jan Van Luxemburg, dkk., Pengantar Ilmu Sastra, Terj. Dick Hartoko, (Jakarta: Gramedia,
1996) h.23
6
Wijaya Heru Santosa dan Sri Wahyuningtyas, Pengantar Apresiasi Prosa, (Surakarta: Yuma
Pustaka, 2010) h.47
7
Gambar di atas adalah gambar bentuk novel avontur, yang
dipusatkan pada seorang lakon atau hero utama. Pengalaman lakon
mulai pada titik A, dan melalui pengalam-pengalaman yang lain
(titik-titik B,C,D, dan seterusnya) hingga ke titik Z, yang
merupakan akhir cerita. Titik itu biasanya pada novel avontur
adalah heroine atau lakon wanita. Sering titik-titik B, C, D, dan
seterusnya itu merupakan rintangan-rintangan bagi lakon untuk
mencapai tujuan, yaitu Z. Novel Maryam karya Okky Madasari
termasuk dalam novel avontur.
b. Novel Psikologis
Novel psikologis berisi cerita mengutamakan pemeriksaan
seluruhnya dari pikiran-pikiran para pelakunya.
A B C D E
* * * * *
Gambar 2. Alur novel psikologis
Gambar di atas menunjukkan bentuk novel psikologis.
Perhatian tidak ditujukan pada avontur yang berturut-turut terjadi
(baik avontur lahir maupun rohani), tetapi lebih diutamakan
pemeriksaan seluruhnya dari semua pikiran-pikiran para pelaku,
yang dalam gambar ditunjukkan oleh A, B, C, D, E, dan
seterusnya. Novel Jalan Tak Ada Ujung karya Mochtar Lubis
termasuk dalam novel psikologis.
c. Novel Detektif
Dalam novel ini, mengungkapkan bagian-bagian cerita untuk
membongkar rahasia kejahatan dan bukti-bukti yang dijadikan
jalan untuk mencapai penyelesaian cerita. Dalam cerita
[image:26.595.123.513.125.639.2]Gambar 3. Alur novel detektif
Bentuk novel seperti gambar di atas biasa terdapat dalam cerita
detektif. Setiap anak panah merupakan sebuah clue atau tanda
bukti, baik dalam rupa seorang pelaku maupun tanda-tanda lain,
dan setiap anak panah ini (kecuali yang sengaja dipergunakan
untuk meragukan pikiran para pembaca), menunjukkan jalan
mencapai penyelesaian cerita. Contoh novel detektif yang terkenal
adalah karya-karya dari Agatha Chistie.
d. Novel Sosial dan Novel Politik
Novel sosial dan novel politik memiliki kesamaan, baik pelaku
pria dan wanita tenggelam dalam masyarakat, dalam kelasnya atau
golongannya. Dengan adanya kepentingan di antara
masing-masing golongan yang pada suatu waktu akan bentrok,
pemogokan, keributan, dan revolusi.
Dalam novel ini persoalan ditinjau bukan dari sudut persoalan
orang-orang sebagai individu, tetapi persoalan ditinjau melengkapi
persoalan golongan-golongan masyarakat. Reaksi setiap golongan
terhadap masalah-masalah yang timbul, dan pelaku hanya
digunakan sebagai pendukung jalan cerita saja.
[image:27.595.123.510.102.679.2]A B
Gambar 4. Alur novel sosial dan novel politik
Gambar di atas adalah gambar bentuk novel sosial. Kedua
garis A dan B merupakan tenaga atau kepentingan masing-masing
keributan, revolusi dan sebagainya. Novel Pulang karya Laila S. Chudori termasuk dalam novel sosial dan novel politik.
e. Novel Kolektif
Novel kolektif merupakan bentuk novel yang paling sukar dan
banyak seluk-beluknya.
Gambar 5. Alur novel kolektif
Dalam novel kolektif, individu sebagai pelaku tidak dipentingkan. Novel kolektif tidak terutama membawa “cerita”, tetapi lebih mengutamakan cerita masyarakat sebagai suatu
totalitas suatu keseluruhan. Novel seperti ini mencampuradukkan
pandangan antropologis dan sosiologis dengan cara mengarang
novel atau roman. Contohnya adalah novel Sang Pencerah karya
Akmal Nasery Basral.
3. Unsur-Unsur Intrinsik Novel
Novel yang utuh terdiri dari berbagai unsur pembentuknya.
Secara garis besar berbagai macam unsur tersebut dapat
dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu unsur intrinsik dan unsur
ekstrinsik. Kedua unsur inilah yang sering disebut para kritikus
dalam rangka mengkaji dan membicarakan novel atau karya sastra
pada umumnya.
Unsur instrinsik adalah unsur-unsur pembangun karya sastra
yang dapat ditemukan di dalam teks karya sastra itu sendiri.
Melalui unsur instrinsik dapat ditemukan informasi-informasi yang
membangun karya sastra tersebut.
a. Tokoh, Watak, dan Penokohan
Tokoh adalah pelaku yang mengemban peristiwa dalam
cerita rekaan sehingga peristiwa itu menjalin suatu cerita.
Sedangkan cara sastrawan menampilkan tokoh disebut penokohan.
Tokoh dalam karya rekaan selalu mempunyai sifat, sikap, tingkah
laku atau watak-watak tertentu. Pemberian watak pada tokoh suatu
karya oleh sastrawan disebut perwatakan.8
Watak atau karakter menurut Stanton, dibagi menjadi dua
konteks. Konteks pertama, karakter merujuk kepada
individu-individu yang muncul dalam cerita. Konteks kedua, karakter
merujuk pada percampuran dari berbagai kepentingan, keinginan,
emosi, dan prinsip moral dari individu-individu.9
b. Tema
Brooks dalam Tarigan mengatakan bahwa tema adalah
pandangan hidup tertentu atau perasaan tertentu mengenai
kehidupan atau rangkaian nilai-nilai tertentu yang membentuk atau
membangun dasar atau gagasan utama dari suatu karya sastra.10
Tema adalah ide yang mendasari suatu cerita. Tema
berperan sebagai pangkal tolak pengarang dalam memaparkan
karya rekaan yang diciptakannya. Tema merupakan kaitan
hubungan antara makna dengan tujuan pemaparan prosa rekaan
pengarangnya.11 Tema merupakan gagasan pokok yang ingin
disampaikan pengarang dalam karya sastranya. Tema biasanya
8
Siswanto, Op. Cit. h. 142
9
Robert Stanton, Teori Fiksi, terj. Sugihastuti dan Rossi Abi Al Irsyad, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2007) h.33 10
Tarigan, op. cit., h.125
11
selalu berkaitan dengan pengalaman kehidupan sosial, cinta,
ideologi, religious dan sebagainya. Dengan demikian, tema adalah
bagian dari suatu cerita yang menggambarkan kondisi emosi dan
kejiwaan pengarang yang membentuk dasar gagasan utama sebuah
cerita.
c. Alur
Alur atau Plot merupakan rangkaian peristiwa dalam suatu
cerita rekaan. Rangkaian peristiwa direka dan dijalin dengan
seksama membentuk alur yang menggerakan jalannya cerita
melalui rumitan ke arah klimaks dan selesaian. Plot atau alur
memiliki beberapa tahapan yaitu tahap pengenalan, tahap
pemunculan konflik, klimaks, peleraian dan tahap penyelesaian.12
1) Tahap Pengenalan
Tahap pengenalan adalah tahap peristiwa dalam suatu cerita
yang memperkenalkan tokoh atau latar cerita. Ciri yang
dikenalkan dari tokoh ini, misalnya nama, asal, fisik, dan
sifatnya.
2) Tahap Pemunculan Konflik
Tahap konflik adalah tikaian, ketegangan, pertentangan
antara dua kepentingan di dalam cerita rekaan. Pertentangan ini
dapat terjadi dalam diri satu tokoh, antara dua tokoh, antara
tokoh dan masyarakat atau lingkungannya, antara tokoh dan
alam, serta antara tokoh dan Tuhan.
3) Tahap Komplikasi
Bagian tengah alur atau cerita rekaan atau drama yang
mengembangkan tikaian. Dalam tahap ini konflik yang terjadi
semakin tajam karena berbagai sebab dan berbagai
kepentingan yang berbeda dari setiap tokoh.
12
4) Tahap Klimaks
Bagian alur cerita yang melukiskan puncak ketegangan,
terutama dipandang dari segi tanggapan emosional pembaca.
5) Tahap Peleraian
Pada tahap ini peristiwa-peristiwa yang terjadi
menunjukkan perkembangan ke arah penyelesaian.
6) Tahap Penyelesaian
Tahap akhir suatu cerita rekaan. Dalam tahap ini semua
masalah dapat diuraikan, kesalahpahaman dijelaskan.
d. Latar atau Setting
Latar yang dimaksud dalam karya sastra naratif adalah
tempat dan suasana lingkungan yang mewarnai peristiwa. Ke
dalamnya mencakup lokasi peristiwa dan sosial budaya
setempat. Perlu diperhatikan adalah hubungan latar dengan
peran tokoh.13 Tidak semua jenis latar cerita itu ada di dalam
cerita rekaan. Dalam cerita rekaan, mungkin saja yang
menonjol hanya latar waktu dan latar tempat. Pengambaran
latar ini ada yang secara terperinci atau ada pula yang tidak.
Hal itu semua, dilihat dari bagaimana sastrawan menciptakan
karya fiksinya.
Latar ini biasanya diwujudkan dengan menciptakan
kondisi-kondisi yang melengkapi cerita. Baik dalam dimensi waktu
maupun tempatnya, suatu latar bisa diciptakan dari tempat dan
waktu imajiner ataupun faktual. Hal yang paling menentukan
bagi keberhasilan suatu latar, selain deskripsinya, adalah
bagaimana novelis memadukan tokoh-tokohnya dengan latar di
mana mereka melakoni perannya.14
13
Atmazaki, Ilmu Sastra: Teori dan Terapan, (Padang: Angkasa Raya, 1990) h.62
14
Furqonul Aziez dan Abdul Hasim, Menganalisis Fiksi: Sebuah Pengantar, (Bogor: Ghalia
1) Hakikat Latar
Latar atau setting yang disebut juga sebagai landas tumpu,
menunjuk pada pengertian tempat, hubungan waktu sejarah,
dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa
yang diceritakan.15 Latar memberikan pijakan cerita secara
konkret dan jelas. Hal ini penting untuk memberikan kesan
realistis kepada pembaca, menciptakan suasana tertentu yang
seolah-olah sungguh-sungguh ada dan terjadi. Pembaca dapat
merasakan dan menilai kebenaran, ketepatan, dan aktualisasi
latar yang diceritakan.
2) Penekanan Unsur Latar
Penekanan latar dapat mencakup ketiga unsur sekaligus atau
hanya satu-dua unsur saja. Unsur latar yang ditekankan akan
berpengaruh terhadap elemen fiksi yang lain, khususnya alur
dan tokoh. Jika elemen tempat mendapat penekanan dalam
sebuah novel, ia akan dilengkapi dengan sifat khas keadaan
geografis setempat yang mencirikannya, yang disebut sebagai
Landmark, yang berbeda dengan tempat-tempat yang lain.16 Penekanan peranan waktu juga banyak ditemui dalam
berbagai karya fiksi di Indonesia. Elemen waktu biasanya
dikaitkan dengan peristiwa faktual, peristiwa sejarah, yang
dapat mempengaruhi pengembangan plot dan penokohan.
Peristiwa-peristiwa sejarah tertentu yang diangkat ke dalam
cerita fiksi memberikan landasan waktu secara konkret.17 Plot
dan tokoh cerita tinggal menyesuaikannya dan kadang-kadang
seolah-olah membuat tokoh menjadi tidak berdaya
menghadapinya sebab hal itu memang di luar jangkauan
pemikirannya.
15
Burhan Nurgiantoro. op. cit., h. 302
16Ibid,
h.310
17Ibid,
3) Latar dan Unsur Fiksi yang Lain
Sastra merupakan produk budaya yang menggambarkan
aktivitas sosial masyarakat yang diwakili oleh tokoh-tokohnya
dalam suatu Setting dan waktu tertentu.18
Latar dengan penokohan mempunyai hubungan yang erat
dan bersifat timbal balik. Bahkan, barangkali tidak berlebihan
jika dikatakan bahwa karakter seseorang akan dibentuk oleh
keadaan latarnya. Dapat dikatakan bahwa sifat-sifat dan
tingkah laku tertentu yang ditunjukkan oleh seorang tokoh
mencerminkan dari mana dia berasal. Tokoh akan
mencerminkan latar.19 Penokohan dan pengaluran memang
tidak hanya ditentukan oleh latar, namun setidaknya peranan
latar harus diperhitungkan.
Latar dalam kaitannya dengan hubungan waktu, akan
berpengaruh terhadap cerita dan pemlotan, khususnya waktu
yang dikaitkan dengan unsur kesejarahan. Peristiwa-peristiwa
yang diceritakan dalam sebuah novel, jika ada hubungan
dengan peristiwa sejarah, harus tidak bertentangan dengan
kenyataan sejarah itu. Hal ini penting sebab pembaca akan
menjadi sangat kritis terhadap masalah yang demikian.20
4) Unsur Latar
Latar memiliki tiga unsur pokok, yaitu tempat, waktu dan
sosial yang masing-masing menawarkan permasalahan yang
berbeda, namun ketiganya saling berkaitan dan saling
mempengaruhi. Ketiga unsur pokok tersebut sebagai berikut:21
18
Heru Kurniawan, Teori, Metode, dan Aplikasi Sosiologi Sastra, (Yogyakarta: Graha Ilmu,
2012) h. 3
19
Nurgiantoro. op.cit., h.313
20Ibid,
h.315
21Ibid,
a) Latar Fisik
Latar fisik adalah tempat dalam wujud fisik yaitu
bangunan, daerah, dan sebagiannya. Latar fisik dibagi
menjadi dua bagian yaitu latar tempat dan latar waktu.
Karena latar tempat secara jelas menunjuk pada lokasi
tertentu, yang dapat dilihat dan dirasakan kehadirannya,
disebut sebagai latar fisik. Keadaan yang agak berbeda
adalah latar yang dihubungkan dengan waktu. Latar waktu
jelas tidak dapat dilihat, namun bekas kehadirannya dapat
dilihat pada tempat-tempat tertentu berdasarkan waktu
kesejarahannya.22
(1) Latar tempat. Dalam sebuah novel, latar menyarankan
kepada lokasi terjadinya peristiwa. Tempat yang
dipergunakan biasanya menggunakan nama-nama
tertentu, inisial tertentu, juga mungkin lokasi tertentu
tanpa nama jelas.
(2) Latar waktu. Berhubungan dengan “kapan” terjadinya
peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Masalah “kapan”
dihubungkan dengan waktu faktual, waktu yang
berkaitan dengan peristiwa sejarah. Latar waktu dapat
bermakna ganda: di satu pihak menyaran pada waktu
penceritaan, waktu penulisan cerita, dan di lain pihak
menunjuk pada waktu dan urutan waktu yang terjadi
dan dikisahkan dalam cerita.
b) Latar sosial. Unsur ini menyaran pada hal-hal yang
berhubungan dengan perilaku kehidupan sosial masyarakat
di suatu tempat, berupa kebiasaan hidup, adat istiadat,
tradisi, keyakinan, pandangan hidup, cara berpikir dan
bersikap, serta keadaan sosial lainnya seperti status sosial
tokoh yang bersangkutan, misalnya rendah, menengah atau
atas.
22Ibid,
e. Sudut Pandang
Sudut pandang adalah tempat sastrawan memandang
ceritanya. Dari tempat itulah sastrawan bercerita tentang tokoh,
peristiwa, tempat, waktu dan gayanya sendiri.23
Sudut pandang memiliki tipe tersendiri sesuai dengan
tujuannya, tipe-tipe sudut pandang tersebut, yaitu:24
1) Orang Pertama-utama, yaitu sang karakter utama bercerita
dengan kata-katanya sendiri.
2) Orang Pertama-sampingan, adalah cerita dituturkan oleh
satu karakter bukan utama (sampingan)
3) Orang Ketiga-terbatas, yaitu dengan cara pengarang
mengacu pada semua karakter dan memosisikannya sebagai
orang ketiga tetapi hanya menggambarkan apa yang dapat
dilihat, didengar, dan dipikirkan oleh satu orang karakter
saja.
4) Orang Ketiga-tidak terbatas, pengarang mengacu kepada
setiap karakter dan memosisikannya sebagai orang ketiga
dengan begitu pengarang juga dapat membuat beberapa
karakter, seperti melihat mendengar atau berpikir.
f. Gaya Bahasa
Gaya bahasa adalah cara seorang pengarang menyampaikan
gagasannya dengan menggunakan media bahasa yang indah
yang mampu menuansakan makna dan suasana yang dapat
menyentuh emosi pembaca.25
23
Siswanto, op.cit., h.151
24
Stanton, op.cit., h.53-54
25
g. Amanat
Amanat adalah pesan atau nasihat merupakan kesan yang
ditangkap pembaca setelah membacanya.26 Saat
mengungkapkan masalah apa yang terjadi kehidupan dan
kemanusiaan lewat karya prosanya, pengarang berusaha
memahami secara dalam keseluruhan masalah itu secara
internal yang dihubungkannya dengan keberadaan suatu
individu maupun dalam hubungan antara individu dengan
kelompok masyarakatnya.
4. Unsur Ekstrinsik Novel
Unsur berikutnya dalam pembangun sebuah novel adalah unsur
ekstrinsik. Sebagai mana dikatakan Burhan, bahwa unsur ekstrinsik
merupakan sebuah unsur yang berada di luar bagian dari karya sastra
tetapi mempengaruhi bangunan cerita sebuah karya sastra.27 Seperti
latar belakang atau biografi pengarang dan situasi atau kondisi
sosial-budaya yang mempengaruhi.
Meskipun unsur ekstrinsik berada di luar karya sastra bukan berarti
tidak penting, karena unsur itulah yang sangat berpengaruh terhadap
totalitas cerita yang dihasilkan. Karya sastra memang pada umumnya
lebih peka terhadap persoalan sosial suatu masyarakat pada suatu masa
tertentu, sebab ada keleluasaan untuk menggunakan bahasa dan kata
untuk melukiskan, menguraikan, dan menafsirkan lewat adegan,
situasi, dan tokoh-tokoh yang bermacam ragam watak dan latar
belakangnya. 28 Unsur-unsur itu pulalah yang berpengaruh besar
terhadap cerita yang dihasilkan dan dengan adanya unsur ekstrinsik
maka dalam karya tersebut akan dapat terungkap cara pengarang dalam
menangkap situasi sosial yang terjadi pada zamannya. Dari pengertian
tersebut dapat dikatakan bahwa novel merupakan cerita rekaan yang
26
Ibid., h.62
27
Nurgiantoro, op.cit., h.23
28
menyajikan tentang aspek kehidupan manusia. Novel juga tidak hanya
dikatakan sebagai alat hiburan, tetapi juga sebagai bentuk dari
segi-segi kehidupan serta nilai-nilai yang terkandung di dalam kehidupan
masyarakat. Dalam sebuah novel, si pengarang berusaha semaksimal
mungkin untuk mengarahkan pembaca kepada gambaran-gambaran
realita kehidupan melalui cerita yang terkandung dalam novel tersebut.
Hal tersebut dapat dikatakan sebagai bagian dari unsur ekstrinsik dari
sebuah novel.
5. Sosiologi Sastra
Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi sastra untuk
mengkaji novel yang akan diteliti, maka dari itu perlu dijelaskan
mengenai sosiologi sastra.
Terlebih dahulu akan dibahas pengertian dari sosiologi. Secara
etimologi kata sosiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu sosio/socius
(yang berarti bersama-sama, bersatu, kawan, teman, masyarakat) dan
logi/logos (bersabda, perkataan, perumpamaan). Jadi, sosiologi merupakan ilmu mengenai asal-usul dan pertumbuhan masyarakat atau
ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan antar manusia dalam
masyarakat yang bersifat umum, rasional dan empiris.29
Sedangkan kata sastra berasal dari akar kata sas (Sansekerta) yang
berarti mengarahkan, mengajar, memberi petunjuk dan instruksi.
Akhiran tra yang berarti latar atau sasaran. Jadi, sastra merupakan
kumpulan atal untuk mengajar, atau dengan kata lain, sastra sebagai
buku petunjuk juga sebagai buku pengajaran yang baik.30
Sosiologi sastra adalah cabang penelitian sastra yang bersifat
reflektif. Penelitian ini banyak diminati oleh peneliti yang ingin
melihat sastra sebagai cermin kehidupan masyarakat. Asumsi dasar
penelitian sosiologi sastra adalah kelahiran sastra tidak dalam
29
Nyoman Khuta Ratna, Paradigma Sosiologi Sastra, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009),
cet.II, h.1
kekosongan sosial. Kehidupan sosial akan menjadi pemicu lahirnya
sastra baru. Karya sastra yang berhasil atau sukses yaitu yang mampu
merefleksikan zamannya.31
Terdapat tiga paradigma pendekatan dalam sosiologi sastra, yaitu
sosiologi pengarang, sosiologi karya sastra, dan sosiologi pembaca.32
Pertama, sosiologi pengarang; inti dari analisis sosiologi pengarang ini adalah memaknai pengarang sebagai bagian dari masyarakat yang
telah menciptakan karya sastra. Oleh karena itu, pemahaman terhadap
pengarangnya menjadi kunci utama dalam memahami relasi sosial
karya sastra dengan masyarakat, tempat pengarang bermasyarakat.
Kedua, sosiologi karya sastra; analisis sosiologi yang kedua ini berangkat dari karya sastra. Artinya, analisis terhadap aspek sosial
dalam karya sastra dilakukan dalam rangka untuk memahami dan
memaknai hubungan dengan keadaan sosial masyarakat di luarnya.
Ketiga, sosiologi pembaca; kajian terhadap sosiologi pembaca berarti mengkaji aspek nilai sosial yang mendasari pembaca dalam memaknai
karya sastra.
Sosiologi sastra adalah model penelitian interdisiplin yang
mengaitkan karya sastra dengan masyarakat. Maka, model penelitian
dilakukan dengan tiga macam,33 sebagai berikut:
1) Menganalisis masalah-masalah sosial yang terkandung dalam
karya sastra itu sendiri kemudian menghubungkannya dengan
kenyataan yang pernah terjadi. Pada umumnya disebut sebagai
unsur ekstrinsik sastra, model hubungan yang terjadi disebut
refleksi.
2) Sama seperti di atas, tetapi dengan cara menemukan hubungan
antar struktur, bukan aspek-aspek tertentu, dengan model
hubungan yang bersifat dialektika.
31
Suwardi Endraswara, Metodologi Penelitian Sastra. (Yogyakarta: CAPS. 2013), h.77
32
Kurniawan, op.cit., h. 11
33
Nyoman Khuta Ratna, Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra, (Yogyakarta: Pustaka
3) Menganalisis karya sastra dengan tujuan untuk memperoleh
informasi tertentu. Model analisis yang pada umumnya
menghasilkan penelitian karya sastra sebagai gejala kedua.
Pada prinsipnya, menurut Laurenson dan Swingewood dalam buku
Metodologi Penelitian Sastra, terdapat tiga perspektif berkaitan dengan sosiologi sastra, yaitu: (1) penelitian yang memandang karya
sastra sebagai dokumen sosial yang di dalamnya merupakan refleksi
situasi pada masa sastra tersebut diciptakan, (2) penelitian yang
mengungkap sastra sebagai cermin situasi sosial penulisnya, dan (3)
penelitian yang menangkap sastra sebagai manifestasi peristiwa sejarah
dan keadaan sosial budaya.34 Ketiga hal tersebut dapat berdiri
sendiri-sendiri dan atau diungkapkan sekaligus dalam suatu penelitian
sosiologi sastra. Hal ini tergantung kemampuan penelitibuntuk
menggunakan salah satu perspektif atau ketiga-tiganya sekaligus.
B. Penelitian Relevan
Penelitian terhadap novel Jalan Tak Ada Ujung pernah dilakukan
oleh mahasiswa Universitas Sanata Dharma dengan judul skripsinya
“Pandangan Kemanusiaan Mochtar Lubis dalam Novel Jalan Tak Ada
Ujung: Sebuah Kajian Sosiologi Sastra” oleh Raden Rosa Dewi mahasiswa Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma tahun 2007. Hasil dari penelitiannya adalah sebagai
berikut: (1) struktur tekstual (alur). Berdasarkan struktur lahir novel Jalan
Tak Ada Ujung memiliki 35 sekuen dan alur yang digunakan adalah maju.
(2) pandangan kemanusiaan Mochtar Lubis dalam novel Jalan Tak Ada
Ujung, meliputi nilai kemanusiaan utama dan nilai kemanusiaan pendukung. Nilai kemanusiaan utama yaitu nilai keberanian, yang meliputi
(a) nilai kemanusiaan Guru Isa menghadapi perjuangan, (b) nilai
keberanian Guru Isa menghadapi krisis ekonomi, (c) nilai keberanian Guru
Isa menghadapi impotensinya, dan (d) nilai keberanian Guru Isa
menghadapi perselingkuhan.
34
Penelitian terhadap novel Jalan Tak Ada Ujung juga pernah diteliti oleh mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal dengan judul skripsinya
adalah “Tinjauan Psikologis Tokoh Novel Jalan Tak Ada Ujung Karya
Mochtar Lubis dan Implikasinya dalam Pembelajaran Sastra Di SMA”
yang ditulis Aditya Candra Jun Soekarno mahasiswa Program Studi
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Sanata Dharma tahun 2014. Kajian psikologi yang
menonjol dalam novel Jalan Tak Ada Ujung Karya Mochtar Lubis adalah
aspek psikologi kepribadian tokoh dengan jumlah kutipan tujuh belas
kutipan, aspek psikologi tingkah laku tokoh dengan jumlah tiga kutipan,
dan aspek psikologi sifat tokoh dengan jumlah dua puluh kutipan.
Penelitian terhadap novel Jalan Tak Ada Ujung juga pernah diteliti
oleh mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo dengan judul skripsinya adalah “Patriotisme dalam Novel Jalan Tak Ada Ujung Karya Mochtar Lubis” yang ditulis Asni Alimun mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Sastra dan Budaya, Universitas
Negeri Gorontalo tahun 2014. Hasil dari penelitiannya adalah tokoh Hazil
dan Rachmat yang berani melemparkan bom pada para tentara Belanda,
dan Tuan Hamidy sebagai juragan beras yang menyumbangkan truknya untuk kepentingan kemerdekaan. Para tokoh menggambarkan memiliki
sikap patriotisme. Sikap patriotisme yaitu rela berkorban, menempatkan
persatuan dan kesatuan, berjiwa pembaharu dan tidak kenal menyerah.
Penelitian lain terkait novel Jalan Tak Ada Ujung karya Mochtar
Lubis juga pernah dilakukan pada Tesis yang ditulis oleh Agus R. Sarjono berjudul “Citra rumah dalam novel 'Jalan tak ada ujung' Mochtar Lubis
dan 'Keluarga Gerilya' Pramoedya Ananta Toer” Universitas Indonesia,
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, tahun 2002. Hasil penelitiannya yaitu,
Rumah dalam KG bukan rumah yang baik. Buruknya rumah KG
disebabkan oleh perilaku dan sosok kaum tua keluarga Gerilya, yakni
kopral Paidjan (sang ayah) dan Amilah (Sang Ibu). Meskipun demikian,
peluang untuk menjadikan rumah keluarga gerilya sebagai rumah yang baik dan membuat krasan masih terbuka di tangan kaum muda. Namun,
revolusi kemerdekaan membuat semua kaum muda keluarga gerilya
memilih untuk merelakan hancurnya rumah mereka demi rumah yang
lebih besar dan lebih mulia yakni nasion. Hal yang berbeda terjadi pada
Namun revolusi menebarkan ketakutan pada Guru Isa yang menyebabkan
isa mengalami impotensi. Impotensi guru Isa menjadikan rumah mereka
sekedar menjadi rumah tanpa rasa krasan. Situasi ini diperparah oleh
perselingkuhan Fatimah dengan Hazil, sahabat Guru Isa. buruk secara
moral, dan tidak memiliki idealisme, sementara kaum muda digambarkan
sebagai sosok yang penuh idealisme dan cita-cita.
Penelitian tentang latar (setting) pernah dilakukan oleh mahasiswa
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dengan judul skripsinya adalah “Analisis Latar (setting) dalam novel Larasati Karya Pramoedya Ananta Toer” yang ditulis Adianto mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah
Sumatera Barat. Hasil penelitiannya yaitu: (1) latar tempat dalam novel
Larasati karya Pramoedya Ananta Toer bervariasi. Latar tempat yaitu di daerah Yogyakarta dan Jakarta yaitu di rumah, di kamar, di jalan, di rumah
sakit, di gedung, di pinggir jalan, di rumah orang Arab, dan lain-lain. (2)
latar waktu seperti pada waktu pagi hari, pada waktu sore hari, malam hari
yang menegangkan dan pada tahun-tahun tertentu yang dapat menonjolkan
suasana tertentu dalam novel, (3) Latar sosial yang ditampilkan di dalam
novel Larasati sangat berpengaruh pada kehidupan tokoh dalam novel.
Melihat penelitian sebelumnya terhadap novel Jalan Tak Ada
Ujung, penelitian tentang ”Analisis Latar dalam Novel Jalan Tak Ada Ujung Karya Mochtar Lubis serta Implikasinya terhadap Pembelajaran
Apresiasi Sastra Indonesia di SMA” Penelitian ini mencari gambaran latar
yang terdapat dalam novel Jalan Tak Ada Ujung karya Mochtar Lubis
selain itu mengkaitkan hasil penelitian tersebut dengan pembelajaran
sastra di sekolah. Implikasi tersebut berupa Rencana Pembelajaran Sastra
tentang Materi Intrinsik Novel. Bahan pembelajaran dilakukan melalui
BAB III
BIOGRAFI PENGARANG
A. Biografi Pengarang
Mochtar Lubis, pengarang ternama ini dilahirkan pada 7 Maret
1922 di Padang. Setelah tamat HIS Sungai Penuh, Mochtar Lubis sekolah
ekonomi di Kayutanam pimpinan M. Syafei, di Kayutanam diajarkan pula
untuk mengembangkan bakat melukis, mematung, bermusik dan
sebagainya. Sejak zaman Jepang ia telah aktif dalam lapangan penerangan. Ia turut mendirikan Kantor Berita ‘Antara’, kemudian mendirikan dan
memimpin Harian Indonesia Raya yang telah dilarang terbit. Ia
mendirikan majalah sastra Horison bersama kawan-kawannya. Pada waktu
pemerintahan rezim Soekarno, ia dijebloskan ke dalam penjara hampir 9
tahun lamanya dan baru dibebaskan pada tahun 1966.
Selain sebagai wartawan, ia dikenal sebagai sastrawan. Mochtar
Lubis merupakan pengarang yang karya-karyanya harus dilihat dalam
hubungan dengan Angkatan 45. Cerita-cerita pendeknya dikumpulkan
dalam buku Si Jamal (1950) dan Perempuan (1956). Sedangkan novelnya
yang telah terbit: Tidak Ada Esok (1950), Jalan Tak Ada Ujung (1952)
yang mendapat hadiah sastra dari Badan Musyawarah Kebudayaan
Nasional (BMKN), Senja di Jakarta yang mula-mula terbit dalam bahasa
Inggris dengan judul Twilight in Jakarta (1963) dan terbit dalam bahasa
Melayu pada tahun 1964. Selain itu, romannya yang mendapat sambutan
luas dengan judul Harimau! Harimau! (Pustaka Jaya 1975) telah
mendapat hadiah dari Yayasan Buku Utama sebagai buku terbaik tahun
1975. Sedangkan Maut dan Cinta (Pustaka Jaya 1971) mendapat hadiah
Yayasan Jaya Raya.
Kadang-kadang ia pun menulis esai dengan nama samaran Savitri
dan juga menterjemahkan beberapa karya sastra asing seperti Tiga Cerita
mendapat hadiah atas laporannya tentang Perang Korea dan 1966
mendapat hadiah Magsaysay untuk karya-karya jurnalistiknya.1
Di zaman Jepang Mochtar Lubis bekerja sebagai anggota tim yang
memonitor siaran radio sekutu di luar negeri. Sebagai wartawan dia
berpindah dari Medan ke Jakarta. Dia memperoleh pengakuan sebagai
wartawan waktu menjabat sebagai ketua pengarang surat kabar bebas
Indonesia Raya, dia berani menentang konsepsi-konsepsi politik Soekarno dengan garang, hingga mengakibatkan dia ditahan di rumah dan dalam
penjara antara tahun 1957 hingga 1966. Sebelum ini, dia telah banyak
mengelilingi dunia, dan kisah-kisah kunjungannya yang bersifat
kewartawanan sebagian dikumpulkan dalam buku-buku tersendiri.
Buku-buku tersebut merupakaan bacaan yang baik. Hal ini bukan saja karena
fakta-fakta yang terkandung, tetapi juga karena penyampaiannya yang
menarik. Malah dalam karya-karya sastranya didapati bahwa
kewartawanan dalam dirinya itu tak pernah tidak ada.2
B. Penghargaan 1. Bidang Pers
Presiden Megawati Soekarnoputri pada tahun 2004,
menganugerahkan bintang tanda jasa kepada tokoh pers Mochtar Lubis
(alm). Mochtar Lubis dinilai telah memberikan pengabdian luar biasa
kepada Negara. Tanda Bintang Mahaputera merupakan tanda jasa
tertinggi setelah Bintang Republik Indonesia. Ia diberi penghargaan
tidak dinilai berdasarkan pengabdiannya kepada pemerintah, tetapi
kepada negara.3
1
Mochtar Lubis. Jalan Tak Ada Ujung. (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia.2003) h. 166-167
2
A. Teeuw. Sastra Baru Indonesia. Cet. 1 (Flores: Indonesia Nusa Indah, 1980) h.261
3 Harian Tempo
, “Mochtar Lubis Dianugerahi Bintang Mahaputera”, edisi Minggu, 15
2. Bidang Sastra
Mochtar Lubis terpilih sebagai sastrawan pertama penerima Hadiah Sastra “Chairil Anwar” yang baru pertama kali diselenggarakan. Hadiah ini merupakan penghargaan Dewan Kesenian Jakarta (DKJ),
bahkan sebagai pengakuan atas mutu karya-karyanya. Penyerahan
hadiah berlangsung dalam sebuah upacara yang dirancang khusus di
Pusat Kesenian Jakarta, Taman Ismail Marzuki. 4
Menurut pihak DKJ, Mochtar Lubis terpilih sebagai orang pertama
penerima hadiah karena dua alasan. Alasan pertama adalah, totalitas
karya-karyanya telah sangat memperkaya khazanah sastra Indonesia.
Alasan kedua yaitu karya-karyanya secara khusus memuat realita
sosial, diwarnai dengan wawasan tentang manusia Indonesia dengan
berbagai dimensinya yang digambarkan cukup tajam dengan
penguasaan masalah hampir tanpa cacat.
Buku fiksinya Jalan Tak Ada Ujung meraih Hadiah Sastra BMKN,
disusul hadiah sama untuk Perempuan-Perempuan. Bukunya
Harimau-Harimau mendapat Hadiah Sastra Yayasan Buku Utama.
C. Pemikiran Mochtar Lubis 1. Kebebasan Kreatif
Sebagai sastrawan, Mochtar Lubis melihat bahwa sastra Indonesia
sebenarnya kaya dengan pengarang potensial. Yang kurang katanya
adalah iklim kreatif menyeluruh, artinya iklim sehat yang bisa
menggerakan seluruh masyarakat. Ia menganggap seniman cukup
kreatif dalam berbagai bidang penciptaan. Tapi, karya sastra katanya
terbelenggu oleh berbagai pembatasan baik dari dalam maupun luar.
Hambatan luar dalam itu bermuara pada suatu hal, yaitu ketakutan. “Penerbit ngeri menerbitkan dan mengedarkan karya-karya yang mengritik keadaan sosial politik atau kekuasaan, pengarang tidak
4Kompas
, “Hadiah Sastra Chairil Anwar untuk Sastrawan Mochtar Lubis”, edisi Sabtu, 15
berani menulisnya,” tuturnya. “Itu sebabnya tak ada kita baca karya fiksi yang menyoroti realita sosial semacam itu, yang bisa menciptakan
gambaran nyata tentang kondisi sosial budaya kita.” Sastrawan dan
wartawan terkemuka yang juga melukis ini, mengatakan berbagai
hambatan itu bukan kesalahan 25 tahun or