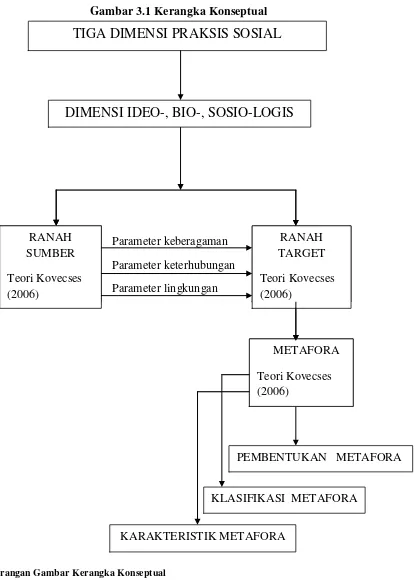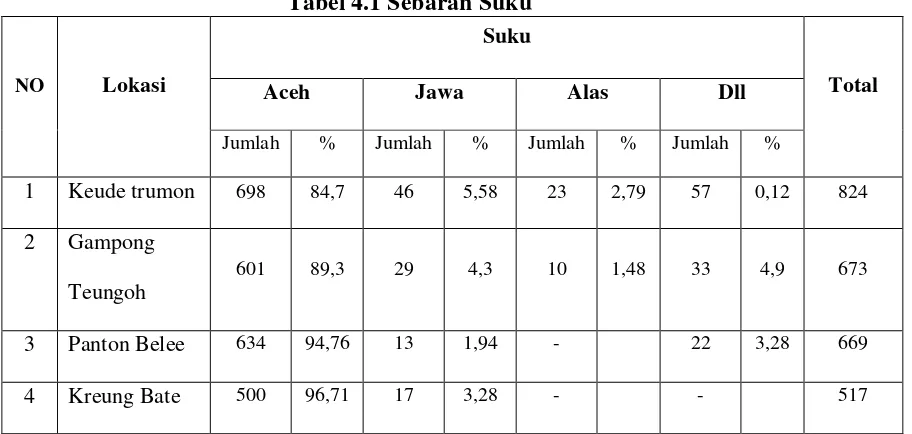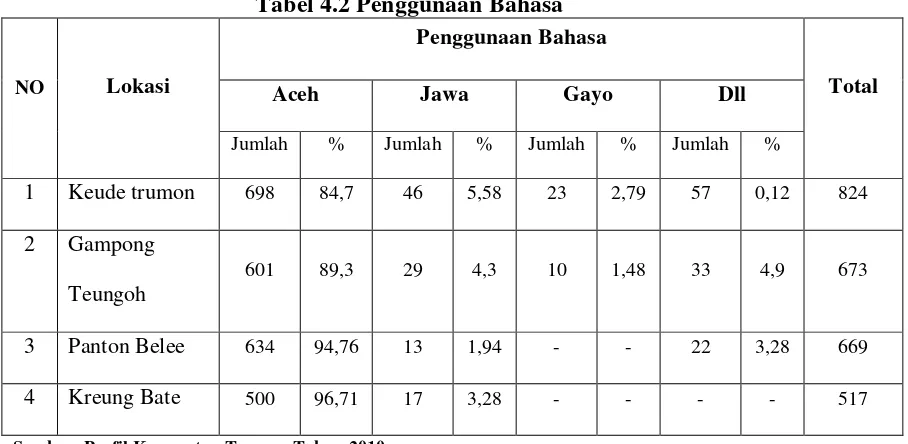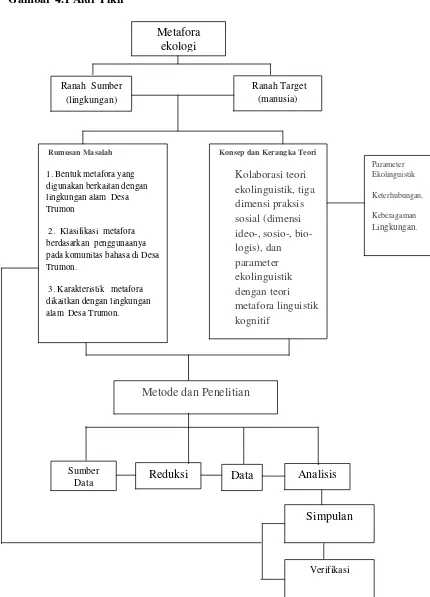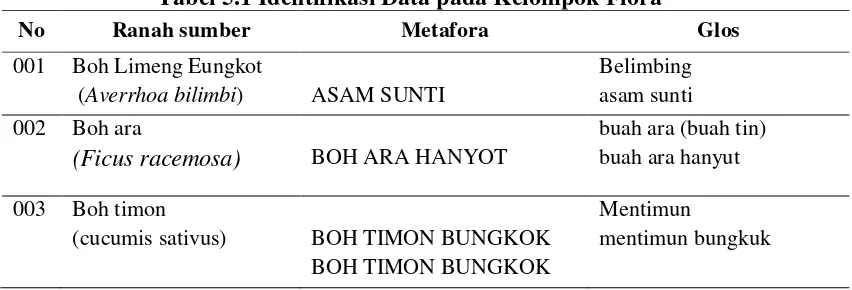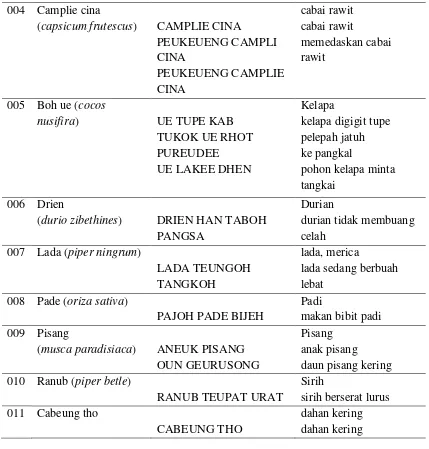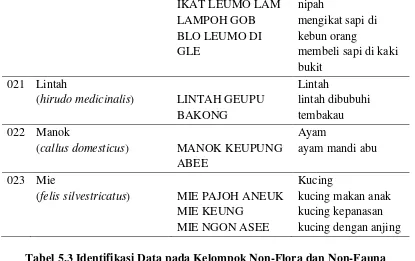KETERKAITAN METAFORA DENGAN LINGKUNGAN
ALAM PADA KOMUNITAS BAHASA ACEH
DI DESA TRUMON ACEH SELATAN:
KAJIAN EKOLINGUISTIK
DISERTASI
Oleh
NUZWATY
NIM: 108107016
Program Doktor (S3) Linguistik
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
KETERKAITAN METAFORA DENGAN LINGKUNGAN
ALAM PADA KOMUNITAS BAHASA ACEH
DI DESA TRUMON ACEH SELATAN:
KAJIAN EKOLINGUISTIK
DISERTASI
Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam Program Doktor Linguistik pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara di
bawah pimpinan Rektor Universitas Sumatera Utara Prof. Dr. Dr. Syahril Pasaribu, DTM&H, M.Sc, (CTM), Sp.A(K) untuk dipertahankan
dihadapan sidang Terbuka Senat Universitas Sumatera Utara
Oleh
NUZWATY
NIM: 108107016
Program Doktor (S3) Linguistik
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Judul Disertasi : KETERKAITAN METAFORA DENGAN LINGKUNGAN ALAM PADA KOMUNITAS BAHASA ACEH DI DESA TRUMON ACEH SELATAN: KAJIAN EKOLINGUISTIK Nama Mahasiswa : Nuzwaty
Nomor Pokok : 108107016 Program Studi : Linguistik
Menyetujui Komisi Pembimbing
Promotor
(Prof. Dr. Aron Meko Mbete)
(Dr. Eddy Setia, M.Ed. TESP)
Ko-Promotor Ko-Promotor
(Dr. T. Thyrhaya Zein, M.A.)
Ketua Program Studi Dekan
(Prof. T. Silvana Sinar, M.A., Ph.D) (Dr. Syahron Lubis, M.A.)
Diuji pada Ujian Disertasi Terbuka (Promosi)
Tanggal: 16 Desember 2014
Panitia Penguji Disertasi
Pemimpin Sidang:
Prof Dr.dr.Syahril Pasaribu,DTM&H, M.Sc, (CTM), Sp.A (K)
(Rekror USU)
Ketua
: Prof. Dr. Aron Meko Mbete, M.S.
UDAYANA Bali
Anggota : Dr. Eddy Setia, M.Ed. TESP.
USU Medan
PERNYATAAN
Judul DisertasiKETERKAITAN METAFORA DENGAN LINGKUNGAN ALAM PADA KOMUNITAS BAHASA ACEH DI DESA TRUMON ACEH SELATAN:
KAJIAN EKOLINGUISTIK
Dengan ini penulis nyatakan bahwa disertasi ini disusun sebagai syarat
untuk memperoleh gelar Doktor Linguistik pada Program Studi Linguistik
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara adalah benar merupakan hasil
karya penulis sendiri.
Adapun pengutipan-pengutipan yang penulis lakukan pada bagian-bagian
tertentu dari hasil karya orang lain dalam penulisan disertasi ini, telah penulis
cantumkan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika
penulisan ilmiah.
Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian
disertasi ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam
bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik
yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Medan, Juli 2014
Penulis,
KETERKAITAN METAFORA DENGAN LINGKUNGAN ALAM PADA KOMUNITAS BAHASA ACEH DI DESA TRUMON
ACEH SELATAN: KAJIAN EKOLINGUISTIK
ABSTRAK
Penelitian ini merupakan kajian ekolinguistik yang difokuskan kepada metafora konseptual yang mengaitkannya dengan unsur ekologi berupa flora dan fauna dalam kognitif manusia yang direkam secara verbal. Penelitian ini dilakukan di Desa Trumon Kabupaten Aceh Selatan.
Tujuan penelitian ini pertama, menganalisis dan mendeskripsikan keterkaitan metafora dengan lingkungan alam pada komunitas bahasa di Desa Trumon. Kedua, menganalisis dan mendiskripsikan klasifikasi metafora. Ketiga menganalisis dan menemukan karakteristik metafora dikaitkan dengan lingkungan alam Desa Trumon.
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah kolaborasi dari teori ekolinguistik dengan tiga dimensi sosial praksis, parameter ekolinguistik (keberagaman, keterhubungan, lingkungan), dan teori metafora konseptual kognitif linguistik.
Pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari delapan orang informan, berusia di atas lima puluh tahun dan sebagai penduduk tetap di wilayah tersebut dan mereka semuanya menikah dengan masyarakat lokal etnik Aceh.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metafora yang digunakan oleh masyarakat bahasa di Desa Trumon terbentuk dari sifat alamiah flora dan fauna yang ada di lingkungan alam sebagai ranah sumber dipetakan kepada manusia dan sifat atau perilaku manusia tersebut sebagai ranah target, keterhubungan antara ke dua ranah tersebut diproses di dalam kognitif penggunanya dan penggunaan metafora tersebut disepakati secara konvensional oleh anggota masyarakat bahasa tersebut.
Ditemukan pula bahwa pada umumnya metafora di Desa Trumon terbentuk dari ranah sumber berdasarkan pengalaman tubuh dan pengalaman inderawi pengguna bahasa tersebut. Karakteristik metafora yang digunakan di Desa Trumon merupakan metafora konseptual yang terbentuk secara konseptual alamiah dari unsur-unsur bahasa dan kognitif manusia melalui tiga dimensi sosial praksis (dimensi ideo-, sosio-, dan biologikal) dan dapat pula digambarkan dalam hubungan ontologi dan epistemik.
THE INTERRELATIONSHIP OF METAPHOR WITH NATURAL ENVIRONMENT ON THE LANGUAGE COMMUNITY OF ACEH IN
TRUMON, SOUTH ACEH: ECOLINGUITICS STUDY
ABSTRACT
This research is ecolinguistics study, focused on metaphors that related to ecological environment, such as flora and fauna which evolved in human’s cognitive. This research is conducted in Desa Trumon, South Aceh.
The research aims firstly at analyzing and describing the relationship of metaphors of Bahasa Aceh that used by the language community in Trumon with the environment. Secondly is at analyzing and describing the classification of metaphors, and thirdly is analyzing and finding the characteristic of metaphors related to the nature environment of Desa Trumon.The theory applied is a collaboration of cognitive conceptual metaphor theory with three dimension social praxis theory and theory of ecolinguistics parameters.
The method employed was qualitative approach and the data obtained was from eight informants who were born and live in Trumon. All of them are above fifties and they also married the locals.
The result of this research shows that the metaphorical frames are structured by forms of interaction of two models; a source and a target domain. Metaphors of Bahasa Aceh in Trumon constituted by the nature of flora and fauna that exist in local surroundings as the source domain, and human’s behavior or his manner stands as the target domain. The source domain imposed some structure on the target by virtue of mapping that characterizing the metaphors. The relationship of both was processed in thought of the language users, and also respected to the convention of the language community.
It is also found that in general, metaphor used in Trumon constructed by bodily experience of the language users. The characteristic of metaphors used in Trumon is conceptual metaphors that constructed by nature in relationship between language entity and human’s cognitive under three dimension of social praxis(ideo-, socio-, biological dimension) which can be drawn on ontology and epistemic relations.
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahi rabbil ‘alamin. Puji dan syukur penulis haturkan kepada
ALLAH Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya
yang diberikan kepada penulis sehingga penulisan disertasi ini dapat diselesaikan
sebagaimana yang diharapkan. Shalawat seiring salam penulis hadiahkan kepada
Nabi Muhammad SAW. Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini
penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
banyak membantu dan turut berpartisipasi selama penulis mengikuti pendidikan
hingga penyelesaian disertasi ini.
Pertama-pertama penulis berterima kasih dan menyampaikan penghargaan
yang tulus kepada Prof. Dr. Aron Meko Mbete yang telah memperkenalkan
kajian ekolinguistik dan bersedia menjadi promotor, serta dengan penuh
keikhlasan memberikan bimbingan, arahan, dan masukan berharga serta dukungan
semangat kepada penulis. Penghargaan dan terima kasih yang sama penulis
sampaikan pula kepada promotor I, Dr. Eddy Setia, M.Ed. TESP dan
ko-promotor II Dr. T. Thyrhaya Zein, M.A. yang telah membimbing, memberikan
saran-saran dan masukan dengan penuh akrab sehingga penulis merasa nyaman
ketika bimbingan.
Selanjutnya penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada Rektor
Universitas Sumatera Utara, Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H., M.Sc.
(CTM), Sp.A. (K) yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menjadi
Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Ilmu
Budaya, Dr. Syahron Lubis, M.A, yang berkenan menerima penulis mengikuti
perkuliahan pada Program Doktor Linguistik dan menggunakan fasilitas yang ada.
Penghargaan yang tinggi dan rasa terima kasih yang tidak ternilai penulis
sampaikan kepada Ketua Program Studi Linguistik, Prof. T. Silvana Sinar, M.A,
Ph.D yang sangat berperan demi keberhasilan penulis untuk menyelesaikan studi
dalam kapasitas beliau sebagai ketua Program Studi linguistik, dosen pengajar,
dan penguji, serta telah memberikan rekomendasi kepada penulis untuk
memperoleh beasiswa BBPS, selanjutnya dukungan semangat yang beliau berikan
kepada penulis untuk mengikuti Program Sandwich-Like di Leiden Universiteit,
Netherland, sehingga penulis dapat mengikuti program tersebut tahun 2012.
Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada
Sekretaris Program Studi Linguistik, Dr. Nurlela, M. Hum, yang memberikan
dorongan dan selalu menanyakan perihal perkuliahan penulis.
Penulis ingin mengkhususkan ucapan terima kasih dan penghargaan
kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Republik Indonesia yang telah
memberikan beasiswa BPPS di Sekolah Pasca Sarjana USU dan beasiswa
Program Sandwich-Like di Leiden Universiteit, Netherland kepada penulis.
Penghargaan yang sama penulis sampaikan pada mantan Koordinator Kopertis
Wilayah I, Prof. Dr. Zainuddin yang telah memberi rekomendasi kepada penulis
untuk mendapatkan BPPS. Penghargaan yang sama pula penulis sampaikan
kepada Rektor Universitas Islam Sumatera Utara, Dr. Ir. M. Asaad, M.Si, yang
untuk melanjutkan studi ke Program Doktor Linguistik di USU. Demikian pula
ucapan terima kasih kepada Dekan FISIP UISU, Drs. Hadeli, M.Si yang telah
membebaskan penulis dari tugas-tugas akademik selama penulis mengikuti
perkuliahan di Program Doktor Linguistik USU. Ungkapan rasa terima kasih juga
penulis sampaikan kepada kepada mantan Direktur Sekolah Pasca Sarjana, Prof.
Dr. Ir. A. Rahim Matondang, MSIE yang telah memberikan rekomendasi kepada
penulis mengikuti Program Sandwich-Like di Leiden Universiteit, Netherland.
Ungkapan terima kasih dan penghargaan penulis sampaikan kepada para
penguji luar komisi, yatni Prof. Dr. Robert Sibarani, M.S dari USU, Prof. Dr
Busmin Gurning, M.Pd. dari UNIMED, dan Prof. Amrin Saragih, M.A., Ph.D.
dari UNIMED yang telah memberikan saran dan masukan,
pertanyaan-pertanyaan, serta kometar-komentar yang sangat bermanfaat untuk penyelesaian
penulisan disertasi ini.
Ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan yang tinggi penulis
sampaikan pada semua staf pengajar di Program Studi Linguistik Linguistik,
Prof.T. Silvana Sinar, M.A. Ph.D, Prof. Amrin Saragih, M.A, Ph.D, Prof. Bahren
Umar Siregar, Ph.D, Prof. Dr. Aron Meko Mbete, MS, Prof. Dr. Robert Sibarani,
MS, Prof. Dr. Busmin Gurning, M.A, Prof. Dr. Paitoon M. Chaiyanara, Dr. Eddy
Setia, M.Ed. TESP, Dr. Bolaz Huzla, Dr. T. Syarfina, M.Hum, Dr. Dwi Widayati,
Dr. Irawati Kahar, M. Pd yang telah memperluas wawasan penulis tentang
linguistik. Penulis juga berterima kasih kepada staf administrasi Prodi Linguistik,
Terima kasih tak terhingga penulis ucapkan kepada semua informan bapak
H. Muhammad Syamsuddin, bapak Marzuki Ibrahim, ibu Hj. Cut Siti Zubaidah
Junet, bapak H. Burhanuddin Yusuf, bapak Ahmad Badawi, ibu Hj. Cut Habibah
binti Jakfar, bapak Teuku U’baidillah bin Teuku Raja Sulaiman dan Bapak Teuku
Laksamana bin Teuku Pithahuddin, dan semua partisipan, yang tidak dapat
penulis sebutkan namanya satu persatu. Ucapan yang sama khususnya kepada
Bapak Muzakir Ali yang dengan kerelaan hati mendampingi penulis selama
penelitian di Desa Trumon. Ucapan yang sama penulis sampaikan juga kepada
kemanakan dr. Mutia Diana dan Muhammad Daniel, SH yang telah menyediakan
semua fasilitas dan akomodasi untuk penulis.
Ungkapan terima kasih atas kerja sama, bantuan, dan persahabatan yang
terjalin selama ini penulis sampaikan kepada semua rekan-rekan mahasiswa S3
Prodi Linguistik, Faridah Yafitham, SS, M. Hum, khususnya angkatan tahun
2010, Putri Nasution SS, M.Hum, Drs Bahagia Tarigan, M.A, Elvi Syahrin SS,
M.Hum, Muhammad Ali Pawiro SS, M.A, H Purwanto Siwi, SS, M.A, Dra.
Roswani Siregar, M. Hum, Dr. Emmy Erwina, M.A, Rina Evianti, Rabiah Adawi
dan rekan-rekan lainnya yang tidak dapat disebut satu persatu.
Dalam kesempatan ini, penulis juga menyampaikan terima kasih pada Dr.
Aune Van Engelehouven yang telah banyak memberikan bimbingan selama
penulis mengikuti Program Sandwich-Like di Leiden Universiteit, Netherland.
Ucapan yang sama disampaikan kepada Dr. R. Busser, Institute Manager Faculty
of Humanities Leiden Universiteit yang telah memberikan fasilitas di KITLV,
Martina Girsang dari Prodi Linguistik (S3) dan Emmi Rahmiwita Nasution dari
Prodi Hukum (S3) yang selalu bersama dan berbagi suka dan duka yang selalu
dikenang selama mengikuti program Sandwich-Like 2012 di Leiden Universiteit.
Penulis mengenang dan memberi penghargaan yang amat tinggi kepada
kedua orang tua penulis, Ayahanda almarhum H. Abdul Munir Nasution dan
Ibunda almarhumah Hj. Siti Khadijah, yang semasa hidup mereka, dengan
kemuliaan hati dan kasih sayang yang tulus, selalu memberikan nasihat dan
mendoakan, serta memberikan dorongan semangat untuk kesuksesan penulis.
Pencapaian akademik penulis sesungguh adalah keberhasilan mereka. Ucapan dan
penghargaan yang sama, penulis sampaikan kepada kedua mertua penulis
almarhum H. Muhammad Yusuf dan almarhumah Hj. Siti Aminah, yang semasa
hidupnya selalu memberi nasihat-nasihat untuk keberhasilan penulis. Penulis
haturkan terima kasih kepada kakak dan adik-adik, kakak Drh. Hj. Idawati
Nasution, Msi, adik Muchrizal Nasution, Dra. Hj. Fitriani. MAP, Ir. Fahrum
Syahrial, Ir. Hj. Zulerwina, Ir. Yudi Assyuri. Ucapan yang sama kepada ipar-ipar,
Alm Drh. H. Samsuddin Ali, Nuriati, Ir. H. Ali Azhar, Ir. Cut Mariana. Drs. H.
Wira Indra Satya, M.Si, dr. Fitriani Lumongga Nasution, M. Kes dan seluruh
keluarga yang senantiasa memberikan dukungan dan perhatian demi keberhasilan
penulis.
Terima kasih yang tak terhingga kepada suami tercinta, H. Amir Husin,
yang tetap menyemangati penulis agar penulis dapat menyelesaikan disertasi ini .
Pengertian dan motivasi, serta kasih sayang yang diberikan adalah sikap yang
Com. Health, Julya Mazaya, SE, MBA, dan si kembar Millatina Urfana, SE dan
Millatina Urfani, SE, yang sejak kecil sering belajar bersama orang tuanya,
dengan bangga penulis ucapkan terima kasih atas pemahaman dan dukungan
semangat yang diberikan kepada mamanya, serta menantu Nofri Alhadi, ST, MIT
dan Riky Armadi, ST yang tetap mendukung penulis diucapkan terima kasih.
Semoga ALLAH SWT memberi keberkahan umur dan hidup mereka.
Akhirnya, terima kasih kepada semua yang belum penulis sebutkan satu
persatu yang telah banyak membantu penulis, baik moril, materi, dan dukungan
doa. Pada kesempatan ini penulis mohon maaf atas segala kesalahan yang
mungkin terjadi selama perkuliahan. Penulis berdoa semoga Allah SWT
memberikan yang terbaik untuk kita semua dan semoga hasil karya ini dapat
bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa. Amin ya Robbal alamin.
Medan, Desember 2014
Nuzwaty
DAFTAR ISI
2.1.2 Parameter Ekolinguistik ... 25
2.1.2.1 Parameter Keberagaman ... 26
2.1.2.2 Parameter Kesalingterhubungan ... 26
2.1.2.3 Parameter Lingkungan ... 29
2.1.3 Teori Dialektikal Sosial Praksis ... 32
2.2 Linguistik Kognitif ... 35
2.3.6 Metafora dan Metonimi ... 51
2.4 Semantik Leksikal ... 52
2.4.1 Makna dan Referensi ... 54
2.4.2 Denotasi dan Konotasi ... 55
BAB III TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL ... 66
4.2.3 Kehidupan Sosial Masyarakat Desa Trumon ... 79
4.3 Data dan Sumber Data ... 81
4.3.1 Teknik Pengumpulan Data ... 83
4.4 Analisis Data ... 84
4.5 Pengecekan Keabsahan Data Penelitian ... 86
BAB V PAPARAN DATA DAN ANALISIS PENELITIAN ... 89
5.1 Pengantar ... 89
5.2 Kelompok Flora ... 93
5.3 Kelompok Fauna ... 123
5.4 Kelompok Non-Flora dan Non-Fauna ... 165
BAB VI PEMBAHASAN TEMUAN PENELITIAN ... 179
6.1 Pengantar ... 179
6.2 Pembentukan Metafora Berkaitan dengan Lingkungan Alam Desa Trumon ... 181
6.3 Klasifikasi Metafora Berdasarkan Penggunaannya pada Komunitas Bahasa di Desa Trumon ... 196
6.4 Karakteristik Metafora Dikaitkan dengan Lingkungan Alam Desa Trumon ... 203
6.4.1 Hubungan Ontologis dan Hubungan Epistemik pada Kelompok Flora ... 204
6.4.2 Hubungan Ontologis dan Hubungan Epistemik pada Kelompok Fauna ... 208
6.4.3 Hubungan Ontologis dan Hubungan Epistemik pada Kelompok Non-Flora dan Non- Fauna ... 213
BAB VII PENUTUP ... 217
7.1 Simpulan ... 217
7.2 Saran ... 221
DAFTAR PUSTAKA ... 223
DAFTAR TABEL
Nomor Judul Halaman
Tabel 4.1 Sebaran Suku ... 74
Tabel 4.2 Penggunaan Bahasa ... 75
Tabel 5.1 Identifikasi Data pada Kelompok Flora ... 89
Tabel 5.2 Identifikasi Data pada Kelompok Fauna ... 90
DAFTAR GAMBAR
Nomor Judul Halaman
KETERKAITAN METAFORA DENGAN LINGKUNGAN ALAM PADA KOMUNITAS BAHASA ACEH DI DESA TRUMON
ACEH SELATAN: KAJIAN EKOLINGUISTIK
ABSTRAK
Penelitian ini merupakan kajian ekolinguistik yang difokuskan kepada metafora konseptual yang mengaitkannya dengan unsur ekologi berupa flora dan fauna dalam kognitif manusia yang direkam secara verbal. Penelitian ini dilakukan di Desa Trumon Kabupaten Aceh Selatan.
Tujuan penelitian ini pertama, menganalisis dan mendeskripsikan keterkaitan metafora dengan lingkungan alam pada komunitas bahasa di Desa Trumon. Kedua, menganalisis dan mendiskripsikan klasifikasi metafora. Ketiga menganalisis dan menemukan karakteristik metafora dikaitkan dengan lingkungan alam Desa Trumon.
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah kolaborasi dari teori ekolinguistik dengan tiga dimensi sosial praksis, parameter ekolinguistik (keberagaman, keterhubungan, lingkungan), dan teori metafora konseptual kognitif linguistik.
Pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari delapan orang informan, berusia di atas lima puluh tahun dan sebagai penduduk tetap di wilayah tersebut dan mereka semuanya menikah dengan masyarakat lokal etnik Aceh.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metafora yang digunakan oleh masyarakat bahasa di Desa Trumon terbentuk dari sifat alamiah flora dan fauna yang ada di lingkungan alam sebagai ranah sumber dipetakan kepada manusia dan sifat atau perilaku manusia tersebut sebagai ranah target, keterhubungan antara ke dua ranah tersebut diproses di dalam kognitif penggunanya dan penggunaan metafora tersebut disepakati secara konvensional oleh anggota masyarakat bahasa tersebut.
Ditemukan pula bahwa pada umumnya metafora di Desa Trumon terbentuk dari ranah sumber berdasarkan pengalaman tubuh dan pengalaman inderawi pengguna bahasa tersebut. Karakteristik metafora yang digunakan di Desa Trumon merupakan metafora konseptual yang terbentuk secara konseptual alamiah dari unsur-unsur bahasa dan kognitif manusia melalui tiga dimensi sosial praksis (dimensi ideo-, sosio-, dan biologikal) dan dapat pula digambarkan dalam hubungan ontologi dan epistemik.
THE INTERRELATIONSHIP OF METAPHOR WITH NATURAL ENVIRONMENT ON THE LANGUAGE COMMUNITY OF ACEH IN
TRUMON, SOUTH ACEH: ECOLINGUITICS STUDY
ABSTRACT
This research is ecolinguistics study, focused on metaphors that related to ecological environment, such as flora and fauna which evolved in human’s cognitive. This research is conducted in Desa Trumon, South Aceh.
The research aims firstly at analyzing and describing the relationship of metaphors of Bahasa Aceh that used by the language community in Trumon with the environment. Secondly is at analyzing and describing the classification of metaphors, and thirdly is analyzing and finding the characteristic of metaphors related to the nature environment of Desa Trumon.The theory applied is a collaboration of cognitive conceptual metaphor theory with three dimension social praxis theory and theory of ecolinguistics parameters.
The method employed was qualitative approach and the data obtained was from eight informants who were born and live in Trumon. All of them are above fifties and they also married the locals.
The result of this research shows that the metaphorical frames are structured by forms of interaction of two models; a source and a target domain. Metaphors of Bahasa Aceh in Trumon constituted by the nature of flora and fauna that exist in local surroundings as the source domain, and human’s behavior or his manner stands as the target domain. The source domain imposed some structure on the target by virtue of mapping that characterizing the metaphors. The relationship of both was processed in thought of the language users, and also respected to the convention of the language community.
It is also found that in general, metaphor used in Trumon constructed by bodily experience of the language users. The characteristic of metaphors used in Trumon is conceptual metaphors that constructed by nature in relationship between language entity and human’s cognitive under three dimension of social praxis(ideo-, socio-, biological dimension) which can be drawn on ontology and epistemic relations.
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Bahasa, kebudayaan, dan lingkungan alam merupakan komponen atau
suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain sepanjang sejarah
kehidupan manusia. Berabad-abad yang lalu para filosof kuno seperti Plato
(427-347 SM), Cratylus dan lainnya pada awalnya memandang bahasa hanya sebagai
sarana komunikasi dalam mengungkapkan atau mentransfer ide-ide, inspirasi, dan
faham filsafati hasil perenungan mereka saja. Eksistensi bahasa yang pada
awalnya hanya dipahami sebagai media komunikasi, lambat laun berubah yang
selanjutnya menjadikan bahasa sebagai objek material kajian mereka dan
menempatkannya sebagai filsafat bahasa.
Mereka mulai mengkaji hubungan bahasa dan alam semesta seperti pada
penamaan-penamaan benda ataupun hewan sesuai dengan peniruan bunyi-bunyi
yang dihasilkan oleh alam seperti suara guntur, gemercik air dan suara binatang.
Bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alam tersebut tertangkap oleh indera manusia,
kemudian diolah di dalam pikiran mereka, menghasilkan sederetan nama-nama
benda yang dirujuknya. Akhirnya, mereka membuat sebuah kesimpulan bahwa
bahasa lahir dari alam, sehingga implementasi kajian bahasa dikaitkan dengan
ecoregion dan lingkungan alam tempat bahasa itu ada atau digunakan, yang
bermuara kepada munculnya beberapa terminologi seperti adanya terminologi
onomatophe, metafora, adanya part of speech, analogi versus anomaly, fisei dan
Bahwa bahasa cenderung dipengaruhi oleh lingkungan alam tempat bahasa
itu digunakan, juga sudah dibicarakan oleh Sapir (1912), Fill dan Muhlhausler
(2001:14). Keterkaitan bahasa dan alam juga dapat dilihat dari ungkapan Laen
lhok laen buya, laen kreung laen eungkeut dapat mengandung atau
mengekspresikan banyak makna. Leksikon nama lhok ‘lubuk’ adalah kode lingual
yang merupakan satuan leksikon dasar. Sebelum menjadi unsur inti dalam
ungkapan tersebut, leksikon lhok secara leksikal memiliki makna denotasi
referensial eksternal yang merujuk entitas-entitas tertentu (lihat Cummings, 2007:
54; Verhaar, 2006: 389) dalam hal ini orang, benda, atau keadaan yang nyata.
Makna leksikal yang terkandung di balik leksikon nama ruang tertentu di sungai,
dalam hal ini lhok adalah ‘bagian sungai atau danau yang dalam’.
Pengetahuan dan pengalaman penutur bahasa Aceh tentang lingkungan
sungai yang dalam, selain yang dangkal, berbasiskan pengenalan, pengetahuan,
bahkan pengalaman komunitas tutur yang tentunya bermula dari keteraturan
interelasi dan interaksi dengan kondisi sungai yang dalam (lhok) dan atau yang
dangkal (kreung) itu, seperti juga dengan biota eungkeut ‘ikan’ dan buya ‘buaya’
ataupun entitas-entitas di lingkungan sosial. Berdasarkan kode-kode leksikal, dan
dengan cakupan makna denotasi, makna konotasi yang disepakati, daya cipta para
penuturnya memeroduksi ungkapan atau peribahasa tersebut. Hal yang sama
terjadi pula pada sejumlah leksikon krueng ‘sungai’ dalam laen krueng laen
eungkeut menjadi ungkapan-ungkapan yang sangat bermakna bagi masyarakat
tuturnya dan terwaris dari generasi ke generasi. Pewarisan itu umumnya
Bagi komunitas penutur bahasa Aceh di Trumon, interelasi dan interaksi
yang terus menerus misalnya: dengan bue ‘kera’, dengan eungkeut ‘ikan’, dengan
abo ‘siput’, dengan glang ‘cacing tanah’ dengan boh timun ‘buah mentimun’, dan
tentunya dengan anekaragam hayati dan nonhayati yang ada di lingkungan hidup
mereka, memberikan ruang bagi mereka untuk mengonstruksi pengetahuan dan
memberi peluang untuk menciptakan ungkapan-ungkapan metaforis yang kaya
makna sosial budaya, sekaligus juga memperkaya bahasa dan budaya Aceh pula.
Dalam bahasa dan budaya lokal Nusantara, dalam hal ini bahasa dan budaya
Aceh, sesungguhnya tersimpan kekayaan dan modal sosial budaya bangsa.
Termasuk di dalamnya adalah kekayaan kearifan lokal yang tersimpan di balik
teks verbal berupa ungkapan-ungkapan metaforik, peribahasa, dan sebagainya ada
di pelbagai wilayah Nusantara (lihat Sibarani, 2012:133).
Ungkapan Laen lhok laen buya, laen kreung laen eungkeut ini, merupakan
bentuk metafora yang menjadikan lingkungan alam sebagai acuan. Maksud
metafora ini dapat diperluas lagi, seperti lain daerah lain bahasa dan lain budaya,
serta lain pula bentuk metaforanya. Sebagai contoh, ungkapan Bahasa Indonesia,
KALAU TIDAK ADA API TIDAK MUNGKIN ADA ASAP, menggambarkan
fenomena alam di mana secara alamiah asap sesungguhnya merupakan gejala
alam yang pada setiap kemunculannya pasti dimulai oleh adanya api sebagai
penyebab keberadaannya. Secara metaforis makna ungkapan itu mengekspresikan
suatu kejadian tidak akan terjadi tanpa penyebab. Jika komunitas bahasa Indonesia
menggunakan dua komponen yaitu asap dan api sebagai perujukan atau referen,
atau ekologi sebagai referen untuk ungkapan yang maknanya sama secara
metaforis yaitu, ‘sesuatu tidak akan terjadi tanpa ada penyebabnya’. Ungkapan
tersebut adalah, MEUNG HANA ANGEN, PANE MUMEET ON KAYEE yang
secara literal atau harfiah bermakna, ‘jika tidak ada angin tidak mungkin daun
bergoyang’. Ungkapan LAEN LHOK LAEN BUYA, atau LAEN KRUENG
LAEN EUNGKEUT terlihat kesesuaiannya pada dua ungkapan KALAU TIDAK
ADA API TIDAK MUNGKIN ADA ASAP dan MEUNG HANA ANGEN,
PANE MUMEET ON KAYEE yang mengandung makna sama tetapi
menggunakan rujukan atau referen unsur ekologi berbeda disebabkan oleh
perbedaan ecoregion dan perbedaan komunitas penuturnya, sebagai cerminan
perbedaan tingkat kedalaman interelasi, interaksi, dan interdipensi dengan
unsur-unsur yang ada di lingkungan walau sebagai masyarakat bahasa yang sama.
Bentuk ungkapan bahasa Aceh seperti MEUNG HANA ANGEN, PANE
MUMEET ON KAYEE, banyak dijumpai dan digunakan dalam interaksi
keseharian masyarakat di Desa Trumon. Desa ini terletak di Aceh Selatan yang
berbatasan dengan Cagar Alam Gunung Leuser. Pada umumnya referen yang
digunakan sebagai acuan untuk sebuah ungkapan ataupun metafora di desa ini
sangat bergantung kepada lingkungan alam desa yang berkaitan dengan flora,
fauna, dan benda-benda yang terdapat di sekitar alam Desa Trumon. Bahasa yang
digunakan oleh masyarakat Trumon dalam interaksi keseharian mereka adalah
bahasa Aceh.
Bahasa Aceh merupakan satu di antara bahasa-bahasa daerah yang
bahasa Aceh, ada pula beberapa bahasa lain nya yang digunakan dalam interaksi
verbal seperti, bahasa Gayo yang merupakan bahasa ibu bagi masyarakat Aceh
Tengah. Bahasa Alas merupakan bahasa daerah yang digunakan di Aceh
Tenggara. Bahasa Tamiang merupakan varian atau dialek dari bahasa Melayu
yang digunakan di Aceh Timur. Bahasa Aneuk Jamee digunakan di sebahagian
Aceh Selatan dan Aceh Barat. Jumlah penutur bahasa Aceh merupakan jumlah
terbesar, yaitu sekitar 70% dari jumlah keseluruhan penduduk NAD;
21.00wib).
Pada umumnya bahasa Aceh digunakan di semua ranah penggunaan
bahasa oleh masyarakat tutur bahasa tersebut, baik dalam situasi resmi maupun
tidak. Hal tersebut juga terjadi di beberapa desa di Aceh Selatan. Sesungguhnya
mayoritas masyarakat Aceh Selatan merupakan penutur bahasa Aneuk Jamee.
Namun di beberapa desa mereka masih menggunakan bahasa Aceh Seperti, di
Kuala Batee, Blang Pidie, Manggeng, Sawang, Tangan-Tangan , Meukek,
Trumon dan Bakongan. Di wilayah ini eksistensi bahasa Aceh masih terlihat dan
digunakan dalam semua situasi dan ranah penggunaan bahasa, seperti yang
diungkapkan oleh ketua Penilik Kebudayaan Aceh di Trumon yang bernama
Teuku U’baidillah bin Teuku Raja Sulaiman dan anggota Majelis Adat Aceh
bidang kebudayaan Aceh Selatan bapak Teuku Laksamana bin Teuku Pitahruddin.
Kedua informan ini masih keturunan raja Trumon (dapat dilihat pada lampiran
Dapat dikatakan masyarakat Desa Trumon masih sangat mencintai
lingkungan alamnya. Adalah kenyataan dan kebanggaan mereka karena masih
terawatnya kawasan hutan lindung yaitu kawasan hutan Cagar Alam Leuser yang
mendapatkan pengakuan internasional dan perlindungan hukum. Hutannya yang
masih rimba belantara menyimpan flora langka yang tumbuh secara liar. Fauna,
aneka satwa yang hidup liar juga terekam secara leksikal dalam bahasa Aceh
seperti rimueng ‘harimau’, gajah ‘gajah’, rusa ‘rusa’. Habitat liar ini tetap dijaga
kelangsungan hidupnya oleh pemerintah setempat. Semua ini dapat dijadikan
wisata ilmiah untuk kemajuan semua bidang ilmu pengetahuan. Paru-paru alam di
kawasan ini masih mampu bekerja dengan sempurna memelihara kesinambungan
kesehatan ekologi dan ekosistem.
Mencintai dan merawat lingkungan alam, serta hidup berdampingan
dengan alam menjadi bagian harmonisasi kehidupan masyarakat Desa Trumon.
Hidup berdampingan dengan alam tidak bermakna bahwa masyarakat Trumon
hidup terisolasi dan tetap mempertahankan penggunaan alat-alat tradisional
dengan menolak segala bentuk peralatan elektronik. Pemanfaatan alat-alat
elektronik di Desa Trumon menggeser peralatan tradisional yang mengakibatkan
beberapa istilah dan kosa kata menjadi tidak umum lagi penggunaannya,
perlahan-lahan hilang dari khasanah bahasa itu. Bahasa akan mengalami perubahan ketika
ekologi yang menunjangnya berubah dapat dilihat dari hasil penelitian yang
dilakukan oleh Mbete (2009) pada bahasa Bali. Contoh yang digambarkan seperti
setapak dalam bahasa Bali yang sudah asing didengar, dan menjadi tidak umum
lagi penggunaannya dalam masyarakat tutur bahasa Bali.
Penggeseran penggunaan peralatan tradisional disebabkan oleh masuknya
alat-alat elektronik yang serba praktis, menjadikan beberapa kata dan istilah
menjadi asing karena sudah tidak digunakannya lagi peralatan tersebut di Desa
Trumon, sebagai contoh geunuku, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur
kelapa sudah berganti dengan mesin pengukur kelapa. Ketergusuran geunuku
akibat dari sudah tidak dipergunakan lagi, tidak berpengaruh pada penggunaan
metafora GEUNUKU HAN MATA TIMAH, yang berasal dari ranah sumber
geunuku. Metafora ini masih tetap digunakan dalam komunikasi keseharian
masyarakat Trumon. Contoh tuturan yang paling umum adalah:
Jino jih GEUNUKU HAN MATA TIMAH. sekarang org III tgl kukuran tanpa mata timah.
Secara harfiah tuturan ini bermakna: Sekarang dia kukuran kelapa tanpa
mata timah. Makna leksikal, jino ‘sekarang’, jih ‘dia’, geunuku ‘kukuran kelapa’,
han ‘tanpa’, mata timah (mata kukuran kelapa yang terbuat dari besi bergerigi).
Makna metaforis yang terkandung dalam tuturan tersebut dialamatkan kepada
seseorang yang pada saat menduduki jabatan dan berpangkat tinggi, orang
tersebut bersikap sombong, angkuh dan ditakuti oleh bawahannya, namun setelah
dia pensiun kesombongannya sirna dan didiskreditkan dalam pergaulan di
masyarakatnya.
Para orang tua di Trumon sering menyampaikan pesan-pesan nasihat dan
mengingatkan anak mereka agar tidak berperilaku angkuh dan sombong, ketika
yaitu alat yang digunakan untuk menggiling padi dan menumbuk tepung beras.
Jeungki sudah tidak ditemukan lagi di desa ini karena sudah digantikan dengan
mesin penggiling padi yang dalam bahasa lokal disebut kilang pade, akan tetapi
metafora JEUNGKI MUGEE, masih digunakan dalam interaksi sosial. Secara
harfiah jeungki muge bermakna alat penumbuk padi yang dimiliki oleh tengkulak.
Makna metaforis JEUNGKI MUGEE ditujukan kepada seseorang yang
mempunyai sifat tamak. Para orang tua di desa ini sering menasihati anaknya agar
tidak tamak dengan tuturan:
Hai neuk bek jadee JEUNGKI MUGEE beu, ‘wahai anakku jangan tamak ya’
Keunikan metafora seperti ini layak untuk dikaji dan dapat menjadi
pertimbangan dalam penelitian tentang bahasa dan fungsi referensial bahasa yang
berkorelasi dengan ekologi. Kajian ini difokuskan kepada penelusuran metafora
sebagai perangkat kebahasaan yang terkait dengan lingkungan alam Desa Trumon
(ecoregion). Judul disertasi yang dipilih adalah: “Keterkaitan Metafora dengan Lingkungan Alam pada Komunitas Bahasa Aceh di Desa Trumon Aceh Selatan: Kajian Ekolinguistik”.
Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan ekolinguistik karena kajian
ekolinguistik memang berupaya menggeluti kajian bahasa yang secara teoritis
dipadukan dengan ekologi dan ekosistem. Lingkungan alam atau ekosistem
sekitar tempat masyarakat bermukim dapat memengaruhi cara berpikir dalam
mengungkapkan maksud tertentu seperti yang dinyatakan oleh Fill dan
Muhlhausler (2001:104). Metafora yang digunakan di Desa Trumon sangat
sebagaimana yang terdapat dalam kedua metafora yang telah disinggung
sebelumnya.
Penelitian ini tidak membicarakan tentang pola pemertahanan bahasa
yang terkait dengan bertahan, bergeser atau lenyapnya metafora bahasa tersebut,
sebagaimana penelitian-penelitian ekolinguistik yang pernah dilakukan oleh
beberapa pakar ekolinguistik seperti Nelde Peter (1979), Haugen (1970),
Mufwene (2004). Penelitian ini hanya mengaji keterhubungan metafora yang
menjadikan lingkungan alam sebagai ranah sumber atau unit dasar metafora
tersebut.
Penelitian ini diarahkan kepada bentuk metafora yang menjadikan
lingkungan alam yaitu flora, fauna serta mineral dan kehidupan manusia sebagai
referensi atau ranah sumber yang berada di dalam kognitif penutur bahasa tersebut
dipetasilangkan kepada manusia atau hewan sebagai tujuan atau ranah target.
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rangsangan kepada peneliti linguistik
untuk mengarahkan fokus penelitian mereka ke bidang ekolinguistik, sebab
ekolinguistik memiliki lahan yang masih luas untuk dikaji.
1.2 Rumusan Masalah
Hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian bergayut kepada
hubungan linguistik dan ekologi dalam tataran bahasa yang bermuara kepada
metafora yang ada di Desa Trumon dalam semua aspek keberadaan dan
penggunaannya.
1. Bagaimanakah pembentukan metafora yang digunakan berkaitan
2. Bagaimanakah klasifikasi metafora berdasarkan penggunaannya pada
komunitas bahasa di Desa Trumon?
3. Bagaimanakah karakteristik metafora dikaitkan dengan lingkungan
alam Desa Trumon?
1.3 Tujuan Penelitian
Pada hakikatnya penelitian ini bertujuan sebagai berikut:
1. Menganalisis dan mendikripsikan keterkaitan lingkungan alam dalam
pembentukan metafora yang digunakan oleh komunitas bahasa di Desa
Trumon.
2. Menganalisis dan mendiskripsikan klasifikasi metafora yang
digunakan oleh komunitas bahasa di Desa Trumon.
3. Menganalisis dan menemukan karakteristik metafora yang dikaitkan
dengan lingkungan alam Desa Trumon.
1.4 Manfaat Penelitian
Kajian ini perlu dan penting dilakukan atas dasar keilmuan untuk
menunjukkan bahwa teori ekolinguistik tidak hanya dapat diaplikasikan kepada
penelitian yang berkaitan dengan kebertahanan ataupun ketergerusan unsur-unsur
bahasa akibat pengaruh moderenisasi, etika antroposentris yang sangat bersifat
instrumentalis, dan perkembangan ilmu pengetahuan, serta perubahan ekosistem.
Teori-teori tersebut tidak pula hanya dapat diterapkan dalam membahas isu
lingkungan berbentuk metafora ekosistem yang penah dilakukan oleh Haugen
referensi atau ranah sumber dipetasilangkan kepada alam itu sendiri seperti, green
houseeffect.
Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini dapat dirinci berikut ini:
1.4.1 Manfaat Teoritis
1. Diharapkan dapat menjadi salah satu bahan rujukan kajian bahasa Aceh
yang bergayut dengan ekologi atau ekosistem berikutnya.
2. Diharapkan menjadi sumbangsih untuk kepustakaan kajian ekolinguistik.
3. Diharapkan dapat memberi informasi tentang kajian metafora selanjutnya.
4. Diharapkan menjadi bahan masukan untuk kajian yang relevan berikutnya.
5. Diharapkan dapat diteruskan oleh peneliti lanjutan.
1.4.2 Manfaat Praktis
1. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat Trumon agar
tetap menggunakan bahasanya yang metaforik dan menyayanginya.
2. Diharapkan dapat memopulerkan kembali bentuk metafora bahasa lokal
yang usang berkaitan dengan pelestarian lingkungan agar lebih dimengerti,
dipahami dan diminati oleh masyarakat tutur khususnya generasi muda
penerus kesinambungan bahasa, budaya dan lingkungan.
3. Diharapkan dapat merangsang dan mendorong masyarakat tutur bahasa
Aceh di Desa Trumon, khususnya generasi muda untuk tetap menggali
kekayaan ungkapan-ungkapan metafora dan memahami makna-makna
kiasan penuntun hidup sebagai khazanah kearifan budaya lokal.
4. Diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk kurikulum muatan lokal
5. Penggalian pemahaman dan pemberdayaan khazanah kebahasaan bahasa
dan budaya.
6. Diharapkan dapat memberikan fakta historis yang informatif bagi
pengembangan dan pemulihan pelestarian lingkungan dalam pemanfaatan
dan pengembangan sumber daya kepariwisataan yang sekaligus akan
menopang pertumbuhan ekonomi masyarakat.
1.5 Definisi Istilah
Beberapa istilah ataupun terminologi yang digunakan dalam penelitian ini,
dibicarakan satu persatu berikut ini:
a. Ekolinguistik adalah kajian yang menyandingkan kajian linguistik
dengan ekologis. Kajian ini dapat pula didefinisikan sebagai
sebuah kajian interaksi antara bahasa-bahasa dan lingkungannya
atau lingkungan tempat keberadaan bahasa itu digunakan, periksa
Haugen (1972:323).
b. Parameter ekolinguistik menggambarkan dimensi keterkaitan
antara bahasa dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial
masyarakat atau masyarakat tutur, entitas yang biotik dan yang
abiotik, periksa Fill dan Muhlhausler (2001:1).
c. Parameter keterhubungan atau parameter kesalingterhubungan
(interrelationship) antara bahasa dengan kajian linguistiknya dan
lingkungan dengan kajian ekologi merupakan gambaran tentang
hubungan timbal balik antara makhluk di lingkungan alam tersebut
yang bernuansa isu lingkungan dikodekan ke dalam bahasa dalam
jangkauan yang luas. Lihat Fill dan Muhlhausler (2001:1).
d. Parameter keberagaman (diversity), keberagaman yang ada di
lingkungannya yaitu perbendaharan kosa kata sebuah bahasa
terpancar dari lingkungan fisik dan lingkungan sosial atau
lingkungan budaya tempat bahasa itu berada dan digunakan.
Lingkungan fisik dimaksud merupakan lingkungan alam, geografi
yang menyangkut topografi seperti, iklim, biota, curah hujan,
sedangkan lingkungan sosial dan lingkungan budaya berkaitan
dengan hubungan antara pikiran dan aspek kehidupan masyarakat
tersebut seperti agama, etika, politik, seni dan lain sebagainya,
periksa Fill dan Muhlhausler (2001:2).
e. Parameter lingkungan (environment) adalah parameter yang
menjelaskan adanya hubungan antara ekologi dengan spesies
hewan atau fauna dan tanaman atau flora, serta seluruh kandungan
mineral yang berada di lingkungan ekologi tersebut, termasuk pula
ke dalamnya lingkungan fisik dan lingkungan sosial atau
lingkungan budaya tempat sebuah bahasa berada dan digunakan.
f. Klasifikasi metafora; Metafora diklasifikasikan ke dalam beberapa
kategori, yaitu metafora berdasarkan tingkat konvensional,
metafora berdasarkan fungsi kognitif, atau berdasarkan
pengalaman tubuh dan panca-indera, berikutnya metafora
g. Dimensi ideologis (ideological dimension) yaitu hal yang berkaitan
dengan pikiran manusia dan pemahaman manusia tentang segala
sesuatu yang terekam dalam kognitif, mental, ideologi, dan sistem
psikis, periksa Lindo dan Jeppe (2000:10).
h. Dimensi sosiologis (sociological dimension) yaitu hal yang
berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat, termasuk ke
dalamnya adalah rasa saling mengenal, saling menyayangi, saling
membenci, lihat Lindo dan Jeppe (2000:10).
i. Dimensi biologis (biological dimensional) yaitu sesuatu hal yang
berkaitan dengan kehidupan biota alam dan segala sesuatu yang
terdapat dalam alam, termasuk ke dalamnya lingkungan alam dan
hidup berdampingan dengan spesies lain yaitu flora, fauna dan
lainnya (ecoregion), periksa Lindo dan Jeppe (2000:10).
j. Ranah sumber (source domain) yaitu pola acuan atau rujukan
dalam pembentukan metafora, periksa Kovecses (2006:117).
k. Ranah target (target domain) yaitu sasaran yang menjadikannya
sebagai metafora, periksa Kovecses (2006: 117).
l. Pemetaan atau pemetaan silang ranah (cross domain mapping),
yaitu transformasi dari ranah sumber kepada ranah target
dalam pembentukan metafora, periksa Kovecses (2006:117).
m. Pengalaman tubuh (bodily experience) atau pengalaman inderawi
juga yang dialami melalui inderawi manusia, periksa Kovecses
(2006: 118).
n. Hubungan ontologis, merupakan interelasi yang melibatkan entitas
dalam dua ranah dan hubungan epistimik, melibatkan hubungan
pengetahuan tentang kedua entitas tersebut, periksa Kovecses
(2006:128).
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
2.1 Kajian Ekolinguistik
Kajian ekolinguistik yang pada awal kemunculannya dinamakan sebagai
kajian ekologi bahasa merupakan paradigma baru yang berkaitan dengan
hubungan ekologi dan linguistik yang diprakarsai oleh Einar Haugen pada tahun
1970. Kajian ini menyandingkan kajian bahasa dengan ekologi yang dapat
didefinisikan sebagai sebuah kajian atas interaksi antara bahasa-bahasa dengan
lingkungannya atau lingkungan tempat keberadaan bahasa itu digunakan, periksa
Haugen (1972:323).
Pada hakikatnya Haugen berupaya menggunakan analogi dari ekologi dan
lingkungan dalam menciptakan metafora berupa metafora ekosistem yang
ditujukan untuk menjelaskan hubungan dan interaksi bermacam-macam bentuk
bahasa yang ada di dunia. Dalam bentuk metafora tersebut Haugen membuat
perbandingan antara ekologi dengan spesies hewan atau fauna dan tanaman atau
flora, serta seluruh kandungan mineral yang berada di lingkungan ekologi
tersebut. Haugen juga menjelaskan hubungan kelompok komunitas pengguna
bahasa dan lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan buatan,
lihat Muhlhausler (1995) dalam Fill dan Muhlhausler (2001:1). Selanjutnya Fill
dan Muhlhausler (2001:2) menjelaskan bahwa Haugen berupaya menciptakan
suatu studi ekologi dan bahasa dalam hubungannya dengan kognitif manusia pada
Peneliti bahasa pada umumnya banyak membicarakan
permasalahan-permasalahan bahasa yang berkaitan dengan fonologi, kaidah-kaidah bahasa dan
leksikon. Jarang sekali pembicaraan yang mengarah kepada ekologi bahasa,
padahal menurut Haugen (1972: 325), penelitian ekologi bahasa atau ekolinguistik
dapat merambah luas dan bekerja sama dengan antropologi, sosiologi, psikologi
dan ilmu politik. Hal ini disebabkan kajian ekolinguistik sejatinya merupakan
kajian interaksi antara bahasa apa saja dengan lingkungannya.
Definisi lingkungan di sini mencakup pikiran seseorang yang merujuk
kepada dunia nyata tempat bahasa itu digunakan karena lingkungan alam dari
sebuah bahasa adalah masyarakat pengguna bahasa tersebut. Selanjutnya Haugen
(1972: 326) menggambarkan bahwa bahasa sesungguhnya hanya ada di dalam
otak penggunanya dan hanya berfungsi menghubungkan penggunanya dengan
sesama dan kepada alam yaitu lingkungan sosial, lingkungan buatan dan
lingkungan alam.
Fill dan Muhlhausler (2001:57) berpendapat bahwa ekolinguistik
melibatkan teori-teori, metodologi, dan studi empiris bahasa, serta berkontribusi
dalam perspektif semua level linguistik yang berkaitan atau berhubungan dengan
ekologi. Jangkauan ekolinguistik luas karena kajian ini dapat menentukan
beberapa disiplin ilmu bahasa, seperti:
a. Menemukan teori bahasa yang tepat.
b. Studi tentang sistem bahasa dan teks.
c. Studi keuniversalan bahasa yang relevan dengan isu-isu lingkungan.
e. Mempelajari bahasa yang berkaitan dengan ekoliterasi (ecoliteracy),
seperti pengajaran pemahaman ekologi kepada anak-anak dan orang
dewasa.
Cabang linguistik ini banyak menggunakan metafora ekosistem untuk
menjelaskan hubungan dan interaksi bermacam-macam bentuk bahasa yang ada di
dunia. Dalam bentuk metafora tersebut Haugen membuat perbandingan hubungan
antara ekologi dengan spesies hewan atau fauna dan tanaman atau flora, serta
seluruh kandungan mineral yang berada di lingkungan ekologi tersebut. Haugen
juga menjelaskan hubungan kelompok masyarakat pengguna bahasa-bahasa
dengan lingkungannya baik lingkungan alam maupun lingkungan buatan.
Muhlhausler (1995) dalam Fill dan Muhlhausler (2001:1), selanjutnya
menjelaskan bahwa Haugen berupaya menciptakan suatu studi ekologi dan bahasa
dalam interelasi dan interdependensi dengan kognitif manusia pada komunitas
yang multilingual.
Peneliti-peneliti dari Universitas Bielefelde di Jerman saat ini mulai
mengarahkan penelitian mereka ke kajian ekolinguistik. Ide mentransfer
konsep-konsep, prinsip-prisip, dan metode-metode, ekologi dan biologi kepada bahasa
berkembang pesat. Pieter Finke (1983, 1993, 1996) mentransformasikan
konsep-konsep ekosistem ke dalam sistem bahasa dan sistem kultural, seperti yang
dijelaskan oleh Fill dan Muhlhausler (2001:44-45). Ilmuwan ini mengkritik
leksikon yang digunakan industri agrikultur untuk kepentingan bisnis dan
perdagangan. Kata-kata seperti production replace, growing, dan giving yang
menjadi makna metafora yaitu pembunuhan (killing) dan pelenyapan (taking
away) yang terjadi.
Ruang kajian ekolinguistik menurut Haugen seperti yang dilaporkan oleh
Mbete (2009:11-12) memiliki keterkaitan dengan sepuluh ruang kaji linguistik
lainnya. Dalam penelitian ekolinguistik sejumlah subdisiplin linguistik dapat
disandingkan dengan satu atau lebih dari sepuluh ruang kaji tersebut. Kesepuluh
ruang kaji tersebut adalah, Sosiolinguistik, Dialektologi, Linguistik Historis
Komparatif, Linguistik Demografi, Dialinguistik, Filologi, Glotopolitik,
Linguistik Preskriptif, Tipologi Bahasa, dan Etnolinguistik termasuk pula
Antropolinguistik, atau Linguistik Kultural.
2.1.1 Hubungan Bahasa dan Ekologi
Sapir dalam Fill dan Muhlhausler (2001:2), pada tahun 1912 menulis
tentang bahasa dan lingkungan yang beranggapan bahwa lingkungan fisik
dari sebuah bahasa terdiri atas karakter geografi sebagai topografi dari sebuah
negara, berhubungan dengan iklim, termasuk pula ke dalamnya flora dan
fauna, curah hujan, serta sumber daya alam yang merupakan sumber
kehidupan dan sumber ekonomi manusia yang terekam secara verbal.
Sehingga, menurutnya kosa kata yang terdapat dalam bahasa-bahasa itu akan
berbeda satu sama lain bergantung pada sosiokultural dan lingkungan
(ecoregion) tempat bahasa itu digunakan. Perbedaan ini hanya bersangkut
paut dengan unsur-unsur leksikal dan tidak berakibat kepada kaidah atau
Vokabulari dari sebuah bahasa tidak hanya bergantung atau
dipengaruhi oleh lingkungan fisik bahasa tersebut, akan tetapi lingkungan
sosial masyarakat penuturnya juga sangat berperan dalam pembentukan
vokabulari sebuah bahasa. Lingkungan sosial dimaksud terdiri atas kekuatan
masyarakat yang membentuk kehidupan dan pikiran setiap individu seperti
agama, kepercayaan, etika, dan pemahaman tentang politik.
Berdasarkan klasifikasi dari ke dua lingkungan ini kelengkapan
vokabulari bahasa dapat mengindikasikan pengetahuan, minat, pekerjaan
serta pandangan hidup penuturnya dan tempat bahasa atau masyarakat tutur
tersebut berada. Penutur bahasa yang hidup di pegunungan akan memiliki
khasanah vokabulari yang lebih banyak berkaitan dengan lembah, ciri tanah,
jenis burung, jenis tumbuhan, kehidupan lebah, dan kehidupan satwa liar
yang ada di lingkungan tertentu (ecoregion). Sebagai contoh suku Noocka
Indian yang secara ekonomis hidupnya sangat bergantung kepada kekayaan
hutan memiliki vokabulari kelautan yang sangat minim. Demikian pula
penutur bahasa yang bermukim di pesisir pantai memiliki lebih banyak
khasanah vokabulari yang berkaitan dengan lingkungan kelautan, seperti
yang terjadi pada suku Paiute, Arizona. Mereka lebih banyak mengenal dan
menciptakan nama-nama ikan, ganggang, bunga karang, pasir dan semua
kandungan laut.
Contoh lain dapat pula dilihat pada bahasa Aceh yang digunakan oleh
masyarakat tutur di Desa Trumon yang menjadikan beras sebagai makanan
yang lebih banyak berkaitan dengan pade ‘padi’dan bu ‘nasi’, sebagai
contoh, eumping pade ‘padi sangrai yang ditumbuk’, bu kulah, bu phet, bu
leukat, bu leumak, bu kanji, bu kuneng, dan bu leugok.
Selanjutnya, Sapir beranggapan bahwa bahasa yang diucapkan oleh
seseorang sangat bergantung kepada pikiran dan tingkah laku orang tersebut
yang terefleksi kepada bentuk vokabulari yang dituturkannya. Anggapan ini
dikenal dengan hipotesis Sapir–Whorf yang diperkenalkan oleh Whorf
dalam tulisannya tahun 1956.
Secara biologis, pada umumnya manusia memiliki kemampuan sama
dalam kapasitas mempelajari bahasanya. Seperti yang diutarakan oleh
Halliday (2001:21-22) bahwa kemampuan ini sama halnya dengan
kemampuan manusia tersebut pada saat belajar berjalan serta belajar berdiri.
Kesemuanya ini tidak bergantung kepada tingkat intelegensia sesorang.
Secara ekologis sesungguhnya manusia adalah makhluk ekologis yang unik,
karena setiap orang mempunyai pengalaman yang berbeda antara satu dengan
lainnya walaupun berada dalam pola lingkungan yang sama dan bahasa yang
sama pula.
Pengalaman yang sifatnya personal ini senantiasa berhubungan
dengan lingkungannya. Lingkungan ini pula yang membentuk kultur manusia
tersebut dan juga membentuk pola penggunaan bahasa seseorang yang
seterusnya terekam dalam kognitif orang tersebut. Pandangan ini sejalan
dengan pandangan Heine (1997:3) bahwa bahasa merupakan produk interaksi
seseorang menciptakan tuturannya dan membangun kemampuan
linguistiknya dapat langsung tergambar dari pengalaman yang diperoleh dari
pengetahuan dan pengalaman tentang lingkungan dan mengaplikasikan
pengalaman tersebut dalam komunikasi yang spesifik dengan sesama.
Rekaman pengalaman yang paling dekat dan paling lekat adalah
tentang dunia nyata sekitar, baik yang bersifat kultural maupun yang bersifat
alamiah. Oleh karena itu, fungsi awal imajineri adalah menggambarkan
lingkungan di sekitar dengan menggunakan bahasa karena bahasa didasari
imajinari yang ada di otak dan pengalaman manusia (Palmer 1996:3 ; lihat
Mbete, 2010:7).
Pakar ekolinguistik, Haugen (1972:326) menggambarkan lingkungan
alam sebuah bahasa adalah masyarakat pengguna bahasa itu, dan bahasa
sesungguhnya hanya ada di dalam otak atau kognitif penuturnya yang hanya
berfungsi menghubungkan penutur dengan sesamanya, dan dengan alam
sekitar yaitu lingkungan sosial dan lingkungan alam. Makna lingkungan di
sini juga mencakup pikiran seseorang yang merujuk kepada dunia atau
wilayah tempat bahasa itu ada dan digunakan.
Lebih lanjut Haugen (1972:325) menyatakan bahwa hubungan bahasa
dengan ekologi pada dasarnya terjadi dalam dua bagian. Bagian pertama
adalah lingkungan psikologikal (psychological environment) yaitu pengaruh
lingkungan terhadap bahasa-bahasa dalam pikiran atau kognitif penutur
hubungan lingkungan dengan masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut
sebagai media komunikasi mereka.
Bahasa layaknya species yang hidup di lingkungan alam yang dapat
hidup dan berkembangbiak, dapat berubah dan dapat pula lenyap atau mati.
Jika bahasa itu digunakan oleh bertambah banyak penuturnya maka bahasa
itu akan tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Namun jika jumlah
penuturnya sedikit dan dominasi terus berkurang, dikhawatirkan bahasa itu
akan bergeser, berubah, lenyap atau berevolusi.
Mufwene (2004:146) berpendapat bahwa ini semua dapat terjadi
disebabkan oleh evolusi bahasa. Pakar ekolinguistik ini membedakan dua
jenis evolusi bahasa. Pertama, evolusi progresif yaitu perubahan yang
menuju ke arah perubahan yang berkembang pesat seperti bahasa Inggris
Amerika yang digunakan masyarakat tutur di benua Amerika bahkan di
pelbagai belahan dunia dewasa ini. Kedua, evolusi yang beranalogikan
kepada evolusi teori Darwin yang menganggap evolusi terjadi melalui proses
seleksi alam. Subtipe dari teori Darwin di mana spesis suatu populasi berasal
dari atau muncul berbeda dari lainnya. Walaupun bahasa tidak termasuk ke
dalam spesies biologi namun rentang umur bahasa dan linguistik
berhubungan satu sama lain sebagaimana hubungan dalam rumpun biologi.
Evolusi bahasa terjadi melalui seleksi alam dapat disebabkan oleh eksploitasi
lingkungan alam dan bencana alam, serta perkembangan teknologi. Evolusi
ini dapat dilihat pula pada idiolek dari individu penutur yang berbeda antara
Hasil penelitian Lucy (1996) tentang bahasa Yucatec Maya seperti
yang diungkap oleh Kovecses (2006:323) menghasilkan satu temuan bahwa
keberadaan bentuk plural dalam bahasa Yucatec sifatnya opsional dan
kadangkala hanya diberlakukan kepada benda-benda hidup. Pola bahasa ini
berkaitan dengan pola pikir penutur jati yang hanya peka kepada jumlah
entitas yang hidup dan tidak kepada yang mati. Hal ini juga terimbas kepada
cara pandang mereka kepada lingkungan pedesaan dalam kehidupan
sehari-hari masyarakat Yucatec.
Hasil penelitian Ashok Kelkar tentang bahasa Inggris suku Marathi
(1957), dibicarakan oleh Haugen (1972:335) bahwa bahasa Inggris yang
digunakan oleh suku Marathi sebagai media komunikasi tidak sama dengan
bahasa Inggris yang dituturkan oleh penutur asli. Masyarakat tutur di Marathi
tidak hanya mengadopsi sistem bunyi bahasa Marathi ke dalam bahasa
Inggris, lebih dari itu mereka juga mengaplikasikan sistem gramatikal bahasa
mereka sendiri ke dalam bahasa Inggris. Bentuk gramatikal tersebut sejatinya
tidak terdapat di dalam sistem bunyi dan kaidah bahasa Inggris, sehingga
amat sulit bagi penutur asli bahasa Inggris untuk mengerti dan memaknai isi
pembicaraan yang dituturkan oleh masyarakat tutur Inggris Marathi. Sistem
bunyi dan sistem gramatikal bahasa Inggris Marathi secara otomatis
menyesuaikan diri dengan sistem bunyi dan sistem gramatikal bahasa
Marathi, karena bahasa dan lingkungan tempat bahasa itu digunakan saling
2.1.2 Parameter Ekolinguistik
Untuk menggambarkan keterkaitan antara bahasa dan lingkungan
diperlukan adanya kajian interdisipliner yang menyandingkan kajian ekologi
dengan linguistik, seperti yang diungkap oleh Mbete (2011:1). Ekologi
merupakan ilmu yang menggeluti hubungan timbal balik antara
makhluk hidup dengan alam sekitarnya, termasuk pula menjelaskan
hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya yang tentu saja bergayut
dengan bahasa manusia itu.
Kajian interdisipliner yang awalnya diprakarsai oleh Einar Haugen
memadukan konsep ekologi dengan linguistik ini, pada awalnya mengkaji
metafora. Kajian ini menerapkan konsep dasar berupa parameter ekologi
bersatu padu dengan kajian linguistik kognitif, seperti yang dijelaskan oleh
Fill dan Muhlhausler (2001:1). Parameter ekologi dimaksud adalah
kesalingterhubungan (interrelationship), lingkungan (environment),
keberagaman (diversity), digunakan sebagaimana berlaku dalam analisis
wacana lingkungan, antropolinguistik pragmatik, semantik kognitif, dan
lainnya. Ketiga-tiga parameter ini akhirnya diaplikasikan ke dalam kajian
penelitian ekolinguistik. Ketiga-tiganya saling terkait erat dan saling
melengkapi. Ketiga-tiganya senantiasa diaplikasikan secara bersamaan dalam
penelitian ekolinguistik. Ketika kajian ekolinguistik membicarakan parameter
ekolinguistik pastilah ketiga terminologi, keberagaman (diversity),
kesalingterhubungan (interrelationship), dan lingkungan (environment),
2.1.2.1 Parameter Keberagaman (Diversity)
Fill dan Muhlhausler (2001:2) mengutarakan bahwa keberagaman
(diversity) perbendaharan kosa kata sebuah bahasa memancarkan
lingkungan fisik dan lingkungan sosial atau lingkungan budaya tempat
bahasa itu berada dan digunakan. Lingkungan fisik dimaksud merupakan
lingkungan alam, geografi yang menyangkut topografi seperti, iklim, biota,
curah hujan, sedangkan lingkungan kebudayaan berkaitan dengan
hubungan antara pikiran dan aspek kehidupan masyarakat tersebut seperti
agama, etika, politik, seni, dan lain sebagainya. Kelengkapan kosa kata
bahasa itu bergantung pula kepada cara pandang, sikap, dan perilaku serta
pekerjaan (profesi) masyarakat tutur bahasa tersebut.
Keberagaman jenis species fauna, flora di satu lingkungan alam
paralel dengan keberagaman vokabulari bahasa di dalam lingkungan sosial
masyarakat tutur tersebut demikian pula sebaliknya. Keberagaman biota ini
memperkaya khasanah vokabulari bahasa tersebut. Keberagaman juga
dapat ditujukan atau berimplikasi kepada hubungan antara ranah sumber
dan ranah target dalam sebuah metafora. Kepada sebuah ranah target dapat
diaplikasikan beberapa ranah target, demikian pula sebaliknya sebuah ranah
target dapat berasal dari beberapa ranah sumber.
2.1.2.2 Parameter Kesalingterhubungan (Interrelationship)
Keberadaan spesies dan kondisi kehidupan mereka tidak dapat
dipandang sebagai dua bagian terpisah, tetapi sebagai satu bagian yang
dicirikan secara individual. Hubungan paralel ini tidak berarti bahwa
bahasa dan spesies biologi sama dalam semua hal. Satu hal mutlak yang
dapat membedakan keduanya adalah bahwa bahasa bukanlah organisme
hidup. Bahasa ditranformasikan dan diwariskan dari satu generasi ke
generasi berikutnya oleh penutur bahasa dan penggunaannya. Berbeda
dengan spesies biologi yang diturunkan melalui perkawinan.
Eksistensi sebuah bahasa sangat bergatung kepada jumlah
penuturnya. Penamaan dan pengklasikasian nama tumbuhan dan hewan
serta jenis batu-batuan bergantung kepada konvensi penuturnya. Istilah
konvensi di sini tidak dapat diartikan sebagaimana lazimnya istilah
konvensi yang digunakan dalam linguistik yaitu istilah yang mengacu
kepada hubungan arbitrer antara bentuk atau lambang linguistik dengan
makna yang dikandungnya. Istilah konvensi ini dialamatkan kepada tingkat
kesepakatan penggunaan bahasa dalam komunitas bahasa tesebut.
Parameter keterhubungan atau parameter kesalingterhubungan
antara linguistik dengan ekologi merupakan hubungan timbal balik antara
makhluk di lingkungan alam tersebut dengan ekologinya yang dapat
terpantul pada metafora ekologi yang bernuansa isu lingkungan, dikodekan
ke dalam bahasa dalam jangkauan yang luas. Konsep metafora seperti yang
digambarkan oleh Kovecses (2006:171), berisikan skema sumber yang
dalam hal ini menyangkut ranah yang bersifat fisik dikodekan secara
verbal kepada ranah yang bersifat abstrak seperti, pada metafora green
Metafora ekologi menurut Fill dan Muhlhausler (2001:104), banyak
bergantung kepada sosiokultural dan unsur kognitif masyarakat tutur
bahasa tersebut. Waktu, situasi, dan ranah penggunaan bahasa juga
memengaruhi bentuk metafora bahasa tersebut. Keterhubungan antara
unsur-unsur ini jelas tergambar seperti yang terjadi pada awal abad
kesembilan belas, kebutuhan akan air sebagai bahan pokok kehidupan,
secara eksklusif disejajarkan dengan uang yang memunculkan metafora
seperti central money supply, ‘central water supply’, dan metafora water is
money, sangat popular saat itu. Dalam praksisnya metafora Inggris water is
money atau metafora bahasa Indonesia, air itu uang juga jelas
menggambarkan betapa sumber air (mineral) dieksploitasi dan bernilai
ekonomis tinggi, di antaranya juga merusak dan menggerus lingkungan.
Parameter keterhubungan antara bahasa dengan ekologi di Desa
Trumon terlihat adanya metafora POK-POK DRIEN. Pok-pok adalah
batang bambu yang dipotong panjangnya sekitar satu meter (2-3 ruas)
kemudian bambu tersebut dibelah dua. Bagian pangkal bambu diikat
dengan tali agar tidak mudah lepas dan salah satu belahan dipasang tali.
Media ini digantungkan pada pohon durian atau buah-buahan lainnya yang
sedang berbuah. Bila tali ditarik akan mengeluarkan suara gaduh. Fungsi
dari benda tersebut untuk mengusir binatang yang akan memakan
buah-buahan. Dalam pemaknaannya secara metaforis pok-pok dialamatkan
kepada orang yang banyak cakap dan mengumbar janji. Seperti dalam
2.1.2.3 Parameter Lingkungan (Environment)
Manusia berinterelasi, berinteraksi, bahkan berinterdependensi
dengan pelbagai entitas yang ada di lingkungan tertentu (ecoregion),
memberi nama dalam bahasa lokalnya, memahami sifat-sifat dan karakter
yang dikodekan secara verbal, semata-mata demi tujuan dan
kepentingan-kepentingan manusia (antroposentrisme) dan juga karena manusia adalah
makhluk ekologis yang memang tidak dapat tidak membutuhkan segala
yang ada demi hidupnya secara biologis (biosentrisme), baik hewan,
tumbuhan, bebatuan, maupun udara dan keluasan pandangan secara ragawi
(kosmosentrisme).
Berbagai cara manusia memengaruhi lingkungannya, sebagaimana
yang pernah dibicarakan sebelumnya. Sikap masyarakat terhadap
lingkungan alam banyak didasari oleh pola kultural masyarakat tersebut.
Sebagai contoh pandangan suatu masyarakat terhadap daging binatang
seperti lembu, babi, ayam, itik kambing sebagai makanan manusia
berkaitan dengan kebutuhan manusia.
Keberadaan binatang-binatang tersebut yang menyangkut dengan
perkembangbiakannya sangat diperhatikan oleh masyarakat yang ada dalam
lingkungan alam itu. Pada gilirannya sifat alamiah dari binatang itupun
menjadi bagian dari perhatian masyarakat dengan kata lain pengetahuan
lokal dan pengetahuan manusia tentang lingkungan alam telah berpengaruh
kepada pandangan hidup, kultur, bahasa dan kosmologi masyarakat yang
hewan dan tumbuhan secara nyata merupakan refleksi dari lingkungan
dengan keanekaragaman hayatinya tempat tinggal masyarakat tersebut.
Lingkungan alam dijadikan sebagai parameter membangun atau
memberi nama-nama tersebut dalam kurun waktu yang sangat panjang,
yang diturunkan secara berkesinambungan dari generasi sebelumnya ke
generasi berikutnya. Dari hasil penelitiannya Muhlhausler (2003:59)
mengemukakan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk pelabelan nama dapat
memakan waktu lebih kurang tiga ratus tahun lamanya untuk
menghubungkan sebuah bahasa dengan lingkungan biologis penuturnya.
Parameter lingkungan (environment) yang menjadi acuan pada
lingkungan alam di Desa Trumon dapat dilihat pada kehidupan siput yang
secara alamiah hidup dalam dua lingkungan alam yaitu lingkungan darat
dan lingkungan air. Dari kehidupan siput terbentuk sebuah metafora yaitu
ABO UDEP DUA PAT. Secara harfiah ungkapan ini mengandung makna
‘siput hidup pada dua tempat’, yaitu: abo ‘siput’, udep ‘hidup’, dua
‘dua’dan pat’ tempat’menjelaskan kehidupan siput yang dapat bertahan
hidup di dalam dua lingkungan alam yang benar-benar berbeda yaitu di
daratan dan di dalam air. Kehidupan siput seperti ini membentuk sebuah
metafora yang tertuju kepada sifat atau perilaku seseorang yang dapat
menyesuaikan diri di semua lingkungan sosial budaya dan semua kalangan
masyarakat.
Ketiga parameter ekologi yang diterapkan dalam kajian ekolingustik