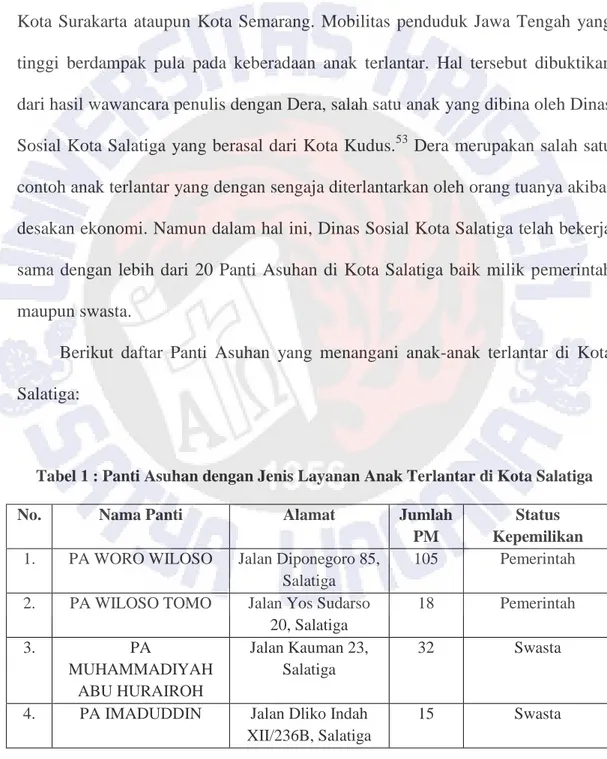BAB II
KERANGKA TEORI, HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
A. KERANGKA TEORI
Anak merupakan harta yang tak ternilai harganya baik dilihat dari perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum maupun perspektif keberlanjutan sebuah generasi keluarga suku dan bangsa.1 Sudah sewajarnya seorang anak mendapatkan bimbingan serta pendidikan terutama dari keluarganya sejak dini. Bimbingan serta pendidikan yang diberikan sejak dini didalam keluarga akan membentuk sifat dan kebiasaan baik yang akan tertanam oleh anak tersebut jika memang anak tersebut di didik dengan baik. Tidak seperti halnya anak yang tidak diinginkan kelahirannya yang pada umumnya keberadaan mereka rawan untuk diterlantarkan dan bahkan tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan perlakuan salah (child abuse). Sebagaimana mestinya, sebagai kelompok anak rawan (children in need of special protection), anak terlantar bukan saja belum terpenuhi hak-hak dasar mereka, bahkan acap kali dilangggar, karena cara pandang yang tanpa sadar berbias pada kepentingan orang dewasa.2 Seorang anak yang sudah mendapatkan tindakan penelantaran harus mendapatkan perlindungan dalam segala bentuk, termasuk pula di dalamnya perlindungan dalam bentuk rehabilitasi sosial. Seperti
1 Imam Sukadi, Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak, De Jure, Jurnal Syariah dan
Hukum, Vol. 5 No. 2, Desember 2013, h. 118.
2 Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, Penerbit Kencana
halnya dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 pada Pasal 34 Ayat (1) telah ditegaskan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”.
1. Pengertian Anak
Dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia, tidak terdapat pengaturan yang tegas tentang kriteria anak.3 Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat dan hukum Islam.4 Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.5
Ditinjau dari aspek yuridis, pengertian “anak” dimata hukum positif Indonesia (ius constitutum/ius operatum) lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (minderjarig/person under age), orang yang dibawah umur/keadaan di bawah umur (minderjarigheid/inferiority) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (minderjarig ondervoodij).6 Anak merupakan seorang yang belum dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Seorang anak juga belum mencapai usia kematangan baik dalam berpikir
3 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung, 2010, h. 31.
4 Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2012, h. 33.
5 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 6 Lilik Mulyadi, Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia, Penerbit PT Alumni,
maupun bertindak. Setidaknya seorang anak harus mendapatkan pendidikan yang baik, baik formal maupun informal yang umumnya dipenuhi oleh keluarganya. Di Indonesia terdapat beberapa pengaturan yang memberikan pengertian mengenai anak.
Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan pengertian anak berdasarkan Pasal 1 Angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa, “batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”7
Pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak-Hak Anak), mendefinisikan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan Undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.8 Berdasarkan Pasal 330 KUH Perdata yang dikatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.
7 Ibid., h. 14. 8
Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa menarik batas antara belum dewasa dengan sudah dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya walaupun ia belum berwewenang kawin.9 Dari beberapa definisi anak yang telah disebutkan, menurut Mahadi mencantumkan status perkawinan sebagai satu tanda kedewasaan tidaklah tepat, karena status perkawinan seseorang belum tentu menjadikan seseorang menjadi dewasa.10 Faktor penting yang menentukan seseorang menjadi dewasa apabila seseorang telah berdiri sendiri, bertindak dalam segala hal dan telah menjadi tuan rumah sendiri walaupun orang tersebut belum kawin.11 Perilaku anak yang sangat rentan dalam bertindak terlebih dalam usianya yang masih dapat dikatakan belum stabil, jika tidak mendapatkan perhatian baik dari keluarga, maupun masyarakat sekitar dapat menjerumuskan anak ke perbuatan delinquency baik dalam bentuk penyalahgunaan obat-obatan, free sex, dan lain sebagainya. Moral seorang anak harus diberikan kearah yang tertuju, sebab jika moral seorang anak ditanamkan dengan baik, anak tersebut akan mengalami tumbuh, dan kembang yang baik. Karena, prinsip-prinsip moral adalah tingkah laku manusia, biasanya prinsip moral tersebut ditangkap manusia dalam
9 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung, 2010, h. 32.
10 Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2012, h. 34.
11
lingkungan hidupnya sendiri dan sejak semula dianggap sebagai suatu keharusan.12
2. Perlindungan Anak
Perlindungan hukum secara umum merupakan perlindungan yang dilihat dari sisi hukum yang diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat tak terkecuali seorang anak. Dalam hal ini seorang anak sangat memerlukannya, dimana anak merupakan seseorang yang belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Mendapatkan sebuah perlindungan juga merupakan sebuah hak yang diterima oleh seseorang tak terkecuali seorang anak. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan fisik dan mentalnya.13 Terutama semakin pesatnya perkembangan teknologi dan informasi serta adanya arus globalisasi yang memberikan perubahan dari cara hidup hingga gaya dalam berpenampilan akan sangat berpengaruh pada pembentukan karakter seorang anak.
Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.14 Bukan berarti diberikannya perlindungan anak justru memberikan batasan-batasan
12 Agus Santoso, Hukum, Moral dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Penerbit
Prenada Media Grup, Jakarta, 2012, h. 84.
13 Ibid., h. 32.
14 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Penerbit PT Refika Aditama, Jakarta, 2010, h. 33.
kepada seorang secara berlebihan. Karena jika perlindungan diberikan secara berlebihan akan memberikan dampak berhentinya seorang anak untuk berkreativitas dan tidak akan berpikiran secara maju dan dewasa karena seringnya bergantung dengan orang lain. Perlindungan yang diberikan secara wajar akan melatih seorang anak untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan hak-haknya.
Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (child abused), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya.15
Berdasarkan hasil seminar perlindungan anak/remaja oleh Prayuana Pusat tanggal 30 Mei 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak yaitu:16
“Pertama, segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
15 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Penerbit PT
Refika Aditama, Bandung, 2018, h. 4.
16
Kedua, segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah nikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.”
Dalam hal ini, yang berperan utama dalam melakukan perlindungan anak adalah keluarga. Dimana keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga (Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum). Keluarga dianggap yang paling memahami karakter, perilaku dan sifat anak tersebut. Disamping itu terdapat pula peran pendukung dari masyarakat dan pemerintah dalam memberikan perlindungan. Untuk itu, kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek.17 Aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak.18 Aspek kedua, menyangkut pelaksanaan kebijakan peraturan-peraturan tersebut.19 Kedua aspek tersebut harus berjalan dengan seimbang yaitu antara peraturan yang mengaturnya dan pelaksanaan atas peraturan yang telah dibetuk dan dibuat. Perlindungan anak yang tercapai dapat memberikan kesiapan bagi anak tersebut, dalam arti anak tersebut dapat
17
Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 3.
18 Ibid. 19
mempersiapkan dirinya dengan baik untuk melanjutkan masa depan sebagai penerus bangsa.
Namun perlindungan kepada seorang anak memiliki dasar dalam pelaksanaannya, yaitu:20
a. Dasar Filosofis: Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
b. Dasar Etis: pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
c. Dasar Yuridis: pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.
Pelaksanaan perlindungan anak, harus memenuhi syarat antara lain: merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak; harus mempunyai landasan filsafat, etika, dan hukum; secara rasional positif; dapat dipertanggungjawabkan; bermanfaat untuk yang bersangkutan; mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur, bukan perspektif kepentingan yang mengatur;
20 Maiding Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung, 2010, h. 37.
tidak bersifat aksidental dan komplimenter, tetapi harus dilakukan secara konsisten, mempunyai rencana operasional, memperhatikan unsur-unsur manajemen; melaksanakan respons keadilan yang restoratif (bersifat pemulihan); tidak merupakan wadah dan kesempatan orang mencari keuntungan pribadi/kelompok; anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai situasi dan kondisinya; berdasarkan citra yang tepat mengenai anak manusia; berwawasan permasalahan (problem oriented) dan bukan berwawasan target; tidak merupakan faktor kriminogen; tidak merupakan faktor viktimogen.21
Adapula prinsip-prinsip perlindungan anak:22 a. Anak tidak dapat berjuang sendiri;
Anak tidak dapat berjuang sendiri termasuk dalam melindungi dan memperjuangkan hak-haknya, karena banyak pihak-pihak yang tentunya mempengaruhi kehidupannya. Pihak-pihak tersebut pada umumnya adalah keluarga, pemerintah dan masyarakat.
b. Kepentingan terbaik anak (the best interest of child);
Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan anak harus dipandang sebagai of paramount importence (memperoleh prioritas tinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak.
c. Ancangan daur kehidupan (life-circle approach);
21 Ibid., h. 37.
22
Perlindungan kepada seorang anak harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Sejak didalam kandungan pun, seorang janin telah diakui keberadaannya sebagai seorang anak sehingga perlindungan harus dilaksanakan hingga seorang anak dapat disebut sebagai seorang yang dewasa.
d. Lintas sektoral.
Perlindungan anak tidak hanya berasalkan dari faktor intern saja, namun juga terdapat faktor eksternal bahkan faktor mikro dan makronya. Infrastruktur kota, kualitas pendidikan, angka kemiskinan dan keadaan yang ada disekitar lingkungan akan berpengaruh dalam pelaksanaan perlindungan anak.
Menurut Anthony M. Platt prinsip dari perlindungan terhadap anak:
a. Anak harus dipisahkan dari pengaruh kerusakan dari penjahat dewasa; b. Anak nakal harus dijauhkan dari lingkungannya yang kurang baik dan diberi perlindungan yang baik. Anak harus dijaga dengan paduan cinta dan bimbingan;
c. Perbuatan anak nakal harus diupayakan untuk tidak dihukum, kalaupun dihukum harus dengan anacaman hukuman yang minimal dan bahkan penyidikan tidak diperlukan karena terhadap anak harus diperbaiki bukan dihukum;
d. Terhadap anak nakal tidak ditentukan hukuman baginya, karena menjadi narapidana akan membuat perjalanan hidupnya sebagai mantan orang hukuman;
e. Hukuman terhadap anak hanya dijalankan jika tidak ada lagi cara lain yang lebih baik dijalankan;
f. Penjara terhadap anak dihindarkan dari bentuk penderitaan fisik yang buruk;
g. Program perbaikan yang dilakukan lebih bersifat keagamaan, pendidikan, pekerjaan, tidak melebihi pendidikan dasar;
h. Terhadap narapidana anak diberi pengajaran yang lebih baik menguntungkan dan terarah pada keadaan dunia luar.
Disamping itu pula, dalam pelaksanaan perlindungan anak diperlukan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu:23
a. Luas lingkup perlindungan:
1) Perlindungan yang pokok meliputi antara lain: sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum.
2) Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.
3) Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
b. Jaminan Pelaksanaan Perlindungan:
1) Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap perlaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
23 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Penerbit Akedemi Pressindo, Jakarta, 1989,
2) Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
3) Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).
3. Hak-Hak Anak
Meskipun seorang anak merupakan seseorang yang belum cakap dalam perbuatan hukum, seorang anak tetap memiliki hak-hak. Karena pada dasarnya, hak-hak anak adalah berbagai kebutuhan dasar yang seharusnya diperoleh anak untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan dari segala bentuk perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak, baik yang mencakup hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya anak.24 Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa asas atau prinsip Konvensi Hak-Hak Anak, meliputi sebagai berikut:25
a. Non diskriminasi
Yang dimaksud adalah tidak adanya pembedaan perlakuan terhadap seorang anak tanpa terkecuali.
24
Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, Dasar Perlindungan Anak, Penerbit Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, h. 4.
25 R. Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Penerbit Sinar Grafika,
b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
Yang dimaksud adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.26
c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
Yang dimaksud adalah adanya hak asasi bagi seorang anak yang harus dilindungi baik itu oleh keluarga, masyarakat, maupun pemerintah.27 d. Penghargaan terhadap pendapat anak
Yang dimaksud adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.28
UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai hak-hak anak yang terdapat dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 yang diantaranya berbunyi:
a. Setiap anak berhak untuk mendapatkan hidup, tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan tanpa adanya diskriminasi dan tindak kekerasan;
26 Penjelasan Pasal 2 huruf b UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 27 Penjelasan Pasal 2 huruf c UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 28
b. Setiap anak berhak untuk mendapatkan status kewarganegaraan, beribadah menurut agamanya, berpendapat, berekspresi dalam bimbingan kedua orang tuanya;
c. Setiap anak berhak mendapat pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan baik fisik, mental, spiritual dan sosial;
d. Setiap anak berhak mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan;
e. Setiap anak berhak mendapatkan pengasuhan dari orang tuanya dan memperoleh perlindungan dari sasarn penganiayaan, dan penyiksaan; f. Setiap anak berhak memndapatkan bantuan hukum baik anak yang
menjadi korban maupun pelaku tindak pidana.
Selanjutnya berdasarkan Pasal 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan beberapa hak anak:
a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlidungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.
Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of Child) Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 44/25 tanggal 20 November 1989 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus, menyebutkan 4 kategori hak-hak anak, sebagai berikut:29
a. Hak terhadap kelangsungan hidup (survival rights), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (the rights of life) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dari perawatan yang sebaik-baiknya (the rights to be the highest standard of health and medical altainable);
b. Hak terhadap perlindungan (protection rights), yaitu hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi;
c. Hak untuk tumbuh kembang (development rights), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar
29 R. Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Penerbit Sinar Grafika,
hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak;
d. Hak untuk berpartisipasi (participation rights), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (the rights of a child to express her/his views in all matters affecting that child).
4. Pengertian, Ciri-Ciri Dan Faktor Anak Terlantar a. Pengertian Anak Terlantar
Pada umumnya, anak yang digolongkan sebagai anak terlantar merupakan anak yang mengalami kemiskinan dalam kehidupannya dan hidupnya sudah pasti tidak terjamin. Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.30 Anak terlantar dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) juga disebutkan bahwa anak yang tidak terpelihara, tidak terawat, tidak terurus dan serba tidak berkecukupan. Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 6, anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
30 Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, Penerbit Prenada Media Group, Jakarta, 2010,
Sedangkan dalam UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, anak terlantar didefinisikan sebagai anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Sosial RI No. 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dikatakan bahwa anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 tahun sampai dengan 18 tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
Anak terlantar merupakan seseorang yang sewajarnya mendapatkan perhatian baik dari masyarakat maupun dari pemerintah. Di Kota Salatiga sendiri telah menetapkan Peraturan Daerah mengenai definisi anak terlantar. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 12 Tahun 2018 tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) telah menyebutkan bahwa anak terlantar adalah seorang anak yang berusia 5 sampai 18 tahun yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga. Selanjutnya Pasal 1 Angka 13 Peraturan Walikota Salatiga No. 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Terlantar di Luar Panti juga menyebutkan pengertian anak terlantar yaitu anak yang tidak terpenuhi
kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial termasuk anak berusia bawah lima tahun.
b. Ciri Anak Terlantar
Ciri anak terlantar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 12 Tahun 2018 tentang PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial), sebagai berikut:
1) Berasal dari keluarga fakir miskin
2) Anak yang mengalami perlakuan salah (kekerasan dalam rumah tangga)
3) Diterlantarkan oleh orang tua/keluarga; atau 4) Anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga
5) Anak yang tidak pernah sekolah atau tidak sekolah lagi dan tidak tamat SMP
6) Makan makanan pokok kurang dari 2 kali sehari 7) Memiliki pakaian kurang dari 4 stel layak pakai 8) Bila sakit tidak diobati
9) Yatim, piatu, yatim piatu
10) Tinggal bersama dengan bukan orang tua kandung yang miskin 11) Anak yang berusia kurang dari 18 tahun dan bekerja.
Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 80/HUK/2010 tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Perlayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan
Daerah Kabupaten/Kota, Bab I, terdapat beberapa ciri-ciri anak terlantar yaitu:31
1) Anak berusia 5-18 tahun;
2) kewajibannya karena beberapa kemungkinan seperti miskin atau tidak mampu; Orang tuanya tidak dapat melakukan
3) Salah seorang dari orang tuanya atau keduanya sakit; 4) Salah seorang atau kedua orang tuanya meninggal dunia; 5) Keluarga tidak harmonis;
6) Tidak ada pengasuh atau pengampu;
7) Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani dan sosial.
Dari beberapa pemaparan ciri anak terlantar diatas, ciri anak terlantar menurut penulis yaitu:
1) Anak berusia 5-18 tahun;
2) Mendapatkan perlakuan penelantaran baik disengaja maupun tidak;
3) Tidak mendapatkan pendidikan secara baik, baik itu bersifat informal maupun formal;
4) Haknya tidak terpenuhi secara utuh;
5) Tidak memiliki orang tua atau wali yang jelas. c. Faktor Anak Terlantar
31 Andy Resky Firadika, Penanganan Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial Berdasarkan Pasal 34 UUD Tahun 1945, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017), h. 17.
Beberapa faktor anak terlantar:
1) Orang Tua Anak Yang Melepaskan Tanggung Jawab
Orang tua memiliki tanggung jawab penuh untuk mengurus, mendidik dan memenuhi kebutuhan anak. Sesekali orang tua melepaskan tanggung jawabnya, atau lalai terhadap tanggung jawabnya, maka dampak yang besar akan berpengaruh pada tumbuh kembang seorang anak. Melepaskan tanggung jawab dalam hal ini dapat dilihat dari berbagai sisi. Diantaranya; kesibukan orang tua saat bekerja; tidak sadarnya orang tua terhadap pentingnya pendidikan, dan broken home.
Kesibukan orang tua yang bekerja dapat mengakibatkan anak secara tidak disadari terjerumus dalam keadaan yang tidak baik. Lalainya orang tua dalam hal ini juga akan berpengaruh pada pendidikan anak yang akan terabaikan. Seorang anak yang waktunya banyak ditinggalkan oleh orang tuanya akan memberikan batasan untuk berinteraksi dikedua belah pihak, sehingga perhatian dari orang tua terhadap anak otomatis akan berkurang. Kebanyakan anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya dalam waktu yang lama biasanya tidak akan peduli lagi dengan orang tuanya. Disamping itu pula, ketidakharmonisan keluarga yang diawali dengan pertengkaran dan dilanjutkan dengan hubungan keluarga yang tidak harmonis, hingga terjadi perceraian akan berdampak pula bagi tumbuh dan kembang
seorang anak. Dengan berbagai latar belakang dan masalah apapun yang menjadi penyebab broken home, anak akan selalu menjadi pihak yang dirugikan.
2) Kondisi Perekonomian Yang Cenderung Lemah
Faktor ekonomi yang lemah dalam sebuah keluarga merupakan salah satu faktor yang dominan dari keterlantaran seorang anak. Perekonomian yang lemah, akan berujung pada kemiskinan dalam sebuah keluarga. Sehingga keluarga tidak mampu memenuhi kewajiban yang seharusnya kepada seorang anak.
3) Faktor Lingkungan (Ekstern) Yang Tidak Mendukung
Sekalipun faktor intern merupakan faktor yang sangat erat dalam tumbuh dan kembang seorang anak, faktor ekstern merupakan salah satu faktor pendorong tumbuh dan kembang anak. Hal tersebut terjadi karena lingkungan yang tidak mendukung dan memberi pengajaran akan nilai-nilai negative. Seperti contohnya, jika lingkungan dipenuhi oleh remaja-remaja yang banyak menghabiskan waktunya untuk mengkonsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang maka tumbuh kembang seorang anakpun dapat terpengaruhi.
4) Hamil Diluar Nikah
Faktor anak terlantar lainnya biasanya merupakan anak yang tidak diharapkan kelahirannya sejak awal yang di latar
belakangi oleh adanya seks bebas (hamil diluar nikah) sehingga tidak ada pertanggungjawaban dari orang tua anak tersebut. Anak tersebut dianggap sebagai aib dan seringkali disembunyikan keberadaannya. Pada tingkat yang ekstrem, perilaku penelantaran anak bisa berupa tindaan orang tua membuang anaknya, entah itu di hutan, di selokan, di tempat sampah, dan sebagainya baik ingin menutupi aib atau karena ketidasiapan orang tua untuk melahirkan dan memelihara anaknya secara wajar.32
5) Bencana Alam
Hadirnya bencana alam akan memberikan dampak yang luar biasa, diantaranya orang tua yang kehilangan anaknya, orang tua yang meninggal dunia dan anaknya menjadi yatim piatu, harta yang hilang secara keseluruhan, rumah yang rata dengan tanah dan lain sebagainya. Hadirnya bencana alam dalam kehidupan manusia tidak akan dapat diprediksi, maka dari itu bencana alam merupakan salah satu faktor anak terlantar.
5. Rehabilitasi Sosial
Rehabilitasi sosial merupakan salah satu cara dimana seseorang dapat memperbaiki kehidupan yang lebih baik. Adanya rehabilitasi sosial, khususnya terhadap seseorang dapat memberikan dan mengarahkan tujuan hidup orang
32 Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, Penerbit Prenada Media Group, Jakarta, 2010,
tersebut untuk lebih baik dengan harapan yang baik pula. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Rehabilitasi merupakan pemulihan kepada kedudukan (nama baik) yang semula perbaikan anggota tubuh yang cacat dan lainnya atas individu (misalnya korban kecelakaan atau korban bencana alam dan lain sebagainya) agar menjadi manusia yang berguna dan memiliki posisi di masyarakat.
Sedangkan menurut para ahli, diantaranya Renwick & Friefeld memberi pengertian bahwa rehabilitasi merupakan suatu kegiatan multidisipliner yang memulihkan kembali aspe-aspek fisik, emosi, kognisi, dan sosial sepanjang kehidupan individu sehingga bisa melakukan komunikasi, aktivitas harian, mobilitas, pekerjaan, hubungan sosial, dan kegiatan yang bermakna.
Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 12 Tahun 2018 tentang Penyandang Masalah Kesejateraan Sosial menyebutkan definisi yang sama mengenai rehabilitasi sosial sebagai turunan dari UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
Sifat responsif dapat diartikan sebagai melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan tidak oleh pejabat melainkan oleh rakyat. Responsif memberikan arti akan tanggapnya seseorang dengan masalah sekitarnya. Secara historis teori “hukum responsif merupakan tujuan utama penganut realisme hukum (legal realism) dan sociological jurisprudence. Nonet dan Selznick menjelaskan bahwa teori hukum ini menginginkan hukum menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan sosial, untuk mencapai tujuan ini mereka mendorong perluasan bidang lain yang memiliki keterkaitan secara hukum”.33 Teori hukum responsif berpendapat bahwa “hukum yang baik seharusnya memberikan suatu yang lebih daripada sekedar prosedur hukum. Hukum tersebut harus kompeten dan juga adil; ia seharusnya mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen terhadap tercapainya keadilan substantif.”34 Dalam hal ini adanya hukum responsif memberikan dorongan kepada sekitar untuk lebih beradaptasi yang selektif berkaitan dengan hal-hal yang esensial. Tidak hanya sekedar orang-perorangan saja, bagi suatu institusi yang responsif dapat memberikan pertahanan secara kuat hal-hal yang esensial bagi integritasnya sembari tetap memperhatikan keberadaan kekuatan-kekuatan baru di dalam lingkungannya.35
Untuk menerapkan hukum responsif dalam kehidupan sehari-hari akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Teori hukum responsif merupakan teori hukum yang memiliki pandangan yang kritis untuk mencapai suatu tujuan. Ciri
33 Luthfiyah Trini Hastuti, Studi Tentang Wacana Hukum Responsif Dalam Politik Hukum Nasional di Era Reformasi, (Surakarta: UNS, 2007), h. xi.
34 Philippe Nonet dan Philip Selznick, Hukum Responsif, Penerbit Nusamedia, Bandung,
2008, h. 84.
35
khas teori hukum responsif sendiri yaitu mencari nilai-nilai tersirat yang terkandung dalam peraturan dan kebijakan.36 Teori hukum responsif memberikan pengertian bahwa dengan adanya hukum dapat menjunjung tinggi semangat demokrasi terlebih di dalam masyarakat. Hukum tidak hanya rules (logic & rules), tetapi juga ada logika-logika yang lain. Bahwa memberlakukan jurisprudence saja tidak cukup, tetapi penegakan hukum harus diperkaya dengan ilmu-ilmu sosial.
Berkaitan dengan teori responsif, dalam hal ini manusia merupakan makhluk sosial dimana manusia membutuhkan orang lain. Di dalam lingkungan kehidupan, kehidupan manusia tidak semuanya dapat hidup dengan layak dan semestinya. Berkembangnya kehidupan manusia dari hari ke hari akan memberikan masalah-masalah baru yang akan timbul. Maka hal ini sangatlah tepat jika teori responsif dapat dikembangkan supaya masyarakat dapat peka dengan sekitarnya tidak melulu hanya pemerintah yang menjadi dominannya. Terutama perihal masalah-masalah sosial yang ada di dalam masyarakat. Salah satunya kehidupan yang tidak terjamin hak-haknya karena beberapa faktor. Yang seharusnya masyarakat peka akan keadaan ataupun situasi di sekitarnya.
Produk hukum responsif atau otonom ini merupakan karakter produk hukum yang mencerminkan pemenuhan atas aspirasi masyarakat, baik individu maupun berbagai kelompok sosial, sehingga secara relatif lebih mampu mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat.37 Dalam hal ini pula, lembaga peradilan dan peraturan huum berfungsi sebagai instrumen pelaksana bagi kehendak masyarakat, sedangkan rumusannya biasanya cukup diperinci sehingga tidak
36 Ibid., h. 90.
37 Henry Arianto, Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia, Universitas Esa
terlalu terbuka untuk ditafsirkan dan diinterpretasikan berdasarkan kehendak dan visi penguasa/pemerintah secara sewenang-wenang.38 Secara tidak sadar, Indonesia menempatkan posisi pemerintah sebagai pemegang kendali yang sangat dominan, sehingga potensi dan aspirasi masyarakat tidak teragregasi dengan baik. Philippe Nonet dan Philip Selznick menjabarkan bahwa ada tiga klasifikasi dasar dari hukum yang ada di masyarakat, sebagai berikut:39
a. Hukum sebagai pelayan kekuasaan represif (hukum represif);
b. Hukum sebagai institusi tersendiri yang mampu menjinakkan represi dan melindungi integritas dirinya (hukum otonom); dan
c. Hukum sebagai fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial (hukum responsif).
Diantara ketiga tipe hukum tersebut, Nonet dan Selznick memberikan argument bahwa hanya hukum responsif saja yang memberikan ketertiban bagi kelembagaan yang dapat memberikan dampak kestabilan dalam suatu masyarakat. Karena sifat responsif memberikan arti akan sebuah kepekaan untuk melayani akan kepentingan sosial oleh rakyat. Tipe hukum responsif mempunyai ciri yang meonjol, yakni:40
a. Pergeseran penekanan dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip dan tujuan;
b. Pentingnya watak kerakyatan (populis) baik sebagai tujuan hukum maupun cara untuk mencapainya.
38
Ibid.
39 Ibid., h. 118-119.
40 Sulaiman, Hukum Responsif: Hukum Sebagai Institusi Sosial Melayani Kebutuhan Sosial Dalam Masa Transisi, h. 6.
Tipe hukum responsif ini memberikan suatu tujuan yang seimbang di dalam hukum. Karena tipe hukum responsif yang dicita-citakan menuntut suatu penafsiran yang lebih luwes yang melihat aturan hukum sebagai terikat kepada problem dan konteks khusus.41 Seperti diungkapkan oleh Edwin M. Schur, sekalipun hukum itu Nampak sebagai perangkat norma-norma hukum, tetapi hukum merupakan hasil dari proses sosial, sebab hukum dibuat dan dirubah oleh usaha manusia dan hukum itu senantiasa berada di dalam keadaan yang berubah pula.42 Setidaknya adanya hukum dapat memudahkan masyarakat untuk lebih leluasa dalam menyatakan.
7. Teori Peran dan Teori Kewenangan a. Teori Peran
Peran adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perikelakuan, pada kedudukan-kedudukan tertentu didalam masyarakat, kedudukan mana dapat dipunyai pribadi ataupun kelompok-kelompok pribadi berperannya pemegang peranan tadi, dapat sesuai atau mungkin berlawanan dengan apa yang ditentukan di dalam kaidah-kaidah.43 Teori peran merupakan teori yang membahas mengenai seseorang dalam melakukan kegiatan sesuai posisi dalam struktur sosialnya. Teori peran juga berbicara mengenai posisi dan perilaku seseorang yang berhubungan juga dengan orang lain dalam
41 A. Mukthie Fadjar, Teori-Teori Hukum Konteporer, Penerbit Setara Press, Malang,
2013, h. 54.
42 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Penerbit Angkasa, Bandung, 1980. 43
Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Penerbit Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h.139.
menjalankan perannya. Peran yang ideal adalah peranan yang sesungguhnya dan perananan yang dikehendaki sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sedangkan peran yang dianggap diri sendiri merupakan peran yang mempertimbangkan antara kehendak hukum yang tertulis dengan kenyataan yang ada.
Peran dapat dijabarkan sebagai berikut:
1) Peran yang ideal yaitu peran yang dilaksanakan oleh individu atau kelompok sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapan;
2) Peran yang seharusnya yaitu peran yang memang seharushnya dijalankan oleh tiap individu atau kelompok sesuai dengan kedudukannya;
3) Peran yang dianggap diri sendiri yaitu peran yang dilaksanakan oleh diri sendiri karena kedudukannya dilakukan untuk kepentingannya;
4) Peran sebenarnya yaitu peran yang dimana individu mempunyai kedudukan dan benar telah menjalankan peran sesuai dengan kedudukannya.
b. Teori Kewenangan
Kewenangan menurut KBBI yaitu berasal dari kata wenang yang berarti hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Teori kewenangan berkaitan erat dengan kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan
bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata negara dan hukum administrasi. Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (macht). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintah mandate secara keseluruhan.44
Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh dari:45
1) Atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang;
2) Delegasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya;
3) Mandat, yaitu terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.
44 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Penerbit Rajagrafindo Persada, Jakarta,
2006, h. 101.
45
B. HASIL PENELITIAN
1. Gambaran dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Salatiga
Dinas Sosial Kota Salatiga terletak di Jl. Merak No.3, Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga. Dinas Sosial Kota Salatiga merupakan salah satu Dinas yang dibentuk sebagai wadah untuk memberikan pelayanan bagi seluruh masyarakat terutama masyarakat yang memiliki masalah berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Dinas Sosial Kota Salatiga berdiri sejak Tahun 2017 disahkan dengan Perwali Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial. Dinas Sosial adalah pecahan dari OPD lama yaitu Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang mengalami perubahan struktur OPD di tingkat Pemerintah
Kota Salatiga pada Tahun 2016.46 Dinas Sosial Kota Salatiga memiliki slogan “CERIA” Cermat, Ringkas dan Akurat.
Bergerak dibidang sosial, memberikan arti bahwa Dinas Sosial akan bersinggungan langsung dengan masyarakat. Maka dari itu peran Dinas Sosial sangat dibutuhkan, khusunya dalam hal ini adalah Dinas Sosial Kota Salatiga. Maka Dinas Sosial Kota Salatiga memiliki struktur organisasi yang akan memberikan dampak kemudahan dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya dalam melaksanakannya.
Berikut gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Salatiga:
Bagan 1 : Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Salatiga
46 http://dinsos.salatiga.go.id/tentang/, dikunjungi pada tanggal 1 Oktober 2019 pukul
Sumber: http://dinsos.salatiga.go.id/struktur-organisasi/
Dinas Sosial dikepalai oleh Kepala Dinas Sosial dan terbagi dalam bidang-bidang dimana bidang-bidang tersebut juga terbagi lagi ke dalam seksi-seksi. Adapun pembagian tugas dari struktur organisasi Dinas Sosial Kota Salatiga, sebagai berikut:
a. Dinas Sosial Kota Salatiga dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, yang memiliki tugas:
1) Merumuskan segala kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan program pelaksanaan tugas dan menyusun ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2) Mengkoordinasikan pelaksanaan program berpedoman supaya terjadi sinkronisasi dan sinergitas dalam melaksanakan tugas; 3) Melaksanakan adminitrasi Dinas melalui koreksi secara
berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku;
4) Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program secara berkala serta melakukan kerja sama Daerah sesuai dengan lingkup tugas Dinas yang berpedoman dengan ketentuan yang berlaku;
5) Melaporkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan pengendalian operasional kegiatan Dinas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
6) Mendelegasikan tugas kepada bawahan dan melaksanakan penilaian prestasi kepada bawahan sesuai dengan ketentuan sebagai cerminan kinerja bawahan.
b. Sekretariat dalam hal ini dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas, yang memiliki tugas;
1) Menyelenggarakan dukungan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Dinas serta administrasi kesekretariatan, keuangan, dan kepegawaian Dinas;
2) Mengkoordinasikan pelaksanaan dan perencanaan serta melaksanakan program dan kegiatan Bidang;
3) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Bidang yang berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan beserta upaya pemecahannya;
4) Menyelenggarakan pelayanan publik Sekretariat dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kerja sama Daerah sosial sesuai dengan lingkup tugas Dinas;
5) Menyelenggarakan administrasi Dinas sesuai ketentuan yang telah berlaku;
6) Menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan pengendalian operasional kegiatan Bidang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
c. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan dukungan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Dinas serta administrasi keuangan Dinas. d. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan
dukungan administrasi kesekretariatan termasuk dalam hal ini penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian Dinas.
e. Bidang Pemberdayaan Sosial, mempunyai tugas membantu Kepala
Dinas merumuskan, menyusun, mengoordinasikan,
menyelenggarakkan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan sosisal yang menjadi kewenangan Daerah. Bidang Pemberdayaan Sosial memiliki 3 (tiga) Seksi yang berada langsung dibawahnya, yaitu:
1) Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan dan Keluarga, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah bidang sosial sub urusan pemberdayaan sosial dilingkungan perorangan dan keluarga serta melaksanakan dan meningkatkan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah sesuai ketentuan yang berlaku; 2) Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial, mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang sosial sub urusan taman makam pahlawan dilingkup kepahlawanan dan restorasi sosial serta melakukan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional di Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3) Seksi Pemberdayaan Sosial dan Kelembagaan Masyarakat, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang sosial sub urusan pemberdayaan sosial dilingup kelembagaan masyarakat serta melaksanakan pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan
keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
f. Bidang Rehabilitasi Sosial, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang sosial sub urusan rehabilitasi sosial dan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan. Bidang Rehabilitasi Sosial memiliki 3 (tiga) Seksi yang berada dibawahnya, yaitu:
1) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang sosial sub urusan rehabilitasi sosial dilingkup penyandang cacat namun tidak termasuk melaksanakan rehabilitasi sosial pada bekas korban penyalahgunaan NAPZA, HIV/AIDS;
2) Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang sosial sub urusan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial dilingkup tuna sosial dan korban perdagangan orang namun tidak termasuk melaksanakan rehabilitasi sosial pada bekas korban penyalahgunaan NAPZA, HIV/AIDS serta melaksanakan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan ke daerah asalnya;
3) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Usia Lanjut, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang sosial sub urusan rehabilitasi dilingkup anak dan usia lanjut dan tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA, HIV/AIDS.
g. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah dibidang perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, pemeliharaan anak terlantar, pendataan dan pengelolaan fakir miskin serta melaksanakan penyelenggaraan pemulihan trauma bagi korban bencana.
1) Seksi Perlindungan Sosial Penanganan Korban Bencana, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjawa kewenangan Daerah bidang sosial sub urusan penanganan bencana. Termasuk didalamnya melaksanakan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana serta melakukan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsigaan bencana Daerah sesuai dengan prosedur dalam penanganan;
2) Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas Pengelolaan Data Fakir Miskin, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang sosial sub urusan perlindungan dan jaminan sosial dilingkup
identiikasi dan penguatan kapasitas pengelolaan data fakir miskin termasuk didalamnya melaksanakan pendataan dan pengelolaan data fair miskin sesuai dengan ketentuan;
3) Seksi Jaminan Sosial Keluarga, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang sosial sub urusan perlindungan dan jaminan sosial dilingkup keluarga termasuk didalamnya melaksanakan pemeliharaan anak terlantar sesuai dengan ketentuan.
Berdasarkan struktur Dinas Sosial Kota Salatiga diatas, Bidang Rehabilitasi Sosial merupakan bidang yang menangani PMKS untuk dilakukan rehabilitasi sosial. Namun, rehabilitasi sosial khususnya anak terlantar, ditangani oleh Seksi Tuna Sosial, dan Korban Perdagangan Orang. Dinas Sosial Kota Salatiga khususnya Bidang Rehabilitasi Sosial, Seksi Tuna Sosial, dan Korban Perdagangan Orang dalam melaksanakan tugasnya akan berkoordinasi dengan instansi-instansi lain yang berkaitan. Diantaranya Dinas Kesehatan, Satpol PP dan DP3A Kota Salatiga.
2. Pengertian, Fungsi, Tugas Dan Wewenang Dinas Sosial Kota Salatiga
a. Pengertian Dinas Sosial
Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi Dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang dimaksud dengan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan
daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Peraturan Walikota Salatiga No. 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial menyatakan bahwa Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial Kota Salatiga. Selanjutnya dalam Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan bahwa Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang sosial.
Dinas Sosial Kota Salatiga merupakan penyelenggara daerah di bidang sosial yang mengurus permasalahan sosial. Permasalahan sosial merupakan perbedaan antara harapan dan kenyataan atau sebagai kesenjangan antara situasi yang seharusnya.47 Masalah sosial yang berada di tengah masyarakat, penanganannya tidak semudah yang dipikirkan oleh masyarakat awam. Pada dasarnya, Dinas Sosial Kota Salatiga menangani berbagai permasalahan sosial yang pada umumnya disebut dengan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial).
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Suprianta selaku Pegawai Dinas Sosial Kota Salatiga selaku Bidang Rehabilitasi Sosial, Seksi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan orang mengatakan bahwa Dinas Sosial Kota Salatiga merupakan Dinas yang bergerak dibidang sosial yang
47https://id.wikipedia.org/wiki/Masalah_sosial dikunjungi pada 10 November 2019 pukul 01.30.
bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat terutama masyarakat yang memiliki masalah sosial.48
Dalam hal ini Kepala Dinas Sosial langsung bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Susunan organisasi dalam Dinas terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, subbagian dan seksi-seksi yang telah ditentukan sesuai dengan bagan struktur organisasi yang telah dijelaskan diatas.
b. Fungsi, Tugas dan Wewenang Dinas Sosial
Berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga menyebutkan bahwa Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf I mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi berdasarkan asas otonomi, dan tugas pembantuan.
Selanjutnya berdasarkan Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga, Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
1) Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
48 Wawancara dengan Bapak Suprianta di Kantor Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan
2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
4) Pelaksanaan dan pelayanan kesekretariatan Dinas; dan
5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Namun dari fungsi diatas, Dinas Sosial Kota Salatiga juga memiliki aturan tetap mengenai tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan pengorganisasian yang tertuang pada Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 12 Tahun 2018 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS dan Perwali Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial.
Selain menjelaskan mengenai PMKS itu sendiri, Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 12 Tahun 2018 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial mengatur pula tentang tugas dan wewenang Dinas Sosial. Sebagai pelaksana urusan pemerintah di daerah Dinas Sosial Kota Salatiga memiliki tugas menyusun rencana, strategi, mekanisme, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penanganan PMKS sebagai bagian dari penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Salah tugas dan fungsi dari Dinas Sosial sendiri adalah penanganan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial). Berdasarkan Pasal 1 Angka 14 Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 12 Tahun 2018 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani maupun sosial. PMKS dalam hal ini tidak hanya dirasakan oleh orang dewasa saja, melainkan juga seorang anak akibat beberapa faktor. Begitupula dalam aturan yang sama, dijelaskan bahwa pendataan dan pemutakhiran serta pengelolaan data PMKS dan PSKS dilakukan oleh Dinas Sosial.
Selanjutnya dalam Pasal 11 Ayat (3), Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:
1) Penyusunan perencanaan penyelenggaraan penanganan PMKS; Dalam penyusunan penyelenggaraan penanganan PMKS, Dinas Sosial Kota Salatiga membedakan cara penanganannya terhadap macam PMKS. Karena PMKS dapat dibedakan berdasarkan kriteria PMKS yang ada di tengah masyarakat.
2) Pengalokasian anggaran untuk penanganan PMKS dalam APBD;
Dalam hal ini PMKS merupakan masalah sosial yang ditiap harinya tidak dapat diperkirakan. Dinas Sosial Kota Salatiga
dalam menyelenggarakan fungsi dan wewenangnya mengalokasikan anggaran seluruhnya demi penanganan PMKS di Kota Salatiga tidak terkecuali bagi PMKS khususnya anak terlantar.
3) Penyelenggaraan penanganan PMKS di Daerah;
Dinas Sosial Kota Salatiga melakukan penanganan PMKS hanya di wilayah Kota Salatiga. Namun berkaitan dengan wilayah Kota Salatiga yang strategis dan mobilitas masyarakat yang tinggi, terdapat banyak PMKS yang ada di Kota Salatiga namun tidak asli penduduk Salatiga. Oleh karena itu, Dinas Sosial Kota Salatiga bekerja sama dengan Dinas setempat yang berkaitan langsung dengan PMKS yang bersangkutan. Koordinasi dengan Dinas di daerah lain memang seharusnya harus berjalan. Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Walikota Salatiga No. 28 Tahun 2018.
4) Pelaksaaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penanganan PMKS di Daerah.
Monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan PMKS di daerah Kota Salatiga telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Salatiga. Hal tersebut dilakukan ditiap harinya, seperti hal monitoring langsung dilakukan dilapangan oleh pihak Dinas Sosial Kota Salatiga sebagai kegiatan untuk memantau keadaan wilayah Kota Salatiga akan PMKS yang ada. Evaluasi dilakukan
ditiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Salatiga sebagai penanganan PMKS.
Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Sosial, berwenang untuk (Pasal 12 Ayat 1):
1) Menetapkan kebijakan penanganan PMKS skala Daerah dengan mengacu pada kebijakan provinsi dan nasional;
2) Menyelenggarakan kerja sama bidang sosial skala Daerah; 3) Mengoordinasikan penanganan PMKS skala Daerah;
4) Memberikan bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi dan fasilitasi penanganan PMKS skala Daerah;
5) Mengembangkan dan pemberdayaan penggunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial untuk penanganan PMKS skala Daerah;
6) Menjalin kerja sama penanganan PMKS antar kabupaten/kota; 7) Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan penanganan PMKS
skala Daerah;
8) Menyediakan sarana dan prasarana penanganan PMKS skala Daerah;
9) Mengembangkan jaringan sistem informasi penanganan PMKS skala Daerah;
10) Menanggulangi bencana skala Daerah;
11) Memberikan izin pengumpulan uang atau barang untuk pendanaan penanganan PMKS skala Daerah;
12) Mengendalikan pengumpulan uang atau barang skala Daerah; dan
13) Melaksanakan dan mengembangkan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar, yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala Daerah.
Dalam melaksanakan wewenangnya, Dinas Sosial Kota Salatiga juga melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam bentuk rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Salatiga ditujukan pada PMKS yang mengalami kondisi ketelantaran, kemiskinan, kecacatan, keterpencilan, penyimpangan perilaku dan ketunaan sosial yang memerlukan perlindungan khusus.
3. Hak dan Kewajiban Dinas Sosial Kota Salatiga
Tidak hanya masyarakat yang berperan aktif dalam penanganan PMKS, namun Dinas Sosial pun ikut berperan aktif sebagai unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah bidang sosial. Berkaitan dengan masih adanya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya anak terlantar, Dinas Sosial Kota Salatiga memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan fungsi untuk penyelenggaraan di Bidang Rehabilitasi Sosial.
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Wahyu selaku Pegawai Dinas Sosial Kota Salatiga, Bidang Rehabilitasi Sosial, Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang, mengatakan bahwa Dinas Sosial Kota Salatiga
tidak memiliki hak secara langsung atas anak telantar, hanya saja Dinas Sosial Kota Salatiga berhak untuk melakukan tindakan sebagaimana dimaksud untuk pelayanan terhadap anak terlantar.49 Hak Dinas Sosial selain itu mendapatkan fasilitas berupa kendaraan untuk melakukan pelayanan terhadap anak terlantar (razia). Namun Dinas Sosial lebih banyak menjalankan kewajiban dalam penanganan anak terlantar, diantaranya:
a. Memonitoring dan mengawasi keadaan anak terlantar;
Monitoring dan mengawasi keadaan anak terlantar selalu dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Salatiga. monitoring bagi anak terlantar di dalam Panti Rehabilitasi atau Panti Sosial dilakukan dengan berkoordinasi langsung dari phak Panti Rehabilitasi atau Panti Sosial. Namun, pengawasan dan monitoring yang dilakukan pihak Dinas Sosial Kota Salatiga perihal anak terlantar diluar Panti Rehabilitasi atau Panti Sosial dilakukan dengan turun ke lapangan langsung di tiap harinya atau turun ke lapangan langsung jika ada informasi dari masyarakat sekitar/instansi terkait dengan keberadaan anak terlantar. b. Memberikan pembinaan, pelatihan dalam bentuk keterampilan;
Pembinaan, pelatihan dalam bentuk keterampilan merupakan salah satu langkah yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Salatiga dalam melakukan kewajibannya. Dengan adanya pelatihan dalam bentuk keterampilan akan memberikan bekal masa depan bagi anak terlantar supaya dapat hidup yang layak dan mandiri.
49 Wawancara dengan Bapak Wahyu di Kantor Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan
c. Dan menjalankan seluruh tugas pokok dan fungsi sesuai dengan aturan yang diberlakukan bagi Dinas Sosial.
4. Anak Terlantar Menurut Dinas Sosial Kota Salatiga
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suprianta selaku Pegawai Dinas Sosial Kota Salatiga bagian Rehabilitasi Sosial, seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang mengatakan bahwa anak terlantar adalah anak yang tidak mendapatkan penghidupan layak baik dari segi pendidikan, sandang, pangan dan papan bahkan hak-haknya tidak terjamin.50 Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya penelantaran terhadap anak, diantaranya kesengajaan orang tua yang menelantarkan anaknya akibat himpitan ekonomi. Menambahkan hasil wawancara dengan Bapak Wahyu selaku Pegawai Dinas Sosial Kota Salatiga, Bidang Rehabilitasi, seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang mengatakan bahwa anak terlantar biasanya sengaja diterlantarkan oleh orang tuanya atau sengaja menelantarkan diri akibat berbagai faktor.51 Menurut Dinas Sosial Kota Salatiga, faktor anak terlantar yaitu:
a. Minimnya standar perekonomian dalam sebuah keluarga. Hal tersebut merupakan faktor yang utama dalam kasus penelantaran anak;
b. Adanya seks bebas yang menyebabkan terjadinya kehamilan diluar nikah. Hal tersebut merupakan salah satu faktor penelantaran anak
50
Wawancara dengan Bapak Suprianta di Kantor Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Salatiga, 27 Maret 2019.
51 Wawancara dengan Bapak Wahyu di Kantor Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan
akibat kelahiran anak tersebut tidak diinginkan oleh kedua orang tuanya yang tidak bertanggung jawab dan hanya menjadi “aib” dalam sebuah keluarga;
c. Adanya keinginan dari anak itu sendiri karena faktor intern dari keluarga anak tersebut, seperti kurangnya perhatian dari keluarganya. Ciri-ciri anak terlantar menurut Dinas Sosial Kota Salatiga diantaranya:
a. Menggunakan baju yang tidak layak dan terlihat sangat kotor, baik dari kebersihan maupun baunya yang menyengat;
b. Fisik yang tidak terurus dan terlihat sangat kurus atau kekurangan gizi;
c. Jika ditanyai oleh masyarakat atau pihak lainnya, seperti tidak tahu arah dan tujuan dirinya akan pergi;
d. Tidak menempuh pendidikan selayaknya;
e. Sebagian besar waktunya hanya dihabiskan dijalanan dan tidak memiliki tempat tinggal yang menetap;
5. Ketentuan Rehabilitasi Sosial Pada Produk Peraturan Hukum Daerah Kota Salatiga
Di Kota Salatiga telah ditetapkan definisi mengenai rehabilitasi sosial yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 9 Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 12 Tahun 2018 tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Pasal 1 Angka 11 Peraturan Walikota Salatiga No. 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Terlantar di Luar Panti, yang
menyatakan bahwa rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suprianta Pegawai Dinas Sosial Kota Salatiga bagian Rehabilitasi Sosial, seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang, rehabilitasi sosial adalah membangun atau memperbaiki kembali yang sudah ada baik dari sisi moral, spiritual dan skill supaya ada jaminan bagi masa depan anak tersebut.52 Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan potensi diri yang ada pada anak untuk jaminan masa depan yang lebih baik.
Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Walikota Salatiga No. 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Terlantar di Luar Panti dijelaskan mengenai maksud adanya Rehabilitasi Sosial:
a. Rehabilitasi Sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
b. Pemulihan dan pengembangan ditujukan untuk mengembalikan keberfungsian secara fisik, mental dan sosial, serta memberikan dan meningkatkan keterampilan.
Selanjutnya Pasal 7 memberikan penjelasan mengenai tindakan Rehabilitasi Sosial yang dapat dilakukan dengan beberapa cara:
52 Wawancara dengan Suprianta di Kantor Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan