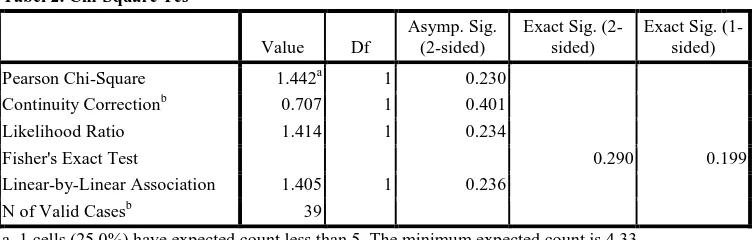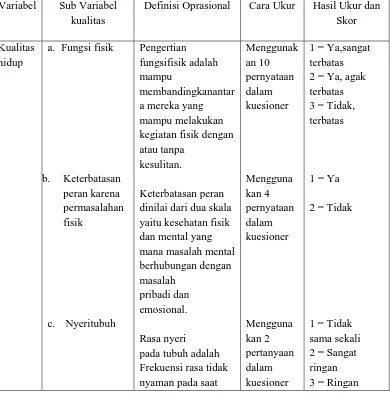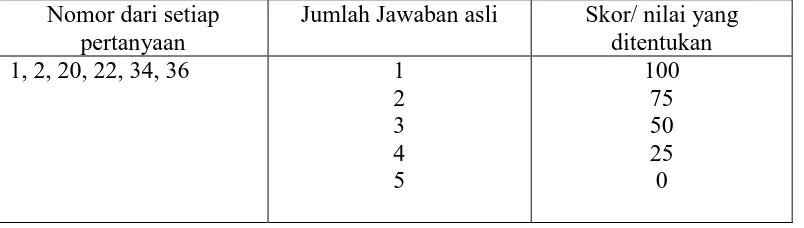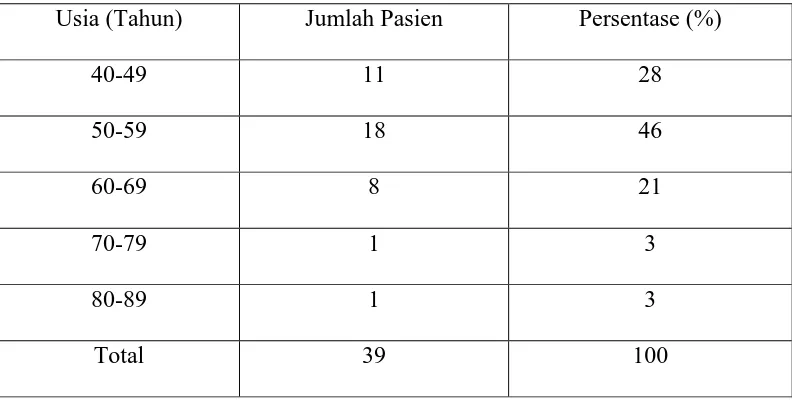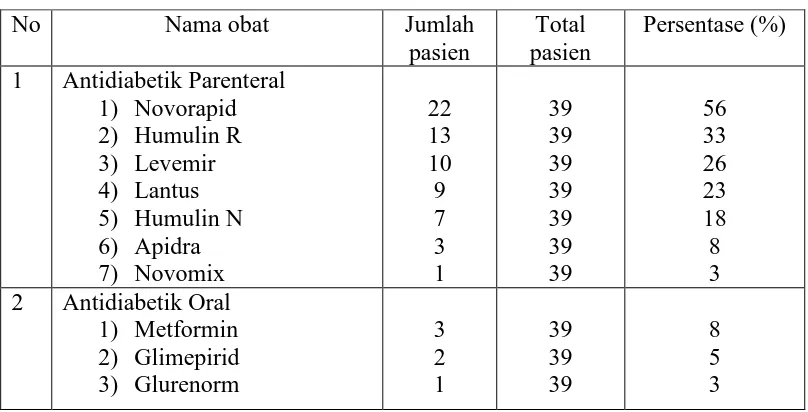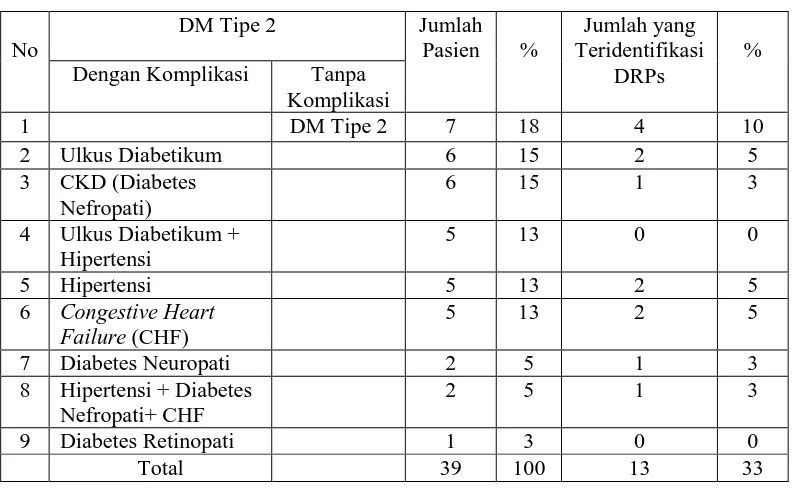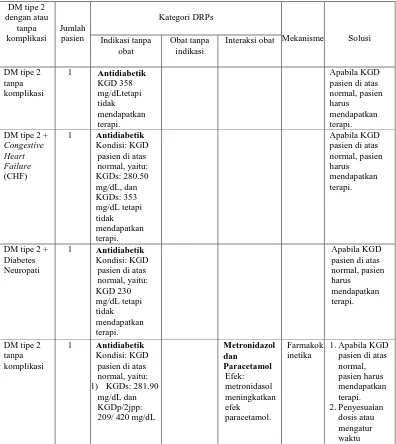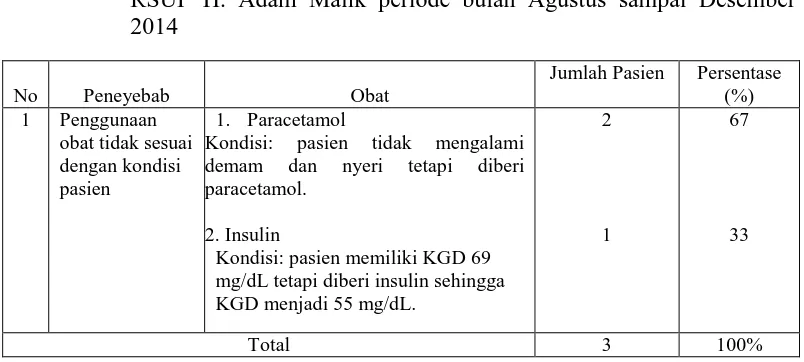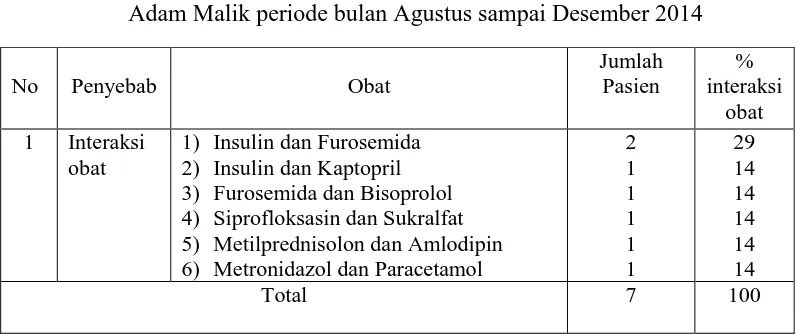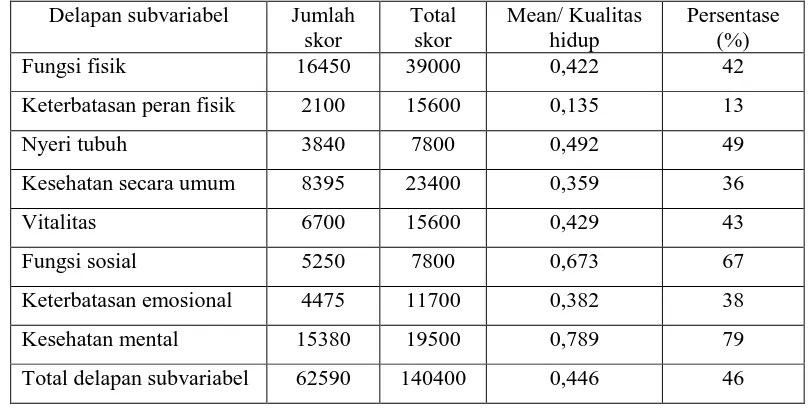Lampiran 1. Data penggunaan obat pasien Substitusi natrium 3 fls nacl 0,9 % 14 gtt/i √
Lampiran 1. Data penggunaan obat pasien
Lampiran 1. Data penggunaan obat pasien
Inj. Ranitidin 50 mg iv √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Humulin R 6-6-6 iu 1/2 hac sc √ √ √
Inj. Ketorolac 30 mg/8 jam iv √
Asam mefenamat 500 mg √
Metformin 2x50 mg √ √ √ √ √ √ √ √ √
Amlodipin 1x5 mg √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Paracetamol 3x500 mg √
Captopril 3x12,5 mg √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Humulin R 10-10-10 iu 1/2 hac sc --> 20-20-20 iu 1/2 hac sc
Inj. Furosemid 1 amp/6 jam --> 2 amp/6 jam iv
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Lampiran 1. Data penggunaan obat pasien
Aminofliud 1fls/h √
11 L 51 IVFD NaCl 0,9 % 20 gtt/i iv √ √ √ √ √ √
IVDF RL 20 gtt/i √ √ √ √ √ √
inj. Ceftriaxon 1gr/12 jam iv √ √ √ √ √ √ √ √ √ Drip metronidazol 500 mg/8 jam iv √ √ √ √
Lampiran 1. Data penggunaan obat pasien
Lampiran 1. Data penggunaan obat pasien
clindamisin 4x300 mg √ √
dripciprofloksasin 400 mg/24 jam √ √
16 P 83 IVFD NaCl 0,9% 10 gtt/i iv √ √ √ √ √ V √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Dulcolax supp √
Retaphyl 2x1/2 tab √ √ √ √ √ √
Lampiran 1. Data penggunaan obat pasien
Dulcolax supp √
18 P 64 IVFD NaCl 0,9% 20 gtt/i iv √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Fenitoin 3x100 mg √
Lampiran 1. Data penggunaan obat pasien
Inj. Metoclopramid 1 amp/8 jam iv √
Inj. Levemir 10 iu (pkl.22.00 wib) --> 12 iu sc
Loperamid 2 tab awal lanjut 1 tab/x menceret
√ √
Sucralfat syrp 3xc1 √
Seroguel XR 200 1x1 (mlm) √ √ √ √ √
Lampiran 1. Data penggunaan obat pasien
Dulcolax supp 1x1 √
21 P 46 IVFD D 10% 10 gtt/i √ √ √
Novorapid 6-6-6 iu 1/2 hac sc --> 16-16-16 iu 5'ac sc
Substitusi meylon 8 fls dalam 100 cc nacl 0,9% 10gtt/i
√ √
Substitusi albumin √
22 L 44 IVFD NaCl 0,9% 10gtt/i iv √ √ √ √ √ √ √
Inj. Ceftriakson 1 gr/12 jam iv √ √ √ √ √ Drip metronidazol 500 mg/ 8 jam iv √ √
Drip ciprofloxacin 200 mg/12 jam √
Humulin R 6-6-6- iu 1/2 hac sc √ √ √ √ √ √ Inj. Ketorolac 1 amp/ 8 jam iv √ √
Inj. Ranitidin 50 mg/12 jam iv √ √
Inj. Metoclopramid 1 amp/8 jam √
GG (gliceril guaiakolat) 3x100 mg √ √
KRS 1x600 mg √ √
Paracetamol 3x500 mg √
Captopril 2x25 mg √ √
Amlodipin 1x5 mg √ √
Clindamisin 3x600 mg √ √ √ √ √
Inerson krim 2xsehari √
23 L 65 IVFD nacl 0,9% 20 gtt/i iv √ √ √ √ √ √ Dextrosa 40% 2 fls (50 ml) √
Lampiran 1. Data penggunaan obat pasien
Spironolakton 1x25 mg √ √
Captopril 3x6,25 mg √ √ √
Aspilet 1x80 mg √ √ √
Simvastatin 1x20 mg √ √ √ √
Substitusi meylon 8 fls dalam 200 cc nacl 0,9% 20 gtt/i Inj. Metoclopramid 1 amp/8 jam iv √ Inj.ranitidin 50 mg/12 jam iv √ √ √ Inj.dexamethason 1 gr/8 jam iv √ √ Novorapid 16-16-16 iu 1/2 hac sc √ √ √
Levemir 12 iu sc √ √ √
Codein 2x10 mg √ √ √
Antasida syr 3x C II √ √ √
Captopril 2x12,5 mg √
Valsartan 1x80 mg √ √ √
Furosemid 1x20 mg √
Domperidon 3x10 mg √ √
Metilprednisolon 3x4 mg √
Retaphyl SR 2x1 √
Aspilet 1x80 mg √ √
Lampiran 1. Data penggunaan obat pasien
Substitusi albumin 20% 1fls √ 27 L 52 IVFD NaCl 0,9% 20 gtt/i iv √ √ √ √
Inj. Ranitidin 50 mg/12 jam iv √ √ √ √ Inj. Metoclopramid 10 mg/ 8 jam iv √ √ √ √
Methylcobalamin 3x1 √ √
Metformin 2x500 mg √ √ √
Lampiran 1. Data penggunaan obat pasien
Substitusi natrium √
30 P 59 IVFD NaCl 0,9% 500cc + 5 fls KCL 10
Lampiran 1. Data penggunaan obat pasien
Spironolacton 1x100 mg √ √ √ √ √ √
Vitamin B complex 3x1 √ √ √ √ √ √
Paracetamol 3x500 mg √ √
Sistenol 3x1 √
Novorapid 6-6-6 iu --> 10-10-10 iu ½ hac sc Novorapid 6-6-6 iu --> 10-10-10 iu ½ hac
Lampiran 1. Data penggunaan obat pasien
Substitusi meylon √
36 P 61 IVFD NaCl 0,9% 20 gtt/i √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Nebulasi ventolin 1xtab/jam √
37 L 45 IVFD NaCl 0,9% 20 gtt/i √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Inj.ceftriaxon 2 gr/24 jam √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Lampiran 1. Data penggunaan obat pasien
nacl 0,9% 30 gtt/i
Novorapid 6-6-6 iu 1/2 hac sc √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Lantus 10 iu (mlm) sc √
Inj. Metoclpramid 1 amp/ 8 jam iv √
Cloxacilin 4x4 tab (ada pada pasien) Pantoprazole 1x1 tab (ada pada pasien) Motilium 1x1 tab (ada pada pasien) Unasyn sultamycilin 2x1 tab (ada pada pasien)
MST (most contius tablet) 2x10 mg √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Substitusi albumin 1 fls/h √ √
38 L 68 IVFD NaCl 0,9% 20 gtt/i √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Paracetamol 3x1000 mg √ √
Lampiran 1. Data penggunaan obat pasien
Keterangan : JK : Jenis Kelamin
P : Perempuan L :Laki-Laki
Amlodipin 1x10 mg √ √ √
Captopril 2x25 mg √ √ √
Lampiran 2. Analisis regimen-regimen pada Lampiran 1
No Assessment
Kategori DRPs
Penyebab Solusi
Indikasi Hipertensi stage 2 Konstipasi
3 DM tipe 2 - - - - -
Congestive Heart Failure (CHF)
4 DM tipe 2 Antidiabetik - - Pasien memiliki KGD
230 mg/dL tetapi tidak diberi antidiabetik.
Apabila KGD pasien di atas normal, pasien harus mendapatkan terapi. Diabetes Neuropati (Diabetes
Gastropati)
Interaksi obat Mekanisme:
Lampiran 2. Analisis regimen-regimen pada Lampiran 1
atau 6 jam setelah pemberian sukralfat.
Interaksi obat Mekanisme: tidak diketahui
Efek: efektifitas insulin menurun (kondisi: KGDp/KGD2jpp: 136/ 267 mg/dL menjadi 191/ 274 mg/dL )
Lampiran 2. Analisis regimen-regimen pada Lampiran 1 Congestive Heart Failure (CHF)
Chronic Kidney Disease (CKD)/ Diabetes Nefropati kadar serum kalium dan furosemid menurunkan kadar serum kalium) Efek: menyebabkan hipotensi dan penuunan detak jantung (kondisi: TD: 140/80 mmHg menjadi 80/60 mmHg dan HR: 80x/i menjadi 60x/i.
Mengatur dosis obat yang diberikan, mengatur waktu pemberian obat atau butuh pemeriksaan tekanan darah lebih sering.
Congestive Heart Failure (CHF) Dispepsia
10 DM tipe 2 Antidiabetik - - Pasien memiliki KGD
358 mg/dL tetapi tidak diberi antidiabetik.
Apabila KGD pasien di atas normal, pasien harus mendapatkan terapi. Hepatomegali
Efusi pleura
Lampiran 2. Analisis regimen-regimen pada Lampiran 1 Ulkus Diabetikum
Pneumonia Anemia
12 DM Tipe 2 - - - - -
Ulkus Diabetikum Anemia
Trombositosis reaktif
13 DM tipe 2 - - - - -
Congestive Heart Failure (CHF) Cholelistitis
Hepatomegali
14 DM tipe 2 - - - - -
Chronic Kidney Disease (CKD) / Diabetes Nefropati
Anemia
15 DM tipe 2 - Paracetamol - Pasien tidak mengalami
demam dan nyeri tetapi diberi paracetamol.
Paracetamol diberikan seperlunya.
Abses anemia Asites hiponatremia hipoalbuminaria
Lampiran 2. Analisis regimen-regimen pada Lampiran 1 Hipertensi Stage 2
penumonia sindrom geriatri
17 DM tipe 2 - - - - -
Chronic Kidney Disease (CKD)/ Diabetes Nefropati
Abses Mammae Anemia
18 DM tipe 2 Antidiabetik
(Insulin)
Pasien memiliki KGD 69 mg/dL tetapi diberi antidiabetik sehinggan KGD menjadi 55 mg/dL.
Apabila KGD pasien di bawah normal, tidak perlu diberikan antidiabetik.
Ulkus Diabetikum Anemia
Hiponatremia hipokalemia
19 DM tipe 2 - - - - -
Post PSMBA (Post Perdarahan Saluran Makan atas)
Anemia
Trombositopenia Sirosis Hepatis
20 DM tipe 2 - - - - -
Lampiran 2. Analisis regimen-regimen pada Lampiran 1 hiponatremia
hipokalemia
21 DM tipe 2 - Paracetamol - Pasien tidak mengalami
demam dan nyeri tetapi diberi paracetamol.
Paracetamol diberikan seperlunya.
Chronic Kidney Disease (CKD)/ Diabetes Nefropati
Post hipoglikemia Anemia
Pneumonia
22 DM tipe 2 - - - - -
Ulkuss Diabetikum Hipertensi Stage 2 Hipokalemia Hiponatremia
23 DM tipe 2 - - - - -
Post hipoglikemia Anemia
24 DM tipe 2 - - - - -
Congestif Heart Failure (CHF) Asidosis Metabolik
Gangguan Elektrolit
25 DM tipe 2 - - - - -
Lampiran 2. Analisis regimen-regimen pada Lampiran 1
26 Dm tipe 2 - - - - -
Hipertensi stage 2 Ulkus diabetikum
27 DM tipe 2 - - - - -
Diabetik Neuropati Dispepsia
28 DM tipe 2 - - - - -
Pneumonia
Chronic Kidney Disease (CKD)/ Diabetes Nefropati
Hipoalbimin Hiponatremia Leukositosis
29 DM Tipe 2 - - - - -
Ulkus Diabetikum Hipertensi Stage 1 Anemia
Hiponatremia
30 DM tipe 2 Antidiabetik - - Pasien memiliki KGDp/
2jpp: 175 mg/dL / 297 mg/dL, HbA1c: 10,1% tetapi tidak diberi antidiabetik.
Apabila KGD pasien di atas normal, pasien harus mendapatkan terapi.
Hipertensi - - Kaptopril dan
Insulin
Interaksi obat. Mekanisme: farmakodinamika
Lampiran 2. Analisis regimen-regimen pada Lampiran 1
(kaptopril meningkatkan efek insulin)
Efek: hipoglikemia (kondisi: KGD: 138 mg/dL menjadi 30 mg/dL)
hipoglikemia dan pengaturan dosis obat serta mengatur waktu pemberian obat agar tidak terjadi interaksi.
Cholelistisis Hipokalemia
31 DM tipe 2 - - Furosemida
dan Insulin
Interaksi obat Mekanisme: tidak diketahui
Efek: efektifitas insulin menurun. (kondisi: KGDp/KGD2jpp: 122/ 221 mg/dL menjadi 135/ 271 mg/dL )
Monitoring KGD secara rutin dan bila KGD meningkat dengan dosis penggunaan insulin yang biasanya maka dosis insulin ditingkatkan.
Sirosis hati
Post PSMBA (Post Perdarahan Saluran Makan Atas)
32 DM tipe 2 - - Metilprednisol
on dan Amlodipin
Interaksi obat Mekanisme:
farmakokinetika pada fase metabolisme
Efek: metilprednisolon menurunkan efektivitas amlodipin.
Penyesuaian dosis atau mengatur waktu
pemeberian obat agar tidak terjadi interaksi.
Lampiran 2. Analisis regimen-regimen pada Lampiran 1
33 DM tipe 2 - - - - -
Chronic Kidney Disease (CKD)/ Diabetes Nefropati
Dispepsia Hiponatremia
34 DM tipe 2 Antidiabetik - - Pasien memiliki KGD
sewaktu 281.90 mg/dL dan KGDp/2jpp: 209/ 420 mg/dl tetapi tidak diberi antidiabetik.
Apabila KGD pasien di atas normal, pasien harus mendapatkan terapi.
Kolangitis Metronidasol
dan
paracetamol
Interaksi obat Mekanisme:
farmakokinetika pada fase metabolisme
Efek: metronidasole meningkatkan efek paracetamol
Penyesuaian dosis atau mengatur waktu pemberian.
Obstructive Jaundice Anemia
35 DM tipe 2 - - - - -
Chronic Kidney Disease (CKD)/ Diabetes Nefropati
Hipertensi stage 2
Congestive Heart failure (CHF) Dislipidemia
Lampiran 2. Analisis regimen-regimen pada Lampiran 1
36 DM tipe 2 Antidiabetik - - Pasien memiliki KGD
sewaktu 280.50 mg/dL dan 353 mg/dL tetapi tidak diberi antidiabeteik.
Apabila KGD pasien di atas normal, pasien harus mendapatkan terapi.
Congestive Heart Failure (CHF) Pneumonia
37 DM tipe 2 - - - - -
Hipoalbuminaria Hipanatremia
38 DM tipe 2 - - - - -
Ulkus Diabetikum Hipertensi stage 2
39 DM tipe 2 - - - - -
Selulitis
Hipertensi Stage 1
Lampiran 3. Kuesioner Penelitian
KUESIONER PENELITIAN
MENILAI KUALITAS HIDUP PASIEN DIABETES MELITUS Responden no :
PETUNJUK : Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan cara memilih satu jawaban yang anda anggap benar sesuai dengan kondisi yang anda rasakan
1. Secara umum: apakah akan anda katakan bahwa kesehatan anda adalah: A. Sangat baik
B. Baik sekali C. Baik D. Sedang E. Kurang
2. Dibandingkan dengan keadaan setahun yang lalu, bagaimana rata-rata kesehatan anda secara umum sekarang ini?
A. Sekarang jauh lebih baik dibanding setahun yang lalu. B. Sekarang agak lebih baik dibanding setahun yang lalu. C. Kira-kira sama dengan keadaan setahun yang lalu.
D. Sekarang agak lebih parah dibandingkan setahun yang lalu. E. Jauh lebih parah dibanding setahun yang lalu.
Katagori berikut ini adalah tentang aktifitas yang mungkin anda kerjakan selama hari-hari tertentu. Apakah kesehatan anda membatasi aktifitas-aktifitas ini? Jika ya, seberapa jauh?
NO Aktivitas Anda
Sangat
3. Aktivitas berat seperti lari, mengangkat benda berat, olahraga berat
4 Aktivitas sedang seperti memindahkan meja, menekan penghisap debu, bowling, main golf 5 Mengangkat atau membawa nampan makanan 6 Naik tangga pada banyak anak tangga 7 Naik tangga pada satu anak tangga 8 Melipat atau menekuk anggota tubuh atau
membungkuk
9 Jalan kaki lebih dari 1km 10 Jalan kaki banyak blok rumah 11 Jalan kaki satu blok rumah 12 Mandi atau memakai baju sendiri
Selama 4 minggu terakhir apakah anda mengalami masalah kerja atau aktivitas sehari-hari akibat kesehatan fisik anda ?
No Pertanyaan Ya Tidak
Lampiran 3. Kuesioner Penelitian
14 Selesainya pekerjaan atau aktivitas lain kurang dari yang dikehendaki
15 Ada keterbatasan dalam mengerjakan pekerjaan atau aktivitas lain ? 16 Mengalami kesulitan melakukan pekerjaan atau kegiatan lain
(misalnya, membutuhkan tenaga ekstra)
Selama 4 minggu terakhir, apakah anda mengalami masalah dengan pekerjaan anda atau dengan aktifitas anda sehari- hari sebagai dampak dari masalah emosional anda (seperti perasaan tertekan atau rasa cemas)?
No Pertanyaan Ya Tidak
17 Mengurangi jumlah waktu yang anda pergunakan dalam pekerjaan atau dalam aktifitas lainnya.
18 Selesainya pekerjaan atau aktivitas lain kurang dari yang dikehendaki
19 Tidak dapat mengerjakan pekerjaan atau aktivitas lain secermat biasanya.
20. Dalam 4 minggu terakhir, sejauh mana masalah kesehatan fisik atau emosional mengganggu aktivitas sosial anda yang normal dengan keluarga, teman-teman, tetangga atau kelompok?
A. Tidak sama sekali B. Agak mengganggu C. Sedang
D. Sangat sedikit E. Terlalu mengganggu
21. Dalam 4 minggu terakhir, seberapa jauh nyeri tubuh yang anda rasakan? A. Tidak ada
B. sangat ringan C. Ringan D. sedang E. parah F. sangat parah
22. Dalam 4 minggu terakhir seberapa nyeri badan anda menghambat kerja normal anda termasuk kerja dirumah atau diluar rumah?
A. Tidak sama sekali B. Agak mengganggu C. Sedang
D. Sangat sedikit E. Terlalu mengganggu
Pertanyaan-pertanyaan ini adalah tentang bagaimana anda merasa dan bagaimana segala sesuatunya berkaitan dengan anda selama empat minggu terakhir. Untuk setiap pertanyaan, berikan sebuah jawaban yang paling dekat dengan cara anda merasakannya. Seberapa sering selama empat minggu terakhir.
No Pertanyaan Setiap
saat
Sering Agak sering
Jarang Sangat jarang
Tidak pernah 23 Apakah anda merasa semangat anda
penuh?
Lampiran 3. Kuesioner Penelitian
25 Apakah anda pernah merasakan sangat terpuruk sehingga tidak ada orang yang dapat menghibur?
26 Apakah anda merasa tenang dan damai?
27 Apakah anda mempunyai tenaga yang banyak?
28 Apakah anda merasa tertekan atau menyendiri?
29 Apakah anda merasa letih?
30 Apakah anda merasa menjadi orang yang berbahagia?
31 Apakah anda merasa lelah?
32. dalam 4 minggu terakhir, seberapa lama masalah kesehatan fisik atau emosional menghambat aktivitas sosial anda seperti mengunjungi teman, sanak saudara dan senagainya?
A. Setiap saat B. Hampir setiap saat C. Kadang-kadang D. Sekali-sekali E. Tidak pernah
Seberapa jauh BENAR atau SALAH menurut anda pernyataan dibawah ini :
No Pertanyaan Benar
33 Kelihatannya saya sedikit lebih mudah sakit dibandingkan dengan orang lain
34 Saya sama sehatnya seperti orang yang saya kenal
35 Saya berharap kesehatan saya menjadi buruk
Lampiran 3. Kuesioner Penelitian
KUESIONER PENELITIAN
MENILAI KUALITAS HIDUP PASIEN DIABETES MELITUS Responden no :
PETUNJUK : Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan cara memilih satu jawaban yang anda anggap benar sesuai dengan kondisi yang anda rasakan
1. Secara umum: apakah akan anda katakan bahwa kesehatan anda adalah: A. Sangat baik
B. Baik sekali C. Baik D. Sedang E. Kurang
2. Dibandingkan dengan keadaan setahun yang lalu, bagaimana rata-rata kesehatan anda secara umum sekarang ini?
A. Sekarang jauh lebih baik dibanding setahun yang lalu. B. Sekarang agak lebih baik dibanding setahun yang lalu. C. Kira-kira sama dengan keadaan setahun yang lalu.
D. Sekarang agak lebih parah dibandingkan setahun yang lalu. E. Jauh lebih parah dibanding setahun yang lalu.
Katagori berikut ini adalah tentang aktifitas yang mungkin anda kerjakan selama hari-hari tertentu. Apakah kesehatan anda membatasi aktifitas-aktifitas ini? Jika ya, seberapa jauh?
NO Aktivitas Anda
Sangat
3. Aktivitas berat seperti lari, mengangkat benda berat, olahraga berat
4 Aktivitas sedang seperti memindahkan meja, menekan penghisap debu, bowling, main golf 5 Mengangkat atau membawa nampan makanan 6 Naik tangga pada banyak anak tangga 7 Naik tangga pada satu anak tangga 8 Melipat atau menekuk anggota tubuh atau
membungkuk
9 Jalan kaki lebih dari 1km 10 Jalan kaki banyak blok rumah 11 Jalan kaki satu blok rumah 12 Mandi atau memakai baju sendiri
Selama 4 minggu terakhir apakah anda mengalami masalah kerja atau aktivitas sehari-hari akibat kesehatan fisik anda ?
No Pertanyaan Ya Tidak
Lampiran 3. Kuesioner Penelitian
14 Selesainya pekerjaan atau aktivitas lain kurang dari yang dikehendaki
15 Ada keterbatasan dalam mengerjakan pekerjaan atau aktivitas lain ? 16 Mengalami kesulitan melakukan pekerjaan atau kegiatan lain
(misalnya, membutuhkan tenaga ekstra)
Selama 4 minggu terakhir, apakah anda mengalami masalah dengan pekerjaan anda atau dengan aktifitas anda sehari- hari sebagai dampak dari masalah emosional anda (seperti perasaan tertekan atau rasa cemas)?
No Pertanyaan Ya Tidak
17 Mengurangi jumlah waktu yang anda pergunakan dalam pekerjaan atau dalam aktifitas lainnya.
18 Selesainya pekerjaan atau aktivitas lain kurang dari yang dikehendaki
19 Tidak dapat mengerjakan pekerjaan atau aktivitas lain secermat biasanya.
20. Dalam 4 minggu terakhir, sejauh mana masalah kesehatan fisik atau emosional mengganggu aktivitas sosial anda yang normal dengan keluarga, teman-teman, tetangga atau kelompok?
A. Tidak sama sekali B. Agak mengganggu C. Sedang
D. Sangat sedikit E. Terlalu mengganggu
21. Dalam 4 minggu terakhir, seberapa jauh nyeri tubuh yang anda rasakan? A. Tidak ada
B. sangat ringan C. Ringan D. sedang E. parah F. sangat parah
22. Dalam 4 minggu terakhir seberapa nyeri badan anda menghambat kerja normal anda termasuk kerja dirumah atau diluar rumah?
A. Tidak sama sekali B. Agak mengganggu C. Sedang
D. Sangat sedikit E. Terlalu mengganggu
Pertanyaan-pertanyaan ini adalah tentang bagaimana anda merasa dan bagaimana segala sesuatunya berkaitan dengan anda selama empat minggu terakhir. Untuk setiap pertanyaan, berikan sebuah jawaban yang paling dekat dengan cara anda merasakannya. Seberapa sering selama empat minggu terakhir.
No Pertanyaan Setiap
saat
Sering Agak sering
Jarang Sangat jarang
Tidak pernah 23 Apakah anda merasa semangat anda
penuh?
Lampiran 3. Kuesioner Penelitian
25 Apakah anda pernah merasakan sangat terpuruk sehingga tidak ada orang yang dapat menghibur?
26 Apakah anda merasa tenang dan damai?
27 Apakah anda mempunyai tenaga yang banyak?
28 Apakah anda merasa tertekan atau menyendiri?
29 Apakah anda merasa letih?
30 Apakah anda merasa menjadi orang yang berbahagia?
31 Apakah anda merasa lelah?
32. dalam 4 minggu terakhir, seberapa lama masalah kesehatan fisik atau emosional menghambat aktivitas sosial anda seperti mengunjungi teman, sanak saudara dan senagainya?
A. Setiap saat B. Hampir setiap saat C. Kadang-kadang D. Sekali-sekali E. Tidak pernah
Seberapa jauh BENAR atau SALAH menurut anda pernyataan dibawah ini :
No Pertanyaan Benar
33 Kelihatannya saya sedikit lebih mudah sakit dibandingkan dengan orang lain
34 Saya sama sehatnya seperti orang yang saya kenal
35 Saya berharap kesehatan saya menjadi buruk
Lampiran 4.Hasil Analisis Hubungan antara DRPs dengan Kualitas Hidup Pasien
DM tipe 2 Di Instalasi Rawat Inap RSUP H. Adam Malik Periode Bulan Agustus sampai Desember 2014
Keterangan: berdasarkan hasil analisi crosstabulasi antara kualitas hidup dan DRPs diperoleh:
a. Pasien yang mengalami DRPs adalah 13 orang dengan 7 orang memiliki kualitas hidup buruk dan 6 orang memiliki kualitas hidup baik. Pasien yang tidak mengalami DRPs adalah 26 orang dengan 19 orang memiliki kualitas hidup buruk dan 7 orang memiliki kualitas hidup baik.
b. Pasien yang memiliki kualitas hidup buruk adalah 26 orang dengan 7 orang yang mengalami DRPs dan 19 orang yang tidak mengalami DRPs. Pasien yang memiliki kualitas hidup baik adalah 13 orang dengan 6 orang yang mengalami DRPs dan 7 orang yang tidak mengalami DRPs.
Tabel 2. Chi-Square Tes
Value Df
Continuity Correctionb 0.707 1 0.401
Likelihood Ratio 1.414 1 0.234
Fisher's Exact Test 0.290 0.199
Linear-by-Linear Association 1.405 1 0.236
N of Valid Casesb 39
a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,33. b. Computed only for a 2x2 Table.
Keterangan: Berdasarkan uji Chi-Square terdapat 1 cell memiliki frekuensi harapan kecil dari 5, sehingga nilai yang diambil adalah Fisher’s Exact Test dengan nilai p = 0,290 yang maknanya adalah menerima Ho yang berarti bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara DRPs dengan Kualitas Hidup pasien DM tipe 2 di instalasi rawat inap RSUP H. Adam Malik.
Tabel 1. Crosstabulasi antara kualitas hidup dan DRPs
Count kualitas_hidup
Total buruk Baik
DRPs DRPs(+) 7 6 13
DRPs(-) 19 7 26
Lampiran 5. Formulir Persetujuan Penelitian
FORMULIR PERSETUJUAN PENELITIAN (Informed Consent)
Saya yang bernama Maria Reunita / 101501151 adalah mahasiswa S1 Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu kegiatan dalam menyelesaikan proses belajar mengajar pada program S1 Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Drug Related Problems (DRPs) terjadi pada pasien diabetes melitus dan bagaimana hubungannya dengan kualitas hidup pasien. Untuk keperluan tersebut saya mohon kesediaan bapak/ibu untuk menjadi partisipan dalam penelitian ini. Selanjutnya saya mohon kesediaan bapak/ibu untuk mengisi kuesioner dengan jujur dan apa adanya. Jika bapak/ibu bersedia, silahkan menandatangani persetujuan ini sebagai bukti kesukarelaan bapak/ibu. Identitas pribadi sebagai partisipan akan dirahasiakan dan semua informasi yang diberikan hanya akan digunakan untuk penelitian ini. Bapak/Ibu berhak untuk ikut atau tidak ikut berpartisipan tanpa ada sanksi dan konsekuensi buruk dikemudian hari. Jika ada hal yang kurang dipahami bapak/ibu dapat bertanya langsung kepada peneliti.
Atas perhatian dan kesediaan bapak/ibu menjadi partisipan dalam penelitian ini saya ucapkan terima kasih.
Medan, Agustus 2014
Peneliti Partisipan
Lampiran 6.Surat Permohonan Izin Melakukan Penelitian di RSUP H. Adam
Lampiran 9. Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Penelitian di RSUP
DAFTAR PUSTAKA
Arif, M., Ernalia, Y., dan Rosdiana, D. (2014). Hubungan Indeks Massa Tubuh dengan Kadar Gula Darah Puasa Pada Pegawai Sekretariat Daerah Provinsi Riau. JOM.Vol.1 No.2.
American Diabetes Association. (2014).Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus.Diabetes Care. Vol 337. Suppl 1.
American Diabetes Association. (2015).Standar of medical care in diabetes 2015.Diabetes Care.Vol 38. Suppl 1.
Badan Penelitian dan Pengembangan Kementrian Kesehatan RI. (2013). Riset
Kesehatan Dasar. Halaman89, 97. Diakses dari
tangal 7 Mei 2014.
Baxter, K. (2010). Stocley’s Drug Interactions. Edisi VIII. London: Pharmaceutical press. Halaman 1-9, 485, 487.
Brunton, L.L., dan Parker, K.L. (2008). Goodman and Gilman’s of Pharmacology
and Therapeutics. Edisi XI. New York: McGraw-Hill. Halaman
1050-1055.
Dewi, M. (2007). Resistensi Insulin Terkait Obesitas: Mekanisme Endokrin dan Intrinsik Sel. Jurnal Gizi dan Pangan. 2(2). Halaman 52.
Ditjen Bina Kefarmasian dan Alkes Departement Kesehatan RI. (2005).
Pharmaceutical Care untuk Penyakit Diabetes Melitus. Jakarta:
Departemen Kesehatan RI. Halaman 24.
Dipiro, J.T., Talbert, R.L., Yee, G.C., Matzkey, G.R., Wells. B.G., dan Posey, L.M. (2008). Pharmacotherapy A Pathophysiologic Aproach. Edisi VII.New York: The McGraw- Hill Companies.Halaman 139, 154, 158-162, 615, 1215,1217, 1219-1226.
Drug.com. (2015).Diakses dari tanggal 15 Februari 2015.
Finkel, R., Clark, M.A., dan Cubeddu, L.X. (2009). Pharmakologi Ulasan
Bergambar. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC. Halaman 343, 347.
Gitawati, R. (2008). Interaksi Obat dan Implikasinya.Media Litbang Kesehatan. Vol. XVIII No. 4. Diakses dari 2015.
Gunawan, G.S. (2009). Farmakologi dan Terapi. Edisi V. Cetak Ulang. Jakarta:Balai Penerbit FK UI. Halaman 233,238.
Guyton, A.C. (1992). Fisiologi Manusia dan Mekanisme Penyakit.Jakarta: Penerbit buku kedokteran EGC. Halaman 699, 707.
Hansten, P.D. (1973). Drug Interactions. Edisi II. Philadelphia:Lea and Febiger. Halaman 81.
International Diabetes Federation. (2013). IDF Diabetes Atlas. Edisi VI. Halaman: 30,31,32. Diakses dari http: tanggal 20 Mei 2014.
Irawan, D. (2010). Prevelensi dan faktor resiko kejadian DM tipe 2 di Daerah Urban Indonesia (Analisa Data Sekunder Riskesdas 2007). Tesis. Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat FKM UI. Halaman 22-23.
Jalal, F., Liputo, N.I., Susanti, N., dan Oenzil, F. (2010). Hubungan Lingkar Pinggang dengan Kadar Gula Darah, Trigliserida dan Tekanan Darah pada Etnis Minang di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.Diakses dar Jelantik, I.M.G., dan Hayati, E. (2014). Hubungan Faktor Risiko Umur, Jenis
Kelamin, Kegemukan, dan Hipertensi dengan Kejadian Diabetes Mellitus Tipe 2 di Wilayah Kerja Puskesmas Mataram. Media Bina Ilmiah39. 8(1). Halaman 40.
Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. (2013). Diabetes Penyebab Kematian
no.6 di Dunia: Kemenkes Tawarkan Solusi Cerdik Melalui Pospidu.
Diakses dari
Khardori, R. (2015). Type 2 Diabetes Mellitus. Diakses dari http://emedicine. medscape.com/article/117853-overview pada tanggal 14 Maret 2015. Khardori, R. (2015). Type 1 Diabetes Mellitus. Diakses dari http://emedicine.
medscape.com/article/117739-overview pada tanggal 14 Maret 2015. Medscape. (2015). Diakses dari
http://reference.medscape.com/drug-interactionchecker pada tanggal 15 Februari 2015.
Ndraha, S.(2014). Diabetes Melitus Tipe 2 da Tatalaksana Terkini.
MedicinusVol.27No.2. Halaman 9.
Ningtyas, D.W. (2013). Analisis Kualitas Hidup Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 di RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan. Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Diakses dari Februari 2016.
RAND Health. (2012). Medical Outcome Study: 36-item Short From Survey
Instrumen.Diakses dari Http;//www.rand.org/health/survey/_tools/
moos/mos-core 36item_survey.htmlpada tanggal 7 Mei 2014.
RAND 36-Item Short Form Health Survey (SF-36)1.0 Questionnaire Items. Orthodoc.aaos.org/DrAlshaikh/SF 36.pdf. Diakses pada tanggal 10 Juni 2014.
Rubenstein, D., Wayne, D., dan Bradley, J. (2003). Kedokteran Klinis. Edisi VI. Jakarta: Penerbit Erlangga. Halaman 187-188.
Rumpuin, C.B. (2013). Analisis Drug Related Problem (DRP) Pada Penderita Rawat Inap dengan Diagnosa DM tipe 2 dengan Stroke Iskemik Dirumah sakit “X” Sidoarjo. Calptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas
Surabaya. 2(2): 6.
Soegondo, S., Soewondo,P., dan Subekti, I. (1995). Penatalaksanaan Diabetes
Melitus Terpadu. Jakarta: Balai Penerbit FK UI. Halaman 127.
Solli, O., Stavem, K., and Kristiansen, I. (2010). Health-Related Quality of Life in Diabetes: The Associations of Complications with EQ-5D Scores. Health
and Quality of Life Outcomes. Diakses dari
Strand, L.M., Morley, P.C., Cipolle, R.J., Ramsey, R., dan Lamsam, G.D. (1990).
Drug-Related Problems: Their Structure and Function. DCIP The Annals
of Pharmacotherapy. 24(11). Halaman 1093-1097.
Sumantri, A. (2011). Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group. Halaman 79, 239, 240, 243.
Tatro, D.S. (2003). A to Z Drug Facts. San Francisco: Facts and Comparisons. Tjay,T.H., dan Rahardja, K. (2007). Obat-Obat Penting. Edisi VI.Cetakan
Pertama. Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo. Halaman555, 748-740.
Trisnawati, S.K., dan Setyorogo, S. (2013). Faktor Resiko Kejadian Diabetes Melitus Tipe 2 di Puskesmas Kecamatan Cengkareng JakartaBarat Tahun 2012. Jurnal Ilmiah Kesehatan. 5(1).
Utami, D.T., Darwin, K., dan Agrina. (2014). Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Hidup Pasien Diabetes Mellitus dengan Ulkus Diabetikum.JOM PSI. Vol. 1 No.2.
Walker,R., dan Whitlesea,C. (2012).Clinical Pharmacy and Therapeutics. Edisi V. London: Elsevier. Halaman688, 704.
WHO. (1997). WHOQOL Measuring Quality of Life. Diakses dari 2014.
WHO Department of Noncommunicable Disease Surveillance Geneva. (1999).
Definition, Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus and its Complications. Report of a WHO ConsultationPart 1: Diagnosis
andClassification of Diabetes Mellitus. Diakses dari
10
Juni 2014.
WHO. (2001). Health Research Methodology A Guide for Training in Research
Methods. Edisi II. Manila: World Health Organization. Halaman 26, 34.
WHO. (2010). Global Status Report On Noncommunicable Disease. page: 1, 9. Diakses dari pada tanggal 20 Mei 2014.
Yusra, A. (2010). Hubungan Antara Dukungan Keluarga Dengan Kualitas Hidup Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 Di Poliklinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta. Tesis Ilmu Keperawatan FKM UI. Halaman 95.
BAB III
METODE PENELITIAN 3.1 Jenis Penelitian
Penelitian dilakukan melalui survey deskriptif, dengan pendekatan
prospektif dan menggunakan rancangan cross sectional, yaitu penelitian non
eksperimental dalam rangka mempelajari korelasi antara DRPs dengan kualitas
hidup pada waktu tertentu (WHO, 2001).
3.2 Populasi dan Sampel 3.2.1 Populasi
Populasi target penelitian ini adalah pasien DM di instalasi rawat inap
rindu A1 dan A2 RSUP H. Adam Malik periode bulan Agustus sampai Desember
2014, yakni terdapat 68 pasien DM tipe 2.
Kriteria inklusi yang harus dipenuhi dalam penelitian ini adalah:
1. Pasien DM tipe 2 yang dirawat di instalasi rawat inap RSUP H. Adam
Malik yang mendapatkan terapi antidiabetik.
2. Pasien yang bisa kooperatif dan mampu memberikan informasi.
3. Bersedia menjadi responden dan bisa baca, tulis.
Kriteria eksklusi merupakan keadaan yang menyebabkan sampel tidak
dapat diikutsertakan. Adapun yang menjadi kriteria eksklusi adalah:
1. Pasien DM tipe 2 yang dirawat di instalasi rawat inap RSUP H. Adam
Malik yang tidak mendapatkan terapi antidiabetik.
2. Data pasien tidak lengkap (yang tidak memuat informasi dasar yang
dibutuhkan dalam penelitian)
4. Tidak Bersedia menjadi responden dan tidak bisa baca, tulis.
Populasi target yang memenuhi kriteria inklusi dijadikan sebagai populasi
studi. Dalam hal ini diperoleh 39 pasien.
3.2.2 Sampel
Populasi target dalam penelitian ini adalah 68 pasien, namun berdasarkan
kenyataan jumlah pasien yang memenuhi kriteria inklusi (populasi studi) adalah
39 pasien, sehingga seluruh populasi studi dijadikan sebagai sampel studi.
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di instalasi rawat inap terpadu A1 dan A2 RSUP
H. Adam Malik pada bulan Agustus sampai Desember 2014.
3.4Analisis
3.4.1 Analisis Karakteristik Pasien
Pengambilan data dilakukan dengan mengakses rekam medik pasien DM
yang dirawat di instalasi rawat inap RSUP H. Adam Malik. Adapun data yang
diakses adalah karakteristik pasien, catatan perkembangan terintegrasi, tabel
rekaman pemberian obat tepat waktu, hasil laboratorium kadar gula darah dan
kuesioner.
3.4.2 AnalisisDrug Related Problems
Defenisi dan Kriteria DRPs menurut Strand, et al., (1990) sebagai berikut:
a. Drug Related Problems adalah kejadian yang tidak diinginkan pasienterkait
terapi obat dan secara nyata maupun potensial berpengaruh pada outcome
b. Indikasi tanpa obat adalah pasien mempunyai kondisi penyakit yang
membutuhkan terapi obat tetapi pasien tidak mendapatkan obat untuk indikasi
tersebut.
c. Obat tanpa indikasi adalah pasien mempunyai kondisi penyakit dan menerima
obat yang tidak mempunyai indikasi medis yang valid.
d. Obat salah adalah pasien mendapatkan obat yang tidak aman, tidak paling
efektif dan kontraindikasi dengan kondisi pasien tersebut.
e. Dosis obat kurang adalah pasien mempunyai kondisi penyakit dan
mendapatkan obat yang benar tetapi dosis obat tersebut kurang.
f. Dosis obat berlebih adalah pasien mempunyai kondisi penyakit dan
mendapatkan obat yang benar tetapi dosis obat tersebut lebih.
g. Reaksi obat merugikan adalah pasien mempunyai kondisi penyakit akibat
reaksi obat yang merugikan.
h. Interaksi obat adalah pasien mempunyai kondisi penyakit akibat interaksi
obat-obat, obat-makanan dan obat-hasil laboratorium.
i. Kepatuhan adalah pasien mempunyai kondisi penyakit tetapi tidak
mendapatkan obat yang diresepkan.
Namun karena keterbatasan data, DRPs yang dianalisis dalam penelitian
ini hanya terbatas dalam 3 kategori:
a. Obat tanpa indikasi.
b. Indikasi tanpa obat.
c. Interaksi obat.
3.4.3 Analisis Kualitas Hidup
Kualitas hidup menurut World Health Organization Quality of Life
(WHOQOL) adalah persepsi individu terhadap posisinya, dan berhubungan
dengan tujuan, harapan, standar dan minat. Definisi ini merupakan konsep yang
sangat luas, menggabungkan kesehatan fisik seseorang, status psikologis, tingkat
kemandirian, hubungan sosial, kepercayaan personal dan hubungannya dengan
lingkungan (WHO, 1997).
Kategori kualitas hidup pasien DM yang diaplikasikan dalam penelitian ini
adalah menurut kuesioner SF-36.
Tabel 3.1 Kategori kualitas hidup menurut kuesioner SF-36 Variabel Sub Variabel
kualitas
Definisi Oprasional Cara Ukur Hasil Ukur dan Skor kegiatan fisik dengan atau tanpa
kesulitan.
Keterbatasan peran dinilai dari dua skala yaitu kesehatan fisik dan mental yang mana masalah mental berhubungan dengan masalah
pribadi dan emosional.
d. Persepsi
aktivitas normal atau saat sakit
Persepsi
kesehatan secara umum pada awalnya berhubungan dengan status kesehatan seseorang selama periode satu tahun.
Vitalitas (energi/ kelelahan) merupakan daya tahan tubuh seseorang dalam
Mengguna
1=Benar sekali 2=Hampir semua benar 3=Tidak tahu 4=Hampir semuanya salah 5=Salah sekali
f. Fungsi sosial
melakukan aktivitas sehari- hari.
Fungsi sosial
merupakan penilaian efek kesehatan terkait pada kegiatan sosial.
Keterbatasan peran karena
masalah emosional dapat muncul karena adanya masalah dikerjaan atau aktivitas sehari-hari yang mengakibatkan masalah emosional. 6=Tidak pernah
3.5 Instrumen Pengukuran Kualitas Hidup 3.5.1 Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer berupa kuesioner
instalasi rawat inap terpadu A1 dan A2 RSUP H. Adam Malik. Untuk kuesioner
jumlah skor yang telah ditentukan yaitu (0-100), dibagi menjadi 8 subvariabel
yang didalamnya ada 36 pertanyaan yang dilihat dari pengalaman responden
selama 4 minggu terakhir meliputi:
1. Fungsi fisik ada 10 pertanyaan pada nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan
12.
2. Keterbatasan peran fisik ada 4 pertanyaan pada nomor 13, 14, 15 dan 16.
3. Nyeri tubuh ada 2 pertanyaan pada nomor 21 dan 22.
4. Kesehatan secara umum ada 6 pertanyaan pada nomor 1, 2, 33, 34, 35 dan
36.
5. Vitalitas ada 4 pertanyaan pada nomor 23, 27, 29 dan 31.
6. Fungsi sosial ada 2 pertanyaan pada nomor 20 dan 32.
7. Keterbatasan emosional ada 3 pertanyaan pada nomor 17, 18 dan 19.
8. Kesehatan mental ada 5 pertanyaan pada nomor 24, 25, 26, 28 dan 30.
Untuk mengidentifikasi kualitas hidup pasien DM maka jumlah nilai
mentah tiap-tiap pertanyaan diubah ke transformed score. Nilai mentah adalah
nilai asli yang didapat dari penjumlahan pilihan responden di kuesioner.
Sedangkan transformed score merupakan nilai dari rentang 0-100 yang diadopsi
dari SF-36 Quetionnaire healty survey (Rand Health, 2012).
Tabel 3.2 Skor dari tiap-tiap pertanyaan
Nomor dari setiap pertanyaan
Jumlah Jawaban asli Skor/ nilai yang ditentukan
1, 2, 20, 22, 34, 36 1
2 3 4 5
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
Untuk menentukan kriteria penilaian kuesioner kualitas hidup digunakan
rumus pendekatan dengan skala Gutman.
Kriteria penilaian = skor tertinggi – interval Jumlah skor tertinggi = 100 (100%)
Jumlah skor terendah = 0 (0%)
Range = skor tertinggi – skor terendah = 100 – 0 = 100% Kategori = 2 (baik dan buruk)
Interval = range : kategori = 100% : 2 = 50%
Kriteria penilaian = 100% – 50% = 50%
Maka: Kualitas hidup kategori baik : mean ≥ 50%
3.5.2 Analisis Data
Setelah semua data terkumpul, maka dilakukan analisis data melalui
beberapa tahap. Pertama mengecek kelengkapan identitas dan data responden
serta memastikan bahwa semua jawaban telah diisi. Dilanjutkan dengan analisis
univariat dan bivariat.
Analisis univariat bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan
karakteristik setiap variabel penelitian (Sumantri, 2011). Analisis univariat pada
penelitian ini untuk mengetahui gambaran distribusi frekuensi. Setelah dilakukan
analisis univariat hasilnya akan diketahui karakteristik atau distribusi setiap
variabel dan dapat dilanjutkan analisis bivariat (Sumantri, 2011). Analisis ini
menggunakan uji statistik Chi-square (X2 ) dengan derajat kepercayaan α = 0,05
untuk menguji hubungan dua variabel yang nominal bernilai positif dengan
bantuan komputerisasi. Keputusan Chi Square adalah apabila ditemukan nilai
signifikan kurang dari 0,05 maka hubungan diantara keduanya adalah signifikan
sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis alternatif (Ha) diterima, dan
dapat di interpretasikan sebagai terdapatnya hubungan DRPs dengan kualitas
hidup pasien DM, sebaliknya apabila ditemukan nilai signifikan lebih dari atau
sama dengan 0,05 maka hipotesis alternatif (Ha) ditolak dan menerima hipotesis
nol (Ho), hal ini dapat di interpretasikan sebagai tidak terdapatnya hubungan
3.6 Bagan Alur Penelitian
Adapun alur pelaksanaan penelitian adalah seperti pada Gambar 3.1.
Gamba 3.1 Flowchart Pelaksanaan Penelitian
Rekam Medik
Mengisi Kuesioner
Mengajukan Kuesioner SF-36
Menilai
Hasil
Kuesioner
Pemilihan Data Berdasarkan Kriteria Inklusi
Identifikasi DRPs Pengambilan
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di instalasi rawat inap RSUP
H. Adam Malik periode bulan Agustus sampai Desember 2014 diperoleh 68
pasien DM tipe 2 sebagai populasi target. Diantara 68 pasien tersebut sebanyak 39
orang yang memenuhi syarat sebagai subjek. Data yang diperoleh dari rekam
medik pasien dan kuesioner yang diberikan kepada pasien. Berdasarkan penelitian
ini pasien perempuan sebanyak 27 orang dan pasien laki-laki sebanyak 12 orang.
Kelompok pasien DM berdasarkan usia ada pada Tabel 4.1.
Tabel 4.1 Kelompok pasien DM berdasarkan usia
Usia (Tahun) Jumlah Pasien Persentase (%)
40-49 11 28
50-59 18 46
60-69 8 21
70-79 1 3
80-89 1 3
Total 39 100
Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa pasien yang berusia 40-49
tahun sebanyak 11 pasien dengan persentase 28%, pasien yang berusia 50-59
tahun sebanyak 18 pasien dengan persentase 46%, pasien yang berusia 60-69
tahun sebanyak 8 pasien dengan persentase 21%, pasien yang berusia 70-79
tahun sebanyak 1 pasien dengan persentase 3%, dan pasien yang berusia 80-89
tertinggi berada pada kelompok usia 50-59 tahun dan jumlah prevalensi tertingi
kedua berada pada kelompok usia 40-49 tahun. Data ini sejalan dengan penelitian
yang dilakukan oleh Zahara (2013) yang menemukan prevalensi tertinggi DM
berada pada kelompok usia 50-59 tahun.
International Diabetes Federation (2013)menyatakan secara global jumlah
terbesar orang yang menderita DM tipe 2 ada pada kelompok usia 40-59 tahun.
Menurut Perkumpulan Endokrinologi Indonesia (PARKENI) batas umur yang
berisiko terhadap DM tipe 2 di indonesia adalah 45 tahun keatas.Demikian juga
halnyapadapenelitian yang dilakukan oleh Trisnawati dan Setyorogo (2013)
ditemukan peningkatan kejadian DM berada pada kelompok usia > 45 tahun.
Peningkatan risiko DM meningkat seiring dengan bertambahnya usia khususnya
pada usia lebih dari 40 tahun, hal ini disebabkan karena pada usia tersebut mulai
terjadi peningkatan intoleransi glukosa dan adanya proses penuaan. Adanya
proses penuaan menyebabkan berkurangnya kemampuan sel β pankreas dalam
memproduksi insulin. Selain itu pada individu yang berusia lebih tua terdapat
penurunan aktivitas mitokondria di sel- sel otot sebesar 35%,hal ini berhubungan
dengan peningkatan kadar lemak di otot sebesar 30% dan memicu terjadinya
resistensi insulin (Trisnawati dan Setyorogo, 2013; Irawan, 2010).
Berdasarkan kelompok jenis kelamin kejadian DM tipe 2 pada perempuan
lebih tinggi dari pada laki- laki. Data ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan
oleh Irawan (2010), dimana persentase DMpada perempuan lebih tinggi dari pada
laki- laki. Dalam hal ini perempuanlebih berisiko mengidap DM karena secara
fisik perempuan memiliki peluang peningkatan indeks masa tubuh yang lebih
membuat distribusi lemak tubuh menjadi mudah terakumulasi akibat proses
hormonal sehingga wanita berisiko menderita DM tipe 2 (Irawan, 2010).
Dari hasil penelilitian yang dilakukanJelantik dan Haryati (2014) juga
menunjukkan penyakit DM sebagian besar ditemui pada perempuan dibandingkan
laki–laki. Hal ini disebabkan karena pada perempuan memiliki LDL atau
kolesterol jahat tingkat trigliserida yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki–
laki dan juga terdapat perbedaan dalam melakukan semua aktivitas dan gaya
hidup sehari–hari, dimana hal tersebut merupakan salah satu faktor risiko
terjadinya penyakit diabetes mellitus. Jumlah lemak pada laki–laki dewasa rata–
rata berkisar antara 15–20% dari berat badan total dan pada perempuan sekitar
20–25%. Jadi peningkatan kadar lipid (lemak darah) pada perempuan lebih tinggi
dibandingkan pada laki-laki, sehingga faktor risiko terjadinya DM pada
perempuan 3-7 kali lebih tinggi dibandingkan pada laki–laki yaitu 2-3 kali
(Soeharto, 2003 dalam Jelantik dan Haryati, 2014).
Peningkatan asam lemak bebas meningkatkan pula distribusi asam lemak
di hati. Hal tersebut meningkatkan proses glukoneogenesis, menghambat ambilan
serta penggunaan glukosa di otot. Akumulasi trigliserida di hati dan di otot akan
mengakibatkan resistensi insulin. Selain itu jaringan lemak ternyata menghasilkan
beberapa sitokin dan hormon yang menghambat kerja insulin (Jalal, dkk., 2010;
4.1 Penggunaan Obat Antidiabetik
Frekuensi penggunaan obat antidiabetik pada pasien DM tipe 2 di instalasi
rawat inap RSUP H. Adam Malik periode bulan Agustus sampai Desember 2014
dapat dilihat pada Tabel 4.2.
Tabel 4.2 Frekuensi penggunaan obat antidiabetik pada pasien DM tipe 2 di
instalasi rawat inap RSUP H. Adam Malikperiode bulan Agustus sampai Desember 2014
No Nama obat Jumlah
pasien
Total pasien
Persentase (%)
1 Antidiabetik Parenteral 1) Novorapid 2 Antidiabetik Oral
1) Metformin
Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui penggunaan obat antidiabetik,
yakni penggunaan antidiabetik parenteral lebih banyak dari pada antidiabetik oral.
Data ini juga sejalan dengan hasil penelitian Rumpuin (2013) yang menemukan
terapi dengan obat antidiabetik untuk DM tipe 2 pada pasien rawat inap di rumah
sakit yang paling banyak digunakan adalah injeksi insulin.
Pada Tabel 4.2 diketahui antidiabetik parenteral yang paling sering
digunakan adalah novorapid. Novorapid merupakan insulin aspart yang memiliki
kerja cepat, yakni awal kerja 15 sampai 30 menit, puncak kerja 1 sampai 2 jam
dan lama kerjanya 5-6 jam (Dipiro, et al., 2008).
Alasan pengguaan antidiabetik parenteraldikarenakan terapi antidiabetik
terapi insulin sebelumnya. Selain itu pasien jugamemiliki kondisi yang
membutuhkan terapi insulin seperti infeksi berat, tindakan pembedahan, gangguan
fungsi ginjal.
Seperti halnya yang dikemukakan oleh Ditjen Bina Farmasi dan Alkes
(2005) insulin diindikasikan untuk penderita DM tipe 2 tertentu, kemungkinan
juga membutuhkan terapi insulin apabila terapi lain yang diberikan tidak dapat
mengendalikan kadar glukosa darah, keadaan stres berat, seperti pada infeksi
berat, tindakan pembedahan, infark miokard akut atau stroke, Ketoasidosis
diabetik, sindroma hiperglikemia, Gangguan fungsi ginjal atau hati yang berat.
Pada Tabel 4.2 dapat diketahui juga antidiabetik oral yang paling sering
digunakan adalah metformin. Metformin merupakan obat antidiabetes oral
golongan biguanid. Biguanid paling sering diresepkan untuk pasien yang
hiperglikemia disebabkan sindrom resistensi insulin. Metformin berguna dalam
pencegahan diabetes tipe 2 yaitu terjadinya infeksi baru diabetes tipe 2 pada paruh
baya, penderita obesitas dengan gangguan toleransi glukosa dan hiperglikemia.
Golongan biguanid ini mempunyai efek menurunkan kadar gula darah yang
meningkat pada penderita DM, tetapi tidak meningkatkan sekresi insulin.
Penurunan kadar gula darah ini disebabkan oleh peningkatan asupan glukosa ke
otot, penurunan glukoneogenesis dan penghambatan absorbsi glukosa disaluran
cerna. Metformin meningkatkan sensitivitas insulin dihati dan jaringan
periferal(otot). Mekanisme pasti bagaimana metformin dapat meningkatkan
sensitivitas insulin masih diteliti. Efeknya ialah turunnya kadar gula darah dan
penurunan berat badan, karena bersifat menekan nafsu makan (Dipiro, et al.,
Pada penelitian ini diperoleh pasien DM tipe 2 dengan atau tanpa
komplikasi yaitu dapat dilihat pada Tabel 4.3.
Tabel 4.3Kategori pasien DM tipe 2 dengan atau tanpa komplikasi yang diperoleh
dalam penelitian ini yang dirawat di instalasi rawat inap RSUP H. Adam Malik periode bulan Agustus sampai Desember 2014
No Dengan Komplikasi Tanpa
Komplikasi
6 Congestive Heart Failure (CHF)
5 13 2 5
7 Diabetes Neuropati 2 5 1 3
8 Hipertensi + Diabetes Nefropati+ CHF
2 5 1 3
9 Diabetes Retinopati 1 3 0 0
Total 39 100 13 33
4.2 Identifikasi Drug Related Problems
Hasil identifikasi masing-masing DRPs dapat dilihat pada Tabel 4.4.
Tabel 4.4 DRPs pada pasien DM tipe 2 di instalasi rawat inap RSUP H. Adam
Malik pada bulan Agustus sampai Desember 2014
No Kategori DRPs
Keterangan:DRPs (+): terjadiDRPs
DRPs (-) : tidak terjadi DRPs
Pada Tabel 4.4 dapat diketahui kategori DRPs yang terjadi pada pasien
DM tipe 2 di instalasi rawat inap RSUP H. Adam Malik adalah indikasi tanpa
obat terjadi pada 5 pasien (13%), obat tanpa indikasi terjadi pada 3 pasien (8%)
pasien yang mengalami 2 kategori DRPs, sehingga jumlah seluruh pasien yang
mengalami DRPs adalah 13 pasien (33%) dari 39 pasien.
Gambaran DRPs yang terjadi pada pasien DM tipe 2 dengan atau tanpa
komplikasi yang dirawat di instalasi rawat inap RSUP H. Adam Malik periode
bulan Agustus sampai Desember 2014 dapat dilihat pada Tabel 4.5.
Tabel 4.5 Gambaran Kejadian DRPs pada pasien DM tipe 2 dengan atau tanpa
komplikasi di instalasi rawat inap RSUP H. Adam Malik periode bulan Agustus sampai Desember 2014
DM tipe 2
Mekanisme Solusi Indikasi tanpa
1 Antidiabetik
KGD 358 pasien di atas normal, pasien
1 Antidiabetik
Kondisi: KGD pasien di atas normal, yaitu: pasien di atas normal, pasien
1 Antidiabetik
Kondisi: KGD pasien di atas normal, yaitu: pasien di atas normal, pasien
1 Antidiabetik
DM tipe 2 + Hipertensi
1 Antidiabetik
Kondisi: KGD pasien di atas normal, yaitu: pasien di atas normal, pasien gejala - gejala hipoglikemia dan pengaturan dosis obat serta mengatur waktu
1 Paracetamol
Kondisi:
1 Antidiabetik
(insulin) pasien di bawah normal, tidak
1 Paracetamol
DM tipe 2 + Ulkus Diabetikum
1 Siprofloksasin
dan Sukralfat rutin dan bila KGD meningkat
Keterangan = KGD: Kadar gula darah TD: tekanan darah KGDs: kadar gula darah sewaktu HR: Heart rate KGD2jpp: kadar gula darah 2 jam post prandial
KGDp: kadar gula darah puasa
4.2.1 Indikasi tanpa obat
Kejadian tidak mendapatkan terapi obat sesuai indikasi pada pasien DM
tipe 2 di instalasi rawat inap RSUP H. Adam Malik periode bulan Agustus sampai
Desember 2014 terjadi pada 5 pasien yaitu pada keadaan pasien yang menderita
Menurut American Diabetes Association (ADA) kriteria diagnosis DM
adalah HbA1C:≥6,5 mg/dL, KGDp ≥126 mg/dL, dan KGD 2jpp ≥200 mg/dL
sementara target KGD adalah KGDp80-130 mg/dL dan KGD 2jpp ≤ 180 mg/dL.
Menurut Soegondo (1995) kriteria pengendalian DM adalah KGDp baik: 80-109
mg/dL, sedang: 110-125 mg/dL, buruk: > 126 mg/dL; KGD 2jpp baik: 110-114
mg/dL, sedang:145-175 mg/dL, buruk: ≥ 180 mg/dL, dan berdasarkanclinical
pathway RSUP H. Adam Malik KGDp yang diharapkan adalah 80-120 mg/dL dan
KGD 2jpp adalah < 200 mg/dL.
Berdasarkan hasil pemeriksaan KGD, pasien memiliki KGDp dan KGD
2jpp diatas normal tetapi tidak mendapatkan terapi. Dengan demikian apabila
KGD pasien di atas normal pasien harus mendapatkan terapi.
4.2.2 Obat tanpa indikasi
Drug related problems kategori obat tanpa indikasi pada pasien DM tipe 2
di instalasi rawat inap RSUP H. Adam Malik periode bulan Agustus sampai
Desember 2014 dapat dilihat pada Tabel 4.6.
Tabel 4.6 Obat tanpa indikasi pada pasien DM tipe 2 di instalasi rawat inap RSUP H. Adam Malik periode bulan Agustus sampai Desember 2014
No Peneyebab Obat
Jumlah Pasien Persentase (%) 1 Penggunaan
obat tidak sesuai dengan kondisi pasien
1. Paracetamol
Kondisi: pasien tidak mengalami demam dan nyeri tetapi diberi paracetamol.
2. Insulin
Kondisi: pasien memiliki KGD 69 mg/dL tetapi diberi insulin sehingga KGD menjadi 55 mg/dL.
2
1
67
33
Total 3 100%
Berdasarkan Tabel 4.6dapat diketahui mendapatkan terapi obat yang tidak
sampai Desember 2014, yakni mendapatkan terapi paracetamol terjadi pada 2
pasien (67%)dan insulinterjadi pada 1 pasien (33%).
Pada penelitian ini ditemukan pasien mendapatkan terapi paracetamol
tetapi pasien tidak mengalami demam maupun nyeri. Paracetamol merupakan obat
bebas yang banyak digunakan sebagai analgesik-antipiretik, walaupun demikian
pengguanaan paracetamol dapat memberikan efek hepatotoksisitas, sehingga
sebaiknya paracetamol diberikan seperlunya saja(Gunawan, 2007).
Pada penelitian ini ditemukan jugapasien yang memiliki KGD dibawah
normal yakni 69 mg/dl tetapi mendapatkan terapi insulin sehingga terjadi
hipoglikemia (KGD: 55 mg/dl), sementara menurut ADA target KGD adalah
KGDp 80-130 mg/dL dan KGD 2jpp ≤ 180 mg/dL dan berdasarkan clinical
pathway RSUP H. Adam Malik target KGDp: 70–120 mg/dL dan KGD 2jpp ≤
200 mg/dL. Dengan demikian ketika KGDdi bawah normal pasien tidak
perludiberi insulin.
4.2.3 Interaksi Obat
Drug related problems kategori interaksi obat yang terjadi pada pasien
DM tipe 2 di instalasi rawat inap RSUP H. Adam Malik periode bulan Agustus
Tabel 4.7 Interaksi obat pada pasien DM tipe 2 di instalasi rawat inap RSUP H. Adam Malik periode bulan Agustus sampai Desember 2014
No Penyebab Obat
1) Insulin dan Furosemida 2) Insulin dan Kaptopril 3) Furosemida dan Bisoprolol 4) Siprofloksasin dan Sukralfat 5) Metilprednisolon dan Amlodipin 6) Metronidazol dan Paracetamol
2
Pada Tabel 4.7 dapat diketahui interaksi obat terjadi pada 7 pasien dari
penelitian yang dilakukan periode bulan Agustus sampai Desember 2014 dan
dapat diketahui interaksi obat yang terjadi adalah interaksi antara insulin dan
furosemida yakni pada 2 pasien (29%), interaksi antara insulin dan kaptopril
terjadi pada 1 pasien (14%), interaksi antara furosemidadan bisoprolol terjadi
pada 1 pasien (14%), interaksi antara siprofloksasin dan sukralfat pada 1 pasien
(14%), interaksi antara metilprednisolon dan amlodipin pada 1 pasien (14%) dan
interaksi antara metronidazol dan paracetamol pada 1 pasien (14%).
Mekanisme interaksi obat terbagi menjadi tiga jenis, yaitu interaksi
farmasetik, interaksi farmakokinetik, dan interaksi farmakodinamik. Interaksi
farmasetik terjadi di luar tubuh (sebelum obat diberikan) antara obat yang tidak
dapat dicampur (inkompatibel). Interaksi farmakokinetik terjadi ketika suatu obat
mempengaruhi absorbsi, distribusi, metabolisme dan ekskresi (ADME) dari obat
lainnya. Sedangkan interaksi farmakodinamik terjadi antara obat yang memiliki
efek farmakologis, antagonis atau efek samping yang hampir sama(Baxter, 2008;
Tingkat keparahan interaksi sangat penting dalam menilai risiko vs
manfaat terapi alternatif. Dengan penyesuaian dosis yang tepat atau modifikasi
jadwal penggunaan obat, efek negatif dari kebanyakan interaksi dapat dihindari.
Tiga tingkat keparahan didefinisikan sebagai:
a. Minor, efek yang terjadi tidak signifikan mempengaruhi hasil terapi.
Pengobatan tambahan biasanya tidak diperlukan. Meminimalkan resiko: menilai
risiko dan mempertimbangkan obat alternatif, mengambil langkah-langkah untuk
mengindari risiko interaksi dan/atau membentuk rencana pemantauan.
b. Moderate, efek yang terjadi cukup signifikan secara klinis, dapat menyebabkan
penurunan status klinis pasien. Pengobatan tambahan, rawat inap, atau
diperpanjang dirawat di rumah sakit mungkin diperlukan. Biasanya menghindari
kombinasi atau menggunakan hanya dalam keadaan khusus.
c. Mayor, efek yang terjadi sangat signifikan secara klinis, terdapat probabilitas
yang tinggi, berpotensi mengancam jiwa atau dapat menyebabkan kerusakan
permanen. Risiko interaksi melebihi manfaat. Hindari kombinasi. (Drug.com,
2015).
1. Insulindan Furosemida
No Interaksi Obat Mekanisme Tingkat Keparahan 1 Insulin dan Furosemida Tidak diketahui Moderate
Pada penelitian ini, dapat diketahui interaksi obat antara insulin dan
furosemida terjadi pada 2 pasien (29%). Interaksi antara insulin dan furosemida
dapat menurunkan efektivitas insulin. Hal ini terlihat dari hasil pemeriksaan KGD
pasien pada saat penggunaan furosemida bersamaan dengan insulin tidak terjadi
Furosemida merupakan salah satu obat golongan diuretik loop yang biasa
digunakan untuk gangguan kardiovaskular, seperti hipertensi dan udem. Diuretik
digunakan sebagai terapi lini kedua pada hipertensi dengan penyakit DM yang
dikombinasikan dengan Angiotensin Converting Enziminhibitor (ACE inhibitor)
atau Angiotensin II Reseptor Blocker (ARB). Selain itu, furosemida sering
digunakan untuk udem yang sering terjadi pada pasien ginjal ataupun hipertensi.
Hal ini dikarenakan obat ini bekerja dengan cara meningkatkan pengeluaran
cairan didalam tubuh melalui urin. Pengeluaran cairan meningkat disebabkan
karena penghambatan reabropsi Na dan air di ginjal (Dipiro, et al., 2008).
Mekanisme interaksi antara insulin dan furosemida belum diketahui secara
pasti, namun literatur menyatakan efek samping dari diuretik loop adalah
hiperglikemia. Hiperglikemia terjadi karena diuretik dapat menyebabkan toleransi
glukosa. Hal inilah yang mungkin menyebabkan interaksi antara furosemida
dengan insulin sehingga perlu dilakukan monitoring kadar glukosa dalam darah
secara rutin dan bila kadar glukosa darah meningkat dengan dosis penggunaan
insulin yang biasanya, maka peningkatan dosis insulin diperlukan (Baxter, 2008;
Hansten, 1973; Drug.com, 2015).
2. Insulin dan Kaptopril
No Interaksi Obat Mekanisme Tingkat Keparahan 1 Insulin dan Kaptopril Farmakodinamika Moderate
Kaptopril adalah obat golongan angiotensin converting
enziminhibitor(ACE inhibitor)yang merupakan obat pilihan pertama dalam
pengobatan hipertensi pada pasien DM dikarenakan efektivitas ACE inhibitor
yang dapat melindungi ginjal dengan dilatasi arteriol eferen sehingga akan
perubahan angiotensin I menjadi angiotensin II, angiotensin II merupakan
vasokonstriktor poten yang juga merangsang sekresi aldosteron. ACE inhibitor
juga memblok degradasi bradikinin dan merangsang sintesa zat-zat yang
menyebabkan vasodilatasi, termasuk prostaglandin E2 dan prostasiklin.
Peningkatan bradikinin meningkatkan efek penurunan tekanan darah dari ACE
inhibitor, selain itu ACE inhibitor juga memiliki efek terhadap penurunan kadar
gula darah dengan meningkatkan sensitivitas insulin (Dipiro, et al., 2008).
Penggunaan kaptopril bersama dengan insulin dapat terjadi interaksi yang
bersifat sinergis sehingga berpotensi menyababkan hipoglikemia. Pada penelitian
ini interaksi antara insulin dan kaptopril terjadi pada 1 pasien (14%), hal ini
terlihat dari hasil pemeriksaan KGD pasien yang menunjukkkan terjadinya
hipoglikemia, yakni KGDp awal 138 mg/dLmenjadi 30 mg/dL. Dengan demikian,
dalam hal ini perlu monitoring kadar gula darah pasien serta memperhatikan
gejala2 hipoglikemia (seperti: pusing, mengantuk, mual, lapar, tremor, gelisah,
lemah, detak jantung cepat) dan pengaturan dosis obat yang diberikan serta
mengatur waktu pemberian obat agar tidak terjadi interaksi obat (Baxter, 2008;
Dipiro, et al., 2008; Drug.com, 2015).
3. Furosemidadan Bisoprolol
No Interaksi Obat Mekanisme Tingkat Keparahan
1 Furosemida dan Bisoprolol Farmakodinamika Moderate
Bisoprolol merupakan obat golongan β-bloker kardioselektif yang
menghambat reseptor β-1 pada jantung dan ginjal. Perangsangan reseptor β-1
menaikkan denyut jantung, kontraktilitas, dan pelepasan renin. Bisoprolol dapat
menurunkan denyut jantung, kontraksi dan menurunkan pelepasan renin.Renin
dalam lintasan metabolisme sistem RAA (Renin-Angiotensin-Aldosteron) yang
mengendalikan tekanan darah dan kadar air dalam tubuh. (Dipiro, et al., 2008).
Furosemidamerupakan obat golongan diuretik loop yang diindikasikan
untuk mengobati udem dan hipertensi. Hal ini dikarenakan furosemida bekerja
dengan cara meningkatkan pengeluaran cairan didalam tubuh melalui
urin.Interaksi yang terjadi antara furosemida dan bisoprolol adalah bisoprolol
meningkatkan kadar serum kalium dan furosemida menurunkan kadar serum
kalium yang dapat menyebabkan hipotensi dan memperlambat detak jantung.
Pada penenitian ini ditemukan interaksi antara furosemida dan bisoprolol terjadi
pada 1 pasien (14%), hal ini dapat dilihat dari hasil pemerikasaan tekanan darah
(TD) dan Heart rate (HR) yang menunjukkan terjadinya hipotensi yakni TD dari
140/80 mmHg menjadi 80/60 mmHg dan penurunan HR dari 80x/i menjadi 60x/i.
Dengan demikian, dalam hal ini perlu pengaturan dosis obat yang diberikan,
mengatur waktu pemberian obat atau butuh pemeriksaan tekanan darah lebih
sering (Drug.com, 2015; Dipiro, et al., 2008).
4. Siprofloksasin dan Sukralfat
No Interaksi Obat Mekanisme Tingkat Keparahan
1 Siprofloksasin dan Sukralfat Farmakokinetika pada fase absorbsi
Moderate
Siprofloksasin adalah antibiotik golongan fluorokuinolon yang
mempunyai spektrum luas, aktif terhadap bakteri gram negatif maupun gram
positif. Antibiotik ini bekerja dengan cara menghambat dua tipe enzim II
topoisomerase yaitu DNA Gyrase dan topoisomerase IV. Enzim topoisomerase II
berfungsi menimbulkan relaksasi pada DNA yang mengalami positive
replikasi DNA. Topoisomerase IV berfungsi dalam pemisahan DNA baru yang
terbentuk setelah proses replikasi DNA bakteri selesai. Antibakteri ini digunakan
untuk pengobatan infeksi saluran kemih (ISK), saluran cerna, saluran nafas,
tulang dan sendi, kulit dan jaringan lunak, penyakit yang ditularkan melalui
hubungan seksual (uretritis dan servisitis gonorea) (Gunawan, 2009).
Sukralfat merupakan salah satu obat gastrointestinal. Dalam hal ini
sukralfat dapat membentuk kompleks protein pada permukaan tukak yang
melindunginya terhadap HCl, pepsin dan empedu. Kompleks ini dapat bertahan
kurang lebih 6 jam di sekitar tukak, selain itu juga dapat menetralkan asam,
menahan kerja pepsin dan mengadsorpsi asam empedu. Penggunaan sukralfat
bersamaan dengan siprofloksasin dapat mengurangi penyerapan siprofloksasin di
saluran cerna sehingga akan mengurangi efektivitasnya. Pada penelitian ini
interaksi antara sukralfat dan siprofloksasin terjadi pada 1 pasien (14%). Dengan
demikian untuk menghindari terjadinya interaksi, siprofloksasin harus diberikan 2
jam sebelum atau 6 jam setelah pemberian sukralfat (Dipiro, et al., 2008;
Drug.com, 2015; Medscape, 2015; Tatro, 2003).
5. Metilprednisolon dan Amlodipin
No Interaksi Obat Mekanisme Tingkat Keparahan
1 Metilprednisolon dan Amlodipin Farmakokinetika fase metabolisme
Moderate
Pada penelitian ini interaksi antara metilprenisolon dan amlodipin terjadi
pada 1 pasien (14%). Metilprednisolon adalah kortikosteroid yang berkerja
dengan menekan pembentukan, pelepasan dan aktivitas mediator peradangan
termasuk prostaglandin, kinins, histamin, enzim liposomal dan sistem
antihipertensi golongan penghambat kanal kalsium. Kalsium merupakan elemen
bagi pembentukan tulang dan fungsi otot kerangka dan otot polos jantung/dinding
ateriole, untuk kontraksi semua otot diperlukan ion kalsium intrasel bebas. Kadar
ion kalsium diluar sel beberapa ribu kali lebih besar daripada di dalam sel. Pada
keadaan tertentu, misalnya akibat rangsangan akan terjadi depolarisasi membran
sel, yang menjadi permeabel bagi ion kalsium sehingga banyak ion kalsium yang
melintasi membran dan masuk kedalam sel. Dalam hal ini, pada kadar kalsium
intrasel tertentu sel mulai berkontraksi, otot jantung dan arteriole menciut
(konstriksi). Amlodipin akan menghambat pemasukan ion kalsium ekstrasel ke
dalam sel dan dengan demikian dapat mengurangi penyaluran impuls dan
kontraksi myocard serta dinding pembuluh darah.Obat ini dimetabolisme di hati
oleh CYP3A4. Penggunaan metilprednisolon bersamaan dengan amlodipin akan
menurunkan efek amlodipin dengan mempengaruhi metabolisme CYP3A4.Dalam
hal ini metilprednisolon menginduksi isoenzim ini sehingga menurunkan efek
amlodipin. Dengan demikan perlu penyesuaian dosis, pemantauan atau mengatur
waktu pemberian sehingga tidak terjadi interaksi (Dipiro, et al., 2008; Drug.com,
2015; Medscape, 2015; Tjay, 2007).
6. Metronidazol dan Paracetamol
No Interaksi Obat Mekanisme Tingkat
Keparahan 1 Metronidazol dan Paracetamol Farmakokinetika fase
metabolisme
Minor
Pada penelitian ini interaksi antara metronidazol dan paracetamol terjadi
pada 1 pasien (14%). Metronidazol adalah antibiotika yang bekerja dengan
memasuki sel bakteri atau protozoa dan mengganggu sintesis DNA dan