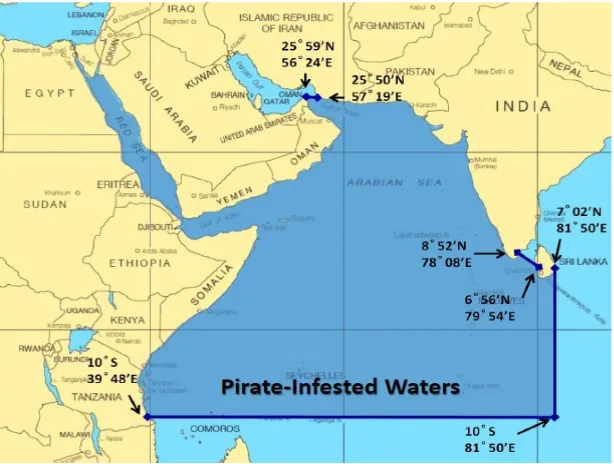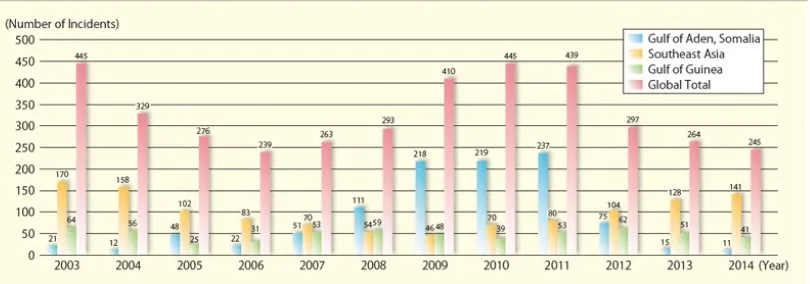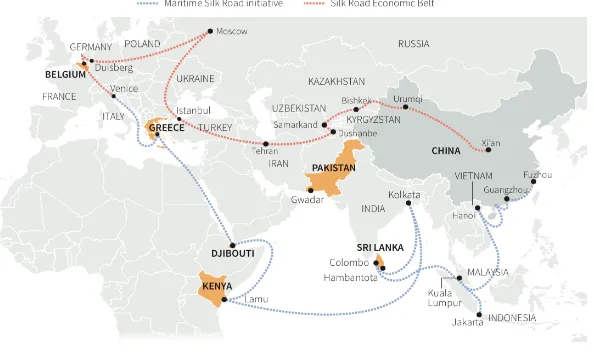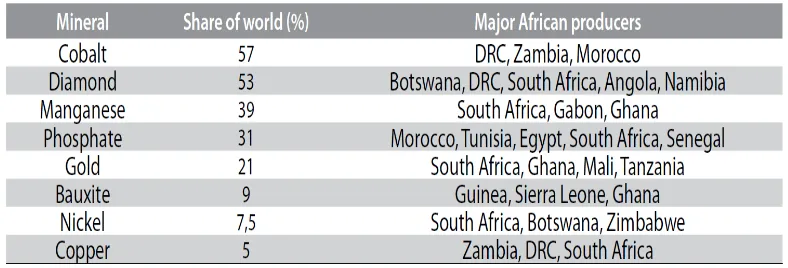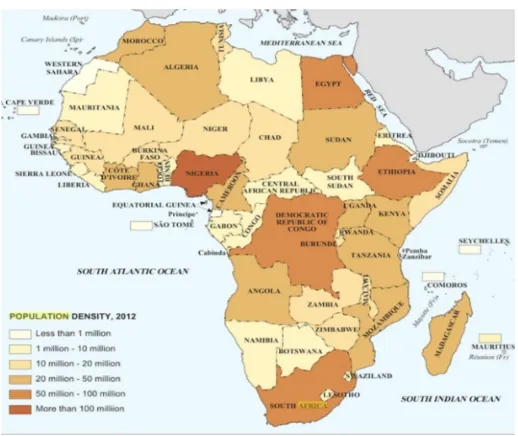KEPENTINGAN JEPANG MEMBANGUN
PANGKALAN MILITER DI DJIBOUTI 2011
Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Oleh:
Muhammad Darmawan Ardiansyah
1112113000007
PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
2017
ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang kepentingan Jepang membangun pangkalan militer di Djibouti pada 2011. Aksi pembajakan kapal yang terjadi di sekitar perairan Somalia dan Teluk Aden yang mencapai puncaknya pada 2008 menjadi latar belakang penting bagi pembangunan pangkalan tersebut. Disaat pembajakan kapal di sekitar perairan Somalia dan Teluk Aden mulai menunjukkan penurunan, terjadi peningkatan pembajakan kapal di sekitar Selat Malaka pada 2014. Akan tetapi, Jepang tidak membangun pangkalan militer di sekitar perairan tersebut seperti yang dilakukannya di Djibouti. Dipilihnya Djibouti sebagai lokasi pembangunan pangkalan militer pertamanya secara tidak langsung memperlihatkan bahwa wilayah perairan ini sangat penting bagi Jepang. Penelitian ini bermaksud untuk memahami lebih jelas mengenai tujuan dan hal-hal apa saja yang mendorong Jepang untuk membangun pangkalan militer di Dijibouti. Adapun skripsi ini akan berfokus pada kepentingan Jepang membangun pangkalan militer di Djibouti.
Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode ini digunakan untuk memberikan jawaban yang tepat dari analisa yang telah dilakukan, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai skripsi ini. Sedangkan kerangka pemikiran utama yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori Neorealisme dan konsep kepentingan nasional yang digunakan untuk menganalisa permasalahan penelitian, sehingga didapat jawaban yang tepat. Dalam konsep kepentingan nasional menurut Neorealisme, self-help menjadi upaya yang sangat penting bagi sebuah negara untuk tetap survive
Jepang membangun pangkalan militernya di Djibouti di tengah krisis global melanda dan terjadinya peningkatan intensitas pembajakan kapal di perairan Somalia dan Teluk Aden.
Kata kunci: Jepang, Djibouti, survival, self-help, relative
A. Kebijakan Pertahanan Jepang Pasca Perang Dingin………...
B. Kebijakan Pertahanan Jepang Pasca 11 September…... 24
32
BAB III PEMBANGUNAN PANGKALAN MILITER JEPANG DI
DJIBOUTI
A. Kondisi Geopolitik di Djibouti………
B. Aksi Pembajakan Kapal di Teluk Aden……...………...
C. Pembangunan Pangkalan Militer Jepang di Djibouti Pada
2011……….
1. Insiden Pembajakan Kapal Jepang oleh Perompak
Somalia……….
2. Respon Jepang Terhadap Pembajakan Kapal di Teluk
Aden……….
3. Respon Cina Terhadap Aksi Pembajakan Kapal di Teluk
Aden………...
BAB IV KEPENTINGAN JEPANG MEMBANGUN
PANGKALAN MILITER DI DJIBOUTI
A. Kepentingan Jepang Terhadap Stabilitas Keamanan di
Perairan Teluk Aden………... 64
B. Kerjasama Ekonomi: Kunci Peningkatan Relative Power Jepang……….
C. Upaya Balancing Jepang Terhadap Cina di Asia Timur…… 70
82
BAB V PENUTUP
Kesimpulan ... 89
DAFTAR TABEL
Tabel IV.B.1 Komoditas Utama Mineral di Afrika………..
Pada 2015……….. 40
DAFTAR GAMBAR
Gambar III.A.1 Letak Djibouti Berdasarkan Jalur Perdagangan Minyak
Gambar III.B.2 Peta Aksi Pembajakan Kapal Oleh Perompak Somalia……...
Gambar III.C.3.3 Peta Jalur Maritime Silk Road Cina……….. Gambar IV.B.4 Peta Persebaran Sumber Daya Alam di Afrika………...
Gambar IV.B.5 Peta Kepadatan Populasi Penduduk di Afrika………. 44
59
75
80
DAFTAR GRAFIK
Grafik III.B.2.2 Data Pembajakan Kapal di Teluk Aden dan Perairan
DAFTAR SINGKATAN
ABE African Business Education
CGPCS Contact Group on Piracy off the Coast of Somalia
CTF 151 Combined Task Force 151
DCOC Djibouti Code of Conduct
DK PBB Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
EUNAVFOR European Union Naval Force
GATT General Agreement on Tariffs and Trade
GDP Gross Domestic Product
IMF International Monetary Fund
IRTC Internationally Recommended Transit Corridor
NATO North Atlantic Treaty Organization
ODA Official Development Assistance
PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa
PKO Peacekeeping Operation
SDF Self-Defense Force
SHADE Shared Awareness and Deconfliction Mechanism
SLOC Sea Lines of Communication
TICAD Tokyo International Conference on African Development
TNG Somalia Transitional Federal Government of Somalia
UNODC United Nations Office on Drugs and Crime
WMD Weapon of Mass Destruction
WTO World Trade Organization
BAB I
PENDAHULUAN
Skripsi ini menganalisis kepentingan Jepang membangun pangkalan militer di
Djibouti pada 2011. Tingginya angka pembajakan kapal di perairan Somalia dan
Teluk Aden telah menjadi perhatian serius berbagai negara, terutama Jepang. Demi
merespon hal tersebut, pada 2009 pemerintah Jepang mengirimkan kapal perangnya
ke perairan Somalia dan Teluk Aden untuk memberantas perompakan kapal di bawah
naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Keseriusan Jepang dalam memberantas
perompak ditunjukkan dengan pembangunan pangkalan militer di Djibouti pada
2011. Akan tetapi, Jepang tidak melakukan hal serupa di perairan Asia Tenggara.
Padahal tingkat aksi pembajakan kapal di perairan ini juga tinggi. Selain itu,
pembangunan pangkalan militer ini merupakan pembangunan pangkalan militer
Jepang yang pertama setelah kekalahannya pada Perang Dunia II.
Di bawah kepemimpinan Konoe Fumimora, Jepang menerapkan kebijakan
luar negeri berdasarkan konsep diplomasi Hakko Ichiu periode 1937-1939.12
Kebijakan inilah yang melatar belakangi Jepang melakukan ekspansi kekuasaan di
wilayah Asia. Sampai pada akhirnya kota Hiroshima dan Nagasaki menjadi sasaran
target bom atom yang dilancarkan oleh Amerika Serikat.3 Serangan itu memberikan
kekalahan telak yang menyebabkan Jepang harus menyerah kepada sekutu. Sejak
kekalahan tersebut, Jepang mulai merubah haluan kebijakan luar negerinya.
1 Marcus Willensky, “Japanese Fascism Revisited.” Stanford Journal of East Asian Affairs. Vol. 5, No. 1, (April, 2005): 69.
2 Hakko Ichiu adalah konsep diplomasi yang digunakan sebagai pijakan Jepang dalam menentukan arah kebijakan luar negerinya pada masa PD II. Inti dari ide tersebut yaitu membentuk perdamaian dunia di bawah naungan Jepang. Hal inilah yang dijadikan Jepang sebagai justifikasi invasinya ke negara-negara Asia. Sumber: Marcus Willensky, “Japanese Fascism Revisited.”
Berdasarkan Postdam Declaration yang diatur dalam pasal 11 menyatakan bahwa:
Jepang diizinkan untuk mempertahankan industri yang menopang perekonomiannya dan diberi keleluasaan membayar ganti rugi perang dalam bentuk lain, lantas bukan berarti hal ini memungkinkan Jepang mempersenjatai diri lagi. Demi tujuan tersebut, akses terhadap bahan baku industri diizinkan. Pada akhirnya, Jepang juga diizinkan untuk berpartisipasi dalam perdagangan dunia.4
Maka dari itu, kebijakan luar negeri Jepang paska PD II lebih diprioritaskan dalam
sektor pembangunan ekonomi.
Untuk mewujudkan hal tersebut dicetuskanlah Yoshida Doctrine oleh Shigeru Yoshida.5 Poin utama dari doktrin ini menyatakan bahwa ekonomi menjadi
konsentrasi utama dari politik luar negeri Jepang untuk membangun kembali
negaranya yang luluh lantak akibat perang. Sehingga dalam setiap perumusan
kebijakan luar negeri pemerintahan Yoshida, doktrin ini menjadi acuan utama demi
mencapai kepentingannya dalam politik internasional.6
4 Government of Japan, “Postdam Declaration,” National Diet Library, 26 Juli 1945, [dokumen resmi on-line]; tersedia di http://www.ndl.go.jp/constitution/e/etc/c06.html; Internet; diunduh pada 30 Juli 2016.
5 David M. Potter, Evolution of Japan’s Postwar Foreign Policy, dalam Laura Rubio Diaz Leal, ed., China y Japon: Modernizacion Economica, Cambios Politicos y Posicionamiento Mundial (Mexico City: Editorial Castillo, 2008), 6.
Colombo Plan menjadi proyek awal dari penerapan Yoshida Doctrine dalam kebijakan luar negeri Jepang.7 Menurut Huang, dengan terjalinnya kerjasama antara
Jepang dan negara-negara tersebut (berkembang), dapat meningkatkan citra positif
Jepang di mata internasional.8 Yang menyebabkan kepercayaan dunia internasional
terhadap Jepang semakin meningkat.
Selain berfokus pada pembangunan sektor ekonomi, Jepang juga berusaha
untuk memperbaiki citranya yang buruk pasca PD II.9 Hal ini diwujudkan dengan
bergabungnya Jepang menjadi anggota PBB pada 18 Desember 1956 di masa
pemerintahan Ichiro Hatoyama.10 Bergabungnya Jepang dalam PBB menunjukkan
bahwa Jepang memiliki komitmen yang tinggi untuk menjaga perdamaian dan
keamanan internasional.
Berakhirnya era Perang Dingin memberikan kesempatan bagi Jepang untuk
meningkatkan pengaruhnya dalam politik internasional. Di bawah pemerintahan
Toshiki Kaifu, Jepang ingin menjadi pihak yang mengambil peran penting dalam
menjaga stabilitas dan keamanan khususnya di Asia.11
7 MOFA Japan, “History of Official Development Assistance,” [artikel resmi on-line]; tersedia di http://www.mofa.go.jp/policy/oda/summary/1994/1.html; Internet; diunduh pada 30 Juli 2016.
8 Meibo Huang, Policies and Practices of China’s Foreign Aid: A Comparison with Japan, dalam Japan’s Development Assistance: Foreign Aind and the Post-2015 Agenda (New York: Palgrave Macmillan, 2016), 139.
9 Bruce Stronach, Beyond The Rising Sun: Nationalism in Contemporary Japan (London: Praeger, 1995), 2.
10 MOFA Japan, “An Argument For Japan’s Becoming Permanent Member,” [artikel resmi on-line]; tersedia di http://www.mofa.go.jp/policy/q_a/faq5.html; Internet; diunduh pada 30 Juli 2016.
Hal di atas diwujudkan dengan dibuatnya sebuah rancangan undang-undang
yang bernama UN Peace Cooperation Bill yang diajukan ke parlemen pada Oktober 1990.12 Poin utama dari Rancangan Undang-Undang ini adalah agar pasukan Jepang
dapat ikut berkontribusi dalam peacekeeping operation yang dilakukan oleh PBB.13
Akan tetapi, parlemen Jepang menolak untuk menyetujui undang-undang tersebut, hal
ini diakibatkan adanya penolakan publik terhadap keterlibatan pasukan Jepang dalam
konflik internasional.14
Maka, dicetuskanlah kembali RUU yang bernama International Peace Cooperation Bill pada September 1991.15 Akan tetapi, RUU ini tidak langsung
disahkan oleh parlemen. Sampai pada akhirnya RUU ini disetujui pada 9 Juni 1992
dan disahkan pada 15 juni 1992 dengan nama InternationalPeace Cooperation Act di bawah pemerintahan Miyazawa Kiichi.16 Landasan hukum inilah yang menjadi awal
dari lahirnya landasan-landasan hukum lain terkait misi internasional yang dilakukan
oleh Self-Defense Force.
Salah satu landasan hukum penting yang menjadi dasar keterlibatan pasukan
Self-Defense Force dalam misi internasional adalah Law on Punishment of and
12 Inoguchi Takashi & Purnendra Jain, Japanese Foreign Policy Today, (New York: Palgrave, 2000), 127.
13 Christopher W. Hughes, Japan’s Security Agenda: Military, Economic, and Enviromental Dimensions, (Colorado: Lynne Rienner Publishers, 2004), 160.
14 Namzariga Adamy, Kebijakan PKO Jepang di Kamboja: Suatu Tinjauan Terhadap Perubahan Kebijakan Luar Negeri Jepang Paska Perang Dingin, Tesis, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004), 6.
15 Namzariga Adamy, Kebijakan PKO Jepang di Kamboja: Suatu Tinjauan Terhadap Perubahan Kebijakan Luar Negeri Jepang Paska Perang Dingin.
Measures against Acts of Piracy.17 Landasan hukum ini dibuat berdasarkan resolusi
Dewan Keamanan PBB nomor 1816.18 Tujuannya adalah untuk menanggulangi aksi
pembajakan kapal yang terjadi di perairan Somalia dan Teluk Aden.19
Tingginya angka pembajakan di perairan Somalia dan Teluk Aden membuat
negara-negara di dunia, termasuk Jepang sangat antusias dalam menumpas aksi
kriminal tersebut.20 Untuk pertama kalinya, pada 2007, kapal tanker Jepang yang
berbendera Panama dibajak di perairan ini. Total sejak 2007 sampai dengan Maret
2011 telah terjadi 10 kali pembajakan terhadap kapal Jepang.21
Berdasarkan Law on Punishment of and Measures against Acts of Piracy Jepang mengirimkan dua kapal perangnya yang membawa 400 personil pada 13
Maret 2009 untuk melakukan misi anti pembajakan di wilayah perairan teluk Aden
sekitar Somalia.22 Hal ini didukung oleh survei yang menunjukkan bahwa 60%
masyarakat Jepang mendukung kebijakan tersebut.23 Aksi ini juga didukung oleh
17 MOFA Japan, “Japan’s Actions Against Piracy Off the Coast of Somalia,” [artikel resmi on-line]; tersedia di http://www.mofa.go.jp/policy/piracy/ja_somalia_1210.html; Internet; diunduh pada 8 Agustus 2016.
18 Jade Lindley, Somali Piracy: A Criminological Perspective (New York: Routledge, 2016), 95.
19 Jennifer G. Cooke, “Piracy in the Gulf of Aden,” 2 Oktober 2008 [berita on-line]; tersedia di
https://www.csis.org/analysis/piracy-gulf-aden; Internet; diunduh pada 8 Agustus 2016.
20 Statista Analyst, “Number of Actual & Attempted Piracy Attacks in Somalia,” [artikel on-line]; tersedia di http://www.statista.com/statistics/250867/number-of-actual-and-attempted-piracy-attacks-in-somalia/; Internet; diunduh pada 5 Agustus 2016.
21 John Knott, “Piracy Off Somalia: An overview of catch and release, counter measures, trends, ransoms, hostages, rescues, recent developments appraised, and proposals for the future,” [berita on-line]; tersedia di http://www.hfw.com/Piracy-off-Somalia; Internet; diunduh pada 4 November 2015.
22 MOD Japan, “Dispatch of MSDF Vessels to Water off the Coast of Somalia,” [berita resmi on-line]; tersedia di http://www.mod.go.jp/e/jdf/no13/policy.html; Internet; diunduh pada 6 Agustus 2016.
http://www.japantimes.co.jp/news/2009/03/15/national/mission-backed-by-60-but-29-shun-Japanese Shipowners Association, Japan Seamen’s Union, serta beberapa Non Governmental Organization Jepang yaitu, Nippon Foundation dan Ocean Policy Research Foundation.24 Hal ini menunjukkan bahwa dinamika dalam negeri
mendukung penuh aksi Jepang dalam pemberantasan perompak di teluk Aden.
Dua tahun berikutnya, tepatnya 1 Juni 2011 Jepang secara resmi
mengoperasikan pangkalan militernya yang terletak di Djibouti. Dana sebesar 4,7
miliar yen atau $59 miliar dianggarkan untuk pembangunan fasilitas militer tersebut.
Pembangunan ini ditujukan untuk mendukung segala kegiatan yang dilakukan oleh
pasukan militer Jepang dalam melakukan aksi pemberantasan pembajakan kapal di
sekitar perairan teluk Aden dan Somalia.25
Operasi pemberantasan aksi pembajakan kapal yang dilakukan oleh Jepang di
perairan Somalia dan Teluk Aden memiliki dasar-dasar hukum yang kuat. Adapun
hukum-hukum tersebut diantaranya adalah Japan’s Basic Act on Ocean Policy yang disahkan pada April 2007. Terdapat dua pasal penting yang berkaitan dengan isu ini
yaitu, pasal 20 yang memuat tentang keamanan transportasi di lautan dan pasal 21
yang berisikan kewajiban negara untuk menjamin keamanan dan keselamatan
kapal-kapal Jepang di lautan.26
sdf-poll/; Internet; diunduh pada 6 Agustus 2016.
24 Harry N. Scheiber & Jin-Hyun Paik, Regions, Institutions, and Law of the Sea: Studies in Ocean Governance (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2013), 260.
25 MOD Japan, “Japanese Facility for Counter – piracy Mission in Djibouti,” [berita on-line]; tersedia di http://www.mod.go.jp/e/jdf/no22/topics.html#article02; Internet; diunduh pada 5 agustus 2016.
Kemudian dasar hukum yang ada dalam Basic Plan on Ocean Policy yang disusun pada 2008. Dalam penyusunan dasar hukum tersebut, pemerintah Jepang
secara tegas menyatakan bahwa perlu diambil tindakan untuk menekan aksi
pembajakan kapal dengan pembuatan kerangka hukum yang sesuai dengan hukum
internasional.27
Selanjutnya pasal 82 yang termuat dalam Self-Defense Force Law, yang menjadi dasar legitimasi Jepang untuk mengirimkan pasukannya memberantas
pembajakan kapal di teluk Aden.28 Kemudian diperkuat oleh Law on Punishment of
and Measures against Acts of Piracy yang disahkan pada 19 Juni 2009. Hal ini memungkinkan pasukan Jepang untuk bertindak lebih efektif dalam melakukan
operasi pembajakan kapal.29
Diresmikannya pangkalan militer pertama Jepang di Djibouti pada 2011 ini
sangat menarik sekali untuk dikaji. Pertama, terjadinya peningkatan pembajakan kapal di perairan Somalia dan Teluk Aden mendorong Jepang untuk membangun
pangkalan militer di perairan tersebut. Akan tetapi, Jepang tidak melakukan hal yang
serupa di perairan Asia Tenggara dan Selat Malaka. Padahal, perairan ini merupakan
wilayah yang paling rawan terjadinya aksi pembajakan kapal daripada perairan
27 Harry N. Scheiber & Jin-Hyun Paik, Regions, Institutions, and Law of the Sea: Studies in Ocean Governance, 261.
28 Yoneyuki Sugita, Japan Viewed from Interdisciplinary Perspectives: History and Prospects (Maryland: Lexington Books, 2015), 182.
Somalia dan Teluk Aden.30 Kedua, pembangunan pangkalan militer ini merupakan
pembangunan pangkalan militer Jepang yang pertama setelah kekalahannya pada
Perang Dunia II.31 Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kepentingan di balik
pembangunan pangkalan militer tersebut.
B. Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan pernyataan masalah di atas, penulis mengajukan pertanyaan
penelitian untuk dibahas dalam skripsi ini, yaitu:
Apa kepentingan Jepang membangun pangkalan militer di Djibouti pada
2011?
C. Tujuan dan Manfaat
Skripsi ini memiliki tujuan sebagai berikut, yaitu:
1) Mengetahui kepentingan Jepang dalam membangun pangkalan militer di
Djibouti, baik itu kepentingan ekonomi dan militer. Dalam hal ini mencoba
untuk memahami arah kebijakan pertahanan Jepang.
2) Mengetahui pengaruh aksi pembajakan kapal oleh perompak Somalia
terhadap stabilitas perekonomian Jepang.
30 Al Jazeera, “The Pirates of Southeast Asia,” [berita on-line]; tersedia di
http://www.aljazeera.com/news/2015/12/pirates-southeast-asia-151206061744642.html; Internet; diunduh pada 29 Januari 2017.
31 Alex Martin, “First Overseas Military Base Since WWII to Open in Djibouti,” [berita on-line]; tersedia di
3) Menganalisis dampak pembangunan pangkalan militer Jepang di Djibouti
terhadap stabilitas keamanan di kawasan Asia Timur.
Berdasarkan tujuan di atas, penulis mengharapkan bahwa skripsi ini dapat
menjadi salah satu referensi yang bermanfaat bagi peneliti yang memiliki ketertarikan
dan minat tinggi terhadap isu ekonomi dan militer Jepang.
D. Tinjauan Pustaka
Penelitian yang membahas mengenai perkembangan kebijakan pertahanan Jepang dan aksi pembajakan kapal di perairan Somalia dan Teluk Aden telah banyak sekali dipublikasikan, diantaranya:
Tesis yang ditulis oleh Mark C. Jackson yang berjudul “Rising Sun Over Africa: Japan’s New Frontier for Military Normalization.”
Secara garis besar tesis ini menjelaskan tentang hubungan Jepang dengan Afrika, terutama hubungan dalam aspek keamanan melalui
Tokyo International Conference on African Development (TICAD) dan peacekeeping operation. Jepang melihat bahwa Afrika dapat menjadi alternatif bagi Jepang untuk meningkatkan statusnya dalam sistem internasional, dari negara yang pasifis menjadi negara yang normal.32
Evolusi kebijakan pertahanan Jepang dan peningkatan aktivitas internasional oleh Japan Self-Defense Force menunjukkan bahwa adanya usaha Jepang meredefinisi kembali posisinya dalam sistem internasional. Kebutuhan Jepang terhadap sumber daya alam dari Afrika secara tidak langsung mendorong Jepang untuk meningkatkan kepentingan yang lain, yakni politik dan keamanan. Kepentingan tersebut digunakan untuk mengurangi pembatasan mengenai peran dan memberikan legitimasi bagi JSDF untuk terlibat aktif dalam misi internasional yang dilakukan oleh PBB.33
Persamaan yang dimiliki oleh tesis dan skripsi ini terletak pada pembahasan tentang kebijakan Jepang dalam merespon fenomena pembajakan kapal di perairan Somalia. Walaupun memiliki topik bahasan yang sama, akan tetapi tesis dan skripsi ini memiliki perbedaan yang signifikan pada jawaban penelitian. Jawaban penelitian yang ada di tesis ini berfokus pada kepentingan Jepang menjadikan Afrika sebagai alternatif dalam meningkatkan posisi pasukan militernya di sistem internasional. Sedangkan, dalam skripsi ini penulis berfokus pada kepentingan Jepang membangun pangkalan militer di Djibouti pada 2011.
Yang kedua, yaitu sebuah working paper yang ditulis pada 2015 oleh Wilhelm Vosse dari Cardiff University yang berjudul, “An Independent Deployer in Informal Organizational Structures: Japan’s
Contribution to the CGPCS.” Artikel ini menjelaskan tentang partisipasi Jepang dalam misi anti pembajakan kapal yang terjadi di sekitar perairan teluk Aden dan Somalia pada 2009 melalui Contact Group on Piracy off the Coast of Somalia (CGPCS).34
Menurut Vosse, kontribusi Jepang terhadap CGPCS diwujudkan dalam bentuk bantuan finansial yang sangat besar.35 Walaupun
Jepang berkontribusi besar terhadap CGPCS, akan tetapi Jepang belum mendapatkan posisi yang strategis di working group
tersebut. Hal ini dikarenakan keterbatasan legalitas hukum-hukum Jepang mengenai misi anti pembajakan kapal yang masih menjadi perdebatan di internal CGPCS itu sendiri.36
Persamaan antara artikel dan skripsi ini terdapat pada pembahasan mengenai kontribusi Jepang terhadap CGPCS yang dibentuk pada 2009, untuk mendukung misi anti pembajakan kapal di perairan teluk Aden dan Somalia. Artikel ini sangat menekankan
34 Wilhelm Vosse, An Independent Deployer in Informal Organizational Structures: Japan’s Contribution to the CGPCS, Working Paper, (Cardiff: Cardiff University, 2015), 1.
35 Wilhelm Vosse, An Independent Deployer in Informal Organizational Structures: Japan’s Contribution to the CGPCS, 16.
pada kontribusi Jepang terhadap CGPCS agar lebih fleksibel dan efisien dalam berkoordinasi serta bertukar informasi. Sedangkan skripsi ini lebih menekankan pada relevansi pembangunan fasilitas militer Jepang di Djibouti dengan misi anti pembajakan kapal di perairan tersebut.
Tulisan ketiga, yakni sebuah skripsi yang ditulis oleh Endar Aminata dari Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang berjudul, “Kebijakan Pemerintah Jepang Mengirimkan Kapal Perang Dalam Memberantas Perompak
Ke Teluk Aden Somalia Tahun 2009.” Endar menjelaskan tentang langkah strategis Jepang untuk terlibat dalam memberantas perompak di teluk Aden. Hal ini merupakan peristiwa yang sangat besar, di mana sebelumnya Jepang tidak pernah terlibat aksi militer pasca kekalahannya di Perang Dunia II.37
Endar melihat bahwa Jepang mulai berani untuk mengambil kebijakan pertahanannya sendiri tanpa bayang-bayang Amerika Serikat.38 Selain itu, Endar menekankan bahwa kebijakan Jepang
mengirimkan pasukan SDF ke teluk Aden tidak melanggar konstitusi
37 Endar Aminata, Kebijakan Pemerintah Jepang Mengirimkan Kapal Perang Dalam Memberantas Perompak Ke Teluk Aden Somalia Tahun 2009, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2010), 6.
1947. Hal ini dikarenakan tujuan utamanya adalah untuk melakukan operasi kriminal, bukan operasi militer. Di mana operasi ini sangat diperlukan untuk mengamankan kepentingan ekonomi Jepang.39
Perbedaan utama dengan skripsi yang penulis teliti adalah fokus pembahasan yang lebih menekankan pada motif utama dibalik kepentingan Jepang membangun pangkalan militer Jepang di Djibouti. Persamaannya terletak pada pembahasan isu kejahatan transnasional berupa pembajakan kapal di teluk Aden. Dapat dikatakan juga skripsi ini ingin melanjutkan pembahasan skripsi yang ditulis oleh Endar, di mana telah terjadi eskalasi dalam isu tersebut. Yang di awal Jepang hanya mengirimkan dua kapal perangnya ke teluk Aden sampai membangun pangkalan militer di Djibouti.
E. Kerangka Pemikiran
Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa konsep yang terdapat dalam ilmu hubungan internasional. Konsep-konsep yang akan penulis gunakan, yaitu:
E.1 Neorealisme
Dalam bukunya yang berjudul Theory of International Politics, Kenneth Waltz menjelaskan bahwa keadaan sistem internasional yang anarki mendorong negara-negara untuk bersiap menghadapi segala situasi, karena sifat alami negara adalah berperang dan hal itu dapat terjadi sewaktu-waktu.40 Self-help adalah prinsip yang
paling penting dalam sistem internasional yang anarki. Berdasarkan prinsip tersebut maka setiap negara akan melakukan segala upaya untuk meningkatkan security-nya.41
Menurut pandangannya, balance of power adalah kondisi yang paling ideal untuk mempertahankan sistem internasional yang anarki. Waltz menjelaskan bahwa balance of power dapat terjadi karena negara-negara dalam sistem internasional yang anarki berusaha untuk survive. Maka dari itu, upaya negara untuk tetap
survive dalam sistem internasional ditujukan demi terciptanya
balance of power. Terdapat dua jenis bentuk dalam balance of power bagi suatu negara yaitu, internal balancing dengan cara meningkatkan kekuatan militer dan kebijakan pertahanan, serta
external balancing dengan cara memperkuat aliansi dengan negara lain.42
40 Kenneth N. Waltz, Theory of International Politics (Philipines: Addison-Wesley Publishing Company, Inc., 1979), 88-102.
Dalam karyanya lain yang berjudul The Origins of War in Neorealist Theory,43 Waltz menjelaskan bahwa terdapat dua faktor
penting dalam sistem anarki yang menyebabkan kompetisi atau konflik. Kedua faktor tersebut yakni: kondisi negara yang berada dalam situasi yang anarki mendorong negara untuk mengamankan negaranya dan adanya ancaman atau potensi ancaman yang mengancam keamanan negaranya. Berdasarkan dua hal di atas, negara akan mengidentifikasi ancaman-ancaman tersebut dan mengunakan power-nya untuk menangkal ancaman-ancaman itu. Hal ini dikarenakan setiap negara akan melakukan berbagai usaha untuk mengamankan negaranya.
Terjadinya eskalasi kebijakan pertahanan Jepang dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa Jepang sedang melakukan upaya self-help untuk mempertahankan eksistensinya dalam sistem internasional yang anarki. Kedinamisan Jepang dalam meningkatkan kebijakan pertahanannya menunjukkan bahwa keputusan Jepang sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi sistem internasional yang anarki.
E.2 National Interest
Kepentingan nasional menjadi salah satu konsep penting yang seringkali
digunakan untuk menganalisis sebab dari perilaku yang ditunjukkan oleh sebuah
negara. Dalam skripsi ini penulis menggunakan konsep kepentingan nasional
berdasarkan pandangan kaum neo-realis. Tentunya konsep kepentingan nasional yang
dikemukakan oleh kaum neo-realis sangat berbeda dengan kaum realis.
Kenneth Waltz sebagai tokoh utama neo realis berpendapat bahwa,
kepentingan nasional merupakan produk yang dihasilkan oleh struktur sistem
internasional, yang memberikan sinyal otomatis kepada negara untuk merespon
peristiwa yang ditimbulkan olehnya. Tidak seperti asumsi Morgenthau yang
menyatakan bahwa kepentingan nasional adalah ide-ide yang digunakan sebagai
acuan pemimpin dalam menentukan kebijakan luar negerinya.44
Pada dasarnya, negara berupaya untuk mengamankan kelangsungan hidup
mereka dengan kapabilitas yang dimiliki dalam merespon sistem internasional.
Dalam proses tersebut, negara memiliki kesempatan untuk mempengaruhi sistem
internasional, tetapi tidak dapat mengontrolnya. Selama negara berada dalam situasi
self-help, survival menjadi hal terpenting yang harus diperjuangkan negara dalam sistem yang anarki. Karena survival menjadi syarat mutlak bagi suatu negara untuk mencapai tujuan-tujuan yang lain.45
44 Scott Burchill, The National Interest in International Relations Theory (New York: Palgrave Macmillan, 2005), 43.
Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat poin-poin penting yang harus
diperhatikan, yaitu:46
1. Negara memiliki kapabilitas untuk mempengaruhi sistem, tetapi tidak
dapat mengontrolnya.
2. Survival menjadi kepentingan nasional paling primer yang harus didahulukan oleh negara sebelum kepentingan yang lainnya.
3. Kemampuan negara untuk mencapai keamanan (security) ditentukan oleh relative power daripada absolute power.
Negara dapat dikatakan bertindak sesuai dengan kepentingan nasional jika
keamanan menjadi prioritas utama kebijakannya. Pada dasarnya, setiap negara
memiliki kebijakannya masing-masing, maka dari itu setiap negara akan
memperhitungkan segala tindakannya dalam merespon sistem yang anarki agar
negara tersebut tidak terjebak dalam situasi yang membahayakan.47
Dalam pandangan Waltz, memaksimalkan relative power menjadi cara terbaik bagi sebuah negara untuk mempertahankan upaya survival mereka dalam sistem internasional yang anarkis. Karena kepentingan yang lain akan mudah di dapat jika
kebutuhan dasar negara dalam mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial
telah tercapai.48
46 Scott Burchill, The National Interest in International Relations Theory, 44-45.
47 Scott Burchill, The National Interest in International Relations Theory, 45.
Terjadinya eskalasi kebijakan luar negeri Jepang terhadap fenomena
pembajakan kapal di Somalia patut menjadi perhatian. Pembangunan pangkalan
militer pertama Jepang di Djibouti sejak kekalahannya pada PD II merupakan hal
bersejarah bagi kebijakan luar negeri Jepang. Keberanian Jepang untuk mengambil
keputusan tersebut tentunya dilandasi oleh motif yang kuat. Dalam hal ini konsep
kepentingan nasional digunakan sebagai alat analisis untuk melihat kepentingan
Jepang dalam membangun pangkalan militer tersebut.
E.3 Balance of Power
Dalam menganalisis penelitian ini penulis mencoba mengkaji permasalahan
dengan konsep “balance of power” yang dikemukakan oleh Stephen M. Walt. Dalam teori ini, Walt menunjukkan bahwa negara melakukan upaya balancing maupun bandwagoning untuk merespon ancaman dari negara lain. Yang pada akhirnya diperlukan beberapa kriteria atau situasi dimana suatu negara mempertimbangkan
negara lain sebagai ancaman.49
Jika suatu negara merasakan besarnya kekuatan melalui kapabilitas suatu
negara secara kuantitatif, misalnya suatu negara yang dianggap sebagai ancaman
adalah negara yang memiliki populasi penduduk yang besar, kekuatan ekonomi yang
stabil, ataupun kapabilitas militer yang semakin meningkat. Selain itu, kedekatan
jarak geografis suatu negara juga bisa menjadi indikator adanya sumber ancaman
terhadap negara lain dalam satu wilayah berdekatan.50
Sehingga negara menganggap ancaman terbesarnya adalah negara yang
berdekatan secara geografis dengan negaranya.51 Kemudian Walt memberikan empat
kriteria sumber ancaman yang dapat dilihat dari suatu negara yang menentukan
kebijakan balancing atau bandwagoning suatu negara, yaitu:
i) Aggregate Power: Negara yang memiliki sekumpulan kekuatan seperti kekuatan ekonomi dan perdagangan, kemajuan teknologi dan industri,
kepadatan populasi, dan kekuatan militer, adalah negara yang sebagian
besar menunjukkan ancaman terhadap negara lainnya dengan
menggunakan kapabilitas tersebut.52
ii) Proximate Power: Dimana wilayah atau jarak jauh dan dekatnya suatu negara dengan negara lain ternyata mampu menentukan ancaman. Negara
lain yang berjarak lebih dekat dengan suatu negara memiliki potensi yang
lebih besar untuk memberikan ancaman dibandingkan mereka yang
berjarak lebih jauh dari negara tersebut.53
iii) Offensive Power: Berkaitan dengan kriteria atau sumber ancaman dilihat dari aggregate power, secara lebih spesifik Walt menunjukkan bahwa
50 Stephen M. Walt, “Alliance of Formation and the Balance of World Power.”
51 Stephen M. Walt, “Alliance of Formation and the Balance of World Power.”
52 Stephen M. Walt, “Alliance of Formation and the Balance of World Power.”
negara yang memiliki kapabilitas tools atau perangkat yang bersifat ofensif seperti angkatan militer dan perlengkapan persenjataan, akan
memiliki kemungkinan untuk memicu ketegangan antar negara maupun
aliansi.54
iv) Offensive Intentions: Offensive power yang dimiliki negara akan menimbulkan hasrat suatu negara untuk menyerang negara lain. Seperti
yang telah disebutkan pada poin sebelumnya, bahwa kekuatan atau
kapabilitas perangkat ofensif adalah modal untuk memberikan ancaman.
Oleh karena itu, hasilnya adalah sikap negara menjadi lebih agresif dan
mengesampingkan international order.
Meningkatnya intensitas ketegangan di Asia Timur, terutama di Laut Cina
Selatan menjadi perhatian serius bagi Jepang. Agresifitas Cina dalam mengklaim
kepemilikan wilayah Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur memberikan ancaman
nyata bagi negara-negara di sekitarnya, salah satunya Jepang. Dengan keterbatasan
kebijakan pertahanan yang dimilikinya, akan menyulitkan Jepang untuk menghadapi
kapabilitas militer Cina yang semakin meningkat.
Maka dari itu, Jepang harus mengambil langkah yang tepat dalam kebijakan
luar negerinya, agar bisa mengimbangi kekuatan Cina di Asia Timur. Berdasarkan
konsep Balance of Power, skripsi ini akan menganalisis mengenai keterkaitan
peningkatan kapabilitas militer Cina terhadap kebijakan luar negeri Jepang
membangun pangkalan militer di Djibouti.
F. Metode Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penulis menggunakan metode ini karena lebih sederhana dan praktis untuk digunakan. Penelitian ini merupakan penelitian yang menjelaskan tentang terjadinya sebuah fenomena yang disusun berdasarkan sumber-sumber yang telah ada. Penelitian ini diawali dengan penelitian yang bersifat deskriptif dan eksploratif yang dilanjutkan dengan mengidentifikasi fenomena tersebut. Penelitian ini berfokus pada satu topik yang melihat asal usul terjadinya sesuatu.55
Kemudian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara kualitatif. Data-data yang digunakan antara lain berasal dari buku-buku, artikel, jurnal akademis, berita, dan internet yang sebagian besar berasal dari situs-situs internet yang memiliki otoritas dalam mempublikasikan tulisan-tulisan yang terkait dengan penelitian ini.
G. Sistematika Penulisan
Bab I Pendahuluan
Pendahuluan adalah bagian penelitian yang menjadi dasar utama
dilakukannya penelitian ini. Bagian ini terdiri dari pernyataan masalah, pertanyaan
penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran,
metode penelitian, dan sistematika penulisan.
Bab II Kebijakan Pertahanan Jepang
Bab ini menjelaskan tentang sejarah kebijakan pertahanan Jepang pasca
perang dingin dan pasca terjadinya peristiwa 11 September sampai saat ini. Bab ini
diawali dengan pembahasan mengenai kebijakan pertahanan Jepang pasca Perang
Dingin. Kemudian dilanjutkan dengan peningkatan kebijakan pertahanan Jepang
pasca terjadinya peristiwa 9 September. Peningkatan kebijakan ini ditandai dengan
dibentuknya National Defence Programme Guidelines (NDPG) pada 2004 yang berisi poin penting mengenai keterlibatan SDF dalam menjaga stabilitas
internasional.
BAB III Pembangunan Pangkalan Militer Jepang di Djibouti
Pada bab ini akan di bahas mengenai kondisi geopolitik di sekitar Djibouti.
Dilanjutkan dengan pembahasan mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi
tumbuhnya pengaruh eksternal di negara tersebut. Meningkatnya pembajakan kapal
di teluk Aden dan Somalia menjadi salah satu faktor penting yang mendorong Jepang
dalam hal ini ditunjukkan dengan pembangunan pangkalan militer pada 2011 di
Djibouti.
BAB IV Kepentingan Jepang Membangun Pangkalan Militer di Djibouti
Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai motif Jepang membangun pangkalan
militer di Djibouti menggunakan teori kepentingan nasional menurut pandangan
kaum neo realisme. Kepentingan utama Jepang terkait pembangunan pangkalan
militernya di Djibouti adalah sebagai upaya survival terhadap ancaman perompak Somalia. Adapun dalam hal ini kepentingan Jepang terhadap keamanan perairan ini
dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu ekonomi dan keamanan. Dalam aspek
ekonomi, Jepang memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap perairan ini
karena sebagian besar perdagangan Jepang didistribusikan melalui transportasi laut.
Keputusan Jepang untuk memperpanjang operasional pangkalan militernya di
Djibouti secara tidak langsung menunjukkan bahwa, ada upaya dari Jepang untuk
meningkatkan relative power-nya. Di mana relative power ini akan sangat berguna bagi Jepang untuk melakukan upaya balancing terhadap Cina di kawasan Asia Timur.
BAB V Penutup
Pada bab ini, penulis akan memaparkan kesimpulan dari tiap bab sampai
dengan hasil analisis yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, sehingga didapat
BAB II
KEBIJAKAN PERTAHANAN JEPANG
Berakhirnya Perang Dingin dijadikan penulis sebagai pengawal untuk
memahami transformasi kebijakan pertahanan Jepang, di mana peristiwa tersebut
merupakan awal perubahan yang signifikan dari kebijakan pertahanan Jepang dalam
dibuatnya konsep ini adalah untuk meningkatkan peran Jepang yang lebih aktif dalam
isu-isu internasional.56
Dalam sisi keamanan, konsep ini digunakan Jepang untuk dapat berkontribusi
dalam UN Peacekeeping Operation mengatasi berbagai permasalahan keamanan demi menciptakan stabilitas keamanan dan perdamaian dunia.57 Berdasarkan hal di
atas, pertama, bab ini akan menjelaskan tentang kebijakan pertahanan Jepang pasca Perang Dingin. Kedua, akan dijelaskan kebijakan pertahanan Jepang pasca peristiwa 9 September. Dimana terjadi peningkatan yang signifikan dalam kebijakan
pertahanan Jepang, yang ditandai oleh pembentukan National Defence Programme Guidelines (NDPG) pada 2004.
A. Kebijakan Pertahanan Jepang Pasca Perang Dingin
Seperti yang telah dijelaskan di atas, berakhirnya perang dingin membawa
perubahan yang sangat besar terhadap arah kebijakan pertahanan Jepang. Konsep
kokusai koken (contribution to the international community) menjadi panduan penting dalam pembentukan kebijakan pertahanan Jepang. Di mana konsep ini tidak
hanya terbatas dalam isu ekonomi saja, tetapi juga isu-isu yang berkaitan dengan
keamanan dan stabilitas perdamaian dunia.58
56 Takehiko Ochiai, “Beyond TICAD Diplomacy: Japan’s African Policy and African Initiatives In Conflict Response.”
57 Louis G. Perez, Japan at War: An Encyclopedia (California: ABC-CLIO, 2013), 371.
58 In Sung Jang, “How the Japanese Understand International Responsibility and Contribution: Its Historical Nature as Featured in the International System,” [artikel on-line]; tersedia di
Masifnya perkembangan isu keamanan pasca perang dingin mendorong
pemerintah Jepang untuk meningkatkan pengaruhnya dalam politik internasional. Di
bawah pemerintahan Toshiki Kaifu, Jepang ingin menjadi pihak independen yang
mengambil peran penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah Asia.59
Hal ini tercermin dalam pidatonya di Singapura yang menyatakan bahwa,
“Jepang akan mengambil peran politik untuk memberikan kontribusi bagi stabilitas wilayah Asia, khususnya Indochina, dan Jepang bersumpah tidak akan lagi menjadi kekuatan militer.”60 Implementasi dari pidato tersebut yakni keikutsertaan Jepang
dalam misi yang dilakukan PBB untuk menyelesaikan konflik internasional,
khususnya di wilayah Asia.
Perang teluk pada 1990-1991 menjadi batu loncatan bagi Jepang untuk terlibat
dalam isu keamanan internasional khususnya di Asia.61 Kontribusi Jepang dalam
penyelesaian konflik di wilayah tersebut lebih bersifat bantuan logistik dan bantuan
finansial untuk pembangunan kembali infrastruktur yang rusak akibat perang.62 Total
dana bantuan yang dikeluarkan Jepang dalam konflik tersebut sebesar 13 miliar dolar
AS.63
59 Keiko Hirata, “Reaction and Action: Analyzing Japan’s Relations With The Socialist Republic Of Vietnam,” dalam Regionalism and Japan: The Bases of Trust and Leadership, Routledge, New York, 2001, hal. 113.
60 Keiko Hirata, “Reaction and Action: Analyzing Japan’s Relations With The Socialist Republic Of Vietnam,” hal. 114.
61 “Current Issues Surrounding UN PKO & Japanese Perspective,”
http://www.mofa.go.jp/policy/un/pko/issues.html. Diakses pada tanggal 31 Juli 2016, pukul 17:45.
62 “Japan’s Response To The Gulf Crisis,”
http://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/1991/1991-2-2.htm. Diakses pada tanggal 31 Juli 2016, pukul 17:58.
Untuk melegitimasi tindakannya, pemerintahan Toshiki Kaifu membuat
sebuah rancangan undang-undang yang bernama UN Peace Cooperation Bill. RUU ini diajukan ke parlemen pada Oktober 1990.64 Akan tetapi, parlemen Jepang menolak
untuk menyetujui undang-undang tersebut, hal ini diakibatkan adanya penolakan
publik terhadap keterlibatan pasukan Jepang dalam konflik internasional.65
Selain itu, sebagian besar publik Jepang pada masa Toshiki Kaifu merasa
pengiriman tersebut telah melanggar konstitusi.66 Dalam Peace Constitution 1947,
secara jelas menyatakan bahwa, “Dengan hati yang tulus didasarkan pada keadilan dan ketertiban bagi perdamaian internasional, rakyat Jepang selamanya menolak perang dan ancaman atau penggunaan kekerasan sebagai hak kedaulatan bangsa dalam menyelesaikan konflik internasional. Untuk memenuhi tujuan paragraf sebelumnya, angkatan darat, laut, dan udara, demikian pula potensi perang lainnya, tidak akan dipelihara. Hak beligerensi negara tidak akan diakui.67
Walaupun intensitas penolakan terhadap keterlibatan pasukan SDF dalam misi
internasional masih cukup tinggi. Pemerintahan Toshiki Kaifu tetap berusaha untuk
membuat sebuah landasan hukum agar pasukan SDF memiliki legitimasi dalam setiap
hal. 62.
64 Inoguchi Takashi & Purnendra Jain, “Japanese Foreign Policy Today,” Palgrave, New York, 2000, hal. 127.
65 Namzariga Adamy, “Kebijakan PKO Jepang di Kamboja: Suatu Tinjauan Terhadap Perubahan Kebijakan Luar Negeri Jepang Paska Perang Dingin,” Tesis Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2004, hal. 6.
66 Japan’s Response To The Gulf Crisis.
http://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/1991/1991-2-2.htm. Diakses pada tanggal 1 agustus 2016, pukul 10:30.
67 “The Constitution of Japan”,
misi yang akan dijalankannya. Maka, dicetuskanlah kembali RUU yang bernama
International Peace Cooperation Bill pada September 1991.68
Akan tetapi, RUU ini tidak langsung disahkan oleh parlemen. Sampai
akhirnya RUU ini disetujui pada 9 juni 1992 dan disahkan pada 15 juni 1992 dengan
nama International Peace Cooperation Act di bawah pemerintahan Miyazawa Kiichi.69 Tujuan utama dibentuknya undang-undang ini adalah untuk meningkatkan
peran Jepang dalam menjaga keamanan dan stabilitas perdamaian dunia, melalui
peacekeeping operation di bawah naungan PBB.70
Prinsip-prinsip yang ada dalam undang-undang tersebut adalah (1)
kesepakatan gencatan senjata di antara kedua belah pihak terjadi, (2) Kedua pihak
setuju akan adanya operasi penjaga perdamaian yang dilakukan oleh Jepang di bawah
naungan PBB, (3) Pasukan perdamaian harus menjaga netralitas di antara pihak yang
berkonflik, (4) Jika prinsip-prinsip di atas tidak terpenuhi, pemerintah Jepang dapat
menarik pasukan perdamaiannya, dan (5) penggunaan senjata diperbolehkan dalam
batas seminimal mungkin untuk melindungi nyawa pasukan.71
68 Namzariga Adamy, “Kebijakan PKO Jepang di Kamboja: Suatu Tinjauan Terhadap Perubahan Kebijakan Luar Negeri Jepang Paska Perang Dingin,” Tesis Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2004, hal. 6.
69 Namzariga Adamy, “Kebijakan PKO Jepang di Kamboja: Suatu Tinjauan Terhadap Perubahan Kebijakan Luar Negeri Jepang Paska Perang Dingin.”
70 Patrick M. Cronin & Michael J. Green, Redefining the US-Japan Alliance: Tokyo’s National Defense Program, (Washington: National Defense University Press, 1994), 37.
Adapun dalam pelaksanaannya, peacekeeping operation yang dilakukan Jepang dapat dibagi dalam 4 macam, yaitu: peacekeeping missions, humanitarian relief operations, election monitoring activities, dan in-kind contributions.72 Sejak
diberlakukannya PKO Act oleh Jepang pada Agustus 1992,73 terlihat bahwa Jepang
memiliki keinginan besar untuk ikut terlibat dalam mendukung stabilitas keamanan
sistem internasional.
Pengiriman pasukan Self-Defense Force ke Kamboja di bawah naungan United Nations Transitional Authorities in Cambodia (UNTAC) menjadi misi pertama pasukan Jepang di bawah undang-undang hukum tersebut.74 Peristiwa ini
merupakan peristiwa yang bersejarah dalam kebijakan pertahanan Jepang. Karena
untuk pertama kalinya di bawah legitimasi hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan, Jepang mengirimkan pasukannya di bawah naungan PBB
untuk menjaga stabilitas keamanan internasional.
Setelah pengesahan PKO Act, pada 1995 pemerintah Jepang melakukan revisi terhadap National Defence Program Outline (NDPO) yang dibuat pada 1976.75 Revisi
tersebut menghasilkan dua poin penting, pertama yaitu perluasan peran pasukan SDF
72 MOFA Japan, “Japan’s Contribution Based on the International Peace Cooperation Act,” [berita resmi on-line]; tersedia di http://www.mofa.go.jp/fp/ipc/page22e_000684.html; Internet; diunduh pada 17 Oktober 2016.
73 MOFA Japan, “Outline of Japan’s International Peace Coopeation,” [berita resmi on-line]; tersedia di http://www.mofa.go.jp/fp/ipc/page22e_000683.html; Internet; diunduh pada 17 Oktober 2016.
74 Peter J. Woolley, Japan’s Navy: Politics and Paradox 1971-2000, (Colorado: Lynne Rienner Publishers, Inc., 2000), 124.
dalam kerjasama keamanan multilateral, seperti bantuan bencana dan peacekeeping operation yang diinisiasi oleh PBB. Kedua, menyusun kembali hal-hal yang menjadi prioritas dalam kebijakan pertahanan Jepang dan menekankan pentingnya aliansi
antara Jepang dan AS sebagai inti dari strategi keamanan Jepang.76
Sebagai tindak lanjut dari strategi keamanan Jepang yang menjadikan aliansi
Jepang dan AS sebagai intinya. Pada April 1996, Jepang dan AS secara resmi
menandatangani ‘US-Japan Joint Declaration on Security – Alliance for the 21st
Century’.77 Perjanjian ini dilakukan untuk menegaskan kembali US-Japan Security
Treaty yang ditandatangani pada 1960. Fokus utama dari perjanjian tersebut adalah
menjadi panduan bagi koordinasi kebijakan pertahanan antara Jepang dan AS untuk
saling mendukung dalam menghadapi ancaman regional maupun internasional pasca
Perang Dingin.78
Revisi NDPO pada 1995 dan ditandatanganinya Joint Declaration antara AS dan Jepang pada 1996 tidak terlepas dari beberapa peristiwa penting yang
menimbulkan gejolak militer di kawasan Asia Timur. Adapun peristiwa penting yang
melatarbelakangi Jepang meningkatkan kebijakan pertahanannya yakni, keputusan
Korea Utara untuk menarik diri dari perjanjian Non Proliferation Treaty (NPT) pada
76 Bhubhindar Singh, Japan’s Security Identity: From a Peace-State to an International State.
77 Bhubhindar Singh, Japan’s Security Identity: From a Peace-State to an International State, 119.
12 Maret 1993, sehingga memungkinkannya untuk meneruskan program nuklirnya
tanpa pengawasan dari International Atomic Energy Agency (IAEA).79
Selain itu, Korea Utara juga melakukan uji coba misil Rodong pada 1991
yang berakhir dengan kegagalan. Pada 1993, Korea Utara kembali mengulangi uji
coba misil Rodong jarak menengah dan sukses.80 Kesuksesan tersebut menarik minat
Iran, di mana minat tersebut ditunjukkan dengan pemesanan 150 misil Rodong pasca
kunjungan militer Korea Utara ke Iran pada Maret 1993.81
Peristiwa lain yakni peningkatan kapabilitas militer China secara signifikan
yang dimulai pada 1990. Di mana peningkatan kapabilitas ini meliputi kemampuan
maritim, misil anti kapal, rudal balistik jarak pendek dan menengah, rudal jelajah,
kapal selam siluman, dan kemampuan cyber serta teknologi ruang angkasa.82
Selanjutnya uji coba nuklir yang dilakukan oleh China dari 1992 sampai dengan 1995
yang mengakibatkan diberhentikannya bantuan ODA dari Jepang ke China.83
Kemudian serangkaian uji coba misil dan latihan militer yang dilakukan oleh
China dari 1995 sampai dengan 1996.84 Adapun uji coba misil dan latihan militer
yang dilakukan oleh China merupakan aksi intimidasi China terhadap Taiwan agar 79 D. Ellsworth Blanc, North Korea, Pariah?, (New York: Nova Science Publishers, Inc., 2001), 29.
80 Andrew T. H. Tan, The Global Arms Trade: A Handbook, (New York: Routledge, 2014), 97.
81 Andrew T. H. Tan, The Global Arms Trade: A Handbook.
82 T. V. Paul, Accomodating Rising Powers: Past, Present, and Future, (Cambridge: Cambridge University Press, 2016), 49.
83 James Reilly, Strong Society, Smart State: The Rise of Public Opinion in China’s Japan Policy, (New York: Columbia University Press, 2012), 85
Taiwan kembali lagi menjadi bagian dari Republik Rakyat China.85 Selanjutnya pada
31 Agustus 1998, Korea Utara kembali melakukan uji coba misil Taepo Dong-1 yang
memiliki jarak tempuh sejauh 1.500-2.000 kilometer. Di mana dalam uji coba ini,
misil tersebut melintas tepat di atas wilayah Jepang.86
Kemampuan misil Korea Utara yang berhasil melintas di atas wilayah Jepang
tentunya memberikan ancaman yang sangat nyata bagi keamanan kedepannya. Maka
dari itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, pada 1999 pemerintah Jepang dan AS
menandatangani sebuah kesepakatan. Kesepakatan ini berisi tentang kerjasama
penelitian dan pengembangan sistem Theater Missile Defense (TMD) yang ditujukan untuk menangkal ancaman serangan rudal yang masuk ke wilayah Jepang.87
Dapat dilihat bahwa kebijakan peningkatan pertahanan Jepang pasca Perang
Dingin merupakan bentuk respon dari terjadinya peristiwa-peristiwa penting yang
mengancam eksistensi Jepang di regional Asia Timur. Bentuk respon ini dapat
dianggap sebagai langkah Jepang untuk meningkatkan keamanan negaranya agar
tetap bisa survive dalam sistem internasional yang anarki.
B. Kebijakan Pertahanan Jepang Pasca Peristiwa 11 September
85 Suisheng Zhao, Across the Taiwan Strait: Mainland China, Taiwan and the 1995-1996 Crisis, (New York: Routledge, 1999), 153.
86 Anthony H. Cordseman, Strategic Threats and National Missile Defenses: Defending the U.S. Homeland, (Connecticut: Praeger, 2002), 133.
Aksi terorisme yang dilakukan terhadap gedung World Trade Center dan gedung Pentagon di Amerika Serikat menjadi awal dari perubahan kebijakan
pertahanan AS.88 ‘War on Terror’ menjadi kebijakan keamanan yang populer pasca
serangan tersebut, di mana AS menyerukan kepada dunia internasional untuk
bekerjasama dalam memberantas aksi terorisme.89
Sebagai sekutu utama AS di Asia, Jepang langsung merespon hal tersebut
dengan membuat undang-undang baru untuk meligitimasi tindakan-tindakan Jepang
dalam memberantas aksi terorisme. Undang-undang baru yang berhasil dibuat oleh
Jepang antara lain, Anti-Terrorism Special Measure Law 2001, Law on Armed Contingency in Japan 2003, dan Law Concerning the Special Measures on Humanitarian and Reconstruction Assistance in Iraq 2003.
Anti-Terrorism Special Measure Law merupakan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah Jepang pada 2001 sebagai bentuk respon terhadap kebijakan ‘War on Terror’ AS.90 Undang-undang ini dibuat oleh Jepang dalam rangka untuk memberikan
kontribusi terhadap operasi Counter Terrorism yang dilakukan oleh AS pasca serangan 11 September.91
88 International Business Publications, United States Defense Policy Handbook: Strategic Information, Policies, Contacts, (Washington DC: International Business Pubilcations, 2008), 117.
89 International Business Publications, United States Defense Policy Handbook: Strategic Information, Policies, Contacts, 130.
90 Rohan Gunaratna & Stefanie Kam, Handbook of Terrorism in the Asia-Pacific, (London: Imperial College Press, 2016), 521.
Poin penting yang terdapat dalam undang-undang ini adalah pasukan Jepang
yang dikirimkan untuk membantu AS dalam melakukan operasi Counter Terrorism hanya digunakan untuk mendukung pasukan AS secara logistik seperti, tansportasi,
perbaikan dan pemeliharaan fasilitas, komunikasi, layanan kesehatan, dan lain-lain.92
Alasan Jepang hanya menggunakan pasukannya dalam membantu urusan logistik
tidak terlepas dari interpretasi Jepang terhadap konstitusi perdamaian pasal 9 yang
melarang Jepang untuk terlibat dalam operasi pertempuran.93
Yang kedua, Law on Armed Contingency in Japan yang disahkan oleh pemerintah Jepang pada 2003. Undang-undang ini dibuat dengan tujuan untuk
melindungi dan mempertahankan teritori Jepang dari serangan bersenjata yang dapat
terjadi sewaktu-waktu.94 Inti dari undang-undang ini adalah memberikan landasan
hukum dan legitimasi bagi pasukan Jepang dalam merespon ancaman bersenjata yang
mengancam kedaulatan Jepang.95
Kemudian Law Concerning the Special Measures on Humanitarian and Reconstruction Assistance in Iraq yang disahkan oleh parlemen Jepang pada 2003. Undang-undang ini dibuat berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1483
yang menyerukan negara-negara anggotanya untuk membantu upaya rekonstruksi
92 James Beckman, Comparative Legal Approaches to Homeland Security and Anti-Terrorism, (New York: Routledge, 2016), 144.
93 James Beckman, Comparative Legal Approaches to Homeland Security and Anti-Terrorism.
perang di Irak.96 Berdasarkan undang-undang di atas pemerintah Jepang mengirimkan
600 pasukannya ke Irak untuk membantu melakukan upaya rekonstruksi pasca perang
di Irak.97
Terdapat dua alasan penting yang mendorong Jepang untuk mengirimkan
pasukan militernya ke Irak. Menurut mantan Direktur Jenderal Japan Defense Agency, Shigeru Ishiba, alasan pertama yaitu pengiriman pasukan ini ditujukan untuk membawa stabilitas keamanan di kawasan, karena Jepang sangat bergantung pada
kelancaran impor minyak dari kawasan tersebut. Kedua, keputusan Jepang mengirimkan pasukannya ke Irak sebagai langkah untuk memperkuat aliansinya
dengan AS.98
Pada 2004, NDPO 1995 secara resmi direvisi oleh pemerintah Jepang dan
berubah menjadi National Defence Program Guidelines yang akan diberlakukan pada 2005. Alasan utama disahkannya kebijakan di atas adalah untuk melindungi
perdamaian, kemerdekaan, dan integritas territorial Jepang dari potensi-potensi
ancaman.99 Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah menetapkan dua tujuan penting
yaitu untuk mencegah segala ancaman mencapai pantai jepang, menangkisnya dan
96 Nigel R. Thalakada, Unipolarity and the Evolution of America’s Cold War Alliances, (New York: Palgrave Macmillan, 2012), 72.
97 Nigel R. Thalakada, Unipolarity and the Evolution of America’s Cold War Alliances.
98 Arpitha Mathur, “Japan’s Changin Role in the US-Japan Security Alliance,”
Strategic Analysis, Vol. 28 No. 4, 2004, 509.
99 Olena Mykai, The EU-Japan Security Dialogue: Invisible but Comprehensive,
meminimalisir kerusakan. Yang kedua, meningkatkan keamanan dan perdamaian internasional untuk mengurangi potensi ancaman terhadap Jepang.100
Selain dua tujuan di atas, kebijakan ini juga ditujukan untuk meningkatkan
kerjasama antara Jepang dan AS dalam Cooperation on Ballistic Missile Defense, Equipment and Technology Exchange.101 Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan
lisensi terhadap Jepang dalam memproduksi rudal Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) dan keikutsertaannya dalam mengembangkan Standard Missile-3 Interceptor.102 Peningkatan kerjasama dalam produksi dan pengembangan rudal untuk
mengantisipasi serangan terhadap Jepang merupakan respon atas terjadinya krisis
nuklir Korea Utara kedua yang terjadi pada 2002-2003.103
Disahkannya NDPG sebagai panduan kebijakan keamanan juga memberikan
dampak yang signifikan terhadap beberapa transformasi dalam tubuh pertahanan
Jepang. Yang pertama yaitu melakukan restrukturasi dalam tubuh militer Jepang, di mana Ground, Marine, dan Air Self-Defense Force berada di bawah satu komando yakni Joint Staff Council.104 Kedua, yakni reformasi Japan Defence Agency menjadi
100 Olena Mykai, The EU-Japan Security Dialogue: Invisible but Comprehensive.
101 Stockholm International Peace Research Institute, Armaments, Disarmament and International Security 2008, (New York: Oxford University Press, 2008), 411. 102 Stockholm International Peace Research Institute, Armaments, Disarmament and International Security 2008.
103 Ramon Pacheco Pardo, North Korea-US Relations Under Kim Jong Il: The Quest for Normalization? (New York: Routledge, 2014), 48.
104 Olena Mykai, The EU-Japan Security Dialogue: Invisible but Comprehensive,
Ministry of Defence pada 15 Desember 2006, yang disahkan oleh parlemen Jepang pada 9 Januari 2007.105
Transformasi dalam struktur Self-Defense Force dan perubahan status Japan Defence Agency menjadi Ministry of Defence menunjukkan bahwa Jepang telah meningkatkan dan memperkuat kemampuannya dalam merespon situasi keamanan
global. Kedua, Jepang secara proaktif mendukung perdamaian dan stabilitas internasional dengan inisiatifnya sendiri.106 Dapat disimpulkan bahwa terjadinya
peningkatan kebijakan pertahanan Jepang merupakan langkah dalam merespon
gejolak stabilitas keamanan global. Walaupun secara konstitusi, kebijakan pertahanan
Jepang dibatasi, akan tetapi, pemerintah Jepang tetap melakukan interpretasi hukum
agar kebijakan pertahanannya sesuai dengan kondisi internasional saat ini.
BAB III
PEMBANGUNAN PANGKALAN MILITER JEPANG DI
DJIBOUTI
Pada bab ini dijelaskan secara singkat mengenai profil negara Djibouti. Profil
tersebut akan lebih difokuskan pada letak geografis Djibouti. Di mana negara ini
memiliki letak yang strategis secara geopolitik dilihat dari sisi ekonomi dan
keamanan. Kestrategisan letak Djibouti mendorong negara-negara yang
105 Olena Mykai, The EU-Japan Security Dialogue: Invisible but Comprehensive.
berkepentingan terhadap perairan Teluk Aden dan Terusan Suez seperti Jepang untuk
membangun relasi yang kuat dengan negara tersebut. Pembangunan fasilitas militer
Jepang di Djibouti menjadi bukti kuat bahwa Jepang memiliki interest yang besar terhadap perairan tersebut.
A. Kondisi Geopolitik di Djibouti
Republic of Djibouti merupakan sebuah negara yang terletak di Afrika Timur yang sering disebut sebagai Horn of Africa. Negara ini berbatasan dengan Eritrea di sebelah utara, Ethiopia di sebelah barat dan selatan, Somalia di sebelah tenggara,
serta Laut Merah dan Teluk Aden di sebelah timur. Negara ini hanya memiliki luas
wilayah sebesar 23.200 km², sehingga membuatnya menjadi negara terkecil di Afrika
Timur dengan total populasi sebesar 793.000 jiwa (2005).107
Dalam sisi ekonomi, Djibouti mengandalkan sektor jasa sebagai sektor
penting untuk mendukung perekonomiannya. Pelabuhan merupakan sektor jasa
penting yang diandalkan oleh Djibouti, karena pendapatan negara sebagian besar
didapatkan melalui sektor tersebut. Pelabuhan-pelabuhan ini digunakan sebagai
tempat transit barang-barang yang akan masuk ke Afrika dan pemberhentian
sementara kapal-kapal barang.108
Alasan utama diprioritaskannya sektor jasa sebagai pendapatan utama negara
adalah karena Djibouti tidak memiliki sektor unggulan lainnya dalam bidang 107 International Business Publications, Djibouti Foreign Policy & Government Guide (Washington: International Business Publications, 2010), 8.
ekonomi. Curah hujan yang rendah, minimnya sumber daya alam, sedikitnya industri
yang beroperasi di negara tersebut, serta sebagian besar makanan didapatkan dari
hasil impor cukup menjadi bukti bahwa Djibouti tidak memiliki sektor unggulan
selain jasa dalam bidang ekonomi.109
Peristiwa penting yang mendorong pemerintah Djibouti untuk
memprioritaskan sektor jasa sebagai sektor unggulan negara adalah perang
Ethiopia-Eritrea pada 1998-2000. Perang ini menjadi pemicu utama dibalik transformasi
kebijakan ekonomi Djibouti. Hilangnya kendali atas pelabuhan Massawa dan Assab
mendorong Ethiopia untuk mengalihkan jalur perdagangannya melalui Djibouti.110
Hal ini menyebabkan aktivitas ekspor-impor yang ada di pelabuhan Djibouti
didominasi oleh Ethiopia dengan presentase sebesar 70%.111
Maka dari itu, pemerintah Djibouti lebih memfokuskan sektor jasa sebagai
sektor unggulan pendapatan negara. Adapun letak strategis Djibouti dapat dilihat dari
gambar berikut ini:
Gambar III.A.1 Letak Djibouti Berdasarkan Jalur Perdagangan Minyak Dunia
109 CIA, The World Factbook 2014-15 (Washington: Central Intelligence Agency, 2014), 217.
110 Katharine Murison, Africa South of the Sahara 2003 (London: Europe Publications, 2003), 392.
Sumber: Murielle Delaporte, “Forward-Based Forces in Djibouti,” [berita on-line]; tersedia di
http://defence.frontline.online/article/2015/2/104-Forward-Based-Forces-in-Djibouti; Internet; diunduh pada 27 Oktober 2016.
Peta di atas menunjukkan bahwa Djibouti terletak di wilayah yang sangat
strategis. Karena negara ini memiliki akses langsung terhadap selat Bab El-Mandab.
Perlu diketahui bahwa Bab El-Mandab merupakan selat penting yang
menghubungkan Samudera Hindia dan Laut Mediterania melalui Laut Merah dan
Terusan Suez.112
Bab El-Mandab menjadi pintu penting bagi dunia pelayaran untuk melakukan
transportasi barang, khususnya minyak. Di mana pada 2006, setiap harinya 3,3 juta
barel minyak diekspor melewati wilayah ini.113 Hampir tiga perempat minyak mentah
dipindahkan dari Timur Tengah ke Eropa melalui pipa yang terbentang di sepanjang
Terusan Suez sampai Laut Mediterania dengan panjang pipa mencapai 320
kilometer.114
112 Bert Chapman, Geopolitics: A Guide to the Issues (California: Praeger, 2011), 78.
113 Bert Chapman, Geopolitics: A Guide to the Issues.
Selain itu, teluk Aden merupakan rute jalur utama perdagangan antara Eropa,
Timur Tengah, dan Asia dengan perkiraan 16.000 kapal melewati wilayah ini setiap
tahunnya. teluk Aden melayani 12% dari total perdagangan global dan 30% dari total
pengiriman minyak mentah dunia.115 Berdasarkan hal di atas walaupun secara
territorial Djibouti memiliki wilayah yang kecil, tapi letaknya yang strategis
memberikan keuntungan yang besar bagi kepentingan geopolitik di kawasan.
Perubahan kebijakan strategi keamanan AS pasca 11 September menjadi
peristiwa penting bagi peningkatan pengaruh eksternal yang ada di Djibouti.
Pembangunan pangkalan militer AS yang bernama Camp Lemonnier di Djibouti pada 2002 menjadi bukti nyata peningkatan tersebut. Pangkalan ini dibuat untuk
mengakomodasi pasukan AS dan sekutu yang tergabung dalam Combined Joint Task Force-Horn of Africa (CJTF-HOA), yang bertujuan untuk membendung pengaruh dan menghancurkan jaringan terorisme di kawasan itu.116
Sebelum AS membangun pangkalan militer di Djibouti, pada masa Perang
Dingin Prancis telah lebih dulu membangun pangkalan militer di negara tersebut.
Prancis dan AS menggunakan pangkalan ini untuk membendung pengaruh
komunisme Uni Soviet di sekitar teluk Aden agar tidak menyebar ke negara-negara di
2011): 90.
115 Brian J. Hesse, Somalia: State Collapse, Terrorism, and Piracy (New York: Routledge, 2011), 82.