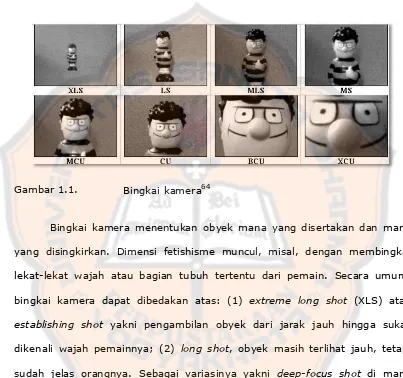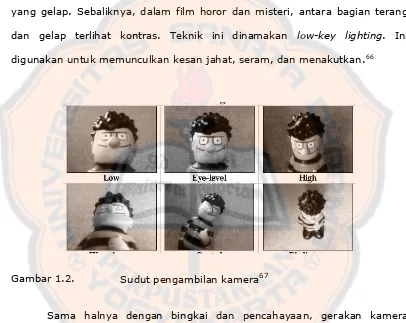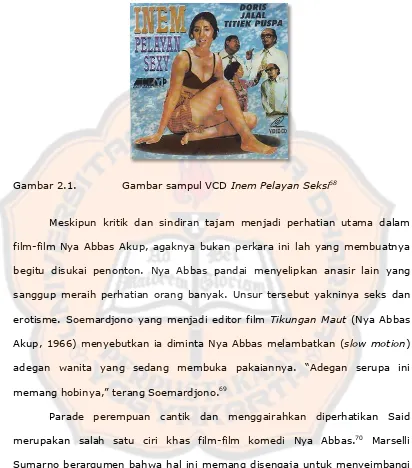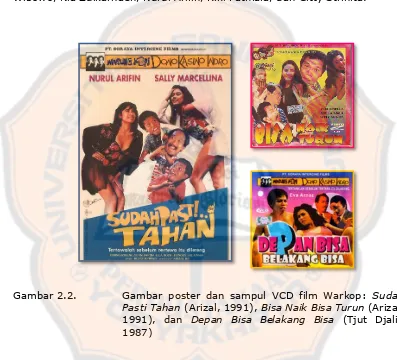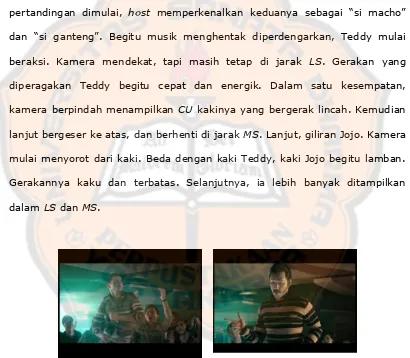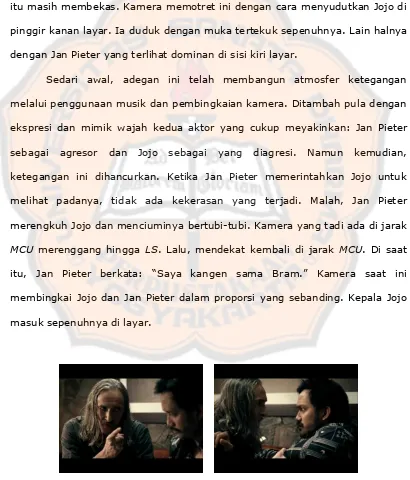MEMANDANG LAKI-LAKI DALAM FILM KOMEDI DEWASA:
Analisis Visual Quickie Express dengan Perspektif Psikoanalisis
T h e s i s
Untuk memenuhi persyaratan mendapat gelar Magister Humaniora (M.Hum.) di Program Magister Ilmu Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
Oleh: Maria Dovita
096322006
PROGRAM MAGISTER ILMU RELIGI DAN BUDAYA
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa thesis berjudul: “Memandang Laki-Laki
dalam Film Komedi Dewasa: Analisis Visual Quickie Express dengan Perspektif
Psikoanalisis” merupakan hasil karya dan penelitian saya pribadi. Di dalam
thesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Peminjaman karya sarjana lain adalah semata-mata untuk keperluan ilmiah sebagaimana diacu secara tertulis di dalam catatan kaki dan daftar pustaka.
Yogyakarta, September 2013
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma,
Nama : Maria Dovita
NIM : 096322006
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada
perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya berjudul:
Memandang Laki-Laki dalam Film Komedi Dewasa: Analisis Visual Quickie
Express dengan Perspektif Psikoanalisis
Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan pada Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk perangkat data, mendistribusikannya secara terbatas dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan saya sebagai penulis.
Demikian pernyataaan ini saya buat dengan sebenarnya.
Yogyakarta, September 2013
KATA PENGANTAR
Sedikit bercerita, penelitian ini terlalu lama di gagasan, begitupun di penulisan. Kalau diibaratkan nasi, bukannya sudah dingin, tapi lebih dari sekadar basi. Bagaimana bisa memakan waktu begitu panjang, bukan karena terlalu dihayati atau dipikir benar-benar. Melainkan disebabkan otak yang terlalu tumpul dan tangan yang terlampau berkarat. Apa yang saya lalui
bukanlah sebuah detour, kalau boleh meminjam istilah Ricouer. Jalan-jalan itu
tampak saling bertindihan. Begitu semrawut hingga sukar dibedakan mana jalan mana rerumputan. Meski dengan kondisi demikian, thesis ini selesai juga. Selesai sejauh yang dapat dituliskan dalam lembaran, tapi tidak terhenti di pemikiran.
Dalam tempo yang tidak singkat itu, sudah banyak sekali pihak yang membantu saya: entah itu dengan sekadar bernyinyir-nyinyir, menyindir, atau yang meminjamkan bahan bacaan dan sumbang pemikiran secara sukarela. Di kertas yang masih terluang ini, untuk itu saya menyampaikan terimakasih kepada:
1. Dr. G. Budi Subanar, S.J. selaku Ketua Program Ilmu Religi dan
Budaya dan pembimbing II, buku Visual Methodologies yang Romo
pinjamkan sangat membantu saya dalam merancang penelitian ini.
Dan, terimakasih atas program “satu hari, satu halaman”, yang
terbukti ampuh mendisiplinkan saya dalam menulis.;
2. Dr. Katrin Bandel selaku pembimbing utama, terimakasih untuk
kritisisme dan saran yang membantu saya untuk mempertajam analisis dalam penelitian ini;
3. Sri Mulyani, Ph.D. selaku reviewer, terimakasih telah bersedia
4. Segenap dosen IRB, baik yang masih mengajar atau tidak: Dr. Baskara T. Wardaya, Dr. St. Sunardi, Dr. Budiawan, Dr. G. Junus Aditjondro, Y. Devi Ardhiani, M.Hum., Dr. Ishadi S.K., Dr. Hary Susanto, terimakasih atas segala bimbingan dan pengarahan;
5. Staf Sekretariat Pascasarjana, Mbak Desi, terimakasih atas semua
„pesan-pesan mesranya‟ baik melalui SMS maupun Facebook yang selalu mengingatkan saya akan kewajiban-kewajiban administrasi di IRB. Terimakasih pula untuk Mas Mul yang membuat suasana kampus IRB menjadi begitu bersih dan menyenangkan;
6. Teman-teman IRB 2009, dengan urutan alfabetis: Abed (seorang
„pendeta‟ metroseksual, pastinya bukan aseksual), Agus (jejaka
Palembang yang selalu riang gembira), Anes (tipe idola para wanita), Elli (aktivis Marxist pemerhati rakyat kecil), Herlinatiens (novelis yang saya cemburui keproduktifannya), Leo (lelaki Jawa tulen yang saya puji ketenangan dan keluwesannya), Mbak Lulud (seorang suster
sekaligus traveller berdaya juang tinggi), Luc (seorang antropolog luar
dalam), Iwan (post-filsuf yang menolak gaek, sangat bergaya dalam
fashion dan tulisan), May (seorang aktivis ekofeminis yang sekarang entah di mana), Mas Probo (cukup dua kata: analitis, dan problematis), Rino (sekarang esmod muda Jakarta yang ceria), Titus (pelawak seumur hidup yang jenial), dan Virus (sastrawan muda Jogja
berbakat yang „katanya‟ tipe lelaki setia) - terimakasih atas
lelucon-lelucon nakalnya yang lalu mengilhami saya melakukan penelitian ini;
7. Teman-teman IRB lintas angkatan lintas generasi yang terus
menginspirasi saya dengan caranya masing-masing, utamanya untuk
angkatan 2012, you guys rock!;
8. Keluarga besar di Batusangkar: Cibu, Apa, dan Dodo atas dukungan
9. Sahabat-sahabat terkasih: Ndut, Runi, Mesi, dan Balo, terimakasih telah menemani saya menuntaskan tulisan ini, meski itu dengan dengkuran kalian;
10.M.C., terimakasih telah menjadi „konselor pribadi‟ yang
menyenangkan. Without you, this thesis would be stylistically awful, as
my life would be literally dreadful. Let‟s go home, shall we?
Akan halnya atap rumah, terlalu lama berjemur, lama kelamaan tirislah di beberapa bagian. Thesis ini persis demikian. Dengan segera dapat ditemukan bolongan-bolongan yang mengganggu. Kacamata yang saya pakai, belum begitu terang dalam melihat. Kalaupun thesis ini tak dapat menjadi contoh bagaimana seharusnya thesis itu dibuat, setidaknya thesis ini dapat menjadi kebalikannya. Untuk ini, saya rela menjadi pengikut Jung, yang suatu
kali bilang: “Mistakes are, after all, the foundations of truth, and if a man
does not know what a thing is, it is at least an increase in knowledge if he
knows what it is not.”
Yogyakarta, September 2013
ABSTRAK
Perempuan sebagai pajangan tentunya bukan hal yang asing dalam sinema kita. Begitupun dalam film komedi. Sedari masa jaya di tahun 1970-an hingga dewasa ini, wilayah dada d1970-an paha perempu1970-an tak pernah absen dipajankan. Kontras halnya dengan tubuh laki-laki. Tubuh laki-laki lebih sering dihadirkan dalam bingkai yang non-erotis. Laki-laki juga acap kali didudukkan sebagai penonton, ketimbang yang ditonton.
Quickie Express, sebuah film komedi dewasa keluaran tahun 2007 berpotensi untuk menghadirkan seksualitas laki-laki dengan agak banyak.
Maka, dengan menyorot film Quickie Express secara partikuler, penelitian ini
hendak menunjukkan bagaimana persisnya tubuh laki-laki ditampilkan dan dikonsumsi. Penekanannya bukan soal apakah tubuh itu tampak atau tidak,
tapi yang terpenting bagaimanakah kamera memposisikan „penonton‟ untuk
memandang tubuh tersebut.
Untuk mencapai tujuan itu, dipakailah pendekatan psikoanalisis seperti yang diterapkan oleh Neale. Pendekatan ini menimbang keterpandangan tubuh laki-laki dengan meninjau dimensi fetishisme, voyeurisme, dan identifikasi. Dengan demikian, perkara bingkai dan gerakan kamera, jalur cerita, lanjut arah pandang karakter di dalam layar, menjadi titik perhatian yang penting dalam melakukan analisis.
Dari pengkajian yang dilakukan terlihat bahwa kamera masih bersikap hati-hati dalam menampilkan tubuh laki-laki. Di satu sisi, kamera ingin menjaga supaya tubuh itu kelihatan, di saat yang bersamaan berusaha pula untuk menutup-nutupinya. Di samping itu, laki-laki juga memiliki kontrol
terhadap narasi, hingga ia mampu mengembalikan pandangan „penonton‟
bahkan balik mengobyektivikasi. Di sinilah letak bedanya antara
pengkonsumsian terhadap tubuh perempuan dan laki-laki. Bila perempuan dapat dipandang dari segala arah dan oleh laki-laki mana saja, maka
keterpandangan terhadap tubuh laki-laki serba terbatas. Dalam Quickie
Express diperlihatkan tubuh laki-laki tidak dapat dinikmati sembarang wanita, melainkan melalui kaca mata tante-tante girang serta waria.
ABSTRACT
Watching female flesh on the center of the screen is nothing extraordinary in Indonesian cinema. Comedy movies are no exception. Since the heyday of comedy on 1970s until recently, female breast and thigh have always been on display. In a stark contrast, male objectification is rare. Male body hardly connotes a sexual object. In fact, male used to be framed as a spectator, rather than a spectacle.
Quickie Express, an adult comedy released on 2007, has a great potential to explore male sexuality. Focusing particularly on the visual aspect of Quickie Express, this research aimed to investigate how male body is displayed and consumed. The emphasis is less on whether the body is seen or not, but more on how the camera directs „the spectator‟ to look at that body.
To pursue that goal, this research applied psychoanalysis approach as suggested by Neale. This approach determined the exposure of male body by considering the dimension of fetishism, voyeurism, and identification. Therefore, camera‟s frame and movement, narration process, and spectatorial look of each character on the screen, would be closely examined.
The result showed that camera reacted ambivalently when exposing male body. On the one side, camera seemed to ensure that the male body is shown, while, simultaneously, it made an attempt to cover that body. Besides, male has an enormous control toward the narration, so he is able to turn back „the spectator‟ gaze, and in turn, objectivise its spectator. Here lies the difference between the way how male body and female body is consumed. Female body can be seen in any direction by any male, meanwhile male body is only can be seen in a flash, limited only through the eye of unhappyly married women and transvestites.
DAFTAR ISI
LEMBAR PERSETUJUAN... i
LEMBAR PENGESAHAN... ii
LEMBAR PERNYATAAN... iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI... iv
KATA PENGANTAR... v
ABSTRAK... viii
ABSTRACT... ix
DAFTAR ISI... x
BAB I PENDAHULUAN... 1
A. Latar Belakang... 1
B. Rumusan Masalah... 13
C. Tujuan Penelitian... 13
D. Manfaat Penelitian... 13
E. Tinjauan Pustaka... 15
F. Kerangka Penelitian... 21
G. Metodologi Penelitian... 24
H. Skema Penulisan... 28
BAB II MENYOAL FILM KOMEDI INDONESIA... 30
A. Film Komedi: Film untuk Ha-Ha-Hi-Hi?... 31
B. Meneroka Film Komedi Indonesia Terdahulu... 35
C. Reformasi dan Kemunculan Film Komedi Dewasa Indonesia... 52
D. Melirik Produksi Quickie Express... 81
BAB III POTRET LAKI-LAKI DALAM FILM QUICKIE EXPRESS...
93
A. Laki-Laki Pekerja: Miskin dan Lusuh... 95
B. Laki-Laki Calon Pekerja Seks: Seksi dan Saru... 112
C. Laki-Laki Pekerja Seks: Kaya dan Berkuasa... 122
D. Tinjauan... 142
BAB IV MEMANDANG LAKI-LAKI DALAM FILM QUICKIE EXPRESS... 146
A. Laki-Laki Pekerja: Seksualitas yang Absen... 148
B. Laki-Laki Calon Pekerja Seks: Laki-Laki Sebagai Obyek Seks?... 176 C. Laki-Laki Pekerja Seks: Si Pemburu Narsis... 187
D. Tinjauan ... 212
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN... 217
A. Kesimpulan... 217
B. Saran... 219
DAFTAR ILUSTRASI
1.1. Bingkai kamera... 26
1.2. Sudut pengambilan kamera... 27
2.1. Gambar sampul VCD Inem Pelayan Seksi... 46
2.2. Gambar poster dan sampul VCD film Warkop: Sudah Pasti Tahan (Arizal, 1991), Bisa Naik Bisa Turun (Arizal, 1991), dan Depan Bisa Belakang Bisa (Tjut Djalil, 1987)... 50
2.3. Poster film-film komedi dewasa Indonesia: Quickie Express (Dimas Djayadiningrat, 2007), Namaku Dick (Teddy Soeriaatmadja, 2008), XXL: Double Extra Large (Ivander Tedjasukmana, 2009), dan Susah Jaga Keperawanan di Jakarta atau Urbany Sexy (Joko Nugroho, 2010)... 80
3.1. Jojo mengepel lantai toserba... 98
3.2. Jojo dicubit oleh salah seorang pengunjung toserba... 100
3.3. Perbandingan gambar adegan bikini Jojo dan seorang perempuan... 104
3.4. Jojo meraba bagian genitalnya... 105
3.5. Mudakir dan calon mangsanya... 106
3.6. Ekspos wilayah perut dan selangkangan Jojo... 109
3.7. Jojo memasuki restoran Quickie Express... 111
3.8. Rekan baru Jojo: Marley dan Piktor... 116
3.9. Latihan tari tiang... 118
3.10. Jojo, Piktor, dan Marley berlatih tari... 119
3.11. Jojo, Piktor, dan Marley mencontoh gerakan trainer... 120
3.12. Jojo, Piktor, dan Marley dipajang pada calon klien... 123
3.14. Kencan pertama Piktor... 127
3.15. Kencan pertama Marley... 128
3.16. Kencan pertama Jojo... 129
3.17. Jojo dilecut di tempat tidur... 130
3.18. Gigolo level advance... 132
3.19. Kencan Jojo dengan Tante Mona... 133
3.20. Jojo versus Teddy di lantai dansa... 135
3.21. Jojo dan Jan Pieter... 138
3.22. Jan Pieter dan Mateo... 139
3.23. Perpisahan... 141
3.24. Jojo sebagai pemburu... 142
4.1. Gerakan diagonal kamera menyorot Jojo menari... 149
4.2. Jojo mengembalikan pandangan „penonton‟... 150
4.3. Menjelang opening title film Inem Pelayan Seksi... 151
4.4. Bingkai XLS saat Jojo menari... 153
4.5. Inem si babu seksi... 154
4.6. Jojo yang menari diambil dari arah belakang... 155
4.7. Antara Jojo, kerumunan, dan barang obralan... 156
4.8. Antara klien Jojo dan gadis berpakaian renang... 160
4.9. Gadis berpakaian renang... 162
4.10. Jojo di kontrakan... 168
4.11. Waria dalam film Love is Brondong...... 173
4.12. Kamera bergerak menjauhi pria yang sedang menari... 179
4.13. Antara instruktur tari, Jojo, dan boneka wanita... 181
4.14. Memajankan tubuh laki-laki pada khalayak wanita... 187
4.15 Gerak vertikal kamera menyorot klien pertama Jojo... 193
4.17. Perempuan yang disangka klien Piktor... 196
4.18. Proses de-erotisasi terhadap klien Jojo... 198
4.19. Keengganan kamera mengobyektivikasi tubuh Piktor... 202
DAFTAR TABEL
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Jika ada yang bertanya film Indonesia mana yang membuat saya
tercengang-cengang, Quickie Express (Dimas Djayadiningrat, 2007) adalah
jawabnya. Menonton film ini tiga tahun setelah rilis, saya masih
terheran-heran dengan „kecanggihan‟ yang disajikannya. Kecanggihan yang tidak
semata-mata saya tumpukan pada estetika kamera, namun terlebih kepada
tema, teks (skrip), dan adegan yang luar biasa „memalukan‟. Barangkali penilaian ini terdengar berlebihan. Sebab, saya tak cukup punya
perbendaharaan film-film lokal untuk benar-benar membandingkan. Namun,
di balik keterbatasan itu, inilah kali pertama telinga saya menangkap kata
seperti „biji‟ begitu lantang diucapkan dalam film nasional.1 Berani kesannya.
Ihwal Quickie Express, film berdurasi 117 menit ini beredar pada
penghujung 2007 lewat jaringan bioskop Cinema 21 dan Blitz Megaplex.
Penonton yang tercatat lebih dari 1 juta.2 Jumlah ini tergolong tinggi. Kalau
hendak dijejer berdasar peringkat, Quickie Express berada di posisi ke-4.3
Angka ini terbatas pada mereka yang menyaksikan di bioskop. Penonton dari
media lain, semisal cakram DVD - mau yang orisinal maupun bajakan, belum
lagi masuk hitungan. Begitupun dengan penonton media virtual macam
internet. Film yang sama saya temui nangkring di situs youtube semenjak
1
Film Indonesia awal yang menyertakan kata-kata atau dialog ‘kasar’, disebut Kristanto, yakni Bernafas Dalam Lumpur (Turino Djunaidy, 1970). Dalam film ini disebutkan bermacam makian, semisal sundel. (Sumber: Kristanto, JB. 1995. Katalog Film Indonesia 1926 – 1995. Grafiasri Mukti: Jakarta, hal: 79)
2
Sumber: http://filmindonesia.or.id, diakses tanggal 3 Mei 2011 3
2009 dalam 11 potongan video. Pada tanggal 1 April 2012, film tersebut
diunggah lagi secara utuh dengan jumlah viewer mencapai 1,630,792.4
Bila Quickie Express didudukkan dengan film-film di jamannya, film ini
terkesan mencolok. Jelas, Quickie Express hadir di tengah dominasi film-film
horor. Sebagaimana diamati Darmawan, periode 2007 – 2008 merupakan
jamannya tokoh-tokoh seram menghantui dunia sinema kita.5 Untuk tahun
2007 saja, dari 52 judul film yang diproduksi tahun 2007, hampir
setengahnya film horor. Sementara, film drama berjumlah 11 judul. Film
komedi bahkan lebih sedikit, hanya 5 judul.6
Tak hanya menang dari segi jumlah, film hantu-hantuan tersebut juga
tak kalah menguntungkan dari segi pendapatan. Dari deretan 10 film yang
paling laku tahun 2007, 6 judul diantaranya adalah film horor. Film-film
tersebut yakni: Terowongan Casablanca (Nanang Istiabudi, 2007), Suster
Ngesot The Movie (Arie Azis, 2007), Pulau Hantu (Jose Poernomo, 2007),
Pocong 3 (Monty Tiwa, 2007), Lantai 13 (Helfy C.H. Kardit, 2007), dan
Kuntilanak 2 (Rizal Mantovani, 2007).7
Singkat cerita, Quickie Express adalah anomali dalam industri film
tahun 2007. Film ini membuat penonton terkaget-kaget bukan karena
keseramannya, melainkan pada „kekurangajarannya‟. Tak heran jika lalu
Quickie Express digelari film komedi seks pertama Indonesia.8 Film ini dengan
gamblang menarasikan berbagai lelucon-lelucon nakal yang ada kalanya tak
masuk akal. Kalau tidak dibetah-betahkan, sulit rasanya menikmati film ini
4
Sumber: http://www.youtube.com/watch?v=Seldn3IRWNI, diakses tanggal 16 Agustus 2013 5
Darmawan, Hikmat. “Mengapa film horor (1)” (Sumber: http://new.rumahfilm.org/artikel-feature/mengapa-film-horor-1/, diakses tanggal 18 November 2011)
6Aartsen, Josscy. 2011. “Film world indonesia: The rise after the fall.”
Thesis di Universitas Utrecht, hal: 29 (Sumber: igitur-archive.library.uu.nl, diakses tanggal 14 Juli 2011)
7
Sumber: http://filmindonesia.or.id, diakses tanggal 3 Mei 2011 8
sampai tuntas. Quickie Express lebih cabul dibanding film kebanyakan. Meski,
masih terbilang „lunak‟ jika dipatut-patut dengan film komedi dewasa impor macam American Pie atau Korea punya: Sex is Zero. Quickie Express tak
sampai menyertakan ketelanjangan penuh. Kalau yang „sekadar‟ mengintip-ngintip, ya banyak.
Lalu, apa yang menarik dikaji dari Quickie Express? Sebelum
menjawab pertanyaan ini, saya akan mengingsut-ingsut terlebih dahulu
dengan membahas persoalan tema, narasi (alur cerita), lalu berujung pada
soal visualisasi.
Mengenai tema, apa yang diusung Quickie Express tidaklah
sepenuhnya baru. Meski, masih ganjil di telinga. Jelasnya, film ini
mengangkat fenomena gigolo di daerah ibukota. Dikisahkan tentang tiga
orang pemuda: Jojo (Tora Sudiro), Marley (Aming Sugandhi), dan Piktor
(Lukman Sardi) yang sama-sama terjun dalam bisnis prostitusi. Mereka dilatih
menjadi “mesin seks tahan banting”, demikian istilah sang germo- yang siap pakai bagi „tante-tante‟ kaya raya. „Tante‟ di sini tak selalu merujuk pada perempuan paruh baya. Akan tetapi, dapat digunakan dalam arti
seluas-luasnya: mau yang tua atau kelewat renta, entah itu wanita atau juga waria.
Pokoknya, asal ada fulus, gigolo-gigolo muda nan ceria siap menunggu di
depan pintu anda.
Selanjutnya, petualangan tiga jagoan ini mengerucut pada kisah Jojo
seorang. Jojo diceritakan sebagai kaum melarat Jakarta yang punya banyak
kemauan. Sebelum menekuni profesi sebagai pekerja seks, ia sempat
mencicipi pahit getirnya bekerja sebagai petugas kebersihan, pembuat tato,
hingga terdampar di tempat tambal ban pinggir jalan. Lalu, ia berserobok
dengan Om Mudakir, keturunan Arab centil berjari ngetril. Om Mudakir
dengan girang hati merekrut Jojo menjadi „anak asuh‟ di layanan male escort
Jojo sebelum dan sesudah menjadi „anak didik‟ Om Mudakir sangatlah berbeda. Perbedaan yang tampak, umpama: dulu pemutar musiknya
konvensional, lalu diganti perangkat digital. Sebelumnya, ia berbaring di
kasur kapuk yang usang, kini ditukar kasur pegas ukuran double yang empuk.
Pokoknya, dari segi materi, Jojo serba wah. Hanya, dari segi cinta, ia kalah.
Kisah asmara Jojo kandas di tengah jalan. Gadis yang digandrunginya, Lila
(Sandra Dewi), ternyata anak dari „tante‟ yang memeliharanya. Tambah, ayah
Lila yang seorang mafioso lagi homo terobsesi pula padanya. Rumit dan
berbelit-belit. Itulah kata-kata yang pas untuk menggambarkan kehidupan
Jojo. Mengakhiri kemelut, Jojo melepas seragam gigolo lalu naik tingkat
menjadi „pemburu‟, the-next-Mudakir!
Telisik punya telisik, fenomena gigolo dan sejenisnya sudah berulang
kali diceritakan dalam film-film lawas. Bahkan dari tahun 1970-an saat
industri „film mesum‟, yang oleh Imanjaya diistilahkan “sexploitation film”9 - mulai marak. Untuk itu, saya ambilkan dua contoh: Noda Tak Berampun
(Turino Djunaedy, 1970) dan Pria Simpanan (Walmer Sitohang, 1997). Noda
Tak Berampun berdurasi 97 menit. Film ini merupakan kelanjutan dari
Bernafas Dalam Lumpur (Turino Djunaedy, 1970) yang dikenali sebagai “film
Indonesia pertama yang menonjolkan seks, perkosaan dan dialog-dialog
kasar.”10
Pria Simpanan durasinya lebih pendek, hanya 79 menit. Film ini
dipasarkan dalam bentuk VCD dengan judul yang lebih menantang: Gigolo
dan Tante Sex.11
Rais (Farouk Avero), yang berperan sebagai germo dalam Bernafas
Dalam Lumpur, dalam sekuelnya „turun jabatan‟ jadi „laki-laki bayaran‟. Gara
9Imanjaya, Ekky: “Idealism versus commercialism in Indonesian cinema: A neverending battle”
(Sumber:
gara ini ia cekcok dan bercerai dengan isterinya, Marina (Rima Melati). Lalu,
Marina menikah lagi dengan Budiman (Rachmat Kartolo). Sementara itu, Rais
masih menginginkan Marina. Ia pun melakukan segala daya dan upaya untuk
merebut mantan isterinya itu. Bahkan dengan jalan menculik anak Marina dan
Budiman. Malang, dalam adegan kejar-kejaran dengan polisi, mobil VW yang
dikemudikan Rais kecelakaan. Akhir cerita, Rais mati.12
Agaknya, permasalahan dalam kehidupan pekerja seks laki-laki tak
jauh-jauh dari pertentangannya dengan kehidupan rumah tangga atau
asmara. Hal serupa juga ditampilkan dalam film Pria Simpanan. Dikisahkan
Yuli (Megi Megawati13) adalah seorang „tante muda‟ yang kesepian, lebih-lebih dari sisi seksual. Suaminya, Yordan (Rengga Takengon), hanya seorang paruh
baya yang kebinalannya pun telah diperkosa waktu. Demikianlah, Yulia mulai
berpetualang dengan instruktur senamnya, Roy (Andre Bjenk). Hubungan ini
terendus suami Yulia yang lantas memerintahkan tukang pukul menciderai
alat vital Roy. Derita Roy bertambah ketika Atika (Indah Febrizha), sang
kekasih tercinta, pun berpaling dari sisinya. Tinggallah Roy sendiri, menyesali
diri.14
Saya paham, tidak sepenuhnya tepat membandingkan kedua film
tersebut dengan Quickie Express. Genre-nya jauh berbeda. Yang satu komedi,
lainnya drama. Namun, setidaknya ketiga film ini sejalan dalam
menggambarkan pekerjaan gigolo yang berkonflik dengan kehidupan
percintaan. Bedanya, Jojo dalam Quickie Express meskipun di awal
menyembunyikan profesinya dari Lila, namun ia sendiri pula yang membuka
12 Ulasan film ini didapat dari tulisan “BDL + NTB + ?” diterbitkan pada tanggal 13 Maret 1971 (Sumber:http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1971/03/13/fl/mbm.19710313.fl56868.id.htm,diakse s tanggal 20 Mei 2010)
13 Megi Megawati dikenal bermain dalam beberapa ‘film panas’, diantaranya:
Gairah 100%, Menentang Nafsu, Membakar Gairah, serta Nafsu Liar. (Sumber: http://www.mail-archive.com/aga-madjid@googlegroups.com/msg14209.html, diakses tanggal 5 April 2011)
14
„aib‟ tersebut. Ia tidak menunggu Lila untuk menangkapnya basah,
sebagaimana yang terjadi pada Roy dalam Pria Simpanan atau Rais dalam
Noda Tak Berampun. Jojo tidak ditinggalkan kekasihnya. Ia memilih untuk
pergi. Oleh karenanya, tak ada drama mengejar sampai mati seperti yang
dilakukan Rais. Jojo malah bangkit dan memulai „kehidupan baru‟. Akan tetapi, jangan terjemahkan „kehidupan baru‟ ini dengan Jojo bertobat atau pun insaf. Ia sudah kadung cinta pada „kehidupan malam‟ yang selama ini digaulinya.
Makanya, Quickie Express tak berpretensi menjadi penceramah moral
seperti film Indonesia pada umumnya. Sebagaimana dikaji Schmidt,
film-film Indonesia cenderung mengambil sikap yang moralistik ketika membahas
tema-tema seks. Boleh diambil satu contoh: Virgin (Hanny Saputra, 2004).
Meski Virgin menampilkan kehidupan remaja metropolis yang serba bebas,
ujung-ujungnya balik lagi ke „kebijakan moral‟. „Kebajikan‟ yang diajarkannya yakni: “when you maintain bodily integrity, your dreams will come true, but when violate bodily boundaries punishment will follow.”15
Quickie Express, seperti ditulis Darmawan, malah menampik „ceramah
moral‟ macam Virgin. Kalaupun ada wacana atau pun moral yang
disampaikannya justru ketidakpedulian terhadap wacana dan moral itu
sendiri.16 Sikap yang abai terhadap nilai ini dapat dicatat sebagai fenomena yang langka dalam sinema Indonesia. Pasalnya, dari masa Orde Baru,
film-film terutama yang berkenaan dengan dunia prostitusi – cenderung moralistik di akhir. Ini dimaksudkan agar bisa lolos dari guntingan badan sensor.17
15
Schmidt, Leonie. 2012. Post-Suharto screens: Gender, politics, Islam and discourses of modernity. Amsterdam Social Science Vol. 4: 1, hal: 43
16 Darmawan, Hikmat: “
Quickie Express: Mengkhianati WARKOP” (Sumber: http://new.rumahfilm.org/resensi/layar-lebar/quickie-express-mengkhianati-"warkop"/, diakses tanggal 25 Maret 2011)
17
Selepas mengurai narasi (skrip), mari beranjak pada persoalan
visualisasi. Dengan niatan menggambarkan dunia pergigoloan, tak heran bila
Quickie Express mempertontonkan tubuh dalam kadar berlebih. Namun, jika
selama ini saya terbiasa menyaksikan pemeran wanita berbusana menantang,
sekarang giliran laki-laki yang melakoni adegan-adegan mendebarkan. Kadar
„buka-bukaan‟ yang ditampilkan Quickie Express termasuk di luar tradisi,
meski tak sampai menampilkan full-frontal nudity. Kabarnya Lembaga Sensor
Film (LSF) memotong film ini sepanjang 2 meter.18 Walau, shoot bagian
bokong Tora Sudiro dan Amink dapat terlihat jelas di beberapa adegan. Belum
lagi gerakan erotis yang diperagakan ketika mereka latihan. Alamak, sangat
mencengangkan!
Di samping parade laki-laki bergaya mesum tersebut, Quickie Express
disebut-sebut memperkenalkan, sebut saja maskulinitas alternatif- dalam
khazanah film Indonesia. Secara spesifik disebutkan, “it [Quickie Express]
adds an unusual dimension to the portrayals of masculinities in the
post-Suharto era”.19 Apa yang dinilai „berbeda‟ dari Quickie Express, bahwa pada
titik tertentu, peran laki-laki dan perempuan seakan-akan dibalik. Alih-alih
menggambarkan perempuan yang pasif, Quickie Express menampilkan
perempuan yang aktif dan agresif. Laki-laki yang biasanya ditampilkan
sebagai „predator‟, dalam Quickie Express malah diposisikan sebagai yang penurut dan patuh.20
Sebagai pembanding, untuk gambaran perempuan yang pasif, dalam
artian yang berlaku sebagai pemanis, bisa ditemukan dengan gampang di
film-film komedi Indonesia. Bahkan, pada kebanyakan film cerita.21 Film-film
18
Sumber: http://filmindonesia.or.id 19
Warkop merupakan contoh yang cukup baik untuk ini. Jika James Bond punya
koleksi Bond’s girl, Warkop juga punya Warkop’s girl. Kiki Fatmala, Sally Marcellina, Lidya Kandou, dan Inneke Koesherawati merupakan diantaranya.
Nurul Arifin, mantan gadis Warkop lainnya, mengomentari perannya: “[...] kehadiran saya di film kelompok ini memang seperti kosmetik.” Eva Arnaz,
yang membintangi sembilan judul film Warkop, bercerita kerap digoda
teman-temannya: “Alaa, mereka [penonton] tuh datang [ke bioskop] gara-gara
pengen ngeliatkamu Va”.22
Pengakuan Nurul Arifin, begitupun Eva Arnaz, seturut dengan hasil
kajian Laura Mulvey tentang posisi perempuan dalam sinema. Jika Nurul
membayangkan dirinya sebagai kosmetik, Mulvey menerjemahkannya dengan
“image”. Dalam pandangannya, kehadiran perempuan dalam film adalah
sebagai pajangan, setara benda mati. Seberapapun pentingnya peran
perempuan ini, bukanlah untuk kepentingan perempuan itu sendiri.
Melainkan, tegas Mulvey, untuk memenuhi hasrat voyeuristik bagi tokoh
laki-laki di dalam film, begitupun penonton. Sebab, penonton akan
mengidentifikasikan dirinya dengan tokoh laki-laki dalam film, untuk lalu
menikmati perempuan sebagaimana tokoh tersebut menikmatinya.23
Quickie Express, dalam hal ini, bukan pengecualian. Meski dalam
artian tertentu, kesenangan melihat ini tak selalu dipuaskannya, bahkan
dapat serta-merta buyar. Untuk tak terlalu mengawang, tengok saja adegan
ketika Jojo bertemu dengan klien pertamanya. Bagaimana Jojo menatap si
Meski kemudian ia harus dikecewakan, begitu pun penonton, karena si
perempuan seksi ternyata (berjenis kelamin) laki-laki.
Lalu, berpikir sederhana, dengan mengekor pada logika Mulvey,
apakah ketika laki-laki diposisikan sebagai obyek seksual, seperti yang terjadi
dalam Quickie Express- akan menstrukturkan penonton untuk melihat dari
sudut pandang perempuan? Dengan kata lain, apakah Quickie Express dapat
dibilang menghadirkan semacam female gaze?
Perbedaan seks/gender, untuk tidak langsung mengasumsikan
ketidaksetaraan seks/gender- sedikit banyaknya tentu mempengaruhi cara
penikmatan laki-laki dan perempuan. Kasarnya, pada tingkatan yang paling
ekstrem, jika film biru untuk laki-laki dibuat dengan menitikberatkan pada
pemeran perempuan, apakah film biru untuk perempuan cukup dibuat dengan
menggeser posisi kamera pada tubuh laki-laki?
Di samping itu, untuk tak terlalu optimis, agaknya persoalan mengenai
female gaze ini lebih kompleks dari sekedar merubah fokus kamera. Sebab,
sebagaimana dipesankan Steve Neale erotisasi terhadap tubuh laki-laki
beresiko memunculkan apa yang disebut sebagai “homosexual overtone”24. Untuk menghindari kesan homoseksual ini pulalah makanya laki-laki jarang
dihadirkan sebagai pajangan serupa perempuan. Jikalau laki-laki
mempertontonkan tubuhnya, sambung Neale, tidak langsung dipasang
terang-terang di muka penonton. Pandangan penonton selalu dimediasi oleh
pandangan tokoh atau karakter lain di film. Dan pandangan ini juga bukan
dalam artian seksual, tapi lebih mencerminkan ketakutan, kebencian, atau
bahkan agresivitas.25
Lalu, bagaimana dengan para lelaki dalam Quickie Express? Sebagai
film yang menokohkan laki-laki, plot film ini pun digerakkan dari sudut
24
Glover, David & Cora Kaplan. 2000. Genders. Routledge: London and New York, hal: 153 25
pandang laki-laki. Namun, itu tak berarti cerita akan selalu berpihak kepada si
tokoh. Laki-laki di sini tak selalu berfungsi sebagai “bearer of the look”26. Malah, di banyak kesempatan laki-laki sengaja dipajang sekadar untuk
dipandang-pandang. Serupa tontonan.
Untuk menjelaskan poin tersebut, saya mengajukan satu contoh.
Dalam adegan perkenalan dengan calon pembeli (baca: tante), Jojo dan
kedua rekannya, separuh telanjang, ditempatkan di ruangan berkaca
transparan yang terang benderang. Sedangkan, para tante duduk manis
menyaksikan di ruangan lain yang temaram. Posisi mereka membelakangi
kamera, paralel dengan penonton. Dengan demikian, tubuh-tubuh yang
terpampang jelas-jelas di depan menjadi obyek tatapan baik para tante,
maupun penonton yang berada di luar.
Akan tetapi, erotisasi terhadap tubuh laki-laki dalam Quickie Express
rupanya berjalan setengah-setengah, alias nanggung. Meski Jojo dan
rekan-rekan tampak bugil sebugil-bugilnya, tubuh yang mereka pertontonkan
tampak tak istimewa. Mencerminkan tubuh laki-laki kebanyakan ketimbang
sebuah persona „ideal‟. Setidaknya ideal dengan mengekor pada macam laki-laki dengan tubuh kekar berisi sebagaimana ditampilkan majalah-majalah gay
yang diteliti Boelllstorff27. Alih-alih menawarkan “a perfect product”28, Quickie
Express malah mengusung apa yang diapresiasi Lee sebagai “weird and
unorthodox concepts of beauty”29
. Benar, di satu sisi Quickie Express dapat
menjadi wacana tandingan terhadap konsep maskulinitas atau laki-laki yang
dominan. Namun, di sisi lain, kenikmatan memandang yang tadi sudah
terjanjikan berkat narasi dan pemosisian kamera, lalu malah berubah menjadi
26
Mulvey, Laura. Op.cit., hal: 750 27
Boellstorff, Tom. 2004. Zines and zones of desire: Mass-mediated love, national romance, and sexual citizenship in gay Indonesia. The Journal of Asian Studies Vol. 63: 2, hal: 381; 384; 394
28
Mulvey, Laura. Op.cit., hal: 754 29
kekonyolan. Dengan sendirinya, kesan sensual (dan potensinya menjadi
sebuah tontonan homoerotik) pun terpinggirkan, jika tidak hilang sama sekali.
Tentu, dari sudut pandang subyektif, penonton aktual orang per orang,
pemaknaan terhadap tubuh laki-laki akan sangat beragam. Oleh karenanya,
perbincangan tentang penonton ini baiknya dipilah tepat-tepat.30 Setidaknya, harus jelas perbedaan antara penonton yang sebenarnya dengan penonton
sebagaimana diimplikasikan oleh pembahasaan kamera. Penonton yang
kedua ini bukan macam penonton yang duduk manis di depan layar, akan
tetapi penonton yang menyaksikan dari dalam layar. Penonton yang dibentuk
oleh teks film, dan hadir bersama-samaan dengan teks film itu sendiri.31 Persisnya, Mulvey, begitupun Neale, hanya sanggup hingga
pembicaraan bagaimana suatu film dapat dinikmati, tanpa
bersungguh-sungguh mengetahui bagaimana kejadian sebenarnya di lapangan.32 Ini bisa jadi sebuah keterbatasan. Namun, terlalu sibuk dengan penonton dalam
artian fisikal ini malah membuat teks film jadi terpinggirkan. Padahal, jumlah
penonton tak membuat suatu film „lebih film‟ ketimbang film lain. Maka, yang
menjadi penekanan kemudian adalah apa yang disampaikan dan dimuat di
dalam teks alih-alih menelaah pencerapannya secara langsung.
Sungguh pun demikian, saya tidak bermaksud mengatakan antara
penonton aktual dengan, sebut saja „penonton imajiner‟- berada dalam posisi yang sama sekali bertentangan, pun tidak pula akan selalu bersesuaian.
„Penonton imajiner‟ ini berkenaan dengan bagaimana sebuah film
30
Saya diingatkan tentang perlunya pemilahan penonton ini lewat tulisan Saputro. Meski, kategori yang dipakainya sama sekali berbeda. Ia membedakan antara penonton aktual dengan “penonton” (dengan tanda petik) yakni penonton sebagaimana dibayangkan atau diimajinasikan oleh pembuat film, lembaga sensor, media massa, dll. (Sumber: Saputro, Kurniawan Adi. 2005. “Melihat ingatan buatan: Menonton penonton film Indonesia 1900 – 1964”. dalam Penghibur(an): Masa Lalu dan Budaya Hidup Masa Kini Indonesia. Ed. Budi Susanto. Penerbit Kanisius: Yogyakarta, hal: 174)
31
McGowan & Kunkle mengistilahkan “internal spectator”. (Sumber: McGowan, Todd & Sheila Kunkle. Eds. 2004. Lacan and Contemporary Film. Other Press: New York, hal: xix – xxiii)
32
menghadirkan dirinya, bagaimana ia menstrukturkan penonton untuk melihat
dari posisi tertentu. Namun, apakah penonton di luar akan selalu mengambil
posisi ini, itu lain soal.
Berikut adalah gambaran penikmatan Quickie Express dari sudut
pandang penonton aktual. Saya menemukan catatan seorang blogger33
mempersaksikan para penonton perempuan menjerit-jerit histeris saat
menyaksikan Quickie Express. Tidak jauh berbeda dengan pengalaman saya
sendiri. Saya dalam posisi sebagai perempuan, berulang kali harus melengos
menonton laki-laki beraksi dengan gerakan yang demikian provokatif.
Gigolo-gigolo Quickie Express, saya perlakukan setara dengan obyek-obyek sadis
dan mengerikan yang membuat saya harus memalingkan muka. Perkara
mengapa saya sampai mengalihkan pandangan, atau refusal to look34 kalau kata Linda Williams- tentunya tidak terlepas dari pembahasaan kamera dalam
mengeksplorasi tubuh laki-laki. Kamera membingkai, mengarahkan dan
menuntun gerak pandang saya terhadap obyek-obyek tertentu pada tubuh
laki-laki yang kemudian saya nilai (tidak) pantas dilihat dekat-dekat.
Namun, patut dipertimbangkan pula, kasus penolakan memandang ini
bukan khas perempuan (meski dalam penelitian ini saya hanya akan memakai
perbedaan seks/gender/orientasi seks sebagai acuan). Terlepas dari kategori
itu, saya menemui kesaksian yang menyebut adanya penonton yang keluar
bioskop sebelum film tuntas. Mereka terdiri dari laki-laki dan perempuan,
entah itu dalam relasinya sebagai orang tua dan anak atau juga pasangan
muda-mudi. Penonton yang bertahan dan tertawa, atau sederhanakan saja
yang pro-Quickie Express, beranggapan bahwa mereka yang kabur itu
33
Sumber: http://leoganda.wordpress.com/, diakses tanggal 22 Maret 2011 34
terlewat naif. Sementara, penonton yang keluar, atau kontra-Quickie Express
– merasa lawakan Quickie Express terlalu ofensif.35 Nah, dalam hal ini, tentu
masalah nilai (etika, moral, atau bahkan agama) yang lebih berperan.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah tubuh laki-laki ditampilkan dalam teks visual film
komedi dewasa Quickie Express?
2. Bagaimanakah teks visual film komedi dewasa Quickie Express
memposisikan „penonton‟ dalam melihat tubuh laki-laki?
C. Tujuan Penelitian
1. Memetakan kode-kode yang dipakai kamera dalam menampilkan
tubuh laki-laki dalam teks visual film komedi dewasa Quickie
Express;
2. Mengidentifikasi struktur pandangan yang dibentuk melalui teks
visual film komedi dewasa Quickie Express.
D. Manfaat Penelitian
Ketika hendak mengkaji gender dalam film/sinema, perhatian acap kali
tertuju pada persoalan perempuan.36 Obyektivikasi, komodifikasi, atau subordinasi seakan menjadi „nama umum‟ buat melabeli perempuan di ranah ini. Alih-alih menggugat mengapa laki-laki ditampilkan demikian „heroik‟ sebagai pencari nafkah sementara perempuan hanya „mainan‟ di dapur
35
Diantaranya dapat dicek di situs-situs: http://www.titiw.com/category/entertainment/movie/ (diakses tanggal 22 Maret 2011); http://leoganda.wordpress.com/ (diakses tanggal 22 Maret 2011); http://ple-q.com/myblog/quickie-express-ngakak-abis.html (diakses tanggal 12 April 2011); http://mistervandysays.wordpress.com/2007/11/26/review-quickie-express/ (diakses tanggal 28 Maret 2011); http://www.exodiac.com/001676/QUICKIE-EXPRESS.htm (diakses tanggal 10 Desember 2010);
http://mumualoha.blogspot.com (diakses tanggal 25 Maret 2010);
http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2007/12/03 (diakses tanggal 26 Juli 2011). 36
sumur-kasur, saya cenderung mempertanyakan mengapa keduanya
disandingkan dan diperbandingkan seakan-akan berada dalam sebuah arena
pacuan? Kasarnya, persoalan mana yang depan dan belakang bisa berubah
seketika seseorang membalikkan badan.
Oleh karena itu, penelitian ini melepaskan diri dari soal emansipasi.
Tidak menuntut, sebut saja – „representasi yang positif‟ bagi laki-laki dan perempuan di dalam sinema. Mungkin ini terdengar naif. Namun, bagi saya,
kategori positif dan negatif itu sangat cair sifatnya. Bukannya nilai selalu
berubah-ubah, sama seperti halnya air yang berganti wujud mengikuti
wadahnya? Hal lain, jujur saja, kategori itu membingungkan saya. Apakah
dengan mereka-reka bagaimana supaya laki-laki tampil lebih seksi di depan
kamera dapat dianggap sebagai suatu hal yang positif?
Sederhananya, karena penelitian ini fokus membahas laki-laki,
sekurang-kurangnya dapat memperpanjang deretan kajian laki-laki (berikut
gender) barang satu kolom. Selebihnya, apa yang menjadi semangat utama
dalam penelitian ini, menyorot problematika dalam menampilkan laki-laki
dalam sinema. Penekanannya bukan pada apakah laki-laki diobyektivikasi
atau tidak, namun lebih pada bagaimana proses obyektivikasi atau
deobyektivikasi itu terjadi. Kalau hal ini ditelusuri lebih lanjut, dapat pula
dilihat bagaimana Quickie Express ikut menyumbang pada pembentukan
wacana maskulinitas di Indonesia.
Di samping itu, yang tak kalah penting, penelitian ini saya tujukan
untuk memperkaya kajian sinema Indonesia. Ini saya anggap mendesak
sebab tak satu dua keluhan tentang minimnya literatur dunia perfilman
Indonesia37. Oleh karenanya, ketimbang berkeluh-kesah soal mutu film
37
Indonesia yang payah, saya rasa ini saatnya menemukan dan mengabarkan
bahwa masih banyak hal-hal berharga yang bisa digali dari sana.
E. Tinjauan Pustaka
Sebagai film yang mengusung tema sedikit „nakal‟, Quickie Express
tentu menarik diteliti. Lagipula, ia cukup populer. Quickie Express menempati
peringkat 4 sebagai film terlaris tahun 2007.38 Saya memang menemukan
beberapa penelitian yang mengkaji film ini. Namun, sejauh yang dapat
ditelusuri, fokus utamanya dihadapkan pada representasi gigolo yang
ditampilkan Quickie Express dengan pisau bedah semiotika Barthes. Selain
itu, ada pula yang hendak melihat muatan pesan kekerasan, seks, dan mistis
dalam Quickie Express dengan berbekalkan metode analisis isi kuantitatif.
Marphin mengkaji representasi gigolo dalam film Quickie Express
dengan menggunakan analisis denotasi dan konotasi Barthes. Ada beberapa
aspek yang menjadi perhatiannya, diantaranya pekerjaan dan profesionalisme
gigolo, kemerdekaan dalam memilih klien, gigolo sebagai pekerjaan yang
marginal, hingga gigolo yang insyaf. Dalam analisanya, Marphin
berkesimpulan pekerja seks laki-laki ini meskipun ditampilkan sebagai
„obyek‟, namun ia memiliki kebebasan untuk memilih konsumen yang
diinginkannya. Sementara itu, dia juga mengangkat sisi profesionalitas gigolo
yang kemudian membedakannya dari pekerja seks wanita maupun waria. 39
Jika Marphin fokus pada masalah kegigoloan, penelitian saya justru
lebih berat pada masalah laki-lakinya: berkutat pada pertanyaan bagaimana
38
Sumber: http://filmindonesia.or.id, 3 Mei 2011
39Marphin, G.F.S. 2010. “Studi semiotik representasi gigolo dalam Quickie Express”
. Skripsi pada Universitas Airlangga, Surabaya. (Sumber: http://alumni.unair.ac.id/detail.php?id=27301 &faktas=Ilmu%20Sosial%20Ilmu%20Politik, diakses pada tanggal 16 Agustus 2013). Selain skripsi Marphin, saya juga menemukan skripsi lain atas nama Winnie Pratiwi yang juga mengkaji representasi gigolo dalam film Quickie Express dari Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Malang. (Pratiwi, Winnie.
2008. “Representasi kehidupan gigolo dalam film Indonesia”,
laki-laki ditampilkan dan dinikmati secara visual. Menjadi gigolo, dalam hemat
saya, hanyalah strategi yang dipakai agar aspek erotik laki-laki dapat diakses
dengan „relatif lebih aman‟. Meski, tetap saja, erotisasi tersebut akan menemui beberapa ganjalan. Misal, dengan mengedepankan lawakan yang
membuat tarian striptease seolah-olah pertunjukan topeng monyet!
Selanjutnya, saya menemukan penelitian Juarsa yang mengkaji
analisis isi pesan dalam film Quickie Express serta 4 film lain yang termasuk
jajaran terlaris di tahun 2007. Film-film tersebut antara lain: Get Married,
Terowongan Casablanca, Nagabonar Jadi 2, dan Film Horor. Hasil
penelitiannya mengungkapkan bahwa 40% dari film-film tersebut memuat
pesan kekerasan, 36% mistik, dan 24% seks. Kesimpulannya jelas, film laris
tahun 2007 didominasi oleh adegan kekerasan dan mistik ketimbang
pornografis.40
Data Juarsa tersebut berguna untuk memperoleh gambaran umum
tentang konten film yang banyak ditonton tahun 2007. Sayangnya, tidak ada
petunjuk bagaimana masing-masing film menampilkan kekerasan secara
berbeda. Apakah kekerasan dilakukan sebagai cara membela diri, untuk
bertingkah sebagai jagoan, atau karena tak mampu mengendalikan emosi?
Adapun rancangan penelitian saya juga fokus pada teks (konten) film. Dalam
artian ini, saya dan Juarsa sejalan dalam hal tidak menyoal resepsi atau pun
produksi. Bedanya, kalaupun saya menyinggung tentang kekerasan itu dalam
kaitannya dengan taktik film untuk mengekspos tubuh laki-laki lebih banyak.
Berbicara lebih lanjut tentang laki-laki dalam film Indonesia, adalah
Marshall Clark diantara segelintir peneliti yang menunjukkan minatnya. Clark
mengkritik, diantaranya dialamatkan kepada Karl Heider dan Khrisna Sen -
perihal analisis gender dalam sinema Indonesia yang melulu menitikberatkan
pada perempuan.41 Paramaditha, yang menulis di lain tempat, juga mempersoalkan hal yang sama. Telaah mengenai perempuan seakan-akan
menjadi satu-satunya kajian yang berarti di dalam studi gender.42 Clark lanjut membandingkan: “Despite the boom in international men’s studies over the
last 15 years or so, scholarship in Indonesian gender studies has been much
slower than in other countries to incorporate the study of men and
masculinity”.43 Satu alasan mengapa soal maskulinitas ini jarang diangkat
karena sudah dianggap sebagai „norma‟, memang sudah begitu adanya. Identitas laki-laki hadir sebagai yang tetap dan tak bermasalah.44
Clark banyak merujuk pada Tom Boellstorff yang mendapati
berkembangnya semacam „political homophobia’ pasca Reformasi 1998. Salah satunya mewujud melalui serangkaian tindakan pengacauan dan kekerasan
terhadap kegiatan-kegiatan bertemakan homoseksual. Homoseksual dianggap
membahayakan tidak hanya bagi maskulinitas yang normatif, namun juga
bagi negara secara keseluruhan.45 Berkaca pada hal tersebut, Clark memprediksi bahwa unsur kekerasan akan mendominasi pembentukan
maskulinitas baru di Indonesia dewasa ini. Setidaknya gejala ini terbaca jelas
dari dua film yang dikajinya: Sembilan Naga (Rudi Soedjarwo, 2006) dan
Mengejar Matahari (Rudi Soedjarwo, 2004).46
Baik film Sembilan Naga maupun Mengejar Matahari berpusat pada
lingkungan pergaulan laki-laki. Bila Mengejar Matahari mengambil periode di
masa remaja, 9 Naga berkisar tentang problematika pria ketika dewasa. Apa
yang diperhatikan, sekaligus dikhawatirkan Clark bahwa kedua film ini terlalu
mengedepankan unsur kekerasan. Bahkan, sampai pada tindakan kriminal.
41
Clark, Marshall. Op.cit., hal: 37 42
Paramaditha, Intan. 2008. Perspektif gender dalam kajian film. Jurnal Perempuan. No. 61, hal: 52 43
Clark, Marshall. Op.cit., hal: 37 44
Neale, Steve. Op.cit., hal: 9 45
Boellstorff, Tom. 2004. The emergence of political homophobia in Indonesia: Masculinity and National Belonging. Journal Ethnos Vol. 69: 4, hal: 480
46
Keduanya mengindikasikan maskulinitas yang hadir dan didefinisikan melalui
keberingasan dan keserampangan. Laki-laki yang mudah kalap yang tak
memperhitungkan konsekuensi perbuatannya baik bagi diri sendiri maupun
keluarganya.47
Kajian Clark jelas menunjukkan bagaimana maskulinitas mengalami
pergeseran seiring dengan perubahan dalam konteks sosial dan politik. Akan
tetapi, seperti yang dikritik Paramaditha, terlalu berfokus di konteks, Clark
jadi abai terhadap teks. Padahal, teks tak kalah penting. Teks memungkinkan
munculnya hal-hal kecil yang sering dianggap remeh-temeh.48 Misal,
bagaimana tepatnya kamera membingkai kekerasan yang dilakukan sang
tokoh? Siapakah yang diposisikan sebagai superior dan inferior? Atau,
sifatnya hanya deskriptif dalam artian tanpa bermaksud menghakimi atau
memihak siapapun?
Walau bagaimanapun, analisis Clark penting untuk mengembangkan
penelitian ini. Pertama, tentu untuk mengetahui konteks bagaimana persisnya
pembentukan maskulinitas di Indonesia dewasa ini berikut faktor-faktor apa
yang mempengaruhinya. Kedua, maskulinitas seperti yang digambarkan Clark
mengafirmasi asumsi Neale tentang penggambaran seksualitas laki-laki di
dalam film. Bahwa seksualitas laki-laki dimungkinkan diekspos melalui adegan
kekerasan dan kebrutalan. Meski sayang, tak ada petunjuk terperinci
bagaimana persisnya hal ini berlangsung di dalam dua film yang dianalisis
Clark.
Adapun untuk kajian yang mendedah teks film secara teliti, yang
dalam tingkatan tertentu bersesuaian dengan penelitian ini, adalah analisis
Paramaditha terhadap film Pasir Berbisik (Nan T. Achnas, 2001). Mengambil
fokus pada tokoh perempuan, Paramaditha tak hendak memperlihatkan
perempuan-perempuan yang melayani selera pandangan lelaki. Tapi, dengan
argumentatif, ia berhasil memperlihatkan bagaimana tokoh perempuan dalam
Pasir Berbisik berusaha menentang tatapan itu dan mengklaim kepemilikan
atas tubuhnya.49
Hal lain yang berbeda dari Pasir Berbisik, voyeurisme di dalam film ini
tidak didefinisikan dengan kecabulan, melainkan keingintahuan. Daya
(diperankan Dian Sastro) adalah seorang anak yang selalu penasaran
terhadap apa-apa yang dilakukan ibunya, Berlian (diperankan Christine
Hakim). Daya, yang diposisikan sejajar dengan penonton, pun mengintipi
ibunya lewat lubang kunci. Akan tetapi, alih-alih mendapat kesenangan dari
pekerjaan mengintip ini, Daya malah selalu terjebak, menjadi tersangka.
Sebab, ibu yang diintipnya tidak tak bergeming. Sebaliknya, ia serba-tahu,
serba-kuasa. Ibunya selalu menyadari dirinya sedang diintipi, dan dengan
sekali pandang mampu menangkap basah Daya, sekaligus penonton.50 Kemahakuasaan Berlian tak berhenti sampai di sini. Ia pula yang
selalu merenggut kenikmatan pandang laki-laki. Daya, anak gadisnya yang
cantik jelita, kadangkala terjebak dalam struktur pandangan laki-laki yang
menafsuinya. Utamanya, ketika ia sedang menari. Berlian selalu awas akan
hal ini. Daya dipanggilnya. Ketika Daya tak lagi menari, ketika itu pula
pengeksploitasian terhadap tubuhnya terhenti. Di lain kesempatan, terhadap
laki-laki yang melirik nakal pada Daya, oleh Berlian tak dibiarkan lama-lama.
Jalan yang ditempuhnya kali ini adalah dengan memecahkan piring, dan
dengan demikian kenikmatan laki-laki terhadap tubuh anaknya pun
terpelanting.51
49
Paramaditha, Intan. 2007. “Pasir Berbisik dan estetika-perempuan baru dalam sinema Indonesia” dalam Pola dan Silangan: Jender dalam Teks Indonesia. Ed. Lisabona Rahman. Yayasan Kalam: Jakarta
50
Ibid., hal: 105 51
Paramaditha lanjut menganalisis, Pasir Berbisik menepikan struktur
pandang maskulin untuk memberikan ruang pada perempuan
mengartikulasikan dirinya. Lewat tokoh ibu dalam film tersebut, tampak
usaha perempuan menolak yang simbolik. Bahasa dipandang sebagai
ancaman terhadap keagenan perempuan. Bahasa hanya akan mendefinisikan
perempuan dari perspektif yang dominan maskulin.52 Pasir Berbisik, bagi Paramaditha mampu “merunyamkan teori Mulvey serta konteks patriarkal di Indonesia”53
. Oleh karenanya, ia menggolongkan film ini sebagai film feminis.
Dengan merujuk Paramaditha, posisi perempuan dalam sinema dapat
dibilang mengalami „kemajuan‟. Jika dahulu (baca: Orde Baru) perempuan selalu ditempatkan sebagai yang ditonton, perempuan masa kini (baca:
pasca-Reformasi) mulai bisa menonton. Dengan kata lain, sudah ada film-film
seperti Pasir Berbisik yang memfasilitasi tatapan perempuan (female gaze).
Bahkan, Paramaditha juga sempat menyebut, meski selintas – sudah ada pula yang mewakili tatapan queer, yaitu dalam film Berbagi Suami (Nia
Dinata, 2006).54
Akan tetapi, jika hendak dicermati benar masih tersisa satu persoalan
dari kehadiran tatapan perempuan ini. Paramaditha, seperti halnya Williams,
menunjukkan tatapan perempuan yang bertujuan untuk memuaskan
keingintahuan, menandakan “investigating gaze”55 alih-alih “erotic gaze”.
Tatapan itu pun harus terinterupsi, dalam Pasir Berbisik oleh tokoh ibu yang
serba-tahu, dan dalam Williams oleh sosok monster yang mengerikan.
Apakah perempuan tidak memiliki hasrat seksual? Atau, pertanyaan yang
erotis? Apakah perempuan dianggap pasif secara seksual hingga mengelak
menatap dalam kerangka ini?
Quickie Express, sebagai film gigolo sejatinya menyimpan potensi
untuk menghadirkan tatapan perempuan yang erotis dan cabul. Sebab,
dengan tema ini eksploitasi seksualitas dan tubuh laki-laki sangat mungkin
terjadi. Namun, perhatian saya tidak terpusat pada hadir atau tidaknya
tatapan perempuan semata. Saya mulai menelusuri dari „representasi‟ tubuh laki-laki. Tepatnya berkenaan dengan bagaimana erotisasi atau malah
non-erotisasi terhadap tubuh laki-laki berlangsung. Kerja selanjutnya, menguak
struktur tatapan sehingga teranglah dengan siapa teks film itu hendak
berkawan. Apakah teks film mengalamati penontonnya sebagai perempuan,
laki-laki, atau bisa jadi queer?
F. Kerangka Penelitian
Penelitian ini berpijak pada asumsi-asumsi Steve Neale dalam esainya
berjudul “Masculinity as Spectacle”. Tulisan Neale ini dapat dikatakan terusan dari esai Laura Mulvey yang cukup berpengaruh: “Visual Pleasure and
Narrative Cinema”. Bahwa Mulvey mengandaikan penonton sebagai laki-laki,
Neale pun turut mengamininya. Bedanya, jika Mulvey berfokus pada
penggambaran perempuan, Neale berpusat pada laki-lakinya. Persisnya,
Mulvey menelisiki bagaimana perempuan dihadirkan sebagai tontonan,
sementara Neale menelaah bagaimana laki-laki acap kali gagal untuk
dipertontonkan.
Terang, Neale tidak dalam posisi mendebat Mulvey. Justru, ia
meminjam asumsi-asumsi Mulvey untuk diterapkan dalam melihat posisi
laki-laki di dalam film. Laki-laki-laki bisa saja dipasang serupa manekin di toko-toko.
Akan tetapi, menurut Neale, tidak dalam bingkai erotik serupa perempuan.
disamarkan atau dihindarkan. Sebab, rata-rata film menujukan teksnya untuk
dinikmati laki-laki (yang heteroseksual tentu), maka pengeksposan terhadap
tubuh laki-laki berpotensi menimbulkan kesan homoerotis.56
Neale lanjut membaca bagaimana persisnya tubuh laki-laki disurukkan
atau dipertontonkan dengan memperhatikan proses identifikasi, voyeurisme,
dan fetishisme.
Proses identifikasi ibaratnya orang berkaca: orang melihat dirinya
melalui bayangan yang hadir di depannya. Di dalam sinema, kaca digantikan
dengan layar; dan bayangan (dalam hal ini ego ideal) mewujud dalam bentuk
karakter atau tokoh yang bermain di dalamnya. Meski penonton dapat
melakukan identifikasi dari berbagai posisi, namun Neale melihat
kecenderungan film mengerucutkan identifikasi penonton, utamanya dengan
tokoh laki-laki.57
Tokoh laki-laki, dengan siapa penonton mengejawantahkan dirinya,
pada umumnya digambarkan sebagai manusia super. Kurang lebih, ya seperti
Gatotkaca yang berotot kawat dan bertulang besi. Identifikasi dengan tokoh
serupa Gatotkaca ini tidak hanya membuat penonton melihat dari kacamata
sang jagoan, namun juga merasa menjadi Gatotkaca itu sendiri.
Membayangkan dirinya gagah, perkasa, serta sakti mandraguna.
Namun, di balik tampilan yang serba megah dari Gatotkaca-Gatotkaca
panggung tersebut, penikmatan terhadap tubuh mereka serba terbatas.
Tubuh-tubuh yang kekar berisi itu dipertontonkan sekadar untuk menandakan
superioritas, menekankan kejantanan. Misal, penonton menyaksikan
kebagusan badan mereka melalui duel dan perkelahian yang sengit. Jarang
sekali mereka ditempatkan dalam bingkai yang erotis. Bahkan tidak dalam
adegan percintaan. Posisi tubuh mereka membelakangi kamera. Mata
56
Neale, Steve. Op.cit., hal: 19 57
mereka, menyatu dengan mata kamera dan penonton, tertuju bulat-bulat
pada pasangan wanita.
Berlanjut pada dimensi kenikmatan memandang: voyeurisme dan
fetishisme. Keduanya dapat dikontraskan satu sama lain, meski dalam
praktek antara voyeurisme dan fetishisme bisa jadi saling bertindihan. Jika
voyeurisme menekankan pada keberjarakan antara penonton dengan
tontonan; fetishisme berusaha memampatkan jarak itu hingga ke titik nol.
Jika penikmatan voyeurisme terletak pada narasi, penikmatan fetishisme
terjadi justru ketika narasi berhenti. Voyeurisme memuaskan penonton, misal
dengan menghukum, entah itu penjahat atau wanita- di akhir cerita.
Fetishisme menyenangkan penonton, umpama dengan teknik zoom dan close
up yang silih berganti ditujukan pada seonggok tubuh (wanita).
Di dalam menampilkan laki-laki, baik dimensi voyeurisme maupun
fetishisme bekerjasama untuk mengalihkan pandangan dari sisi erotisnya.
Neale mencontohkan pada seri film Western dari Leone. Film ini
menyuguhkan tubuh laki-laki, akan tetapi tubuh tersebut telah terlucuti dari
konotasi seksualnya. Pandangan penonton pada tubuh tersebut juga tidak
terjadi secara langsung, melainkan dimediasi oleh karakter lain di dalam film.
Tambah pula, pandangan dari karakter itu pun bukan dalam arti seksual,
melainkan menyiratkan ketakutan atau kebencian.58
Apa yang perlu dipertimbangkan, kajian Neale lebih fokus pada
film-film laga. Merupakan film-film aksi ketimbang film-film seksi. Neale tidak menampik
sisi erotis laki-laki dapat juga dieksplorasi. Misal, seperti tampak dari karakter
Rock Hudson dalam film garapan Sirk. Atau, John Travolta ketika ia bermain
dalam Saturday Night Fever. Hanya, dalam mempertontonkan laki-laki di
ranah ini, laki-laki „diperempuankan‟ terlebih dahulu. Feminisasi terhadap
58
laki ini biasa ditemui dalam film-film bergenre drama musikal di mana
laki-laki tak segan-segan meliuk-liukkan tubuhnya.59
Quickie Express jelas bukan film laga atau drama musikal. Film ini
menempatkan dirinya di jalur komedi. Khususnya, komedi untuk dewasa.
Tokoh laki-laki yang diangkatnya hanya lelaki biasa. Yang luar biasa
barangkali pekerjaannya: pekerja seks alias gigolo. Sebagai gigolo, aspek
seksual laki-laki tentu lebih ditonjolkan. Akan tetapi, tidak langsung dapat
dikatakan bahwa film ini ditujukan untuk kenikmatan mata perempuan.
Sebab, berkaca dari kajian Neale, menampilkan laki-laki sebagai obyek
voyeur atau fetish tidaklah segampang membalik posisi kamera. Aspek narasi
dan pandangan dari karakter lain sedikit banyaknya berpengaruh juga.
Ringkasnya, dalam penelitian ini asumsi-asumsi Neale dipakai untuk
memperlihatkan di titik mana laki-laki ditampilkan (atau gagal ditampilkan)
sebagai wisata erotis bagi yang memandangnya.
G. Metodologi Penelitian
Penelitian ini menggunakan perspektif psikoanalisis sebagaimana
dirintis Laura Mulvey, dan lalu dilanjutkan Steve Neal. Meski psikoanalisis ala
Mulvey ini sering dikritik sebagai “psikoanalisis-psikoanalisis-an”, karena salah mengenali tatapan (gaze) Lacan sebagai aktif,60 bukan berarti argumen-argumen Mulvey sama sekali keliru. Mulvey mungkin Lacanian sesat, tapi
tidak sepenuhnya menyesatkan.
Sama seperti yang digagas oleh para “genuine Lacanian”, apa yang dibaca Mulvey juga bersumber dari teks. Atau, bahasa visual dalam konteks
ini. Ia mendedah teks untuk mereka di mana teks memposisikan
penontonnya. Penonton ini bukanlah dalam artian aktual, sebut saja penonton
59
Ibid. 60
imajiner yang kehadirannya dibentuk oleh teks itu sendiri. Mulvey tidak persis
menteoretisasi pengalaman orang-orang yang menonton, namun bagaimana
teks mengalamati penonton. Dalam konsep para Lacanian ortodoks, secara
eksplisit mereka menyebut dengan “internal spectator”.61
1. Sumber Data
Sebagai sumber data primer yang digunakan yakni teks film Quickie
Express dalam format DVD yang berdurasi seluruhnya 117 menit. Sebagai
sumber data sekunder diambilkan dari buku, jurnal, hasil penelitian, ataupun
artikel dan ulasan (cetak dan virtual) yang menyangkut film dan film komedi
di Indonesia, serta masalah maskulinitas dan representasi laki-laki di film.
2. Teknik Pengolahan Data
Penelitian dengan pisau bedah psikoanalisis cenderung longgar dalam
hal kerangka kerja. Psikoanalisis tidak menyediakan tahapan analisis yang
sistematis seperti yang dipunyai semiotika Barthes atau analisis wacana
Fairclough, misal. Cara kerjanya cukup dengan mencomot barang satu atau
dua konsep, untuk lalu diterapkan dalam menginterpretasi gambar.
Interpretasi terhadap suatu gambar sangat mungkin berbeda, tergantung
konsep yang digunakan.62
Adapun penelitian ini mengaplikasikan tiga konsep, yakni: voyeurisme,
fetishisme dan identifikasi. Voyeurisme lagaknya orang mengintip yang
memperoleh kesenangan dari obyek, sementara dirinya tersembunyi. Film
membahasakan ini dengan cara: (1) menjaga jarak antara tokoh laki-laki dan
perempuan dalam film; dan (2) menjaga jarak antara tokoh perempuan
dengan penonton. Beda lagi dengan fetishisme, jarak pada dimensi
61
McGowan & Kunkle. Op.cit., hal: xix – xxiii 62
voyeurisme ditebas hingga penonton dapat berhadapan langsung dengan
obyek. Hal ini dibaca melalui: (1) bingkai kamera; (2) pencahayaan; dan (3)
gerakan kamera. Selanjutnya, identifikasi. Identifikasi menentukan
keberpihakan penonton yang diketahui lewat: (1) posisi kamera; (2) sudut
pandang kamera.63
Gambar 1.1. Bingkai kamera64
Bingkai kamera menentukan obyek mana yang disertakan dan mana
yang disingkirkan. Dimensi fetishisme muncul, misal, dengan membingkai
lekat-lekat wajah atau bagian tubuh tertentu dari pemain. Secara umum,
bingkai kamera dapat dibedakan atas: (1) extreme long shot (XLS) atau
establishing shot yakni pengambilan obyek dari jarak jauh hingga sukar
dikenali wajah pemainnya; (2) long shot, obyek masih terlihat jauh, tetapi
sudah jelas orangnya. Sebagai variasinya yakni deep-focus shot di mana
dalam 1 frame terdapat beberapa obyek dengan jarak CU, MS, dan LS; (3)
medium long shot (MLS), menampilkan orang dari lutut hingga kepala; (4)
medium shot (MS), orang ditampilkan dari pinggang ke atas; (5) medium
close up (MCU), jika pengambilan dimulai dari dada ke atas; (6) close up
63
Ibid., hal: 110; 112; 114 64