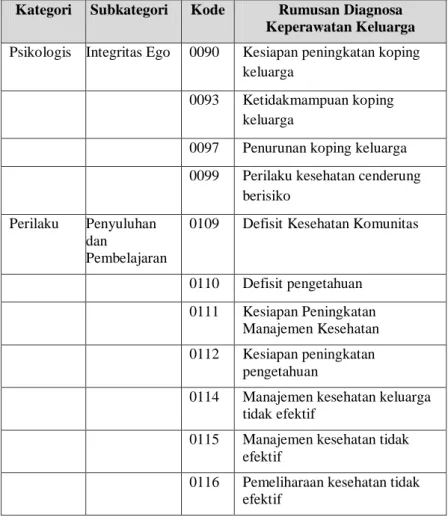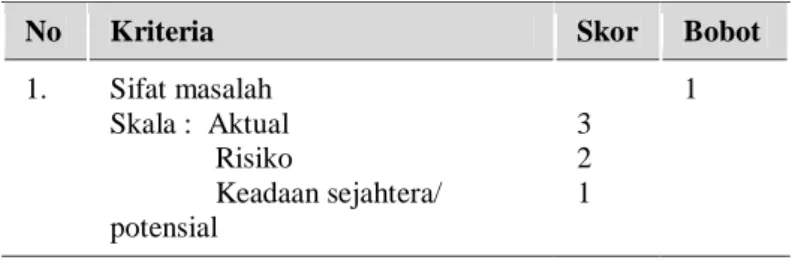See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/371699594
Buku Ajar Keperawatan keperawatan keluarga
Book · June 2023
CITATIONS
10
READS
2,261
2 authors:
Umi Hani
Universitas Karya Husada Semarang 16PUBLICATIONS 28CITATIONS
SEE PROFILE
Fery Agusman Motuho Mendrofa universitas karya husada semarang 41PUBLICATIONS 37CITATIONS
SEE PROFILE
B U K U A J A R KEPERAWATAN
KELUARGA
Dr. Fery Mendrofa, M.Kep, Sp.Kom Iva Puspaneli Setiyaningrum, Ns.S.kep, M.Kep
Penerbit
BUKU AJAR
KEPERAWATAN KELUARGA
Dr. Fery Mendrofa, M.Kep, Sp.Kom
Iva Puspaneli Setiyaningrum, Ns.S.kep, M.Kep Penulis
CV. CATUR KARYA MANDIRI
Jl. Mangga VI No. 71, Semarang, Telp. (024) 841 9620 Dicetak Oleh
Desain Sampul
CV. CATUR KARYA MANDIRI
Editor
Umi Hani, Ns.S.Kep, M.Kep
256 hal + viii Cetakan I : 2021
Diterbitkan oleh:
Mitra Sehat
Jl. Elang Raya No. 1D & 1E, Kel. Sambiroto, Semarang Hak Cipta @2020 pada penulis
ISBN: 978-623-96654-0-1
KATA PENGANTAR
Puji Syukur Kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin-Nya Kami dapat menyelesaikan Buku ini dengan judul “Buku Ajar Keperawatan Keluarga”. Semoga dengan adanya buku ini dapat menambah pengetahuan dan bisa mengaplikasikannya.
Kami menyadari dalam penulisan buku ini, masih banyak kekurangan maupun kesalahan. Oleh karena itu, Kami sangat mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang sifatnya membangun.
Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyusun buku ini.
Semarang, Maret 2021 Penulis
DAFTAR ISI
Cover ... i
Halaman Pengesahan ... ii
Kata Pengantar ... iii
Daftar Isi ... v
Bab I Konsep Keluarga ... 1
A. Definisi Keluarga ... 1
B. Struktur Keluarga ... 4
C. Tipe Keluarga ... 10
D. Fungsi Keluarga ... 14
E. Tugas Kesehatan Keluarga ... 18
F. Contoh Aplikasi Tugas Kesehatan Keluarga ... 22
G. Tahap dan Tugas Perkembangan Keluarga ... 25
H. Peranan Keluarga ... 35
I. Tingkat Kemandirian Keluarga ... 36
J. Konsep Keluarga Sejahtera ... 37
Bab II Praktik Keperawatan Keluarga ... 40
A. Konsep Dasar ... 40
B. Tingkatan Praktik Perawatan Kesehatan Keluarga ... 44
C. Peran Perawat Keluarga ... 48
Bab III Konsep Keperawatan Keluarga ... 54
A. Latar Belakang Keluarga Sebagai Fokus Sentral Pelayanan Keperawatan ... 54
B. Interaksi Keluarga dengan Rentang Sehat Sakit ... 60
C. Penilaian Terhadap Gejala ... 60
D. Proses dan Strategi Koping Keluarga ... 63
E. Teori Krisis Keluarga Menurut Hill (1949) ... 64
F. Tingkat Pencegahan dalam Keluarga ... 65
G. Keperawatan Keluarga Rentan atau Risiko ... 68
Bab IV Konsep Dasar Asuhan Keperawatan Keluarga ... 71
A. Latar Belakang Keluarga Sebagai Sasaran Pelayanan ... 71
B. Prinsip-Prinsip Keperawatan Keluarga ... 73
C. Pengambilan Keputusan dalam Perawatan Kesehatan Keluarga 73 D. Hambatan Perawatan Kesehatan Keluarga ... 74
E. Halangan Perkembangan Perawatan Kesehatan Keluarga ... 75
Bab V Terapi Modalitas Keluarga... 76
A. Pengertian ... 76
B. Jenis Terapi Modalitas ... 76
C. Contoh Terapi Modalitas Keluarga ... 79
Bab VI Terapi Herbal ... 90
A. Latar Belakang Obat Tradisional ... 90
B. Pengertian Obat Herbal ... 90
C. Konsep Pengobatan Herbal ... 91
D. Pengobatan Herbal dan Kimia ... 92
E. Perbedaan Konsep Pengobatan Herbal dan Kimia ... 92
F. Tumbuhan Untuk Tanaman Obat... 93
Bab VII Terapi Modalitas Lansia ... 98
A. Latar Belakang ... 98
B. Pengertian Terapi Modalitas ... 99
C. Program Pada Lansia ... 99
D. Peran Perawat Dalam Terapi Modalitas ... 101
E. Tujuan Terapi Modalitas Lansia ... 101
F. Macam- Macam Terapi Modalitas Lansia ... 101
G. Teknik ... 102
H. Kegel’s Exercize ... 104
Bab VIII Terapi Modalitas Dalam Penatalaksanaan Pasien Pasca Gangguan Jiwa Setelah Pulang Dari RSJ Ke Rumah Di Tengah Keluarga ... 106
A. Pendahuluan ... 106
B. Jenis Terapi Modalitas ... 107
Bab IX Metode dan Media Pendidikan Kesehatan Keluarga ... 112
A. Metode Pendidikan Kesehatan ... 112
B. Media (Alat Peraga) ... 121
Bab X Konsep Pis-Pk (Program Indonesia Sehat-Pendekatan Keluarga) ... 127
A. Pengertian ... 127
B. Konsep Pendekatan Keluarga... 127
C. Sasaran ... 128
D. Indikator Status Kesehatan Keluarga ... 129
Bab XI Konsep Asuhan Keperawatan Keluarga ... 132
A. Pengertian Pelayanan Keperawatan Keluarga ... 132
B. Tujuan Asuhan Keperawatan Keluarga ... 133
C. Tahapan Asuhan Keperawatan Keluarga ... 134
Bab XII Aplikasi Asuhan Keperawatan Keluarga Dengan Pendekatan Pis-Pk Asuhan Keperawatan Keluarga Pada Tahap Perkembangan; Keluarga Pasangan Baru ... 173
A. Data Keluarga... 173
B. Data Pengkajian Individu yang Sakit ... 177
C. Data Penunjang Keluarga... 181
D. Kemampuan Keluarga Melakukan Tugas Pemeliharaan Kesehatan Anggota Keluarga ... 185
E. Diagnosa Keperawatan ... 187
F. Analisa Data ... 188
G. Diagnosa Keperawatan Prioritas ... 190
H. Intervensi Keperawatan ... 191
I. Implementasi Keperawatan ... 220
J. Catatan Perkembangan... 235
BAB I
KONSEP KELUARGA A. DEFINISI KELUARGA
Keluarga sebagai bagian sub-sistem di dalam masyarakat memiliki karakteristik yang unik dalam kehidupan keluarga tersebut. Pengertian keluarga sangat bervariatif sesuai orientasi teori yang menjadi dasar pendefinisiannya. Definisi keperawatan tentang keluarga dipengaruhi keterlibatan personal diri perawat dengan keluarganya sendiri dan pengalaman klinis. Keluarga berasal dari bahasa Sansekerta (kula dan warga) kulawarga yang berarti anggota kelompok kerabat (Padila, 2012).
Berikut beberapa pengertian keluarga, diantaranya yaitu:
a. Marilyn M. Friedman (1998)
Keluarga adalah sebuah kelompok kecil yang terdiri dari individu- individu yang memiliki hubungan erat satu sama lain, saling tergantung yang diorganisir dalam satu unit tunggal dalam mencapai tujuan tetentu
b. Duval dan Logan (1986)
Keluarga adalah sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran dan adopsi yang bertujuan menciptakan, mempertahankan budaya dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional seta sosial dari tiap anggota keluarga.
c. Salvicion G. Bailon dan Aracelis Maglaya (1978)
Keluarga adalah dua atau lebih individu yang hidup dalam satu rumah tangga karena adanya hubungan darah, perkawinan atau adopsi. Mereka saling ebrinteraksi satu dengan yang lain, mempunyai peran masing-maisng dan menciptkan serta mempertahankan suatu budaya.
d. WHO (1969)
Keluarga adalah anggota rumah tangga yang saling berhubungan melalui ikatan darah, adopsi dan perkawinan.
e. Hanson (2005)
Keluarga merujuk pada dua atau lebih individu yang saling tergantung satu sama lain dan memberi dukungan secara emosional, fisik, dan atau keuangan.
f. Depkes RI (1988)
Mendefinisikan keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal disuatu tempat dibawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.
DITAMBAHKAN:
g. UU RI No. 52 Tahun 2009
Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, atau suami, istri, dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
h. BKKBN (2011)
Keluarga yaitu satuan individu/seseorang yang tidak diikat dalam hubungan keluarga, hidup dan makan serta menetap dalam satu rumah, misalnya seorang janda/duda sebagai anggota keluarga sendiri, atau dengan anak yatim piatu dan lain-lain.
i. Bergess (1962)
Keluarga terdiri atas kelompok orang yang terikat oleh perkawinan, keturunan/ hubungan sedarah atau adopsi (orang tua -anak); tinggal bersama dalam satu rumah, anggota berinteraksi dan berkomunikasi
dalam peran sosial, serta mempunyai kebiasaan/ kebudayaan yang berasal dari masyarakat tetapi memiliki keunikan tersendiri.
Dari uraian diatas menunjukan bahwa keluarga merupakan suatu sistem. Sebagai suatu sistem, keluarga memiliki anggota yaitu ayah, ibu, anak, atau semua individu yang tinggal dalam rumah tangga tersebut. Anggota keluarga tersebut saling berinteraksi, interelasi, dan interdependensi untuk mencapai tujuan bersama. Keluarga merupakan sistem yang terbuka sehingga dapat dipengaruhi oleh supra sistemnya seperti lingkungan (masyarakat). Sebaliknya, sebagai subsistem dari lingkungan (masyarakat), keluarga dapat mempengaruhi masyarakat (supra-sistem) (Effendy& Makhfudli, 2013).
Dari beberapa pengertian diatas, tampak begitu luas dan variatif dalam membuat definisi keluarga, selanjutnya kita dapat melihat maka dapat disimpulkan secara umum bahwa keluarga itu terjadi jikalau ada :
1. Keluarga terdiri dari orang orang yang disatukan dalam ikatan perkawinan, darah dan ikatan adopsi;
2. Para anggotanya hidup bersama-sama dalam satu rumah tangga, jika terpisah masih memperhatikan satu sama lain;
3. Anggota keluarga berinteraksi dan berkomunikasai satu dengan yang lain dalam peran-peran sosial keluarga;
4. Keluarga menggunakan budaya yang sama yang diambil dari masyarakat dengan ciri tersendiri;
5. Mempunyai tujuan menciptakan dan mempertahankan budaya, meningkatkan perkembagan fisik, psikologis, dan sosial anggotanya.
(Padila, 2012) dan (Harmoko, 2012).
B. STRUKTUR KELUARGA
Menurut Friedman, Bowdan dan Jones (2003) dalam Susanto (2012) fungsi dalam keluarga merupakan apa saja yang dikerjakan dalam keluarga, sedangkan struktur keluarga meliputi proses yang digunakan dalam keluarga untuk mencapai hasil yang diharapkan. Proses ini meliputi komunikasi antar anggota keluarga, tujuan, pemecahan konflik, pemeliharaan, dan penggunaan sumber internal dan eksternal. Tujuan reproduksi, seksualitas, ekonomi, dan pendidikan dalam keluarga memerlukan dukungan secara psikologi antar anggota keluarga, apabila dukungan tersebut tidak didapatkan maka akan menimbulkan konsekuensi emosional seperti marah, depresi, dan perilaku yang menyimpang. Tujuan yang ada di dalam keluarga akan lebih mudah tercapai bila terjadi komunikasi yang jelas dan secara langsung.
Komunikasi tersebut akan mempermudah menyelesaikan konflik dan pemecahan masalah. Struktur dalam keluarga didasari oleh organisasi meliputi keanggotaan dan pola hubungan yang terus menerus.
1. Ciri- Ciri Struktur Keluarga
Ciri-ciri struktur keluarga, menurut Effendy dan Makhfudli (2013) diantarnanya yaitu :
a. Terorganisasi
Keluarga adalah cerminan sebuah organisasi, dimana setiap anggota keluarga memiliki peran dan fungsinya masing-masing sehingga tujuan keluarga dapat tercapai. Organisasi yang baik ditandai dengan adanya hubungan yang kuat antara anggota sebagi bentuk saling ketergantungan dalam mencapai tujuan.
b. Keterbatasan
Dalam mencapai tujuan, setiap anggota keluarga memiliki peran dan tanggung jawabnya masing- masing, sehingga
dalam berinteraksi tidak bisa semena-mena tetapi memiliki keterbatasan yang dilandaskan pada tanggung jawab masing- masing anggota keluarga.
c. Perbedaan dan kekhususan
Adanya peran yang beragam dalam keluarga menunjukan bahwa masing- masing anggota keluarga mempunyai peran dan fungsi yang berbeda dan khas. Seperti halnya peran ayah sebagai pencari nafkah utama dan peran ibu sebagai anggota keluarga yang merawat anak-anak.
2. Jenis Struktur keluarga :
a. Berdasarkan dominasi jalur hubungan darah
1) Patrilineal : keluarga sedarah yang terdiri dari sanak saudara sedarah dalam beberapa generasi, dimana hubungan itu disusun melalui jalur ayah.
2) Matrilineal : keluarga sedarah yang terdiri dari sanak saudara sedarah dalam beberapa generasi dimana hubungan itu disusun melalui jalur garis ibu.
b. Berdasarkan dominasi keberadaan tempat tinggal
1) Matrilokal : sepasang suami istri yang tinggal bersama keluarga sedarah ibu
2) Patrilokal : sepasang suami istri yang tinggal bersama keluarga sedarah suami
c. Berdasarkan dominasi pengambilan keputusan
1) Patriakal : dominasi pengambilan keputusan ada pada pihak suami, peran ayah yang mengetuk palu persetujuan, namun dalam menentukan keputusan tersebut harusnya melibatkan ibu sebagai orang yang mempertimbangkan.
2) Matriakal : dominasi pengambilan keputusan ada pada pihak istri. Dalam struktur matriakal peran istri adalah sebagai pengambil keputusan. Namun seharusnya perlu melibatkan suami dalam mempertimbangkan keputusan tersebut.
3. Dimensi struktur keluarga
Parad dan Caplan (1965) yang diadopsi dalam Friedman (1998) membagi menjadi empat dimensi struktur keluarga yaitu:
a. Pola komunikasi keluarga
Pola komunikasi keluarga adalah proses tukar menukar perasaan, keinginan, kebutuhan-kebutuhan dan opini. Pola dan proses komunikasi ini akan menggambarkan bagaimana cara komunikasi dalam keluarga diterapkan baik antar sesama orang tua dengan anak, anak dengan anak, dan anggota keluarga besar dengan keluarga inti.
Komunikasi berhasil jika pesan dapat dimengerti, berfungsi baik jika ada kehangatan, keterbukaan, dan jujur. Dapat meningkatkan kreatifitas menumbuhkan kemandirian anak dan tumbuh kembang anak.
Komunikasi keluarga sebagai simbolik transaksional menciptakan dan mengungkapkan pengertian dalam keluarga.
Struktur komunikasi untuk memudahkan pencapaian fungsinya yang umum. Komunikasi yang adekuat memungkinkan keluarga untuk mensosialisasikan anak-anak dengan lebih baik sebagai fungsi dasar keluarga (Galvin & Brommel, 1986).
Komunikasi dalam keluarga dapat berupa komunikasi secara emosional, komunikasi verbal dan non-verbal, komunikasi sirkuler (wright & Leahey, 2000). Komunikasi emosional
memungkinkaan setiaap individu dalam keluarga dapat mengekpresikan perasaan seperti bahagia, sedih, atau marah di antara para anggota keluarga. Pada komunikasi verbal individu dalam keluarga dapat mengungkapkan perasaan masing-masing.
b. Pola Peran Keluarga
Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan sesuai dengan posisi sosial yang diberikan sehingga pada struktur peran biasa bersifat format atau informal. Posisi atau status dalam keluarga yang dapat dipandang oleh masyarakat sebagai suami, istri atau anak. Peran formal dalam keluarga merupakan suatu kesepakatan bersama yang dibentuk dalam suatu norma keluarga.
Peran di dalam keluarga menunjukan pola tingkah laku dari semua anggota di dalam keluarga (Wright, 1984).
Peran didalam keluarga dapat terjadi peran ganda sehingga anggota keluarga dapat menyesuaikan peran tersebut. Peran di dalam keluarga dapat fleksibel sehingga anggota keluarga dapat beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi.
c. Nilai dan Norma Keluarga
Nilai adalah suatu ide, sikap, dan kepercayaan yang secara sadar maupun tidak sadar mengikuti seluruh anggota keluarga dalam suatu budaya yang lazim (Parad dan Caplan, 1985).
Menurut Rokeach (1983) nilai diartikan sebagai keyakinan abadi berbentuk perilaku spesifik, berfungsi sebagai pedoman atas tindakanya. Kebudayaan keluarga merupakan sumber sistem nilai dan norma-norma utama sebuah keluarga.
Nilai merupakan persepsi seseorang tentang suatu hal apakah baik atau bermanfaat bagi dirinya. Norma mengarah sesuai dengan nilai yang dianut masyarakat, dimana norma dipelajari sejak kecil
(De Laune, 2002). Nilai memberikan dasar untuk posisi seseorang pada berbagai isu personal, profesional, social, dan politik. Nilai yang merupakan perilaku motivasi diekspresikan melalui perasaan, tindakan, dan pengetahuan. Nilai merupakan tujuan dari keperilakuan individu. Nilai memberikan makna kehidupan dan meningkatkan harga diri (Delaune, 2002). Nilai berfungsi sebagai pedoman umum bagi perilaku dan dalam keluarga nilai-nilai tersebut membimbing perkembangan aturan-aturan dan nilai-nilai dari keluarga. Nilai merupakan suatu sistem, sikap dan kepercayaan yang secara sadar atau tidak, mempersatukan anggota keluarga dalam satu budaya. Nilai keluarga juga merupakan suatu pedoman perilaku dan pedoman bagi perkembangan norma dan peraturan. Norma adalah pola perilaku yang baik, menurut masyarakat berdasarkan sistem nilai dalam keluarga.
d. Pola Kekuatan Keluarga
Kekuatan adalah kemampuan individu untuk mengontrol, mempengaruhi dan mengubah tingkah laku seseorang. Menurut Cromwell dan Olson (1995) , kekuatan merupakan aspek paling fundamental dari semua interaksi sosial. Struktur kekuatan keluarga menggambarkan kemampuan anggota keluarga untuk mempengaruhi dan mengendalikan orang lain untuk mengubah perilaku keluarga yang mendukung kesehatan. Friedman, Bowden, & Jones (2003) mengungkapkan bahwa kekuatan keluarga merupakan kemampuan (potensial atau aktual) dari individu untuk mengendalikan atau mempengaruhi untuk merubah perilaku orang ke arah positif. Tipe struktur kekuatan dalam keluarga antara lain : legitimate power/ authority (hak untuk mengontrol) seperti orangtua terhadap anak, referrent power
(seseorang yang ditiru), resource or expert power (pendapat, ahli dll), reward power (pengaruh kekuatan karena adanya harapan yang akan diterima), coercive power (pengaruh yang dipaksakan sesuai dengan keinginannya), informational power (pengaruh yang dilalui melalui persuasi), affective power (pengaruh yang diberikan melalui manipulasi dengan cinta kasih misalnya hubungan seksual). Hasil dari kekuatan tersebut yang akan mendasari suatu proses dalam pengambilan keputusan dalam keluarga seperti konsensus, tawar menawar atau akomodasi, kompromi atau de facto, dan paksaan.
4. Fungsi Keluarga Yang Berhubungan Dengan Struktur
Fredman, Bowden & Jones (2003) fungsi keluarga yang berhubungan dengan struktur keluarga adalah sebagai berikut :
a. Struktur egalisasi : masing-masing keluarga mempunyai hak yang sama dalam menyampikan pendapat (demokrasi)
b. Struktur yang hangat, menerima dan toleransi.
c. Struktur yang terbuka dan anggota yang terbuka; mendorong kejujuran dan kebenaran (honesty dan authenticity).
d. Struktur yang kaku; suka melawan dan tergantung pada peraturan.
e. Struktur yang bebas; tidak adanya peraturan yang memaksakan (permissiveness).
f. Struktur yang kasar; abuse, menyiksa, kejam dan kasar.
g. Suasana emosi yang dingin (isolasi, sukar berteman).
h. Disorganisasi keluarga (disfungsi individu, stres emosional).
5. Karakteristik dari Sistem Keluarga (Sistem Terbuka)
a. Komponen: masing-masing anggota keluarga mempunyai sifat interdependensi, interaktif, dan mutual.
b. Batasan: filter/batasan yang digunakan untuk menyeleksi informasi yang masuk dan yang keluar. Masing-masing keluarga berbeda tergantung faktor sosial, ekonomi, spiritual, dsb.
c. Keberadaan: Keluarga merupakan bagian dari sistem yang lebih lebih luas yaitu masyarakat.
d. Terbuka (batas yang permeable) dimana di dalam keluarga terjadi pertukaran antar sistem.
e. Mempunyai: masing-masing keluarga mempunyai organisasi/
struktur yang akan berpengaruh di dalam fungsi yang ada dari anggotanya
C. TIPE KELUARGA
Pembagian tipe keluarga menurut Sussman (1974) dan Maclin (1988) dalam Effendi dan Makhfudli (2013) ada 2 yaitu :
1. Keluarga tradisional
• Tipe keluarga ini merupakan keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak.
• Pasangan inti terdiri dari suami dan istri saja.
• Keluarga dengan orang tua tunggal; satu orang sebagai kepala keluarga, biasanya bagian dari konsekuensi perceraian.
• Lajang yang tinggal sendirian.
• Keluarga besar yang mencakup tiga generasi
• Pasangan usia pertengahan atau pasanag lanjut usia
• Jaringan keluarga besar 2. Keluarga non-tradisional
• Pasangan yang memiliki anak tanpa menikah
• Pasangan yang hidup bersama tanpa menikah (kumpul kebo)
• Keluarga homoseksual (gay dan/ atau lesbian)
• Keluarga lebih dari satu pasangan dengan anak-anak secara bersama-sama menggunakan fasilitas dan sumber-sumber yang ada.
Keluarga yang memerlukan pelayanan kesehatan berasal dari berbagai macam pola kehidupan. Sesuai dengan perkembangan sosial, maka tipe keluarga berkembang mengikutinya. Agar dapat mengupayakan peran serta keluarga dalam meningkatkan derajat kesehatan, maka perawat perlu memahami, dan mengetahui berbagai tipe keluarga (Harmoko, 2016) antara lain sebagai berikut.
1. Tradisional
a. The nuclear family (keluarga inti), keluarga yang terdiri dari suami, istri dan anak.
b. The dyad family, keluarga yang terdiri dari suami dan istri (tanpa anak) yang hidup bersama dalam satu rumah.
c. Keluarga usila, keluarga yang terdiri dari suami istri yang sudah tua dengan anak sudah memisahkan diri
d. The childless family, keluarga tanpa anak karena terlambat menikah dan untuk mendapatkan anak terlambat waktunya, yang disebabkan karena mengejar karir/pendidikan yang terjadi pada wanita.
e. The extended family (keluarga luas/besar), keluarga yang terdiri dari tiga generasi yang hidup bersama dalam satu rumah seperti nuclear family disertai: paman, tante, orang tua (kakak-nenek), keponakan, dll.
f. The single-parent family (keluarga duda/janda), keluarga yang terdiri dari satu orang tua (ayah dan ibu) dengan anak, hal ini terjadi biasanya
melalui proses perceraian, kematian dan ditinggalkan (menyalahi hukum pernikahan).
g. Commuter family
Kedua orang tua bekerja di kota yang berbeda, tetapi salah satu kota tersebut sebagai tempat tinggal dan orang tua yang bekerja diluar kota bisa berkumpul pada anggota keluarga pada saat akhir pekan (week-end)
h. Multigenerational family, keluarga dengan beberapa generasi atau kelompok umur yang tinggal bersama dalam satu rumah.
i. Kin-network family, beberapa keluarga inti yang tinggal dalam satu rumah atau saling berdekatan dan saling menggunakan barang-barang dan pelayanan yang sama. Misalnya : dapur, kamar mandi, televisi, telpon, dll.
j. Blended family, keluarga yang dibentuk oleh duda atau janda yang menikah kembali dan membesarkan anak dari perkawinan sebelumnya
k. The single adult living alone / single-adult family, keluarga yang terdiri dari orang dewasa yang hidup sendiri karena pilihannya atau perpisahan (separasi), seperti : perceraian atau ditinggal mati
2. Non-tradisional
a. The unmarried teenage mother
Keluarga yang terdiri dari orang tua (terutama ibu) dengan anak dari hubungan tanpa nikah.
b. The step-parent family
Keluarga dengan orang tua tiri.
c. Commune family
Beberapa pasangan keluarga (dengan anaknya) yang tidak ada hubungan saudara, yang hidup bersama dalam satu rumah, sumber, dan fasilitas yang sama, pengalaman yang sama, sosialisasi anak dengan melalui aktivitas kelompok/membesarkan anak bersama.
d. The nonmarital heterosexual cohabiting family
Keluarga yang hidup bersama berganti-ganti pasangan tanpa melalui pernikahan
e. Gay and lesbian families
Seseorang yang mempunyai persamaan sex hidup bersama sebagaimana pasangan suami-istri (marital partners).
f. Cohabitating couple
Orang dewasa yang hidup bersama diluar ikatan perkawinan karena beberapa alasan tertentu.
g. Group-marriage family
Beberapa orang dewasa yang menggunakan alat-alat rumah tangga bersama, yang merasa telah saling menikah satu dengan yang lainnya, berbagi sesuatu, termasuk seksual dan membesarkan anaknya.
h. Group network family
Keluarga inti yang dibatasi oleh set aturan/nilai-nilai, hidup berdekatan satu sama lain dan saling menggunakan barang-barang rumah tangga bersama, pelayanan dan bertanggung jawab membesarkan anaknya.
i. Foster family
Keluarga menerima anak yang tidak ada hubungan keluarga/
saudara dalam waktu sementara, pada saat orangtua anak tersebut perlu mendapatkan bantuan untuk menyatukan kembali keluarga yang aslinya.
j. Homeless family
Keluarga yang terbentuk dan tidak mempunyai perlindungan yang permanen karena krisis personal yang dihubungkan dengan keadaan ekonomi dan atau problem kesehatan mental.
k. Gang
Sebuah bentuk keluarga yang destruktif, dari orang-orang muda yang mencari ikatan emosional dan keluarga yang mempunyai perhatian, tetapi berkembang dalam kekerasan dan kriminal dalam kehidupannya.
DILENGKAPI PADA BEBERAPA POIN D. FUNGSI KELUARGA
Menurut Friedman (1998) dalam Padila (2012) Dion & Betan (2012) secara umum fungsi keluarga adalah sebagai berikut.
1. Fungsi afektif
Fungsi afektif ini merupakan fungsi keluarga yang terutama mengajarkan segala sesuatu untuk mempersiapkan anggota keluarga berhubungan dengan orang lain. Fungsi ini dibutuhkan untuk perkembangan individu dan psikososial anggota keluarga. Fungsi afektif berhubungan dengan fungsi internal keluarga yang merupakan basis kekuatan keluarga. Keberhasilan fungsi ini tampak melalui keluarga yang bahagia. Anggota keluarga mengembangkan konsep diri yang positif, rasa memiliki dan dimiliki, rasa berarti serta sumber kasih sayang. Reinforcement dan support dipelajari dan dikembangkan melalui interaksi dalam keluarga. Adanya perceraian, kenakalan anak, atau masalah lain yang sering timbul dalam keluarga dikarenakan fungsi afektif yang tidak terpenuhi oleh keluarga. Ciri dari struktur keluarga yang kuat kecenderungan menerima,memuji
individualitas dan keunikan, mentoleransi ketidaksepakatan. Rasa hormat dan penerimaan diberikan tanpa syarat, tanpa perbandingan, anggota keluarga didorong untuk tumbuh dan mengembangkan kreativitas imajinasi.
Komponen yang perlu dipenuhi oleh keluarga untuk memenuhi fungsi afektif:
a) Saling mengasuh, cinta kasih, kehangatan, saling menerima dan mendukung. Setiap anggota keluarga yang mendpat kasih sayang dan dukungan, maka kemampuanya untuk memberi akan meningkat sehingga tercipta hubungan yang hangat dan saling mendukung. Hubungan yang baik dalam keluarga tersebut akan menjadi dasar dalam membina hubungan dengan orang lain diluar keluarga. Prasarat untuk mencapai saling asuh adalah komitmen dasar dari masing–masing pasangan dan hubungan perkawinan secara emosional memuaskan dan terpelihara. Brown (1989) dalam Harmoko (2012) memandang mutual nurturance sebagai suatu fenomena spiral, karena setiap anggota keluarga menerima kasih sayang dan perhatian dari orang lain dalam keluarga, sehingga kapasitanya untuk memberi kepada anggota keluarga lain meningkat. Dengan demikian, akan timbul adanya sikap saling mendukung dan kehangatan emosional.
b) Saling menghargai, dengan mempertahankan iklim yang positif dimana setiap anggota keluarga baik orang tua maupun anak diakui dan dihargai keberadaan dan haknya. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah keluarga harus memelihara suasana dimana harga diri, kedua orangtua dan hak anak sangat dijunjung tinggi.
Keseimbangan saling menghormati dapat dicapai apabila setiap anggota keluarga menghormati hak, kebutuhan, dan tanggung
jawab anggota keluarga yang lain. Orang ua perlu menyediakan struktur yang memadai dan panduan yang konsisten, sehingga batas-batas bisa dibuat dan dipahami. Namun demikian perlu fleksibilitas dalam sistem keluarga agar memberikan ruang gerak bagi kebebasan untuk berkembang menjadi individu.
c) Ikatan dan identifikasi, kekuatan yang besar dibalik persepsi dan kepuasan dari kebutuhan-kebutuhan individu dalam keluarga dalam pertalian (bonding) atau kasih sayang (attachment) digunakan saling bergantian. Kasih sayang menjadi ikatan emosional paling unik dan abadi antara dua orang tertentu. Ikatan ini dimulai sejak pasangan sepakat hidup baru. Kemudian dikembangkan dan disesuiakan dengan berbagai aspek kehidupan dan keinginan yang tidak dapat dicapai sendiri. Hubungan selanjutnya akan dikembangkan menjadi hubungan orangtua-anak dan antar anak melalui proses identifikasi. Identifikasi adalah sikap seseorang mengalami apa yang terjadi dengan orang lain, seolah- olah hal itu terjadi pada dirinya. Proses ini menjadi inti ikatan kasih sayang, oleh karena itu perlu diciptakan proses identifikasi yang positif dimana anak meniru perilaku orang tua melalui hubungan interaksi mereka.
d) Keterpisahan dan kepaduan, selama awal sosialisasi, keluarga membentuk dan memprogramkan tingkah laku seorang anak, sehingga hal tersebut membentuk rasa memiliki identitas. Untuk memenuhi perasaan dan memenuhi keterpaduan yang memuaskan. Anggota keluarga berpadu dan berpisah satu sama lain. Setiap keluarga menghadapi isu-isu keterpisahan dan keterpaduan dengan cara yang unik, beberapa memberikan penekanan pada satu sisi dari pada sisi yang lain.
2. Fungsi sosial
Proses perkembangan dan perubahan yang dialami individu yang menghasilkan interaksi sosial dan belajar berperan dalam lingkungan sosial (Gegas, 1079) dan Friedman (1998) dalam Padila 2012.
Sedangkan Soekanto 2000 mengemukakan bahwa sosialisasi adalah suatu proses anggota masyarakat yang baru mempelajari norma- norma masyarakat dimana dia menjadi anggota. Sosialisasi dimulai sejak individu dilahirkan dan berakhir setelah meninggal. Keluarga merupakan tempat individu melakukan sosialisasi. Tahap perkembangan individu dan keluarga akan dicapai melalui interaksi atau hubungan yang diwujudkan dalam sosialisasi. Angota keluarga belajar disiplin memiliki nilai atau norma, dalam budaya dan perilaku melalui interaksi dalam keluarga, sehingga individu mampu berperan dalam masyarakat. Fungsi ini mengembangkan dan temapat melatih anak untuk kehidupan sosial sebelum meninggalkan rumah untuk berhubungan dengan orang lain di luar rumah.
3. Fungsi reproduktif
Keluarga berfungsi untuk mempertahankan generasi dan menjaga kelangsungan keluarga. Keluarga berfungsi untuk meneruskan kelangsungan keturunan dan menambah sumber daya manusia. Fungsi keluarga meneruskan keturunan, memelihara membesarkan anak, memenuhi gizi keluarga, dan merawat anggota keluarga.
4. Fungsi ekonomi
Keluarga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara ekonomi dan tempat mengembangkan kemampuan individu meningkatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Komponen yang dilaksanakan keluarga dalam menjalankan fungsinya yaitu mencari sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan
keluarga, mengatur penggunaan penghasilan keluarga, menabung untuk memnuhi kebutuhan pendidikan anak dan jaminan hari tua.
5. Fungsi perawatan/pemeliharaan kesehatan
Fungsi keluarga untuk memepertahankan keadaan kesehatan anggota keluarga agar tetap memiliki produktivitas tinggi. Fungsi ini dikembangkan menjadi tugas keluarga di bidang kesehatan. Fungsi ini menjadi vital dalam pengkajian keluarga. Guna menempatkan dalam suatu perspektif fungsi ini menyediakan kebutuhan-kebutuhan fisik seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan perawatan kesehatan.
Jika dilihat dari perspektif masyarakat. Keluarga merupakan syitem dasar dimana perilaku sehat dan perawatan kesehatan diatur, dan diamankan. Keluarga memberikan perawatan yang bersifat promotif dan preventif dan secara bersama-sama merawat angota keluarga yang sakit. Lebih jauh lagi keluarga mempunyai tanggung jawab utama untuk memulai dan mengkoordinsikan pelayanan yang diberikan oleh para professional perawat kesehatan. Keluarga menyediakan makanan, pakaian, perlindungan, dan memelihara kesehatan.
Keluarga melakukan praktik askep kesehatan untuk mencegah terjadinya gangguan atau merawat anggota yang sakit harus mampu menentukan kapan meminta pertolongan pada tenaga kesehatan ketika salah satu anggotanya mengalami gangguan kesehatan.
E. TUGAS KESEHATAN KELUARGA
Tugas Kesehatan Keluarga menurut Bailon dan Maglaya (1998) dalam Effendi & Makhfudli (2013) dan Mukhlisin (2013)
1. Mengenal Masalah Kesehatan
Kesehatan menjadi aspek yang penting dalam keluarga. Tanpa kesehatan sesuatu tidak berarti tanpa kesehatan. Karena kesehatanlah
kadang seluruh sumber daya dan dana akan habis. Orang tua mengenal keadaan kesehatan dan perubahan yang dialami anggota keluarga.
Perubahan sekecil apapun yang dialami anggota keluarga secara tidak langsung menjadi perhatian orangtua dan keluarga. Apabila menyadari adanya perubahan kondisi pada anggota keluarga, perlu dicatat kapan, apa, seberapa peruabahan terjadi dan seberapa besar perubahannya. Sejauh mana keluarga mengetahui dan mengenal fakta masalah kesehatan meliputi pengertian, tanda gejala, faktor penyebab dan yang mempengaruhinya serta persepsi keluarga terhadap masalah kesehatan yang dialami.
2. Mengambil keputusan
Tugas ini merupakan upaya utama keluarga untuk mencari pertolongan yang tepat sesui dengan keadaan keluarga, dengan pertimbangan siapa di antara anggota keluarga yang mempunyai kemampuan memutuskan sebuah tindakan. Tindakan kesehatan yang dilaksanakan oleh keluarga semestinya tepat agar masalah kesehatan yang sedang terjadi dapat dikurangi atau diatasi. Jika keluarga mempunyai keterbatasan dalam mengambil keputusan, maka keluarga dapat meminta bantuan kepada orang lain di lingkungan tempat tinggalnya. Sebelum keluarga mampu mengambil keputusan upaya mencari pertolongan yang tepat sesuai keadaan mengatasi masalah, perlu dikaji keadaan keluarga dalam membuat keputusan, diantaranya :
a. Sejauh mana keluarga mengerti sifat dan luasnya masalah kesehatan yang dialami
b. Apakah keluarga merasakan adanya masalah kesehatan
c. Apakah keluarga merasa menyerah terhadap masalah kesehatan yang dialami
d. Apakah keluarga merasa takut akan akibat penyakit
e. Apakah keluarga mempunyai sifat negatif terhadap masalah kesehatan
f. Apakah keluarga mampu menjangkau fasilitas kesehatan g. Apakah keluarga kurang percaya pada tenaga kesehatan
h. Apakah keluarga mendapat info yang salah terhadap tindakan untuk mengatasi masalah kesehatan
i. Siapa yang mengambil keputusan atau meminta bantuan siapa 3. Merawat anggota keluarga yang sakit
Keluarga yang sering mengalami keterbatasan, maka anggota keluarga yang mengalami gangguan kesehatan perlu memperoleh tindakan lanjutan atau perawatan agar masalah yang lebih parah tidak terjadi. Perawatan dapat dilakukan di institusi pelayanan kesehatan atau di rumah apabila keluarga telah memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan untuk pertolongan pertama. Ketika memberikan perawatan kepada anggota keluarga yang sakit, keluarga harus mengetahui hal- hal berikut :
a. Keadaan penyakit (sifat, penyebaran, komplikasi, prognosis dan perawatannya)
b. Sifat dan perkembangan perawatan yang dibutuhkan c. Keberadaan fasilitas yang diperlukan untuk perawatan
d. Sumber-sumber yang ada dalam keluarga (anggota keluarga yang bertanggungjawab, sumber keuangan, fasilitas fisik, psikososial) e. Sikap keluarga terhadap yang sakit
4. Memodifikasi lingkungan rumah yang mendukung kesehatan Rumah menjadi tempat berlindung dimana waktu lebih banyak waktu berhubungan dengan tempat tinggal. Semestinya rumah harus menjadi
lambang ketenangan, keindahan, dan menunjang derajat kesehatan bagi anggota keluarga. Rumah menjadi:
a. Sumber keluarga yang dimiliki,
b. Keuntungan/ manfaat pemeliharaan lingkungan, c. Pentingnya hiegene sanitasi,
d. Upaya pencegahan penyakit,
e. Sikap pandangan keluarga terhadap sanitasi, f. Kekompakan antar anggota keluarga.
5. Memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan
Apabila mengalami gangguan masalah kesehatan keluarga atau anggota keluarga harus dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada disekitarnya. Keluarga dapat berkonsultasi atau meminta bantuan tenaga kesehatan. Ketika merujuk keluarga ke fasilitas kesehatan, keluarga harus tahu:
a. Keberadaan fasilitas keluarga
b. Keuntungan yang diperoleh dari fasilitas kesehatan
c. Tingkat kepercayaan keluarga terhadap petugas dan fasilitas kesehatan
d. Pengalaman yang kurang baik terhadap petugas kesehatan e. Fasilitas kesehatan yang terjangkau oleh keluarga.
Kelima tugas kesehatan keluarga tersebut saling terkait dan perlu dilakukan oleh keluarga, perawat perlu mengkaji sejauh mana keluarga mampu melaksanakan tugas tersebut dengan baik dan memberikan bantuan atau pembinaan terhadap keluarga untuk memenuhi tugas kesehatan keluarga (Harmoko, 2012) ( Dion &
Betan, 2013).
F. CONTOH APLIKASI TUGAS KESEHATAN KELUARGA Masalah
Kesehatan Pelaksanaan Tugas Kesehatan Potensial
peningkatan gizi balita/anak
1. Mengenal Masalah Kesehatan :
Keluarga mengatakan lebih memperhatikan gizi anak-anak, menyatakan bahwa makanan bergizi penting bagi anak-anak (Intervensi : EBP. Penkes Modifikasi Nutrisi pada Anak; Penkes Pemantauan Tumbang Anak)
2. Mengambil Keputusan:
Kami akan selalu memberikan makanan yang bergizi pada anak kami
3. Merawat Anggota Keluarga Yang Sakit:
Keluarga sangat peduli dengan pertumbuhan anaknya. Makanan yang disedikan sudah sesuai dengan standar kebutuhan anak
4. Modifikasi Lingkungan:
Makanan bergizi seperti sayur dan buah-buahan dikebun dan sekitar rumah
5. Memanfaatkan fasilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat:
Setiap bulan anak selalu dibawa ke Posyandu balita untuk ditimbang, BB selalu naik, kecuali sedang sakit.
Masalah
Kesehatan Pelaksanaan Tugas Kesehatan Keluarga Kebiasaan
merokok pada Bpk. M
1. Mengenal Masalah Kesehatan:
Bpk . M mengatakan merokok dapat menyebabkan penyakit paru, saya tahu merokok banyak ruginya, tapi saya sulit menghentikanya.
2. Mengambil Keputusan:
Kalau tidak saya hentika merokok pasti saya akan sakit, tapi saya sulit untuk memulainya. Padahal uangnya bias digunakan untuk membeli makanan keluarga
3. Merawat Anggota Keluarga Yang Sakit :
Saya tidak tahu bagaimana cara menghentikan merokok tersebut. (EBP: cara menghentikan kebiasaan merokok ex; permen xylitol, permen susu, permen buah, hypnosis dll)
4. Modifikasi Lingkungan Rumah:
Dirumah saya merokok juga, tetapi tidak didekat anak-anak, diluar rumah sambil santai (EBP:
Intervensi situasi rumah yang menjadikan lupa merokok/ nyaman/ tidak panas/ harmonis/ jauh dari asbak)
5. Memanfaatkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan:
Saya belum pernah ada keluhan selama merokok, jadi tidak pernah berobat ke Puskesmas atau ke dokter.
(EBP; Kenalkan pada Posbindu)
Masalah
Kesehatan Pelaksanaan Tugas Kesehatan Keluarga Risiko penyakit
menular (ISPA, cacingan) pada anggota
keluarga
1. Mengenal Masalah Kesehatan:
Kami tahu kamar kami gelap, tetapi tidak ada uang untuk membongkar kamar. Kamar dan ruangan yang gelap mudah menimbulkan penyakit. Kadang anak main dilantai, katanya bisa cacingan. (Intervensi : Beri penkes tentang pengaruh lingkungan terhadap timbulnya penyakit ISPA dan Cacingan, Penkes Nutrisi Tumbang Anak
2. Mengambil Keputusan:
Sulit bagi kami merubahnya dalam waktu dekat, walaupun kami tahu akibatnya paling kami jaga anak kami tidak main tanah dan tetap pakai alas kaki didalam rumah. (Intervensi; Dukungan untuk konsisten dengan pemikiran tersebut dan niat akan mengalokasikan jika ada dana untuk memperbaiki kondisi)
3. Merawat Anggota Keluarga Yang Sakit :
Kami tetap pakai alas kaki walaupun didialam rumah, saya rajin potong kuku anak anak dan akalu makan harus cuci tangan dulu pakai sabun.(Intervensi lain;
Personal hiegene, nutrisi adekuat, modifikasi nutrisi anak)
4. Modifikasi Lingkungan Rumah:
Tiap pagi kami buka jendela, tapi mebuat jendela dikamar belum ada biaya. Tiap hari saya mebersihkan lingkungan didalam dan diluar rumah (Intervensi EBP: penggunaan genteng kaca hemat, penggunaan karpet plastic dilantai kamar tidur, membersihkan dengan menyiram terlebih dahulu lantai tanah dengan air biar tidak berdebu)
5. Memanfaatkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan:
Akan mendatangi posyandu tiap bulan, jika ada program pemberian obat cacing akan saya berikan pada anak saya.
(Sutanto, 2012)
G. TAHAP DAN TUGAS PERKEMBANGAN KELUARGA
Tahap perkembangan keluarga menurut Duvall dalam Mubarak (2011) (Sutanto, 2012) (Dion dan Betan, 2013), adalah sebagai berikut.
1. Tahap I : Keluarga Pasangan Baru atau Keluarga Baru/ Beginning Family
Keluarga baru dimulai pada saat masing-masing individu suami istri membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah dan meninggalkan (psikologis) keluarga masing-masing dan sudah memiliki keluarga baru. Keluarga baru merupakan anggota dari tiga keluarga; keluarga suami, keluarga istri dan kelurga pasangan baru itu sendiri. Masing-masing pasangan menghadapi perpisahan dengan orangtua dan mulai membina hubungan baru dengan keluarga dan kelompo sosial pasangan masing- masing. Hal ini perlu diputuskan kapan waktu yang tepat untuk mendapatkan anak dan jumlah anak yang diharapkan.
Tugas perkembangan keluarga Tahap Perkembangan I/
Beginning Family :
a. Membina hubungan intim
Dari dua keluarga digabungkan, peran berubah, fungsi baru diterima, belajar hidup bersama sambil memenuhi kebutuhan kepribadian yang mendasar.
b. Membina hubungan dengan keluarga lain, teman, kelompok sosial Sikap saling simpati dan mendukung, berkomunikasi secara spontan dan terbuka, berpisah dari keluarga asal, membina berbagai hubungan; orang tua, sanak saudara, teman, ipar dan loyalitas harus diubah.
c. Mendiskusikan rencana memiliki anak
Mendiskusikan untuk mendapatkan anak dan jumlah anak yang diharapkan.
Masalah kesehatan utama yang muncul adalah penyesuain seksual dan peran perkawinan, kehamilan yang tidak direncanakana, penyakit kehamilan, keluarga berencana, konseling prenatal dan komunikasi.
Masalah keperawatan yang mungkin muncul: ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan, konflik pengambilan keputusan, ketegangan peran, kesiapan meningkatkan komunikasi, ketidakmampuan koping keluarga, ketidakefektifan pola seksualitas, defisit pengetahuan, kesiapan meningkatkan peran.
2. Tahap II : Keluarga ‘Child Bearing’/ Kelahiran Anak Pertama
Keluarga yang menantikan kelahiran dimulai dari kehamilan sampai kelahiran anak pertama berlanjut sampai anak pertama berusia 30 bulan/ 3,2 tahun. Karena fokus pada perawatan bayi. Kelahiran bayi pertama membuat banyak peruabahan besar dalam keluarga, sehingga keluarga dituntut adaptif dengan peranya dlam pemenuhan kebutuhan bayi.
Kelahiran bayi banyak pasangan yang merasa terabaikan. Peran perawat mengkaji peran orangtua, bagaimana orang tua berinteraksi merawat bayi dan bagaiman bayi berespon. Perawat menfasilitasi hubungan orang tua dan bayi yang hangat sehingga jalinan kasih sayang antara bayi dan orangtua tercapai. Masa ini merupakan masa transisi menjadi orang tua yang akan menimbulkan krisis keluarga.
Tugas Perkembangan Klg Tahap Perkembangan II /Kelahiran Anak Pertama :
a. Persiapan menjadi orangtua
b. Adaptasi dengan perubahan anggota keluarga; peran, interaksi, dan kegiatan
c. Mempertahankan hubungan yang memuaskan dengan pasangan.
d. Membagi peran dan tanggung jawab (peran orang tua terhadap bayi dengan memberi sentuhan kehangatan)
e. Menata ruang untuk anak f. Biaya child bearing
g. Bimbingan orangtua tentang pertumbuhan perkembngan anak h. Mengadakan kebiasaan keagamaan secara rutin
Masalah kesehatan utama yang muncul adalah pendidikan maternitas mengenai persiapan untuk pengalaman melahirkan, transisi menjadi orang tua, perawatan bayi yang sehat, mengenali secara dini dan menangani masalah–masalah kesehatan fisik anak dengan tepat, imunisasi, pertumbuhan perkembangan bayi yang normal, family planning, parenting education (include spiritual and religious value), interaksi keluarga, gaya hidup sehat dan peningkatan kesehatan secara umum.
Masalah keperawatan yang mungkin muncul pada tahap ini;
ketegangan peran pemberi asuhan, ketidakefektifan proses hamil- melahirkan, resiko ketidakefektifan proses kehamilan melahirkan, kesiapan meningkatkan proses kehamilan melahirkan, risiko hambatan menjadi orang tua, ketidakefektifan performa peran, risiko gangguan hubungan ibu janin pelemahan koping keluarga, risiko disintegrasi perilaku bayi, ketidakefektifan pola menyusui bayi, diskontinuitas pemberian asi, ketidakefektifan dinamika menyusu bayi
3. Tahap III : Keluarga dengan Anak Prasekolah/ Families With Preschool
Tahap dimulai saat kelahiran anak berusia 2,5 tahun dan berakhir pada saat anak berusia 5 tahun. Pada fase ini keluarga sangat repot, biasanya anak berikutnya lahir pada tahap ini, anak sanagt tergantung pada orangtua. Kedua orangtua harus mengatur waktu hingga kebutuhan anak terpenuhi. Orangtua merancang dan mengarahkan perkembangan keluarga hingga tetap utuh dengan menguatkan hubungan pasangan.
Orangtua menstimulasi tumbuh kembang anak.
Tugas Perkembangan Keluarga Tahap Perkembangan III / Families With Preschool
a. Memenuhi kebutuhan anggota keluarga (rumah, privasi, dan rasa aman)
b. Membantu anak bersosialisasi)
c. Beradaptasi dengan anak yang baru lahir, sementara kebutuhan lain harus terpenuhi
d. Mempertahankan hubungan yang sehat di dalam maupun di luar keluarga/mengarahkan pernikahan yang langgeng
e. Pembagian waktu untuk individu, pasangan, dan anak (tahap paling repot)
f. Kegiatan waktu stimulasi tumbuh kembang
Masalah kesehatan yang sering muncul adalah communicable disease of children, accident, injury, marital relationship, sibling relation, family planning, growth and development needs, parenting issues, child abuse and neglect, good health practices.
Masalah keperawatan yang mungkin muncul pada tahap perkembangan keluarga ini: ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan,
ketidakefektifan manajemen kesehatan, risiko ketegangan peran pemberi asuhan, risiko bahaya lingkungan, resiko jatuh, risiko infeksi, resiko keracunan, perubahan menjadi orang tua, perubahan pertumbuhan dan perkembangan, kesiapan meningkatkan nutrisi, risiko stres pada pemberi asuhan.
4. Tahap IV : Keluarga dengan Anak Sekolah/ Families With School Children
Tahap ini dimulai pada saat anak tertua memasuki sekolah pada usia 6 tahun dan berakhir pada usia 12 tahun. Umumnya keluarga sudah mencapai jumlah anggota keluarga maksimal, sehingga keluarga sangat sibuk. Selain aktivitas di sekolah, masing–masing anak memiliki aktivitas dan minat yang berbeda. Demikian pula orangtua memiliki kegiatan yang berbeda. Orang tua belajar tuntutan ganda mencari kepuasan dalam mengasuh generasi berikutnya dan memperhatikan perkembangan mereka sendiri.
Tugas Perkembangan Keluarga Tahap Perkembangan IV / Families With School Age:
a. Membantu sosialisasi anak terhadap lingkungan luar, tetangga, sekolah dan lingkungan.
b. Mempertahankan keintiman pasangan
c. Memenuhi kebutuhan dan biaya kehidupan yang semakin meningkat, termasuk kebutuhan untuk meningkatkan kesehatan anggota keluarga
d. Mendorong anak mencapai pengembangan daya intelektual e. Keluarga beradaptasi dengan pengaruh teman dan sekolah anak f. Meningkatkan komunikasi terbuka
Masalah kesehatan utama yang muncil pada fase ini diantaranya adalah communicable disease of children, accident, family planning economic needs, school home work, school activities, parenting issues, child abuse and neglect, good health practices/ Breakfast.
Masalah keperawatan yang mungkin muncul pada tahap perkembangan keluarga ini: perilaku kesehatan cenderung berisiko, ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan, ketidakefektifan manajemen kesehatan keluarga, ketidakefektifan perlindungan, ketidakefektifan dinamika makan anak, ketidakefektifan perlindungan, kesiapan meningkatkan koping keluarga
5. Tahap V : Keluarga dengan Anak Remaja/ Families With Teenagers Tahap ini dimulai pada saat anak pertama berusia 13 tahun dan berakhir pada usia 20 tahun. Tahap ini adalah tahap yang paling sulit, yang rawan karena anak akan mencari identitasnya dalam pembentukan kepribadian, menghendaki kebebasan, mengalami perubahan kognitif dan biologis.
Tujuan keluarga ini adalah melepas remaja dan memberi tanggung jawab. Orangtua melepas otoritasnya dan membimbing anak utuk belajar bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Sering muncul konflik orang tua–anak. Anak menginginkan kebebasan, orang tua mengontrol aktivitas anak. Orang tua perlu menciptakan komunikasi terbuka, menghindari permusuhan hingga orang tua anak tetap harmonis.
Tugas Perkembangan Keluarga Tahap Perkembangan V / Families With Teenagers:
a. Memberikan kebebasan yang seimbang dengan tanggung jawab mengingat remaja yang sudah tambah dewasa meningkat otonominya/tahapan paling sulit
b. Mempertahankan hubungan dengan keluarga
c. Mempertahankan komunikasi terbuka antara anak dan orangtua d. Hindari konflik perdebatan, kecurigaan, dan permusuhan e. Perubahan sistem peran dan peraturan untuk tumbang.
Masalah kesehatan utama yang muncul yaitu accident, injury, drug abuse, menstruation, school needs, school activities, parenting issues, teenager problems, harm communication.
Masalah keperawatan yang mungkin muncul pada tahap perkembangan Families With Teenagers: perilaku kesehatan cenderung berisiko, ketidakefektifan manajemen kesehatan keluarga, risiko ketidakefektifan hubungan, konflik peran orangtua, ketidakefektifan kontrol impuls, risiko ketidakefektifan hubungan, ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan, kurang pengetahuan keluarga mengenai kesehatan, hambatan menjadi orang tua, ketidakefektifan dinamika makan remaja, distres moral.
6. Tahap VI : Keluarga dengan Anak Dewasa atau Pelepasan/ Launching Center Families
Tahap ini dimulai pada saat anak pertama meninggalkan rumah dan berakhir saat anak terakhir meninggalkan rumah. Lamanya tahap ini tergantung dari jumlah anak dalam keluarga atau jika anak belum berkeluarga akan tetap tinggal bersama orang tua. Tujuan utama tahap ini adalah mengorganisaikan kembali keluarga untuk tetap berperan dalam melepas anak untuk hidup sendiri. Keluarga mempersiapkan
anak tertua untuk membentuk keluarga sendiri dan membantu anak terakhir untuk lebih mandiri.
Tugas Perkembangan Keluarga Tahap Perkembangan VI / / Launching Center Families
a. Memperluas keluarga inti menjadi keluarga besar b. Membantu anak mandiri di masyarakat
c. Pemantauan kembali peran dalam rumah tangga
d. Mempersiapkan anak hidup mandiri dan menerima kepergiannya.
e. Mempertahankan keintiman pasangan
f. Melanjutkan untuk memperbaharui dan menyesuaikan kembali hubungan perkawinan
g. Menciptakan lingkungan yang dapat menjadi contoh anak- anaknya
h. Membantu orang tua/suami istri yang sedang sakit memasuki masa tua.
Masalah kesehatan utama pada masa ini yaitu komunikasi keluarga luas, komunikasi dewasa muda dengan orang tua, melepas anak, membantu memandirikan keluarga baru, masalah pemberian perawatan bagi orang tua yang memasuki lanjut usia, muncul penyakit kronis dan faktor- faktor yang berpengaruh sperti kolesterol tinggi, obesitas dan hipetrensi derta menopuse pada wanita.
Masalah keperawatan yang mungkin muncul pada tahap perkembangan keluarga tahap ini: ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan, perilaku kesehatan cenderung beresiko, kesiapan meningkatkan manajemen kesehatan, kurang dukungan keluarga, masalah hubungan, kesiapan meningkatkan kesejahteraan spiritual.
7. Tahap VII : Keluarga Usia Pertengahan/ Middle Age Families Tahap ini dimulai pada saat anak terakhir meninggalkan rumah dan berakhir saat pensiun atau salah satu pasangan meninggal. Pada beberapa pasangan ini menjadi tahap yang dirasakan sulit karena masalah lanjut usia, perpisahan dengan anak dan perasaan gagal sebagai orang tua. Setelah semua anak meninggalkan rumah, pasangan berfokus mempertahankan kesehatan dengan pola hidup sehat, diet semibang, olahraga rutin dan menikmati hidup dan pekerjaannya. Pasangan mempertahankan dengan teman sebaya juga dengan anak cucu sehingga merasakan kebahagiaan kakek nenek.
Hubungan anat pasangan perlu semakin dieratkan dengan memeperhatikan ketergantungan dan kemandirian masing –masing pasangan.
Tugas Perkembangan Keluarga Tahap Perkembangan VII / Middle Age Families:
1. Mempertahankan kesehatan
2. Mempertahankan hubungan yang memuasakan dengan teman sebaya dan anak-anak, cucu
3. Meningkatkan keakraban pasangan
4. Mempertahankan kesehatan dengan perilaku hidup sehat
5. Mempunyai lebih banyak waktu dan kebebasan dalam mengolah minat sosial dan waktu santai.
6. Memulihkan hubungan/ kontak dengan anak dan keluarga.
7. Persiapan masa tua/pensiun
Masalah kesehatan utama yang muncul yaitu menjalani peran baru, kehangatan dengan anak cucu, economic problems, saling
merawat, kehilangan, kesepian, menjalin hubungan pasangan baru, penyesuaian keluarga baru.
Masalah keperawatan yang mungkin muncul: ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan, perilaku kesehatan cenderung beresiko, kesiapan meningkatkan manajemen kesehatan, gangguan proses keluarga, diskontinuitas proses keluarga, resiko ketidakefektifan perencanaan aktivitas, hambatan pengelolaan mood.
8. Tahap VIII: Keluarga Lanjut Usia
Tahap akhir perkembangan keluarga ini dimulai pada saat salah satu pasangan pensiun, berlanjut salah satu pasangan meninggal sampai keduanya meninggal. Proses lanjut usia dan pensiun menjadi realita yang tidak dapat dihindari berbagai stresor dan kehilangan yang harus dialami keluarga. Stresor tersbut seprti kehilangan pendapatan, kehilangan berbagai hubungan sosial, kehilangan pekerjaan dan perasaan menurunya produktivitas dan fungsi kesehatan. Mempertahankan penataan kehiduapn yang memuaskan menjadi tugas utama keluarga ini. Lansia umunya lebih dapat beradaptasi dengan rumah sendiri dari pada tinggal dengan anaknya. Tinggal dengan pasangan akan membuat lebih adaptif pada lansia dibanding tinggal dengan teman sebaya. Dengan memnuhi tugas perkembangan berukut diharapkan orangtua mampu beradaptasi menghadapi stresor tersebut.
Tugas Perkembangan Keluarga Tahap Perkembangan VIII / Old Families:
a. Beradaptasi dengan kehilangan pasangan, teman, kekuatan fisik, pendapatan
b. Mempertahankan suusana rumah yang menyenangkan c. Mempertahankan keakraban suami istri saling merawat
d. Mempertahankan hubungan dgn anak dan sosial masyarakat e. Melakukan ‘live review’/ mengenang masalalu bahw a hidupnya
berrati.
Masalah kesehatan utama yang muncul diantaranya menurunnya kekuatan fisik, berkurangnya sumber finansial, kerentanan psikologis, merawat pasangan, kehilangan, kesepian, religion aspect dan isolasi sosial.
Masalah keperawatan yang mungkin muncul pada tahap perkembangan keluarga tahap ini antara lain risiko ketidakberdayaan, kepedihan kronis, hambatan religiositas, kesiapan meningkatkan kesejahteraan spiritual, risiko kesepian, isolasi sosial.
H. PERANAN KELUARGA
Peranan keluarga menggambarkan seperangkat perilaku interpersonal, sifat, kegiatan, yang berhubungan dengan individu dalam posisi dan situasi tertentu. Peranan individu dalam keluarga didasari oleh harapan dan pola perilaku dari keluarga, kelompok dan masyarakat (Muhlisin, 2012). Berbagai peranan formal dalam keluarga menurut Nasrul Effendi (1998) dalam (Effendi & Mafkhfudli, 2013) yang terdapat di dalam keluarga adalah sebagai berikut :
1. Peranan Ayah
Ayah sebagai suami dari istri, berperan sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung, dan pemberi rasa aman, sebagai kepala keluarga, sebagai anggota dari kelompok sosialnya, serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya
2. Peranan Ibu
Sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya, ibu mempunyai peranan untuk mengurus rumah tangga, sebagai pengasuh dan pendidik anak-anaknya,
pelindung dan sebagai salah satu kelompok dari peranan sosialnya, serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya, disamping itu juga dapat berperan sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarganya.
3. Peranan Anak
Anak-anak melaksanakan peranan psiko-sosial sesuai dengan tingkat perkembangannya, baik fisik, mental, sosial dan spiritual.
I. TINGKAT KEMANDIRIAN KELUARGA
Kemandirian keluarga menurut (Depkes, 2006) dalam Riasmini (2017) program perawatan kesehatan komunitas dibagi menjadi empat tingkatan dengan tujuh kriteria sebagai penilaian, yaitu:
a. Kriteria 1 : Menerima perugas perawatan kesehatan komunitas a. Kriteria 2 : Menerima pelayanan keperawatan yang diberikan sesuai
dengan rencana keperawatan.
b. Kriteria 3 : Keluarga tahu dan dapat mengungkapkan masalah kesehatan secara benar.
a. Kriteria 4 : Memnafaatkan fasilitas pelayanan kesehatan secara aktif b. Kriteria 5 : Melakukan perawatan kesehatan sederhana sesuai dengan anjuran c. Kriteria 6 : Melakukan tindakan pencegahan secara aktif.
d. Kriteria 7 : Melaksanakan tindakan promotif secara aktif Tabel Tingkat Kemandirian Keluarga
Tingkat Kemandirian
Kriteria 1
Kriteria 2
Kriteria 3
Kriteria 4
Kriteria 5
Kriteria 6
Kriteria 7
Tingkat I
Tingkat II
Tingkat III
Tingkat IV
DITAMBAHKAN
J. KONSEP KELUARGA SEJAHTERA
Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materil yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009). Kesejahteraan keluarga dipengaruhi oleh faktor internal yang mencakup jumlah anggota keluarga, tempat tinggal, dan keadaan sosial ekonomi keluarga, serta faktor eksternal yang meliputi faktor di luar lingkungan keluarga seperti alam dan ekonomi negara (BKKBN, 2015).
Kategori keluarga sejahtera sesuai dengan tingkat kesejahteraan menurut BKKBN (2017) yaitu:
1) Tahapan Keluarga Prasejahtera (KPS)
Keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu dari 5 kebutuhan dasarnya (basic needs) sebagai keluarga sejahtera I.
2) Tahapan Keluarga Sejahtera I (KS I)
Yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal tetapi belum dapat kebutuhan psikologis (psychological needs) keluarga. Indikatornya yaitu:
a) Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.
b) Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.
c) Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik.
d) Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan.
e) Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi.
f) Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.
3) Tahapan Keluarga Sejahtera II (KS II)
Yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, juga telah dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya (psychologica needs), tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya, seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi. Adapun indikator keluarga sejahtera II (KS II) atau indikator kebutuhan psikologis (psychologica needs) keluarga yaitu :
a) Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing- masing.
b) Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur.
c) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun.
d) Luas lantai rumah paling kurang 8 m2 untuk setiap penghuni rumah.
e) Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing.
f) Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.
g) Seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulisan latin.
h) Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi.
4) Tahapan Keluarga Sejahtera III (KS III)
Yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, sosial psikologis dan pengembangan keluarganya (developmental needs). Pada keluarga sejahtera III, kebutuhan fisik, sosial psikologis dan pengembangan telah terpenuhi, adapun indikatornya yaitu:
a) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.
b) Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang.
c) Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi.
d) Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.
e) Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar, majalah, radio, tv, internet.
5) Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus (KS III+)
Yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, sosial psikologis dan pengembangannya dam akuntabilitas diri (self esteem) telah terpenuhi. Adapun indikator keluarga sejahtera III plus yaitu:
a) Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materil untuk kegiatan sosial.
b) Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/ institusi masyarakat.
BAB II
PRAKTIK KEPERAWATAN KELUARGA A. KONSEP DASAR
1. Keperawatan
Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan professional yang menjadi bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, berbentuk pelayanan bio-psiko-sosial dan spiritual yang komprehensif, ditujukan pada individu, keluarga dan masyarakat baik sehat maupun sakit yang mencakup seluruh proses kesehatan manusia. Lokakarya keperawatan pada tahun 1983 di Jakarta yang merupakan titik tolak diterimanya profesionalisme keperawatan di Indonesia, yang mendefinisikan keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan professional yang merupakan bagian integral dari pelayanan keperawatan, yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, berbentuk pelayanan bio-psiko-sosial-spiritual yang komprehensif yang ditujukan pada individu, keluarga, masyarakat, baik yang sehat maupun sakit mencakup seluruh aspek proses kesehatan manusia.
Dari pengertian tersebut terdapat 4 (empat) elemen utama yang menjadi perhatian, yaitu; (1) Keperawatan adalah ilmu dan kiat –sains terapan (applied science), (2) Keperawatan adalah profesi yang berorientasi pada pelayanan-helping health illness problem, (3) Keperawatan mempunyai empat tingkat klien; individu, keluarga, kelompok dan komunitas, (4) Pelayanan keperawatan mencakup seluruh rentang pelayanan kesehatan (sakit-sehat yang mencakup seluruh proses kehidupan manusia) (Alimul Aziz, 2004) dalam Dion
& Betan (2012).
2. Pelayanan Keperawatan Kesehatan Keluarga
Praktik keperawatan adalah tindakan mandiri perawat profesonal melalui kerjasama yang bersifat kolaboratif dengan klien dan tenaga kesehatan lain dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup, wewenang dan tanggung jawabnya (Dion & Betan, 2013).
Menurut Riasmini dkk (2017) pelayanan keperawatan keluarga adalah salah satu area pelayanan keperawatan yang dapat dilaksanakan di masyarakat. Pelayanan keperawatan keluarga yang saat ini dikembangkan merupakan bagian dari pelaynanan keperawatan kesehatan masyaearakat (Perkesmas). Keperawatan keluarga adalah proses pemberian pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan keluarga dalam lingkup keperawatan. Pelayanan keperawatan kelurga merupakan pelayanan holistik yang menempatkan keluarga dan komponenenya sebagai fokus pelayanan dan melibatkan anggota keluarga dalam tahap pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi tindakan keperawatan dengan memobilisasi sumber-sumber pelayanan kesehatan yang tersedia di keluarga dan sumber-sumber dari profesi lain termasuk pemberi pelayanan kesehatan dan sektor lain di komunitas.
Pelayanan kesehatan keluarga di rumah merupakan integrasi pelayanan keperawatan keluarga dengan pelayanan kesehatan lain di rumah untuk mendukung kebijakan pelayanan kesehatan di masyarakat sehingga dapat mengatasi masalah kesehatan pasien dan keluarganya di rumah. Pelayanan keperawatan keluarga di rumah ini di dukung kerja sama antara petugas kesehatan dengan pasien dan anggota keluarganya. Pelayanan keperawatan ini di rumah maupun di
tempat dimana perawat melaksanakan praktik keperawatan dan dapat diberikan oleh berbagai jenis tenaga baik tenaga professional, tenaga pembantu pelayanan kesehatan maupun tenaga pendamping (caregiver). Dalam praktik pelayanan keperawatan keluarga perawat berperan secara mandiri maupun kolaboratif dengan tim kesehatan lain, dengan upaya pelayanan kesehatan yang diberikan mencakup pencegahan primer, sekunder dan tersier (Depkes, 2008).
Perawat keluarga dapat memeodifikasi lingkungan keluarga, memfasilitasi pencapaian tugas perkembangan keluarga, mempertahankan struktur dan fungsi ekluarga, serta megadaptasikan keluarga terhadap stresor masalah di keluarga sehingga keluarga dapat mengatasi permasalahan kesehatan secara mandiri (Susanto, 2013).
a. Karakteristik Praktik Keperawatan Keluarga
Permasalahan kesehatan keluarga saat ini di Indoesia semakin kompleks, yang memerlukan perawat keluarga dalam memberikan dukungan perawatan keluarga (Friedman, Bowden &
Jones, 2003). Beberapa karakteristik praktik keperawatan keluarga adalah sebagai berikut :
1. Praktik keperawatan keluarga ditekankan pada pengenalan dan integrasi konsep keluarga.
2. Praktik keperawatan kelarga mencoba mengaplikasikan perspektif yang lebih luas seperti teridentifikasi dalam pendekatan perawat terhadap asuhan keperawatan terutama melakukan pengkajian keluarga.
3. Praktik keperawatan keluarga difokuskan pada interaksi keluarga dan dinamika keluarga.
4. Praktik keprawatan keluarga melibatkan anggota keluarga dalam asuhan, terutama dalam mengambil keputusan dan pemberian asuhan.
b. Faktor peningkatan perkembangan keperawatan keluarga Susanto (2012) menuliskan tentang praktik keperawatan keluarga dewasa ini mengalami perkembangan dalam pelayanan kepada keluarga dalam meningkatkan peranan keluarga dalam perkembangan keperawatan keluarga dalam pelaksanaan tugas perkembangan dan kesehatan keluarga. Beberapa peningkatan perkembangan keperawatan keluarga didasarkan oleh beberapa kondisi yang ada di masyarakat (Friedman, Bowden & Jones, 2003) adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya pengenalan dalam keperawatan dan masyarakat terhadap kebutuhan promosi kesehatan dan bukan secara praktis berorientasi pada penyakit.
2. Adanya peningkatan jumlah populasi lansia dan pertumbuhan penyakit kronik.
3. Berkembangan kesadaran keluarga untuk lebih memperhatikan masalah keluarga di komunitas.
4. Penerimaan secara umum teori-teori yang didasarkan keluarga seperti teori interpersonal tertentu.
5. Terapi keluarga dan perkawinan beralih dan tumbuh dalam pedoman klinik dan layanan anak, perkawinan, dan keluarga.
6. Pertumbuhan penelitian-penelitian keluarga dan penemuan yang signifikan mendorong perkembangan keperawatan keluarga.
B. TINGKATAN PRAKTIK PERAWATAN KESEHATAN KELUARGA
Terdapat beberapa level/tingkatan pendekatan keperawatan keluarga menurut Friedman (1998) dalam Achjar (2012) yaitu :
1. Level 1 (Family as Context)
Individu merupakan fokus intervensi dan keluarga sebagai background. Keluarga dipandang sebagai konteks bagi klien yang merupakan latar belakang atau fokus sekunder, sedangkan individu merupakan bagian terdepan atau fokus primer atau berkaitan dengan pengkajian dan intervensi keperawatan. Dalam hal ini perawat keluarga, dapat menganggap keluarga sebagai bagian sistem pendukung sosial klien tetapi hanya dengan sedikit keterlibatan keluarga ke dalam rencana perawatan klien.
2. Level 2 (Family as Client)
Keluarga sebagai penjumlahan dari anggota-anggotanya (keluarga sebagai kumpulan dari anggota keluarga). Dalam praktik keperawatan keluarga, keluarga dipandang sebagai kumpulan dari anggota keluarga, sehingga asuhan keperawatan bisa digunakan untuk seluruh anggota keluarga tersebut. Asuhan keperawatan diberikan bukan hanya pada satu individu, tetapi bisa lebih individu. Fokus dari keluarga sebagai klien adalah bagaimana individu anggota keluarga berdampak pada keluarga secara menyeluruh (Stanhope dan Lancaster, 2012). Hal ini memerlukan kemampuan perawat dalam merespon ekspresi verbal dan nonverbal seluruh anggota keluarga saat terdapat anggota keluarga yang sakit. Rumusan diagnosis keperawatan yang ditegakkan tidak lagi berfokus pada kebutuhan anggota keluarga sebagai individu namun dampak masalah kesehatan pada salah satu anggota keluarga pada seluruh anggota keluarga.