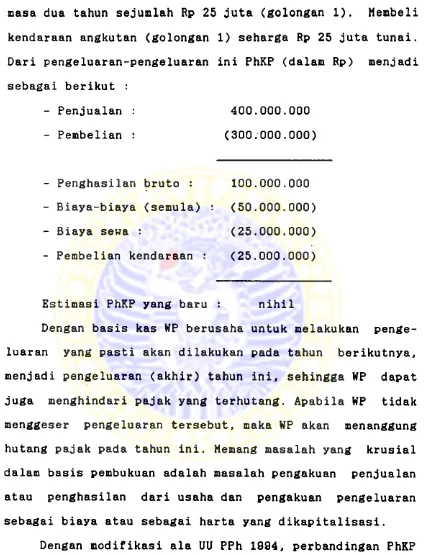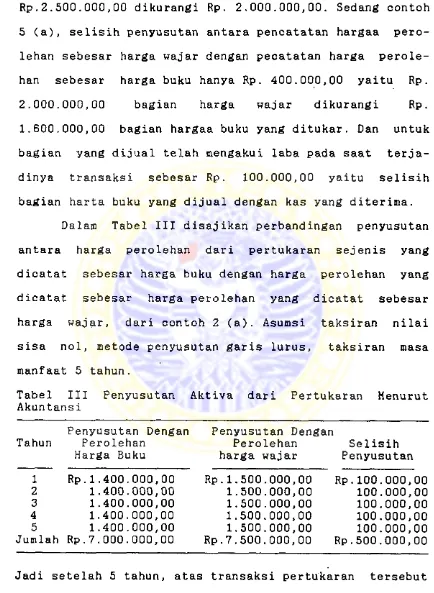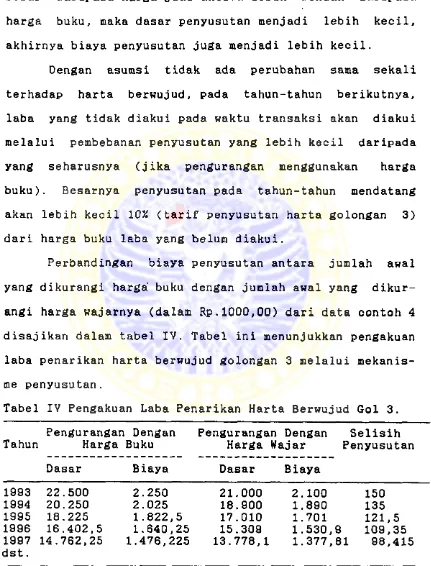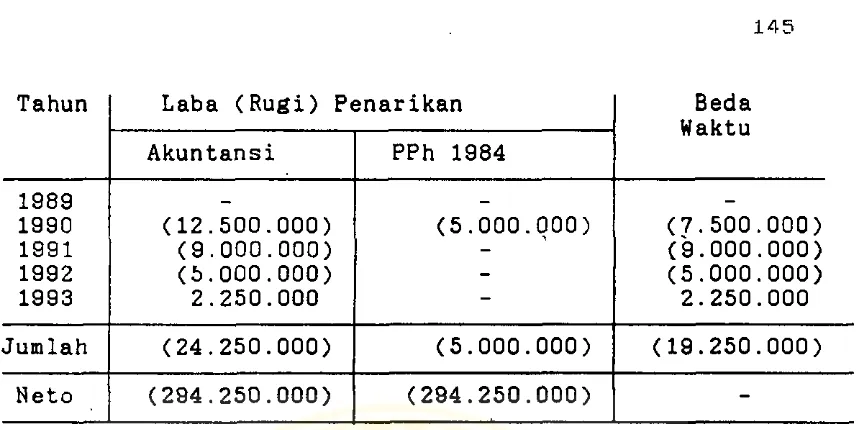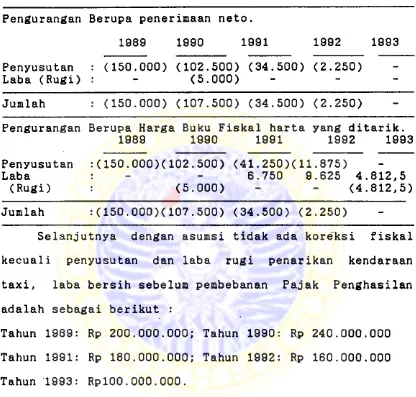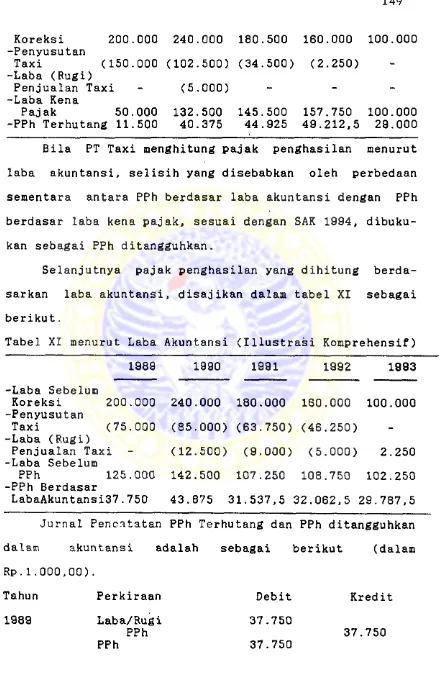DAN LABA RUGI PENARIKAN AKTIVA TETAP
UNTUK PENETAPAN LABA
MENURUT AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN
DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI
■
2.04c f 9
S 'A-sy
D IA JU K A N OLEH
M. ALI ASYHAR
No. Pokok : 048812917
K E P A D A
SKRIPSI
ANALISIS PENGAKUAN PENYUSUTAN
DAN LABA RUGI PENARIKAN AKTIVA TETAP
UNTUK PENETAPAN LABA
MENURUT AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN
DIAJUKAN OLEH :
M. ALI ASYHAR
No. Pokok : 048812917
TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH
DOSEN PEMBIMBING,
TANGGAL
KETUA JURUSAN,
-SURABAYA,...
TELAH DISETUJUI DAN SIAP UNTUK DIUJI
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadlirat Allah SWT.
atas segala limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga
skripsi ini bisa terselesaikan.
Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyara-
tan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi
Universitas Airlangga, sehingga mutlak harus dipenuhi
oleh mahasiswa.
Kiranya skripsi ini sulit terselesaikan tanpa ban-
tuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan yang
baik ini kami ingin menyampaikan rasa terima kasih dan
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :
1. Bapak Budi Setiorahardjo, selaku dosen pembimbing
dalam penulisan skripsi ini. Beliau telah banyak
membantu demi kelancaran skripsi ini.
2. Rekan Arief Tejo Sumartono, tanpa bantuannya rasanya
sulit untuk menyelesaikan skripsi ini dengan secepatn-
ya.
3. Juga rekan Hasan S., Sugeng S., dan Hasyim. Teriina
kasih atas pemberian dorongan/motivasi untuk secepatn-
ya menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula kepada
rekan-rekan jurrassie '88 UNAIR.
4. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Johar
Djaelani dan Mas Heru Tjaraka yang telah berkenan mel-
Ibarat tak ada gading yang tak retak, maka kami
menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesem-
purnaan, untuk itu segala kritik yang konstruktif akan
diterima dengan senang hati.
Akhirnya kami berharap mudah-mudkhan skripsi ini
bisa membawa manfaat yang besar bagi perkembangan akun
tansi dan perpajakan di Indonesia. Amiin.
Surabaya, Akhir Juni 1995
Penulis
M. Ali Asyhar
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ... I
DAFTAR ISI ... Ill
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah ... 1
1.2. Perumusan Masalah ... 3
1.3. Tujuan Penelitian ... .4
1.4. Manfaat Penelitian ... 4
1.5. Sistematika Penulisan Skripsi ... 5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Landasan Teori ... 7
2.1.1. Penyusutan, Laba Rugi Penarikan aktiva Tetap Menurut Akuntansi... 7
2.1.1. Pengertian Aktiva Tetap ... 7
2.1.2. Penyusutan Aktiva Tetap ... 8
2.1.3. Laba Rugi Penarikan Aktiva Tetap.. 24
1. Laba Rugi Penarikan ... 25
v • 2. Laba Rugi Pertukaran ... 26
2.1.2. Penyusutan, Laba Rugi Penarikan Aktiva Tetap Menurut Perpajakan ... 28
2.1.2.1. Harta yang disusutkan ... 28
2.1.2.2. Penyusutan Harta berwujud dan tak Berwujud menurut perpajakan.... 36
disusut-kan dan jangka waktu penyusutan ... 44
2.1.2.4. Tarif, Dasar, dan metode penyusu tan ... 47
2.1.2.5. Laba Rugi Penarikan ... 50
2.2. Metode Penelitian ... 55
2.2.1. Definisi Operasional ... 55
2.2.2. Jenis dan sumber Data ... 55
2.2.3. Teknik Analisis ... 56
BAB III PEMBAHASAN 3.1, Pengaruh Ketentuan Tentang Penyusutan Terhadap Laba Kena Pajak ... 57
3.1.1. Basis Pembukuan ... *... 58
3.1.2. Harta Yang Disusutkan ... 65
3.1.3. Penentuan Harga Perolehan ... 75
3.1.4. Pengelompokan Harta dan Jangka Waktu Penyusutan ... 96
3.1.5. Tarif, Dasar, dan Metode Penyusutan .... 104
3.2. Pengaruh Pengakuan Laba Rugi Penarikan Terhadap Laba Kena Pajak ... 129
3.2.1. Pengakuan Laba Penarikan dan Pertukaran.. 131
3.2.1. Pengakuan Rugi Penarikan dan Pertukaran.. 137
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN 4.1. Simpulan ... 151
4.2. Saran ... 156
BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah
Dalam rangka menuju era industrialisasi seperti yang
digalakkan oleh pemerintah dan dalam era perekonomian
saat. ini, aktiva tetap akan semakin banyak digunakan
dalam dunia usaha. Aktiva tetap biasanya meliputi jumlah
yang besar dari keseluruhan aktiva, lebih-lebih untuk
perusahaan yang bergerak dalam bidang industri. Pembeba
nan aktiva tersebut sebagai biaya dilakukan melalui
penyusutan, deplesi, dan amortisasi selama beberapa
tahun. Istilah aktiva tetap tidak dikenal dalam perpaja
kan, istilah ini hanya dikenal dalam akuntansi. Sedang
perpajakan (pajak penghasilan di Indonesia) menggunakan
istilah harta berwujud dan harta tidak berwujud.
Pembebanan aktiva tetap sebagai biaya dalam akuntan
si dikenal dengan istilah penyusutan untuk aktiva berwu
jud, deplesi untuk sumber alam, dan amortisasi untuk
aktiva tidak berwujud dan beban yang ditangguhkan. Perpa
jakan menggunakan istilah penyusutan untuk harta berwujud
dan amortisasi untuk harta tidak berwujud, beban yang
ditangguhkan, hak penambangan minyak dan gas bumi, dan
hak pengusahaan hutan (HPH). Istilah deplesi tidak ada
dalam perpajakan. Istilah-istilah ini sebenarnya sama,
menjadi biaya dengan cara yang sistenatis dan rasional
selama taksiran masa pemanfaatan.
Disatu sisi pemerintah berkepentingan memungut
pajak, disisi lain pemerintah berkewajiban mendorong
industrialisasi. Oleh karena itu ketentuan perpajakan
harus dapat memenuhi dua hal yang saling bertentangan
tersebut. Jangan sampai ketetentuan penyusutan perpajakan
hanya dapat memasukkan pajak ke kas negara, tetapi mem-
buat perusahaan tidak berkembang karena enggan melakukan
ekspansi industrialisasi.
Seiring dengan proses industrialisasi, maka banyak
perkembangan baru dalam cara perolehan. aktiva tetap
misal ruilslag; build, operate, and transfer (BOT);
build, operate, and own (BOO). Ruilslag sebenarnya bukan
hal baru dalam akuntansi maupun perpajakan, karena ruils
lag merupakan pertukaran aktiva dalam hal ini tenah.
Seperti dikemukakan A.P. Parlindungan, “pada waktu ini
banyak sekali dilakukan ruilslag dari sejunlah tanah
instansi pemerintah dengan swasta. Swasta menyediakan
lahan dan bangunan pengganti, kemudian swasta memperoleh
lahan eks instansi pemerintah tersebut.*
Sedang BOT (Build, Operate, and Transfer) sesuai
dengan arti yang terkandung didalamnya, maka harta yang
dibangun, dikelola dalam jangka waktu tertentu kemudian
diserahkan kepada pihak lain. Pihak pSnerima ini bukannya
menerima harta BOT tanpa pengorbanan. Pengorbanan pihak
penerima ini berupa kesanggupan untuk menyediakan lahan
atau lokasi tempat pembangunan aktiva yang bersangkutan.
Dengan demikian kepemilikan aktiva BOT oleh pihak pemban-
gun tidaklah tetap, tetapi hanya sementara yaitu untuk
jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang
dibuat oleh kedua belah pihak. Karena setelah jangka
waktu pengelolaan sesuai perjanjian habis, aktiva BOT
harus diserahkan kepada pihak penyedia lokasi.
Disamping BOT ada lagi BOO (Build, Operate, and
Own). Berbeda dengan BOT, dalam BOO tidak ada ketentuan
yang mengharuskan pihak pembangun menyerahkan aktiva BOO
kepada pihak manapun. Kepemilikan aktiva BOO bersifat
tetap, selama tidak dijual atau dialihkan kepada pihak
lain. Jadi dalam hal ini kepemilikan aktiva BOO sama
dengan kepemilikan aktiva yang diperoleh seperti dari
pembelian biasa.
2. Perunusan Hasalah
Keskipun antara akuntansi dan perpajakan mempunyai
pengertian yang pada dasarnya sama mengenai aktiva berwu
jud dan tak berwujud, tetapi masih terdapat perbedaan
pengakuan terhadap suatu aktiva boleh diakui
Dan Lsesuni d e n g a n lal.ur beLcikut^ m a s a l a h s e p e r t i >J i
atas, m a k a y a n g m e p j a d i m a s a l a h di sini a d a l a h b a h w a *
p e r b e d a a n - p e r b e d a a n t e r s e b u t ada y a n g b e l u m d i a t u r atau
d i t u a n g k a n d a l a m p e r a l u r a n - p e r a t u r a n , b ai k o le h p e r p a j a
kan m a up un akuntansi.
3. 'i’ujuan Perisi itian
Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dari peneli
tian ini yaitu :
1. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi perbedaan-
perbedaan dalam pengakuan penyusutan dan laba rugi
penarikan aktiva tetap baik menurut akuntansi maupun
perpajakan.
2. Untuk mengetahui apakah ketentuan-ketentuan yang ada
sekarang masih capat diterapkan atas perkembangan-
perkembangan baru ataukah perlu dikeluarkan ketentuan
baru.
3. Dengan penelitian ini pula diharapkan diketahui apakah
ketentuan yang ada telah cukup untuk mencegah penghin-
daran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.
4. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:
1. l'kut memberi aumbangan kepada dunia ilmu pengetahuan ,
terutama dibidang akuntansi dan perpajakan.
2. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penyusu
dapat diambil manfaatnya sesuai dengan permasalahan
yang ada.
3. Sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya.
5. Sistenatila Penulisan Skripsi
Skripsi ini terdiri dari empat bab. Secara garis
besar isi dari masing-masing bab adalah sebagai berikut :
BAB I : Pendahuluan
Bab ini terdiri dari latar belakang permasa
lahan, pembatasan masalah, tujuan yang ingin
dicapai dan manfaat penelitian serta siste-
matika penulisan skripsi.
BAB II : Tinjauan Pustaka
Bab kedua akan menguraikan teori pengakuan
biaya penyusutan dan laba rugi penarikan
aktiva tetap dari sudut pandang akuntansi
dan perpajakan. Landasan teori ini akan
merujuk pada Standar Akuntansi Keuangan 1994
disamping prinsip akuntansi yang lazim.
Sedangkan perpajakannya merujuk pada UU PPh
1994 di Indonesia maupun ketentuan yang
berada dibawahnya.
BAB III : Pembahasan
Bab ketiga membahas masalah ketentuan penyu
sutan atas harta berwujud dan harta tak
harta yang dapat disusutkan, penentuan harta
perolehan, pengelompokan harta dan jangka
waktu penyusutan, tarif, dasar, dan metode
penyusutan; serta membahas ketentuan penga-
kuan laba rugi penarikan harta berwujud dan
harta tak berwujud.
BA5 IV : Kesimpulan dan Saran
Dalam bab ini akan dikemukakan kesimpulan
dari hasil pembahasan bab-bab terdahulu dan
saran-saran untuk memperbiki ketentuan
penyusutan dan amortisasi serta pengakuan
laba rugi penarikan harta berwujud dan harta
tak berwujud khususnya untuk keperluan
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Landasan Teori
2.1.1. Penyusutan, Laba Rug! Penarikan Aktiva Tetap
Menurut Akuntansi
2.1.1.1. Penflertian Aktiva.,Tetap. Pengertian aktiva
tetap, menurut IAI, yang dltuangkan dalam SAK 1994 Nooer
16 paragraf 05 adalah sebagal berikut :
Yang dimaksud dengan aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau yang dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operas! perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. 2
Pengertian di atas hampir sama dengan pengertian
aktiva tetap menurut Eldon S. Hendriksen, hanya dia
menambah ciri lain yang tak disebut SAK 1994, "they are
all nonmonetery in nature;... yaitu aktiva tetap
bersifat non moneter.
Dari pengertian tersebut suatu jenis aktiva
dimasuk-kan sebagai aktiva tetap oleh suatu perusahaan, tetapi
oleh perusahaan lain dapat saja dikelompokkan sebagai
2IAI.Standar Akuntansi Keuangan. PSAK Nomor 16, Para graf 05, Salemba Empat, Jakarta, 1994.
persediaan atau sebagai investasi jangka panjang.
Sedangkan yang dimaksud aktiva tidak berwujud menur
ut SAK 1994 PSAK Nomor 19 paragraf 02 adalah, "Aktiva tak
(intangible asset) adalah aktiva tak lancar (non current
asset) dan tak berbentuk yang memberikan hak keekonomian
dan hukum kepada pemiliknya ...“4
Masa manfaat aktiva tidak berwujud ada yang dibatasi
oleh ketentuan atau peraturan lain, misal hak paten, hak
cipta, dan franchise, ada pula yang mempunyai masa man
faat yang tidak terbatas waktunya misalnya goodwill.
2.1.1.2. Penyusutan Aktiva Tetap- Telah disebutkan
di atas bahwa masa manfaat aktiva tetap dan aktiva tidak
berwujud lebih dari setahun, sedangkan pengeluaran untuk
memperoleh aktiva tersebut hanya pada satu waktu. Untuk
menunjukkan biaya karena pemakaian aktiva tetap, maka
diadakan pembebanan biaya melalui penyusutan. Pembebanan
melalui penyusutan ini merupakan upaya untuk menaati
konsep matching cost against revenue. Penandingan ini
memang sulit dilakukan dan sangat diragukan ketepatannya.
Penyebab hal ini adalah bahwa pembebanan penyusutan tidak
terlepas dari taksiran-taksiran manajemen. IAI memberikan
pengertian penyusutan dalam SAK 1994, yaitu PSAK No. 17
paragraf 02 sebagai berikut:
Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diesti- masi. Penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung.
Dari pengertian di atas, terlihat bahwa penyusutan,
deplesi, serta amortisasi ketiga-tiganya mempunyai arti
sama. Yaitu alokasi atas nilai aktiva tetap sebagai
biaya, yang mana masing-masing istilah diperuntukkan
terhadap aktiva dengan memperhatikan wujud (jenis) aktiva
tetap. Oleh karena itu seolah-olah aktiva tetap dibagi
menjadi tiga jenis yaitu berwujud, sumber alam, dan tak
berwujud. Memang benar aktiva tetap mencakup pula sumber
alam, tetapi tidak demikian halnya dengan aktiva tidak
berwujud. Jika dilihat dari prinsip aktiva dalam PAI
1984, 1AI memisahkan aktiva tak berwujud dari aktiva
tetap, yang masing-masing merupakanpos tersendiri dan
terpisah satu sama lain dalam neraoa.
Skripsi ini hanya membahas mengenai alokasi pembeba
nan aktiva tetap dan aktiva tidak.berwujud sebagai biaya
melalui penyusutan dan amortiasi. Akan tetapi, secara
ringkas dapat dijelaskan penyajian aktiva tetap dan
aktiva tidak berwujud dalam neraca. Komponen aktiva
terdiri dari aktiva lancar, investasi, aktiva tetap,
aktiva tidak berwujud, dan aktiva lain-lain. Di sini
jelas bahwa altiva tetap dipisahkan dari aktiva tidak
berwujud. Sedang dalam pengertian aktiva tetap mencakup
pula sumber alam.
Ada tiga faktor yang mempengaruhi jumlah beban
penyusutan yaitu dasar penyusutan, taksiran umur manfaat
atau jangka waktu penyusutan, dan metode penyusutan.
Dasar Penyusutan
Pengertian dasar penyusutan menurut Schroeder,
McCullers dan d a r k adalah sebagai berikut, "The depre
ciation base is that portion of the cost of the asset
that should be charge to expense over its expected useful Q
service life.*'0 Jadi dasar penyusutan merupakan bagian
dari nilai aktiva yang akan dibebankan sebagai biaya
selama taksiran masa manfaat.
Dengan demikian, jumlah seluruh nilai perolehan
tidak secara otomatis menjadi dasar penyusutan. Hal ini
disebabkan adanya nilai sisa, yang ditaksir akan dapat
diterima, jika aktiva tersebut tidak dipakai lagi dan
dijual. Nilai perolehan akan sama dengan dasar penyusutan
bila taksiran nilai sisanya adalah nihil.
Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa dasar
penyusutan dipengaruhi oleh nilai perolehan dan nilai
sisa. Nilai perolehan aktiva tetap itu sendiri
dipengaru-^Richard G. Schroeder, Levis D. McCullers, dan Myrtle Clark, Accounting Thporv Text And Reading. Edisi ketiga,
hi oleh cara perolehan. Berikut ini diuraikan cara pero
lehan aktiva tetap dan komponen-komponen yang termasuk
nilai perolehan.
a. Aktiva tetap yang Diperoleh Dalaii Bentuk Siap Pakai
Aktiva yang diperoleh dengan cara ini dicatat sebe-
sar harga beli aktiva yang bersangkutan ditambah biaya-
biaya lain misalnya bea masuk, biaya pemasangan, biaya
angkut, pajak penjualan barang mewah jika aktiva yang
dibeli merupakan barang mewah (PPn BM) sesuai undang-
undang, sehingga aktiva yang dimaksudkan benar-benar siap
untuk digunakan. Sedang pajak pertambahan nilai (PPN)
masukan atas pembelian barang jika dapat dikreditkan dari
PPN keluaran maka tidak termasuk biaya yang dikapitalisa-
si. PPN yang dikapitalisasi adalah PPN yang tidak dapat
dikreditkan dari PPN keluaran. Untuk pembelian tunai
harga beli adalah sebesar yang dibayarkan.
Sedangkan pembelian dengan cara kredit atau angsur-
an, maka harga perolehan aktiva adalah harga yang sehar-
usnya dibayar jika aktiva tersebut dibeli secara tunai.
Dengan perkataan lain harga perolehan.adalah harga tunai,
tidak termasuk unsur bunga yang dibayarkan.
b. Aktiva Tetap yang Dibangun Sendiri
Harga perolehan aktiva tetap yang dibangun sendiri
meliputi seluruh biaya berkenaan dengan pembangunan
ini mencakup bahan langsung, upah langsung, biaya produk
si tak langsung. Masalah timbul bila pembangunan dibiayai
dengan dana pinjaman. IAI memberikan pernyataan dalam
PSAK No. 26 bahwa pinjaman ini boleh dikapitalisasi, jika
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1. Biaya pembangunan aktiva tersebut dapat diakumulasikan secara terpisah.
2. Diperlukan jangka waktu yang cukup , lama untuk membangun atau memproduksi aktiva yang bersangku tan .
3. Pembangunan atau produksi tersebut memerlukan biaya yang besar, sehingga melibatkan perusa haan dengan niaya bunga yang tinggi.
c. Aktiva Tetap Diperoleh dari Pertukaran Aktiva Non noneter
Pencatatan aktiva yang diperoleh dengan cara ini,
perlu memperhatikan jenis pertukarannya. Pertukaran
aktiva tidak sejenis, perolehan dioatat dengan nilai
wajar/pasar (berkaitan dengan laba rugi, akan dibahas
tersendiri).
Pertukaran aktiva sejenis, harga perolehan aktiva
tetap pada dasarnya adalah nilai buku atau harga pasar
aktiva yang diserahkan, mana yang lebih rendah. Pertukar
an sejenis tidak melibatkan uang, aktiva dicatat sebesar
harga buku atau harga pasar, mana yang lebih rendah. Jika
melibatkan uang, uang yang diserahkan manambah harga buku
atau harga pasar yang lebih rendah tadi. Sedang
an sejenis dengan menerima uang, maka harus dilihat
dahulu penjumlahan uang yang diterima dengan herga pasar
aktiva yang diterima. Jika penjumlahan tersebut lebih
kecil dari harga buku aktiva yang diserahkan, maka harga
perolehan aktiva yang diterimadicatat sebesar harga pasar
aktiva yang diterima. Bila penjumlahan tersebut lebih
besar dari harga buku aktiva yang diserahkan, maka harga
buku aktiva yang diserahkan diperlakukan menjadi dua
bagian yaitu bagian yang dijual dan bagian yang ditukar,
yang nilainya proporsional dengan kas yang diterima dan
harga pasar aktiva yang diterima. Bagian harga buku
aktiva yang ditukar inilah yang menjadi nilai perolehan
aktiva yang diterima.
Bagian harga buku yang dijual dan harga buku yang
ditukar ditentukan sebagai berikut. Bagian harga buku
yang dijual adalah kas dibagi penjumlahan (kas dan harga
wajar aktiva yang diterima) dikalikan harga buku aktiva
lama yang ditukar.Dan bagian harga buku aktiva yang
ditukar adalah harga wajar aktiva yang diterima dibagi
penjumlahan dikalikan harga buku aktiva lama yang ditu
kar .
Berikut ini diberikan contoh-contoh untuk memperje-
las uraian pertukaran aktiva sejenis.
Contoh 1, pertukaran sejenis tidak melibatkan uang.
Nilai perolehan aktiva lama RplO.000.000,00 dan akumulasi
terse-but mempunyai harga pasar (a) Rp2.500.000,00 atau (b)
Rpl.000.000,00 adalah sebagai berikut.
Harga ,Pasar£a)• Harga pasar (by
Aktiva baru 2.000.000 1.000.000
Akumulasi penyusutan 8.000.000 8.000.000
Rugi pertukaran - 1.000.000
Aktiva lama 10.000.000 10.000.000
contoh 2, seandainya dalam transaksi contoh i terse
but di atas melibatkan uang, yaitu dengan menyerahkan
uang sejumlah Rp5.000.000,00, maka pencatatannya menjadi
sebagai berikut.
Harga pasar (a^ Harga pasar (b)
Aktiva baru 7.000.000 6.000.000
Akumulasi penyusutan 8.000.000 8.000.000
Rugi pertukaran - 1.000.000
Aktiva lama 10.000.000 10.000.000
kas 5.000.000 5.000.000
Contoh 3, sedang bila transaksi oontoh 1 melibatkan
uang, dengan menerima uang Rp500.000,00, maka pencata
tannya adalah sebagai berikut.
Harga pasar <ai Harga pasar (b)
Kas 500.000 500.000
Aktiva baru 1.600.000 500.000
Akumulasi penyusutan 8.000.000 8.000.000
Rugi pertukaran * 1.000.000
Akt iva lama 10.000.000 10.000.000 Laba pertukaran 100.000
D. Cara Penetapan Aktiva Tetap yang Diperoleh Secara
Gabungan
Pembelian sekelompok aktiva yang dilakukan sekalian,
harga perolehan aktiva gabungan tersebut ke masing-masing
aktiva, dengan perbandingan nilai wajar masing-masing
aktiva yang dibeli tersebut. Hal ini untuk menghasilkan
ketepatan penghitungan harga perolehan aktiva.
e. Aktiva yang Diperoleh dari Sumbangan
Harga perolehan aktiva yang diperoleh dari sumbangan
atau hibah atau sejenisnya dicatat sebesar harga dan
bukan merupakan pendapatan tetapi dicatat sebagai modal
yang berasal dari sumbangan.
f. Perolehan Aktiva Tetap dengan Sena Guna Usaha
Sewa guna usaha atau leasing dapat diartikan sebagai
berikut:
Kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa- guna- usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa-guna-usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh (Leas- see) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.
Pernyataan IAI No. 30 membagi jenis leasing menjadi
capital lease/finance lease dan operating lease, yang
pembedaannya didasarkan pada arti ekonomis bukan makna
hukum formalitas.
Suatu transaksi sewa guna usaha, menurut PSAK
No.30, dikelompokkan sebagai capital lease bagi penyewa
guna usaha atau leassee (dan sebagai finance lease bagi
perusahaan sewa guna usaha atau lessor) Jika memenuhi 3
syarat. Ketika syarat menurut Pernyataan IAX No. 30
tersebut sebagai berikut :
1. Penyewa guna usaha memiliki hak opsi untuk membe- li aktiva yang disewagunausahakan pada akhir masa sewa guna usaha dengan harga yang telah disetujui bersama pada saat dimulainya perjanjian sewa guna usaha.
2. Seluruh pembayaran berkala yang dilakukan penyewa guna usaha ditambah dengan nilai sisa mencakup pengembalian harga perolehan barang modal yang disewagunausahakan serta bunganya sebagai keun- tungan perusahaan sewa guna usaha (full payout lease).
3. Masa sewa guna usaha minimum 2 (dua) tahun.
Jika ada satu syarat yang tidak dipinuhi maka tra-
saksi harus dikelompokkan sebagai transaksi operating
lease.
Perlakuan akuntansi terhadap aktiva tetap sewa guna
usaha jenis finance lease oleh perusahaan sewa guna usaha
(lessor) meskipun secara hukum masih memiliki aktiva
tersebut, tetapi secara ekonomis telah memindahkan hak
dan resiko atas aktiva kepada lessee, maka lessor tidak
mencatat dalam pembukuannya, selanjutnya penyusutan atas
aktiva yang bersangkutanpun tidak ada. Sebaliknya bagi
penyewa guna usaha atau lessee, perolehan aktiva ini
disebut sebagai capital lease dan dicatat sebesar nili
tunai dari seluruh pembayaran berkala dan harga opsi, dan
diamortisasi selama masa manfaat yang ditaksir.
Sedang untuk jenis operating lease, hal ini tidak
/ *
berbeda dengan sewa-menyewa biasa. Lessor tetap mencatat
aktiva dan menyusutkannya, lessee tidak mencatat aktiva
dan tidak menyusutkan atau mengamortisasinya.
g. Perolehan Aktiva Tak Berwujud
Perolehan aktiva ini meliputi seluruh biaya yang
terjadi dalam rangka memperoleh aktiva tersebut. Aktiva
tak berwujud yang dikembangkan sendiri, kapitalisasi
dilakukan bila pengeluaran dapat diidentifikasi atas
aktiva yang bersangkutan. Bila tidak, pengeluaran dibe-
bankan langsung sebagai biaya.
Termasuk dalam aktiva tak berwujud ini antara lain
adalah hak oipta, hak paten, dan franchise (yang mempun-
yai masa manfaat tidak terbatas).
Disamping harga perolehan , biaya-biaya setelah
perolehan untuk penambahan, perbaikan, atau penggantian
komponen aktiva yang memperpanjang masa manfaat, mening-
katkan kapasitas atau mutu, maka biaya-biaya ini harus
dikapitalisasi dan dibebankan melalui penyusutan.
Setelah mengetahui harga perolehan, maka langkah
selanjutnya adalah menaksir nilai sisa untuk' menetapkan
dasar penyusutan. Dalam hal ini mutlak tergantung kebija-
kan manajemen.
Apabila terjadi penarikan aktiva tetap maupun aktiva
penyusu-tan. Pengurangan ini dilakukan dengan mendebet akumulasj.
penyusutan dan mengkredit harga perolehan (termasuk di
dalamnya biaya-biaya yang tadinya dikapitalisasi dengan
cara menambah harga perolehan). Jika dari penarikan ini
ada diterima kas, selisih kas yang diterima dengan harga
buku merupakan laba rugi.
Jangka Waktu Penyusutan
Pada sub bab terdahulu telah dikemukakan bahwa
alokasi aktiva tetap sebagai biaya dilakukan selama
taksiran umur ekonomisnya. Selain itu SAK 1994 Juga
menyebutkan penyusutan dan amortisasi harus dilakukan
secara layak berdasarkan taksiran masa manfaatnya. Artin-
ya biaya penyusutan/amortisasi harus dibebankan pada
tahun yang menerima panghasilan dari penggunaan aktiva.
Tahun yang tidak menerima manfaat aktiva tersebut, konse-
kuensinya juga tidak dibebani biaya penyusutan atau
dengan kata lain aktiva yang sudah tidak digunakan lagi,
maka tidak ada lagi penyusutan atas aktiva tersebut.
Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menandingkan
antara biayayang terjadi dengan penghasilan yang dipero
leh dari pengorbanan biayanya atau (matching cost against
revenue). Apabila terdapat aktiva yang tidak digunakan
lagi yang jumlah nilainya besar, aktiva tersebut dicatat
dalam kelompok aktiva lain-lain berdasarkan nilai reali-
Tahun-tahun yang akan dibebani biaya penyusutan dan
amortisasi tergantung taksiran manajemen. Taksiran mana
jemen dapat didasarkan pada waktu atau unit penggunaan
atau kriteria lain. Taksiran ini sepenuhnya tergantung
pada manajemen perusahaan yang bersangkutan. Artinya,
manajemen di suatu perusahaan dapat menaksir berbeda
dengan manajemen di perusahaan lain atas aktiva yang
sama. Namun, taksiran harus tetap rasional, serta mengacu
pada hubungan biaya dan manfaat atas penggunaan aktiva
bersangkutan, sehingga mencerminkan hanya tahun-tahun
yang memperoleh penghasilan dari penggunaan aktivalah
yang dibebani biaya penyusutan atau amortisasi.
Jadi meskipun jangka waktu penyusutan atau amortisa
si tidak dapat ditetapkan secara pasti, tetapi tahun-
tahun yang dibebani biaya penyusutan dan amortisasi harus
dapat dipastikan telah memanfaatkan aktiva tetap dan
aktiva tak berwujud. Konsekuensi dari prinsip ini, misal
ada aktiva yang belum habis alokasi pembebanan penyusu
tannya, karena sudah tidak dimanfaatkan lagi, maka tahun-
tahun yang tidak memanfaatkan tidak dibebani penyusutan.
Oleh karena penyusutan dibebankan pada masa yang
menerima manfaat, maka jika aktiva baru digunakan pada
pertengahan tahun, beban untuk tahun yang bersangkutan
juga hanya setengah dari pembebanan tahunan. Ada beberapa
cara perlakuan terhadap pengakuan penyusutan atas aktiva
berjalan, yaitu sebagai berikut. is recognised on retirement.
5. Depreciation is recognised for a full year on acquisition during the year but no depreciation is recognised on retirement.10
Hetode Penyusutan
Pembebanan biaya penyusutan dapat dilakukan melalui
berbagai metode. Metode penyusutan dan amortisasi yang
diakui oleh SAK 1994 adalah sebagai berikut.
a. Metode Penyusutan Berdasarkan Vaktu
1. Metode Garis Lurus
Metode ini membebankan Jumlah biaya penyusutan
yang sama atas nilai dasar penyusutan ke tahun-tahun
selama masa manfaat. Tarif metode penyusutan ini
adalah 1/n, n adalah umur aktiva atau masa manfaat.
Jumlah biaya penyusutan tiap-tiap tahunnya tersebut
adalah sebesar dasar penyusutan dibagi dengan masa
manfaatnya.
2. Metode Pembebanan Menurun
a. Jumlah angka tahun
Metode ini membebankan penyusutan dengan pecahan
jumlah tahun, dan pecahan dimulai dari angka tahun
terbesar kemudian angka pembilang menurun satu demi
satu ke tahun-tahun berikutnya. Hal ini dapat dije-
laskan dengan contoh berikut. Suatu aktiva tetap
dengan umur manfaat ekonomis 5 tahun, maka jumlah
angka tahunnya adalah 5 + 4 + 3 + 2 + l = 15. pro
porsi penyusutan tahun pertama sampai dengan tahun
kelima berturut-turut adalah 5/15, 5/15, 3/15, 2/15,
dan 1/15.
b. Saldo Menurun
Metode ini membebsankan penyusutan dengan tarip
tetap yang dikalikan dengan nilai buku. Nilai sisa
dalam hal ini hanya untuk menentukan dasar penyusu
tan (jumlah yang akan disusutkan). Dan peyusutan
hanya akan dilakukan sampai sejumlah dasar penyusu
tan. sedang tarip penyusutan diperoleh dari rumus
1/n, dengan n adalah umur ekonomis.' Beberapa penulis
buku memberikan rumus untuk tarip penyusutan metode
ini sebagai berikut, ”{1 - rV [ r / c ] } ” .11 Dengan n:
umur aktiva, r: nilai sisa, dan c: nilai perolehan.
c. Saldo Menurun Ganda
Metode ini sama dengan metode saldo menurun* hanya
tarifnya dua kali lipat dari tarip saldo menurun.
b. Metode Penyusutan Berdasarkan Unit Penggunaan
1. Metode Jam Jasa
Metode ini membebankan penyusutan berdasarkan jam
jasa yang digunakan. Tarip pembebanan per jam
diperoleh dari dasar penyusutan dibagi taksiran
jam jasa, kemudian penyusutan tiap tahunnya
adalah jam yang digunakan tahun tersebut dikali-
kan tarip pembebanan per jamnya.
2. Metode Jumlah Unit Produksi
Metode ini sama saja dengan metode jam jasa,
hanya tarip pembebanan didasarkan pada jumlah
produk yang digunakan. Tarip pembebanan per unit
produk diperoleh dari dasar penyusutan dibagi
taksiran produk yang akan dihasilkan. Kemudian
biaya penyusutan dalam suatu tahun adalah tarip
per unit dikalikan produk yang benar-benar diha
silkan pada tahun tersebut.
c. Metode Penyusutan Berdasarkan kriteria Lain
1. Metode Berdasarkan Jenis dan Kelompok
a. Metode Group
Metode ini memperlakukan sekelompok aktiva yang
sejenis (similar) sebagai suatu kelompok tunggal
ekonomis dan nilai sisa yang sama. Penyusutan
dibukukan dalam satu pos. Tarip penyusutan dida-
sarkan pada rata-rata nasa manfaat aktiva dalam
kelompok tersebut. Penyusutan diterapkan terhadap
semua aktiva yang masih dipakai dalam kelompok
tersebut tanpa memperhatikan mulainya digunakan .
Penarikan aktiva dilakukan dengan mengkredit
perolehan dan mendebet akumulasi penyusutan. Bila
penarikan ada kas yang diterima, maka akumulasi
penyusutan yang didebet adalah selisih harga
perolehan dengan kas yang diterima (tidak rugi
laba). Sedang penambahan aktiva dicatat dengan
mendebet aktiva ini sebesar harga perolehannya.
b. Hetode Komposit
Metode ini hampir sama dengan metode group, hanya
aktiva yang dikelompokkan lebih bervariasi
(dissimilar). Tarip komposit ditetapkan dengan
menganalisis penyusutan tiap tahun dari masing-
masing aktiva dalam kelompok. Dasar penyusutan
masing-masing aktiva dibagi dengan taksiran masa
manfaatnya, kemudian menjumlahkan masing-masing
hasil bagi tersebut menjadi jumlah tunggal.
Selanjutnya jumlah tunggal ini dibagi dengan
harga perolehan merupakan tarip komposit. Sedang
rata-rata masa manfaat adalah dasar penyusutan
2. Metode Anuitas
Metode ini memperlakukan penyusutan seharusnya
tidak dibebani dengan dasar penyusutan saja,
tetapi juga dibebani bunga seandainya dana terse
but ditanamkan pada aktiva yang menghasilkan.
Beban penyusutan tiap tahun harus mengandung pula
bunga atas dasar penyusutan. Oleh karena itu
nilai tunai dari penyusutan sama dengan harga
perolehan dikurangi nilai tunai nilai sisa.
3. Metode Persediaan
Metode ini memperlakukan pembebanan penyusutan
sama dengan persediaan. Aktiva yang sudah tidak
ada atau tidak dipakai, dibebankan sebagai penyu
sutan. Hal ini dapat dilakukan dengan arus perta-
ma masuk pertama keluar [FIFO] atau terakhir
masuk pertama keluar [LIFO].
Untuk amortisasi pada umumnya menggunakan metode
garis lurus, namun demikian tidak menutup kemungkinan
penggunaan amortisasi lain, apabila metode tersebut
dianggap lebih layak dan lebih mencerminkan penandingan
biaya dan manfaat.
2.1.1.3.Laba__Rugi__ Penarikan Aktiva Tetap. Aktiva
tetap atau aktiva tak berwujud jika telah tua dan tidak
ekonomis lagi maka akan ditarik dari pemakaian. Penarikan
kemudian aktiva lama dijual atau tidak dipakai lagi. Atau
bisa juga menukar dengan aktiva lama dengan aktiva yang
baru. Berikut ini diuraikan pengakuan laba rugi penarikan
[disposal] dan pertukaran [exchange].
1. Laba Rugi Penarikan
Manajeman dengan segala pertimbangannya dapat memu-
tuskan untuk menarik aktiva tetap. Aktiva tetap atau
aktiva tidak berwujud yang sudah tidak dimanfaatkan, maka
aktiva tersebut tidak boleh membebani periode yang tidak
menerima manfaatnya. Artinya jika suatu aktiva ditarik
dari suatu pemakaian, sedang nilai bukunya masih ada,
nilai buku tersebut tidak dibebankan pada periode-periode
berikutnya [yang tidak lagi memanfaatkannya]. Nilai buku
ini dibebankan sebagai kerugian pada periode terjadinya
penarikan. Pengakuan ini dilakukan dengan mengkredit
harga perolehan dan mendebit akumulasi penyusutan, sedang
nilai buku yang masih ada diakui sebagai kerugian.
Apabila penarikan dilakukan dengan menjual aktiva,
maka selisih kas dengan nilai buku merupakan keuntungan
atau kerugian, yang harus diakui pada periode terjadinya.
Selisih lebih adalah keuntungan, dan selisih kurang
adalah kerugian.
>
Pengakuan keuntungan dan kerugian penarikan aktiva
tetap seperti diatas berlaku juga terhadap penarikan
tidak memberikan manfaat ekonomis, maka nilai buku yang
masih ada dihapuskan sebagai kerugian. Aktiva tak berwu
jud yang ditarik dengan cara dijual, selisih lebih atau
kurang kas atas nilai buku adalah keuntungan atau keru
gian .
2. Laba Rugi Pertukaran
Untuk pertukaran aktiva ini layaknya mungkin hanya
terjadi pada aktiva tetap, tidak terjadi pada aktiva
tidak berwujud. Oleh karena itu SAK 1994 tidak mengatur
pengakuan laba rugi pertukaran aktiva tak berwujud,
sepertinya halnya PAI 1984 juga tidak mengatur perolehan
aktiva tak berwujud dari pertukaran.
SAK 1994 membagi pertukaran aktiva tetap menjadi dua
jenis, yaitu pertukaran aktiva tidak sejenis dan sejenis.
Pertukaran aktiva tidak sejenis, perbedaan antara nilai
buku aktiva yang diserahkan dengan harga wajarnya dicatat
sebagai laba atau rugi dan diakui pada periode terjadin
ya.
Pertukaran aktiva sejenis, kerugian selalu diakui
pada periode terjadinya pertukaran seperti halnya pertu
karan tidak sejenis. Namun, keuntungan dari pertukaran
aktiva sejenis, tidak langsung diakui tetapi ditangguh
kan. Disamping itu harus dilihat dulu, apakah pertukaran
ini melibatkan uang atau tidak. Bila tidak melibatkan
melibat-kan uang tapi justru menyerahmelibat-kan uang, juga tidak ada
pengakuan keuntungan. Pengakuan keuntungan pertukaran
aktiva sejenis baru ada, bila menerima uang, dan harga
wajar aktiva lebih tinggi dari nilai bukunya. Laba yang
diakuipun hanya sebagaian, yaitu sebesar perbandingan
antara uang yang diterima dibagi penjumlalahan uang dan
nilai wajar aktiva yang diterima dikalikan keuntungan
[selisih harga wajar aktiva yang diserahkan dengan nilai
bukunya].
Pengakuan laba seperti di atas karena berpegangan
pada prinsip bahwa, ” ... earning process is complete or
virtually complete, and exchange has taken place."12 Laba
rugi diakui bila proses memperoleh penghasilan telah
sempurna atau selesai atau nyata-nyata telah selesai dan
pertukaran telah terjadi. Pertukaran sejenis ini dianggap
proses memperoleh penghasilan belum selesai.
Sedang pengakuan keuntungan sebagian, hal itu dia
nggap bahwa jumlah itulah proses memperoleh penghasilan
telah sempurna (karena sebagian itulah yang telah
dijual). Hal di atas sejalan dengan opini APB No. 29,
bahwa pertukaran aktiva sejenis merupakan "... exchanges
that do not result in the culmination of the earning
process."^
12Schroeder, Hccullers, dan Clark, o p. cit.r hal. 72.
Pengakuan laba rugi atas pertukaran menganut konsep
konservatisme, yaitu bila menghadapi alternatif yang
tidak pasti, selalu dipilih kemungkinan yang paling
merugi. Jadi apabila harga wajar atau harga pasar aktiva
lebih kecil dari harga buku,maka akan diakui kerugian dan
mencatat perolehan aktiva dengan harga wajar atau pa-
sarnya. Sedang bila harga wajar atau pasar aktiva lebih
tinggi daripada harga bukunya, maka tidak langsung menga
kui laba, tetapi memilih untuk menangguhkan laba dan
mencatat aktiva sebesar harga bukunya. Laba yang ditang
guhkan ini akan diakui melalui pengakuan beban penyusutan
yang lebih kecil daripada yang seharusnya. Jadi seolah-
olah tidak ada pengakuan laba yang ditangguhkan tadi, hal
ini dikarenakan tidak dinyatakan dalam suatu rekening
tertentu yang secara eksplisit menyebutkan pengakuan
laba.
2.1.2. Penyusutan, Laba Rugi Penarikan Aktiva Tetap
Menurut Perpajakan dan Permasalahannya
2.1.2.1. Harta yang Disusutkan. Pengertian harta
yang disusutkan menurut UU PPh 1994 adalah "...harta
berwujud yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan
atau yang dimiliki untuk mendapatkan, managih, dan meme-
dari satu tahun, kepuali tanah...
Dalam penjelasan pasal 11 UU PPh 1994, disebutkan
pembebanan biaya untuk menghasilkan yang mempunyai masa
manfaat lebih dari 1 tahun dilakukan melalui penyusutan
untuk harta berwujud dan amortisasi untuk harta tak
berwujud atau biaya lain, yang mana berlaku prinsip-
prinsip yang sama atas keduanya.
Pengertian harta menurut UU PPh 1994, berarti menca
kup harta yang dapat disusutkan dan yang tidak dapat
disusutkan. Tanah menurut UU PPh 1994 secara tegas dite
tapkan termasuk harta yang tidak dapat disusutkan. Harta
berwujud selain tanah meskipun dimiliki perusahaan tetapi
digunakan untuk keperluan pribadi pengelola perusahaan,
juga tidak boleh disusutkan, yang biayanya dibebankan ke
perusahaan. Hal ini disebutkan dalam UU PPh 1994 pasal 9
ayat 1 huruf d, bahwa untuk menentukan penghasilan kena
pajak (PhKP), pemberian kenikmatan pemakaian kendaraan
bermotor dan perumahan milik perusahaan, kecuali peruma
han di daerah terpencil sesuai ketentuan PPh 1994, tidak
diperbolehkan dikurangkan sebagai biaya. Pengertian
daerah terpencil diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan
nomor 960/KMK.04/1983. Daerah yang disebut daerah terpen
cil dalam ketentuan tersebut harus memenuhi syarat yaitu
sulit memperoleh perumahan untuk disewa, dan letaknya
jauh dan sulit untuk dicapai oleh masyarakat pada umumn-
ya.
Masalah yang ada berkaitan dengan hal ini adalah
mengenai tanah. Tanah yang dimiliki oleh perusahaan di
Indonesia berupa hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan
(HGB) dan hak-hak lain yang jangka waktunya terbatas.
Perusahaan tidak dapat memiliki hak milik (HM) yang
jangka waktunya tidak terbatas. Karena terbatas jangka
waktunya apakah HGU, HGB, dan hak lainnya tadi boleh
disusutka atau tidak.
Untuk membahas hak atas tanah perlu dipahami
penger-tian hak atas tanah. Yang dimaksud dengan hak atas tanah
ialah, "Hak yang memberi wewenang kepada yang empunya
untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah
yang dihakinya."
Hak atas tanah di Indonesia seperti yang diatur
dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), banyak macam
ragamnya, seperti dikemukakan oleh Effendi Perangin
sebagai berikut:
Lengkapnya hak-hak atas tanah itu menurut pasal 16 jo 53 ialah: Hak milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka tanah, Hak Memungut Hasil Hutan, Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang dan Hak Sewa Tanah, Pertanian. Tetapi sesungguhnya Hak Membuka Tanah dan Hak Memun gut Hasil Hutan bukanlah hak atas tanah, berdasarkan
perumusan di atas.... Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Basil, Hak Menumpang dan Hak Sewa Tanah Pertanian disebut UUPA sebagai hak Yang bersifat sementara, satu saat akan dihapuskan.16
Sehubungan dengan penyusutan atau amortisasi tanah
atau hak atas tanah, maka pembahasan dibatasi pada hak
atas tanah yang bersifat tetap (bukan yang bersifat
sementara), dan diperoleh dengan cara mengeluarkan biaya,
tepatnya Hak Hilik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan,
Hak Pakai, dan Hak Sewa.
Untuk membahas mengenai hak-hak tersebut, berikut
ini diuraikan pengertian dan ciri-ciri dari hak-hak atas
tanah tersebut, yang diikhtisrkan dari UUPA.
Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan
terpenuh. HM memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
a. tidak terbatas jangka waktunya,
b. dapat dijadikan jaminan hutang hipotek,
c. dapat beralih kepada ahli waris jika pemegang hak
meninggal,
d. dapat dijual atau dialihkan dengan cara lain,
e. hanya dapat diperoleh dari penetapan pemerintah,
pemegang HM hanya dapat mengalihkan Hak Milik.
Hak Milik hanya dapat dimiliki oleh warga negara
Indonesia perorangan, secara sendiri-sendiri atau secara
bersama-sama. Badan hukum tidak boleh memiliki HM,
li ditunjuk bardasarkan Peraturan Pemerintah. Badan hukum
yang dapt memiliki HM misalnya bank milik pemerintah,
koperasi pertanian, badan keagamaan yang ditunjuk Kenteri
Dalam Negeri setelah mendengar pertimbangan Menteri
Agama, badan sosial yang ditunjuk Menteri Dalam Negeri
setelah mendengar pertimbangan Menteri Sosial.
HGU merupakan hak untuk mengusahakan tanah dibidang
pertanian, perikanan, perkebunan. HGU memiliki ciri-ciri:
a. terbatas jangka waktunya, tetapi ada jaminan untuk
memperpanjang haknya,
b. dapat dijadikan jaminan hutang hipotek,
c. dapat beralih kepada ahli waris,
d. dapat dijual atau dialihkan dengan cara lain,
e. hanya dapat diperoleh dari penetapan pemerintah, tidak
dapat diperoleh dari selain pemerintah.
HGU dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia
(WNI), badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia
dan berkedudukan di Indonesia.
Kemudian HGB, yaitu hak untuk mendirikan bangunan di
atas tanah tempat bangunan tersebut berdiri. Ciri-ciri
HGB adalah:
a. terbatas jangka waktunya, tetapi ada jaminan untuk
perpanjangan haknya,
b. dapat dijadikan jaminan hutang hipotek,
c. dapat beralih kepada ahli waris,
e. KGB bisa diperoleh dari pemerintah, atau dari per-
janjian dengan pemegang HM atas tanah, namun Effendi
Perangin menyebutkan karena belum ada peraturan
pelaksanaannya,... belum mungkin seorang pemilik
memberi hak guna bangunan itu di atas tanah mili-
knya."
Persyaratan orang atau badan hukum yang dapat memil
iki HGB sama dengan persyaratan untuk orang atau badan
hukum yang dapat memiliki HGU.
Berikutnya hak pakai, yaitu hak untuk mendirikan
bangunan atau mengusahakan tanah untuk usaha pertanian,
perikanan, perkebunan. Hak pakai memiliki ciri-ciri
yaitu:
a. terbatas jangka waktunya dan tidak ada jaminan
perpanjangan haknya,
b. tidak dapat dijadikan jaminan hutang hipotek, namun
disebutkan oleh Effendi Perangin bahwa, "Untuk
dijadikan jaminan khusus bagi kreditur tertentu,
maka biasanya tanah Hak Pakai itu diserahkan dengan
Kuasa Menjual Sebagai Jaminan."
c. tidak dapat beralih kepada ahli waris meskipun hak
tidak batal dengan sendirinya.
17Ibid., hal. 283.
d. pengalihan hak pakai harus seizin pihak yang berwe-
nang memberi izin,
e. dapat diperoleh dari pemerintah atau dari perjanjian
dengan pemegang HM atas tanah.
Hak Pakai dapa dimiliki oleh WNI, orang asing yang
berkedudukan di Indonesia, badan hukum yang didirikan
berdasarkan hukum di Indonesia, badan-badan asing yang
mempunyai perwakilan di Indonesia.
s
Dan hak sewa adalah hak untuk mempergunakan tanah
milik orang lain untuk keperluan bangunan. Hak ini tidak
berbeda dengan hak atas penggunaan aktiva tertentu karena
disewa. Hak ini hanya dapat diperoleh dengan perjanjian
dengan pemegang hak milik, bukan dari pemerintah.
Hak sewa dapat dimiliki oleh WNI, orang asing yang
berkedudukan di Indonesia, badan hukum yang didirikan
menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia,
badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.
Dilihat dari oara perolehan tanah di Indonesia khu
susnya bagi perusahaan atau badan hukum, sebenarnya akan
selalu terdapat dua jenis biaya yaitu biaya perolehan
awal dan biaya-biaya yang dikeluarkan setelah perolehan
awal. Hal ini dikarenakan badan hukum atau perusahaan di
Indonesia pada umumnya tidak dapat memiliki Hak Milik,
perusahaan hanya dapat memiliki hak atas tanah yang
jangka waktunya terbatas, seperti HGU, dan HGB.
untuk uang pendaftaran, uang pemasukan, dan sumbangan
landreform serta uang pembebasan tanah. Uang pendaftaran
yaitu biaya yang dikeluarkan oleh pemohon hak untuk
memperoleh keterangan tentang tanah dari kantor agraria,
membuat sertifikat dan biaya-biaya yang berhubungan
dengan pendaftaran tanah.
Uang pemasukan yaitu sejumlah uang tertentu yang di
bayarkan oleh pemohon hak ke[ada negara agar kepada
pemohon diberikan hak atas tanah sesuai yang diminta.
Apabila tanah yang dimohon haknya merupakan tanah yang
dibebaskan terlebih dahulu, maka tidak dipungut uang
pemasukan, tetapi dipungut uang administrasi sebesar 1%
dari uang pemasukan yang seharusnya dibayar.
Uang sumbangan landreform yaitu sejumlah uang yang
dibayarkan kepada yayasan dana landreform yang besarnya
adalah 50% dari uang pemasukan atau uang administrasi.
Yang dimaksud pembebasan tanah yaitu semacam pembelian
hak atas tanah agar pemegang hak bersedia melepaskan
haknya dengan penggantian, yang dapat berupa uang atau
harta lain.
Sedangkan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan
awal yaitu biaya untuk memperpanjang hak atau untuk
meperbarui hak. Biaya untuk memperpanjang atau untuk
memperbarui hak ini sama dengan biaya perolehan awal,
akan tetapi tentu saja tidak termasuk uang pembebasan
yang memperpanjang hak sehingga tidak perlu membebaskan
tanah terlebih dahulu.
2.1.2.2. Penyusutan Harta Berwu.iud dan Tak__BerHtt.iud
Menurut Perpajiakan. Secara eksplisit, pengertian mengenai
penyusutan disajikan dalam UU PPh 1994. pengertian
mengenai penyusutan ini dapat dipahami dari beberapa
pasal yang mengatur tentang hal tersebut. Pasal 6 UU PPh
1994 menyebutkan, untuk menghitung jumlah PhKP ditentukan
dari penghasilan bruto dikurangi, antara lain, penyusu
tan. Kemudian pasal 11 ayat 6 UU PPh 1994 menyebutkan
penyusutan ditetapkan dengan mengalikan dasar penyusutan
(yang dapat berupa harga buku atau harga perolehan) tiap-
tiap golongan dengan masing-masing tarifnya. Bahkan pasal
9 ayat 2 memperjelas definisi panyusutan -tersebut.
Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa penyusu
tan adalah alokasi pembebanan biaya perolehan harta
berwujud (yang tersirat dalam dasar penyusutan) selama
beberapa tahun pajak.
Sama halnya dengan penyusutan, tentang amortisasi di
sini diberikan definisi atau pengertian secara eksplisit
pula. Dalam pasal 9 ayat 2 UU PPh 1994 disebutkan bahwa
"Pengeluaran untuk mendapatkan, managih, dan memelihara
penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1
ligus, melainkan dibebankan melalui amortisasi..."19
Biaya di sini meliputi pengeluaran-pengeluaran untuk
memperoleh harta tak berwujud dan biaya-biaya lain yang
mempunyai masa manfaat lebih dari setahun, misalnya biaya
sewa yang dibayar di muka untuk jangka waktu 2 tahun.
1. Penentuan Harga Perolehan
Seperti telah dijelaskan di atas, bahwa dasar penyu
sutan merupakan jumlah yang akan digunakan untuk menetap-
kan jmlah beban penyusutan dalam tahun tertentu. Dasar
penyusutan di sini dapat berupa harga buku untuk harta
golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan 4 bisa
juga berupa harga perolehan, yaitu khusus untuk golongan
bangunan.
Dasar penyusutan meskipun berupa harga buku, hal ini
tidak dapat lepas dari penentuan harga perolehan pada
saat pembelian. Demikian halnya dengan dasar penyusutan
berupa harga perolehan. Berikut ini diuraikan penetapan
harga perolehan dari berbagai oara perolehan.
a. Harta Berwujud yang Diperoleh dari Penbelian
UU PPh 1984 pasal 10 ayat 1 menyebutkan bahwa harga
perolehan adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan,
tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai biaya-biaya
diluar harga harta yang bersangkutan.
Masalahnya bagaimana dengan biaya-biaya lain yang
dikeluarkan agar harta benar-benar siap digunakan, nis-
alnya biaya pengangkutan, bea masuk, biaya pemasangan,
PPn BM, PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan. Apakah
biaya-biaya tersebut akan dikapitalisasi atau dibebankan
langsung pada tahun terjadinya.
Dan bagaimana halnya dengan pembelian secara tidak
kontan atau cicilan. Apakah bunga yang dibayarkan dikapi
talisasi atau dibebankan langsung pada tahun terjadinya
pembayaran.
b. Harta Berwujud yang Dibangun Sendiri
Perolehan harta dengan cara ini tidak disebutkan
oleh UU PPh 1994, tetapi cara perolehan ini dapat dida-
sarkan pada pasal 10 ayat 1 UU PPh 1994 juga. Jadi harga
perolehan meliputi seluruh jumlah yang dikeluarkan.
Masalah yang timbul di sini adalah bagaimana perla
kuan biaya, bunga pinjaman yang digunakan untuk membangun
harta tadi. Apakah mengikuti ketentuan akuntansi yang
apabila syarat-syarat tertentu dipenuhi, biaya bunga atas
pinjaman boleh dikapitalisasi, ataukah langsung dibeban
kan seperti halnya biaya bunga lain.
c. Harta yang Diperoleh dari Pertukaran
Perolehan dengan cara ini disinggung dalam penjela-
san pasal 10 ayat 2 UU PPh 1994. Dalam penjelasan terse
but dicontohkan mengenai pertukaran harta, yang harga
menjadi harga perolehan dan juga menjadi pengurang untuk
menetapkan dasar penyusutan, jika harta yang ditukar
harta golongan bukan bangunan.
Masalahnya bagaimana bila terjadi pertukaran harta
yang harga pasarnya tidak seimbang dan melibatkan uang.
Jumlah mana akan dicatat sebagai harga perolehan harta
baru dan jumlah mana akan digunakan sebagai pengurang
untuk menentukan dasar penyusutan, dan bagaimana pula
untuk pertukaran bangunan.
d. Pembelian Harta Secara Kelonpok
Perolehan yang dilakukan dengan cara membeli seke
lompok harta, sejauh pengetahuan penyusun belum ada
ketentuan PPh 1994 yang mengaturnya. Sebagai contoh,
harga perolehan secara individual dari sekelompok harta
jika ditotal adalah Rp500 juta. akan tetapi, jika seke
lompok harta tersebut dibeli sekaligus harganya hanya
Rp450 juta.
Masalahnya bagaimana mencatat perolehan harta terse
but, bila dibeli secara kelompok dan harta tersebut
berlain-lainan golongannya atau bahkan dari sekelompom
harta tadi terdapat harta yang tidak boleh disusutkan.
e. Perolehan Harta dengan Sena Guna Usaha
Sewa guna usaha atau leasing secara khusus diatur
dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMR. 01/1991.
Keputusan tersebut mulai berlaku tanggal 19 Januari 1991.
48/KMK. 013/1991, karena ketentuan ini sudah tidak berla-
ku lagi, pembahasan selanjutnya akan mengacu pada keten
tuan yang masih berlaku, yaitu Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 1169/KMK. 10/1991.
Leasing menurut PPh 1994 dibagi menjadi dua jenis,
yaitu leasing dengan hak opsi (finance lease) dan tanpa
hak opsi (operating lease). Dalam pasal 13 Keputusan
Menteri Keuangan tersebut disebutkan bahwa perlakuan
akuntansi leasing dilaksanakan sesuai dengan standar
akuntansi leasing yang ada di Indonesia. Dan syarat
-syarat yang harus dipenuhi apakah suatu transaksi akan
dikelompokkan sebagai transaksi finance/capital lease
yang diatur dalam pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan
tersebut, juga hampir sama dengan syarat-syarat yang
ditentukan dalam akuntansi, seperti yang telah diuraikan
sebelumnya. Hanya syarat bahwa masa leasing minimum 2
tahun, oleh PPh 1994 dibedakan bahwa untuk golongan 1
minimum 2 tahun, golngan 2 dan 3 minimum 3 tahun, dan
golongan bangunan minimum 7 tahun. Syarat yang lain,
jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna
usaha pertama dan ditambah nilai sisa barang modal harus
dapat menutup harga perolehan dan keuntungan lessor, dan
perjanjian mengatur mengenai opsi bagi lessee.
Di samping itu persyaratan untuk operating lease
juga disebutkan secara jelas dalam pasal 4, yaitu jumlah
pertama tidak dapat menutup harga perolehan barang modal
dan keuntungan lessor dan perjanjian tidak mengatur opsi
bagi lessee.
Namun, perlakuan mengenai pembebanan penyusutan
menurut PPh 1994 diatur berbeda dengan akuntansi, yaitu
diatur dalam pasal 14 dan 16 Keputusan Menteri tersebut
sebagai berikut.
Untuk finance lease:
a. Lessor tidak boleh melakukan penyusutan harta yang
bersangkutan.
b. Lessee tidak boleh melakukan penyusutan atas harta
yang bersangkutan selama masa leasing.
c. Setelah lessee menggunakan hak opsinya untuk membeli
harta yang bersangutan, lessee baru melakukan penyu
sutan dengan dasar penyusutannya adalah nilai sisa
(residual value) harta tersebut, yang telah disepa-
kati oleh lessor dan lessee pada awal perjanjian
leasing.
d. Pembayaran leasing yang telah dibayar atau terhutang
oleh lessee, kecuali pembebanan atas tanah, dapat
dikurangkan dari penghasilan bruto sebagai biaya.
Untuk operating lease:
Operating lease ini tidak lain dengan sewa-menyewa biasa.
a. Lessor melakukan penyusutan sesuai pasal 10 UU PPh
1994.
guna usaha sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari
penghasilan bruto.
Masalahnya di sini dalam hal leasing jenis finance
lease, siapakah yang menyusutkan harta tersebut, atau
apakah harta yang disewa-guna-usahakan jenis finance
lease memang tidak disusutkan baik oleh lessor maupun
lessee.
Selain cara-cara perolehan seperti di atas, sejalan
dengan perkembangan dunia usaha ada pula cara perolehan
harta berwujud yang lain dari yang telah diuraikan di
atas, yaitu ruilslag. Euilslag mu1anya merupakan pertu
karan persil (tanah) dengan persil juga. Akan tetapi pada
akhirnya berkembang menjadi pertukaran tanah dengan
sekelompok harta misal tanah (di lokasi yang baru/lain)
ditambah gedung di atas tanah yang baru dan peralatan
lain.
f. Perolehan Harta Tak Berwujud
Disebutkan dalam pasal 10 UU PPh 1994, bahwa harga
perolehan harta tak berwujud dan biaya lain yang mempun
yai masa manfaat lebih dari setahun diamortisasi sesuai
dengan golongannya. Karena di depan telah disebutkan
bahwa harta berwujud dan tak berwujud berlaku prinsip
yang sama, maka harga perolehan ini juga sama yaitu
jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan.
Termasuk dalam golongan harta tak berwujud ini
biaya penelitian dan pengembangan. Akhir-akhir ini sedang
hangat mengenai perjanjian build, operate and transfer
(BOT), yaitu perjanjian antara dua pihak, pihak pertama
sanggup menyediakan tanah dan pihak kedua bersedia mem-
bangun sarana gedung dan lain-lain di atas tanah milik
pihak pertama, kemudian pihak kedua mengelolanya dalam
jangka waktu tertentu sesuai perjanjian, setelah jangka
waktu habis, pihak kedua menyerahkan gedung dan sarana
lain tersebut sesuai dengan perjanjian kepada pihak
pertama. Sedang tanah dari semula adalah milik pihak
pertama dan hak atas tanah tidak berpindah. Jadi kepemil-
ikan pihak kedua atas harta yang dibangunnya bersifat
sementara.
Masalahnya bagaimana penyusutan atau amortisasi yang
dilakukan. Apakah pihak kedua akan menyusutkan sarana
gedung dan lain-lainnya sesuai golongannya secara indi
vidual, ataukah BOT dianggap sebagai satu pos harta tak
berwujud. Apakah pihak pertama juga melakukan penyusutan.
Oi samping itu masih ada pula perjanjian BOO yaitu
Build, Operate and Own. Dengan BOO sarana yang dibangun
tetap dimiliki dan dioperasikan oleh yang membangun,
selama tidak dialihkan kepada pihak lain. Masalahnya,
bagaimana pula perlakuan penyusutan dan amortisasinya.
Dasar penyusutan menurut PPh 1994 hanya dipengaruhi
oleh harga perolehan, karena tidak dikenal adanya nilai
ini dimaksudkan sebagai insentif bagi wajib pajak, bahwa
seluruh pengeluaran, asal tetap merupakan biaya untuk
mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, maka
pengeluaran tersebut boleh dikurangkan dari penghasilan
bruto. Dasar penyusutan menurut PPh 1994 selanjutnya
diuraikan pada sub bab Tarif, Dasar dan Metode Penyusu
tan .
2.1.2.3. Pengelojipokan Harta vang__
Disusutkan_daa
Jangka Waktu Penyusutan.
a. Pengelompokan Harta yang Disusutkan
PPh 1994 menentukan harta yang disusutkan dan dia
mortisasi menjadi empat golongan, yang didasarkan pada
jangka waktu kegunaan harta. Pengelompokan ini diatur
dalam pasal 11 ayat 6 UU PPh 1994, yaitu sebagai berikut.
a. Golongan 1, meliputi harta bukan bangunan, yang
mempunyai masa manfaat lebih dari setahun tetapi
tidak lebih dari 4 tahun.
b. Golongan 2, mencakup harta bukan bangunan, yang
memiliki masa manfaat lebih dari 4 tahun, tetapi
tidak lebih dari 8 tahun.
c. Golongan 3, yaitu harta golongan bukan bangunan,
yang memiliki masa manfaat lebih dari 8 tahun,
tetapi tidak lebih dari 16 tahun.
d. Golongan 4, yang mencakup harta bukan bangunan yang
20 tahun.
e. golongan bangunan yang meliputi :
Permanen : masa manfaatnya sampai "20 tahun
Tidak permanen : masa manfaatnya tidak lebih dari
10 tahun
Selanjutnya untuk menentukan suatu harta akan digo-
longkan sebagai golongan 1, golongan 2 atau golongan
lainnya, diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor
961/KMK. 04/1983, yang kemudian disempurnakan dengan
Keputusan Menteri Keuangan No. 826/KMK. 04/1984.
b. Jangka Waktu Penyusutan
Golongan harta seperti di atas akan memasukkan harta
yang mempunyai masa manfaat yang berbeda-beda dalam satu
golongan. Yang akibatnya harta dengan masa manfaat yang
berbeda disusutkan dalam jangka waktu yang sama. Sabagai
misal harta golongan 2, harta yang mempunyai masa manfaat
5, 6, 7, atau 8 tahun secara jelas akan masuk dalam
golongan ini. Menurut logika, harta yang mempunyai masa
manfaat 5 tahun seharusnya disusutkan dalam jangka waktu
5 tahun, demikian juga untuk harta dengan masa manfaat 8
tahun akan disusutkan selama 6 tahun.
Akan tetapi masalahnya menurut PPh 1994, harta-harta
tersebut dianggap memiliki masa manfaat yang sama yaitu
memiliki masa manfaat paling lama 8 tahun. Namun, jangka
8 tahun, tetapi sampai batas waktu tak terhingga a w .
sampai harta yang bersangkutan ditarik dari pemakaian.
Kemudian bagaimana dengan masa manfaat harta tak berwujud
yang telah jelas, misal pembayaran sewa di muka untuk 5
tahun.
selanjutnya, PP no. 42 Tahun 1985 pasal 3 ayat 1
menentukan saat dimulaimya dilakukan penyusutan dan
amortisasi adalah pada tahun pengeluaran, dengan perke-
cualian sebagai berikut:
a. untuk harta yang masih dalam pengerjaan penyusutan
dan amortisasi dimulai setelah harta selesai penger-
jaannya,
b. untuk harta yang disewa-guna-usahakan penyusutan
dimulai pada tahun harta yang bersangkutan disewa-
guna-usahakan. .
Jadi penyusutan dan amortisasi tidak dilakukan pada
waktu harta yang bersangkutan digunakan. Dan itupun
dilakukan untuk 1 tahun penuh, tanpa melihat kapan dimu-
lainya penggunaan, jadi tidak ada penyusutan dengan
pecahan tahun, misal 6 bulan.
Suatu harta yang sama jenisnya, karena dipakai untuk
usaha yang berbeda sehingga frekuensi pemakaiannya juga
berbeda, dengan hal tersebut tentunya taksiran masa
manfaat juga akan berbeda. Namun menurut PPh 1994 suatu t harta pengelompokannya harus nengikuti Keputusan Menteri